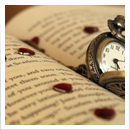Budaya administrasi Korea ditampilkan oleh jaringan yang normatif, relasional,
hierarkis, dan substantif (Hamilton 1996a). Familisme (Hamilton 1996a; Lockett 1993; Redding
1993, 1996; Redding dan Wong 1993; Wong 1996) merupakan salah satu faktor budaya untuk
memfasilitasi masyarakat berbasis jaringan. Karena Konfusius pentingnya keluarga, hubungan
dalam organisasi cenderung dimodelkan pada hubungan kekeluargaan; yaitu, sebuah kelompok
atau organisasi dipandang sebagai sebuah keluarga. Sebagian besar praktik manajemen dan bisnis
dilakukan dalam konteks keluarga yang dominan (Redding dan Wong 1993).
Familisme menekankan kerja sama berdasarkan ikatan afektif baik pada tingkat vertikal
maupun horizontal—dengan kata lain bergaul dengan atasan dan bergaul dengan sesama pekerja
(Redding dan Wong 1993). Inti dari hubungan antara manajer dan karyawan adalah rasa hormat
dan kesetiaan bawahan kepada manajer dan perlindungan paternalistik atasan, perawatan, dan
perlindungan karyawan, berdasarkan kebajikan Konfusius seperti bakti, menghormati otoritas dan
usia, dan loyalitas kepada orang lain (Redding 1996). Tak perlu dikatakan, hubungan kekeluargaan
semacam ini dalam sebuah organisasi ditandai dengan afiliasi afektif atau emosional karyawan
dengan organisasi di mana mereka berada (Redding dan Wong 1993).
Singkatnya, penekanan pada ikatan atau jaringan pribadi, kepekaan terhadap hubungan
sosial antarpribadi, saling ketergantungan, dan ikatan afektif di antara orang-orang mengarah pada
keharmonisan sosial. Negara-negara Barat dipandang jauh lebih mementingkan nilai-nilai praktis
dan pragmatis berdasarkan egosentrisme, individualisme, rasionalisme, dan kesukarelaan daripada
budaya Korea, yang menekankan nilai-nilai moral dan normatif yang berfokus pada jaringan sosial
dan nilai-nilai kelompok.
Ketekunan, hemat, dan tabungan bukan hanya prinsip ekonomi tetapi juga nilai-nilai
dalam Konfusianisme, seperti dalam etika Protestan. Kepemimpinan dan perencanaan elit birokrat
dalam kolaborasi dengan para pemimpin politik selama negara birokrasi modern (1960–1987)
dapat dipahami sebagai representasi peran paternal yang sesuai dengan zaman. Sumpah dinas yang
diucapkan oleh semua pejabat publik pada bulan November 1981 (Kementerian Administrasi
1979, 13) memuat frasa “pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa”, “kejujuran dan pelayanan
201
kepada rakyat”, “kreativitas] dan tanggung jawab terhadap tugas, ” “kehormatan dan iman di
tempat kerja,” dan “kejujuran dan keteraturan dalam kehidupan pribadi.”
Akan tetapi, untuk semua kontribusi potensialnya, Konfusianisme memiliki konotasi
negatif bagi sebagian orang. Dari segi cara berpikir, orientasi nilai, dan pola perilaku birokrat,
birokrasi Korea dominan berkonotasi negatif. Dipercaya secara luas bahwa birokrasi tunduk pada
otoritarianisme, formalitas, fatalisme, kasih sayang, dan faksionalisme—sangat berbeda dari
birokrasi Eropa Barat yang didasarkan pada rasionalitas, yang dianut oleh Max Weber (Cho 1973;
Kim 1966; B.S. Kim 1968; H.D. Kim 1968; Paik 1987).
Ada kecenderungan untuk memilih Konfusianisme, antara lain, sebagai faktor utama dari
aspek negatif birokrasi yang mengakar di Korea. Ada pandangan kuat bahwa warisan
Konfusianisme berdampak buruk pada perkembangan positif birokrasi. Seperti yang ditunjukkan
sebelumnya, budaya administrasi Korea didominasi oleh hierarki pekerjaan, “kelompokisme”, dan
otoritarianisme. Budaya itu, sedikit banyak, terkait dengan struktur politik dan administrasi yang
tersentralisasi. Menurut Chae dan Cho (2004), tinjauan kinerja dalam budaya otoriter ditandai
dengan evaluasi berdasarkan dominasi dan kepatuhan, evaluasi yang lebih mempertimbangkan
hierarki pekerjaan, dan evaluasi top-down. Insentif kinerja biasanya diberikan dengan
pertimbangan yang menguntungkan dari layanan lama, pengalaman, loyalitas, kerja tim, dan
penekanan pada senioritas. Keputusan promosi menekankan kesetiaan dan kepatuhan dan lebih
memperhitungkan penilaian atasan daripada upaya yang dilakukan oleh individu. Namun,
situasinya perlahan-lahan mengalami perubahan karena demokratisasi setelah tahun 1987 dan
internasionalisasi; lebih banyak bobot diberikan pada demokrasi administratif dan kinerja.
16.5 REFORMASI ADMINISTRASI
16.5.1 SEJARAH REFORMASI
Pemerintah Korea memiliki reformasi yang sedang berlangsung. Tujuan utama reformasi
pada periode sebelumnya adalah pembangunan bangsa pada tahun 1940-an, memulihkan tatanan
sosial dan rekonstruksi pada era pasca-Perang Korea pada tahun 1950-an, dan memfasilitasi
industrialisasi yang pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Tujuan reformasi ini mencerminkan
ideologi “pembangunan yang diatur” (Caiden dan Jung 1981). Sejak akhir 1980-an, pembuat
202
kebijakan publik di Korea melanjutkan reformasi administrasi yang agresif, tetapi ini berbeda dari
sebelumnya. Mereka telah dipandu oleh pertimbangan kembali peran pemerintah yang tepat di
negara yang demokratis dan maju, serta kebutuhan untuk menanggapi urgensi baru, seperti krisis
keuangan Asia pada akhir 1990-an.
Selama akhir tahun 1970-an, sejumlah pembuat kebijakan dan pakar mulai berpikir bahwa
perekonomian Korea tidak perlu lagi bergantung pada intervensi pemerintah yang agresif,
termasuk perencanaan pembangunan ekonomi 5 tahun yang telah menjadi pokok sejak tahun 1962.
Pertimbangan ulang tentang peran yang tepat dari pemerintah lebih lanjut dirangsang oleh gagasan
pemerintahan kecil yang lazim di negara-negara Anglo-Amerika. Pada tahun 1980, pemerintah
Chun Doo-Hwan mengadopsi gagasan pemerintahan yang berorientasi pasar, yang sebagian
diperkenalkan melalui reformasi administrasi 15 Oktober 1981, yang dalam satu gerakan
memberhentikan sekitar 12% pegawai negeri sipil pemerintah pusat berpangkat lebih tinggi (Jung
1997). ). Sejak saat itu hingga tahun 2003, dengan peresmian pemerintahan Kim Dae-Jung,
pemerintahan kecil menjadi norma untuk melakukan reformasi administrasi yang serius di Korea
Selatan. Sejak tahun 1987, demokratisasi administrasi publik telah menjadi tujuan penting lain dari
reformasi administrasi publik.
Pada tahun 1988 di bawah pemerintahan Roh Tae-Woo, Komite Presiden untuk
Reformasi Administratif (PCAR), yang awalnya terdiri dari para ahli sipil, mengusulkan sebuah
“pemerintahan kecil dan efisien yang akan berkontribusi pada pembentukan demokrasi” sebagai
yang paling tujuan reformasi yang penting (Jung 1997). Mengurangi sejumlah besar peraturan
pemerintah yang dikenakan pada masyarakat sipil dan mendesentralisasikan kekuasaan baik antara
pemerintah pusat dan daerah dan di dalam birokrasi adalah salah satu tujuan utama PCAR dan hal
itu tercermin dengan baik dalam proposal akhirnya (PCAR 1989). Implementasinya lemah, dan
selama 5 tahun pemerintahan Rho Tae-Woo, pegawai negeri meningkat sebesar 180.000, yang
merupakan peningkatan tahunan rata-rata sebesar 4,7% (Korea Institute of Public Administration
1996). Pemerintah juga tidak secara efektif melaksanakan tujuan reformasi deregulasi dan
desentralisasi.
203
Krisis keuangan Asia merupakan titik balik utama. Pada akhir tahun 1997, pemerintah
Kim gagal mengelola kekurangan likuiditas mata uang asing dan harus meminta pinjaman
penyelamatan dari IMF. Pemerintahan Kim Dae-Jung, yang diresmikan pada Februari 1998, harus
memulai masa jabatannya dengan mengatasi krisis valuta asing dan kesulitan ekonomi yang
diakibatkannya; Tingkat pertumbuhan ekonomi Korea menurun dari rata-rata 7% sejak tahun
1960-an menjadi –6,5% pada tahun 1998. Tingkat pengangguran, yang tetap di bawah 2,5%
sepanjang tahun 1990-an, meningkat menjadi 8% pada tahun 1998. Di bawah pengawasan IMF,
Pemerintahan Kim secara agresif melakukan serangkaian penyesuaian struktural di sektor
keuangan, perusahaan, tenaga kerja, dan publik. Pedoman IMF untuk restrukturisasi sektor publik
dialihkan dari model reformasi manajemen publik baru yang berorientasi pasar.
Teori manajemen publik baru diperkenalkan sebagai teori reformasi administrasi
menyerukan reformasi pemerintahan di bawah pemerintahan Roh Moo-Hyun. Ia kemudian
memperoleh kekuatan sebagai “rancangan sistematis untuk reformasi pemerintahan” yang dapat
membersihkan inefisiensi ekonomi terencana, konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan,
korupsi,ketidakfleksibelan dan ketidakmampuan birokrasi, dan pemerintahan otoriter oleh
birokrasi. Sejak awal 1990-an, setiap presiden telah mendirikan sebuah organisasi yang
bertanggung jawab atas reformasi pemerintahan dan memanfaatkannya sebagai kendaraan utama
untuk mempromosikan perubahan dan pengembangan organisasi.
16.5.2 MENILAI PENCAPAIAN REFORMASI
16.5.2.1 PERAMPINGAN PEMERINTAH
Korea mempertahankan pemerintahannya relatif kecil. Jumlah pegawai
pemerintah sebagai persentase dari total tenaga kerja, jumlah pengeluaran publik untuk
upah sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB), dan total pengeluaran
pemerintah sebagai persentase dari PDB adalah yang terendah di antara Organisasi Kerja
Sama Ekonomi. dan Pembangunan (OECD). Sejak awal 1980-an, negara tersebut telah
mempublikasikan kebijakan pemerintahan kecil sebagai tujuan penting dari reformasi
204
administrasi, meskipun pemerintahan Roh mengejar pemerintahan yang efisien dan cakap
terlepas dari ukurannya.
Pemerintah Chun pertama kali menerapkan gagasan pemerintahan kecil di
Korea pada tahun 1981 dengan pengurangan 599 pegawai di tingkat direktur divisi atas
dan 35.890 pegawai di bawahnya—sekitar 5% dari pemerintah pusat. Namun,
perampingan ini lebih menitikberatkan pada pengurangan jumlah PNS tanpa mengurangi
jumlah fungsi atau jabatan pemerintah pusat. Akibatnya, jumlah pegawai pemerintah
kembali meningkat, mulai sekitar 1,7% pada tahun berikutnya.
Pemerintah Kim Young-Sam melakukan reorganisasi pada tahun 1993 dan
1994 yang menghapus sejumlah besar posisi di birokrasi pusat tetapi gagal mengurangi
jumlah pegawai layanan publik. Salah satu alasannya adalah Undang-Undang Layanan
Nasional, yang melindungi pegawai negeri dari pengunduran diri yang tidak disengaja dan
membentuk apa yang disebut personel "satelit". Kecuali tahun 1998 sampai 2002—segera
setelah krisis devisa—jumlah pegawai negeri terus bertambah. Krisis valuta asing tahun
1997 memaksa pemerintah Kim Dae-Jung melakukan penyesuaian struktural dan tanpa
syarat mengadopsi model manajemen publik baru untuk mematuhi pedoman pemulihan
IMF (Jung 2006).
Berbeda dengan empat pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Roh Moo-
Hyun tidak mengadopsi kebijakan pemerintahan kecil. Sebaliknya, pemerintah Roh
mengusulkan pemerintahan yang efisien dan cakap sebagai salah satu tujuan reformasi
terpentingnya. Tujuan reformasi administrasi lainnya adalah (1) menjadikan pemerintahan
lebih terbuka, transparan, dan lebih dekat dengan rakyat; (2) meningkatkan kualitas hidup
masyarakat; dan (3) memperkenalkan prosedur yang disederhanakan dan seragam (PCGID
2003). Administrasi Lee Myung-bak tampaknya tidak menekankan perampingan
pemerintah tetapi data untuk memverifikasi ini tidak tersedia saat ini.
Namun, meskipun Korea belum berhasil melakukan perampingan pemerintah
seperti yang direncanakan, pemerintahnya tetap yang terkecil di antara negara-negara
OECD. Pada 1980-an, pengeluaran pemerintah Korea sebagai persentase dari PDB
205
termasuk yang terendah di antara negara-negara OECD (sekitar 20% dan tidak ada defisit
keuangan). Akibatnya, pemerintah tidak menganggap serius masalah besaran anggaran dan
tidak menyajikan rencana pengurangan belanja tertentu. Sejak tahun 1988, belanja publik
terus meningkat, dengan peningkatan hampir 10% pada tahun 2000-an. Pertumbuhan
berkelanjutan dari pemerintah Korea ini dapat dijelaskan dengan demokratisasi politik.
Sejak transisi demokrasi tahun 1987, tuntutan pelayanan publik terus meningkat, terutama
bagi masyarakat miskin, cacat, lanjut usia, perempuan, dan anak muda. Dengan proses
elektoral yang lebih kompetitif, lingkungan politik yang baru telah memaksa pembuat
kebijakan untuk menanggapi tuntutan tersebut.
16.5.2.2 DEREGULASI
Sejak awal 1980-an, pemerintah telah banyak berinvestasi dalam reformasi
peraturan untuk merevitalisasi bisnis. Pemerintah Korea telah memprakarsai berbagai
macam deregulasi dengan mendirikan PCAR (1993–1998), Komisi Deregulasi Ekonomi
(1993–1997), dan Dewan Reformasi Regulasi (1998–sekarang). Menurut laporan tahunan
resmi, sejumlah prosedur dan peraturan administrasi telah diperbaiki. Misalnya, 1.880 di
antara 2.177 kasus reformasi peraturan yang diajukan pada tahun 1993–1996 diselesaikan
(Jung 2001). Namun, 70% dari kasus yang diselesaikan oleh PCAR adalah rasionalisasi
prosedural, dan hanya 10% yang melibatkan penghapusan fungsi regulasi. Di bawah
pemerintahan Roh, jumlah peraturan pemerintah telah meningkat. Selama tahun pertama
pemerintahan, praktik regulasi meningkat dari 7.575 kasus menjadi 7.797 kasus. Sunset
law hanya diterapkan pada 0,58% dari total peraturan pemerintah (Kwon 2005).
16.5.2.3 REORGANISASI
Pemerintah Korea melakukan serangkaian reorganisasi yang dirancang untuk
meningkatkan koordinasi kebijakan sekaligus mengurangi ukuran pemerintahan.
Koordinasi kebijakan antar lembaga sulit dilakukan karena pertumbuhan birokrasi yang
bertahap, yang menyebabkan tumpang tindih fungsional antar kementerian dan lembaga
206
pemerintah. Untuk meningkatkan koordinasi kebijakan dan merampingkan proses
kebijakan, komite reformasi mengusulkan sistem “kementerian super” yang
menggabungkan organisasi dan fungsi terkait dari berbagai lembaga. Pemerintah Kim
Young-Sam berhasil secara dramatis mereorganisasi pemerintah pusat dengan
menghapuskan tiga kementerian, satu lembaga, dan satu biro luar (Jung 1997).
Badan yang kuat dari negara pembangunan Korea, Dewan Perencanaan
Ekonomi, digabungkan dengan Kementerian Keuangan untuk membentuk Kementerian
Keuangan dan Ekonomi. Reorganisasi 1993 menghapus empat menteri, lima wakil
menteri, lima wakil wakil menteri, 34 direktur jenderal biro, 127 direktur divisi, dan 966
staf di bawah pangkat direktur divisi. Namun, sejak saat itu, sistem superdepartemen
sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas koordinasi kebijakan dan untuk mengurangi
ukuran pemerintah telah terbengkalai.
Namun, pemerintah Korea telah mendirikan sejumlah lembaga baru sebagai
tanggapan atas isu pascaindustrialisasi dan transisi pascademokrasi (Jung 2007). Ini
termasuk Kementerian Tenaga Kerja (1981), Komisi Pengawas (1998), Mahkamah
Konstitusi (1988), Ombudsman Nasional (1994), Kementerian Sumber Daya Laut dan
Kelautan yang baru (1996), Kementerian Kesetaraan Gender (2001 ), dan Badan
Investigasi Maladministrasi Pejabat Tinggi (2005). Lembaga-lembaga baru ini telah
menghasilkan demokrasiasi pemerintahan publik yang lebih besar, memberikan lebih
banyak check and balances dalam pemerintahan, dan menawarkan warga negara dan
kelompok kepentingan akses yang lebih besar kepada pemerintah.
16.5.2.4 EFISIENSI ADMINISTRASI
Salah satu tujuan reformasi yang disosialisasikan pemerintah Korea adalah
merekayasa ulang proses administrasi untuk mengatasi inefisiensi birokrasi. Reformasi ini
termasuk memberdayakan tingkat administrasi yang lebih rendah, melembagakan sistem
evaluasi kinerja, menciptakan lembaga eksekutif gaya Inggris, dan mengembangkan tata
kelola elektronik. Koordinasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga bersifat
207
hierarkis, yang berasal dari sekretariat presiden di Gedung Biru dan lembaga pusat yang
kuat, seperti Kementerian Perencanaan dan Anggaran, sejak 1998.Sejak akhir 1990-an,
Korea telah memperkenalkan sistem agensi eksekutif. Namun, upaya agensifikasinya
terbatas dibandingkan dengan Inggris Raya, Australia, dan Selandia Baru. Sejak tahun
2000, pemerintah Korea telah membentuk 23 lembaga eksekutif administratif (AEA) yang
mengimplementasikan fungsi kebijakan rutin seperti menerbitkan surat izin mengemudi
dan mengoperasikan teater nasional. Proyek e-government adalah upaya lain untuk
“debirokratisasi.” Pemerintah Korea telah mencapai tingkat e-government tertinggi di
dunia.
16.5.2.5 DESENTRALISASI
Pemerintah pusat Korea telah mengendalikan pemerintah daerah secara efektif
melalui berbagai pengaturan kelembagaan. Seiring dengan momentum transisi menuju
demokrasi pada akhir 1980-an, pemerintah melembagakan serangkaian reformasi
devolusioner (dijelaskan dalam Bagian 16.3.2). Meskipun upaya desentralisasi cukup
besar, bagaimanapun, pemerintah pusat masih mempertahankan sejumlah mekanisme
kontrol atas manajemen personalia pemerintah daerah, keuangan dan penganggaran publik,
dan reorganisasi karena warisan sentralisasi telah mengakar begitu dalam. Sebagian besar
kementerian dan lembaga pusat masih secara langsung melaksanakan kebijakan mereka
melalui pemerintah daerah dengan menggunakan “petunjuk administratif, yang
mempersulit kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
16.6 KESIMPULAN
Administrasi publik Korea berkembang secara bertahap dari pemerintahan kecil yang
tidak efektif selama kerajaan Joseon pada akhir abad ke-19 menjadi pemerintahan yang
jauh lebih efisien dan demokratis saat ini. Sistem administrasi publik modern diterapkan
setelah Perang Dunia II, setelah itu Korea mengalami gejolak sosial. Selama Perang Korea,
rezim otoriter yang dibentuk oleh kudeta militer mengembangkan birokrasi yang kuat yang
208
memimpin negara dalam pembangunan ekonomi dan keamanan nasional. Tetapi
demokrasi dan pemerintahan lokal dibatasi, dan korupsi merajalela. Ketidakpuasan publik
yang kuat menyebabkan berakhirnya rezim otoriter militer ini. Sejak tahun 1987,
pemerintahan demokratis telah diperkuat, dan banyak upaya reformasi telah dilakukan
untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan, meningkatkan partisipasi
publik, melanjutkan sistem otonomi lokal, dan meliberalisasi aktivitas pasar.
209
CHAPTER 17
Proses Kebijakan Publik dan Partisipasi Warga Negara di Korea
Selatan
17.1 PENGANTAR
Pembangunan ekonomi yang kuat dan diprakarsai oleh pemerintah telah menjadi yang
utama prioritas Korea sejak akhir Perang Korea tahun 1953. Pembangunan ekonomi sangat
berhasil di bawah rezim Presiden Park Chunghee pada 1960-an dan 1970-an, dan strategi ekonomi
presiden berturut-turut tidak jauh dari itu pendahulu mereka.
Sejak akhir 1980-an, Korea mulai mengalami perubahan paradigma yang besar. Yang lama
Paradigma pembangunan ekonomi diarahkan dan dikendalikan masyarakat secara top-down
sistem di mana efisiensi adalah nilai tertinggi dan komunikasi satu arah diterima dengan sedikit
pertanyaan atau perlawanan. Paradigma demokrasi baru dihormati membentuk konsensus nasional
melalui partisipasi publik, kolaborasi, dan musyawarah erasi, dan berfokus pada implementasi
yang transparan dan evaluasi yang adil atas publikasi program lic.
Baru -baru ini di Korea memiliki pemahaman mengembangkan bahwa konflik sosial yang
diciptakan oleh pengambilan keputusan sepihak menimbulkan biaya bahwa demokrasi kolaboratif,
partisipatif, atau deliberatif1 dapat mencegah atau menyelesaikannya (Agranoff dan McGuire
2003; Gray 1989; Bingham, Nabatchi, dan O'Leary 2005).
Tata kelola dan sistem partisipasi suatu negara paling baik dipahami jika memang demikian
didekati dari perspektif budaya dan sosial dan perkembangan sejarah bangsa (Van Speier 2009).
Tata kelola melibatkan orang (Bingham et al. 2005)
210
17.2. LATAR BELAKANG: PROSES SEBELUM TAHUN 1990-AN
Sebelum akhir 1980-an, proses pembuatan kebijakan di Korea terbatas pada
internallingkaran pemerintah, yang hanya mencakup kementerian dan kantor terkait, dan
Biru House.2 Penekanan nasional pada pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang
kuat ment tradisi dan sistem politik secara efektif mengecualikan partisipasi
pemberitahuan- entitas politik yang kurang berkembang seperti Majelis Nasional dan
politik partai, LSM (lembaga swadaya masyarakat), kelompok kepentingan, dan
masyarakat dari proses pembuatan kebijakan. Pendapat publik jarang diungkapkan dan
sipil kelompok gerakan jarang terjadi. Orang-orang hanya dipandang sebagai objek
mengawasi dan mengontrol (Kim 1992; Ahn 2008). Ada sedikit peluang bagi LSM untuk
melakukannya berpartisipasi secara formal dalam proses kebijakan. Birokrasi pemerintah
dimonopoli hak pembuatan kebijakan de facto dalam lingkungan yang sangat stabil.
Karakteristik proses pembuatan kebijakan antara tahun 1960-an dan 1980-an di bawah
pemerintahan otoriter presiden Park Chunghee, Chun Duwhan, dan Roh Taewoo dapat
diringkas sebagai monopoli pengambilan keputusan di pub- proses kebijakan lic. Dalam
banyak kasus, pembuatan kebijakan resmi tidak lebih dari proses formal untuk
mengonfirmasi kesepakatan yang sudah dibuat. Keputusan paling penting adalah
diputuskan secara tidak resmi dalam pertemuan rahasia sebelumnya. Pertemuan publik
resmi, seperti rapat kabinet, hanya berfungsi sebagai proses konfirmasi dan dokumentasi.
Proses pembuatan kebijakan bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Pemerintah
membutuhkan mitra bisnis yang andal, dengan sub- ukuran konstan, yang dapat berfungsi
sebagai mesin pembangunan ekonomi utama bagi negara mencoba. Sebagai imbalannya,
perusahaan bisnis menginginkan dukungan pemerintah untuk berperan sebagai mitra.
Yang pertama (1962–1966) dan kedua (1967–1971) “Lima Tahun Ekonomi Nasional
Rencana Pembangunan” menyerukan untuk mengkonsentrasikan dukungan pemerintah
pada area bisnis seperti kilang minyak, semen, pupuk, galangan kapal, serat sintetis,
elektronik, besi, dan bahan kimia (Choi 2008, 112). Tanpa pengalaman yang memadai atau
cukup pembiayaan, perusahaan bisnis tidak bisa tidak mengandalkan dukungan
211
administratif dan investasi keuangan langsung dan tidak langsung dari pemerintah untuk
inkubasi keberhasilan industri.
Hasilnya adalah sukses besar dalam pembangunan ekonomi. Melalui serangkaian rencana
pembangunan ekonomi, Korea mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar
8,45% untuk periode 1962–1981 (dihitung ulang dari Kang, Lee, dan Choi 2008, 181).
Perusahaan bisnis terintegrasi secara aktif dalam rencana ekonomi nasional untuk
mencapai tujuan pembangunan. Model negara pengembangan tipikal ini melayani negara
sangat baik berkaitan dengan pencapaian ekonomi. Ekonomi datang dengan efek samping
yang serius. Secepat ini pertumbuhan dimungkinkan dengan mengorbankan proses hukum
dan keadilan sosial. Perusahaan bisnis mengambil kesempatan untuk pencarian rente
ekonomi (Kong 1995, 238–239). Kebanyakan industri yang ingin dikembangkan oleh
pemerintah secara alami dimonopoli perusahaan bisnis yang dekat dengan pemerintah
melalui bantuan pajak khusus dan izin bisnis yang tidak adil (Cho 1990, 180). Bahkan,
sebagian besar perusahaan yang tumbuh di era pembangunan berkat dukungan pemerintah
menjadi chaebol dan masih menikmati status itu hari ini. Pemerintah mentolerir
pelanggaran peraturan yang dilakukan bisnis perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja
dilakukan.
Melalui proses ini, pemerintah berisiko ditangkap oleh industri kepentingan percobaan.
Untuk menjinakkan pemerintah dan memajukan kepentingan swasta, perusahaan bisnis
mencoba metode ilegal seperti suap dan pertukaran bantuan yang tidak adil. Bisnis yang
korup praktek-praktek yang tersebar luas dan pemerintah menutup mata terhadap korupsi
di nama pembangunan ekonomi.
Perilaku ini berlanjut hingga akhir 1980-an dan meninggalkan kesan negatif yang
mendalam warisan dengan menanamkan beberapa sentimen mengerikan dalam masyarakat
Korea. Yang pertama adalah kebencian terhadap chaebol dan ketidakpercayaan pada
pemerintah. Yang kedua adalah hasilnya lebih penting daripada proses: Jika hasilnya
berhasil, maka proses yang tidak semestinya bisa terjadi dibenarkan. Korea mengorbankan
banyak masalah mendasar selama pembangunan ekonomi periode ment yang mem-boot
kelancaran transisi demokrasi bangsa. Negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar
biasa dalam waktu sesingkat itu sebagai kompensasi mengabaikan nilai-nilai demokrasi.
212
17.2.1 SISTEM ADMINISTRASI YANG KUAT
Jalur dan waktu pembangunan sosial dan ekonomi di Korea berbeda dari model
untuk negara-negara Barat. Mengikuti perkembangan Jepang- negara pilihan, model Korea
sangat bergantung pada elit birokrat (Ahn dan Jung 2007).Pertumbuhan-pertama praktik
yang diperjuangkan oleh pemerintah memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat
bahwa tuntutan demokratis seperti hak asasi manusia atau pembangunan konsensus datang
hanya setelahnya pertumbuhan ekonomi.
Y. S. Ha dkk. (2006) berpendapat bahwa pemerintah Korea didasarkan pada
administrasi yang kuat dan bahwa fitur ini merupakan hambatan utama bagi pembuatan
kebijakan yang demokratis kerangka. Korea secara tradisional mengandalkan presiden
yang kuat. Sebagai aparatur formal untuk melaksanakan inisiatif presiden (sebagian besar
digunakan untuk tujuan yang cukup dapat dibenarkan seperti percepatan pembangunan
ekonomi), pemerintah memiliki kekuatan yang sangat kuat juga (Kim 1996; Ha 2004).
Pemeriksaan kelembagaan yang paling kuat dari legislatif kepada pemerintah
adalah pemeriksaan administrasi (Ahn 1994). Otoritas Nasional Majelis untuk melakukan
inspeksi kantor-kantor pemerintah dibangkitkan pada tahun 1988. Tetapi anggota Majelis
Nasional sering menderita kekurangan yang memadai akses informasi. Keahlian anggota
dewan yang relatif lemah dalam hal ini area pada umumnya juga berkontribusi terhadap
kegagalan inspeksi yang efektif dan memberikan kelonggaran pemerintah untuk
menghindari pertanyaan inspeksi dengan mudah.
Pemerintah juga memainkan peran yang sangat penting dalam membuat undang-
undang. Pemerintah mendominasi jumlah RUU yang disahkan hingga saat ini (Tabel
17.1).Anggota majelis dapat mengajukan RUU, tetapi ide utamanya sering berasal dari
organisasi pemerintah. Kualitas RUU yang diajukan juga jauh lebih baik dalam kasus yang
diprakarsai pemerintah, seperti yang ditunjukkan pada tingkat penarikan. Berdasarkan Law
Times (2009), tingkat penarikan tagihan yang diprakarsai pemerintah hanya 0,33% (dua
kasus) di Majelis Nasional ke-18 per April 2009, sedangkan tagihan yang diprakarsai
legislatif setinggi 11% (402 kasus). Sumber itu juga melaporkan bahwa tingkat pengesahan
RUU yang diprakarsai legislatif sangat rendah 4,4%.
213
Dalam banyak kasus, partai yang berkuasa membenarkan dan menegaskan
pemerintahan agenda pemerintah dengan mengusulkan RUU yang berasal dari pemerintah.
Partai yang berkuasa dan kadang-kadang bahkan pihak nonpemerintah tidak akan rugi
dalam praktik ini karena mereka dapat mengusulkan tagihan dengan nama mereka.
Hingga April 2008, SMG telah menerima 13.149 ide di portal sejak program
dimulai pada Oktober 2006; ini setara dengan 23 proposal per hari (SMG 2008). Namun,
sebuah portal internal ada di mana pejabat SMG—hanya pejabat—yang bisa mengusulkan
ide-ide untuk meningkatkan layanan kota. Sangat menarik kira-kira 60.000 ide didaftarkan
di portal itu dalam periode waktu yang sama. Nomor gagasan yang disampaikan oleh
pejabat pemerintah jauh melebihi jumlah warga, seperti yang dilakukan jumlah gagasan
yang diadopsi.
Pemerintah Korea adalah sektor dominan dibandingkan legislatif atau publik.
Meskipun negara menghormati pemisahan formal dan pembagian kekuasaan antar sektor,
pemerintah pemerintah memimpin masyarakat sipil dengan segala cara. Ini adalah hasil
alami dari yang lama tradisional pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an.Selama
periode ini, legislatif Korea, partai politik, dan kelompok penekan belum dewasa (Paik
1989). Birokrat pemerintah adalah kelompok elit yang direkrut melalui sistem ujian yang
sangat ketat—pemeriksaan pamong praja yang lebih tinggi yang diundangkan pada tahun
1949 dan diubah pada tahun 1961 dan 1963. Dalam keadaan demikian, pemerintah, di
bawah arahan presiden diktator seperti Park Chunghee, Chun Duwhan, dan Roh Taewoo,
memiliki kekuatan yang kuat, mendorong gagasan untuk pengembangan memimpin
negara, dan memimpin masyarakat dalam banyak hal.
17.2.2 PEMBENTUKAN PARTISIPATIF
Pemerintah pada tahun 1990-an Sejak akhir 1980-an, berkat upaya berkelanjutan
untuk menanamkan semangat demokrasi di Indonesia negara, permintaan publik untuk
berpartisipasi—baik secara formal maupun informal—dalam pengambilan keputusan
pemerintah mulai mendapatkan momentum. Presiden Roh Moo- hyun (2003–2008)
menamai pemerintahan barunya sebagai pemerintahan partisipatif dalam bukunya pidato
pengukuhan pada tahun 2003 dan mengembangkan berbagai jenis peta jalan untuk
214
dipromosikan partisipasi warga negara dan desentralisasi. Pemerintah Lee Myung-bak saat
ini (2008–sekarang) tidak banyak menyimpang dari ketergantungannya pada partisipasi
warga, terutama setelah gejolak nyala lilin melawan Perjanjian Perdagangan Bebas antara
Korea dan Amerika Serikat.
Majelis Nasional dan partai politik mengambil sikap yang semakin kuat terhadap
pemerintah karena otoriter dan formalistik. Berbagai kelompok sosial secara proaktif
mengungkapkan pandangan mereka sendiri. Bahkan warga awam pun mulai mencoba
menyampaikan sudut pandang mereka melalui gerakan kelompok dan pemerintah tidak
dapat mempertahankan sikapnya yang tertutup dan rahasia.
Pemerintah partisipatif telah dibentuk dan distabilkan selama ini tahun 1990-
banyak upaya untuk mereformasi proses pembuatan kebijakan telah dilakukan di 2000-an.
Akibatnya, banyak yang mengambil bentuk kelembagaan yang konkrit. Presiden Komite
Inovasi dan Desentralisasi Pemerintah (2007) menunjukkan tiga bentuk seperti itu.
Yang pertama adalah revitalisasi komunitas kebijakan, yang terdiri dari berbagai
kelompok konferensi yang mengumpulkan pendapat dan membangun konsensus yang luas
antara pemerintah, kelompok kepentingan, pakar, dan pihak terkait di setiap tahapan proses
pembuatan kebijakan.
Upaya kedua adalah perluasan dan peningkatan keterbukaan informasi publik
aksesibilitas. Metode pengungkapan informasi adalah sekarang lebih merupakan gaya
sesuai permintaan dan perlu diubah menjadi lebih proaktif sistem pengungkapan.
Pemerintah saat ini mendorong semua organisasi administratif untuk bergabung dengan
pengungkapan sukarela dan kebijakan akses penuh ini.
Upaya terakhir adalah hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
hal. Di Korea, majelis provinsi didirikan pada tahun 1991 dan penduduknya telah memilih
kepala pemerintah daerah dan anggota dewan provinsi secara langsung sejak itu 1995.
Namun, pemerintah pusat masih menganggap entitas otonom daerah sebagai organisasi
bawahan.
Pendekatan partisipatif memiliki kelemahan. Dan bisa mengundang dis-
menghormati pemerintah, politik di antara kelompok kepentingan, manipulasi strategis
215
kekuasaan, dan mempersempit kepentingan khusus dengan mengorbankan kepentingan
yang lebih sah (Schneider dan Ingram 1997). Meskipun partisipasi umumnya
meningkatkan publik kepercayaan, kegiatan pembangunan konsensus mungkin tidak
secara langsung terkait dengan peningkatan publik kepercayaan kecuali kinerja
administratif membaik. Wang dan Van Wart (2007)berpendapat bahwa integritas
administrasi dan kinerja sangat penting untuk meningkat kepercayaan publik.Partisipasi
publik bahkan bisa menimbulkan konflik baru antara pusat dan daerah pemerintah daerah
yang berdaya. Namun, banyak kasus konflik Korea ternyata sangat destruktif, baik secara
mental maupun fisik, dan telah menciptakan celah yang tidak dapat ditarik kembali antara
pihak-pihak yang berkonflik.
Perintah eksekutif "Pencegahan Konflik dan Resolusi Badan Publik" tahun 2007
mengatur pembentukan saluran komunikasi di lembaga tingkat nasional antara peserta
yang sah untuk agenda kebijakan tertentu. Melalui saluran ini, pejabat pemerintah,
kelompok kepentingan, ahli masalah, dan LSM mungkin memiliki diskusi deliberatif, dan
mediasi dan koordinasi konflik dapat dilakukan dibuat Menggunakan saluran ini pada
dasarnya adalah pengambilan keputusan dan konflik partisipatif pengelolaan. Model baru
akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Publik akan membutuhkannya pengalaman
untuk sistem baru untuk bekerja dengan lancar. Untungnya, perintah eksekutif adalah
komprehensif dan fokus pada upaya tersebut di tingkat kelembagaan. Itu tujuan dari RUU
ini adalah untuk berkontribusi pada persatuan sosial dengan mengintegrasikan kepentingan
sosial yang beragam dan mengelola konflik.
Elemen utama dari peraturan ini termasuk penggunaan analisis dampak konflik dan
pengambilan keputusan partisipatif, serta penciptaan Manajemen Konflik dan Badan
Musyawarah dan Pusat Dukungan Penanganan Konflik, yang berisi Lembaga Arbitrase
Konflik. Manajemen konflik Korea skema relatif lebih dekat dengan apa yang Bingham et
al. (2005) menyebut Legislatif proses yang menggunakan proses-proses seperti demokrasi
deliberatif, versations, penganggaran partisipatif, juri warga, pembuatan kebijakan
kolaboratif, dan berbagai bentuk dialog antarwarga lainnya, daripada mengandalkan proses
kuasi yudisial seperti alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam bentuk mediasi,
fasilitasi, atau arbitrasi.
216
17.3 CONTOH PEMBUATAN KEBIJAKAN
PROSES: KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Dalam proses kebijakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
menetapkan tujuan dasar dan sasaran kebijakan, ulasan dan koordinat kebijakan terkait,
dan membuat standar peraturan untuk implementasi melalui undang-undang fungsi tif.
Meskipun MOE adalah mesin utama untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan
lingkungan nasional, urusan lingkungan hidup begitu besar dan kompleks bahwa entitas
pembuat kebijakan juga termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor KLH setempat,
kementerian dan kantor pemerintah pusat terkait, Presidential Green Growth KPU, dan
pemerintah daerah otonom.
Beberapa kebijakan hanya perlu didiskusikan di dalam KLH. Namun, semakin
banyak program kebijakan membutuhkan pertimbangan tidak hanya di dalam lingkaran
lingkungan, tetapi juga di lingkungan dinas terkait lainnya. Untuk yang terakhir, MOE
pertama-tama membuatnya sendiri proposal melalui diskusi internal kemudian
membandingkan dan berkoordinasi dengan proposal tandingan dari kantor lain melalui
serangkaian pembicaraan manajer tingkat menengah. Kemudian, proposal yang disintesis
melewati pertemuan tingkat manajerial teratas, seperti rapat menteri dan wakil menteri.
Tergantung agenda, keputusan dapat melewati Komisi Pertumbuhan Hijau Presiden.
keputusan kebijakan adalah diselesaikan di Dewan Kabinet sebagai protokol dan akhirnya
dikonfirmasi dengan memperoleh sanksi presiden.
Proses pembuatan kebijakan lingkungan adalah peredaran darah dan kompleks,
sehingga keputusan akhir mungkin berbeda dari awal niat kebijakan (Kim dan So 2001).
Tuntutan banyak pemangku kepentingan untuk berubah kebijakan untuk akun kepentingan
mereka dalam banyak hal untuk tampilan akhir keputusan. Partai yang berkuasa memiliki
dampak melalui pemerintahan formal proses konsultasi ing-party. Partai-partai yang tidak
berkuasa juga memiliki kesempatan untuk membuat argumen tentang isu-isu kebijakan di
Majelis Nasional melalui kegiatan legislatif dan tekanan politik. Banyak lainnya, seperti
perusahaan bisnis dan lingkungan mental LSM, menggunakan kegiatan lobi atau
permintaan formal kepada pemerintah terkait kantor untuk mempengaruhi hasil kebijakan
217
menguntungkan untuk kepentingan mereka. Meskipun MOE bertanggung jawab atas
keseluruhan proses pengambilan keputusan dan kebijakan akhir proses yang ditandai
dengan banyak konflik, negosiasi, tawar menawar, dan membangun konsensus di antara
para pemangku kepentingan kebijakan.
17.4 UPAYA KELEMBANGAAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN
PARTISIPASI PUBLIK
Untuk mengatasi cacat proses pembuatan kebijakan sepihak, pemerintah Korea sedang
bereksperimen dengan berbagai sistem partisipatif. Partisipasi warga negara dapat berupa
bentuk yang beragam dan diwujudkan pada setiap tahap partisipasi: penetapan agenda,
pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Kim et al. 2004).
Sistem partisipatif saat ini dilakukan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
17.4.1 REFERENDUM WARGA NEGARA
Referendum warga negara mungkin merupakan alat yang sangat efektif untuk
menyelesaikan masalah kebijakan yang menantang yang tidak dapat diselesaikan oleh
pemerintah (Y. C. Yang 2007, 94). Meskipun referendum diperkenalkan di Korea pada
tahun 2004, penduduk setempat telah memilih masalah yang tertunda pada beberapa
kesempatan sebelumnya. Acara-acara ini termasuk tempat pembuangan sampah di Ulsan;
konstruksi sistem kereta gantung di Tongyoung; demarkasi batas kota administratif di
Gwangjin-Gu, Seoul; pemindahan kamp Angkatan Darat AS di Inchon; dan pembuangan
limbah nuklir di Buan.
Siapa pun yang berusia 20 tahun atau lebih berhak untuk memilih di bawah sistem
referendum Korea. Kandidat referendum termasuk masalah kebijakan publik yang
menempatkan biaya signifikan pada atau memiliki efek signifikan pada penduduk.
Peraturan daerah menentukan apakah referendum diperlukan. Para pemimpin pemerintah
daerah mungkin berpendapat bahwa referendum diperlukan untuk mendengar pandangan
publik tentang isu-isu yang dapat secara langsung dan signifikan mempengaruhi warga
negara, seperti penciptaan, fusi, atau pencabutan lembaga otonom lokal dan pembangunan
218
fasilitas yang signifikan. Warga juga dapat meminta referendum jika 0,5% dari semua
penduduk melakukannya. Majelis lokal juga dapat meminta referendum jika dua pertiga
dari anggota mendukung dan setidaknya ada setengah dari mereka yang hadir.
17.4.2 PENARIKAN KEMBALI WARGA
Pejabat pemerintah dapat diberhentikan dari posisi mereka sebelum masa jabatan
mereka selesai (Kim 2004) atas tuduhan, petisi, atau suara warga negara. Korea
mengadopsi sistem ini pada tahun 2007. Semua hak ditangguhkan jika setidaknya 10%
penduduk menyatakan niat mereka untuk pemungutan suara ulang. Sepertiga dari
penduduk harus menandatangani Formulir Permintaan Penarikan dan menyerahkan kepada
Komite Pemilihan untuk menyiapkan pemungutan suara, dan pejabat yang bertanggung
jawab dikeluarkan dari kantor dengan suara mayoritas. Citizen recall adalah aparat
keamanan darurat terhadap penggelinciran dari tatanan konstitusional dan menyebabkan
pejabat publik berperilaku etis; namun, fungsinya lebih sebagai pencegahan daripada
koreksi (Myung 2007).
Upaya warga di Goyang dan Gwangju memainkan peran kunci dalam berlalunya
sistem penarikan warga (Kim 2006). Untuk pertama kalinya dalam sejarah nasional,
Goyang berusaha memanggil kembali walikotanya karena secara sewenang-wenang
mengeluarkan izin usaha ke pub dan motel di zona sekolah. Namun upaya itu gagal setelah
serangkaian tuntutan hukum yang membosankan. Di Gwangju, kelompok warga
berpendapat bahwa setidaknya 10 dari 29 pejabat lokal tingkat tinggi yang ditunjuk secara
politik di pemerintahan metropolitan Gwangju terkait dengan korupsi.
17.4.3 LITIGASI WARGA NEGARA
Dalam sistem litigasi warga negara, warga negara sebagai pembayar pajak
memantau kemungkinan kesalahan dan pemborosan pengeluaran publik. Meskipun ada
lembaga audit dan evaluasi publik, warga negara dapat langsung meminta
pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah. Korea memperkenalkan sistem serupa
219
pada tahun 1949, tetapi dihapuskan pada tahun 1988. Amandemen Undang-Undang
Pemerintahan Sendiri Lokal tahun 2006 menghidupkan kembali klausul yang berkaitan
dengan litigasi warga negara.
Salah satu kelompok warga terbesar di Korea, Koalisi Warga untuk Keadilan
Ekonomi, pertama kali mengorganisir komite pengawasan anggaran pada tahun 1999;
LSM melompat ke dalam gerakan setelah itu. Sebagai tanggapan, Kementerian
Perencanaan dan Anggaran menciptakan pusat pengawasan pemborosan anggaran untuk
menerima panggilan semacam itu. Sebanyak 574 kasus dilaporkan pada tahun 2006 (Lee
2007). Panggilan kemudian disampaikan ke lembaga yang bertanggung jawab. Karena
litigasi warga adalah kontrol langsung atas pemborosan anggaran publik, itu belum banyak
digunakan. Tindakan tidak langsung seperti pengawasan anggaran, permintaan audit
warga, atau penarikan warga negara lebih sering digunakan.
17.4.4 PAFRTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEN ANGGARAN
PEMERINTAH
Secara tradisional, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyusun
anggaran. Namun, pemerintah semakin mencerminkan suara warga dalam proses
anggarannya. Sebagai bagian dari inovasi pemerintah, Kementerian Administrasi
Pemerintahan dan Dalam Negeri menyarankan setiap daerah untuk mengikutsertakan
warga negara dalam proses pembuatan anggaran melalui "Pedoman Pembuatan Anggaran
Pemerintah Daerah" dari tahun 2005.
17.4.5 PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM UJI COBA
Sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan, ada banyak diskusi sejak tahun
2000 untuk memperkenalkan sistem juri warga negara atau sistem hakim awam untuk
memastikan partisipasi peradilan warga negara. Akibatnya, Undang-Undang Pengadilan
Pidana Partisipasi Warga Negara, campuran dari juri warga negara dan sistem hakim
awam, disahkan Majelis Nasional pada tahun 2007 dan mulai berlaku pada tahun 2008.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah nasional Korea, warga negara dapat berpartisipasi
220
dalam persidangan kriminal. Namun, bahkan sebelum pengadilan pidana partisipasi warga
secara resmi diperkenalkan di tingkat institusional, Susung gu dari Daegu telah
menggunakan sistem tersebut (Sun dan Kim 2003).
Sistem Korea unik karena mencakup hakim awam dan juri warga negara. Yang
pertama memastikan bahwa pertimbangan juri warga terpisah dari pertimbangan hakim
profesional dan bahwa mereka mencapai keputusan dengan suara bulat dalam setiap kasus.
Yang terakhir memastikan bahwa juri dapat menerapkan aturan mayoritas setelah
mendengar dari hakim yang berpengalaman jika mereka tidak dapat mencapai keputusan
dengan suara bulat. Hakim tidak mengambil bagian dalam percakapan. Hakim dan dewan
juri membahas tingkat keparahan suatu pelanggaran, tetapi hakim membuat keputusan
akhir atas dakwaan tersebut.
17.5 KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DAN PUBLIK
Meskipun pemerintah mengoperasikan sistem partisipatif untuk mempromosikan
partisipasi, itu akan memakan waktu sampai pola pengambilan keputusan yang berpusat
pada birokrasi dan tertutup menghilang. Budaya pengambilan keputusan yang pluralistik
adalah hal baru bagi pemerintah Korea. Meskipun lingkungan politik dan sosial berubah
dengan cepat dan masyarakat sipil telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, pola
pengambilan keputusan yang ada masih inersia dan sebagian besar bergantung pada
birokrasi pemerintah. Singkatnya, kekuatan dan otoritas politik Korea terkonsentrasi di
pemerintahan. Berdasarkan sistem presidensial yang kuat, tidak ada orang lain selain
presiden dan birokrasi yang menjadi inti dari proses pengambilan kebijakan. Majelis
Nasional memeriksa presiden dan pemerintah, tetapi pendulum kekuasaan tidak seimbang
sebagaimana mestinya.
17.5.1 PROSES KEPUTUSAN LOKASI PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR
Tenaga nuklir yang dihasilkan dari 19 pembangkit listrik adalah sumber listrik
utama di Korea, terhitung 40% dari total listrik negara itu. Namun, kapasitas fasilitas
221
pengolahan limbah nuklir mendekati batasnya, dan menemukan lokasi pembuangan limbah
adalah prioritas utama bagi negara tersebut. Pemerintah telah berusaha untuk menemukan
tempat pembuangan limbah nuklir (NWDS) sembilan kali sejak 1986, termasuk di
Anmyundo, Gurupdo, Youngwang, dan Uljin, tetapi upayanya untuk menyelesaikan suatu
tempat telah gagal setiap saat karena tentangan sengit dari penduduk setempat. Kasus ini
menunjukkan dengan sangat baik bahwa proses pengambilan kebijakan pemerintah yang
tidak mengintegrasikan kekhawatiran masyarakat memiliki sedikit peluang untuk berhasil.
17.5.2 PROSES ADOPSI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL
Salah satu dari banyak perselisihan yang terjadi di Korea pada awal milenium baru
adalah Sistem Informasi Pendidikan Nasional (NEIS). Untuk meningkatkan efektivitas
administrasi pendidikan dan memenuhi tuntutan masyarakat umum, NEIS diciptakan untuk
menghubungkan sistem sekolah individu ke Kementerian Pendidikan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (MOEHRD) dan kantor pendidikan lokal melalui Internet
(MOEHRD2001). Orang tua, guru, dan siswa semuanya dapat masuk ke akun sekolah
mereka secara online. MOEHRD berharap bahwa banyak pekerjaan yang sebelumnya tidak
mungkin dilakukan akan dimungkinkan dengan metode online ini. Pemerintah tidak tahu
berapa banyak oposisi yang akan dihadapi proposal NEIS dari pihak-pihak yang
berkepentingan.
Konflik muncul ketika Serikat Guru & Pekerja Pendidikan Korea (KTEWU), yang
sebagian besar anggotanya adalah guru kiri radikal, mengajukan petisi ke Komisi Hak
Asasi Manusia Nasional (NHRC) pada tahun 2003, dengan alasan bahwa NEIS dapat
melanggar hak-hak siswa dan orang tua dan menjadi sasaran peretasan Internet. Alasan
penting lainnya yang tidak muncul dalam petisi, tetapi paling menarik bagi KTEWU,
adalah bahwa NEIS membawa peningkatan beban kerja guru dan staf karena mereka perlu
membuat database besar dengan mengetikkan banyak dokumen tulisan tangan dari sistem
lama serta informasi baru. Terlepas dari kekhawatiran ini, MOEHRD melanjutkan dan
mulai membangun sistem.
222
Birokrasi Korea tidak terkecuali. Kedua kasus Korea menunjukkan bahwa rencana
pengambilan keputusan birokrasi sepihak tidak berfungsi lagi tetapi hanya menimbulkan
konflik yang tidak perlu. Dalam banyak kasus, program kebijakan diketahui warga ketika
diumumkan secara resmi. Partisipasi publik tidak dipanggil pada awalnya, melainkan
sangat enggan pada saat-saat terakhir dalam situasi yang tidak dapat dihindari hanya
setelah pemerintah dipojokkan oleh entitas yang terlibat.
Konflik publik terjadi karena warga negara yang tidak memiliki kesempatan
sebelumnya untuk mengungkapkan pendapat mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka
di luar saluran komunikasi terkait. Kurangnya pengalaman dalam diskusi penuh ide-ide
kebijakan dengan publik dalam tahap perencanaan, Korea belajar dengan cara yang sulit
bahwa pembuatan kebijakan sepihak berdasarkan metode birokrasi menghalangi
komunikasi yang sehat dengan warga negara dan kelompok kepentingan terkait dan
membawa kegagalan dalam kebijakan pemerintah. Model pengambilan keputusan decide–
announce–defend (DAD) di era pembangunan sudah tidak berfungsi lagi. Diperlukan
model baru yang menampilkan saluran komunikasi terbuka antara pemerintah dan
masyarakat.
17.6 KESIMPULAN
Keadaan ekonomi saat ini yang dinikmati negara ini didasarkan pada proses
pembangunan yang dipimpin pemerintah yang dilaksanakan pada 1960-an dan berlanjut
hingga akhir 1980-an. Sampai tahun 1990-an, proses ini terbuka untuk tidak lain adalah
birokrat pemerintah, sebuah kelompok elit di Korea yang memonopoli proses kebijakan
publik. Kemajuan pengambilan keputusan partisipatif di Korea datang dari banyak
pengalaman pahit.
Konflik sosial tercipta karena pemerintah tidak dapat menangani secara efektif
tuntutan publik untuk mencerminkan pendapat mereka melalui partisipasi dalam proses
pengambilan kebijakan. Korea perlu terlibat dalam tindakan lebih lanjut untuk membuat
223
demokrasi bekerja; Proses saat ini tidak efektif dan tidak memberikan ruang yang cukup
untuk partisipasi publik. Banyak masalah yang dapat dihindari atau dikurangi dengan
menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dan deliberatif.
Publik Korea saat ini menginginkan proses kebijakan publik yang lebih terbuka,
transparan, dan partisipatif. Manajer kebijakan publik Korea, yang sekarang bertanggung
jawab atas harapan publik yang beragam, banyak, dan saling bertentangan, semakin
terpanggil untuk mempertimbangkan pendekatan partisipatif dalam proses pembuatan
kebijakan, bahkan ketika mereka membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk
merumuskan kebijakan.
224
BAB 18
Hubungan Antar Pemerintah di Korea:
Dari Ketergantungan Menjadi Kemandirian
18.1 PENGANTAR
Selama setengah abad terakhir, otonomi lokal Korea telah muncul secara terputus-
putus dan pola yang tidak konsisten. Setelah Perang Korea, otonomi daerah menjadi rapuh
tetapi sebagian didirikan. Ketentuan konstitusional tentang otonomi daerah dan
daerahpemilihan secara formal ditentukan dan dialami secara singkat (1960–1961).
Namun,rezim militer dari tahun 1961 sampai 1987 membubarkan dan/atau menindas
otonomi lokal dan menunda pelaksanaannya. Pada tahun 1995, Republik Korea
mengadakan pemilihan local dan, untuk pertama kalinya dalam setengah abad, baik kepala
eksekutif maupun anggota dewan pemerintah daerah dipilih secara populer. Itu adalah
peristiwa penting dalam sejarah hubungan antar pemerintah Korea.
18.2 SETENGAH ABAD BAHASA KOREA
Hubungan Antar Pemerintah Selama setengah abad terakhir, Korea mengalami
perkembangan politik yang signifikan masalah. Meskipun sering terjadi krisis tatanan
konstitusional dan ketidakstabilan politik, negara telah mencapai transisi dan konsolidasi
demokrasi baru-baru ini dan luar biasa
225
18.2.1 OTONOMI DAERAH NOMINAL DAN TERTUNDA (1948-1961)
Sejarah modern pemerintahan sendiri lokal Korea dimulai tak lama setelah Dunia
Perang II ketika konstitusi pertama Republik Korea didirikan pada tahun 1948.Konstitusi
ini mengabdikan dua pasal untuk otonomi daerah. Pasal 96 menyatakan: “Lokal entitas
otonom harus, dalam hukum dan peraturan, berurusan dengan hal-hal yang berkaitan
kepada otonomi daerah dan urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Negara dan mengelola
harta milik mereka sendiri.” Pasal 97 UUD 1948 menjadi dasar masa depan berlakunya
undang-undang tentang pemerintahan sendiri dan otonomi daerah akan tergantung.Hukum
dan frase peraturan menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat dibatasi oleh perintah
eksekutif nasional dan oleh undang-undang. Atas dasar ketentuan konstitusional tersebut,
Rhee Administrasi Syng-Man (1948–1960) memberlakukan Undang-Undang Otonomi
Lokal pada tahun 1949. Undang-undang ini menetapkan pembentukan sistem
pemerintahan daerah yang terdiri dari dua tingkat: (1) pemerintah daerah tingkat atas (kota
metropolitan Seoul dan beberapa provinsi), dan (2) tingkat pemerintah daerah yang lebih
rendah (kota, kabupaten, kota, dan kotapraja). Pelaksanaan otonomi daerah sempat
tertunda akibat Perang Korea (1950–1953).
Dari pemberlakuannya pada tahun 1949 hingga kudeta militer Park Chung-Hee
tahun 1961. Lokal pertama pemilihan diadakan pada tahun 1952 untuk anggota dewan
lokal tingkat bawah dan tingkat atas bukan untuk membangun sistem pemerintahan sendiri
lokal. Sebaliknya, mereka berkembang dan meluas kekuatan politik Presiden Rhee Syng-
Man. Amandemen UU Otonomi Daerah pada tahun 1960 dimaksudkan untuk membangun
demokrasi kerakyatan dan mewujudkan beberapa tingkat otonomi lokal. Namun, otonomi
daerah nyaris tidak terlihat terang sebelum dibayangi dan diatasi oleh kudeta militer yang
dipimpin oleh Jenderal Park Chung-Hee pada tahun 1961.
Komite Revolusi Militer segera menangguhkan otonomi daerah Selama
pemerintahan Taman Nasional (1961–1979), otonomi daerah sepenuhnya ditangguhkan.
Otonomi lokal terbengkalai selama lebih dari seperempat abad. Selama periode ini,
otonomi daerah tidak dapat dijalankan. Konstitusi Republik Keempat (1972–1979), apa
yang disebut konstitusi yusin (1972), menenggelamkan otonomi daerah lebih jauh ke
dalamgelap malam Administrasi Chun Doo-Hawn (1980–1987) melembagakan konstitusi
226
baru, konstitusi ini menunjukkan bahwa jadwal pemulihan dewan lokal akan diputuskan
oleh berlakunya hukum perundang-undangan. Administrasi Chun, seperti administrasi
Park,menunda pembentukan kembali dewan local.
18.2.3 MEMULAI OTONOMI DAERAH (1988-1995)
Konstitusi pemerintahan Roh Tae-Woo (1988–1993) akhirnya menghapus
ketentuan yang membatasi pengenalan dewan lokal.Penguasa yang tidak demokratis
seperti Presiden Park Chung-Hee(1961–1979) dan Presiden Chun Doo-Hawn (1980–
1987) menghapus otonomi local dan menghambat perkembangannya. Akibatnya, otonomi
daerah merosot dan tertunda selama seperempat abad dari rezim militer yang sangat
terpusat. Pemerintahan Kim Young-Sam (1993–1998) mengadakan pemilihan kepala
eksekutif serta anggota dewan pemerintah daerah pada Juni 1995. Pemilihan skala penuh
memilih total 245 kepala eksekutif pemerintah daerah. Pemilihan populer ini membangun
kembali yang bermakna sistem otonomi lokal sederhana dikorea.
18.2.4 MENGEJAR DEVOLUSI SETELAH 1995
Sejak tahun 1995, Korea telah mengadakan empat siklus pemilihan lokal pada
tahun 1995, 1998, 2002, dan 2006. Selama dekade terakhir, otonomi daerah melalui
pemilihan umum telah menjadi bagian yang penting tetapi hanya satu bagian dari sistem
politik dan administrasi Korea. Terlepas dari perkembangan dan perubahan yang luar biasa,
otonomi daerah masih dalam tahap pemula. Sebagian besar kekuasaan, tanggung jawab
kebijakan, dan sumber daya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dari total semua
fungsi pemerintahan, kira-kira seperempatnya dimiliki oleh pemerintah daerah.3 Porsi ini
relatif rendah jika dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Jepang (34%), Prancis
(40%), dan Amerika Serikat (50%). ).4 Devolusi fungsi dan tanggung jawab kebijakan
telah dalam proses implementasi sejak diberlakukannya Devolution Promotion Act pada
tahun 1999.
Ketimpangan pembagian fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dan
daerah, ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal, serta lemahnya self-governing
227
Untuk mengatasi hambatan terhadap otonomi daerah ini, pemerintahan Kim Dae-Jung
(1998–2003) dan Roh Moo-Hyun (2003–2008) memberikan prioritas kebijakan pada
devolusi dengan membentuk komite khusus. Ini adalah Komisi Presiden untuk Promosi
Devolusi pada tahun 19995 dan Komite Presiden untuk Inovasi dan Desentralisasi
Pemerintahan pada tahun 2003.6 Meskipun statistik menunjukkan bahwa lebih banyak
fungsi telah dilimpahkan sejak tahun 1998 dibandingkan dengan periode sebelumnya,
fungsi inti seperti kepolisian dan pendidikan masih belum selesai. kontrol pemerintah
pusat.7 Gubernur dan walikota juga diatur dalam mengatur badan eksekutif mereka sendiri
sampai batas tertentu oleh pemerintah pusat.
Salah satu upaya devolusi yang paling luar biasa adalah pembentukan provinsi
otonomi khusus Jeju. Ini adalah upaya eksperimental untuk memberikan kekuasaan
otonom ke Pulau Jeju—sebuah pulau berorientasi liburan dan resor di lepas pantai selatan
semenanjung Korea. Undang-Undang Khusus tahun 2006 tentang Pembentukan Provinsi
Otonomi Khusus Jeju dan Pengembangan Kota Bebas Internasional memberi Pulau Jeju
kekuatan untuk mengoperasikan sistem sekolahnya sendiri dan fungsi polisi secara
mandiri, serta lebih banyak otonomi dalam mengatur badan eksekutifnya sendiri. Selain
itu, kantor lapangan kementerian nasional diserahkan kepada operasi Provinsi Jeju sendiri
(Komite Presiden untuk Inovasi dan Desentralisasi Pemerintah 2007, 124–126).9
Sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang terdesentralisasi dan
seimbang, pemerintahan Roh Moo-Hyun menjalankan rencana untuk merelokasi 12 dari
18 kementerian utama pemerintah ke luar wilayah ibu kota. Ini termasuk Kantor Perdana
Menteri dan Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Upaya “dekonsentrasi” ini akan
menghasilkan kota administrasi baru (Sejong, kota otonom khusus) kira-kira 80 mil selatan
Seoul. Pemerintah juga mengusulkan untuk memindahkan kantor pusat dari 177
perusahaan milik negara (perusahaan publik) dan organisasi di luar wilayah ibu kota pada
akhir tahun 2012. Apa yang disebut era “lokalisasi” mungkin akan muncul. Jika
berkembang sampai taraf tertentu, itu merupakan pelengkap atau setidaknya pelengkap
otonomi politik, administratif, dan fiskal lokal.
Selama setengah abad terakhir, otonomi pemerintah daerah meningkat secara tidak
teratur tetapi bertahap. Isu otonomi selama ini berpusat pada aspek kelembagaan,
228
khususnya pemilihan umum. Isu ilustrasi yang penting adalah bagaimana membentuk
entitas administratif dan legislatif lokal, bagaimana memilih eksekutif lokal dan anggota
dewan, dan kekuasaan apa yang harus dialokasikan kepada pemerintah lokal.
Pelembagaan pemerintahan sendiri di daerah bukanlah jaminan bahwa otonomi
daerah akan terwujud secara efektif. Bagaimana bisa signifikan, kuat, dan efektifotonomi
daerah dapat terpenuhi? Otonomi hukum, politik, dan administrasi diperlukan, tetapi tidak
cukup, untuk mencapai otonomi. Pemenuhan otonomi daerah yang signifikan
membutuhkan tingkat otonomi fiskal daerah yang substansial. Bagian berikutnya mengkaji
otonomi daerah dalam konteks hubungan keuangan antar pemerintah.
18.3 HUBUNGAN FISKAL ANTAR PEMERINTAH
Pemahaman tentang tren dan variasi fiskal antar pemerintah adalah salah satu syarat
yang diperlukan untuk memahami hubungan antar pemerintah (Wright 1988). Oleh karena
itu kami mencurahkan perhatian khusus untuk pemerintah .
18.3.1 KETIDAKSEIMBANGAN FISKAL VERTIKAL
Distribusi komparatif antara pemerintah pusat dan daerah disebut
“ketidakseimbangan fiskal vertikal.” Dikatakan bahwa sumber daya fiskal pemerintah
daerah tidak cukup untuk mendukung atau menjalankan sistem baru pemerintahan sendiri
daerah. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, sumber daya fiskal tambahan perlu
ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah atau lebih banyak pendapatan yang dihimpun di
daerah. Pergeseran seperti ini akan meningkatkan prospek sistem otonomi daerah yang
efektif. Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal: Kota dan Provinsi
Distribusi sumber daya keuangan antar pemerintah daerah di Korea tidak merata.
Kemandirian finansial (atau kemandirian) pemerintah daerah tingkat atas, Ini menampilkan
pendapatan asli daerah untuk kota besar dan provinsi sebagai persentase dari total
pendapatan. Tabel tersebut menunjukkan pola swasembada keuangan yang jelas untuk
229
pemerintah daerah tingkat atas. Kota-kota metropolitan memiliki tingkat PAD yang jauh
lebih tinggi. Seoul tampaknya beroperasi tanpa bantuan keuangan konsekuen dari
pemerintah pusat. Pemerintah kota metropolitan lainnya memperoleh 60–75% dari
pendapatan mereka secara swadaya.
Dengan satu pengecualian, pemerintah provinsi berangkat secara dramatis dari
kota-kota metropolitan. Daerah-daerah ini jarang mendapatkan sepertiga dari pendapatan
mereka dari sumber mereka sendiri. Namun, Provinsi Gyeonggi (terletak di sekitar Seoul)
mendanai tiga perempat pendapatannya dari sumbernya sendiri. Semua pemerintah
provinsi lainnya hanya mendanai 20–40% dari anggaran mereka dari sumber mereka
sendiri. Provinsi Jeolla
18.3.2 Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal: Kota dan Provinsi
Distribusi sumber daya keuangan antar pemerintah daerah di Korea tidak merata.
Ini menampilkan pendapatan asli daerah untuk kota besar dan provinsi sebagai persentase
dari total pendapatan. Pola swasembada keuangan yang jelas untuk pemerintah daerah
tingkat atas. Kota-kota metropolitan memiliki tingkat PAD yang jauh lebih tinggi. Seoul
tampaknya beroperasi tanpa bantuan keuangan konsekuen dari pemerintah pusat.
Pemerintah kota metropolitan lainnya memperoleh 60–75% dari pendapatan mereka secara
swadaya.
Dengan satu pengecualian, pemerintah provinsi berangkat secara dramatis dari
kota-kota metropolitan. Daerah-daerah ini jarang mendapatkan sepertiga dari pendapatan
mereka dari sumber mereka sendiri. Namun, Provinsi Gyeonggi (terletak di sekitar Seoul)
mendanai tiga perempat pendapatannya dari sumbernya sendiri. Semua pemerintah
provinsi lainnya hanya mendanai 20–40% dari anggaran mereka dari sumber mereka
sendiri. Provinsi Jeolla.
18.3.3 Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal: Semua Pemerintah Daerah
230
Swadaya keuangan dapat dilihat dari perspektif lokal alternatif. Tabel 18.3
menunjukkan swasembada keuangan untuk tingkat pemerintahan daerah yang lebih rendah
dan lebih tinggi. Pemerintah tingkat bawah adalah kotamadya (77), kabupaten (88), dan
distrik otonom (69). Persentase dalam tabel menunjukkan tingkat relatif otonomi fiskal
daerah yang diukur dengan ketergantungan pada pendapatan asli daerah untuk empat
kategori pemerintah daerah. Lebih dari setengah (53%) dari semua pemerintah daerah
memperoleh kurang dari 30% dari pendapatan mereka dari sumber mereka sendiri. Dengan
kata lain, lebih dari dua pertiga anggaran mereka bergantung pada bantuan keuangan
eksternal.
Situasi keuangan pemerintah daerah tingkat bawah (pemerintah kota, kabupaten,
dan kabupaten otonom) sangat penting. Tabel 18.3 mengungkapkan kelemahan fiskal
banyak pemerintah daerah tingkat bawah. Lebih dari setengah dari 16 kota metropolitan
dan pemerintah provinsi melaporkan 50% atau lebih swasembada keuangan. Di antara 234
pemerintah daerah yang lebih rendah, hanya 30 (13%) yang mencapai tingkat swasembada
ini. Masalah keuangan yang paling serius ditemukan di antara pemerintah daerah. Lebih
dari 90% dari 88 pemerintah ini mengamankan kurang dari 30% anggaran mereka dari
sumber mereka sendiri.
Tiga pola ketidakseimbangan fiskal horizontal di antara pemerintah daerah Korea
telah diidentifikasi. Pertama, pemerintah daerah tingkat atas relatif kuat dalam swasembada
keuangan. Kedua, pemerintah kota perkotaan dan metropolitan mendapatkan swasembada
keuangan yang jauh lebih tinggi daripada pemerintah pedesaan, dan pemerintah kabupaten
melaporkan swasembada keuangan terendah. Ketiga, pemerintah daerah di dekat Seoul,
ibu kota Korea, secara konsisten lebih mandiri secara finansial. Seoul dan kota-kota
terdekat adalah pusat kegiatan politik dan ekonomi. Populasi dan basis pajak mereka cukup
untuk mengamankan tingkat otonomi fiskal lokal yang relatif lebih tinggi.
18.4 TRANSFER FISKAL ANTAR PEMERINTAH
Sistem transfer fiskal antar pemerintah biasanya ada untuk mengatasi
ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal. Pemerintah pusat biasanya memberikan
231
beberapa atau dukungan keuangan yang signifikan kepada pemerintah daerah.
Kesenjangan antara kebutuhan fiscal dan pendapatan asli daerah biasanya diisi oleh
transfer fiskal antar pemerintah. Tiga jenis transfer fiskal antar pemerintah telah beroperasi
antara pemerintah pusat dan daerah: (1) pajak bagi hasil daerah, (2) subsidi nasional (hibah
bantuan), dan (3) dana transfer daerah. Namun, sejak tahun 2004, dana transfer daerah telah
dihentikan dan digantikan oleh rekening khusus pembangunan berimbang nasional.
18.4.1 PAJAK BAGI HASIL DAERAH
Pajak bersama lokal adalah dana di mana persentase tetap dari pajak domestik
nasional dialokasikan untuk ditransfer secara otomatis ke pemerintah daerah. Pemungutan
pajak nasional ini dibagi dengan semua pemerintah daerah. Sistem pajak bersama ini
diperkenalkan pada tahun 1951 dan telah diubah beberapa kali. Pada tahun 1969, sistem
tersebut mengalokasikan 17,6% dari total pemungutan pajak dalam negeri kepada
pemerintah daerah. Namun, dari tahun 1973 hingga 1982, sistem tersebut ditangguhkan
oleh administrasi Park Chung-Hee. Selama periode itu, pemerintah pusat setiap tahun
menentukan jumlah yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Hal ini jelas
menempatkan sejumlah besar diskresi di tangan pejabat pusat untuk memberi penghargaan
(atau menghukum) pemerintah daerah dan/atau pejabat daerah.
Sistem pajak bersama dipulihkan pada tahun 1983 dan mencadangkan 13,27% dari
pendapatan pajak dalam negeri untuk transfer fiskal. Pada tahun 2000, persentase tetap
ditingkatkan menjadi 15% oleh pemerintahan Kim Dae-Jung. Pemerintahan Rho Moo-
Hyun meningkatkan pangsa lagi menjadi 18,3, 19,13, dan 19,24% masing-masing pada
tahun 2004, 2005, dan 2006. Kenaikan tahun 2004 sebenarnya merupakan kompensasi atas
penghapusan dana transfer daerah. Kenaikan lebih lanjut pada tahun 2005 dan 2006
dihasilkan dari transfer hibah yang diperinci ke dana umum tanpa menyerahkan beberapa
program subsidi nasional kepada pemerintah daerah.10 Oleh karena itu, kenaikan tarif
baru-baru ini tidak dapat dianggap sebagai kenaikan bersih dalam transfer fiskal antar
pemerintah.
232
Sistem pajak bersama lokal mengatasi ketidakseimbangan fiskal baik vertikal
maupun horizontal. Penambahan sumber daya fiskal daerah dan pemerataan kemampuan
fiskal daerah dimaksudkan agar semua pemerintah daerah dapat memberikan tingkat
pelayanan publik dasar yang dapat diterima kepada penduduk setempat.
Ada dua subkategori pajak bersama daerah: umum dan khusus. Pajak bagi hasil
umum terdiri dari 90,9% dari total pajak bagi hasil daerah dan dialokasikan berdasarkan
formula yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan dalam perintah eksekutif
presiden yang disiapkan oleh Kementerian Pemerintahan dan Dalam Negeri.11 Pajak bagi
hasil khusus adalah 9,1% dari total pajak bersama. Dana ini diberikan berdasarkan
kebutuhan khusus daerah. Administrasi pajak bersama khusus tunduk pada kekuasaan
diskresioner dari pemerintah pusat. Persentase pajak bagi hasil khusus diturunkan dari 9,1
menjadi 4% pada tahun 2004 karena meningkatnya kritik tentang alokasi dana yang
sewenang-wenang oleh pemerintah pusat. Sisanya 96% dibagikan dengan rumus pajak
bagi hasil umum.
Sebaliknya, formula yang telah ditentukan sebelumnya untuk pajak bagi hasil
umum tidak memberikan ruang bagi keleluasaan oleh pemerintah pusat. Tujuan formula
alokasi pajak bagi hasil umum daerah adalah untuk mengkompensasi perbedaan antara
kebutuhan fiskal dan penerimaan pajak pemerintah daerah. Defisit fiskal yang dihitung
adalah indeks yang digunakan untuk alokasi pajak bagi hasil umum daerah.
18.4.2 SUBSIDI NASIONAL
Pajak bersama daerah diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan
kebijaksanaan umum, sedangkan subsidi nasional untuk proyek-proyek khusus. Subsidi
nasional dialokasikan untuk (1) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan proyek-
proyek tertentu yang disukai oleh pemerintah pusat, dan (2) memberikan bantuan keuangan
untuk acara-acara khusus atau tidak biasa (misalnya festival olahraga nasional yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pemulihan bencana alam).
233
Fitur utama dari sistem hibah proyek ini adalah karakter kondisionalnya. Ada
batasan atau batasan khusus untuk penggunaan hibah dalam bantuan. Kondisi biasanya
berlaku untuk penggunaan substantif uang hibah dan memerlukan kondisi lain seperti
pencocokan, perencanaan sebelumnya, akuntansi, dan pelaporan.
Satu masalah dengan program hibah nasional ini adalah bahwa pemerintah daerah
yang memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi persyaratan pencocokan
secara aktif mengajukan dana nasional. Pemerintah daerah dengan sumber daya fiskal,
kemampuan dan keterampilan administratif, serta jaringan politik yang efektif yang terkait
dengan pemerintah pusat lebih mungkin untuk mendapatkan hibah nasional. Kritik lain
melibatkan kecilnya subsidi yang diperinci. Seringkali prioritas proyek yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat bertentangan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Porsi subsidi
nasional untuk total transfer antar pemerintah berfluktuasi tetapi telah meningkat secara
signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Variabilitasnya mempengaruhi stabilitas dan
prediktabilitas keuangan lokal. Tabel 18.4 melaporkan jumlah nominal (dalam won)
subsidi nasional.
18.4.3 REKENING KHUSUS PEMBANGUNAN PERIMBANGAN NASIONAL
Neraca khusus pembangunan berimbang nasional diperkenalkan untuk
mempromosikan revitalisasi daerah-daerah yang tertekan; pengembangan budaya, seni,
dan pariwisata lokal; dan pengembangan strategis klaster industri regional. Beberapa
sumber keuangan mendanai rekening khusus. Ini termasuk hasil dari pendapatan pajak
minuman keras dan transfer dari beberapa rekening khusus. Contoh rekening khusus
tersebut adalah restrukturisasi pedesaan, perbaikan lingkungan, dan pengelolaan lahan
(Komite Presiden Inovasi Pemerintah dan Desentralisasi 2005, 43-44). Meskipun
mengelompokkan program-program yang dioperasikan secara terpisah oleh berbagai
kementerian ke dalam satu rekening memiliki keuntungan untuk membentuk program
pemerintah, proses pengajuan pendanaan dari rekening khusus pembangunan berimbang
nasional telah menjadi sangat rumit (Komite Presiden untuk Inovasi Pemerintah dan
Desentralisasi 2007, 163–164).
234
18.4.4 DANA TRANSFER LOKAL
Program hibah ini diperkenalkan pada tahun 1991 dan beroperasi hingga tahun
2004. Program ini dimaksudkan terutama untuk mengamankan pembangunan daerah yang
lebih seimbang serta berfungsi sebagai pelengkap sumber daya fiskal daerah. Penyaluran
dana ini diatur dalam UU Dana Transfer Daerah. Sumber daya program hibah ini berasal
dari beberapa sumber pajak (misalnya, pajak minuman keras, pajak transportasi, dan pajak
pembangunan pedesaan). Proyek-proyek yang ditunjuk dimana dana ini dapat digunakan
adalah pemeliharaan jalan, pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, pencegahan
pencemaran air, dukungan pemuda, dan pembangunan daerah.
Pemeliharaan jalan merupakan proyek yang paling signifikan dari program hibah
ini. Sekitar 40–50% dari dana transfer daerah dihabiskan untuk pemeliharaan jalan selama
periode ini.12 Program hibah ini juga berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan. Sekitar
25–33% dari uang hibah dialokasikan untuk proyek pencegahan pencemaran air. Selain
itu, program tersebut mendorong pembangunan daerah. Sejumlah besar dana (sekitar 20%)
dihabiskan untuk pembangunan lokal, dan kurang dari 10% dialokasikan untuk
pengembangan kawasan pertanian dan perikanan. Alokasi hibah itu atas dasar formula
yang ditentukan dalam Undang-Undang Dana Transfer Lokal. Hibah pemeliharaan jalan,
misalnya, dialokasikan secara proporsional dengan jarak jalan lokal di masing-masing
pemerintah daerah. Dana transfer lokal dikritik karena sumber pendapatan dan operasi
aktualnya. Minuman keras, transportasi, dan pajak pembangunan pedesaan, yang
merupakan sumber dana transfer daerah, diberlakukan dan dikelola sebagai pajak
purposive (earmarked).
Namun, ada kekurangan hubungan langsung antara sumber pendapatan dan
pengeluaran. Dalam hal pengoperasian dana, pemerintah daerah memiliki beban dana
pendamping, meskipun ini bukan tujuan awal dari dana tersebut (Komite Presiden untuk
Inovasi dan Desentralisasi Pemerintah 2007, 163–164).
Dana transfer daerah dihapuskan pada tahun 2004, dan pendapatan untuk program
ini dialihkan ke pajak bagi hasil daerah, subsidi nasional, dan rekening khusus
pembangunan berimbang nasional. Penghapusan dana transfer daerah mengurangi
235
kerumitan sistem keuangan daerah. Namun, hal itu juga memperlemah tingkat otonomi
fiskal daerah karena subsidi nasional dan neraca khusus pembangunan nasional
dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini mengurangi kewenangan diskresi
lokal.
18.4.5 SUMBER PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH: GAMBARAN
UMUM
Analisis sumber pendapatan pemerintah daerah ditujukan untuk memahami
pentingnya transfer fiskal antar pemerintah serta jenis dan pola swasembada fiskal yang
lebih besar atau lebih kecil. Tabel 18.6 memberikan dasar untuk mendapatkan gambaran
umum. Pemerintah daerah di Korea bergantung pada tiga jenis sumber pendapatan utama:
1) Pendapatan asli daerah, (2) transfer fiskal antar pemerintah, dan (3) pinjaman daerah. Selama
6 tahun terakhir, hampir dua pertiga dari pendapatan mereka dikumpulkan dari sumber mereka
sendiri—yaitu, pajak daerah dan pendapatan bukan pajak. Setengah dari pendapatan asli daerah
berasal dari pajak daerah dan setengah lainnya dari pendapatan bukan pajak seperti retribusi
dan biaya lain-lain. Sumber pendapatan utama kedua adalah transfer fiskal antar pemerintah.
Pemerintah daerah mengamankan sedikit lebih dari sepertiga dari pendapatan mereka melalui
transfer fiskal antar pemerintah. Ketergantungan pada pendapatan antar pemerintah di antara
pemerintah daerah telah stabil. Pemerintah daerah mengandalkan pajak bersama daerah dan
subsidi nasional (hibah bantuan) hampir sama.
2) Mereka masing-masing menyumbang 13–18% dari total pendapatan daerah. Proporsi dana
transfer lokal sekitar 5%. Bagi hasil pajak dan subsidi nasional jauh lebih penting daripada
dana transfer daerah. (Kategori terakhir ini berhenti setelah 2004.)
3) Pemerintah daerah Korea memiliki tingkat ketergantungan yang substansial (namun sangat
bervariasi) pada transfer pemerintah pusat. Ketergantungan pada hubungan donor-penerima
(Pressman 1975) menyebabkan hubungan kekuasaan yang bervariasi antara pemerintah pusat
dan daerah. Namun, pola kekuatan asimetris jauh dari pandangan eksklusif (Ingram 1977).
Pendekatan kami untuk memahami
236
18.5 KESIMPULAN: DARI KETERGANTUNGAN MENUJU INTERPEDENSI
Pertama, selama setengah abad terakhir, otonomi lokal Korea telah berkembang
cara yang terputus dan tidak konsisten. Selama pemerintahan Partai Demokrat (1960–
1961), otonomi lokal rapuh tetapi sebagian mapan. Konstitusional penetapan otonomi
daerah dan pemilihan kepala daerah secara formal dan singkat berpengalaman. Namun,
rezim militer (1961–1987) membubarkan atau menindas local. otonomi dan menunda
pelaksanaannya. Pembangunan ekonomi, administrasi efisiensi, dan reunifikasi lebih
diutamakan daripada perwujudan otonomi daerah dan salah satu hasilnya adalah
penundaan jangka panjangnya. Namun, sejak awal 1990-an, seiring dengan perkembangan
demokrasi Korea, beberapa derajat otonomi lokal telah muncul.
Pergeseran otonomi lokal Korea dapat disimulasikan secara grafis oleh Gambar
18.1. Garis lengkung dari tahun 1950 hingga sekarang ditampilkan secara kasar namun
mendekat kebangkitan, kejatuhan, dan kebangkitan otonomi daerah. Garis putus-putus dari
sekarang maju menunjukkan prospek masa depan untuk otonomi lokal Korea. Ada empat
jalur yang mungkin: peningkatan cepat, peningkatan inkremental, status quo, dan
penurunan menolak. Hasil dari serangkaian kebijakan devolusi saat ini yang mengatasi
hambatan otonomi daerah akan mempengaruhi arahnya di masa depan. Mungkin yang
paling mungkin garis tren kedua: peningkatan bertahap dalam otonomi daerah.Pengamatan
kedua menekankan hubungan antara otonomi lokal dan demokratisasi.
Ketiga, otonomi lokal Korea dan perkembangannya sangat bergantung pada pilihan
politik dan kebijakan pemerintah pusat. Sejak awal 1990-an, langkah besar menuju
otonomi daerah telah diambil oleh pemerintah pusat untuk reformasi masyarakat Korea,
pada umumnya, dan sistem pemerintahan pada khususnya.
Keempat, ikhtisar hubungan fiskal antar pemerintah ini mengidentifikasi keduanya
secara vertical dan ketidakseimbangan fiskal horizontal. Skema transfer fiskal antar
pemerintah yang baru atau yang direvisi sangat penting jika upaya untuk mengurangi
ketidakseimbangan fiskal ingin dilakukan berhasil. Hal ini penting karena otonomi lokal
secara hukum dan administratif sering terjadi fasad tanpa tingkat otoritas fiskal lokal yang
signifikan. Kelima, transfer fiskal antar pemerintah merupakan sumber pendapatan
237
penting untuk mayoritas pemerintah lokal Korea. Sepertiga dari anggaran mereka, rata-
rata, adalah dijamin dari pendapatan antar pemerintah. Namun, angka ini sangat
menyesatkan.
Terakhir, pelaksanaan diskresi pada urusan lokal merupakan prinsip penting dari
otonomi daerah. Di Korea, bagaimanapun, pengawasan administrasi yang kuat dan
pemantauan pemerintah daerah oleh instansi pemerintah pusat terus berlanjut banyak
bidang operasi pemerintah daerah. Untuk mencapai Realitas penuh otonomi lokal,
hubungan pusat-daerah harus bergeser dari hubungan vertikal-koersif ke hubungan tawar-
menawar horizontal. Ini membutuhkan budaya yang signifikan dan perubahan perilaku
serta kelembagaan, yang tidak dapat dicapai dalam semalam. Otonomi lokal di Republik
Korea merupakan isu IGR yang menjadi contoh hampir semuanya dari beberapa variabel
yang ditentukan dalam panorama penjelasan Norton.
238
BAB 19
ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN UPAYA ANTIKORUPSI DI
KOREA SELATAN
19.1 PENGANTAR
Bab ini mengulas korupsi birokrasi dan etika administrasi di Korea Selatan.
Kekhawatiran tentang korupsi yang terus berlanjut semakin membuat khawatir para
pejabat yang, dalam dekade terakhir, telah mengambil langkah-langkah untuk
memberantasnya. Tingkat transparansi Korea berada di peringkat yang jauh lebih rendah
daripada kinerja ekonomi: peringkat ke-43 versus peringkat ke-13 di dunia.
Bab ini membahas perubahan dan penyebab korupsi di Korea Selatan dari waktu
ke waktu, membandingkannya dengan negara-negara Asia lainnya, dan mengkaji teori-
teori yang bersaing untuk penyebabnya. korupsi. Ini juga memberikan ulasan tentang
inisiatif antikorupsi di bawah pemerintahan Korea yang berbeda dari Park Chung-hee
hingga Roh Moo-hyun. Bab ini diakhiri dengan ikhtisar kebijakan dan undang-undang
antikorupsi utama dan menunjukkan bahwa persepsi korupsi perlahan membaik di Korea
Selatan.
19.2 KORUPSI DI KOREA SELATAN
Pelayanan publik telah lama dihormati sebagai pekerjaan bergengsi di Korea.
Cendekiawan di dinasti Joseon (AD 1392~1910) mencoba mewujudkan masyarakat ideal
yang diimpikan oleh Konfusianisme, yang merupakan ideologi resmi penguasa. Dinasti
ingin merekrut sarjana kebijaksanaan dan kebajikan, dan standar etika yang lebih tinggi
diperlukan untuk mereka (Choe 1974).
Secara umum, pembenaran moral terhadap birokrasi di Korea berasal dari
Konfusianisme. Menurut Frederickson (2002), ajaran sentral Konfusianisme dalam
kaitannya dengan birokrasi dapat diringkas sebagai berikut: aturan manusia, penekanan
239
pada elit moral, pentingnya konvensi moral, dan menempatkan nilai tinggi pada
pendidikan. lihat Frederickson untuk diskusi yang lebih rinci). Pejabat publik dinasti
berusaha mewujudkan ajaran esensial Konfusianisme tentang birokrasi dalam politik
nyata.
Dinasti Joseon mencoba merekrut orang-orang seperti itu melalui ujian negara yang
ketat dan sangat kompetitif, yang disebut gwageo, yang didirikan pada masa dinasti Goryeo
(958 M). Meskipun sifat dan isi ujian untuk pelayanan publik berubah secara signifikan
selama bertahun-tahun, prestise dan hak istimewa ujian tersebut bertahan hingga saat ini,
dan ujian resmi adalah cara dominan bagi orang untuk memasuki layanan publik saat ini.
Misalnya, dari 352 pejabat dari 1392 hingga 1600 yang bertugas di Dewan Negara, yang
merupakan lembaga pembuat kebijakan tertinggi dan terdiri dari tiga anggota, 304 (86,4%)
masuk ke pemerintahan melalui gwageo (Choe 1974).
Pejabat publik memiliki kekuasaan besar atas kehidupan sehari-hari orang-orang
yang mereka pimpin. Banyak birokrat di dinasti Joseon adalah birokrat yang baik sering
dipuji. Mereka disebut chungbaekri (birokrat bersih) dan orang awam sering mengangkat
batu yang mencatat perbuatan baik mereka setelah masa jabatan mereka berakhir.
Chungbaekri sering dipuji dan dipandang sebagai contoh ideal untuk diikuti oleh birokrat
lain. Namun, seperti namanya, tidak semua orang baik atau bersih. Pejabat memiliki
banyak kesempatan untuk memerintah dengan cara yang kejam dan, terutama pada periode
akhir dinasti, terjadi korupsi serius terkait dengan berbagai jenis pajak.3 Di tahun-tahun
berikutnya, hal ini akan melemahkan fondasi keuangan dinasti dan mendorong
keruntuhannya.
Ada diskusi tentang pengaruh Konfusianisme terhadap korupsi di Korea. Di satu
sisi, ajaran Konfusianisme mendorong orang untuk bertindak dengan benar dan benar,
tetapi di sisi lain, Konfusianisme juga mengajarkan ketaatan pada kekuasaan dan otoritas
(Park, Regh, dan Lee 2). Beberapa pejabat publik di dinasti Joseon menentang raja untuk
menunjukkan kesalahannya dan dihukum atau bahkan dipenggal kepalanya karena
tindakan tersebut. Mereka sering menerima kematian seperti itu sebagai suatu kehormatan
dan perbuatan mereka sering dikenang sebagai contoh yang harus diikuti. Namun
penekanan pada hubungan interpersonal yang harmonis cenderung melemahkan upaya
240
whistleblowing “Waktu telah berubah, tetapi peluang untuk korupsi berlimpah”. Salah satu
tema paling umum ditemukan dalam keterikatan antara bisnis dan pemerintahan di Korea.
Park (2006) berpendapat bahwa alasan utama korupsi di Korea Selatan terkait dengan:
1) Kebijakan pembangunan ekonomi yang dipimpin pemerintah yang menghasilkan hubungan erat
antara elit politik dan bisnis (yang disebut Kang (2002a) sebagai “kapitalisme kroni”)
2) Pertumbuhan ekonomi yang eksplosif dan
3) Peraturan pemerintah yang berlebihan.
Grup bisnis, yang disebut chaebol, dikendalikan oleh satu keluarga. Luo berpendapat
bahwa “keterikatan intim para chaebol dengan pemerintah berturut-turut dan politisi
terkemuka” di Korea Selatan dapat dilihat sebagai hubungan bisnis antar pribadi, di antara
para pemain kunci. Kebijakan ekonomi yang dipimpin pemerintah disertai dengan peraturan
bisnis yang berlebihan oleh birokrasi yang terkadang menimbulkan biaya keuangan yang
tinggi untuk bisnis. Elit politik, kemudian, menggunakan kekuatan regulasi mereka untuk
meminta dana politik dari chaebol sebagai imbalan atas kesepakatan bisnis dan kontribusi
politik yang istimewa.
Kebijakan secara mandiri. “Otonomi tertanam” ini merupakan karakteristik negara
berkembang yang konon menjadi kunci efektivitas pemerintah Korea dan kebijakannya.
Evans berpendapat bahwa tradisi Konfusian memperkuat konsep birokrasi meritokratis dan
"korps elit" di mana korupsi dipandang sebagai pelanggaran akhir karir yang melarang
pekerjaan sektor publik di masa depan (1995, 51-54).
Selain itu, berbagai bentuk korupsi, nepotisme, dan pemberian hadiah juga merupakan
bagian dari lanskap Korea. Park dkk. (2005, 189) berpendapat bahwa faktor sosial-budaya
seperti “otoritarianisme, faksionalisme dan favoritisme” terkait dengan penyebaran korupsi.
Fukuyama (1995) mencatat kekeluargaan Konfusius8 sebagai faktor potensial dalam
mendorong nepotisme dan pertukaran hadiah dalam masyarakat kapitalisme kroni. Tentu saja,
praktik tradisional membangun hubungan bisnis pribadi yang erat di Korea memberikan
peluang untuk korupsi, yang mencakup pemberian hadiah yang berlebihan dan pola sosial
seperti seringnya bersosialisasi dan minum setelah jam kerja. Meskipun pola-pola ini agak
241
berkurang dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa pengusaha telah membatasi pemberian
hadiah di antara karyawan, praktik tersebut masih berlanjut.
Fukuyama (1995, 131) berpendapat bahwa kekeluargaan di Korea membuat negara
tersebut lebih individualistis dibandingkan dengan Jepang; namun, individualisme sebenarnya
adalah “persaingan keluarga atau garis keturunan”. Seringkali, chaebol memperluas cakupan
keluarga atau garis keturunan ke seluruh grup bisnis. Grup Daewoo, salah satu chaebol
terbesar, yang hancur selama krisis keuangan Asia, menyebut dirinya keluarga Daewoo.
Perluasan yang sama dari konsep garis keturunan berlaku untuk birokrasi. Jika seseorang
berasal dari kementerian yang sama, lulus ujian pegawai negeri pada tahun yang sama, atau
lulus dari universitas atau sekolah menengah yang sama, seseorang secara otomatis menjadi
anggota “klan” dan diminta untuk setia demi kepentingan kelompok. Budaya seperti itu
cenderung memperlakukan pelapor sebagai pengkhianat.
Namun, kekeluargaan telah melemah selama bertahun-tahun. Hal ini dapat dijelaskan oleh
berbagai faktor, tetapi salah satu yang utama adalah meningkatnya partisipasi modal asing
dalam pengoperasian chaebol. Misalnya, per Agustus 2009, lebih dari 47% saham Samsung
Electronics dimiliki oleh orang asing (Samsung Electronics 2009). Meningkatnya partisipasi
asing memberikan tekanan pada chaebol untuk memaksimalkan kepentingan pemegang
saham daripada kepentingan keluarga pemilik. Meningkatnya kepemilikan asing atas chaebol
telah menciptakan keretakan dalam hubungan lama antara pemerintah dan chaebol.
Faktor lainnya adalah gerakan sipil. Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif
memainkan peran penting dalam membuat chaebol lebih transparan. Beberapa dorongan
inovasi pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah faktor lainnya. Gerakan inovasi tersebut
berusaha menjadikan birokrasi lebih profesional dan rasional serta mengubahnya menjadi
organisasi yang lebih efisien. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab-bab berikut. Salah
satu faktor yang tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap meluasnya korupsi di Korea
adalah bahwa elit politik tidak berbuat banyak tentang hal itu di banyak negara pasca perang
Dunia.
242
Di luar ini, orang Korea biasa memiliki sedikit cara untuk mengatasi korupsi politik;
misalnya, kebebasan berbicara dan pers sangat dibatasi di bawah aturan otokratis Rhee
Syngman dan Park Chung-hee. Lie (1998) berpendapat bahwa otoritas pemerintah atas
masyarakat sipil dan bisnis di bawah pemerintahan Park Chung Hee menyebabkan korupsi
pada skala yang jauh lebih besar dan dengan cara yang lebih meresap daripada yang dilakukan
pemerintahan Rhee Syngman.
19.3 TINGKAT KORUPSI
Sebagian besar data korupsi sistematis di Korea ada untuk periode setelah 1995, dengan
beberapa kembali ke 1980; namun, data korupsi yang sangat terbatas ada untuk periode sebelum
1980. Tabel 19.1 menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi birokrasi yang dilaporkan meningkat
setelah demokratisasi pada tahun 1987. Namun, perlu dicatat bahwa angka sebelum dan sesudah
Kim Young-sam tidak cocok. Juga, seperti yang dijelaskan sebelumnya, rezim Kim Young-sam
memulai kampanye anti-korupsi sebagai salah satu prioritas utamanya, yang menyebabkan
peningkatan laporan korupsi birokrasi. Jumlah transaksi ilegal meningkat selama bertahun-tahun
dan memuncak pada rezim Roh Moo-hyun.
Hubungan antara pemerintah dan chaebol selama tahun 1980-an dan 1990-an sangat dekat
dan kolusi, dan itu tercermin dalam sumbangan. Misalnya, chaebol seperti Samsung, Hyundai,
Donga, dan Daewoo memberikan sumbangan politik ilegal kepada Presiden Chun yang berkisar
antara 15 hingga 22 milliar won; Samsung Hyundai, Daewoo, dan LG memberikan kontribusi
politik ilegal kepada Presiden Rho Tae-woo antara 21 dan 25 miliar won. Baik Presiden Chun
maupun Presiden Roh menerima sejumlah besar sumbangan politik tidak resmi. Secara khusus,
Chun bertemu dengan pemilik 30 chaebol besar dan mengumpulkan 5 miliar won dari masing-
masing; dia memberikan 100 miliar won kepada Roh untuk kampanye kepresidenannya (Oh dan
Sim 1995; Anda 2005).
Meskipun Presiden Kim Young-sam tidak secara langsung menerima sumbangan politik
dari para chaebol selama masa kepresidenannya, ia menerima sekitar 60 miliar won dari Chung
Tae-soo, kepala Grup Hanbo, dalam pemilihan presiden 1992 (Woo 1991, 60). Samsung secara
243
ilegal menyumbangkan setidaknya 10 miliar won dan 34 milliar won (8 dan 22 miliar won pada
harga konstan 1990) kepada Lee Hoi-chang dalam pemilihan presiden 1997 dan 2002 (PSPD 2005;
dibacakan dari You 2005). Chung Ju-Young, pendiri Hyundai Group, ditemukan telah
menyumbangkan 2~3 bil- singa menang dua kali setahun kepada Presiden Roh Tae-woo serta 10
miliar won kepadanya pada tahun 1992.
Sumbangan ilegal ini digunakan terutama untuk pemilihan presiden. Sumbangan Chaebols
cenderung berkonsentrasi pada kandidat untuk partai yang berkuasa. Tetapi mereka melindungi
taruhan mereka dengan memberikan sumbangan politik kepada partai oposisi juga. Selain itu,
presiden membutuhkan uang untuk mengendalikan anggota partai mereka, terutama anggota
Majelis Nasional. Sebagai pemimpin partainya, presiden diharapkan dapat memberikan bantuan
keuangan bagi kandidat partai yang berkuasa untuk pemilihan umum. Donasi ilegal digunakan
untuk tujuan tersebut. Namun, Presiden Chun Doo-hwan dan Presiden Roh Tae-woo ditemukan
telah mengumpulkan kekayaan untuk tujuan pribadi mereka, berbeda dengan penerus mereka.
19.4 PENILAIAN KORUPSI BARU-BARU INI
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak survei terperinci telah dilakukan mengenai
etika di Korea. Sejak 2002, Korea Independent Commission against Corruption (KICAC; sekarang
Anticorruption and Civil Rights Commission [ACRC]) telah melakukan Survei Integritas Korea,
alat ilmiah dan sistematis untuk menilai tingkat korupsi dan mengidentifikasi faktor korupsi di
sektor publik. Ini mensurvei warga biasa yang mengalami layanan publik.
Organisasi publik dengan skor lebih tinggi memiliki integritas lebih. Setiap item dipastikan
sebagai berikut:
1) Skor korupsi yang dirasakan dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Apakah menurut Anda
pejabat pemerintah telah menerima suap atau hiburan dari bisnis Anda dalam setahun terakhir?"
2) Skor korupsi yang dialami dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Berapa banyak dan
seberapa sering Anda memberikan suap atau hiburan untuk bisnis Anda dalam setahun terakhir?"
244
3) Skor lingkungan korupsi dihitung dari tanggapan terhadap ques- tion, "Apakah menurut Anda
menerima suap atau hiburan telah menjadi praktik biasa dan pertemuan informal (atau prosedur)
diperlukan untuk bisnis Anda dalam setahun terakhir?"
4) Skor prosedur administrasi dihitung dari respons terhadap pertanyaan "Apakah menurut Anda
prosedur dan pedoman administratif dan transparan?"
5) Skor sikap pejabat pemerintah dihitung dari respons terhadap
pertanyaan, "Apakah menurut Anda pejabat pemerintah berurusan secara adil dengan bisnis Anda-
masalah dan ingin menerima suap atau hiburan?"
6) Skor pengendalian korupsi dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Menurut Anda, berapa
banyak upaya yang dilakukan pemerintah Anda untuk mengekang korup-tion di tahun lalu?"
Peningkatan skor menunjukkan bahwa berbagai program antikorupsi telah efektif dalam
meningkatkan tingkat integritas di sektor publik Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Survei Integritas Korea dilaksanakan setiap tahun dan organisasi publik cenderung
mempersiapkan survei terlebih dahulu untuk mencapai skor yang lebih tinggi dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Persiapan tersebut juga diharapkan dapat membuat organisasi-organisasi
tersebut lebih transparan dan bersih.
Kesimpulannya, berbagai langkah menunjukkan bahwa persepsi kor- pecah terus
meningkat, meskipun sederhana, di Korea Selatan selama 6 tahun terakhir.
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak survei terperinci telah dilakukan mengenai
etika di Korea. Sejak 2002, Korea Independent Commission against Corruption (KICAC; sekarang
Anticorruption and Civil Rights Commission [ACRC]) telah melakukan Survei Integritas Korea,
alat ilmiah dan sistematis untuk menilai tingkat korupsi dan mengidentifikasi faktor korupsi di
sektor publik. Ini mensurvei warga biasa yang mengalami layanan publik.
Organisasi publik dengan skor lebih tinggi memiliki integritas lebih. Setiap item dipastikan
ebagai berikut:
1) Skor korupsi yang dirasakan dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Apakah
menurut Anda pejabat pemerintah telah menerima suap atau hiburan dari bisnis Anda
dalam setahun terakhir?"
245
2) Skor korupsi yang dialami dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Berapa banyak
dan seberapa sering Anda memberikan suap atau hiburan untuk bisnis Anda dalam setahun
terakhir?"
3) Skor lingkungan korupsi dihitung dari tanggapan terhadap ques- tion, "Apakah menurut
Anda menerima suap atau hiburan telah menjadi praktik biasa dan pertemuan informal
(atau prosedur) diperlukan untuk bisnis Anda dalam setahun terakhir?"
4) Skor prosedur administrasi dihitung dari tanggapan terhadap ques-tion, "Apakah menurut
Anda prosedur dan pedoman administratif sesuai dan transparan?"
5) Skor sikap pejabat pemerintah dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Apakah
menurut Anda pejabat pemerintah menangani masalah bisnis Anda secara adil dan ingin
menerima suap atau hiburan?"
6) Skor pengendalian korupsi dihitung dari tanggapan terhadap pertanyaan, "Menurut Anda,
berapa banyak upaya yang dilakukan pemerintah Anda untuk mengekang korupsi pada
tahun lalu?"
Peningkatan skor menunjukkan bahwa berbagai program antikorupsi telah efektif dalam
meningkatkan tingkat integritas di sektor publik Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Survei Integritas Korea dilaksanakan setiap tahun dan organisasi publik cenderung
mempersiapkan survei terlebih dahulu untuk mencapai skor yang lebih tinggi dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Persiapan tersebut juga diharapkan dapat membuat organisasi-organisasi
tersebut lebih transparan dan bersih. Kesimpulannya, berbagai langkah menunjukkan bahwa
persepsi Korea pecah terus meningkat, meskipun sederhana, di Korea Selatan selama 6 tahun
terakhir.
19.5 PROGRAM DAN STRATEGI ANTIKORUPSI DI KOREA SELATAN
Pemerintahan otoriter di Korea sering berusaha menggunakan program antikorupsi sebagai
sarana untuk menenangkan kemarahan publik atas korupsi dalam pelayanan publik. Selain itu,
rezim-rezim ini sengaja memanfaatkan program antikorupsi untuk melegitimasi rezim mereka dan
menindas saingan politik. Perang melawan korupsi sering dinyatakan tepat setelah mereka
246
mengambil alih kekuasaan dengan cara yang kuat. Namun, dalam sebagian besar kasus, langkah
seperti itu ternyata hanya retorika.
Presiden Rhee Syngman mengabaikan penanganan korupsi, sehingga perang melawan
korupsi dimulai dengan Presiden Park Chung-hee. Dia mendirikan lembaga antikorupsi de facto
pertama, Dewan Audit dan Inspeksi (BAI), pada tahun 1963. BAI diciptakan untuk "pemeriksaan
langsung pada birokrasi ekonomi" (Quah 1999, 489). Park juga mengesahkan Undang-Undang
untuk Menangani Akumulasi Kekayaan Terlarang, yang disambut baik oleh masyarakat.
Namun, kampanye antikorupsi Park tidak berlangsung lama. Dia harus bekerja sama
dengan pengusaha korup karena dia membutuhkan dukungan keuangan untuk menjalankan mesin
politiknya dan dia mencoba melegitimasi kudetanya dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat
(Kang 2002a, 2002b). Pada tahun 1975, administrasi Taman memperkenalkan seojungshaeshin
(reformasi administrasi umum), yang merupakan gerakan untuk melawan perpecahan di bidang
pelayanan sipil.
19.4.1.1 SETELAH DEMOKRATISASI: PEMERINTAHAN KIM YOUNGSAM (1993-
1998)
Banyak bantuan membantu menjelaskan peningkatan upaya antikorupsi selama
periode ini. Globalisasi ekonomi Korea memberikan tekanan internasional pada
pemerintah menjadi lebih transparan dan memenuhi standar internasional dalam hal
inisiatif antikorupsi (Kim dan Im, 2001). Demokratisasi melahirkan berbagai organisasi
kemasyarakatan dan partisipasi aktif yang turut memajukan upaya antikorupsi.
Keberhasilan pembangunan ekonomi menyebabkan pertumbuhan kelas menengah dalam
masyarakat Korea, yang menekan rezim otoriter pada 1980-an. Akhirnya, setelah kematian
rezim itu, sebuah pemerintahan sipil baru menjadi perhatian mengurangi korupsi politik
dan birokrasi yang melibatkan kolusi politisi, birokrat, dan pengusaha karena ini akan
membedakan arus pemerintah dari rezim militer yang korupsi.
Menanggapi tuntutan demokratisasi yang terus berlanjut, Presiden Kim Young-sam
menerapkan salah satu kampanye antikorupsi yang paling komprehensif, termasuk revisi
247
UU Etika Pelayanan Publik dan pengenalan sistem transaksi keuangan pada tahun 1993.
Sebelum sistem rekening bank dapat dibuka dengan nama palsu atau nama pinjaman, ini
telah menjadi sumber utama ekonomi hitam, penipuan besar-besaran, korupsi, dan skema
penggelapan pajak. Dengan diperkenalkannya sistem, akun seperti itu menjadi ilegal dan
sebagian besar transaksi keuangan ilegal terkait korupsi diblokir (Kim, 2007). Juga, itu
memberikan banyak data untuk digunakan untuk penyelidikan sekali pun korupsi
ditemukan. Sistem transaksi keuangan nama asli dulu direncanakan secara rahasia sangat
mirip dengan operasi militer dan dieksekusi oleh perintah darurat presiden untuk keuangan
dan ekonomi nasional (Sheridan 1997, 13–15).
Presiden Kim juga memberhentikan beberapa menteri di kabinetnya dan jenderal
militer yang terlibat dalam kudeta 1979 serta terkait dengan Hanahoe, sebuah rahasia
tertutup organisasi dalam perwira militer elit Korea. Ini meruntuhkan kekuasaan yang
korupsi rantai rezim lama, yang telah makmur berdasarkan perlakuan khusus dan hak
istimewa. Anehnya, dia juga memiliki mantan presiden Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo
ditangkap atas tuduhan korupsi dan makar. Mereka didakwa karena sistematis kegiatan
suap yang melibatkan beberapa chaebol besar negara. Presiden Kim Young-sam juga
memperkuat peran BAI dan mendirikannya Komite Pencegahan Korupsi (CPC) sebagai
badan penasehat BAI ketua (Quah 1999, 181).
Selain itu, ia dengan serius mengejar reformasi regulasi melalui Komite Reformasi
Administrasi, yang karya-karyanya berkontribusi pada pengurangan praktik korupsi di
pemerintahan. Meskipun antikorupsi Kim dorongan itu terhalang dan ternoda oleh
penangkapan putranya karena penyuapan di Hanbo skandal pinjaman dan krisis keuangan
Asia pada tahun 1997, Kim telah menunjukkan kemampuannya komitmen untuk
memberantas korupsi (Heo dan Kim 2000). Antikorupsi miliknya upaya diperluas tidak
hanya untuk administrasi dan partai politik, tetapi juga untuk militer, bisnis, bank, dan
bahkan polisi lalu lintas, semuanya sudah diketahui untuk korupsi mereka.
19.4.1.2 SETELAH KRISIS KEUANGAN ASIA 1997: PEMERINTAHAN KIM DAE-
JUNG (1998-2003)
Korupsi yang meluas di masyarakat Korea dituding sebagai salah satu penyebab
utama krisis ekonomi tahun 1997. Masyarakat Korea maupun masyarakat internasional
(termasuk intervensi Dana Moneter Internasional) sangat dituntut bahwa pemerintah
248
memberantas korupsi sehingga mengubah cara kerja ekonomi dari pemerintahan yang
berpusat pada pasar. Tekanan tinggi dibuat Presiden Kim Dae-jung memperkenalkan
program antikorupsi yang lebih komprehensif.
Pertama, pemerintah memperkuat aspek kelembagaan pemberantasan korupsi
aturan. Itu diundangkan Undang-Undang Anti-Korupsi pada tahun 2001, didirikan
Presiden Komisi Antikorupsi pada tahun 1999, dan menciptakan antikorupsi independent
organisasi bernama KICAC pada tahun 2002 (Kim 2007). Kedua, administrasi juga
memperkenalkan berbagai reformasi untuk program antikorupsi.
Pemerintah juga mewajibkan pengungkapan keuangan dari pejabat publik untuk
perubahan keuangan lebih dari US$10.000 setahun, dengan pengecualian gaji yang
ditentukan. Pemerintah mulai secara ketat mengontrol dan membatasi jenis pekerjaan di
mana pensiunan pejabat publik dapat melamar karena pensiunan pejabat publik dapat
melakukannya memanfaatkan informasi dan jaringan pribadi yang dia miliki selama di
pemerintahan untuk keuntungan perusahaan barunya.
19.4.1.3 PEMERINTAHAN ELEKTRONIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT:
PEMERINTAH ROH MOOHYUN (2003-2008)
Yang terpenting, pemerintahan Roh Moo-hyun merevisi Pemilihan Kantor Publik
Bertindak. Revisi dimaksudkan untuk mengurangi korupsi dalam pemilihan pejabat publik.
Selain itu, pemerintah memperkenalkan berbagai pendekatan lunak untuk mengurangi korupsi
secara sistematis. Arah atau paradigma baru kebijakan antikorupsi yang dianut KICAC juga
mencerminkan pendekatan lunak, antara lain:
1) Pergeseran kebijakan dari hukuman ke pencegahan
2) Perbaikan kelembagaan di daerah rawan korupsi
3) Administrasi yang lebih transparan
4) Memperkuat etika dalam pelayanan publik dan manajemen perusahaan
5) Sistem terkonsolidasi untuk melindungi pelapor
Presiden Roh Moo-hyun berkampanye dan dikenal karena retorika antikorupsinya
yang kuat. Meskipun dia dan keluarganya tidak dituduh melakukan korupsi serius selama
249
masa kepresidenannya, setelah dia meninggalkan jabatannya, mereka menjadi sasaran
sebuah pengaruh skandal, dia juga tidak bisa menghindari jerat korupsi di tingkat
kekuasaan yang tinggi. Sekitar setahun setelah dia meninggalkan kantor, dia dipanggil oleh
jaksa atas dugaan menerima suap sebesar US$6 juta dari Park Yeon-Cha seorang
pengusaha yang dekat dengan mantan presiden. Dia bunuh diri pada Mei 2009, melompat
dari tebing di belakang rumahnya di pedesaan.
Sebagai bagian dari rencana reorganisasi pemerintah yang komprehensif, Presiden
saat ini Lee Myung-bak menciptakan ACRC pada tahun 2008 dengan mengintegrasikan
Ombudsman Korea, Komisi Independen Korea melawan Korupsi, dan Administrasi
Komisi Banding.
19.4.2 KARAKTERISTIK UTAMA ARUS ANTI KORUPSI
Program anti-korupsi Korea saat ini mengandalkan tata kelola elektronik dan
melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme antikorupsi
nasional, informasi publik, reformasi kelembagaan dan hukum, penguatan budaya etis, dan
deteksi dan hukuman yang ketat terhadap perilaku korupsi. Selain itu, inisiatif integritas
dalam pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi program sedang berlangsung.
Saat ini, dua undang-undang antikorupsi yang berbeda berlaku di Korea Selatan:
UU Antikorupsi dan UU Etika Pelayanan Publik. Yang pertama termasuk kode etik bagi
pejabat publik dan pembatasan pascakerja yang berlaku untuk pejabat publik yang korup.
Selain itu, kode tersebut melarang pejabat mana pun untuk melibatkan diri dalam personel
perubahan dengan menggunakan posisi mereka atau campur tangan untuk keuntungan
pribadi. Itu juga dilarang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari
penggunaan informasi resmi untuk investasi pribadi atau perdagangan properti.
Selain itu, kode tersebut membatasi pejabat publik untuk menerima apa pun uang
atau hadiah. Untuk menciptakan suasana yang sehat di area publik, pejabat wajib
melaporkan setiap kuliah luar yang melebihi empat kali sebulan selama periode 3 bulan.
250