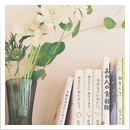Silogisme
pq premis 1
qr premis 2
pr kesimpulan
Contoh:
1. Hasil dari penarikan kesimpulan berikut adalah ….
Jika saya rajin bersedekah maka rezeki saya makin banyak
Jika rezeki saya makin banyak maka saya makin bahagia
....
Pembahasan :
Misalkan:
p : Saya rajin bersedekah
q : Rezeki saya makin banyak
r : Saya makin bahagia
pq
qr
p r
p r : Jika saya rajin bersedekah maka saya makin bahagia
Jadi, kesimpulannya: Jika saya rajin bersedekah maka saya makin bahagia.
2. Diberikan 2 premis seperti berikut:
~p q
qr
....
Maka, kesimpulannya adalah ....
Pembahasan:
~p q Ingat bentuk ekuivalensi:
qr
p q ~ p q
....
Maka, premis pertama bisa diubah menjadi:
pq
qr
pr
Jadi, kesimpulannya p r .
3. Dari ketiga premis berikut : Ingat bentuk ekuivalensi:
premis 1 : ~ p q
premis 2 : ~ r ~q p q ~ p q
premis 3 : ~ r q r ~ r ~ q
....
Kesimpulannya adalah .... Ini adalah bentuk silogisme:
Pembahasan:
premis 1 : ~p q pq
premis 2 : ~r ~q qr
premis 3 : ~r pr
....
Premis 1 dan 2 diubah menjadi:
pq
qr
~r
....
Kemudian, diubah lagi menjadi:
pr
~r
~ p
Jadi, kesimpulannya adalah ~p.
Dimensi Tiga H G
E F
Kubus
D C
Diagonal bidang B
Contoh diagonal bidang adalah AC, BG, dan FH. Aa
Panjang diagonal bidang = a 2
Diagonal ruang
Contoh diagonal ruang adalah AG, BH dan
seterusnya.
Panjang diagonal ruang = a 3
Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang
a. Kedudukan Titik Terhadap Garis
1. Titik P terletak pada garis h, jika garis h melalui titik P.
P
h
2. Titik P di luar garis h, jika garis h tidak melalui titik P.
P
h
b. Kedudukan Titik Terhadap Bidang
1. Titik P di bidang α, jika bidang α melalui titik P.
P
α
2. Titik P di luar bidang α, jika bidang α tidak melalui titik P.
P
α
c. Kedudukan Garis Terhadap Garis
1. Garis g dan h berimpit, jika semua titik pada garis g terletak pada garis h, dan sebaliknya.
g=h
2. Garis g dan h berpotongan, jika memiliki satu titik potong.
g
h
titik potong
3. Garis g dan h sejajar, jika kedua garis tersebut tidak punya titik potong.
g
h
4. Garis g dan h bersilangan, jika kedua garis tersebut tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak
berada pada bidang yang sama.
g
h
α
d. Kedudukan Garis Terhadap Bidang
1. Garis g terletak pada bidang α, jika paling sedikit terdapat dua titik di garis g terletak pada bidang α .
g
α
2. Garis g sejajar dengan bidang α, jika terdapat garis pada bidang α yang sejajar dengan garis g.
g
α
3. Garis g menembus bidang α, jika garis g tidak terletak pada bidang α dan tidak sejajar dengan
bidang α. Atau, garis g pasti memiliki titik tembus terhadap bidang α.
g
titik tembus
α
e. Kedudukan Bidang Terhadap Bidang
1. Bidang α dan berimpit, jika kedua bidang tersebut punya daerah persekutuan.
Daerah persekutuan
α
2. Bidang α dan sejajar, jika kedua bidang tersebut tidak punya titik/garis/bidang persekutuan.
h
g
α
3. Bidang α dan berpotongan, jika kedua bidang tersebut tidak sejajar.
B AB adalah garis perpotongan bidang
α dan β.
α
A
Proyeksi
Proyeksi Titik
1. Proyeksi titik ke garis
Proyeksi titik P ke garis h adalah menarik garis tegak lurus dari titik P ke garis h.
P
P’
h
Titik P’ hasil proyeksi titik P
2. Proyeksi titik ke bidang
Proyeksi titik P ke bidang α adalah menarik garis tegak lurus dari titik P ke bidang α.
P
P’ Titik P’ hasil proyeksi titik P
α
Proyeksi Garis
1. Proyeksi garis ke garis
Proyeksi dari garis AB ke garis CD diperoleh dengan menarik garis dari titik A dan B tegak lurus ke
garis CD. B
A
C Proyeksi AB adalah A’B’
A’
B’ D
2. Proyeksi garis ke bidang
Proyeksi dari garis AB ke bidang α diperoleh dengan menarik garis dari titik A dan B tegak lurus ke ke
bidang α. B Garis AB berada di luar bidang α.
A
α A’ B’ Proyeksi AB adalah A’B’ B
Garis AB menembus bidang α,
sehingga titik A = A’.
αA B’ Proyeksi AB adalah AB’
B
Garis AB tegak lurus bidang α. Jadi,
proyeksi AB pada α adalah garis
AB itu sendiri.
A
α Proyeksi AB adalah titik A saja.
Jarak Titik, Garis, dan Bidang Dalam Dimensi Tiga
Jarak Antar-Dua Titik
B Jika diketahui sisi mendatar dan sisi tegaknya,
y maka jarak antara titik A dan B adalah:
A AB x2 y2
x
B(x2, y2) Jika diketahui koordinat titik A dan B, maka
jarak antara titik A dan B adalah:
A(x1, y1)
AB (x2 x1)2 ( y2 y1)2
Jarak Titik ke Garis
Jarak titik P ke garis h sama dengan jarak titik P ke hasil proyeksinya (P’), yaitu PP’.
P
PP’ adalah jarak titik P ke garis
h
P’ h
Jarak Titik ke Bidang
Jarak titik P ke bidang α sama dengan jarak titik P ke hasil proyeksinya (P’), yaitu PP’.
P
PP’ adalah jarak titik P ke garis α
P’
α
Jarak Dua Garis Sejajar
Jarak garis g dan garis h diperoleh dengan cara membuat garis lain yang memotong dan tegak lurus garis
g dan h. Jarak antara kedua titik potong itulah jarak garis g dan h.
l
Ag
AB adalah jarak garis g dan h
B
h
Jarak Antara Garis dan Bidang yang Sejajar
Jarak garis g ke bidang α diperoleh dengan cara menarik garis ke bidang α melalui sebuah titik di garis g,
sehingga garis tersebut tegak lurus dengan garis g dan bidang α.
g
P
PP’ adalah jarak garis g ke bidang α
P’
α
Jarak Dua Bidang yang Sejajar
Jarak antara dua bidang α dan diperoleh dengan cara membuat garis yang menembus secara tegak
lurus pada bidang tersebut. Garis yang melalui kedua titik tembus pada bidang α dan adalah jarak
antara kedua bidang tersebut.
Q
P PQ adalah jarak bidang α dan
α
Contoh:
Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Maka, jarak titik A ke garis EC adalah ....
Pembahasan: H G
Tarik titik proyeksi A ke EC (misalkan titik itu adalah P). Maka,
jarak A ke EC adalah panjang garis AP. Segitiga ACP dapat E F
digambarkan sebagai berikut: C
P
E D
P
63
6 A 6B
A 62 C
L 1 at Ingat, Bro!
2
AC = diagonal bidang = a 2
L AEC 1 AC AE 1 EC AP CE = diagonal ruang = a 3
22
Keterangan:
6 2 6 6 3 AP Alas (a) dan tinggi (t) harus saling tegak lurus.
6 2 AP Jadi, jika alasnya AC maka tingginya AE. Dan,
3 jika alasnya EC maka tingginya AP
AP 6 2 3
33
AP 6 6 2 6 cm
3
Maka, jarak titik A ke garis EC adalah 2 6 cm .
Sudut-Sudut Dalam Dimensi Tiga θ B
A B’
Sudut Antara Garis dan Bidang
Lihat gambar berikut.
Garis AB menembus bidang α di A dan B’ adalah proyeksi titik B.
Maka, sudut antara garis AB dan bidang α adalah BAB' .
α
Sudut Antara Garis Bersilangan
Garis g dan h saling bersilangan. Untuk mencari sudut di antara garis g dan h, geser salah satu garis
sehingga berpotongan, maka titik potong itulah titik sudut antara garis g dan h.
gg
h Garis h digeser ke g θ h’
αα
Sudut di Antara Dua Bidang
Garis l adalah garis perpotongan bidang α dan . Tarik garis di bidang α yang tegak lurus dengan garis l
(kita sebut garis g) dan tarik garis di bidang yang tegak lurus dengan garis l (kita sebut garis h).
Perpotongan garis g dan h itulah yang membentuk sudut antara bidang α dan , yaitu sudut θ.
h l
g
α
θ
Contoh:
1. Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika T adalah tengah-tengah bidang atap. Jika AT
dan alas membentuk sudut θ maka nilai cos adalah ....
Pembahasan: G H
T
θ T
A 22 4 EF
T’
C D C
4
T’
AC diagonal bidang = a 2 4 2 A4 B
AT’ = 1 AC 2 2
2
AT (2 2)2 42 8 16 24 2 6
cos samping 2 2 1 3
miring 2 6 3 3
cos 1 3
3
3. Kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 4 cm. Sudut yang dibentuk antara bidang AFH dan CFH adalah θ,
maka nilai sin adalah ....
Pembahasan: sin 1 depan AT ' 2 2 1 1 3
2 miring AT 2 6 33
H G
T
samping TT ' 4 2 1
cos 1 miring AT 26 63 6
2
EF
sin 2 sin 1 cos 1
2 2
4D
C T 2 1 3 1 6 2 18
33 9
T’ θ 26
A 4B
26 1 1 2 2
2 2 3
4
22 22 C
A T’
Ingat, Bro!
42
Irisan Bangun Ruang Sin2A = 2sinA.cosA
Bidang irisan adalah sebuah bidang yang memotong bidang suatu bangun ruang sehingga membagi dua
bangun ruang tersebut. Untuk memperjelas, berikut contohnya.
Contoh:
Diberikan kubus ABCD.EFGH. Titik P, Q, dan R adalah titik tengah dari AE, BC, dan CG. Maka, bidang
irisan yang terbentuk adalah .... X
H SG
Pembahasan:
Langkah-langkahnya sebagai berikut. T FR
1. Buat garis melalui QR dan perpanjangan garis FG, Z
E
sehingga kita mendapat titik potong X. PD C
2. Perpanjang garis FB sehingga berpotongan Q
dengan garis yang melalui QR di Y.
3. Perpanjang garis YP sehingga berpotongan A UB
dengan perpanjangan garis FE di Z.
4. Hubungkan titik X dan titik Z. Y
5. Maka, terbentuk segitiga XYZ yang memotong
bidang-bidang kubus di PQRSTU.
6. PQRSTU (segienam) itulah yang merupakan
bidang irisan kubus ABCD.EFGH.
STATISTIKA
Data Tunggal
Jika diberikan data tunggal berikut:
x1, x2 , x3, ... , xn
Dari data tersebut dapat diperoleh unsur-unsur statistika berikut.
Rata- rata (mean)
x x1 x2 x3 ........ xn n
n
xi
atau ditulis x i1
n
Modus (Mo)
Modus adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak.
Median (Me)
Median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan.
M e x( n21)
Jangkauan (J)
Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil.
J xmaks xmin
Kuartil (Q)
Kuartil adalah nilai yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian, setelah data tersebut diurutkan.
Berikut ilustrasinya:
Bagian I Bagian II Bagian III Bagian IV
xQQ Q3 xn
112
Q2 Me (Median) Catatan :
Keterangan: Jika n ganjil Qi X i (n1)
x1 = data terkecil
4
xn = data gerbesar
Q1 = kuartil 1 atau kuartil bawah Jika n genap Qi X i n 1
Q2 = kuartil 2 atau kuartil tengah 42
Q3 = kuartil 3 atau kuartil atas
Operasi-operasi yang berhubungan kuartil adalah:
1. Jangkuan kuartil
J k Q3 Q1
2. Simpangan kuartil (jangkuan semi interkuartil)
Sk 1 (Q3 Q1)
2
Simpangan rata-rata (SR)
n
xi x
S R i1 n
Ragam (varians)
n atau S SB2
(xi x)2
S i1
n
Simpangan baku (SB)
SB n atau SB S
(xi x)2
i1
n
Contoh:
1. Dari hasil pendataan umur (dalam tahun) pada sebuah kelompok adalah sebagai berikut:
6, 1, 3, 8, 9, 10, 3,12, 3, 15
Carilah unsur- unsur dari data statistik tersebut!
Pembahasan:
a. Rata-rata:
x 6 1 3 8 9 10 3 12 3 15 70 7
10 10
b. Modus (Mo):
Mo = 3
c. Median (Me):
Data setelah diurutkan : 1, 3, 3, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15
Me x( n1 )
2
x(1021) x5,5 Letak median antara 6 dan 8. Jadi:
68 Me 6 8 7
2 2
7
d. Jangkuan (J):
J xmaks xmin
J 15 1 14
e. Quartil (Q):
Setelah data diurutkan : 1, 3, 3, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15
Q1 3 Q3 10
Q2 6 8 7
2
Jika dikerjakan dengan rumus, karena n genap (n=10) maka:
Qi X i n 1
42
Q1 X 1 n 1 X 1 (10)1 X 5 1 X 3 3
42 42 22
Q2 X 2n 1 X 2(10) 1 X 5 1 X 5,5 7
42 42 2
Q3 X 3(10) 1 X 151 X8 10
42 22
Jk Q3 Q1 10 3 7
Sk 1 (Q3 Q1) 1 (7) 3,5
2 2
f. Simpangangan rata-rata (SR):
n
xi x
S R i1 n
SR 1 7 3 7 3 7 3 7 6 7 8 7 9 7 10 7 12 7 15 7
10
SR 644 411 2358 38 3,8
10 10
g. Ragam (varians):
n
(xi x)2
S i1
n
S (1 2 (3 2 (3 2 (3 2 (6 2 (8 2 (9 7)2 (10 2 (12 2 (15 2
7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7)
10
S 36 16 16 16 1 1 4 9 25 64 188 18,8
10 10
h. Simpangan baku (SB):
n
(xi x)2
SB i1 atau SB S
n
SB S 18,8 4,3
2. Terdapat data nilai matematika 5 orang anak sebagai berikut:
a, 4, 3, t, 9
Jika rata-rata kelas kelima anak tersebut adalah 6 dan nilai selisih a dan t (t > a) adalah 2, maka
berapakahan nilai t?
Pembahasan:
x a43t 9 6 t a 14
5 ta2
a t 16 30
a t 14 2t 16
t 8
Data Tunggal dengan Frekuensi
Sama halnya dengan data tunggal, data tunggal dengan frekuensi ini hanya berbeda karena setiap data
yang ditampilkan memiliki frekuensi tertentu.
Berikut adalah contoh data berat badan di sebuah kelas 1 SD ditulis dalam bentuk tabel frekuensi:
24, 22, 25, 25, 21, 23, 24, 23, 22, 24, 21, 22, 23, 21, 21, 22, 25, 24, 23, 24
Tabel frekuensi Tabel frekuensi
Berat (kg) Frekuensi xi fi
21 4
22 4 x1 f1
23 4 x2 f2
24 5
25 3 ... ...
... ...
xn fn
Unsur- unsur statistika untuk data dengan frekuensi pada dasarnya tidak jauh beda dengan data tunggal
tanpa frekuensi. Perbedaannya, unsur-unsur statistikanya dikelompokkan dengan jumlah frekuensi
tertentu. Berikut ini unsur-unsur statistik tersebut:
Rata- rata (mean)
n
fi xi
x i1
n
Simpangan rata-rata (SR)
n
fi xi x
S R i1 n
Ragam (varians)
n
fi (xi x)2
S i1
n
Simpangan baku (SB)
SB n
fi (xi x)2
i1
n
Contoh:
Tabel berikut menyajikan jumlah mobil yang dimilki oleh sekelompok orang.
Jumlah Mobil Jumlah Orang
3 4
4 4
5 3
6 6
7 3
Carilah unsur-unsur statistikanya!
Pembahasan:
xi fi fk fi xi fi xi x fi (xi x)2
3 44 12 4|3 – 5|=8 4(3 – 5)2 = 16
4|4 – 5|=4 4(4 –5)2 = 4
4 48 16 3|5 – 5|=0 3(5 – 5)2 = 0
6|6 – 5|=6 6(6 – 5)2 = 6
5 3 11 15 3|7 – 5|=6 3(7 – 5)2 = 12
6 6 17 36
7 3 20 21
fi xi 100 fi (xi x) 38
fi 20 fi xi x 24
a. Rata-rata:
n
x
fi xi 100 5
i 1
n 20
b. Modus (Mo):
Mo = 6 (karena nilai 6 frekuensinya paling banyak, yaitu 6.)
c. Median (Me):
M e x( n21) x( 2021) x10,5 5
d. Jangkuan (J):
J xmaks xmin
J 734
e. Quartil (Q):
Qi X i n 1
42
Q1 X 1 n 1 X 1 (20) 1 X 5,5 4
42 42
Q2 X 2 n 1 X 2(20) 1 X10,5 5
42 42
Q3 X 3 n 1 X 3(20) 1 X15,5 6
42 42
f. Simpangan Rata-rata (SR):
n
SR
i 1 fi xi x 24 1, 2
n 20
g. Ragam (varians):
n
S i1 fi (xi x )2 38 1, 9
n 20
h. Simpangan baku (SB):
n
fi (xi x)2
SB i1 atau SB S
n
SB S 1,9 1,38
Data Dalam Bentuk Interval
Contoh:
Interval Frekuensi Nilai Tengah Interval Frekuensi Nilai Tengah
1-5 3
ai bi fi (xi ) 6-10 4 8
a1 b1 f1 x1 4 13
a2 b2 f2 x2 11-15 4 18
16-20 5 23
.... .... .... 21-25 3
.... .... ....
an bn fn xn
Keterangan: Interval ke-2 = 6 – 10
Batas bawah kelas ke-2 = 6
Interval/kelas ke-i = ai bi Batas atas kelas ke-2 = 10
Tepi bawah kelas ke-2 = 6 – 0,5 = 5,5
Batas bawah kelas ke-i = ai Tepi atas kelas ke-2 = 10 + 0,5 = 10,5
Panjang kelas = 10,5 – 5,5 = 5
Batas atas kelas ke-i = bi
Nilai tengah kelas ke-2 = 6 10 8
Tepi bawah kelas ke-i = a i 0,5 2
Tepi atas kelas ke-i = b i 0,5
Panjang kelas (C) = tepi atas – tepi bawah
Nilai tengah: xi ai bi
2
Rata-rata (mean) Interval fi xi fi .xi
1. Cara langsung Catatan : 1-5 4 3 12
32
x fi xi nf 48 52
n 90
6-10 69
11-15 4 13
x 255 = 12,75 16-20 5 18
20
21-25 3 23
fi 20 fi xi 255
2. Cara simpangan rata-rata
x xs fi di Interval fi xi di fi di
n
1-5 4 3 –15 –60
xs = rata-rata sementara 6-10 4 8 –10 –40
di xi xs 11-15 4 13 –5 –20
16-20 5 18 0 0
x 18 105 21-25 3 23 5 15
20
fi 20 fi di 105
x 18 5,25 12,75
Rata-rata sementara xs=18 (diambil dari dari frekuensi
paling besar).
3. Cara coding
x xs fi ki C Interval fi xi ki fi ki
n
1-5 4 3 –3 –12
ki = ... , –2, –1, 0, 1, 2, .... 6-10 4 8 –2 –8
11-15 4 13 –1 –4
C = Panjang kelas 16-20 5 18 00
21-25 3 23 13
x 18 21 5 fi 20
20 fi ki 21
x 18 1, 05 5
x 18 5,25 12,75
C = 5,5 – 0,5 = 5 0 dimulai dari xs
Catatan :
ki ditulis berurutan mulai dari 0 diletakkan pada xs (rata-rata sementara). Kemudian turun -1, -2, -
3.... dan seterusnya untuk interval sebelum xs . Dan naik 1, 2, 3 .... dan seterusnya untuk interval
setelah xs .
Modus (Mo)
Mo Tb d1 C Interval fi
d1 d2
Tb = tepi bawah kelas modus 1-5 4
d1 = selisih f modus dengan f sebelumnya 6-10 4
d2 = selisih f modus dengan f sesudahnya 11-15 4 d1 = 5 – 4 = 1
1 16-20 5
1 2
Mo 15,5 5 21-25 3 d2 = 5 – 3 = 2
Mo 15,5 1 5
3
M o 15,5 1,7 17,2 Letak modus karena f-nya terbesar:
Tb = 16 – 0,5 = 15,5
Median (Me)
Me Tb 1 n f ks C Interval fi fk
2
1-5 4 4
f me 6-10 4 8
11-15 4 12
n = jumlah data 16-20 5 17 fks = 8
21-25 3 20
fks = frekuensi kumulatif sebelum letak n 20
median data
fme = frekuensi median
letak median fme = 4
Tb = 11– 0,5 = 10,5
10 8
Me 10,5 4 5 Keterangan:
Me 10,5 2 5 fk (frekuensi kumulatif) adalah jumlah frekuensi dengan
4
frekuensi-frekuensi sebelumnya secara berurutan.
Me 10,5 2,5 13
Quartil
Qi Tb i n fks C Interval fi fk
4
1-5 4 4
f Qi 6-10 4 8 fk1 = 4
11-15 4 12 fk2 = 8
fks = frekuensi kumulatif sebelum letak kuartil 16-20 5 17 fk3 = 12
21-25 3 20
fQi = frekuensi kuartil
Q1 5,5 1 .20 4 5
4
4
5,5 5 4 5 5,5 1 .5 n 20 Keterangan:
44
letak kuartil ke-3
letak kuartil ke-2 letak kuartil ke-1 di 1 n
4
letak kuartil ke-1
5,5 1, 25 6,75 letak kuartil ke-2 di 2 n
4
2 .20 8 letak kuartil ke-3 di 3 n
4 4
10,5
Q2 4 5
10,5 10 8 5 10,5 2 .5
44
10,5 2,5 13
Q3 15,5 3 .20 12 5
4
5
15,5 15 12 15,5 3 18,25
Rata-Rata Gabungan
Rata-rata gabungan digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdiri minimal dua kelompok data.
xg na x a nb xb Keterangan:
na nb
xg = rata-rata gabungan
xa = rata-rata kelompok a
na = jumlah anggota kelompok a
xb = rata-rata kelompok b
nb = jumlah anggota kelompok b
Contoh:
1. Kelas 11A dengan jumlah siswa 30 orang rata-rata nilai matematikanya 60, sedangkan kelas 11B yang
jumlah siswanya 35 orang rata-rata nilai matematikanya 64. Jika kedua kelas digabungkan maka nilai
rata-rata gabungannya adalah ....
Pembahasan:
na 30 ; xa 60
nb 35; xb 64 ; xg ?
xg na x a nb xb 30 60 35 64 1.800 2.240 4.040 62, 15
na nb 30 35 65 65
4. Rata-rata berat badan 5 orang anak adalah 42 kg. Jika Badu dan Budi bergabung, maka rata-rata berat
badan 7 orang anak menjadi 45 kg. Berapakah rata-rata berat badan Badu dan Budi?
Pembahasan:
na 5 ; xa 42 nb 2 karena kelompok kedua hanya ada 2
nb 2 ; xg 45 ; xb ? orang, yaitu Badu dan Budi.
xg na x a nb xb
na nb
45 5 42 2 xb
52
45 210 2 xb
7
315 210 2 xb
105 2 xb
xb 52,5 kg
Jadi, rata-rata berat badan Badu dan Budi adalah 52,5 kg.
Peluang
Pencacahan
Pengisian Tempat
Jika sebuah kejadian dapat terjadi sebanjak m kemungkinan dan kejadian lainnya sebanyak n
kemungkinan, maka seluruh kejadian yang terjadi sebanyak m x n.
Contoh
1. Neng Amel akan melakukan perjalan dari kota Bandung ke Surabaya melalui Semarang. Jika Bandung
– Semarang ada 3 pilihan rute jalan dan Semarang – Surabaya ada 4 pilihan rute jalan, maka:
a. Berapa cara perjalanan yang ditempuh Amel dari Bandung ke Surabaya?
b. Berapa cara rute perjalanan pulang pergi Bandung – Surabaya, dengan syarat jalan yang sudah
dilalui saat pergi tidak boleh dilalui lagi?
Pembahasan: 3 4 Bandung Semarang Surabaya
a. Cara pergi: 3 x 4 = 12 cara
b. Cara pergi: 12 cara X Semarang X
Cara pulang: 3 2
Bandung Surabaya
3 x 2 = 6 cara
Cara pergi-pulang (PP) = 12 x 6 = 72 cara.
2. Disediakan bilangan: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bilangan tersebut, berapa banyaknya bilangan:
a. Tiga digit bebas (tanpa syarat )
b. Tiga digit beda (tidak boleh ada angka berulang)
c. Tiga digit > 500 dan berbeda
d. Tiga digit genap dan berbeda
Pembahasan:
a. Tiga digit bebas (tanpa syarat ):
666 6 x 6 x 6 = 216 Semua angka dapat dipakai kembali.
b. Tiga digit berbeda:
654 Angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai
6 x 5 x 4 = 120 lagi.
c. Tiga digit > 500 dan berbeda:
354 3 x 5 x 4 = 60
Paling depan ada 3 kemungkinan, yaitu angka: 5, 6, 7
d. Tiga digit genap dan berbeda:
653 5 x 4 x 3 = 90
Bilangan terakhir ada 3 kemungkinan angka genap, yaitu: 2, 4, 6.
3. Ada 3 wanita dan 2 pria akan berfoto duduk sejajar, dengan syarat pria harus berada di posisi paling
pinggir. Ada berapa cara mereka dapat duduk?
Pembahasan:
2 3 2 1 1 2 x 3 x 2 x 1 x 1 = 12 cara
pria wanita pria
Permutasi
Faktorial
n! n (n 1) (n 2) .... 3 2 1 Syarat: n 0
Bisa ditulis juga sebagai berikut: Ketentuan: 0! 1
n ! n (n 1) (n 2)!
Contoh:
5! 5 4 3 21 120
5! 5 4! 120
4! 4 3 21 24
10! 10 9 8 7! 10 9 8 720
7! 7!
Permutasi dengan semua unsur beda
Permutasi adalah susunan unsur-unsur yang bebeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi, susunan
AB tidak sama dengan BA (AB BA).
Permutasi r unsur dari n unsur adalah:
Prn n! ; dengan n r Penulisan permutasi:
(n r)!
Prn n Pr P(n,r)
Contoh:
1. Tentukan nilai dari:
a. P310
b. P28 CADAS:
Pembahasan: P310 artinya, 10 turun 3 kali.
P310 10 9 8 720
a. P310 10!
(10 3)! CADAS:
10! 10 98 7! 10 98 720 P28 artinya, 8 turun 2 kali.
7! 7! P28 8 7 56
b. P28 8!
(8 2)!
8! 8 7 6! 8 7 56
6! 6!
2. Dari huruf-huruf : S, I, B, E, J, O akan disusun kata yang terdiri dari 4 huruf yang berbeda. Maka,
ada berapa susunan kata yang mungkin dibentuk?
Pembahasan:
n=6,r=4 CADAS:
6! 6! 6 5 43 2! P46 6 5 4 3 360
4)! 2! 2!
P46 (6 6 5 4 3 360
3. Jika ada 10 orang calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, maka ada berapa cara untuk memilih
mereka?
Pembahasan:
n = 10 , r = 2 CADAS:
P210 10! 10! 10 9 8! P210 10 9 90
(10 2)! 8! 8!
10 9 90
Permutasi dengan beberapa unsur sama
Banyaknya permutasi n unsur, jika terdapat k1 unsur sama, k2 unsur sama, ... ,kn unsur sama.
P n!
k1 !k2 ! ... kn !
Contoh:
1. Dari susunan huruf : MATEMATIKA, ada berapa susunan huruf lainnya yang mungkin dibentuk?
Pembahasan:
n = 10
k1 = 2 (jumlah huruf M)
k2 = 3 (jumlah huruf A)
k3 = 2 (jumlah huruf T)
P 10! 10 9 8 7 6 5 4 3! 10 9 8 7 6 5 151.200
2! 3! 2! (2 1)3!(2 1)
Banyaknya permutasi r unsur dari n unsur; dan terdapat k1 unsur sama, k2 unsur sama, ... , kn unsur
sama.
P n!
(n r)!k1!k2 ! ... kn !
Contoh:
Dari susunan huruf: MATEMATIKA akan dibuat susunan 5 huruf. Ada berapa susunan huruf yang
mungkin dibentuk?
Pembahasan:
n = 10
r=5
k1 = 2 (jumlah huruf M)
k2 = 3 (jumlah huruf A)
k3 = 2 (jumlah huruf T)
P 10! 10 9 8 7 6 5! 10 9 8 7 1.260
(10 5)! 2! 3! 2! 5!(2 1)(3 2 1)(2 1) 4
Permutasi siklis (melingkar)
Banyak permutasi n unsur yang disusun melingkar adalah:.
P (n 1)!
Contoh:
Sebanyak 4 pria dan 2 wanita akan duduk melingkar dalam sebuah pertemuan, dengan ketentuan:
a. Mereka duduk tanpa syarat
b. Wanita selalu duduk berdampingan
Pembahasan: PP
a. n = 6 (4 pria + 2 wanita)
P
P (6 1)! 5! 5 4 3 2 1 120 P
b. n = 5 ( 4 pria + 1 kelompok wanita (2 wanita))
WW
P (5 1)! 4! 4 3 2 1 24
Ingat kelompok wanita juga punya susunan P22 2
Jadi, susunan duduk seluruhnya adalah 24 x 2 = 48 cara duduk.
Kombinasi
Kombinasi adalah susunan unsur-unsur yang bebeda dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi, susunan
AB sama dengan BA (AB = BA).
Kombinasi r unsur dari n unsur adalah:
Penulisan kombinasi:
C n n! ; dengan n r Crn n Cr C(n,r)
r (n r)!r!
Dalam kombinasi berlaku:
C n C(nnr)
r
Contoh:
1. Penyelesaian dari:
a. C310
b. C810
c. (n1) Cn 10, n = ....
Pembahasan: CADAS:
a. C310 (10 10! 3! C310 artinya: 10 turun 3 kali dan dibagi 3 turun
3)!
sampai 1
10! 10 9 8 7! 10 9 8 120 P310 10 9 8 120
7! 3! 7! (3 2 1) 3 2 1 3 21
b. C810 (10 10! 2!
8)!
CADAS:
10! 10 9 8! 10 9 45 C810 C210 10 9 45
8! 2! 8! (2 1) 2 1 21
c. (n1) Cn 10
(n 1)! 10
((n 1) n)!n!
(n 1) n! 10
(1)! n!
(n 1) 10
1
n 1 10
n9
2. Seorang guru olahraga akan memilihi 2 siswa untuk pasangan ganda badminton dari 10 siswa yang
mencalonkan diri. Ada berapa cara guru tersebut dapat memilih pasangan ganda yang mungkin?
Pembahasan:
n = 10, r = 2 CADAS:
C210 10! 10! 10 9 8! 10 9 45 C 10 10 9 45
2!(10 2! 8! (2 1).8! 2 1 2 21
2)!
Penggunaan Kombinasi Dalam Binomial Newton
Segitiga Pascal 1 0C0
n=0 11 1C0 1C1
n=1 121 2C0 2C1 2C2
n=2 1331 3C0 3C1 3C2 3C3
n=3 14641 4C0 4C1 4C2 3C3 4C4
n=4 1 5 10 10 5 1 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5
n=5
dan seterusnya.
Ekuivalen dengan: 1
(a + b)0 = 1a + 1b
(a + b)1 = 1a2 + 2ab +1b2
(a + b)2= 1a3 + 3a2b + 3ab2 + 1b3
(a + b)3= 1a4 + 4a3b + 6+a12bb22 + 4ab3 + 1b4
(a + b)4= 1a5 + 5a4b + 10a3 b2 + 10a2b3 + 5ab4 + 1b5
(a + b)5=
Jadi, bentuk umumnya: Suku ke-k n Cr a nr b r
n suku ke-k, maka r = k -1
(a b)n n Cr anrbr
r 0
Contoh:
1. Hasil dari (a + b)3 adalah ....
Pembahasan:
(a b)3 3 C0 a30b0 3C1 a31b1 3C2 a32b2 3C3 a33b3
= 1a3b0 + 3a2b1 + 3a1 b2 + 1 a0 b3
= 1a3 + 3a2b + 3ab2 + 1b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
2. Suku ke-3 dari ( 2x + y )8 adalah ....
Pembahasan:
( 2x + y )8 n = 8
suku ke-3 r = 2
suku ke-k = n Cr a nr br
suku ke-3 = 8 C 2(2x)82 y 2 28 (2x)6 y2 28 (64x6 ) y 2 1.792x6 y2
Peluang Sebuah Kejadian
Peluang sebuah kejadian adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan dan seluruh kejadian
yang mungkin terjadi. Catatan:
P( A) n( A) ; dengan n(A) ≤ n(S)
n(S ) 0 ≤ P(A) ≤ 1
P(A) =0 artinya, kejadianmustahil terjadi
P(1) = 1 artinya, kejadian pasti terjadi
P(A) = peluang kejadian A
n(A) = banyaknya kemungkinan kejadian A
n(S) = banyaknya seluruh kemungkinan yang bisa terjadi/ banyaknya ruang sampel.
Contoh:
1. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Berapakah peluang muncul mata dadu genap?
Pembahasan:
n(A) = 3 (angka genap pada dadu: 2, 4, 6)
n(S) = 6 (seluruh angka pada dadu: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Peluang muncul mata dadu genap: P( A) n( A) 3 1
n(S) 6 2
2. Seorang ibu akan melahirkan seorang anak. Berapakah peluang seorang ibu tersebut akan melahirkan
anak laki-laki atau perempuan?
Pembahasan:
n(A) = 2 (bisa laki-laki atau bisa perempuan)
n(S) = 2 (laki-laki dan perempuan)
Peluang melahirkan anak laki-laki atau perempuan: P( A) n( A) 2 1
n(S) 2
Peluang Komplemen Sebuah Kejadian
Peluang komplemen sebuah kejadian A adalah peluang selain kejadian A atau ditulis P’(A).
P'( A) 1 P( A)
Contoh:
Peluang Andi lulus dalam tes masuk perguruan tinggi adalah 0,56. Berapakah peluang Andi akan gagal
dalam tes tersebut?
Pembahasan:
Peluang Andi lulus tes masuk perguruan tinggi: P(A) = 0,56 ()
Peluang Andi gagal tes masuk perguruan tinggi: P’(A) = 1 – 0,56 = 0,44
Frekuensi Harapan Suatu Kejadian
Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan akan terjadi pada suatu waktu. Frekuensi
harapan ini diperoleh dari perkalian antara peluang sebuah kejadian dengan banyaknya percobaan yang
dilakukan.
F( A) n P( A)
F(A) = frekuensi harapan kejadian A
n = banyaknya percobaan
P(A) = pelualang kejadian A
Contoh:
Sepuluh kartu yang bernomor 1 s/d 10 dikocok secara acak. Kemudian, akan diambil sebuah kartu lalu
dikembalikan lagi. Jika pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 100 kali, maka berapakah frekuensi
harapan terambilnya kartu bernomor prima?
Pembahasan: P(A) n(A) 4 2
n(A) = 7 (bilangan prima: 2, 3, 5, 7) n(S) 10 5
n(S) = 10 (kartu bernomor: 1, 2, 3, ... , 10)
n = 100 (banyak percobaan yang dilakukan )
F(A) = n P(A)
2
Frekuensi harapan terambilnya kartu bernomor prima: F(A) = 100. = 40
5
Kejadian Majemuk
Kejadian Saling Lepas
Kejadian A dan B saling lepas, jika kejadian A dan B tidak bisa terjadi bersama. Jika digambarkan, kejadian
saling lepas ditunjukkan sebagai berikut.
S B
A
A B
Peluangnya adalah:
P( A B) P( A) P(B)
Contoh:
Dua buah dadu dilambungkan bersama. Berapakah peluang muncul jumlah kedua mata dadu 8 atau 10?
Pembahasan: Dadu 1 Dadu 2
n(A) = 5 jumlah mata dadu 8:
123456
{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)} 1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
n(B) = 3 jumlah mata dadu 10: 2 (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
3 (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
{(4,6),(5,5),(6,4)} 4 (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
n(S) = 36 5 (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,5)
P( A B) P( A) P(B) 6 (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
5 3 8 2
36 36 36 9
Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 8 atau 10: 2 .
9
Kejadian Tidak Saling Lepas
Kejadian A dan B tidak saling lepas, jika kejadian A dan B bisa terjadi bersama. Jika digambarkan,
kejadian tidak saling lepas ditunjukkan sebagai berikut.
S AB
AB
P( A B) P( A) P(B) P( A B)
Contoh:
Dari setumpuk set kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Berapakah peluang terambil kartu berwarna
merah atau as?
Pembahasan:
n(A) = 26 (jumlah kartu warna merah)
n(B) = 4 (jumlah kartu as)
n( A B) = 2 (jumlah kartu as dan merah)
n(S) = 52 jumlah seluruh kartu bridge)
Peluang terambil kartu berwarna merah atau as:
P( A B) P( A) P(B) P( A B)
26 4 2
52 52 52
28 7
52 13
Kejadian Saling Bebas (Beruntun)
Kejadian berurutan A dan B dikatakan saling bebas, jika kejadian A tidak memengaruhi kejadian B.
Peluangnya adalah:
P( A B) P( A) P(B)
P(A B) = peluang kejadian A dan B secara berurutan
Contoh:
Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning. Dari dalam kantong, akan diambil 2 bola
satu per satu dan bola yang sudah diambil dikembalikan lagi ke dalam kantong. Berapakah peluang
terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua?
Pembahasan:
n(A) = 4 (jumlah bola merah)
n(B) = 3 (jumlah bola kuning)
n(S) = 7 (jumlah seluruh bola)
Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua:
P( A B) P( A) P(B) n( A) n(B) 4 3 12
n(S) n(S) 7 7 21
Kejadian Tidak Saling Bebas
Kejadian berurutan A dan B dikatakan tidak saling bebas, jika kejadian A memengaruhi kejadian B.
Peluangnya adalah:
P( A B) P( A) P(B | A)
P(B | A) = peluang kejadian B setelah kejadian A
Contoh:
Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning. Dari dalam kantong akan diambil 2 bola
satu per satu dengan bola yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Berapakah peluang terambilnya
bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua?
Pembahasan:
n(A) = 4 (jumlah bola merah) ; n(S A ) = 7 (jumlah seluruh bola saat awal)
n(B) = 3 (jumlah bola kuning); n(S B ) = 6 (jumlah seluruh bola setelah diambil 1 bola)
P( A B) P( A) P(B | A)
n(A) n(B)
n(S A ) n(S B )
4 3 12 2
7 6 42 7
Lingkaran
Definisi
Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu
tersebut adalah pusat lingkaran (P), sedangkan jarak titik ke titik pusat tersebut dinamakan jari-jari (r).
r Unsur utama dalam lingkaran adalah :
titik pusat (P) dan jari-jari (r).
P
Persamaan Lingkaran
Persamaan lingkaran dengan titik pusat (0,0)
Y Penjelasan:
Rumus jarak di antara dua titik:
K(x,y)
r d (x2 x1)2 ( y2 y1)2
P(0,0) X Pada lingkaran di samping berlaku:
Persamaannya: d (x2 x1)2 ( y2 y1)2 r
(x 0)2 ( y 0)2 r
x2 y2 r2 x2 y2 r
x2 y2 r2
Pusat (P) = (0,0)
Jari-jari = r
Persamaan lingkaran dengan titik pusat (a, b)
Penjelasan :
Y Pada lingkaran di samping, berlaku:
P(x,y)
d (x2 x1)2 ( y2 y1)2 r
r (x a)2 ( y b)2 r
(a,b)
X (x a)2 ( y b)2 r 2
Persamaannya :
(x a)2 ( y b)2 r 2
Pusat (P) = (a,b)
Jari-jari = r Atau, jika diuraikan kembali, akan diperoleh:
x2 y2 Ax By C 0
(x a)2 ( y b)2 r 2
A = –2a; B = –2b ; C = a2 + b2 – r2 x2 2ax a 2 y 2 2by b2 r 2
x2 y 2 2ax 2by a 2 b2 r 2 0
x2 y 2 Ax By C 0
Pusat (P) = A , B ; Jari-jari (r) = 1 A2 1 B2 C pusat2 C
2 2 44
Contoh:
1. Persamaan lingkaran dengan pusat (2, –3) dan jari-jari 4 adalah ....
Pembahasan:
P = (a,b) = (2, –3); r = 4
(x a)2 ( y b)2 r 2
(x 2)2 ( y (3))2 42
(x 2)2 ( y 3)2 16
x2 y2 4x 6y 3 0
2. Carilah pusat dan jari jari persamaan lingkaran:
x2 y2 6x 2y 3 0
Pembahasan: A = –6, B = 2, C = –3
x2 y2 Ax By C 0
x2 y2 6x 2y 3 0
Pusat (P) = A , B (6) , 2 3,1
2 2 2 2
Jari-jari (r) = pusat2 C 32 12 (3) 9 1 3 13
3. Persamaan lingkaran dengan pusat (–1, 2) dan melalui (4, 5) adalah....
Pembahasan:
P = (a,b) = (–1, 2)
r = ....
(x a)2 ( y b)2 r 2 (–1,2)
(x (1))2 ( y 2)2 r 2 (4,5)
(x 1)2 ( y 2)2 r 2
Melalui (4, 5):
(4 1)2 (5 2)2 r 2
25 9 r 2
34 r2
(x 1)2 ( y 2)2 34
Rumus-Rumus Penting Dalam Lingkaran
Titik Tengah di Antara Dua Titik
T x1 x2 , y1 y2 A T B
2 2
(x1, y1 ) // // (x2, y2 )
Jarak Titik ke Titik d
d (x2 x1)2 ( y2 y1)2
(x1, y1) (x2, y2 )
Contoh:
Suatu persamaan lingkaran yang garis diameternya melalui (5, 4) dan (–3, 6). Maka, persamaan lingkaran
tersebut adalah ....
Pembahasan: (–3, 6)
(x2,y2)
P x1 x2 , y1 y2
2 2 P
5 3 , 4 6 (5, 4)
2 2 (x1, y1)
= (1, 5)
Panjang diameter (D) dari (–3, 6) sampai (5, 4) adalah:
D (x2 x1)2 ( y2 y1)2
(3 5)2 (6 4)2 (8)2 (2)2 64 4 68
2 17
r 17 Catatan:
r 2 17 D = 2r atau r = ½ D
L (x a)2 ( y b) r 2
(x 1)2 ( y 5)2 17
Jarak Titik ke Garis (x1,y1)
d ax1 by1 c d
a2 b2
ax by c 0
Contoh:
Suatu lingkaran dengan pusat di A(3, 2) dan disinggung oleh garis 3x 4 y 27 0 . Maka, persamaan
lingkaran tersebut adalah ....
Pembahasan:
r d ax1 by1 c (x1,y1)
a2 b2 (3, 2)
r 3(3) 4(2) 27 9 8 27 10 2 r
32 42 9 16 5
3x 4 y 27 0
L (x a)2 ( y b)2 r 2
(x 3)2 ( y 2)2 4
Kedudukan Titik Terhadap Lingkaran
Berikut adalah kedutukan titik A terhadap lingkaran x2 y 2 Ax By C 0 .
Titik A di dalam lingkaran Titik A pada lingkaran Titik A di luar lingkaran
A(x1,y1) A(x1,y1) A(x1,y1)
x2 y2 Ax1 By1 C 0 x2 y2 Ax1 By1 C 0 x2 y2 Ax1 By1 C 0
1 1 1 1 1 1
atau (x1 a)2 ( y1 b)2 r 2 atau (x1 a)2 ( y1 b)2 r 2 atau (x1 a)2 ( y1 b)2 r 2
Contoh:
1. Kedudukan titik T(1,2) terhadap llingkaran x2 y 2 4x 5y 10 0 adalah ....
Pembahasan:
x2 y 2 4x 5y 10 0 Substitusi T(1,2) kepada persamaan lingkaran:
12 22 4(1) 5(2) 10 ? 0
1 4 4 10 10 ? 0
1?0
1>0
Jadi, titik T(1,2) berada di luar lingkaran.
2. Kedudukan titik K(2, –3) terhadap lingkaran (x 3)2 ( y 2)2 10 adalah ....
Pembahasan:
(x 3)2 ( y 2)2 10 Substitusi K(2, –3) kepada persamaan lingkaran:
(2 3)2 (3 2)2 ?10
12 (1)2 ?10
2 ? 10
2 < 10
Maka, titik K(2, –3) berada di dalam lingkaran.
Kedudukan Garis Terhadap Lingkaran
Untuk mengetahui hubungan garis dan lingkaran, dapat ditentukan dengan nilai diskriminan D
(D b2 4ac) .
memotong lingkaran menyinggung lingkaran tidak memotong/menyinggung
D>0 D=0 D<0
Contoh:
Kedudukan garis y 2x 3 terhadap lingkaran x2 y2 2x 3y 5 0 adalah...
Pembahasan: Subtitusikan y garis ke persamaan lingkaran
y 2x 3
x2 y2 2x 3y 5 0
x2 (2x 3)2 2x 3(2x 3) 5 0
x2 4x2 12x 9 2x 6x 9 5 0
5x2 16x 23 0 a = 5, b = 16, c = 23
D b2 4ac
(16)2 4(5)(23)
256 460 204
Karena D = –204 < 0, garis tersebut tidak memotong/menyinggung lingkaran.
Persamaan Garis Singgung Lingkaran
Diketahui Titik Singgungnya
Bentuk persamaan garis singgung (PGS) lingkaran, jika diketahui titik singgungnya adalah sebagai
berikut:
x2 y2 r2 (x a)2 ( y b)2 r2 x2 y 2 Ax By C 0
(x1,y1) (x1,y1) (x1,y1)
PGS : x1 x+ y1 y = r2 PGS : (x1-a)(x-a)+(y1-a)(y-a) = r2 PGS : x1x+ y1y + A (x1+x) + B (y 1+y)+C=0
2 2
Contoh:
1. Persamaan garis singgung lingkaran x2 y2 10 di titik (1,3) adalah ....
Pembahasan : (x1, y 1)
x2 y2 10 melalui titik (1, 3)
PGS : x1x y1y r 2
1x 3y 10
x 3y 10
2. Persamaan garis singgung lingkaran (x 2)2 ( y 4)2 5 di titik (3, –2) adalah ....
Pembahasan:
(x 2)2 ( y 4)2 5 melalui titik (3, –2) (x1, y 1)
PGS : (x1 a)(x a) ( y1 b)( y b) r 2
(x1 2)(x 2) ( y1 4)( y 4) 5
(3 2)(x 2) (2 4)( y 4) 5
1(x 2) 2( y 4) 5
x 2 2y 85
x 2y 1
3. Persamaan garis singgung lingkaran x2 y2 2x 4y 5 0 di titik (2,1) adalah ....
Pembahasan:
x2 y 2 2x 4y 5 0 melalui titik (2,1) (x1, y 1)
x1x y1 y A ( x1 x) B ( y1 y) c 0
2 2
2x 1y 2 (2 x) 4 (1 y) 5 0
2 2
2x y (2 x) 2(1 y) 5 0
2x y 2 x 2 2y 5 0
x 3y 5 0
Diketahui Gradien Garis Singgungnya
x2 y2 r2 (x a)2 ( y b)2 r 2 atau x2 y 2 Ax By C 0
gradien = m gradien = m
PGS : y mx r m2 1 PGS : y b m(x a) r m2 1
Contoh:
1. Persamaan garis singgung lingkaran x2 y 2 5 dengan gradien 2 adalah ....
Pembahasan:
x2 y 2 5, m = 2, r 5
y mx r m2 1
y 2x 5 22 1
y 2x 5 5
y 2x 5
Jadi, PGS-nya adalah y 2x 5 atau y 2x 5 .
2. Persamaan garis singgung lingkaran (x 2)2 ( y 3)2 2 dengan gradien –2 adalah ....
Pembahasan :
(x a)2 ( y b)2 r 2
(x 2)2 ( y 3)2 2 ;a = –2, b = 3, r 2 dan m = –2
y b m(x a) r m2 1
y 3 2(x 2) 2 (2)2 1
y 3 2x 4 2 5
y 2x 4 3 10
y 2x 1 10
Jadi, PGS-nya adalah:
y 2x 1 10 atau y 2x 1 10
3. Garis singgung lingkaran x2 y 2 4x 6y 3 0 dengan gradien 3 adalah ....
Pembahasan:
x2 y 2 4x 6y 3 0 ; A = 4, B = –6, C = 3
Pusat (P) =
A , B 4 , (6) 2,3 sehingga a = –2 , b = 3.
2 2 2 2
r pusat2 C (2)2 32 3 4 9 3 10
Diketahui m = 3, maka:
PGS: y b m(x a) r m2 1
y 3 3(x (2)) 10 32 1
y 3 3(x 2) 10 10
y 3x 6 3 10
y 3x 9 10
Jadi PGS-nya:
y 3x 9 10 atau y 3x 9 10
y 3x 19 atau y 3x 1
Diketahui Titik di Luar Lingkaran
Jika diketahui titik P(x1, y1) di luar lingkaran, maka ada dua garis singgung yang bisa dibuat dari titik
tersebut, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut.
y y1 m1(x x1)
P(x1,y1)
y y1 m2 (x x1)
Maka, langkah penyelesaiannya adalah:
1. Buat persamaan garis yang melalui titk P(x1,y1) dengan gradien m (belum diketahui) dengan
menggunakan rumus: y y1 m (x x1) .
2. Subtitusikan persamaan garis yang diperoleh pada langkah 1 tersebut ke persamaan lingkaran.
3. Dari persamaan lingkara, kita tentukan nilai diskriminan yang bersesuaian (D = 0). Karena garis
menyinggung lingkaran, maka akan didapat nilai m.
4. Masukkan nilai m (gradien) garis yang didapat ke persamaan garis pada langkah 1.
Contoh:
1. Dari titik T(0,10) akan dibuat garis singgung lingkaran x2 y 2 10 . Maka, persamaan garis
singgung yang terjadi adalah... T(0,10)
Pembahasan:
Langkah 1:
T(0,10) dan gradien m:
y y1 m (x x1)
y 10 m(x 0)
y mx 10
Langkah 2:
x2 y 2 10
x2 (mx 10)2 10
x2 m2 x2 20mx 100 10
(m2 1)x2 20mx 90 0 , sehingga a m2 1, b 20m, c 90
Langkah 3:
D=0
b2 4ac 0
(20m)2 4(m2 1)(90) 0
400m2 360m2 360 0
40m2 360
m2 9
m 9 3 ,
Jadi, m1 3 atau m2 3 .
Langkah 4:
y mx 10
Maka, untuk m1 3 atau m2 3 didapat persamaan garis:
y 3x 10 atau y 3x 10
1
Suku Banyak
Pengertian Suku Banyak
Bentuk umum suku banyak adalah:
an xn an1xn1 an2 xn2 .... a2 x2 a1x a0
Keterangan:
an , an1, an2 , ... , a2 , a1, a0 adalah koefisien variabel x.
xn , xn1, xn2 , ... , x2 , x adalah variabel dengan pangkat tertinggi n.
Mencari Nilai Suku Banyak
Metode subtitusi
Contoh:
Diberikan suku banyak f (x) 2x3 4x2 6x 8 , maka nilai dari f (2) adalah ....
Pembahasan:
f (x) 2x3 4x2 6x 8
f (2) 2(2)3 4(2)2 6(2) 8
16 16 12 8
28
Jadi, f (2) = 28.
Metode Horner/bagan/skema
Contoh:
1. Diberikan suku banyak f (x) 2x3 4x2 6x 8 , maka nilai suku banyak untuk x = 2 adalah ....
Pembahasan:
f (x) 2x3 4x2 6x 8 ; koefisien variabelnya adalah 2, 4, –6, dan 8.
x=2 x3 x2 x1 x0
2 4 –6 8
+ + +
2 4 2 16
2 20
2 8 10
28
Jadi, hasilnya adalah 28.
2
2. Suatu suku banyak g(x) 5x4 3x2 44x 5 , maka nilai g(–3) adalah ....
Pembahasan:
g(x) 5x4 3x2 20x 5 , koefisien vareabelnya adalah 5, 0, 3, 44, 5
x = –3 x4 x3 x2 x1 x0
5 03 44 5
+ +
3 ++
–15 3 45 3 –144 3 300
5 –15 48 –100 305
Jadi, hasilnya adalah 305.
Pembagian Suku Banyak
Metode menurun
Contoh:
1. Suatu suku banyak f (x) 3x4 5x3 6x2 2x 6 dibagi dengan x 3, maka hasil dan sisanya
adalah ....
Pembahasan:
3x3 4x2 6x 16 hasil bagi Catatan:
x 3 3x4 5x3 6x2 2x 6
Proses pembagian berhenti, jika yang
3x4 9x3 dibagi berderajat lebih rendah dari
4x3 6x2 pembaginya.
4x3 12x2
6x2 2x sisa
6x2 18x
16x 6
16x 48
42
Jadi, hasil pembagian suku banyak f(x) oleh x + 3 adalah 3x3 4x 2 6x 16 dan sisa 42.
2. g(x) 4x4 2x3 2x 10 dibagi x 2 x 3 sisanya adalah ....
Pembahasan:
3
g(x) 4x4 2x3 2x 10 bisa ditulis menjadi g(x) 4x4 2x3 0x2 2x 10 .
4x2 6x 18 hasil bagi Catatan:
x 2 x 3 4x 4 2x3 0x2 2x 10 sisa
Pembagian berhenti di 38x 64 ,
4x 4 4x3 12x 2
6x3 12x 2 2x karena memiliki derajat lebih rendah
6x3 6x 2 18x
18x2 20x 10 dari pembagi x 2 x 3 .
18x2 18x 54
38x 64
Jadi, hasil pembagian suku banyak g(x) oleh x 2 x 3 adalah 4x2 6x 18 dan sisa 38x 64 .
Metode Horner
Contoh:
1. Suatu suku banyak f (x) 3x4 5x3 6x2 2x 6 dibagi dengan x 3, maka hasil dan sisanya
adalah...
Pembahasan:
Dari pembagi x 3, didapat pembuat nolnya x + 3= 0 sehingga x = –3.
x4 x3 x2 x1 x0
3 5 –6 2 –6
+
x = –3 ++ + 3 48
42
3 –9 3 12 3 –18
3 –4 6 –16 sisa
x3 x2 x1 x0
hasil bagi
Hasil pembagian: 3x3 4x 2 6x 16 dan sisanya = 42.
Metode Horner Kino
Metode pembagian ini digunakan, jika pembaginya berupa fungsi tidak linier.
Contoh:
1. Suatu suku banyak g(x) 4x4 2x3 2x 10 dibagi x 2 x 3 , maka hasil dan sisanya adalah ....
Pembahasan:
4
g(x) 4x4 2x3 2x 10 bisa ditulis g(x) 4x4 2x3 0x2 2x 10 .
Pembagi x 2 x 3 kita ‘nol’ kan x2 x 3 0 maka:
x2 x 3 koefisien : 1 dan 3.
x4 x3 x2 x1 x0
4 2 0 2 10
3 +
+ + +
1 1 4 3 12 3 18 3 54
+ +
1 6 1 18
46 18 38 64
x2 x1 x0 x1 x0
hasil bagi sisa
Jadi, hasil pembagiannya adalah 4x2 6x 18 dan sisa = 38x 64 .
Teorema Sisa
Penjelasan Dasar
Dalam pembagian suku banyak ada empat unsur penting yaitu : suku banyak F(x), pembagi P(x), Hasil H(x)
dan sisa S(x). Jika dituliskan dalam satu kesatuan menjadi :
F(x) = P(x) H(x) + S(x) Ilustrasi dengan angka:
analogi 13 dibagi 2 adalah hasilnya 5 dan sisa 3.
Jadi, pembagian tersebut bisa dituliskan:
sisa 13 = 2 . 5 + 3
suku banyak pembagi hasil
sisa
Jika sisa pembagiannya nol atau S(x) = 0, maka: bilangan hasil
F(x) habis dibagi P(x) yang dibagi pembagi
P(x) faktor dari F(x)
Pangkat tertinggi sisa satu lebih kecil derajatnya dari pada pangkat tertinggi pembagi:
Pangkat Tertinggi Pangkat Tertinggi Sisa konstanta
Pembagi
xn-1
xn x2
x3 x
x2 k
x
5
Pencarian Sisa Dengan Teorema Sisa
Dari persamaan berikut:
F(x) = P(x) H(x) + S(x)
Misalkan, kita mengganti pembagi P(x) dengan (x – A) maka:
F(x) = (x – A) H(x) + S(x)
Kita akan mencari sisa S(x) dengan menghilangkan H(x) menggunakan cara subtitusi x = A. Maka, didapat:
F(A) = (A – A) H(A) + S(A)
F(A) = 0 . H(A) + S(A)
F(A) = S(A)
Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan:
sisa = F(A) dengan A adalah pembuat nol dari pembagi
Contoh:
1. Suatu suku banyak f (x) 3x4 5x3 2x 5 dibagi dengan x 2 maka sisanya adalah ....
Pembahasan:
x 2 pembuat nolnya x A 2 , maka sisa pembagiannya:
f (x) 3x4 5x3 2x 5
Sisa = f(A)
Sisa = f(2)
3(2)4 5(2)3 2(2) 5
48 40 4 5
17
2. Jika fungsi suku banyak 2x47 4x71 3x2.012 7k habis dibagi oleh (x 1) , berapakah nilai k tersebut?.
Pembahasan:
Karena habis dibagi, maka pembagian suku banyak tersebut memberikan sisa 0.
x 1 pembuat nolnya x A 1, maka :
f (x) 2x47 4x71 3x2.012 7k
Sisa = f(A) = f(–1) = 0 Catatan:
2(1)47 4(1)71 3(1)2.012 7k 0 (–1)genap = 1
(–1)ganjil = –1
2(1) 4(1) 3(1) 7k 0
2 4 3 7k 0
5 7k 0
5 7k
k5
7
6
3. Suatu suku banyak, apabila dibagi dengan x 2 menghasilkan sisa 10; dan apabila dibagi dengan
x 3 bersisa –5. Maka, berapakah sisa suku banyak tersebut jika dibagi dengan x2 x 6 ?
Pembahasan: Ingat, karena pangkat pembagi x2
f (x) (x 2) 10 maka sisanya adalah x.
f (2) 10
f (x) (x 3) 5 CADAS:
f (3) 5 -10 - (-30) = 20
f (2) 10 (2, 10)
f (x) (x2 x 3) ax b f (3) 5 (3, 5)
f (x) (x 2)(x 3) ax b
Eliminasi: 5y 15x 20
Sisa = f(A) = ax + b y 3x 4
f (2) 2a b 10 sisa
f (3) 3a b 5
5a 15
a=3
2a b 10
2(3) b 10
6 b 10
b4
Jadi, sisanya adalah 3x 4 .
Teorema Faktor dan Akar
Pengertian Faktor dan Akar
Suatu nilai merupakan faktor dari suatu suku banyak, jika suku banyak dibagi dengan nilai tersebut tidak
memiliki sisa atau sisa = 0.
Sisa = 0 Ilustrasi dengan angka:
F(x) = P(x) H(x) + S(x) 12 dibagi 2 adalah hasilnya 6 dan sisa 0.
Jadi, pembagian tersebut bisa dituliskan:
Hasil = faktor 12 = 2 . 6 + 0
Pembagi = faktor
sisa
faktor
faktor
Atau bisa dikatakan (x – a) merupakan faktor dari f(x), jika f(a) = 0 dengan nilai a disebut akar. Berikut
ilustrasinya:
F(x) = (x – a)(x – b)(x – c) a, b, c adalah akar dari F(x)
faktor
7
Cara Mencari Faktor dan Akar
Jika diketahui suku banyak:
f (x) an xn an1xn1 an2 xn2 .... a2 x2 a1x a0
faktor atau akarnya diperoleh dengan cara berikut ini:
1. Tentukan faktor bulat positif a0 (kita namakan p) dan tentukan faktor bulat positif an (kita namakan q).
2. Kita tentukan kombinasi p dan q dengan k p .
q
3. Masukkan nilai k ke f(x). Jika f(k) = 0, maka k adalah salah satu akar suku banyaknya dan (x – k) adalah
salah satu faktornya.
Contoh:
1. Carilah akar dan faktor dari suku banyak x4 2x3 5x 2 x 10 .
Pembahasan:
Langkah 1:
x 4 2x3 5x 2 x 10 an 1 dan a0 10
p = 1, q = 1, 2, 5, 10
Langkah 2:
k p 1, 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10
q
Langkah 3:
f (1) (1)4 3(1)3 5(1)2 1 10 1 3 5 1 10 0
Karena f(1) = 0 maka x = 1 adalah akar dan (x – 1) adalah faktor.
f (1) (1)4 3(1)3 5(1)2 1 10 1 3 5 1 10 8 0
Karena f (1) 0 maka x = –1 bukan akar.
f (2) (2)4 3(2)3 5(2)2 2 10 16 24 20 2 10 52 0
Karena f (2) 0 maka x = 2 bukan akar.
f (2) (2)4 3(2)3 5(2)2 2 10 16 24 20 2 10 0
Karena f(– 2) = 0 maka x = – 2 adalah akar dan (x +2) adalah faktor.
Kita sudah mendapatkan 2 faktor (x – 1) dan (x +2). Jika keduanya dikalikan, akan diperoleh:
(x 1)(x 2) x2 x 2
Maka, x2 x 2 juga merupakan faktor suku banyak tersebut. Untuk mencari faktor lainnya, bisa
dilakukan dengan membagi suku banyak dengan x2 x 2 .
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Kelas X, XI,XII
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search