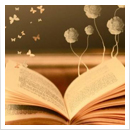LAPORAN AKHIR
“STUDIO PROSES PERENCANAAN”
2
+
LOKASI STUDI
Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang
KELOMPOK 1A
1. WINDY AGUS S (042639505)
2. YUNI AMBARWATI (042639544)
3. NURUL HIDAYAH (042639609)
4. I’IS FEBRIANTO (042639497)
5. SHOVIATUL JANNAH (042639426)
6.
Jl. Mayjen Sungkono No.9, Bumiayu, Kecamatan Kedungkadangan, Kota
Malang, Jawa Timur 65135
Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wata’ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya sehingga
kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir Studio Proses Perencanaan dengan sebaik-
baiknya. Dalam menyelesaikan proposal ini tentunya tidak sedikit hambatan dan tantangan yang kami
alami baik dalam pengumpulan data awal maupun pengerjaannya. Banyak pihak yang tentunya
membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini. Untuk itu, kami berterima kasih kepada:
1. Ibu Fanita Cahyaning Arie, S.T., M.T. dan Bapak Zulkifli, S.T., selaku dosen
pembimbing Studio Proses – UPBJJ-UT Malang yang telah memberikan ilmu,
keterampilan, nasihat, dan wawasan selama proses penyusunan Proposal Teknis
Studio Proses Perencanaan ini.
2. Rekan-rekan Studio Proses Perencanaan – UPBJJ-UT Malang 2022.1 atas
kerjasama, waktu, tenaga, dan dukungannya.
3. Serta, pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian Laporan Studio Proses
Perencanaan ini.
Kami berharap Proposal Teknis ini dapat menjadi acuan dasar praktik Studio Proses Perencanaan
yang akan dilakukan. Tentunya kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan proposal ini
terdapat banyak kekurangan, mengingat betapa minimnya pengetahuan dan kemampuan yang kami
miliki.
Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik, masukan dan sasaran yang sifatnya membangun dari
para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan Proposal Teknis ini. Kami
mengharapkan Proposal Teknis ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta inspirasi bagi
pembaca.
Malang, Maret 2022
Tim Penulis
Kelompok 1A – UPBJJ-UT Malang 2022.1
LAPORAN AKHR STUDIO | 1
KATA PENGANTAR ................................................................................................ 1
DAFTAR ISI................................................................................................................ 2
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... 5
DAFTAR TABEL........................................................................................................ 9
DAFTAR PETA ........................................................................................................ 11
1 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 13
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................13
1.2 Rumusan Isu Spasial...........................................................................................................14
1.3 Tujuan dan Sasaran............................................................................................................14
1.3.1 Tujuan ................................................................................................................................................................. 14
1.3.2 Sasaran ................................................................................................................................................................ 14
1.4 Ruang Lingkup....................................................................................................................14
1.4.1 Ruang Lingkup Materi ...................................................................................................................................... 14
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah ................................................................................................................................... 15
1.5 Metode dan Teknik Survey................................................................................................16
1.5.1 Metode Pengumpulan Data ............................................................................................................................ 16
1.5.2 Teknik Survey.................................................................................................................................................... 17
1.6 Diagram Alir ......................................................................................................................20
2 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 21
2.1 Teori perencanaan Wilayah dan Kota ..............................................................................21
2.2 Teori Desa dan Kota..........................................................................................................22
2.2.1 Desa..................................................................................................................................................................... 23
2.2.2 Kota..................................................................................................................................................................... 24
2.3 Teori klasifikasi desa ..........................................................................................................25
2.4 Fisik Dasar ..........................................................................................................................26
2.4.1 Iklim ..................................................................................................................................................................... 26
2.4.2 Curah Hujan ...................................................................................................................................................... 27
2.4.3 Kelerengan ......................................................................................................................................................... 27
2.4.4 Hidrologi............................................................................................................................................................. 27
LAPORAN AKHR STUDIO | 2
2.4.5 Jenis Tanah ......................................................................................................................................................... 27
2.5 Fisik Binaan ........................................................................................................................28
2.5.1 Struktur Ruang Desa........................................................................................................................................ 28
2.5.2 Fasilitas................................................................................................................................................................ 32
2.5.3 Utilitas................................................................................................................................................................. 34
2.6 Kependudukan ...................................................................................................................38
2.6.1 Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk............................................................................................... 39
2.6.2 Kelompok Umur............................................................................................................................................... 39
2.6.3 Jenis Kelamin ..................................................................................................................................................... 39
2.6.4 Pendidikan .......................................................................................................................................................... 39
2.6.5 Agama.................................................................................................................................................................. 40
2.6.6 Mata pencaharian.............................................................................................................................................. 40
2.6.7 Piramida Penduduk........................................................................................................................................... 40
2.6.8 Persebaran Penduduk ...................................................................................................................................... 40
2.6.9 Kelahiran, Kematian, dan Migrasi.................................................................................................................. 41
2.6.10 Proyeksi Penduduk...................................................................................................................................... 41
2.7 Kebudayaan ........................................................................................................................41
2.7.1 Kegiatan dan Tradisi Masyarakat Desa ........................................................................................................ 42
2.7.2 Kesenian ............................................................................................................................................................. 43
2.8 Perekonomian Desa...........................................................................................................44
2.8.1 Teori Potensi Desa .......................................................................................................................................... 44
2.8.2 UMKM................................................................................................................................................................. 45
2.9 Kelembagaan Desa ............................................................................................................46
2.10 Intensitas Pemanfaatan Ruang..........................................................................................46
2.10.1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang............................................................................................... 47
3 BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN....................... 49
3.1 Orientasi Wilayah Perencanaan .......................................................................................49
3.2 Letak Geografis Wilayah Perencanaan.............................................................................53
3.3 Aspek Fisik Wilayah Perencanaan ....................................................................................55
3.3.1 Fisik Dasar.......................................................................................................................................................... 55
3.3.2 Fisik Binaan......................................................................................................................................................... 65
3.4 Aspek Kependudukan Wilayah Perencanaan.................................................................103
3.4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun .......................................................................................................103
3.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin...................................................104
3.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.......................................................................................................104
3.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ...............................................................................................105
3.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ...................................................................................107
3.5 Aspek Perekonomian Wilayah Perencanaan .................................................................108
3.6 Aspek Kelembagaan Wilayah Perencanaan ...................................................................109
3.7 Aspek Sosial Budaya Wilayah Perencanaan...................................................................109
LAPORAN AKHR STUDIO | 3
4 BAB 4 ANALISIS ............................................................................................ 113
4.1 Analisis Fungsi Kawasan ..................................................................................................113
4.2 Analisis Lahan Sawah Di Lindungi(LSD).........................................................................117
4.2.1 Penetapan Faktor LSD...................................................................................................................................120
4.2.2 Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).................................................................................................126
4.3 Analisis Kependudukan....................................................................................................129
4.3.1 Trend Penduduk .............................................................................................................................................129
4.3.2 Kepadatan Penduduk .....................................................................................................................................130
4.3.3 Komposisi Penduduk .....................................................................................................................................133
4.3.4 Proyeksi Penduduk.........................................................................................................................................134
4.4 Analisis Wilayah Perencanaan ........................................................................................136
4.4.1 Analisis Kebutuhan Fasilitas..........................................................................................................................136
4.4.2 Analisis Kebutuhan Utilitas...........................................................................................................................153
4.5 Analisis Prekonomian ......................................................................................................171
4.5.1 Mata Pencaharian............................................................................................................................................171
4.5.2 Sumber Perekonomian..................................................................................................................................174
4.6 Analisis Arah Pergerakan ................................................................................................187
4.6.1 Arah Pergerakan Pendidikan........................................................................................................................187
4.6.2 Arah Pergerakan Ekonomi............................................................................................................................190
4.6.3 Arah Pergerakan Mata Pencaharian............................................................................................................192
4.7 Analisis Kelembagaan ......................................................................................................194
4.7.1 Jenis Kelembagaan ..........................................................................................................................................194
4.7.2 Analisis Social Network Analysis(SNA).....................................................................................................204
4.7.3 Desa Tawangargo ...........................................................................................................................................205
4.8 Analisis Sosial Budaya......................................................................................................208
5 BAB 5 ISU STRATEGIS KAWASAN........................................................... 211
5.1 Analisis Pengembangan Potensi Desa ............................................................................211
5.1.1 Sektor Pertanian .............................................................................................................................................211
5.1.2 Sektor Pariwisata............................................................................................................................................213
5.2 Analisis Permasalahan Desa ............................................................................................215
6 BAB 6 PENUTUP ........................................................................................... 220
6.1 Kesimpulan.......................................................................................................................220
6.2 Rekomendasi ....................................................................................................................221
7 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 223
LEMBAR ASISTENSI ............................................................................................ 224
LAPORAN AKHR STUDIO | 4
Gambar 1.1 Kuisioner Survey .......................................................................................................................... 16
Gambar 1.2 Observasi Tempat Pembuangan Sampah ................................................................................ 16
Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Desa ..................................................................... 17
Gambar 1.4 Karangka Sampel........................................................................................................................... 18
Gambar 1.5 Kerangka Berpikir ........................................................................................................................ 20
Gambar 2.1 Ilustrasi KDB ................................................................................................................................. 47
Gambar 2.2 Ilustrasi KDH................................................................................................................................. 48
Gambar 3.1 KEK Pariwisata.............................................................................................................................. 50
Gambar 3.2 Temperatur Udara ....................................................................................................................... 55
Gambar 3.3 Perbandingan luas jenis tanah di kabupaten malang ............................................................. 58
Gambar 3.4 Tanah Andosol .............................................................................................................................. 59
Gambar 3.5 Tanah Latosol ................................................................................................................................ 60
Gambar 3.6 Tanah Regosol............................................................................................................................... 60
Gambar 3.7 Penggunaan Lahan Desa Tawangargo ...................................................................................... 66
Gambar 3.8 Foto Mapping Penggunaan Lahan.............................................................................................. 67
Gambar 3.9 Foto Mapping Sarana Kesehatan............................................................................................... 71
Gambar 3.10 Foto Mapping Perdagangan dan Jasa ...................................................................................... 74
Gambar 3.11 Diagram Jumlah Fasilitas Pendidikan..................................................................................... 76
Gambar 3.12 Foto Mapping Sarana Pendidikan............................................................................................ 78
Gambar 3.13 Diagram Sarana Peribadatan.................................................................................................... 80
Gambar 3.14 Foto Mapping Sarana Peribadatan .......................................................................................... 81
Gambar 3.15 Foto Mapping Jaringan Listrik Desa Tawangargo ............................................................... 83
Gambar 3.16 Foto Mapping Jaringan Telekomunikasi Desa Tawangargo............................................. 86
Gambar 3.17 Jenis Drainase Desa Tawangargo ........................................................................................... 88
Gambar 3.18 Foto Mapping Jenis Drainase di Desa Tawangaro .............................................................. 89
Gambar 3.19 Foto Mapping Sumber Air Bersih........................................................................................... 92
Gambar 3.20 Persebaran TPS........................................................................................................................... 94
Gambar 3.21 Klasifikasi Jalan ............................................................................................................................ 96
Gambar 3.22 Klasifikasi Jalan Desa Tawangargo......................................................................................... 96
Gambar 3.23 Diagram Kondisi Jalan ............................................................................................................... 97
LAPORAN AKHR STUDIO | 5
Gambar 3.24 Foto Mapping Kondisi Jalan...................................................................................................... 98
Gambar 3.25 Diagram Jenis Perkerasan Jalan ............................................................................................... 99
Gambar 3.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Nama Dusun ....................................................................103
Gambar 3.27 Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....................................105
Gambar 3.28 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan........................................................106
Gambar 3.29 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ..................................................107
Gambar 4.1Gambar 4.2 Luas Fungsi Kawasan............................................................................................115
Gambar 4.3 Peta Fungsi Kawasan.................................................................................................................115
Gambar 4.4 Luas Sawah di Desa Tawangargo............................................................................................118
Gambar 4.5 Lahan Sawah Desa Tawangargo ..............................................................................................119
Gambar 4.6 Faktor pengunci pertama..........................................................................................................121
Gambar 4.7 Faktor pengunci pertama..........................................................................................................122
Gambar 4.8 Hasil Panen Padi..........................................................................................................................123
Gambar 4.9 Faktor Pengunci Kedua .............................................................................................................123
Gambar 4.10 Faktor Pengunci Ketiga ...........................................................................................................124
Gambar 4.11 Faktor Pengunci Ke empat.....................................................................................................125
Gambar 4.12 Diagram Luas Penetapan LSD ...............................................................................................126
Gambar 4.13 Penetapan LSD Desa Tawangargo .......................................................................................127
Gambar 4.14 Diagram Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir .......................................129
Gambar 4.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Nama Dusun ....................................................................130
Gambar 4.16 Piramida Penduduk Desa Tawangargo...............................................................................133
Gambar 4.17 Proyeksi penduduk tahun 2025-2040..................................................................................135
Gambar 4.18 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan .........................................................................137
Gambar 4.19 Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa ............................................................................140
Gambar 4.20 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Jasa .....................................................141
Gambar 4.21 Kebutuhan fasilitas Pendidikan ..............................................................................................143
Gambar 4.22 Diagram Jumlah Fasilitas Pendidikan...................................................................................144
Gambar 4.23 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan........................................................145
Gambar 4.24 Foto Mapping Sarana Pendidikan..........................................................................................146
Gambar 4.25 Peta Radius Pelayanan Sarana Pendidikan...........................................................................148
Gambar 4.26 Kebutuhan fasilitas Peribadatan ............................................................................................150
LAPORAN AKHR STUDIO | 6
Gambar 4.27Peta Radius Pelayanan Fasilitas Peribadatan ........................................................................151
Gambar 4.28 Peta Jaringan Listrik .................................................................................................................153
Gambar 4.29 Peta Jaringan Telekmunikasi ..................................................................................................155
Gambar 4.30 .4.31 Peta Jaringan Drainase ..................................................................................................157
Gambar 4.32 Peta Jaringan Jalan ....................................................................................................................160
Gambar 4.33 Penampang Melintang Jalan Kolektor ..................................................................................162
Gambar 4.34 Penampang Melintang Jalan Lokal .........................................................................................163
Gambar 4.35 Penampang Melintang Jalan Lingkungan ..............................................................................164
Gambar 4.36 Sumber Air Desa Tawangargo ..............................................................................................166
Gambar 4.37 Pengelolaan Sampah Individu.................................................................................................168
Gambar 4.38 Tempat Pembuangan Sampah................................................................................................168
Gambar 4.39 Alur Pengelolaan Sampah Desa Tawangargo.....................................................................169
Gambar 4.40 Penggunaan Lahan Desa Tawangargo..................................................................................171
Gambar 4.41 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ..................................................173
Gambar 4.42 Foto Mapping Komoditas per dusun ...................................................................................175
Gambar 4.43 Kebun Sawi yang ada di Desa Tawangargo ........................................................................177
Gambar 4.44 Hutan UB Forest........................................................................................................................177
Gambar 4.45 Tanaman Kopi...........................................................................................................................178
Gambar 4.46 Petani Kopi ................................................................................................................................179
Gambar 4.47 Dusun Sahabat Alam................................................................................................................180
Gambar 4.48 Brosur Dusun Sahabat Alam .................................................................................................181
Gambar 4.49 Lintas arjuno..............................................................................................................................181
Gambar 4.50 Taman yang masih dalam proses pembangunan................................................................182
Gambar 4.51 Toko Bu Tuti.............................................................................................................................183
Gambar 4.52 Restoran Bebek Kerto............................................................................................................183
Gambar 4.53Jagung manis mbak arni ............................................................................................................184
Gambar 4.54 Produk yang ada di Dusun Suwaluhan.................................................................................184
Gambar 4.55 Produk yang ada di Dusun Boro...........................................................................................185
Gambar 4.56 Produk yang ada di Dusun Boro...........................................................................................185
Gambar 4.57 Produk yang ada di Dusun Leban .........................................................................................185
Gambar 4.58 Produk yang ada di Dusun Lasah..........................................................................................186
LAPORAN AKHR STUDIO | 7
Gambar 4.59Produk yang ada di Dusun Boro............................................................................................186
Gambar 4.60 Struktur Pemerintahan Desa Tawagargo ...........................................................................195
Gambar 4.61 Struktur Organisasi BPD ........................................................................................................199
Gambar 4.62Struktur LPMD...........................................................................................................................200
Gambar 4.63 Struktur organisasi BUMDes.................................................................................................202
Gambar 4.64 Struktur organisasi PKK(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)...............................203
Gambar 4.65 Struktur Organisasi Gapoktan ..............................................................................................204
Gambar 4.66 Degree Centrality........................................................................................................................205
Gambar 4.67 Closeness Centrality....................................................................................................................206
Gambar 4.68 Betweeness Centrality ................................................................................................................207
Gambar 4.69 Kebudayaan Desa Tawangargo .............................................................................................210
Gambar 5.1 Foto Mapping UB Forest ..........................................................................................................211
Gambar 5.2 Foto Mapping Sektor Pertanian ..............................................................................................212
Gambar 5.3 Wisata Lintas Arjuno.................................................................................................................213
Gambar 5.4 Wisata Pertanian Organik ........................................................................................................214
Gambar 5.5 Dusun Sahabat Alam..................................................................................................................214
Gambar 5.6 Kondisi Jalan yang kurang baik ................................................................................................216
Gambar 5.7 Akibat akses jalan yang tidak rata ...........................................................................................217
Gambar 5.8 Drainase yang berisi sampah....................................................................................................218
Gambar 5.9 Dusun Boro .................................................................................................................................219
Gambar 6.1 Perbaikan Jalan dengan Gotong Royong ...............................................................................221
Gambar 6.2 Pembersihan Drainase...............................................................................................................221
Gambar 6.3 Pengelolaan sampah yang baik................................................................................................222
Gambar 6.4 Strategi Marketing ......................................................................................................................222
LAPORAN AKHR STUDIO | 8
Tabel 1.1 Ruang Lingkup Materi....................................................................................................................... 14
Tabel 3.1 Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah Dan Sifat-Sifatnya.................................... 57
Tabel 3.2 Kelas Kelerengan............................................................................................................................... 63
Tabel 3.3 Penggunaan lahan .............................................................................................................................. 65
Tabel 3.4 Fasilitas Kesehatan Di Desa Tawangargo .................................................................................... 70
Tabel 3.5 Perdagangan dan jasa Di Desa Tawangargo................................................................................ 73
Tabel 3.6 fasilitas Pendidikan di Desa Tawangargo ..................................................................................... 76
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.................................................................................. 77
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur ............................................................................. 77
Tabel 3.9 Sarana Peribadatan di Desa Tawangargo..................................................................................... 80
Tabel 3.10 Jumlah Pemeluk Agama ................................................................................................................. 80
Tabel 3.11 Jenis drainase Desa Tawangargo ................................................................................................. 88
Tabel 3.12 Jenis Drainase .................................................................................................................................. 88
Tabel 3.13 Kondisi Jalan di Desa Tawangargo.............................................................................................. 97
Tabel 3.14Tabel Jenis perkerasan jalan ......................................................................................................... 99
Tabel 3.15 Persebaran dan kepadatan penduduk Desa Tawangargo. ...................................................103
Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ..................................................................104
Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....................................................................................104
Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .............................................................................105
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.................................................................107
Tabel 3.20 Kebudayaan Desa Tawangargo..................................................................................................110
Tabel 3.21 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..............................................................................110
Tabel 3.22 Kebudayaan di Desa Tawngargo ...............................................................................................112
Tabel 4.1 Skoring Kelerengan.........................................................................................................................113
Tabel 4.2 Skoring Jenis Tanah.........................................................................................................................113
Tabel 4.3 Skoring Intensitas Hujan................................................................................................................114
Tabel 4.4 Kriteria Kemampuan Lahan dan Cirinya....................................................................................114
Tabel 4.5 Luas Fungsi Kawasan ......................................................................................................................115
Tabel 4.6 Luas sawah........................................................................................................................................117
Tabel 4.7 Luas Faktor Pengunci Pertama.....................................................................................................122
LAPORAN AKHR STUDIO | 9
Tabel 4.8 Hasil Produksi padi .........................................................................................................................123
Tabel 4.9 Penetapan LSD.................................................................................................................................126
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir .........................................................................................129
Tabel 4.11 Persebaran dan kepadatan penduduk Desa Tawangargo. ...................................................130
Tabel 4.12 Perhitungan Kepadatan Penduduk ............................................................................................130
Tabel 4.13 Perkembangan jumlah penduduk tahun 2025-2040..............................................................134
Tabel 4.14 Kebutuhan Sarana Kesehatan.....................................................................................................136
Tabel 4.15 Kebutuhan Radius Fasilitas Kesehatan .....................................................................................137
Tabel 4.16 Tabel fasilitas Pendidikan di Desa Tawangargo......................................................................144
Tabel 4.17Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan...............................................................................145
Tabel 4.18Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur ..........................................................................145
Tabel 4.19 Radius Fasilitas Pendidikan..........................................................................................................147
Tabel 4.20 Radius Fasilitas Peribadatan ........................................................................................................150
Tabel 4.21 Ukuran Jalan..................................................................................................................................161
Tabel 4.22 Sumber Air Desa Tawangargo...................................................................................................166
Tabel 4.23 Luas Guna Lahan Desa Tawangargo.........................................................................................171
Tabel 4.24 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian........................................................................172
Tabel 4.25 Tabel komoditas unggulan Desa Tawangargo........................................................................175
Tabel 4.26 Hasil Pertanian Desa Tawangargo tahun 2017 ......................................................................176
Tabel 4.27 Fasilitas Pendidikan Desa Tawangargo.....................................................................................187
Tabel 4.28 Arah Pergerakan Pendidikan Desa Tawangargo....................................................................188
Tabel 4.29 Hasil Wawancara Pergerakan Ekonomi...................................................................................190
Tabel 4.30 Hasil Wawancara Pergerakan Mata Pencaharian ..................................................................192
Tabel 4.31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.................................................................208
Tabel 5.1 Tabel Titik Kerusakan Jalan ..........................................................................................................215
LAPORAN AKHR STUDIO | 10
Peta 3.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten ................................................................................................. 51
Peta 3.2 Peta Administrasi Kecamatan........................................................................................................... 52
Peta 3.3 Peta Administrasi Desa ...................................................................................................................... 54
Peta 3.4 Peta Curah Hujan................................................................................................................................ 56
Peta 3.5 Peta Jenis Tanah................................................................................................................................... 62
Peta 3.6 Peta Kelerengan................................................................................................................................... 64
Peta 3.7 Penggunaan Lahan Desa Tawangargo ............................................................................................. 69
Peta 3.8 Peta Persebaran Sarana Kesehatan ................................................................................................. 72
Peta 3.9 Peta Persebaran Perdagangan dan Jasa ......................................................................................... 75
Peta 3.10 Peta Persebaran Fasiltas Pendidikan ............................................................................................. 79
Peta 3.11 Peta Persebaran Fasilitas Peribadatan .......................................................................................... 82
Peta 3.12 Peta Jaringan Listrik Desa Tawangargo........................................................................................ 85
Peta 3.13 Peta Jaringan Telekomunikasi......................................................................................................... 87
Peta 3.14 Peta Jaringan Drainase ..................................................................................................................... 90
Peta 3.15 Peta Persebaran Sumber Air .......................................................................................................... 93
Peta 3.16 Peta Persebaran TPS ........................................................................................................................ 95
Peta 3.17 Peta Klasifikasi Jalan........................................................................................................................100
Peta 3.18 Peta Kondisi Jalan............................................................................................................................101
Peta 3.19 Peta Perkerasan Jalan .....................................................................................................................102
Peta 4.1 Peta Klasifikasi Kawasan Desa Tawangargo ................................................................................116
Peta 4.2 Peta Lahan Sawah Di Lindungi ......................................................................................................128
Peta 4.3 Peta Kepadatan Penduduk Desa Tawangargo ............................................................................132
Peta 4.4 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan ..................................................................................139
Peta 4.5 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Jasa...............................................................142
Peta 4.6 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan ..................................................................................149
Peta 4.7 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Peribadatan ................................................................................152
Peta 4.8 Peta Analisa Jaringan Listrik Desa Tawangargo..........................................................................154
Peta 4.9 Peta Analisa Jaringan Telekomunikasi Desa Tawangargo ........................................................156
Peta 4.10 Peta Jaringan Drainase ..................................................................................................................159
Peta 4.11 Peta Analisa Jaringan Jalan............................................................................................................165
LAPORAN AKHR STUDIO | 11
Peta 4.12 Peta Analisa Sumber Air................................................................................................................167
Peta 4.13 Peta Persebaran TPS ......................................................................................................................170
Peta 4.14 Peta Pergerakan Pendidikan .........................................................................................................189
Peta 4.15 Peta Pergerakan Ekoomi ...............................................................................................................191
Peta 4.16 Peta Pergerakan Mata Pencaharian .............................................................................................193
LAPORAN AKHR STUDIO | 12
1.1 Latar Belakang
Perencanaan merupakan penentuan langkah-langkah yang digunakan untuk
mencapai suatu tujuan. Perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang
digunakan untuk suatu wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati atau
ditetapkan. Perencanaan sendiri terdiri dari beberapa tahapan . Salah satu tahapan dasar
dalam melakukan perencanaan khususnya dalam lingkup wilayah dan kota yaitu berupa
proses perencanaan yang meliputi pengenalan wilayah dan pengumpulan data . Pengenalan
wilayah menjadi hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi
wilayah baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi , maupun system aktivitas masyarakat di wilayah
tersebut . Selain itu, pengumpulan data juga menjadi hal yang tidak kalah penting karena
merupakan bagian dari pengenalan wilayah dan berguna untuk memastikan keakuratan hasil
dari pengenalan wilayah secara kasat mata .
Fokus utama dari perencanaan adalah orientasi yang membahas tentang masa
depan dan cara-cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi perencanaan
juga berorientasi pada masa sekarang. Menurut Dempster (1998), berorientasi pada masa
depan, berarti melakukan pemikiran tentang masa saat ini sebagai hasil dari masa lalu, dan
melihat kemungkinan apa yang dapat dicapai pada masa mendatang. Maka dari itu,
perencanaan merupakan memikirkan mengenai kondisi saat ini dan masa lalu untuk melihat
kemungkinan yang dapat dicapai pada masa mendatang, serta menyusun rangkaian tindakan
untuk mewujudkan apa yang telah dipikirkan. Perencanaan merupakan hal penting dalam
pembangunan suatu wilayah dan kota.
Perencanaan perlu dilakukan dalam pembangunan wilayah dan kota. Hal ini
dikarenakan konsen terhadap kebaikan seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu
pendekatan pembangunan yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan dalam jangka
panjang yakni ditemukan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan atau sustainable
development. Dengan ini jika menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan, maka
dapat disimpulkan bahwa perencanaan diperlukan dalam rangka mewujudkan kepentingan
seluruh masyarakat melalui pemeliharaan lingkungan alam (fisik), kehidupan sosial dan
budaya, serta ekonomi.
Dalam Studio Proses Perencanaan ini, wilayah perencanaan yang digunakan yaitu
Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang . Desa Tawangargo sendiri
merupakan salah satu desa yang berada di dataran tinggi yang tepatnya berada di kaki gunung
Arjuno. Dengan wilayah yang berada di dataran tinggi, Desa Tawangargo memiliki komoditas
unggulan berupa hasil pertanian padi dan juga sayuran. Pemandangan alam yang indah
menjadikan Desa Tawangargo dapat menjadi objek wisata. Selain itu, Desa Tawangarago
dilewati oleh jalur utama penghubung Kota Batu dan Kota Surabaya, sehingga diarahkan
untuk kawasan pertumbuhan cepat. Dengan potensi Desa Tawangargo tersebut, menjadi
latar belakang dalam kegiatan proses perencanaan diperlukan agar dapat dikembangkan
semaksimal mungkin kedepannya. Oleh karena itu, dalam Studio Proses Perencanaan ini
dibuat untuk mengidentifikasi potensi dan juga permasalahan yang ada di Desa Tawangargo.
Kegiatan identifikasi karakteristik wilayah, penyusunan potensi dan permasalahan serta
penyusunan gagasan-gagasan awal perencanaan diperlukan guna membuat perencanaan yang
sesuai, tepat sasaran dan berkelanjutan di wilayah Desa Tawangargo..
LAPORAN AKHR STUDIO | 13
1.2 Rumusan Isu Spasial
Merujuk pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana kondisi fisik dan lingkungan Desa Tawangargo?
2. Bagaimana aspek kependudukan di Desa Tawangargo?
3. Bagaimana kondisi aspek ekonomi di Desa Tawangargo?
4. Bagaimana kondisi aspek sarana, prasarana, dan transportasi di Desa
Tawangargo?
5. Bagaimana aspek kebijakan dan kelembagaan yang ada di Desa Tawangargo?
6. Apa potensi dan permasalahan yang ada di Desa Tawangargo?
1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan
Tujuan dari kegiatan studio proses perencanaan yang berlokasi di Desa
Tawangargo, Kecamatan Karangploso adalah untuk mengetahui karakteristik Desa
Tawangargo. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenali dan memahami kondisi fisik dan non-
fisik.
1.3.2 Sasaran
Untuk dapat mencapai tujuan dari kegiatan studio proses perencanaan, maka
diperlukan beberapa sasaran, diantaranya:
1. Mengetahui kondisi fisik Desa Tawangargo
2. Mengetahui kondisi sosial budaya dan kependudukan dari Desa Tawangargo
3. Mengetahui kondisi perekonomian Desa Tawangargo
4. Mengetahui kondisi kelembagaan yang ada di Desa Tawangargo
5. Mengetahui potensi yang dapat dikembangkan di Desa Tawangargo
6. Mengetahui permasalahan yang ditemukan di Desa Tawangargo
1.4 Ruang Lingkup
Pada Ruang lingkup wilayah di Studio Proses Perencanaan terdiri atas 2 (dua)
cakupan antara lain Ruang Lingkup Materi dan Ruang Lingkup Wilayah. Berikut ini adalah
penjelasan mengenai kedua ruang lingkup tersebut.
1.4.1 Ruang Lingkup Materi
Merujuk pada sasaran yang dirumuskan diatas ruang lingkup yang mendasari
penelitian ini adalah :
Tabel 1.1 Ruang Lingkup Materi
LAPORAN AKHR STUDIO | 14
Aspek Data dan Informasi
Fisik • Fisik Dasar
- Iklim
Kependudukan - Curah Hujan
- Kelerengan
Kebudayaan - Jenis Tanah
Kegiatan/Aktivitas
Masyarakat • Fisik Binaan
- Land use
Ekonomi - Fasilitas
- Utilitas
Kelembagaan
• Data jumlah penduduk per dusun
Sumber: Hasil Analisa Kelompok • Data jenis kelamin penduduk
• Data kelompok umur penduduk
• Data jumlah penduduk 5 tahun terakhir
• Data Mata pencaharian penduduk
• Data persebaran penduduk
• Data fertilitas penduduk
• Data Mortalitas penduduk
• Data jenis agama penduduk
• Adat Istiadat
• Tradisi
• kesenian
• Pergerakan penduduk
• Pusat Pendidikan
• Pusat perdagangan
• Pusat pemerintahan
• Pergerakan penduduk
• Industri
• UMKM
• Kekayaan Alam
• Sistem organisasi
• Jenis organisasi
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah studi yaitu Desa Tawangargo. Desa Tawangargo
merupakan salah satu desa di kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur. Desa Tawangargo ini memiliki luas wilayah seluas 1154 ha. Ruang lingkup wilayah di
Desa Tawangargo terbagi menjadi enam dusun yaitu dusun Suwaluwan, dusun Kalimalang,
dusun Ngudi, Dusun Leban, dusun Lasah dan dusun Boro yang terdiri dari 56 Rukun
Tetangga (RT) dan berada dalam koordinasi 14 Rukun Warga (RW). Batas Desa
Tawangargo yaitui sebelah utara berbatasan dengan Perhutani, sebelah barat berbatasan
dengan Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebelah selatan berbatasan dengan
Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan
Desa Donowarih.
LAPORAN AKHR STUDIO | 15
1.5 Metode dan Teknik Survey
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, ada beberapa teknik
digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut
dipergunakan untu memperoleh data dan informasi yang nantinya digunakan untuk
kebutuhan analisis penelitian ini.
1. Interview/Wawancara
Gambar 1.1 Kuisioner Survey
Sumber: Hasil Survey 2021
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara Tanya jawab secara langsung.
Wawancara penelitian ini dilakukan kepada pihak desa beberapa masyarakat di Desa
Tawangargo sesuai data yang dibutuhkan.
2. Observasi
Gambar 1.2 Observasi Tempat Pembuangan Sampah
Sumber: Dokumentasi 2021
Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengamati obyek penelitian secara langsung, serta melihat dan mengambil suatu data yang
dibutuhkan langsung di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan di penelitian ini adalah
mengamati kondisi Desa Tawangargo terkait beberapa aspek seperti aspek fisik dan
lingkungan, aspek sosial kependudukan, aspek sarana dan prasarana, dan aspek kelembagaan
dan pembiayaan.
LAPORAN AKHR STUDIO | 16
3. Dokumentasi
Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Desa
Sumber: Dokumentasi 2021
Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dimana dokumentasi bisa
menjadi bukti terjadinya suatu hal dan bukti valid untuk kebutuhan data yang dibutuhkan.
Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-
sumber data yang dibutuhkan. Dokumentasi juga bisa diartikan sebagai pengambilan data
melalui dokumen tertulis maupun elektronik yang digunakan sebagai data pendukung
kelengkapan data yang lain.
4. Literatur
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data non spasial yang nantinya
berguna sebagai penunjang informasi saat analisa. Literature ini dilihat pada website resmi
Desa Tawangargo serta jurnal jurnal yang berkaitan dengan lokasi perencanaan.
1.5.2 Teknik Survey
Teknik survey merupakan suatu teknik atau tata cara yang nantinya digunakan
sewaktu survey atau obsevrasi langsung maupun tidak langsung. Survey juga mengumulkan
data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relative lebih
kecil. Pengambilan sampel bertujuan menggali semua informasi yang dibutuhkan pada
penelitian ini. Kerangka sampel yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada kerangka
survey di bawah ini.
LAPORAN AKHR STUDIO | 17
Gambar 1.4 Karangka Sampel
Sumber: Hasil Analisa 2021
Penelitian di Desa Tawangargo dalam memperoleh data kuantitatif dan kualitatif
kami harus menentukan sampel. Dimana dari masing-masing tipe data memerlukan metode
dalam pengambilan sampel yang berbeda-beda .
Sampel Data Kuantitatif menggunakan pendekatan metode probability sampling
dimana metode ini memungkinkan seluruh populasi sampel memiliki peluang yang sama
untuk dijadikan anggota sampel . Dalam bagan kerangka survei di Tawangargo ini kami
samplingkan populasi dalam kelompok pembagian wilayah dimana sulit jika hanya di ambil
per individu, oleh karenanya kami menggunakan pendekatan metode cluster sampling
dimana pengidentifikasian dalam memperoleh data (perekonomian, Transportasi dan
fasilitas+utilitas) dalam pembagian wilayah kami dapatkan dari kelompok masyarakat per
dusun . Selanjutnya bergeser ke arah kiri dari sampling masyarakat per dusun dalam data
kuantitatif , yakni di sebelah kiri sendiri ada cara mendapatkan data Sosial kependudukan
dimana data ini terbilang heterogen sehingga kami memperolehnya dari sekertaris desa dan
admin yang ada di desa .
Untuk jenis data kualitatif sendiri kami menggunakan pendekatan metode Non-
probability sampling dimana metode ini tidak memungkinkan populasi samplingnya memiliki
peluang yang sama . Di sini di ibaratkan sampling aktivitas warga, sistem persampahan,
sistem air bersih, Kelembagaan desa serta batas desa yang kami tentukan dengan metode
snowball sampling dimana dari data satu sampel bisa menjadi banyak sampel dikarenakan
LAPORAN AKHR STUDIO | 18
informasi dari satu pihak dapat bercabang ke pihak lain yang memang pada porsinya dapat
memberikan informasi yang lebih luas lagi . Seperti pada pengambilan data aktivitas warga,
sistem persampahan dan sumber air bersih kami samplingkan kepada kepala dusun lalu dari
kepala dusun di berikan arahan untuk menggali lagi informasi kepada masyarakat kemudian
dari sampling masyarakat luas ini di ambil berdasarkan kebutuhan untuk para pedagang,
supir, petani, dan ibu rumah tangga . Dimana masing-masing memberikan informasi yang
beragam mengenai aktivitas warga misalnya dimana untuk pendidikan, serta kebutuhan
sehari harinya pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda mulai dari para pedagang, petani,
supir dan ibu rumah tangga . Suatu misal untuk para pedagang pastinya memikirkan untuk
kebutuhan sehari harinya jauh lebih besar karena harus dijual . Berbeda lagi dengan ibu
rumah tangga dimana kebutuhannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari tanpa di jual lagi
seperti para pedagang .
Selanjutnya bergeser ke kanan untuk metode dalam memperoleh data kualitatif
yakni kelembagaan desa serta batas desa . Dimana disini samplingnya yaitu kepala desa lalu
turun lagi ke sekertaris desa lalu di arahkan ke kepala dusun . Hal ini dirasa yang lebih tau
kondisi warganya yakni kepala dusunnya . Untuk lingkup data data yang memang banyak
kami temukan informasinya pada Steakholder di dalam area balai desa itu sendiri .
LAPORAN AKHR STUDIO | 19
1.6 Diagram Alir
Aspek Data dan Informasi Analisa Output
Fisik Dasar - Curah hujan Analisis Fungsi Kawasan (SK Klasifikasi Fungsi Kawasan
- Kelerengan Metan No - Kawasan Budidaya
- Hidrologi - Kawasan Penyangga
- Jenis Tanah 837/KPTS/UM/11/1980) - Kawasan Lindung
Binaan - Penggunaan Analisis Lahan Sawah Di Lindungi Mengidentifikasi lahan sawah
lahan (Land Intensitas Pemanfaatan Ruang yang dilindungi
Use) Analisis Persebaran Fasilitas dan
Utilitas Mengidentifikasi KDB, KLB,
- Fasilitas dan KDH
- Utilitas Trend Penduduk
Komposisi Penduduk Mengidentifikasi persebaran
Kependudukan - Jumlah Penduduk Menurut Dusun Proyeksi Penduduk fasilitas dan utilitas
- Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir
Mengidentifikasi Aspek
- Jumlah Penduduk Menurut jenis kelamin Kependudukan
dan kelompok umur
- Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian
- Jumlah Penduduk Menurut Jenis Agama
Penduduk
Perekonomian - Mata Pencaharian Analisa Perekonomian Mengidentifikasi Aspek
- Komoditas Unggulan Perekonomian
Kegiatan/Aktivitas - UMKM
Masyarakat - BUMDes Analisa Pergerakan Penduduk Mengidentifikasi Aktivitas
Kebudayaan Msyarakat
- Pergerakan Pendidikan
Kelembagaan - Pergerakan Ekonomi Analisa Sosial Budaya Mengidentifikasi Aspek Sosial
- Pergerakan Mata Pencaharian Analisa Sosial Budaya Budaya
- Tradisi Mengidentifikasi Aspek Sosial
- Kesenian Budaya
- Struktur Organisasi Menyusun Laporan
- Jenis Organisasi Studio Proses
Gambar 1.5 Kerangka Berpikir
Sumber: Hasil Analisa 2021
LAPORAN AKHR STUDIO | 20
Tinjauan pustaka merupakan tahap penyusunan proposal studio proses
perencanaan. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berguna sebagai dasar yang akan
dipergunakan proses penyusunan laporan akhir studio proses perencanan. Tinjauan yang
kami lakukan memuat literatur yang berhubungan langsung dengan laporan yang akan kami
susun. Tinjauan pustaka ini meliputi teori-teori yang kami kumpulkan dari sumber-sumber
yang kami temukan. Berikut isi dari tinjauan pustaka yang berhasil kami susun berdasarkan
hasil temuan kami tentang teori-teori yang mendukung laporan kami dari proses hingga
akhir.
Ada beberapa muatan yang kami susun yang berhubungan dengan laporan ini,
diantaranya teori tentang perencanaan wilayah dan kota, teori desa dan kota serta
interaksinya, teori tentang klasifikasi desa, teori struktur ruang desa, teori infrastruktur
desa, teori kelembagaan desa, teori ekonomi desa, dan teori tentang potensi desa. Beberapa
teori tersebut merupakan hal dasar yang memuat informasi yang mendukung penyusunan
laporan yang kami susun. Teori-teori tersebut kami dapatkan dari beberapa sumber dan
literatur yang berhasil kami kumpulkan sehingga kami dapat menyusun tinjauan pustaka ini.
Berikut penjelasan tentang beberapa teori di dalam tinjauan pustaka ini
Teori yang pertama adalah teori tentang perencanaan wilayah dan kota , teori
ini adalah teori yang sangat erat hubungannya dengan laporan yang kami susun. Hal ini karena
laporan ini merupakan linkup dasar laporan Studi Proses ini mengenai dasar dari pengertian
perencanaan wilayah dan kota. Berikut adalah penjelasan mengenai teori Perencanaan
Wilayah dan Kota.
2.1 Teori perencanaan Wilayah dan Kota
Perencanaan didefinisikan sebagai proses persiapan, dilakukan pada awal
kegiatan, dilaksanakan berdasarkan cara yang sistematis, rekomendasi untuk kebijakan dan
tindakan, dengan perhatian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi.
Sebuah perencanaan diusahakan memenuhi kriteria yang baik karena mengingat kedudukan
sebuah perencanaan sangat penting untuk menentukan keberhasilan sebuah kegiatan.
Berikut beberapa teori Perencanaan Wilayah dan Kota dari beberapa ahli, 1
Menurut Friedmann (1987) dalam buku Aplikasi Teori Perencanaan dari Konsep
ke Realita Perencanaan selalu mengandung empat unsur utama , yaitu:
1. Perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial
ekonomi.
2. Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan.
3. Perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan
dan proses pengambilan keputusan.
4. Perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif
perencanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan serta menentukan
strategi apa yang digunakan. Maka sebuah perencanaan juga mencakup pemikiran
yang matang, dimana perlu cara-cara yang disesuaikan dengan situasi kondisi
1 Aplikasi Teori perencanaan: dari konsep ke Realita, Dr. S Djuni Prihatin , M.Si, Buana Grafika 2019
LAPORAN AKHR STUDIO | 21
serta memperkecil adanya masalah di kemudian hari. Perencanaan ini kemudian
diaplikasikan pada berbagai bidang dalam pembangunan termasuk perencanaan
wilayah dan kota. Perencanaan dengan pendekatan keruangan (spatial plan) pada
awalnya dipandang sebagai penerapan desain fisik pada lingkungan pemukiman
(Friedman, 1987; Taylor, 1998). Sedangkan Taylor (1998) memberikan hal yang
berbeda dalam menguraikan perencanaan perkotaan (urban planning) pada masa
awal perang dunia kedua dalam tiga komponen, yaitu:
a. Perencanaan kota sebagai perencanaan fisik. Hal ini dimaksudkan bahwa
dalam perencanaan wilayah dan kota selalu berkaitan dengan penataan fisik
baik infrastruktur maupun pemetaan ruang. Wilayah dan perkotaan sebagai
objek pemangunan menjadi bahan garapan yang diatur sedemikia rupa agar
menuju pemafaatan yang efisien.
b. Aspek desain adalah sentral pada perencanaan. Perencanaan wilayah dan
kota dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih nyaman dan aman. Oleh
karena itu suatu kota di desain sedemikian rupa dengan perencanaan yang
baik dan matang. Kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh kondisi
lingkungan yang menjadi tempat tinggal, maka sudah. Menjadi kewajiban
pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan
desain yang diciptakan dengan penuh perencanaan dan pertimbangan.
c. Perencanaan kota meliputi pembuatan master plan yang menunjukkan
ketepatan konfigurasi spasial penggunaan lahan dan bentuk kota yang
dihasilkan oleh arsitek atau insinyur ketika mendesain bangunan dan bentuk-
bentuk lain buatan manusia.
Menurut Teori lain, Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan
yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam
wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang
ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada
azas prioritas2. Maksud dari pembangunan yang lebih baik yaitu suatu perencanaan wilayah
dilakukan untuk memberi akses kepada masyarakat dalam megembanngkan kualitas
hidupnya dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur dan akses yang dibangun.
Perencanaan wilayah dan kota ini juga dimaksudkan. untuk memanfaatkan segala sumber
daya yang ada termasuk lingkungan secara menyeluruh dan memprioritaskan kepentingan
umum di masyarakat.
Teori yang kedua adalah teori tentang desa dan koa serta teori tentang interaksi
desa dan kota. Teori tentang desa merupakan sub utama yang dibahas dalam laporan studio
proses ini. Begitu juga dengan teori tentang kota, hal ini menjadi hal dasar yang di gunakan
untuk mengetahui pengertian baik desa maupun kota secara umum dan interaksi yang terjadi
antara desa dan kota. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai bagian ini :
2.2 Teori Desa dan Kota
Desa dan kota adalah dua wilayah dengan kondisi yang berbeda. Sebelum
membahas tentang interaksi desa dan kota, marilah kita pahami dulu pengertian desa dan
kota. Untuk membuat batasan yang tepat dan bersifat umum mengenai desa atau kota
tidaklah mudah. Banyak aspek yang dapat dimunculkan untuk memberikan batasan tentang
2 Riyadi dan Bratakusumah, 2003 dalam buku Aplikasi Teori Perencanaan dari Konsep ke Realita
LAPORAN AKHR STUDIO | 22
apa yang disebut desa dan kota. Desa dankota sama-sama merupakan tempat tinggal
penduduk sengan segala aktivitasnya. Desa dan kota bukan merupakan dua hal yang lahir
secara terpisah, dapat dikatakan bahwa kota merupakan perkembangan lanjut dari desa.
2.2.1 Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti
tanah air tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village
diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a countryarea, Smaller than atown”. Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.3
Didalam Penelitian Pola Keruangan desa dan kota ( Suparmi; 2012 ) batasan
pengertian desa menurut beberapa ahli memberi pengertian yang berbeda diantaranya,
Bintarto (1983:11-12) memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan
antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu
ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial,
ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga
dalam hunungannya dengan daerah lain. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan
penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Selain itu beliau juga
memberikan pengertian lain mengenai desa, R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat
dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan
lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi
yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang
saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah
penduduk.
Berbeda dengan V.C. Finch, memberikan konsep desa merupakan suatu tempat
tinggal dan bukan merupakan pusat perdagangan. Sedangkan C. Paul H. Landis memberikan
definisi desasebagai berikut, Untuk kepentingan statistik, desa adalah tempat tinggal
penduduk dengan jumlah kurang dari 2.500 orang. Untuk kajian psikologi sosial, desa adalah
daerah-daerah yang penduduknya ditandai dengan derajat keakraban/intimitas yang tinggi,
dan Untuk kajian ekonomi desa merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi mayoritas
agraris. Selain 3 pokok ttersebut Paul H. Landis juga memberikan definisi desa lebih lengkap
dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarkatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni
Sebagai berikut :
1. Pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat
dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan
pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
Roucek dan Waren jugaa mengemukakan ciri-ciri pedesaan sebagai berikut:
1. Masyarakat desa bersifat homogen, dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam
kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku
2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.
3 Peningkatan kapasitas desa berdasarkan pada undang-undang no. 6 tahun 2014 (sebuah kajian tentang
otonomi desa) oleh erni irawati universitas diponegoro
LAPORAN AKHR STUDIO | 23
3. Faktor geografis besar pengaruhnya terhadap kehidupan
4. Hubungan antara sesama anggota masyarakat lebih intim/akrab dari pada di kota.
Selain beberapa tokoh diatasi, N.Daldjoeni (2011:4), Desa dalam arti umum juga
dapat dikatakan sebagai Pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan pendudukaya
bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam dan H.A.W. Widjaja (2009:3)
juga memberikan pengertian lain tentang desa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah knekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 4
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota, adanya homogenitas
pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencaharian yaitu mayoritas agraris, nilai
kebudayaan maupun tingkah laku,hubunganantar penduduk yang akrab.
2.2.2 Kota
Pembahasan kedua setelah desa adalah kota. Secara umum kota adalah tempat
dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan
kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas penduduknya . Sedangkan
menurut bahasa, Kota berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan dan
perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam artian fisik , sosial,
ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan
kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah Kota.
Didalam Penelitian Pola Keruangan desa dan kota ( Suparmi; 2012 )batasan
pengertian kota menurut beberapa ahli memberi pengertian yang berbeda diantaranya,5
1. Bintarto (1983:36) menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu
sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk
yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan
coraknya yang materialistis. Hal menonjol yang membedakan desa dengan kota
adalah desa merupakan masyarakat agraris, sedang kota nonagraris.
2. Wirth, kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat dan permanen,
dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya
3. Max Weber, kota adalah sustu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat
dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.
4. P.J.M.Nas, kota dapat dilihat dari berbagai segi,
a. Dari segi morfologi kota, adanya cara membangun dan bentuk fisik
bangunan yang berjejal-jejal
d. Dari segi ekonomi, merupakan daerah bukan agraris. Fungsi kota yag khas
adalah kegiatan budaya, industri, perdagangan dan niaga, serta kegiatan
pemerintahan
e. Dari segi sosial, bersifat kosmopolitan, hubungan sosial impersonal, sepintas
lalu, terkotak-kotak.
4 Modul Pola Keruangan Desa dan Kota, Suparmi, 2012
5 Modul Pola Keruangan Desa dan Kota, Suparmi, 2012
LAPORAN AKHR STUDIO | 24
Selain beberapa pendapat di atas, Kota juga bisa disebut sebagai pemukiman yang
relatif besar, pa`dat dan permanent, dihuni oleh orang-orang yang hetrogen kedudukan
sosialnya (Louis wirth) dalam Khairudin, 1992: 4-5).
Setelah membahas mengenai desa dan kota, berikut akan dijelaskan tentang
aspek-aspek yang ada di desa dan kota khususnya aspek-aspek yang ada di desa. Aspek-aspek
tersebut merupakan hal yang paling pokok dan dasar dalam setiap perencanaan yang
dilakukan. Didalam laporan ini juga akan di bahas mengenai aspek aspek tersebut yang terdiri
dari 7 aspek pembahasan.
2.3 Teori klasifikasi desa
Klasifikasi desa menurut perkembangannya menngutip dari Modul Geografi yang
berjudul Interaksi Keruangan Desa dan Kota (2019) terbitan Kemdikbud, terdapat 4
klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Berikut beberapa penjelasan
mengenai klasifikasi tentang desa :
1. Desa tradisional atau pra-desa
Tipe desa ini bercirikan pada masyarakatnya yang masih terasing dari kehidupan
luar dan sepenuhnya bergantung pada alam di sekitar lingkungan sekitar mereka. Adapun
ketergantungan itu terlihat dari cara bercocok tanam, memenuhi kebutuhan pangan,
membuat tempat tinggal dan mengolah makanan, serta lain sebagainya. Penduduk desa tipe
ini cenderung tertutup dan komunikasinya dengan masyarakat di luar daerahnya minim.
2. Swadaya
Merupakan desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan
juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya.
Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan
miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
3. Desa Swakarsa
Merupakan desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik
dannonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangansumber keuangan atau dana. Desa
swakarsa belumbanyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah
peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang
berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja
serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
4. Desa swasembada
Merupakan desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga
dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi
fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang
modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana
yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.6
6 Modul Pola Keruangan Desa dan Kota, Suparmi, 2012
LAPORAN AKHR STUDIO | 25
2.4 Fisik Dasar
2.4.1 Iklim
Perubahan iklim menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam penataan
ruang dikarenakan perubahan iklim mempunyai dampak yang sangat besar terhadap
kehidupan seluruh makhluk hidup. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015) dalam
kompas.com dijelaskan bahwa iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode
waktu yang lama. Dengan mengetahui iklim, manusia bisa menentukan tanaman apa yang
harus dibudidayakan sebagai bahan pangan. Berkat iklim juga kita bisa bersiap untuk bencana
alam, maupun memilih destinasi berlibur.Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi.
Klimatologi mempelajari kecenderungan cuaca di suatu wilayah. Para peneliti klimatologi
memantau curah hujan, suhu, dan kecepatan angin.7
Didalam buku Klimatologi Pertanian karya Gunardi Djoko Winarno dkk beliau
menyebutkan bahwa Iklim adalah keadaan rata – rata cuaca disuatu daerah dalam jangka
lama dan tetap. Definisi lain, iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah,
dan bukan hanya merupakan cuaca rata – rata (Wirjomiharjo dan Swarinoto, 2007). Iklim
merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin,
kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang dengan
penyelidikan dalam waktu yang lama minimalnya 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas.
Iklim adalah kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang
lama, sehingga disebut sebagai rata-rata dari unsur cuaca secara umum. Iklim bersifat stabil
bila dibandingkan dengan cuaca. Perubahan iklim berlangsung dalam periode yang lama dan
meliputi area yang sangat luas. Matahari merupakan kendali utama sistem iklim.8
Iklim yaitu rata-rata cuaca dalam waktu yang lama (dalam kurun waktu 25-30
tahun) dan dalam tempat yang relatif luas. Sedangkan cuaca merupakan segala fenomena
yang terjadi di lapisan troposfer dalam waktu singkat dan tempat yang sempit. Ilmu yang
mempeajari tentang iklim disebut klimatologi dan cuaca disebut meteorology. Badan resmi
yang mengurus informasi iklim dan cuaca adalah BMKG (Badan Metorologi Klimatologi dan
Geofisika).9
Dengan kemajuan teknologi, proses identifikasi iklim wilayah telah
dipadupadankan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga data-data zona iklim dapat
ditampilkan dalam bentuk keruangan berupa zona-zona tipe iklim wilayah. Hal itu dilakukan
untuk mempermudah pembacaan dan penginterpretasian data-data tersebut. Selain itu
menurut Federal Geographic Data Committee (2003) pemanfaatan SIG didasarkan pada
analisis keputusan yang membutuhkan sistem referensi geografi dunia nyata terlalu kompleks
untuk dikembangkan sehingga harus disederhanakan. Penyederhanaan ini dalam bentuk
pemetaan suatu wilayah dimana data spasial dan informasi atribut diintregasikan dengan
berbagai tipe data dalam suatu analisis.10
7 https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/31/060000169/pengertian-iklim-dan-jenisnya?page=all
8 Klimatologi Pertanian karya Gunardi Djoko Winarno dkk
9 Jurnal Sumberdaya Alam & Lingkungan, Analisis Spasial Penentuan Iklim Menurut Klasifikasi Schmidt-
Ferguson dan Oldeman di Kabupaten Ponorogo, Retnoe Ayu Sasmito dkk,
LAPORAN AKHR STUDIO | 26
2.4.2 Curah Hujan
Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama
periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan
horizontal. Hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam
tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir (Suroso 2006).11
2.4.3 Kelerengan
Kemiringan lahan adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada
suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan
dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. Panjang satu garis menunjukkan
kelerengan yang sama. Kemiringan lahan menunjukkan karakter daerah yang harus
dipertimbangkan dalam arahan penggunaan lahan. Kemiringan lahan tiap daerah berbeda-
beda tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Kemiringan lahan
dipengaruhi oleh ketinggian lahan terhadap laut karena semakin dekat dengan laut cenderung
semakin rata12
2.4.4 Hidrologi
Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian hidrologi. Menurut Asdak
(1995), hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya (cairan, gas,
padat) pada, dalam, dan di atas permukaan tanah. Sedangkan Arsyad (2009) berpendapat
bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari proses penambahan, penampungan, dan
kehilangan air di bumi. Singh (1992), menjelaskan pengertian hidrologi adalah ilmu yang
membahas karakteristik kuantitas dan kualitas air di bumi menurut ruang serta waktu,
termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi,
pengembangan maupun manajemen13.
2.4.5 Jenis Tanah
Berdasarkan bahan dan proses pembentukannya tanah dibedakan menjadi
beberapa jenis antara lain tanah aluvial/endapan, tanah humus, tanah kapur, tanah vulkanik,
dan tanah gambut. Tanah aluvial merupakan tanah yang terdapat di sepanjang aliran sungai,
terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Sifat tanah ini sangat dipengaruhi
oleh meterial yang dikandung oleh sungai yang melaluinya. Tanah aluvial cocok untuk
pertanian karena memiliki tekstur yang lembut dan mudah digarap.
Tanah humus berasal dari pelapukan ranting, daun, dan bagian tumbuhan lainnya.
Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak sehingga tingkat kesuburannya sangat
tinggi. Ciri yang dimiliki tanah humus adalah berwarna gelap (antara cokelat tua sampai
warna hitam) dan tampak bintik berwarna putih dalam tanah itu.
Berbeda dengan tanah humus, tanah kapur tidak memiliki unsur hara sehingga
tanah ini bersifat tidak subur. Hal ini terjadi karena tanah kapur berasal dari pelapukan
batuan kapur yang tidak mengandung unsur hara. Lapisan tanah di atas kapur umumnya tipis
sekali dan memiliki sifat kurang dapat menyerap atau menampung air. Tanah pasir
merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan pasir. Biasanya , tanah ini banyak kita
11 https://foresteract.com/curah-hujan/
12 Sinery, Rudolf, Hermanus, Samsul, dan Devi, 2019
13 http://repository.lppm.unila.ac.id/26780/1/PENGANTAR%20HIDROLOGI.pdf
LAPORAN AKHR STUDIO | 27
jumpai di pantai atau daerah kepulauan. Tanah pasir sangat mudah dilalui air atau bersifat
porous, tidak mengandung air dan mineral sehingga kurang baik untuk pertanian. Tanah
vulkanik adalah tanah yang berasal dari muntahan gunung berapi
Tanah organosol atau tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari bahan
induk berupa bahan organik hutan atau rumput-rumputan yang mengalami pelapukan. Unsur
hara yang terkandung di dalam tanah gambut sangat sedikit, sehingga tanahnya kurang subur
dan kurang baik untuk lahan pertanian. Tanah gambut juga relatif kurang baik untuk dijadikan
perkebunan karena memiliki kandungan asam yang tinggi. Untuk menetralkannya biasanya
diberi kapur. Tanah laterit terbentuk karena unsur hara hilang dalam tanah akibat erosi,
terkena hujan terus menerus. Tanah ini memiliki warna merah bata karena banyak
mengandung zat besi dan alumunium, sehingga kurang cocok untuk ditanami.14
2.5 Fisik Binaan
2.5.1 Struktur Ruang Desa
Di dalam buku modul pola keruangan desa dan kota oleh Suparmi : 2012 ,
Struktur ruang desa terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu penggunaan lahan dan pola
permukiman desa. Berikut merupakan pembahasan dari kedua hal pokok tersebut :
2.5.1.1 Penggunaan Lahan Desa
Menurut Wibberley dalam JoharaT.Jayadinata(1999:61) wilayah perdesaan
menunjukkan bagian suatu negeri yang memeperlihatkan penggunaan lahan yang luas sebagai
ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau. Lahan di
perdesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. Kehidupan
sosial seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolah raga dan sebagainya.
Kegiatan itu biasanya dilakukan di dalam perkampungan.Lahan yang ada juga dimanfaatkan
untuk kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan ekonomi bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan yang pada umumnya dilakukan di
luar kampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa lahan di wilayah perdesaan adalah untuk
permukiman dalam rangka kehidupan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan
ekonomi.
2.5.1.1.1 Pertanian Lahan Basah
Lahan basah adalah wilayah tanah pertanian yang jenuh dengan air baik bersifat
musiman maupun permanen. Lahan basah biasanya tergenangi oleh lapisan air dangkal. Lahan
basah mempunyai manfaat mencegah genangan air berlebih (banjir, abrasi, dll), membantu
manusia dalam air minum, irigasi, dan sebagainya serta dapat digunakan untuk bahan
pembelajaran dan penelitian. Contoh dari lahan basah adalah Sawah, Rawa, Hutan mangrove,
Terumbu karang, Padang lamun, danau dan sungai.15
2.5.1.1.2 Pertanian Lahan Kering
Lahan kering merupakan jenis pertanian yang dilakukan pada sebuah lahan yang
kering, yaitu lahan yang memilki kandungan air yang rendah, bahkan ekstrimnya adalah lahan
kering ini merupakan jenis lahan yang cenderung gersang, dan tidak memiliki sumber air yang
14 https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Tanah%20dan%20Kehidupan_IK/Jenis-tanah.html
15 Sistem Pakar Pemilihan Tanaman Pertanian Untuk Lahan Kering Penulis : Heliza Rahmania Hatta Septya
Maharani Zainal Arifin Malik Annisa Dyna Marisa Khairina Ramadiani ISBN : 978-602-6834-683 ©2018.
Mulawarman University Press Edisi : September 2018
LAPORAN AKHR STUDIO | 28
pasti, seprti sungai, danau ataupun saluran irigasi. Lahan kering hanya mengharapkan dari
curah hujan. Lahan kering itu sendiri tergolong kepada jenis lahan suboptimal yang
didefinisikan sebagai lahan yang kurang dapat mendukung produksi pangan karena
kekurangan satu atau lebih unsur atau komponen pendukungnya.16
2.5.1.1.3 Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik
dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam
penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka
terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH),
adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang
tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa
badan air. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang
perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka
hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.17
2.5.1.1.4 Hutan
Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dinilai dari peranan dan manfaatnya bagi
kehidupan manusia. Hutan berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi hutan lindung,
konservasi, dan produksi. Pengertian hutan adalah bentuk kehidupan berupa kawasan yang
ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kumpulan pepohonan dan tumbuhan
yang ada, mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas.
Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi dan berfungsi sebagai penyangga
kehidupan. Fungsinya untuk melindungi suatu daerah atau wilayah dari bencana alam, seperti
tanah longsor, kekeringan, banjir dan bencana ekologis lainnya. Hutan lindung juga dijadikan
sebagai pelindung daerah aliran sungai (DAS).
Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi sebagai cadangan kebutuhan
pengawetan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hutan konservasi dikelompokkan
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kawasan suaka alam dan kelompok kawasan
pelestarian alam. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk
menghasilkan atau dieksploitasi hasil hutannya. Contohnya adalah Hak Pengusahaan Hutan
(HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), serta jenis hutan untuk kepentingan produksi lainnya
yang dapat menghasilkan berbagai jenis kayu dan non kayu.18
2.5.1.1.5 Permukiman Desa
Persebaran dan pemusatan penduduk desa dapat dipengaruhi oleh keadaan
tanah, tata air, topografi dan ketersediaan sumberdaya alam yang terdapat di desa yang
16 Sistem Pakar Pemilihan Tanaman Pertanian Untuk Lahan Kering Penulis : Heliza Rahmania Hatta Septya
Maharani Zainal Arifin Malik Annisa Dyna Marisa Khairina Ramadiani ISBN : 978-602-6834-683 ©2018.
Mulawarman University Press Edisi : September 2018
17 https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau
18 https://rimbakita.com/hutan-produksi/
LAPORAN AKHR STUDIO | 29
bersangkutan. Pola persebaran permukiman desa dalam hubungannya dengan bentang
alamnya, dapat dibedakan atas:
1. Pola Terpusat
Bentuk permukiman terpusat merupakan bentuk permukiman yang
mengelompok (aglomerated, compact rural settlement). Pola seperti ini banyak
dijumpai didaerah yang memiliki tanah subur, daerah dengan relief sama,
misalnya dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk bertempat tinggal.
Banyak pula dijumpai di daerah dengan permukaan air tanah yang dalam, sehingga
ketersediaan sumber air juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap
bentuk pola permukiman ini.
2. Pola tersebar atau terpencar
Bentuk permukiman tersebar, merupakan bentuk permukiman yang terpencar,
menyebar di daerah pertaniannya (farm stead), merupakan rumah petani yang
terpisah tetapi lengkap dengan fasilitas pertanian seperti gudang mesin pertanian,
penggilingan, kandang ternak,penyimpanan hasil panen dan sebagainya. Bentuk
ini jarang ditemui di Indonesia, umumnya terdapat di negara yang pertaniannya
sudah maju.Namun demikian, di daerah-daerah dengan kondisi geografis
tertentu, bentuk ini dapat dijumpai, misalnya daerah banjir yang memisahkan
permukiman satu sama lain,daerah dengan topografi kasar, sehingga rumah
penduduk tersebar, serta daerah yang kondisi air tanah dangkal sehingga
memungkinkan rumah penduduk dapat didirikan secara bebas.
3. Pola memanjang atau linier
Pola memanjang memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang di kiri
kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi, atau mengikuti
garis pantai. Bentuk permukiman seperti ini dapat dijumpai di dataran rendah.
Pola atau bentuk ini terbentuk karena penduduk bermaksud mendekati
prasarana transportasi, atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti
nelayan di sepanjang pinggiran pantai.
4. Pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu
Bentuk permukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran
rendah, yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan
penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan seharihari, misalnya mata air,
waduk dan fasilitas lainnya.
Selain itu menurut pendapat lain, Landis mengemukakan empat tipe pola
permukiman desa sebagai berikut :
1. Farm village type
Merupakan satu desa dimana penduduk bersama dalam satu tempat dengan
sawah ladang berada di sekitarnya. Desa seperti ini banyak terdapat di Asia
Tenggara, juga di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Di sini tradisi masih
dipegang kuat oleh masyarakatnya, demikian pula dengan ke gotong royongan
yang masih cukup kuat. Tetapi hubungan antar individu dalam proses produksi
usaha tani sudah bersifat komersial karena masuknya revolusi hijau yang
merupakan teknologi pertanian modern. Di samping itu desa yang berdekatan
dengan daerah perkotaan akan mengalami gangguan sebagai akibat perluasan
LAPORAN AKHR STUDIO | 30
kota.Gangguan yang dimaksud adalah terjadinya alih fungsi lahan produktif untuk
permukiman, kantor pemerintah, swasta dan sebagainya.Semua ini merupakan
kondisi objektif yang tidak terelakkan, sehingga akan mempengaruhi kegotong
royongan, ketaatan pada tradisi yang sebelumnya masih dipegang kuat oleh
masyarakat desa yang bersangkutan.
2. Nebulous farm village type
Merupakan desa dimana sejumlah penduduk berdiam bersama dalam suatu
tempat, sebagian lainnya menyebar di luar tempat tersebut, di antara sawah
ladang mereka. Di Indonesia banyak terdapat di Sulawesi, Maluku,
Papua,Kalimantan dan sebagian Pulau Jawa terutama di daearh-daerah dengan
sistem pertanian tidak tetap atau perladangan berpindah. Tradisi dan gotong
royong serta kolektivitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat ini.
3. Arranged isolated farm type
Suatu desa diamana penduduk berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan
dengan trade center dan selebihnya adalah sawah ladang mereka, tipe ini banyak
ditemui di negara barat. Tradisi kurang kuat, sifat individu lebih menonjol, lebih
berorientasi pada bidang perdagangan.
4. Pure isolated farm type
Tempat tinggal penduduk tersebar bersama sawah ladang masing-masing, banyak
dijumpai di negara Barat. Tradisi, dinamika pertumbuhan, orientasi perdagangan,
sifat individualistik sama dengan desa sebelumnya.
Sedangkan menurut pendapat Everett M.Roger dan Rabel J.Burge (1972)
mengelompokkan pola permukiman sebagai berikut:
1. The scattered farmstead community
Sebagian penduduk berdiam di pusat pelayanan yang ada, sedang yang lain
terpencar bersama sawah ladang mereka. Tipe ini sama dengan nebulous farm
village type.
2. Cluster village
Penduduk berdiam terpusat di suatu tempat, dan selebihnya adalah sawah ladang
mereka
3. The Line Village
Dari beberapa pendapat diatas bentuk pola permukiman penduduk di berbagai
wilayah bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat,
ketersediaan pusat pelayanan serta jalur transportasi yang ada. Bentuk pola
permukiman di pegunungan akan berbeda dengan yang ada di dataran, berbeda
pula dengan bentuk yang ada di sekitar jalan raya. Bentuk permukiman penduduk
di perdesaan pada prinsipnya mengikuti pola persebaran desa, yang dapat
dibedakan atas permukiman mengelompok atau memusat, permukiman
terpencar, permukiman linier dan permukiman mengelilingi fasilitas tertentu.19
19 Modul Pola Keruangan Desa dan Kota, Suparmi, 2012
LAPORAN AKHR STUDIO | 31
2.5.2 Fasilitas
Menurut ahli Suryo Subroto, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat
memberikan kemudahan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha, bisa berupa benda
ataupun uang. Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa fasilitas adalah semua hal yang dapat
mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan
tertentu20
2.5.2.1 Fasilitas Industri
Menurut G. Kartasapoetra (1987) “Industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi
barang yang bernilai tinggi”. Definisi lain menyatakan industri adalah sebagai suatu untuk
memproduksi barang jadi melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang
tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi
mungkin (Sade, 1985). Menurut Abdurachmat dan Maryani (1998: 27) Industri merupakan
salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting.Ia mengasilkan berbagai kebutuhan hidup
manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sampai
perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.21
2.5.2.2 Fasilitas Perdagangan Jasa
Perdagangan menurut Mayana (2004) adalah sektor jasa yang menunjang
kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat dan antarbangsa, sedangkan menurut Ahman
dan Indriani (2007) perdagangan adalah kegiatan tukar - menukar atau transaksi jual beli
antara dua pihak atau lebih. Menurut Utoyo (2004) perdagangan merupakan proses tukar
menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. kegiatan sosial ini muncul
karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Secara keseluruhan
perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang atau
memproduksi barang untuk menjual barang itu dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan. Jasa menurut Kotler dan Keller (2016) adalah setiap tindakan atau kinerja yang
dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, tidak berwujud dan mengakibatkan
kepemilikan sesuatu. Produksinya tidak selalu menghasilkan bentuk fisik. Sedangkan menurut
Buchary Alma (2012) jasa adalah sesuatu yang 23 dapat diidentifikasi secara terpisah, tidak
berwujud dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan
menggunakan benda-benada berwujud atau tidak. Dalam hal ini jasa sangat memegang peran
penting karena merupakan mata rantai dari seluruh sektor perekonomian dan berhubungan
dengan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan jasa merupakan sumber penting bagi
pertumbuhan atas dasar peningkatan produktifitas, karena sektor ini menyerap tenaga kerja
paling banyak. Kedua sektor perdagangan dan jasa memiliki keterkaitan karena nilai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sejalan.22
2.5.2.3 Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada masyarakat untuk
upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang sifatnya promotif, preventif dan juga
rehabilitatif. Beberapa contoh fasilitas kesehatan yaitu puskesmas, RSUD, apotek, layanan
BPJS, rumah sakit, posyandu dan lain sebagainya.
20 https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/fasilitas/
21 http://repository.uin-suska.ac.id/4150/3/BAB%20II.pdf
22 https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2487/8/UNIKOM_LUSIA%20ELSA%20DIKA%20DAMAYANTY_BAB%20II.pdf
LAPORAN AKHR STUDIO | 32
2.5.2.4 Fasilitas Sekolah
Fasilitas sekolah merupakan segala hal yang bisa digunakan oleh pengelola
pendidikan seperti guru, kepala sekolah, murid serta staf dalam proses pendidikan. Biasanya
juga bisa digambarkan berupa sarana dan prasarana yang ada di sekolah.Beberapa contoh
fasilitas sekolah yaitu meja belajar, ruang kelas, ruang laboratorium, kursi sekolah, lapangan,
ruang guru, perpustakaan, tempat parkir dan lain sebagainya.
2.5.2.5 Fasilitas Peribadatan
Fasilitas untuk ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama
secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Di dalam sebuah perumahan, fasilitas
ibadah adalah bagian dari sarana atau fasilitas umum (fasum). Semua bangunan yang menjadi
fasilitas ibadah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan batin manusia sebagai makhluk yang
memiliki Tuhan. Bentuk bangunan fasilitas ibadah sendiri disesuaikan dengan agama yang
dianut, yaitu:
1. Masjid untuk ibadah bagi umat beragama Islam.
2. Gereja untuk ibadah bagi umat beragama Katolik dan Kristen.
3. Kelenteng untuk ibadah bagi umat Khonghucu.
4. Pura untuk ibadah bagi umat Hindu.
5. Vihara untuk ibadah bagi umat Budha.
2.5.2.6 Fasilitas Persampahan
Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegitan rumah tangga, pasar,
perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan dan besi tua
bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang
sudah terpakai (Sucipto, 2012). Menurut Subekti, 2009 dalam (Alfiandra, 2009) bahwa
Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik yang dianggap tidak
berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi
investasi pembangunan.
Fasilitas persampahan di sini mengandung arti suatu aktifitas ataupun materi yang
berfungsi melayani kebutuhan pengelolaan masalah sampah yang meliputi, pewadahan,
pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir sampah, sehingga secara tidak langsung
adalah bagaimana peran pemerintah mengatasi pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan
fasilitas pembuangan sampah yang diberikan oleh/kepada masyarakat sekitar agar sampah
tersebut tidak menjadi limbah dan tercemar seperti membuang sampah yang tidak pada
tempatnya.23
2.5.2.7 Fasilitas Perkantoran Dan Pelayanan Umum
Fasilitas Pemerintahan & Layanan Publik adalah segala bentuk pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seluruh
bagian pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib mendukung
adanya fasilitas ini secara merata di setiap daerah.
Pemberian layanan ini dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuknya bermacam-macam, yang paling
penting pelayanan erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga,
23 https://media.neliti.com/media/publications/150700-ID-analisis-proyeksi-pertumbuhan-penduduk-d.pdf
LAPORAN AKHR STUDIO | 33
KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi. Adapun karakteristik
dari fasilitas pemerintahan dan layanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara (2003), di
antaranya:24
1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.
2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang
ingin dicapai.
3. Dituntut untuk akuntabel kepada publik.
4. Memiliki tujuan sosial.
5. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan.
6. Seringkali menjadi sasaran isu politik.
2.5.3 Utilitas
2.5.3.1 Saluran listrik udara
Sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga
listrik untuk menghantarkan listrik ke tempat yang jauh. Saluran dapat terdiri dari satu atau
lebih konduktor (umumnya kelipatan tiga) yang dipasang di menara atau tiang. Karena
sebagian besar insulasi disediakan oleh udara, maka saluran listrik udara umumnya
merupakan metode termurah untuk mentransmisikan listrik dalam jumlah besar25. Saluran
listrik udara dibedakan berdasarkan tegangan listrik yang dihantarnya, yakni:
1. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) – kurang dari 1000 volt, digunakan untuk
distribusi listrik antar permukiman.
2. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) – antara 1000 volt (1 kV) dan 69 kV,
digunakan untuk distribusi listrik antar kawasan.
3. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) - antara 70 kV hingga 150 kV, digunakan
untuk transmisi listrik antar wilayah.
4. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) – antara 275 kV hingga 800
kV,[2] digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh.
2.5.3.2 Infrastruktur Desa
Secara umum Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan
transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas public yang lain
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan
ekonomi .26
Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan
sistem ekonomi dalam kehidupam sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat
didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau strukturstruktur dasar, peralatan-peralatan,
instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan
sistem ekonomi masyarakat. (Grigg,2000) (Moteff 2003 dalam NSS Prapti, Suryawardana, &
Triyani, 2015) mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang
ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Vaughn and pollard
24 https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/fasilitas-pemerintahan-dan-layanan-publik/
25 https://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_listrik_udara
26 Grigg,1988) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015)
LAPORAN AKHR STUDIO | 34
(2003) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015), menyatakan infrastruktur secara
umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, Bandar udara, pelabuhan,
bangunan umum, dan juga termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi,
pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah dan telekomunikasi.
Menurut Green dan Haines (dalam Adi, 2013;240) infrastruktur dapat berupa jalan raya,
jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon,
dan lain sebagainya.
2.5.3.3 Jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa
jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting
terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang,
pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam
rangka mewujudkan pembangunan nasional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
dijelaskan bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat
jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-
pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan
jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut
fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan
kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan
nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan
prinsip-prinsip otonomi daerah.
2.5.3.3.1 Sistem Jaringan Jalan
Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah
dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan
perkotaan, dan kawasan perdesaan. Berdasarkan sistem jaringan jalan, maka dikenal 2 istilah,
yaitu :
1. Sistem jaringan jalan primer
Jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan
distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai
berikut:
a. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah,
pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan.
b. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang
menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran
perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan
dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder
LAPORAN AKHR STUDIO | 35
Jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan
perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer,
fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya
sampai ke persil.
Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang
menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai
dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.
2.5.3.3.2 Fungsi Jalan
Berdasarkan fungsinya, maka jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu :
1. Jalan Arteri
Arteri Primer : Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Didesain
berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam, lebar badan jalan minimal 11
meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan
kegiatan lokal, jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi, serta tidak boleh terputus
di kawasan perkotaan.
Arteri Sekunder : Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan
sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekuder kesatu, atau kawasan
kawasan sekuder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Didesain berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 30 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 11 meter, dan lalu
lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
2. Jalan Kolektor
Kolektor Primer : Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Didesain berdasarkan berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan jumlah
jalan masuk dibatasi.
Kolektor Sekunder : Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder
ketiga. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar
badan jalan minimal 9 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas
lambat.
3. Jalan Lokal
Lokal Primer : Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan
nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan
lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana
paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter, dan tidak boleh
terputus.
Lokal Sekunder : Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, kawasan sekunder kedua #
LAPORAN AKHR STUDIO | 36
dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan
lebar badan jalan minimal 7,5 meter.
4. Jalan Lingkungan
Lingkungan Primer : Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam
kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter
untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan
yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai
lebar badan jalan minimal 3,5 meter.
Lingkungan Sekunder : Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan
perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan
lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi
kendaraanbermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi
kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5
meter.
Lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter ini dimaksudkan agar lebar jalur lalu
lintas dapat mencapai 3 meter, dengan demikian pada keadaan darurat dapat dilewati mobil
dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadan kebakaran, ambulan, dan sebagainya.
2.5.3.3.3 Bagian Jalan
Dilansir dari dpukulonprogo.go.id, jalan merupakan tempat yang digunakan
untuk lalu lintas kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Selain itu,
jalan seharusnya memiliki fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan pejalan kaki seperti
trotoar, jembatan penyeberangan orang, zebra/pelican cross dan lain-lain. Menurut PP No.
34 Tahun 2006 Tentang Jalan, jalan memiliki bagian-bagian yang diberi nama ruang manfaat
jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)27
Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan
dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya Badan jalan
meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur
pejalan kaki Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang. Manfaat jalan,
dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang
masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan
yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara
lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang Ruang milik
jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter.
2. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter,
3. jalan sedang 15 (lima belas) meter, dan d jalan kecil 11 (sebelas) meter
Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik
jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan
pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak
27 dpukulonprogo.go.id
LAPORAN AKHR STUDIO | 37
mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang
pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ruang milik jalan tidak
cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan.
2.5.3.3.4 Jenis Perkerasan Jalan
Berdasarkan keterangan yang di ambil dari Perencanaan Perkerasan Jalan oleh
Siti Asiyah MT. Teknil Sipil Universitas Sulta Ageng Tirtayasa, beliau menulis definisi dan
teori tentang perkerasan jalan serta jenis karakteristik Perkerasan Jalan sebagai berikut,
1. Definisi perkerasan jalan
PerkerasanJalan adalahsatuataubeberapa bahanlapisyang dipadatkan di atas tanah dasar
dengan maksud agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar tanpa terhambat.
2. Fungsi perkerasan jalan
Fungsi perkerasan jalan: mengusahakan agara tanah dasar lebih tahan terhadap
beban lalu lintas dan cuaca sedemikian rupa sehingga usaha pemeliharaan mampu
mempertahankan permukaan untuk tetap dalam kondisi layak untuk dilewati.
Jenis – jenis perkerasan jalan yaitu:
3. Perkerasan Fleksibel (Kerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya)
Konstruksi perkerasan lentur (Perkerasan Fleksibel) yaitu perkerasan yang
menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. lapisan-lapisan perkerasan
bersifat dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.
4. Perkerasan Kaku (kerasan yang menggunakan air mani (Semen Portland) sebagai bahan
pengikatnya)
Konstruksi perkerasan kaku(Perkerasan Kaku) yaitu perkerasan yang
menggunakan semen (Portland Cement) sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton
dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis
pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton.
5. Komposit Pavement (perekrasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur).
Konstruksi perkerasan komposit (Perkerasan Komposit) yaitu perkerasan kaku
yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan
fleksibel diatas perkerasan kaku atau perkerasan kaku diatas perkerasan lentur28
2.6 Kependudukan
Didalam buku Ilmu Kependudukan Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH dijelaskan
beberapa definisi dari teori kependudukan, Definisi demografi berdasarkan Multilingual
Demographic Dictionary (IUSSP, 1982) adalah "Demography is the scientific study of human
populations in primarly with the respect to their size, their structure (compotition) and their
development (change)" dalam bahasa Indonesia berarti ilmu sains yang mempelajari penduduk
(suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi) penduduk dan
perkembangannya (perubahannya).29
28 https://www.academia.edu/38469942/materi_1_jenis_jenis_perkerasan_jalan_pdf
29 Ilmu Kependudukan, Lucky Radita Alma, Wineka Media, 2019
LAPORAN AKHR STUDIO | 38
Philip M. Hauser dan Dudley Ducan (1959) menyebutkan bahwa "Demography
is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there
in and the components of such changes which maybe identified as natality, territorial
movement (migration), and social mobility (change of states)" yang menyebutkan bahwa
demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan
komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya
timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan
status).
Mantra (2003) menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses
penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi
penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan
karena proses demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi
penduduk (Mantra, 2003). Berdasarkan teori ini berikut akan dijelaskan tentang beberapa
struktur dan komposisi Penduduk sesuai dengan mantra ( 2003
2.6.1 Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk
Pada dasarnya penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun
kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu
tahun. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja,
tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan
ekonomi. pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk. Didalam jumlah
penduduk terdapat beberapa pokok bahasan , berikut akan dijelaskan beberapa pokok
tersebut :30
2.6.2 Kelompok Umur
Berdasarkan BPS Jumlah Penduduk menurut kelompok umur (interval 5
tahunan) dan jenis kelamin : Jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu jumlah
penduduk sebelum mencapai usia genap 5 tahun. Kelompok umur ini sering disebut balita
(bawah lima tahun). Penyebutan satuan tahun pada umur penduduk dilakukan dengan
pembulatan ke bawah.
2.6.3 Jenis Kelamin
Berdasarkan BPS jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan
perempuan. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan
genetik.
2.6.4 Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah
tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil
diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.
30 Bambang utoyo , Geografi membuka cakrawala dunia untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas
/Madarasah Aliyah Program IImu Pengetahuan Sosial.PT Setia Purna .h.26.
LAPORAN AKHR STUDIO | 39
Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas
tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.
2.6.5 Agama
Penduduk Menurut Agama adalah Informasi tentang jumlah penduduk
berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana
peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan
antar umat beragama.
2.6.6 Mata pencaharian
Berdasarkan BPS mata pencaharian adalah macam kegiatan pekerjaan atau
aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang termasuk dalam golongan bekerja, sedang
mencari pekerjaan, dan pernah bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan, dalam
upaya memenuhi kebutuhan hidup selama minimal seminggu sebelum waktu pencatatan
data.
2.6.7 Piramida Penduduk
Piramida Penduduk merupakan sebuah grafik komposisi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin yang digambarkan secara visual. Berdasarkan komposisi penduduk
menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu negara dapat dibedakan
menjadi tiga kelompoka :31
1. Ekspansif
Jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini
terdapat pada negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat
akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran dan sudah mulai menurunya tingkat
kematian. Negara-negara yang termasuk dalam tipe ini adalah Indonesia,
Malaysia, Philipina, India dan Costa Rica.
2. Konstruktif
Jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini
terdapat pada negara-negara yang tingkat kelahiran turun dengan cepat, dan
tingkat kematiannya rendah. Negara-negara yang termasuk dalam tipe ini adalah
Jepang, dan negara-negara di Eropa Barat, misalnya Swedia.
3. Stasioner
Jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada
kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang memiliki
tingkat kematian dan kelahiran rendah, misalnya Jerman.
2.6.8 Persebaran Penduduk
Mengutip Kemdikbud RI, distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk
penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau
tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk.
31 Ilmu Kependudukan, Lucky Radita Alma, Wineka Media, 2019
LAPORAN AKHR STUDIO | 40
2.6.8.1 Kepadatan
Berdasarka BPS Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan
luas.Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program
transmigrasi.Kepadatan penduduk kasar atau Crude Population Density (CPD) menunjukkan
jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud
adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi.
2.6.8.2 Pertumbuhan
Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah terjadi disebabkan oleh beberapa
faktor kependudukan, diantaranya adalah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan
juga adanya migrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang
dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi
jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh bertambahnya
jumlah kelahiran bayi (fertilitas), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah
kematian (mortalitas) yang terjadi pada semua golongan umur, serta migrasi juga berperan
imigran (pendatang) akan menambah dan emigran akan mengurangi jumlah penduduk. (Ida
Bagoes Mantra, 2003).
2.6.9 Kelahiran, Kematian, dan Migrasi
Fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita, fertilitas
mengacu pada jumlah bayi yang lahir hidup sedangkan mati adalah menghilangnya semua
tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
Selain kedua aspek tersebut migrasi .
Menurut Mantra (1985:157) dalam Erdiana (2017), mobilitas penduduk dapat
dibagi menjadi 2 bentuk yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non permanen
atau mobilitas sirkuler. Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk
menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara ataupun batas
administrasi/ batas bagian dari suatu negara (Eridiana, 2017).
2.6.10 Proyeksi Penduduk
Perhitungan penduduk pada masa yang akan datang, berdasarkan jumlah
penduduk sekarang dan dengan asumsi tertentu tentang tren fertilitas, mortalitas dan
migrasi (Sumarno, 2018). Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan
pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran,
kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah
dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi
diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang
mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain,
termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.
2.7 Kebudayaan
Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari pengetahuan, keyakinan,
kesenian, moral, hukum, adat -istiladat, peralatan kerja, bangunan dan semua kemampuan
dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagal anggota masyarakat.
Keseluruhan elemen kompleksitas itu terutama ditujukan untuk melindungi dan
mempertahankan hidup kemudian menurut Paul B. Horton, Kebudayaan merupakan segala
LAPORAN AKHR STUDIO | 41
sesuatu, baik berupa materi maupun non materi, yang dipelajari dan dialami bersama secara
sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Kebudayaan yang berupa materi selalu
merupakan hasil perkembangan kebudayaan non materi ( norma atau nilai ) sedangkan
menurut tokoh lain Max Weber mengatakan bahwa Kebudayaan merupakan rangkaian
dialektis antara kehidupan sosial dan ide atau nilai. Kehidupan sosial itu meliputi struktur
sosial dan kebendaan hasil dari perbuatan manusia sedangkan ide atau nilai meliputi sistem
nilal, sistem kepercayaan, ideologi maupun pandangan hidup ( world view ). Begitu juga
Menurut Ignas Kleden dan Kuntowijoyo dapat dinterprestasikan bahwa Kebudayaan
merupakan rangkaian dari satu kesatuan (sistem) dari elemen pengetahuan, perilaku,
normatif, dan simbolik. Rangkalan elemen itu selalu mengalami perubahan, baik dalam proses
interaktif maupun dialektik. Pendapat yang terakhir adalah menurut C. Kluckhohn dan
Kotjaraningrat Kebudayaan merupakan kepercayaan dan hasil karya manusia yang meliputi
7 unsur yaitu, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti: rumah, alat pertanian, alat
transportasi, alat produksi dll, Sistem perekonomian atau mata pencaharian seperti berburu,
bertani, nelayan, cara produksi, distribusi dsb, Sistem kemasyarakatan yang meliputi sistem
perkawinan, sistem hukum, sistem politik maupun sistem kekerabatan, Bahasa sebagai
simbol dapat berupa seni rupa, seni patung, ucapan dll, Kesenian yang merupakan karya
ekspresi keindahan seperti: lukisan, tarlan, nyanyian dsb, Sistem pengetahuan dan Agama.32
2.7.1 Kegiatan dan Tradisi Masyarakat Desa
Mengutip dari jurnal budaya dan karakteristik masyarakat desa oleh M. Husain
Mr beliau memberikan pengertian Masyarakat di sektor pedesaaan memiliki ciri khas
tersendiri yang memiliki perbedaan jauh dengan kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan
antara satu desa dengan desa yang lainnya memiliki keberagamangan baik dari segi adat
reusam maupun pola interakaksi dan komunikasi sesame warga anggota
masyarakatnya,Dalam aspek sosila kehidupan sesama anggota masyarakat sisektor desa,
masyarakat disektor ini memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, misalakan dalam gaya
hidup, nilai-nilai kebersamaan, bersahaja,akrab sesama anggota masyarakat yang lainnya.
Dalam kehidupan keseharian mareka saling kenal mengenal antara anggota masyarakat yang
lain, mareka memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan, kebiasaan, begitu juga
hal nya dengan karakter yang mereka miliki sangat dipengaruhi oleh aspek sosila lingkungan
mereka, begitu juga halnya dengan kegiatan ekonomi atau bertani juga dipengaruhi alam
sekitar, misalkan seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang
bukan agraris adalah bersifat sambilan.
Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian, masyarakat
tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, sosial budaya
dan sebagainya Bagi masyarakat pedesaan yang masih menganut pola pertanian tradisional
terjadi hubungan yang erat antar sesam anggota masyarakat yang lain, hal ini setentunya
dikarenakan dalam proses pertanian tradisional menjunjung tinggi tolong menolong dan
gotong royong, apalagi dengan sistem tradisional yang menyebakan antar petani saling bantu
membantu dan tolong-menolong sesama warga masyarakat lainnya. Tolong menolong
sesama anggota masyarakat merupakan cirri khas daripada masyarakat disektor ini. Begitu
juga dalam hal kesertiakawanan sosial, kekompakan dan kesatuan. Selain dari pada itu
masyarakat ini juga memiliki sifat-sifat yang sama, persamaan dalam pengalaman,pola dan
32 Pointers Perkuliahan, Teori Kebudayaan, Drs. AS Mardatani N.MA, 2011
LAPORAN AKHR STUDIO | 42
budaya kerja. Dari segi hubunganya antara sesama anggota masyarat bersifat informal, tetapi
tidak bersifat kontrak sosial atau perjanjian.
Nilai-nilai kebersamaan dan tolong menolong sesama anggota masyarakat
misalkan pada acara pesta, sunat rasul, kemalangan atau kematian dan berbagai kegiatan
sosial lainnya baik secara pribadi maupun untuk kepentingan umum mareka saling
bergotong-royong, begitu juga halnya dengan kegiatan usaha tani yang mereka lakukan,
mereka saling bantu membantu, sehingga setiap petani tidak perlu member upah kepada
petani yang lain, mareka hanya menyiapkan makanan, minuman untuk petani yang
membantunya disawah.kebiasaan atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat tani bersifat tidak
terikat dalam bentuk perjanjian, akan tetapi mereka saling mempercayai antara sesama
petani lainnya.
Tradisi seperti ini, telah ada dalam kehidupan sosila masyarakat tani dipedesaan
sejak ber abad-abad yang lampau, yang merupakan warisan dari generasi kegenerasi
selanjutnya. Mereka saling membantu petani lainnya, kebiasaan ini dilakukan atas dasar
permintaan seseorang petani kepada petani lainnya. Nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki
masayarat desa sangat terasa dan ketara sebelum kemunculan tehnologi. Namun paska
kemasukan mekanisasi pertanian tersebut tradisi ini telah terkikis. Disebabkan dewasa ini,
para petani untuk membajak tanah sudah bertukar dari cangkul dengan traktor, juga
penanaman padi yang awalnya dilakukan dengan tenaga manusia bertukar dengan mesin,
begitujuga dengan memotong padi dengan tenaga manusia dengan menggunakan arit
berubah dengan mesin pemotong padi.nilai-nilai kebersamaan yang merupakan warisan dari
generasi-kegerasi yang telah mengakar dalam aspek kehidupan masyarakat di sektor ini
sudah mulai, seiring dengan perjalan waktu dan kemunculan industry-industri pertanian.33
2.7.2 Kesenian
Menurut para ahli, arti dari kata kesenian itu ada banyak. Maka dari itu supaya
lebih mengenal makna kesenian lebih jauh, berikut akan kami ulas pengertian dari kesenian
menurut para ahli, antara lain:34
1. Menurut William A. Haviland, kesenian adalah keseluruhan sistem yang
berkaitan dengan proses imajinasi manusia yang keratif kepada kelompok
masyarakat umum berdasarkan kebudayaan tertentu.
2. Menurut J.J Hogman, kesenian adalah suatu hal yang terdiri atas ide, aktifitas,
dan artifacts.
3. Menurut Kottak, kesenian itu sebagai bentuk hasil ekspresi, keindahan, dan
kualitas semua hal yang lebih baik dari aslinya.
4. Menurut Kuntjaraningrat, kesenian itu merupakan sesuatu yang kompleks dan
terdiri atas gagasan, norma, ide, nilai-nilai, dan peraturan yang lebih kompleks.
Kegiatan kesenian itu memiliki pola manusia dan biasanya berbentuk benda
buatan dari manusia.
5. Menurut Irving Stone, kesenian adalah kebutuhan pokok. Jadi sama seperti
mantel hangat atau roti yang sering dimanfaatkan di musim dingin. Mereka
berpikir bila kesenian itu barang mewah. Sehingga roh manusia merasa lapar dan
haus terhadap kesenian layaknya perut yang kelaparan dan meminta makanan.
33 Jurnal Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan, M. Husain MR, Oktober 2021
34 https://keluhkesah.com/pengertian-kesenian-menurut-para-ahli-dan-contohnya/
LAPORAN AKHR STUDIO | 43
2.8 Perekonomian Desa
Ekonomi pedesaan merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam
mengembangkan sistem perekonomian desa. Jika dilihat dari aspek spasial, tujuan ekonomi
pedesaan ini adalah terciptanya kawasan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras,
serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan
dan untuk mewujudkan masyarkat yang damai, demokratis, berdaya saing, maju, dan
sejahtera. Menurut Adisasmita,(2006:70) dalam (Rudiansyah, 2015) menyampaikan pendapat
bahwa dalam pengembangan ekonomi pedesaan diperlukan adanya program pembangunan
prioritas lebih besar, diantaranya yaitu:
1. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar pedesaan; tujuan dari
program ini adalah meningkatkan akseibilitas, memperlancar aliran investasi,
produksi dan distribusi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar desa.
2. Pengembangan kawasan pedesaan tertinggal; program ini ditujukan untuk
mendorong pengembangan kawasan pedesaan tertinggal dengan menggali
potensi sumber daya alam yang dimiliki
3. Pengembangan kawasan cepat tumbuh; program ini bertujuan untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi kawasan pedesaan yang berpotensi cepat
tumbuh sebagai andalan pengembangan ekonomi pedesaan dan pergerakan
kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya.35
2.8.1 Teori Potensi Desa
Dikutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan karya Suprayitno Mahasiswa Program S1
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman didalam
jurnalnya menjelaskan tentang teori dan definisi potensi desa. Didalam tilisannya menurut
Soekidjo(2009:1) menjelaskan bahwa pembangunan suatu daerah memerlukan dua asset
yang biasa disebut dengan sumber daya, yakni sumber daya alam(natural resources) dan
sumber daya manusia(human resources). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam
menentukan keberhasilan suatu pembangunan wilayah. Dari segi istilah, kata potensi berasal
dari bahasa inggris “to potent” yang berarti keras atau kuat. Jadi, potensi memiliki arti
kekuatan, kemampuan, dan daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi masih
belum optimal. Sedangkan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat
yang diakui oleh pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten(Soemardjan, 2000).
Berdasarkan pengertian potensi dan desa di atas, maka dapat dipahami bahwa
potensi desa adalah kemampuan, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah,
baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi maish belum dimanfaatkan secara
maksimal. Maju mundur nya sebuah desa sangat bergantung pada kekuatan potensi desa.
Didalam tulisan Jurnal Ilmu Pemerintahan karya Suprayitno disebutkan bahwa potensi desa
terbagi menjadi dua macam potensi, yaitu potensi fisik dan non fisik yang diharapkan
kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan desa.36
1. Potensi fisik, merupakan sumber daya alam yang terdapat di desa dan diharapkan
dapat memberi manfaat bagi kelangsungan dan perkembangan desa yang
meliputi:
35 https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/viewFile/2831/2492
36 http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/issue/view/37
LAPORAN AKHR STUDIO | 44
a. Tanah, yaitu sumber tambang dan mineral, sumber tanaman, mata
pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal.
b. Air,merupakan sumber air untuk irigasi, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
c. Iklim, peranan iklim sangat penting bagi desa yang bersifat agraris.
d. Ternak, menjadi sumber tenaga, bahan makanan, dan pendapatan
masyarakat.
e. Sebagai sumber tenaga kerja potensial baik pengolah tanah dan produsen
dalam bidang pertanian, maupun tenaga kerja industri di kota.
2. Potensi non fisik, potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa
yang bersangkutan. Potensi non fisik ini meliputi:
a. Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat
merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas
dasar kerja sama dan saling pengertian.
b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang
dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat.
c. Aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi
kelancaran jalannya pemerintahan desa.
2.8.2 UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada
setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai
dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
UMKM didefinisikan sebagai berikut: 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha
Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
Adapun pengertian UKM menurut Suhardjono dalam Rafika (2010)
mendefinisikan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sertakepemilikan
sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteriaperusahaan di Indonesia dengan jumlah
tenaga kerja 1 - 4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 –
19 sebagai usahakecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 - 99 sebagai 15
industrimenengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orangsebagai usaha
besar.37
37 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8772/BAB%20II%20Baru.pdf
LAPORAN AKHR STUDIO | 45
2.9 Kelembagaan Desa
Dilansir dari media neliti.com, praktik demokrasi semakin marak terjadi pada
masa demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1999 sampai sekarang, seperti adanya
pemilihan Calon Legislatif (Caleg), pemilihan Gubernur, pemilihan Walikota, pemilihan
Bupati, dan pemilihan Kepala Desa. Sebagaimana dalam praktiknya, demokrasi melibatkan
berbagai macam aktor dan lembaga dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Pelaksanaan
demokrasi memuat aspek kelembagaan yang merupakan keutamaan dari berlangsungnya
praktik politik yang demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga perwujudan yang
ada di desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain lembaga tersebut,
munculnya civil society atau lembaga informal seperti kelompok perkumpulan pemuda,
kelompok agama, dan sebagainya juga ikut menyumbang partisipasi dan melakukan
pengawasan terhadap proses jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan
pemerintahan desa itu sendiri.
Utami, Molo, Widiyanti (2011) menyatakan bahwa kelembagaan dari aspek
formal merupakan gambaran/ deskripsi potret dari aspek regulative institusi formal yang
terdiri dari batas yuridiksi, peraturan, sanksi dan monitoring. Kelembagaan menyediakan
pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk
bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan.
Kelembagaan formal di desa merujuk pada organisasi yang berada di bawah tanggung jawab
atau komando pemerintahan desa.
Berikut beberapa teori tentang kelembagaan dalam rana kajian sosiologi, istilah
kelembagaan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang tepat dan tergolong
membingungkan (Syahyuti, 2006). Syahyuti, (2006) mengemukakan bahwa “kata
kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup
(constituted) dikalangan masyarakat”. Masih menurut Syahyuti (2006) “kelembagaan adalah
kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat dan dibangun untuk satu fungsi
tertentu”. Berbeda dengan Syahyuti, Suhardjo (1999) menyimpulkan bahwa “lembaga adalah
suatu sistem atau kompleks nilai dan norma”. Istilah lain dari lembaga sosial adalah lembaga
pranata sosial. “Pranata sosial adalah suatu sitem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat
kepada serangkaian aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus
mereka” (Koentjaraningrat, 1974).38
Sesuai dengan definisi lembaga sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan
khusus masyarakat (dalam hal ini masyarakat desa) adalah kebutuhan untuk pembangunan
desa.
2.10 Intensitas Pemanfaatan Ruang
Intensitas Pemanfaatan Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang di banyak daerah di Indonesia, pelaksanaannya
sering atau tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain,
38 https://media.neliti.com/media/publications/180901-ID-none.pdf
LAPORAN AKHR STUDIO | 46
tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan
lemahnya penegakan hukum yang berlaku.
2.10.1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona
terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar
Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik
di atas maupun di bawah permukaan tanah. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah
ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu zona, yang
meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas
persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
KDB maksimum dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona
dengan KDB 60%, maka properti yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 60%
dari luas lahan.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien yang menunjukkan luas lahan
yang tertutup bangunan dibandingkan dengan total luas lahan dalam satu kavling,
Penentuan KDB ditinjau dari aspek lingkungan dengan tujuan untuk
mengendalikan luas bangunan di suatu lahan pada batas-batas tertentu sehingga
tidak mengganggu penyerapan air hujan ke tanah, (Nobble, 1993).
20 % 20 %
80 % KDB 80 % KDB
Gambar 2.1 Ilustrasi KDB
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum dan Maksimum KLB adalah koefisien
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga
lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan
terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan. Koefisien
Lantai Bangunan/KLB (Floor Area Ratio), adalah perbandingan luas lantai total
dengan luas lahan persil. Luas bangunan yang dihitung merupakan seluruh luas
bangunan yang ada, mulai dari lantai dasar hingga lantai diatasnya. Faktor yang
perlu diperhatikan dalam penentuan KLB adalah upaya mempertahankan fungsi
kegiatan dengan mencegah berkembangnya konflik land use ke kawasan
sekitarnya, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005).
LAPORAN AKHR STUDIO | 47
Koefisien Dasar Hijau Minimal KDH adalah angka prosentase perbandingan
antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan
bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH minimal digunakan
untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH
minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan
air dan kapasitas drainase. KDH minimal dinyatakan dinyatakan dalam satuan
persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20%.
20 % 20 %
80 % KDH 80 % KDH
Gambar 2.2 Ilustrasi KDH
2. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah koefisien yang menunjukkan luas lahan
yang tidak tertutup bangunan dibandingkan dengan total luas lahan dalam satu
kavling. Semestinya KDH berwujud softscape, contohnya tanah berumput, tanah
dengan tanaman/pohon, maupun tanah terbuka, yaitu angka presentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai, (Nobble, 1993).
LAPORAN AKHR STUDIO | 48
3.1 Orientasi Wilayah Perencanaan
Kecamatan Karangploso adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi kecamatan Karangploso terletak di sebelah barat, Kota
Malang. Secara administratif, kecamatan Karangploso dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang
ada di Malang Raya. Di sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kecamatan Singosari.
Sedangkan di sebelah timur, kecamatan karangploso, berbatasan langsung dengan
Kecamatan Singosari, dan kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Di sebelah selatan,
Kecamatan Karangploso berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Junrejo, Kota
Batu. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Kecamatan Karangploso memiliki luas wilayah 5.957.898 Ha dengan Sembilan
desa yaitu Ampeldento, Boce, Donowarih, Girimoyo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo,
Tawangargo, dan Tegalgondo. Sebagian wilayah kecamatan ini berupa area tegal, kebun,
hutan dan sawah. Tak heran jika sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai
petani. Namun, dengan didirikannya beberapa pabrik yang berada di kecamatan karangploso,
membuat penduduk yang awalnya bekerja sebagai petani kemudian beralih sebagai pegawai
pabrik.
Wilayah Kecamatan Karangploso ini dapat disimpulkan sebagai jalan pintas dari
area utara Jawa Timur, tepatnya dari Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo menuju Kota
Batu. Rest Area dibangun untuk memfasilitasi wisatawan yang melintas Kecamatan
Karangploso yang berlokasikan di Desa Donowarih, tepatnya sebelah barat Kantor
Kecamatan Karangploso. Rest Area ini menjadi objek wisata andalan di Kecamatan ini
dimana fungsinya sebagai tempat persinggahan bagi para wisatawan yang hendak berwisata
ke Kabupaten Malang, Kota Malang, ataupun Kota Batu. Tempat ini menyediakan banyak
fasilitas umum bagi wisatawan yang kebetulan mampir.
Sebagai wilayah penunjang pengembangan perkotaan, Kecamatan Karangploso
termasuk ke dalam jalur Segitiga Emas (Penghubung antar kota) KEK Pariwisata, yaitu
Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Dengan posisi yang strategis inilah yang
membuat Karangploso diarahkan menjadi kawasan pertumbuhan cepat. KEK Pariwisata atau
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata merupakan zona pariwisata diperuntukkan bagi
kegiatan usaha untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan,
pameran serta kegiatan terkait.
LAPORAN AKHR STUDIO | 49
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN KELOMPOK 1A UPBJJ MALANG
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search