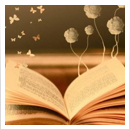Pertama, kesulitan dan kemalasan membuat karya tulis ilmiah,
walaupun banyak di antara mereka lulusan sarjana. Ironisnya,
mereka memilih berada dalam lingkaran kesulitan daripada mengurai
kesulitan agar menjadi benah merah yang dapat memberikan manfaat
secara kontribusial dalam proses belajar mengajar.
Kedua, sikap egoisme yang berlebihan sehingga tidak mau
bertanya dan berlatih menulis karya ilmiah. Pernyataan ini dilandasi
kenyataan di lapangan bahwa mereka yang bergolongan IV a adalah
guru-guru sudah tua sehingga memiliki sikap kekakuan tinggi.
Dampaknya, mereka enggan bertanya dengan guru-guru lebih muda.
Ketiga, kurangnya kebiasaan membaca dan menulis. Sungguh
menyedihkan, apabila dalam suatu sekolah tidak memiliki media
massa dan bacaan bernuansa pendidikan. Lebih menyedihkan lagi,
ketika guru sudah tidak tertarik pada tulisan bertajuk pendidikan, dan
justru tertarik dengan tulisan bernuansa kriminalitas: “seorang
suami, tega membunuh istrinya” barangkali lebih menarik dan
menjadi perhatian guru daripada, “quantum learning, alternatif
pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan”.
Kondisi tersebut diperparah dengan sikap guru yang ingin
menang sendiri, seperti: mengharuskan siswa mengarang, tetapi guru
tidak pernah menunjukkan hasil karangannya, mengharuskan siswa
menutup/menyimpan buku ketika ulangan, tetapi guru justru
membuka buku dengan dalih membuat soal, dan sebagainya.
Pembelajaran yang memenangkan guru seperti ilustrasi di atas,
secara evolusif akan menjadi bumerang bagi guru sendiri.
Setidaknya tiga permasalahan yang menghantui guru dalam
hubungan pengembangan profesi, seakan-akan menjadi cermin bagi
dunia pendidikan bahwa sumber daya manusia bidang pendidikan
belum mengalami peningkatan signifikan. Selama ini, upaya-upaya
yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program peningkatan
mutu pendidikan cukup baik, tetapi pada tahap implementasi dan
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 243
evaluasi menjadi kurang baik. Hal ini lantaran kesiapan dan
kemampuan sumber daya manusia bidang pendidikan pada tataran
bawah sebagai objek bidikan dari sasaran program, belum mampu
diajak berlari.
Yang terjadi dan nge-trend saat ini, adalah pendidikan berbasis
proposal. Dalam pengertian, pihak-pihak yang pandai membuat
proposal saja yang mendapat kucuran dana dari pemerintah.
Sedangkan outcome dari dana yang diberikan kurang bermakna
secara aplikatif terhadap efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu
pendidikan.
Secara khusus, program pembiasaan guru melakukan
pengembangan profesi belum tersentuh secara komprehensif. Di
dunia perguruan tinggi (dosen), memiliki anggaran dana berlimpah
untuk mengadakan penelitian. Sedangkan di dunia pendidikan dasar
dan menengah, dana untuk mengadakan penelitian yang merupakan
salah satu unsur pengembangan profesi nyaris tidak ada.
Mencermati Fenomena
Menanti uluran tangan pemerintah untuk memberikan
stimulan dana pengembangan profesi ibarat menjaring angin. Oleh
karena itu, ada baiknya guru menjemput bola dengan serangkaian
aktivitas yang mengarah pada pengembangan profesi. Ada bekal
sederhana yang dapat dipakai sebagai obat kemalasan bagi guru
dalam mengembangkan profesi.
Pertama, cermati situasi dan fenomena aktual yang terjadi di
dunia pendidikan, dengan menarik garis lurus antara teoretis dan
praktis. Jika terjadi garis bengkok, segeralah di-counter dengan
tulisan yang substansinya meluruskan, sehingga ada keterkaitan yang
sinergis antara harapan dan kenyataan.
Kedua, mulailah menulis ketika Anda sedang malas. Idiom
Prof. Dr. Rustono Guru Besar Unnes tersebut seakan-akan memberi
244 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
pemahaman bahwa sikap malas merupakan kendala utama guru
dalam mengembangkan profesi. Mengikis rasa malas bukanlah hal
mudah, tetapi menjadikan kekuatan rasa malas untuk berkarya
merupakan hal yang perlu dicoba.
Ketiga, belajar dari kesuksesan orang lain yang bermuara pada
pentingnya bertanya dan berlatih. Sebenarnya, sikap egoisme
berlebihan merupakan satu upaya menutupi kelemahan guru.
Karenanya, guru tidak perlu merasa menang sendiri. Kesadaran
bertanya dan berlatih merupakan wujud pemanfaatan kekuatan
egoisme.
Kemalasan guru mengembangkan profesi beriringan dengan
ketakutan guru memulai berkarya. Kondisi ini, menjadikan mereka
puas dengan apa yang selama ini diraih. Oleh karena itu, mari para
guru kita kikis kemalasan dan ketakutan dengan memberikan setitik
karya memajukan dunia pendidikan yang realistis, bukan pendidikan
berwacana teoretis.
__dimuat di koran sore Wawasan, 26 September 2002.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 245
MENYIAPKAN GURU BANTU MENJADI PNS
Oleh Trimo
Akhir Maret ini, Depdiknas menggelar kulminasi dari
serangkaian aktivitas rekrutmen guru bantu, dengan mengadakan tes
serentak di berbagai daerah se-Indonesia. Tes dimaksudkan untuk
menyaring para calon guru bantu, yang nantinya akan memperkuat
barisan pahlawan tanpa tanda jasa dalam menyemaikan tunas-tunas
muda.
Berbagai persiapan tentu dilakukan calon guru bantu, baik
yang menyangkut administrasi maupun aktualisasi potensi. Hal
tersebut karena pemerintah (dalam hal ini Depdiknas) memberikan
peluang sama terhadap semua lulusan berlabel guru untuk bersaing
menjadi guru bantu.
Walaupun pemerintah sudah berupaya menekan sekecil
mungkin adanya pelanggaran dalam rekrutmen guru bantu, tetapi di
lapangan tetap berkembang berbagai fenomena bernuansa pesimis
terhadap upaya pemerintah tersebut. Fenomena tersebut di antaranya
komitmen pemerintah untuk menjadikan rekrutmen guru bantu
sebagai langkah awal menyiapkan calon guru bantu menjadi PNS.
Adakah komitmen tersebut? Kalau ada, konsistenkah
komitmen tersebut? Kalau tidak, untuk kepentingan apa rekrutmen
guru bantu dilaksanakan? Tulisan ini sekadar memberikan
perenungan mendalam mengenai keberadaan guru bantu di tengah-
tengah kondisi pendidikan di negeri Indonesia.
Asal Jalan
Secara nasional, Depdiknas akan mengangkat 190.714 guru
bantu yang diharapkan mampu mengatasi kekurangan guru di
berbagai daerah, khususnya Sekolah Dasar. Gaji yang akan diterima
246 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
guru bantu adalah 400.000 rupiah per bulan setelah dipotong pajak.
Seperti dikatakan Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas Soewondo
bahwa guru honorer yang selama ini sudah mengajar di sekolah akan
diprioritaskan untuk mendaftar sebagai guru bantu. Program guru
bantu ini sifatnya sementara, sampai persoalan kekurangan guru
yang banyak dikeluhkan berbagai daerah bisa diatasi
(depdiknas.go.id.com).
Mencermati ungkapan Soewondo, orang akan memahami
bahwa sebenarnya prioritas utama dalam rekrutmen guru bantu
adalah guru wiyata bakti. Artinya, mereka yang masih aktif
berwiyata bakti mendapat peluang lebih besar dalam rektrutmen guru
bantu. Sayangnya, prioritas tersebut sebatas mendaftar, bukan
diterima.
Apalagi, program guru bantu tersebut bersifat sementara
sehingga tidak memberikan jaminan bagi mereka yang sudah
diterima menjadi guru bantu untuk diangkat menjadi pegawai negeri
sipil.
Kesan yang saya tangkap dari serangkaian program yang
diluncurkan Depdiknas bernuansa sembrana, asal jalan, dan coba-
coba tanpa diperhitungkan nutturant effect dari program yang
diwacanakan. Sejenak berkaca dari program-program tempo dulu
yang nyaris belum tuntas dan disusul program baru, sehingga
menjadikan program lama, basi dan tak tersentuh.
School Based Management yang hanya dimaknai pendidik
pada tataran teoretis saja, beberapa produk kebijakan pembelajaran
terkesan memaksa guru menerapkan dalam proses belajar mengajar,
rekrutmen tenaga pengajar yang tidak transparan dan bernuansa
uang, dan sebagainya.
Kebijakan-kebijakan yang tanpa memperhitungkan dampak
bagi pengembangan sumber daya manusia inilah, menjadikan kondisi
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 247
pendidikan di negara kita terpuruk. Ironisnya, tanda-tanda datangnya
keterpurukan tidak dimaknai sebagai awal kehancuran sehingga
perlu disiapkan seperangkat tindakan aplikatif yang orientasinya
pada pengembangan sumber daya manusia, tetapi justru dimaknai
para petinggi pendidikan dengan memunculkan program baru
sehingga para guru lupa tanda-tanda keterpurukan.
Penyiapan kondisi datangnya keterpurukan pendidikan dengan
memunculkan kebijakan pembelajaran dan program baru, secara
evolusif akan menjadikan dunia pendidikan di negeri ini hanya
kelihatan bagus secara luar saja, tetapi secara subtansi tidak mampu
berkompetisi.
Tentu kita masih ingat, beberapa hasil penelitian mengenai
kualitas sumber daya manusia yang menempatkan Indonesia pada
peringkat terakhir, di antaranya penelitian PERC (Political and
Economic Riisk Consultancy) menyatakan bahwa sistem pendidikan
di Indonesia peringkat terakhir dari 12 negara di Asia.
Belajar dari Kegagalan
Selalu mengalami kesalahan serupa dan tidak becermin dari
kegagalan kebijakan sebelumnya, inilah sebenarnya kunci
ketidakmenentuan pendidikan di negeri ini. Agaknya kebijakan guru
bantu juga tidak becermin dari kegagalan sistem pendidikan guru.
Sekadar mengingatkan, dahulu untuk menjadi guru Sekolah Dasar
cukup melalui proses pendidikan kursus guru, SPG/SGO, dan
sekarang D II PGSD.
Idealnya, munculnya lembaga pencetak guru SD yang baru
tentu menutup peluang lembaga pendidikan sebelumnya untuk
diangkat menjadi PNS. Sebenarnya hal tersebut sudah dilaksanakan
pemerintah, sejak April 1994 rekrutmen guru SD harus berbasis
pendidikan D II. Dengan demikian tidak terbuka kesempatan bagi
mereka yang hanya berijazah SPG/SGO.
248 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Kebijakan tersebut tentu menjadikan mereka yang hanya
bermodal ijazah SPG/SGO menarik diri dari dunia pendidikan, dan
memilih alternatif pekerjaan lain yang memberikan jaminan masa
depan. Banyak di antara mereka yang alih profesi, dari guru menjadi
nonguru. Ketika mereka sudah lupa dengan murid-murid dan cara
mengajar yang baik, pemerintah memberikan kesempatan untuk ikut
mengikuti rekrutmen guru SD.
Mereka pun lantas kebingungan dan berupaya mencari cara
melengkapi dokumen administrasi. Yang mengherankan, banyak di
antara mereka yang sudah tidak aktif mengajar puluhan tahun justru
diterima menjadi PNS, sementara mereka yang masih setia mengabdi
tidak diterima.
Fenomena tersebut menjadi buah bibir dan marak
diperdebatkan, sehingga muncul gerakan demonstrasi di berbagai
daerah yang menuntut proses rekrutmen tenaga pengajar agar
transparan dan berdasarkan validitas data di lapangan.
Belajar dari kesalahan, kelemahan, dan kegagalan berbagai
program pendidikan yang dirumuskan pemerintah, saya berangan-
angan menjadikan proses rekrutmen guru bantu tahun ini sebagai
langkah awal mempersiapkan mereka menjadi pegawai negeri sipil.
Terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam proses
rekrutmen tenaga pengajar tahun-tahun lalu merupakan alasan utama
yang dapat dijadikan acuan mengantisipasi sejak dini adanya
penyimpangan serupa. Menyiapkan guru bantu untuk diangkat
menjadi PNS, tentu bukan pekerjaan mudah.
Proses Berkelanjutan
Setidaknya, langkah awal tersebut dapat dijadikan masa
training bagi guru bantu sebelum resmi menjadi PNS. Langkah ini
akan memperbaiki citra pendidikan di mata masyarakat, sekaligus
sebagai jaminan bagi guru bantu dalam melaksanakan aktivitasnya.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 249
Walau sekadar angan-angan, proses penyiapan guru bantu
menjadi PNS, nantinya akan menjadi trade dunia pendidikan.
Artinya, masa-masa training menjadi guru bantu akan dimaknai
sebagai proses berkelanjutan, seperti yang sudah diterapkan
manajemen bisnis dalam perusahaan. Menurut saya, ada beberapa hal
yang patut diperhatikan dalam menyiapkan masa training guru
bantu.
Pertama, pengkajian rekrutmen guru bantu yang berkaitan
eksistensi guru wiyata bakti. Proses ini dimaksudkan memberi
peluang signifikan bagi guru wiyata bakti untuk mendaftar dan
memperoleh prioritas diterima sebagai PNS. Data guru wiyata bakti
nyata di Dinas P dan K dapat dijadikan acuan menetapkan skala
prioritas, sehingga memperkecil adanya peluang manipulasi data
yang sering terjadi setiap ada pengangkatan guru.
Kedua, penyiapan soal yang memiliki tingkat validitas dan
reliabilitas tinggi sehingga tidak menimbulkan salah tempat dan
dapat dikerjakan peserta sesuai bidang profesinya. Hal ini sangat
penting lantaran soal-soal ujian CPNSD tahun lalu, kurang mampu
mengungkap kompetensi tenaga pendidikan. Bahkan, terdapat
beberapa butir pertanyaan yang tidak relevan dengan spesialisasi
yang dipilih peserta ujian. Dalam konteks ini, perlu dipersiapkan tim
pembuat soal independent yang terdiri atas kalangan akademisi,
pemerhati pendidikan, dan LPTK.
Ketiga, penetapan indikator kinerja yang mengacu padu
pengembangan kompetensi guru baik kompetensi personal,
profesional, dan kemasyarakatan. Indikator kinerja diterjemahkan
dalam seperangkat instrumen yang berfungsi menilai kelayakan guru
bantu.
Keempat, pengawasan dan pembinaan secara kontinu terhadap
guru bantu yang menjalani masa training. Hal ini sangat diperlukan
sebagai umpan balik terhadap kinerja guru bantu, sekaligus sebagai
250 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
bahan pertimbangan pengangkatan PNS. Peran Kepala Sekolah
sebagai atasan langsung dan institusi tingkat atasnya sangat
menentukan objektivitas pelaporan kinerja yang dilakukan guru
bantu dalam proses belajar mengajar.
Kelima, memberikan peningkatan kesejahteraan guru bantu
dengan melibatkan komite sekolah. Dalam konteks ini, komite
sekolah dapat menerapkan fungsinya sebagai pendukung (supporting
agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga
dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, khususnya
dalam peningkatan kesejahteraan. Hal ini lantaran upah guru bantu
yang hanya 400.000 rupiah, jelas tidak seimbang dengan jerih payah
dan pengabdiannya dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Sumbang pikir di atas hanya angan-angan yang diharapkan
mampu membantu mengatasi permasalahan-permasalahan krusial
dan kontekstual dalam dunia pendidikan. Tidak terkecuali
permasalahan guru bantu yang sampai sekarang masih dibayang-
bayangi rasa pesimis dan tidak menentu.
Bila hari ini cita-cita saudaraku belum tercapai, percayalah
esok hari pasti akan ada hari lebih baik.
__dimuat di koran sore Wawasan, 28 Maret 2003.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 251
PRAMUKA, MASIHKAH MILIK KITA?
Oleh Trimo
Mendengar kata Pramuka, orang tentu berasumsi bulan
Agustus, lantaran sepak terjang dan aktivitasnya nyaris hanya bisa
dilihat masyarakat umum pada bulan tersebut. Sedangkan bulan-
bulan lain kata Pramuka seolah-olah hanya menjadi pengisi satu
sudut kecil kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yang tidak semua
Gugus Depan aktif melaksanakannya.
Sekadar merefleksi, Pramuka memang organisasi yang dari
zaman kolonial sampai zaman reformasi diidolakan pemerintah.
Simak saja berbagai upaya yang membangun Pramuka secara
holistik, baik dari segi usia maupun instansi pemerintah. Semua
siswa usia 7-25 tahun dikelompokkan dalam kategori peserta didik,
25 tahun ke atas sebagai pembina, dan mereka yang usia lanjut
dihimpun dalam Hiprada dan Pandu Wreda.
Tidak ketinggalan, di berbagai instansi dari kelurahan
sampai pusat para kepala kelurahan/kepala desa, camat, bupati/wali
kota, gubernur, presiden tidak bisa mengelak untuk menjadi
Pramuka. Kepolisian dengan Saka Bayangkara, Angkatan Laut
dengan Saka Bahari, Angkatan Udara dengan Saka Dirgantara,
Kehutanan dengan Saka Wana Bakti, Kesehatan dengan Saka Bakti
Husada, Keluarga Berencana dengan Saka Kencana, Pariwisata
dengan Saka Pandu Wisata, dan saka-saka lain yang merupakan
manifestasi Pramuka dalam upaya memberikan pendidikan generasi
muda.
Parpol Pramuka?
Pada pertemuan Pembina Pramuka, saya pernah berkelakar
andai saja Pramuka jadi partai politik barangkali dapat
memenangkan pemilu. Alasan saya sederhana lantaran secara
252 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
keanggotaan semua orang sudah pernah menjadi Pramuka dan
merasakan betapa kegiatan Pramuka penuh nuansa “ikhlas bakti bina
bangsa berbudi bawa laksana”.
Sudah saya tebak sebelumnya bahwa ide guyon tersebut tidak
mendapat sambutan. Semua Pembina Pramuka yang hadir
menyatakan tidak sependapat dengan apa yang saya lontarkan.
Bahkan ada yang menanggapai serius bahwa berdirinya Pramuka
bukan untuk menyusun kegiatan yang menjurus partai politik, tetapi
lebih terfokus kepada pembinaan generasi muda.
Dalam benak, umpan saya terpancing. Apa yang saya
lontarkan sebenarnya hanya pencerahan pemikiran lantaran sudah
lama stakeholders Pramuka hanya berpandangan homogen. Tidak
pernah ada dinamika pemikiran yang merupakan refleksi perlunya
Pramuka berwawasan ke depan memikirkan negeri Indonesia.
Dalam kondisi negara tidak menentu, apa yang dilakukan
Pramuka cenderung sama dengan kondisi negara sebelumya. Simak
saja berbagai kegiatan Pramuka dari Siaga, Penggalang,
Penegak/Pandega, dan Pembina selalu menampilkan aktivitas
monoton. Para Pembina Pramuka hanya berpikir kegiatan Pesta
Siaga, Jambore, Raimuna, dan Karang Pamitran dari zaman dulu
sampai sekarang tanpa memiliki dinamika aktivitas heterogen.
Secara konsep sebenarnya tidak ada orang meragukan
organisasi berlambang tunas kelapa tersebut. Hal ini lantaran
keberadaannya cukup terbukti mampu mengakomodasi kekuatan dan
aktivitasnya cenderung baik. Hampir tidak pernah ada berita di
media mengenai tindak kejahatan dan kriminal berlabel Pramuka.
Yang menjadi bahan renungan barangkali bukankah para
pelaku tindak kejahatan tersebut ketika sekolah juga pernah menjadi
anggota Pramuka? Nilai apakah yang mereka serap dan teladani dari
kegiatan Pramuka? Bukankah Pramuka selalu berkampanye dengan
untaian lagu: “Pramuka siapa yang punya, pramuka siapa yang
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 253
punya, pramuka siapa yang punya, yang punya kita semua”. Kata
kita yang dimaksud adalah seluruh bangsa Indonesia.
Konsekuensi logis dari lagu tersebut adalah rasa handarbeni
terhadap gerakan Pramuka sehingga segala pikiran, ucapan, dan
tindakan senantiasa berpedoman pada Trisatya dan Dasadarma.
Realitas di lapangan belum sepenuhnya anggota gerakan Pramuka
mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut. Lihat saja tayangan iklan di
televisi dengan setting Pramuka yang memamerkan produk sepatu
terkenal, tanda-tanda/atribut Pramuka yang dikenakan tidak benar,
seperti pemasangan tanda pelantikan yang keliru (Pramuka
perempuan masih menggunakan tanda pelantikan Pramuka laki-laki).
Hal serupa juga terulang pada penayangan sinetron Bidadari 2 yang
mengambil setting kegiatan Pramuka beberapa hari lalu.
Bawa Laksana
Sejujurnya, konsep ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa
laksana sangatlah cocok untuk negeri Indonesia, bukan “ikhlas harta
demi kedudukan”. Hal menarik dari konsep tersebut semata-mata
mengajak seluruh komponen bangsa agar memberikan setitik bakti
untuk negeri ini, senantiasa teguh pada pendirian, dan menepati apa
yang dikatakan.
Dalam etika Jawa dikenal satu ungkapan yang berbunyi
“sabda pandhita ratu, tan kena wola-wali”, yang dapat dimaknai
bahwa seorang pemimpin haruslah konsekuen mewujudkan apa yang
diucapkan. Kristalisasi dari ungkapan itu adalah perlunya pemimpin
memiliki sifat bawalaksana. Dalam filsafat Jawa, seorang raja (dan
tentunya, demikian pulalah seorang pemimpin) harus memiliki sifat
bawalaksana di samping sifat-sifat baik lainnya. Ini tecermin dari
ungkapan yang sering diucapkan Ki Dalang dalam setiap lakon
wayang, yang berbunyi: “dene utamaning nata, berbudi
254 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
bawalaksana.‖ (sifat utama bagi seorang raja adalah bermurah hati
dan teguh memegang janji).
Sifat bawalaksana dianggap mempunyai nilai tinggi, sehingga
ia harus dimenangkan apabila terjadi berbenturan dengan nilai-nilai
lain, termasuk nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Etika bawalaksana
ini mengandung nilai bersifat universal. Di mana pun dan kapan pun
juga, sikap tersebut pasti diakui mengandung nilai filsafat baik dan
perlu dipegang teguh semua orang.
Lantas, bagaimana dengan etika bawa laksana pemimpin
negeri ini? Tanpa memberi komentar berlebihan, masyarakat
barangkali dapat memberi penilaian terhadap kinerja para pemimpin
negeri ini. Becermin pada perilaku Pramuka yang kental dengan
nuansa ikhlas bakti bina bangsa dan berbudi bawa laksana agaknya
dapat dijadikan pengobat kegelisahan negeri yang mendapat julukan
zamrud khatulistiwa.
Bersatu dan Bersama
Selaras dengan tema HUT Pramuka ke-42 yang dicanangkan
Kwarda Jateng, yakni: “Bersatu dalam Kebersamaan dan Bersama
dalam Persatuan”, gerakan Pramuka selayaknya menjadi pelopor
perlunya merekatkan kembali nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa menuju kebersamaan membangun bangsa di tengah-tengah
kehidupan mengglobal.
Setidaknya ada beberapa hal yang patut direnungsarikan
sebagai bekal gerakan Pramuka dalam menjadi pelopor persatuan
dan kesatuan bangsa.
Pertama, pertajam serangkaian kegiatan yang bernuansa
persatuan secara spesifik dengan mengaktifkan kegiatan di gugus
depan sebagai basis pembinaan generasi muda. Kegiatan bersifat
beregu yang merupakan refleksi dari pentingnya kebersamaan perlu
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 255
ditingkatkan lebih aplikatif sebagai wujud pengamalan Dasadarma
Pramuka.
Kedua, konsisten dan disiplin dalam menjalankan tugas
sebagai internalisasi semboyan Pramuka: ikhlas bakti bina bangsa
berbudi bawa laksana. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan
intensitas kegiatan bakti, baik kepada sesama dan lingkungan sekitar
sebagai bentuk pengalaman Dasadarma ke-2, cinta alam dan kasih
sayang sesama manusia.
Ketiga, mengamalkan nilai-nilai luhur gerakan Pramuka dalam
kehidupan sehari-hari dan responsif terhadap berbagai fenomena di
lapangan. Wujud nyatanya dengan berpikir, berucap, dan bertindak
yang baik dalam selubung kehidupan pluralis. Selebihnya
menindakkritisi berbagai gagasan-gagasan yang bersifat inovatif
demi kemajuan Pramuka di masa depan.
Keempat, senantiasa menjalin interaksi dan koordinasi dengan
organisasi lain dalam upaya membangun negeri Indonesia. Hal ini
didasari pentingnya kebersamaan selaras dengan pepatah: “Bersatu
kita teguh bercerai kita runtuh”. Kebersamaan tersebut juga dapat
menepis asumsi orang bahwa Pramuka adalah organisasi yang
dijadikan anak emas pemerintah.
Memandulah terus suatu saat akan kautemukan sesuatu yang
indah! Dirgahayu Gerakan Pramuka! Semoga masih menjadi milik
kita semua sehingga mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan
bangsa demi masa depan Indonesia tercinta.
256 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
KESEPAKATAN MELANGGAR
DALAM REKRUTMEN CPNS
Oleh Trimo
Sahabat penulis yang tidak mau disebut namanya, bertukar
pikiran tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang
hari ini marak diguncingkan. Hal yang menjadi tanda tanya penulis
ketika berdiskusi adalah ketidaktertarikan sahabat tadi yang notabene
masih berstatus guru wiyata bakti untuk mengikuti rekrutmen CPNS.
Alasan sederhana, ia sudah lebih dari lima kali dikecewakan lantaran
tidak terima CPNS. Sampai sekarang, ia masih berasumsi bahwa
untuk menjadi CPNS harus menyiapkan vitamin D (baca: duit)
sebagai sarana wajib yang jumlahnya nyaris tidak terjangkau
masyarakat umum.
Apa benar untuk menjadi CPNS harus membayar? Barangkali
kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada masyarakat, mungkin
sebagian besar dari mereka menjawab ya lantaran fenomena yang
berkembang membenarkan hal itu dan publik telanjur memberi cap
negatif terhadap rekrutmen CPNS.
Apakah ada bukti bahwa mereka yang sudah diterima menjadi
CPNS itu benar-benar membayar? Pertanyaan ini mungkin patut
dilontarkan oleh oknum yang terlibat proses membudaya di setiap
sektor pemerintahan negeri ini. Ibarat bermain api, tentu mereka
berupaya tidak terkena jilatan api sehingga kecil kemungkinan ada
bukti-bukti memberatkan.
Proses Rekrutmen
Itulah realitas yang benar-benar ada di masyarakat dan kita
tidak memandang sebelah mata. Sebenarnya, kalau dicermati
mendalam, proses rekrutmen CPNS akhir-akhir ini sudah
menggunakan sistem yang baik. Dalam pengertian, proses
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 257
perencanaan dan pelaksanaannya sudah ditata rapi. Namun demikian,
finishing-nya yang acapkali tidak berjalan sesuai prosedur-prosedur
awal.
Meminjam istilah George R. Tery bahwa dalam setiap
kegiatan bertajuk apa pun selalu berhubungan dengan empat fungsi
manajemen, yakni: planning, organizing, actuating, dan controlling.
Proses rekrutmen CPNS tentu juga tidak terlepas dari keempat proses
tersebut.
Proses perencanaan (planning) merupakan kegiatan rasional
dan sistemik dalam menetapkan keputusan, langkah-langkah yang
akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka mencapai tujuan
efektif dan efisien. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu
dilakukan yakni: 1) Menetapkan dan merumuskan tujuan
operasional, 2) Menganalisis situasi dan kondisi dengan strenght,
weakness, opportunity, treath (SWOT), 3) Menetapkan
permasalahan, 4) Menentukan prioritas dan mengidentifikasi
alternatif pemecahan masalah, 5) Mengambil keputusan, 6)
Menyusun rencana kegiatan.
Fungsi planning sudah dilaksanakan panitia penyelenggara
rekrutmen CPNS Kabupaten/Kota. Terbukti sudah ada pemetaan
kebutuhan tenaga yang dibutuhkan dengan kualifikasi tertentu. Hal
yang menarik adalah seleksi setiap daerah dilaksanakan dalam waktu
yang tidak bersamaan.
Proses pengorganisasian (organizing) dimaknai sebagai proses
menetapkan hubungan perilaku antarorang secara efektif sehingga
mereka dapat bekerja sama efisien dan memperoleh kepuasan dalam
mengerjakan tugas mencapai tujuan. Setidaknya, dalam proses ini
ada enam langkah yang harus dilakukan, yakni: memahami tujuan
institusional, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan, mengelompokkan
kegiatan yang serumpun dalam satu unit kerja, menetapkan job
description, menyusun personel, dan menentukan hubungan kerja.
258 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Titip
Pada proses pengorganisasian inilah, mulai muncul
sinyalemen titip lantaran sudah ada pembentukan panitia. Bahkan
ada yang berupaya mencari rekomendasi pejabat untuk memuluskan
langkah. Sebenarnya, keterlibatan orang-orang dalam proses titip
merupakan kebutuhan kedua belah pihak yang mengharapkan
terjadinya simbiosis mutualisme.
Lantaran berhubungan kebutuhan, maka terjalinlah
kesepakatan yang hanya diketahui stakeholders (yang
berkepentingan) saja. Yang jelas kesepakatan tersebut bermuara pada
satu kesepakatan saling melanggar aturan dan norma-norma.
Proses penggerakan (actuating), merupakan proses yang
melibatkan semua anggota untuk bekerja sama ikhlas dan bergairah
mencapai tujuan sesuai rencana. Pada proses inilah, biasanya
dilakukan para spekulan mencari nasabah. Walau secara teoretis
fungsi ini harus dilaksanakan ikhlas dan bersemangat, tetapi di
lapangan acapkali diterjemahkan kurang benar lantaran peluang
melakukan kesepakatan untuk melanggar terbuka lebar. Andai tidak
terbuka, pasti ada jalan lain menerobos lantaran pengalaman yang
cukup dan keterlibatannya dalam budaya itu sudah membumi.
Proses pengawasan (controlling), merupakan proses
meminimalisasi kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi yang tidak
efektif serta keluar dari tujuan. Intinya, fungsi pengawasan adalah
menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan. Pada tataran normatif, proses pengawasan tentu dilakukan
dengan melibatkan orang-orang ahli dalam bidang kepengawasan.
Karenanya, kompetensi kepengawasan tidak diragukan lagi. Apakah
para pengawas berani memberikan sanksi, bagi orang-orang yang
terlibat kesepakatan melanggar?
Negeri kita, konon negara hukum. Semuanya harus dibuktikan
secara autentik sehingga tidak dapat memberikan sanksi dengan serta
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 259
merta. Optimalisasi fungsi perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengawasan tentu akan mewujudkan tujuan yang
dirumuskan. Dalam konteks penerimaan CPNS, maka tujuan utama
terseleksinya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yakni orang-
orang yang memiliki kompetensi andal sesuai dengan bidang
tugasnya.
MBO
Opini publik yang berasumsi bahwa untuk menjadi CPNS
harus membayar, tidak boleh menjadikan para penyelenggara
emosional. Justru, opini tersebut perlu dijadikan bahan renungan
sekaligus self evaluation.
Dalam teori manajemen, sebenarnya ada satu paradigma yang
setidaknya dapat mengurangi keraguan publik terhadap rekrutmen
CPNS, yakni Management By Objective (MBO). Reddin (1971)
mengatakan bahwa inti dari MBO adalah mengelola suatu kegiatan
berdasar sasaran yang ingin dicapai.
Walaupun agak otoriter lantaran tidak mengenal kompromi,
MBO merupakan senjata ampuh menyeleksi SDM berkualitas.
Artinya, apabila orang-orang yang mendaftar CPNS tidak sesuai
kriteria ditetapkan, tidak dapat diterima walaupun berani membayar
puluhan juta rupiah.
Secara sederhana, apabila proses rekrutmen CPNS tidak
menjadi tanda tanya publik, terapkan MBO dengan memberikan
hasil tes yang dikerjakan peserta secara transparan. Semua peserta
tanpa kecuali, berhak mengetahui hasil tes yang dikerjakan sehingga
tidak menimbulkan tanda tanya ketika yang bersangkutan tidak
diterima. Langkah ini juga memperkecil gerak munculnya
kesepakatan melanggar.
Untuk merekrut SDM berkualitas, juga dapat memberikan
bobot setiap aspek seperti tingkat pendidikan, indeks prestasi, lama
260 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
mengabdi, tes akademik, dan domisili peserta. Selama ini, yang
sering dilakukan hanyalah mengumumkan daftar peserta lolos seleksi
tanpa diikuti perolehan nilai. Padahal, salah satu fungsi penilaian
adalah mengetahui sejauh mana peserta menguasai bahan yang
diujikan sekaligus menjadi feed back terhadap kekurangannya.
Beranikah penyelenggara mengumumkan hasil tes semua peserta?
Kelak, hal tersebut harus berani dicoba. Bila perlu, mulai
sekarang. Bukankah kita tidak akan membiarkan negeri terpuruk?
Bukankah semua sepakat bahwa kita membutuhkan SDM
berkualitas?
Pro dan kontra terhadap kebijakan adalah hal biasa, lantaran
proses itu merupakan pendewasaan berpikir. Oleh karena itu, ada
baiknya pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) dalam proses
rekrutmen CPNS positive thinking, saling bekerja sama dan
mengingatkan akan tujuan utama yakni menyeleksi insan-insan
berkualitas agar bersama-sama dapat membangun negeri tercinta ini.
Trimo, S.Pd., kepala sekolah di Kabupaten Kendal, mahasiswa
pascasarjana Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
―dimuat di koran Wawasan, Selasa Wage 4 November 2003.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 261
GURU DI TENGAH FENOMENA KRITIK
Oleh Trimo
Saat berdiskusi dengan teman-teman seprofesi mengkaji
berbagai fenomena peningkatan mutu pendidikan, penulis diserang
habis-habisan lantaran memberi pernyataan kekuranggigihan guru
dalam mengembangkan kompetensi personal, profesional, dan
kemasyarakatan.
Berbagai fenomena kritik yang penulis lontarkan tentang
ketidakberdayaan guru juga diamini teman-teman guru. Bahkan,
dianggap cocok mewakili kondisi guru saat ini. Fenomena kritis yang
dihadapi guru merupakan refleksi kejenuhan dan kebingungan dalam
menanggapi ide-ide ideal pemerintah (Depdiknas).
Sekadar mengingatkan bahwa di sekolah muncul hampir
bersamaan berbagai inovasi pembelajaran, seperti: (1) Pembelajaran
aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), (2)
Pembelajaran portofolio, (3) Pembelajaran kontekstual, dan (4)
Pembelajaran model quantum learning dan quantum teaching, dan
berbagai model pembelajaran inovatif lain.
Jika dikaji mendalam, semua model pembelajaran bernuansa
inovatif bermuara pada pentingnya keterlibatan siswa secara aktif
pembelajaran. Proses pembelajaran baru tersebut identik dengan
pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) tempo dulu, hanya
berbeda pengemasannya.
Fenomena Kritik
Bukan bermaksud menempatkan guru pada sudut sempit
penuh debu dan tak leluasa bernapas, jika ada asumsi sederhana
bahwa guru masih belajar memaknai interaksi. Bahkan, belum bisa
berubah dalam konteks pentingnya penerapan inovasi pembelajaran.
262 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Semua guru tahu dan mengerti mengglobalnya dunia dengan
segala pengaruh yang ditimbulkan. Ironisnya, ada kecenderungan
guru kurang tanggap berbagai perubahan. Guru hanya mencukupkan
dirinya untuk tahu tetapi enggan menelaah mendalam.
Ada guru yang sinis terhadap inovasi tetapi suka mengangguk
tanda setuju tanpa mengkaji mendalam makna anggukan tersebut.
Demikian juga, guru lebih senang ngegerundel saat datang
perubahan tanpa mencerna makna perubahan tersebut.
Ada guru yang lebih suka menggunakan LKS (baca: Lembar
Kesengsaraan Siswa) tanpa melalui proses pembelajaran bermakna.
Dengan LKS, materi pelajaran bisa diselesaikan sekejap.
Ada guru yang lebih senang menggunakan ancaman untuk
mengingatkan siswa daripada menerapkan teknik-teknik profesional
saat dididik jadi guru. Padahal guru sudah mempelajari teori
pemberian reward dan memahami bahwa memberikan reward bagi
siswa merupakan kewajiban tidak bisa ditinggalkan.
Ada guru yang lebih bangga menjadi satu-satunya sumber
belajar tanpa berpikir perlunya berinteraksi dengan makhluk lain di
luar dirinya. Menjadi pewarta materi dengan siswa duduk tenang
tanpa perlawanan, sering menjadi kebanggaan. Padahal keterlibatan
siswa dalam proses pembelajaran merupakan conditio sine qua non
atau mutlak dilakukan.
Ada guru yang lebih senang menyimpan alat peraga secara
rapi daripada memanfaatkan alat tersebut untuk kepentingan proses
pembelajaran. Padahal guru sudah mempelajari teori perkembangan
kognitif Piaget dan memahami dari zaman dulu bahwa pembelajaran
dengan alat peraga lebih bermakna daripada pembelajaran kering.
Ada guru yang lebih senang melakukan manipulasi data,
khususnya dalam pengerjaan nilai. Apalagi pengerjaan rapor dalam
kurikulum berbasis kompetensi. Dalam konteks ini, konon guru tidak
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 263
perlu dilatih karena sudah memiliki keterampilan memanipulasi yang
diperoleh dari pengamatan dan pengalaman turun temurun.
Ada guru yang lebih menggunakan sesuatu produk
pembelajaran bersifat instan daripada berlatih mendesain sendiri
sebagai tanda aktualisasi kompetensi guru.
Ada guru yang tidak mau belajar membuat karya ilmiah dan
memilih golongannya mentok di IVA sehingga merasa bebas
administrasi. Ada guru yang menggunakan siswanya sebagai objek
les privat dan memberikan perhatian khusus bagi siswa yang
mengikuti les privatnya.
Ada guru lainnya yang dapat dikaji mendalam, yang bermuara
pada kurangnya peduli terhadap pendidikan dalam konteks mikro
(pembelajaran) dan makro (pendidikan anak negeri).
Namun, di antara yang kurang peduli terhadap pendidikan
setidaknya masih banyak guru yang peduli walaupun kapasitasnya
belum optimal. Ironisnya, sistem penggajian di Indonesia bukan
berdasar pada kegigihan guru dalam mendesain pembelajaran
bermakna, tetapi lebih menghargai masa kerja.
Kondisi tersebut tentu rentan permasalahan. Seorang guru
yang menerapkan pembelajaran secara teacher centered tidak akan
berpengaruh terhadap gaji yang diterima dibanding guru yang
mengajar secara student centered.
Keterampilan Dasar Mengajar
Sanjungan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa agaknya
menjadikan guru lebih bangga terhadap profesi mulia tersebut.
Apalagi, batas sanjungan tersebut sangatlah tipis. Artinya, orang
tidak akan membedakan sanjungan tersebut terhadap guru yang
peduli terhadap pendidikan dan yang kurang peduli.
Rutinitas umum yang sering dilakoni guru adalah mengajar.
Dalam konteks mengajar inilah sebenarnya orang dapat memaknai
264 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
seorang guru peduli terhadap pendidikan atau tidak. Setidaknya guru
yang peduli terhadap pendidikan dalam konteks mikro perlu
menguasai keterampilan dasar mengajar.
Lantaran menuju satu muara pembelajaran yang bermakna,
maka segala bentuk model inovasi pembelajaran tentu berpulang
pada kreativitas guru. Karenanya, kita perlu membekali keterampilan
dasar mengajar guru. Hal ini sangat penting lantaran semua model
pembelajaran terkini tidak akan mampu diterapkan apabila guru tidak
menguasai keterampilan dasar mengajar. Turney (1973)
mengemukakan 8 (delapan) keterampilan dasar mengajar.
Pertama, keterampilan bertanya yang mensyaratkan guru
harus menguasai teknik mengajukan pertanyaan cerdas, baik
keterampilan bertanya dasar maupun lanjut.
Kedua, keterampilan memberi penguatan. Karena penguatan
merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian.
Ketiga, keterampilan mengadakan variasi, baik dalam gaya
mengajar, penggunaan media, dan bahan pelajaran, pola interaksi
dan kegiatan.
Keempat, keterampilan menjelaskan yang mensyaratkan guru
merefleksi segala informasi sesuai kehidupan sehari-hari.
Setidaknya, penjelasan harus relevan dengan tujuan materi, sesuai
kemampuan dan latar belakang siswa, serta diberikan pada awal,
tengah, ataupun akhir pelajaran sesuai keperluan.
Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran.
Dalam konteks ini, guru perlu mendesain situasi yang beragam
sehingga kondisi kelas menjadi dinamis.
Keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Hal terpenting dalam proses ini adalah mencermati aktivitas siswa
dalam diskusi.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 265
Ketujuh, keterampilan mengelola kelas, mencakupi
keterampilan yang berhubungan penciptaan dan pemeliharaan
kondisi belajar optimal, serta pengendalian kondisi belajar optimal.
Kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan, yang mensyaratkan guru agar mengadakan pendekatan
pribadi, mengorganisasikan, membimbing dan memudahkan belajar,
serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Penerapan keterampilan dasar mengajar secara holistik
setidaknya dapat dijadikan cermin bagi guru untuk melakukan efikasi
diri dan kontekstual. Efikasi diri berkaitan dengan keyakinan guru
akan kemampuan mendesain pembelajaran bermakna. Efikasi
kontekstual bermuara pada pentingnya guru memiliki kesadaran
hakiki akan keterbatasan kemampuan dalam menerapkan proses
pembelajaran bermakna di kelas.
Empat Pilar Pendidikan
Dalam konteks penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(Kurikulum 2004) dan sejalan pemberlakukan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP), konsep pembelajaran bermakna erat
kaitannya empat pilar pendidikan yakni: belajar mengetahui
(learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup
bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri
(learning to be).
Konsep learning to know mensiratkan makna bahwa pendidik
harus mampu berperan sebagai informator, organisator, motivator,
direktor, inisiator, transmiter, fasilitator, mediator, dan evaluator bagi
siswanya, sehingga peserta didik perlu dimotivasi agar timbul
kebutuhan informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu yang
ingin dikuasai.
Konsep learning to do mensiratkan bahwa siswa dilatih untuk
sadar dan mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif
266 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Terkait hal tersebut,
proses pembelajaran perlu didesain aplikatif agar keterlibatan peserta
didik, baik fisik, mental, dan emosionalnya dapat terakomodasi
sehingga mencapai tujuan diharapkan.
Learning to live together merupakan tanggapan nyata terhadap
arus individualisme serta sektarianisme yang makin menggejala
dewasa ini. Fenomena ini bertalian erat dengan sikap egoisme yang
mengarah pada chauvinisme pada peserta didik sehingga
melunturkan rasa kebersamaan dan menghargai.
Sedangkan konsep learning to be, perlu dihayati praktisi
pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percara
diri (self confidence) tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama
bagi siswa untuk hidup bermasyarakat.
Mengantisipasi berbagai fenomena kritik, ada baiknya guru
melakukan efikasi diri dan kontekstual sehingga memiliki semangat
konservatif tinggi dan terbebas dari titik kejenuhan.
Oleh karena itu, berpikir divergent dalam memaknai berbagai
fenomena kritik perlu dilakukan guru agar mampu menempatkan hati
nuraninya ke satu titik kesadaran tinggi, yakni kesadaran
memberikan yang terbaik untuk anak-anak negeri Indonesia.
__dimuat di koran sore Wawasan, 30 April 2005.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 267
MENGGAGAS SEKOLAH MODEL
Oleh Trimo
Ketika berdiskusi dengan beberapa teman guru yang notabene
suka mengkritisi berbagai kebijakan inovasi pendidikan, kami saling
beradu argumen mengenai wujud nyata dari serangkaian kebijakan
yang pernah digulirkan pemerintah.
Gunjingan kami yang sempat memanas tersebut lantas
menyepakati tidak adanya kesinambungan antara harapan pemerintah
(dalam hal ini Depdiknas) dengan kenyataan di lapangan (dalam hal
ini sekolah). Sekadar mengingatkan, pemerintah pernah
mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, education
for all school based management yang dibarengi dengan sejumlah
inovasi pembelajaran menggunakan kata berbasis (pendidikan
berbasis masyarakat, pendidikan berbasis internet, kurikulum
berbasis kompetensi, penilaian berbasis kelas, dan lain-lain), dan
berbagai program inovasi lain yang bermuara pada peningkatan mutu
pendidikan.
Yang agak aktual adalah penerapan kurikulum berbasis
kompetensi yang dimasyarakatkan dengan sebutan kurikulum 2004.
Serangkaian permasalahan penerapan KBK kemudian menjadi
selubung yang dimainkan cantik oleh stakeholders pendidikan, tanpa
terkecuali. Proses pembelajaran bermakna dan integrasi penilaian
yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor menjadi ciri
khas penerapan KBK. Sudahkah demikian?
Aplikasi Gagasan
Pengisian rapor ala KBK dengan angka puluhan dengan
sederet komponen membingungkan guru bisa menjadikan derita
berkepanjangan. Simak saja pengisian rapor KBK siswa SD. Setiap
mata pelajaran memiliki lebih dari satu komponen yang harus dinilai.
268 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Secara keseluruhan seorang guru SD harus mengisi 26 komponen
nilai puluhan yang tersebar ke-8 mapel.
Tidak hanya itu, guru SD harus melakukan penilaian kualitatif
setidaknya 9 aspek yang meliputi kedisiplinan dan tanggung jawab,
kebersihan dan kerapian, kerja sama, kesopanan, kemandirian,
kerajinan, kejujuran, kepemimpinan, dan ketaatan. Lantas muncul
pertanyaan sederhana, bagaimana guru SD mampu melakukan
penilaian tersebut?
Agaknya pemerintah sudah menyiapkan seperangkat antisipasi
manakala menggulirkan gagasan inovatif dengan menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bertajuk peningkatan mutu. Sosialisasi
hasil penataran, workshop, studi banding, dan sejenisnya menjadi
program unggulan tatkala gagasan baru mengemuka.
Secara proses, penyampaian gagasan inovatif sudah
dilaksanakan sesuai program dan berjenjang sampai tataran
pelaksana lapangan. Griffin dan Mooehead (1986) mengatakan
bahwa gagasan inovatif akan terwujud apabila ada perubahan
persepsi, suasana, dan makna. Ketiga hal tersebut perlu dipahami
guru dengan merefleksi diri khususnya dalam menerapkan
pembelajaran bermakna.
Persoalan yang muncul kemudian adalah pada tahap aplikasi.
Ada kecenderungan stakeholders pendidikan kurang memberikan
respons positif terhadap upaya pembaruan tersebut. Masih segar
dalam ingatan kita, penerapan School Based Management di sekolah-
sekolah negeri. Sudahkah gagasan otonomi sekolah tersebut
merakyat? Atau hanya jadi slogan kebanggaan? Adakah konsukensi
logis terhadap sekolah yang belum dan enggan menerapkan berbagai
inovasi pendidikan?
Beberapa daerah memaknai berbagai upaya peningkatan mutu
pendidikan beragam. Dalam konteks pembelajaran yang bernuansa
KBK di pendidikan dasar, ada daerah yang menyatakan siap
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 269
melaksanakan KBK, tta ada juga sebagian yang belum siap
menerapkan KBK setelah melakukan analisis SWOT. Daerah yang
belum menerapkan KBK tentunya belajar dari daerah yang sudah
menerapkan KBK. Yang menjadi bahan renungan adalah apa yang
akan diperoleh saat belajar dari daerah-daerah cerdas kalau
pemaknaan terhadap KBK belum holistik?
Sekolah Model
Bagai buah simalakama, itulah sebenarnya potret berbagai
inovasi pendidikan yang digulirkan pemerintah. Satu program belum
dievaluasi komprehensif, sudah muncul program lain. Ironisnya,
guru dipaksa mengatakan keberhasilan setiap program dengan
dukungan data yang berbeda realita.
Ibarat membangun rumah, kita mulai dari sudut ruangan. Saat
ruangan itu belum selesai, kita harus membangun sudut ruangan lain
secara bersama. Begitulah seterusnya, sampai kita lupa sudut
ruangan yang belum selesai dibuat lantaran roboh.
Perumpaan di atas setidaknya dapat dijadikan refleksi para
penyelenggara pendidikan untuk merumuskan pemikiran cerdas agar
konsep-konsep inovasi pendidikan dapat diterapkan secara benar.
Menurut penulis, salah satu alternatif yang dapat dilakukan
penyelenggara pendidikan untuk menjembatani ketimpangan inovasi
pendidikan khususnya di Sekolah Dasar adalah pembentukan sekolah
model. Ide dasar konsep ini dilandasi pemikiran bahwa guru mudah
terkejut manakala mengetahui keberhasilan suatu inovasi pendidikan.
Kulminasinya, guru melakukan studi banding. Apa yang hendak
dibandingkan kalau guru sendiri belum mencoba menerapkan?
Sekolah model dapat dibentuk di setiap kecamatan dengan
memperhatikan berbagai hal, di antaranya kondisi fisik sekolah,
ketersediaan sarana prasarana, siswa, guru, kepala sekolah, dan
komite sekolah. Setiap kecamatan, tentunya ada salah satu SD yang
270 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
memenuhi kriteria tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan untuk membentuk Sekolah
Model, yakni:
Pertama, menentukan SD yang letaknya strategis. Penentuan
lokasi juga memperhatikan kondisi fisik, ketersediaan sarana
prasarana pembelajaran, dan jumlah siswa ideal (40 siswa per kelas).
Langkah ini dimaksudkan memudahkan transportasi dan komunikasi.
Selebihnya, sekolah lebih terkonsentrasi menerapkan inovasi.
Kedua, mengatur tenaga pengajar. Tempatkan guru-guru yang
memiliki idealisme, dedikasi, dan komitmen tinggi dalam
menjalankan tugas. Dalam konteks ini, mutasi perlu dilakukan agar
sekolah yang dijadikan model didukung sumber daya berkualitas.
Ketiga, merekrut kepala sekolah cerdas dalam melaksanakan
perannya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor,
leader, inovator, dan motivator. Optimalisasi peran kepala sekolah
tentunya akan mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan.
Menempatkan kepala sekolah yang berani menindakkritisi setiap
fenomena aktual dalam bidang pendidikan dengan aktivitas nyata,
perlu dilakukan agar terjadi konsistensi antara harapan dan
kenyataan.
Hasil penelitian Gibson (1988) menunjukkan bahwa
keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan banyak
ditentukan kapasitas kepala sekolahnya, di samping guru-guru yang
memiliki komitmen tinggi dalam tugas.
Keempat, mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai
badan pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting
agency), pengawas (controlling agency), dan badan mediator
(mediator agency) berbagai kebijakan pendidikan. Hal ini perlu
dilakukan karena ada kesan bahwa komite sekolah masih sama
dengan BP3 tempoe doeloe. Pelibatan komite sekolah secara nyata
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 271
dalam kegiatan sekolah akan mendukung terwujudnya sekolah model
yang nantinya menjadi pusat mutu (center for excellence).
Serangkaian langkah dalam perumusan Sekolah Model bukan
harga mati. Namun, setidaknya empat komponen tersebut komponen
paling dominan dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan
mutu pendidikan.
Menata Sistem
Terwujudnya Sekolah Model akan mengurangi keterkejutan
guru akan keberhasilan inovasi pendidikan. Konsekuensi logis
Sekolah Model adalah dijadikannya ujicoba berbagai inovasi
pendidikan. Di Sekolah Model inilah, gagasan ideal berbagai inovasi
dilaksanakan. Dengan demikian, guru-guru tidak perlu bersusah
payah studi banding ke daerah lain apabila di Sekolah Model sudah
menerapkannya.
Bila guru bertanya dan hendak belajar mengenai pembelajaran
bermakna ala KBK, Sekolah Model mampu memberikan
pencerahan. Berkembangnya Sekolah Model di tiap-tiap kecamatan,
secara evolusif membantu pemerintah meningkatkan mutu
pendidikan.
Tentu untuk mencapai Sekolah Model dalam kondisi ideal
memerlukan penahapan panjang. Seperti dikemukakan Supriadi
(2002) bahwa orang yang mendalami teori difusi inovasi akan segera
tahu bahwa setiap perubahan atau inovasi dalam bidang apa pun,
termasuk pendidikan, memerlukan tahap-tahap yang dirancang benar
sejak ide dikembangkan hingga dilaksanakan.
Mewujudkan Sekolah Model sebagai grass root dan pioneer
penerapan inovasi pendidikan tidak semudah membalik telapak
tangan. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian menata sistem
pendidikan secara holistik. Setidaknya gagasan sederhana ini dapat
272 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
dicoba di setiap kecamatan agar ketidakjelasan output dan outcome
dari penerapan inovasi pendidikan dapat termentahkan.
__dimuat di harian Suara Merdeka, 9 Mei 200).
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 273
KAPAN NEGERI KITA BEBAS BUTA AKSARA?
Oleh Trimo
Program pemberantasan buta aksara dilaksanakan pemerintah
Indonesia sejak tahun 60-an. Akan tetapi, sampai saat ini masih
banyak anggota masyarakat Indonesia yang buta aksara. Hasil Survei
Penduduk Antar Sensus (Supas) yang dilaksanakan BPS tahun 1996
menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang buta aksara kurang
lebih sejumlah 5,9 juta jiwa. Sedangkan data sasaran program
pemberantasan buta aksara di Jawa Tengah tahun 2003 adalah
772.767 warga belajar (Dikmas Jateng 2003).
Sebenarnya pemerintah sudah berupaya melakukan
peningkatan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, bagi
warga belajar buta aksara dengan berbagai program, antara lain
Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Program Kejar Paket A, B, dan C.
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menerapkan
pendekatan keaksaraan fungsional dalam mengatasi pemberantasan
buta aksara. Keaksaraan fungsional merupakan pendekatan atau cara
mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan
menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung
(calistung) yang didasarkan pada kebutuhan, minat, pengalaman
hidup sehari-hari, serta memanfaatkan potensi yang ada di
lingkungan sekitar.
Namun demikian, proses pelaksanaan uji coba program
keaksaraan fungsional juga belum dipantau optimal lantaran
terbatasnya anggaran di tingkat kabupaten yang rata-rata tiap
kelompok hanya dipantau 3 bulan sekali. Bahkan ada beberapa
kelompok yang belum sempat dipantau proses pembelajarannya.
Kurangnya pemantauan ini juga mengakibatkan kurang bimbingan
teknis kepada tutor dalam melaksanakan proses pembelajaran.
274 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Lantas pertanyaan sederhana muncul: sebenarnya apa yang
terjadi dengan program-program pengentasan buta aksara?
Buta Aksara
Jika merefleksi perihal buta aksara, tentunya yang menjadi
sorotan adalah masyarakat. Hal ini lantaran mereka yang menjadi
sasaran buta aksara adalah masyarakat. Karenanya, orientasi
pengentasan buta aksara harus berbasis masyarakat. Artinya,
masyarakat harus dijadikan subjek dalam proses pengentasan buta
aksara.
Osborne (1998) mengatakan bahwa pendidikan senantiasa
memilih jalan pembebasan yang arahnya melahirkan masyarakat
mandiri dan kreatif. Pendidikan berbasis masyarakat (community
based education) memang dicanangkan pemerintah. Watson (1991)
mengemukakan tiga elemen dalam pendidikan berbasis masyarakat,
yakni: (1) Mementingkan warga belajar, (2) Program dimulai dari
perspektif kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan
dasar masyarakat, dan (3) Pembangunan masyarakat yang
menekankan bahwa program belajar harus beralokasi di masyarakat.
Lagi-lagi, program tersebut sepertinya tidak banyak diketahui
masyarakat. Bahkan, masyarakat pun masih berasumsi negatif
terhadap pembiayaan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan angka
buta aksara cukup memprihatinkan. Data laporan akhir tahun 2004
yang dikeluarkan Dinas P dan K Jateng sungguh memprihatinkan.
Data tersebut menunjukkan jumlah buta huruf di Jateng mencapai
3.621.341 orang atau sekitar 11% dari penduduk Jateng. Dari jumlah
itu, 2.875.294 orang merupakan kelompok masyarakat berusia 45
tahun ke atas. Disusul kelompok usia 10-44 tahun yang jumlahnya
mencapai 746.047 orang.
Laporan tersebut sekaligus mendukung hasil penelitian yang
dilakukan Arif (2003) mengenai analisis kebutaaksaraan di Indonesia
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 275
dan upaya penanggulangannya. Penelitian tersebut menyimpulkan
ada tiga daerah yang angka buta aksaranya termasuk rendah, yakni
Sulawesi Utara (3,3%), Jakarta (4,08%), dan Maluku (4,1%).
Sementara itu, daerah buta aksara yang termasuk tinggi adalah Papua
(27,84%), Nusa Tenggara Barat (22,06%), dan DIY (18,51%). Upaya
penanggulangan buta aksara dilakukan dengan gerakan massal dan
menggunakan sistem penyampaian berupa kursus maupun kelompok
belajar.
Sekadar mengingatkan bahwa buta aksara wanita (17,23%)
lebih besar daripada buta aksara laki-laki (8,3%) baik di perdesaan
maupun perkotaan (BPS, 1990). Penuntasan buta aksara menjadi
melek aksara 100% adalah suatu target ideal (teoretis) yang sulit
dicapai karena banyak faktor memengaruhi. Target ideal dapat
dicapai apabila semua provinsi sudah mencapai target 100%.
Buta aksara bagai duri dalam daging di pembangunan
umumnya, dan dunia pendidikan khususnya. Karenanya salah satu
kebijakan jangka menengah pembangunan pendidikan nasional
(2004-2009) adalah menurunkan jumlah penduduk buta aksara.
Persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan seluruh komponen
yang mendukung keberhasilan program tersebut?
Team Work
Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk
mengurangi buta aksara.
Pertama, refleksi dan evaluasi berbagai program yang
dilakukan. Keberhasilan suatu program merupakan fondasi
merumuskan kebijakan serupa pada tataran makro. Sementara
kekurangberhasilan suatu program perlu dilakukan identifikasi
kendala-kendalanya. Seperti kendala-kendala pelaksanaan program
pendidikan berbasis masyarakat, di antaranya: kurangnya anggaran
pelaksanaan, budaya menunggu masyarakat, dan sikap birokrat yang
276 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
belum menunjukkan pelayanan prima layaknya total quality
management.
Kedua, komitmen tinggi dari stakeholders pendidikan. Dalam
konteks ini perlu dibentuk team work (together yakni kebersamaan,
empathy artinya saling merasakan, assist yaitu membantu, maturity
artinya bersikap dewasa, willingness yakni kemampuan saling
memberi dan mengerti, organization artinya tertata dan terkelola
baik, respect berarti saling menaruh rasa hormat, dan kindness
artinya suatu iktikad baik). Ibarat sistem, delapan kata kunci tersebut
merupakan satu kesatuan kuat untuk mengoptimalkan program
pengentasan buta aksara.
Ketiga, pengawasan bersama antara keluarga, sekolah, dan
masyarakat sebagai wujud aplikasi konsep tri pusat pendidikan.
Menanamkan pentingnya pendidikan keluarga perlu dilakukan sejak
dini agar anak-anak melek huruf. Setidaknya agar mereka mampu
menguasai tiga kemampuan dasar yakni membaca, menulis, dan
berhitung.
Anak-anak yang buta huruf juga bisa diakibatkan lantaran
putus sekolah. Karenanya, sekolah perlu mencermati anak-anak yang
orang tuanya kurang mampu. Sejalan program pemerintah yang
diberikan sekolah yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
tentunya tidak akan ada lagi alasan putus sekolah di dunia
pendidikan dasar hanya persoalan tidak mampu membiaya sekolah.
Demikian juga masyarakat perlu mengamati keberadaan anak-
anak usia sekolah di lingkungannya. Tokoh masyarakat (termasuk
tokoh agama, adat, dan pendidik) berperan sebagai pemprakasa,
mediator, movitator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai
penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemprakasa,
perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 277
fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana,
pembina kegiatan, dan pemecah masalah.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu diperankan
sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat,
pendamping masyarakat, pengembang, penyedia dana dan teknologi,
informasi pasar, dan penyedia tenagga ahli, dan pengelola program.
Setidaknya tiga hal tersebut merupakan inti dari pentingnya
pemberdayaan stakeholders pendidikan dalam rangka mengatasi
berbagai persoalan krusial khususnya terkait program pengentasan
buta aksara. Semua warga negara berkewajiban memberikan
sumbangsih sesuai kemampuan dan keterketukan hati nurani.
Ada baiknya hari aksara tahun ini dijadikan momentum
pembangkitan kesadaran bagi stakeholders pendidikan baik sebagai
individu maupun komunitas masyarakat tertentu untuk lebih peduli
mengentaskan buta aksara. Penulis yakin kebersamaan stakeholders
pendidikan dalam mengentaskan buta aksara akan menuai hasil
memuaskan di masa datang.
Trimo, S.Pd., M.Pd., Kepala Sekolah di Kab. Kendal, Dosen Luar
Biasa IKIP PGRI Semarang
―dimuat di koran Wawasan, 8 September 2005.
278 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
GELISAH SEKOLAH DALAM SELIMUT BOS
Oleh Trimo
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan pemerintah.
Kegelisahan selama penantian dengan berbagai upaya gali lubang
tutup lubang untuk mencukupi kebutuhan sekolah, seakan-akan
terbayar oleh kucuran dana dari program pendidikan spektakuler
berskala nasional, yakni BOS. Walau saat ini, program tersebut baru
dirasakan dunia pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
Dunia pendidikan SD/MI/SDLB/Salafiah/sekolah keagamaan
non-Islam setara SD memperoleh Rp235.000,00/ siswa/ tahun.
Sementara tingkat pendidikan
SMP/MTs/SMPLB/Tsanawiah/sekolah keagamaan non-Islam setara
SMP mendapatkan dana Rp324.500,00/siswa/tahun. Pada tahun
anggaran 2005, pemerintah mencairkan dana BOS untuk periode
Juli-Desember terlebih dulu.
Sekadar mengingatkan, di antara sekian banyak persoalan
yang mendasari munculnya program BOS adalah rendahnya
partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin, lantaran
tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak
langsung. Biaya langsung, seperti iuran sekolah, buku, seragam, dan
alat tulis. Sementara biaya tidak langsung meliputi transportasi,
kursus, uang saku, dan biaya lain-lain.
Walaupun pemerintah melakukan berbagai upaya yang
bermuara pada peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan, tetapi
tampaknya belum mampu mengurai berbagai persoalan pendidikan
tataran makro. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan
Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk Bantuan Khusus Murid
(BKM), tetap saja belum mampu mengantisipasi banyaknya anak
yang tidak mampu mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 279
Data Balitbang Depdiknas (2003) menunjukkan 693,7 ribu
orang (1,7%) anak usia 7-15 tahun belum pernah sekolah, dan 2,7
juta orang (6,7%) anak mengalami putus sekolah. Secara kumulatif,
jumlah siswa putus sekolah dalam kurun waktu dua tahun terakhir
mencapai 1,39 juta untuk jenjang SD/MI, dan 535,7 ribu untuk
jenjang SMP/MTs, serta 352,6 ribu untuk jenjang SMA/SMK/MA.
Sekolah Gelisah
BOS diluncurkan. Persoalan-persoalan krusial yang terkait
mahalnya biaya pendidikan, tentu lambat laun mereda. Jika
diidentifikasi, setidaknya permasalahan BOS berasal dari sekolah,
orang tua, dan masyarakat.
Sekolah yang tidak transparan dalam mengelola keuangan dan
terkesan kucing-kucingan dengan badan pengawas merupakan
indikator awal munculnya permasalahan. Berbagai pungutan yang
dilegalkan sekolah dengan dalih dana BOS tidak mencukupi, seakan-
akan menjadi fenomena tersendiri. Kewajiban siswa membeli buku
paket oleh sekolah, LKS, dan iuran-iuran insidental makin
menambah bingung orang tua dan masyarakat mengenai
pemanfaatan dana BOS.
Munculnya BOS, bagi sebagian orang tua dan masyarakat
seakan-akan mengurai pemikiran adanya sekolah gratis. Memang, di
beberapa sekolah perdesaan dampak BOS sangat terasa. Namun, di
sekolah perkotaan yang acapkali mendagangkan sekolah tentu sangat
berbeda. Munculnya BOS, setidaknya memangkas perdagangan
terselubung di sekolah, seperti fee dari penerbit buku, LKS, dan
barang-barang cetakan lain. Inilah sebenarnya, kegelisahan sekolah
ketika pemerintah mengucurkan dana BOS. Sekolah benar-benar
gelisah campur takut.
Bayangan tim pengawas yang mencerca berbagai pertanyaan
terkait BOS, penyiapan data-data pendukung, menyamakan persepsi
280 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
guru, orang tua, dan masyarakat sampai pada ancaman penjara bagi
kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOS seakan-akan
menjadi prolog sekaligus epilog dalam tidur stakeholder pendidikan.
Jika dikelola profesional, kucuran dana BOS yang disalurkan
pemerintah secara langsung melalui rekening sekolah sudah cukup
bahkan melebihi kebutuhan sekolah yang dianggarkan RAPBS tahun
sebelumnya. Sungguh luar biasa apabila sekolah mampu memetakan
dana BOS sesuai aturan main yang gencar disosialisasikan. Sekolah
tidak akan lagi gelisah hanya persoalan dana.
Apalagi, pemerintah membuka keran untuk sekolah apabila
dana BOS tidak mencukupi. Persoalannya adalah masih banyak
sekolah yang memungut dana tanpa melalui proses komunikasi
multiarah.
Peningkatan terhadap kinerja sekolah merupakan conditio sine
qua non oleh sekolah. Setidaknya, ada empat komponen yang perlu
dimaknai mendalam, yakni kepala sekolah, guru, siswa, dan komite
sekolah. Ibarat sebuah sistem, keempat komponen tersebut saling
berkaitan mewujudkan kinerja sekolah dalam tataran mikro dan
peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro.
Kinerja Sekolah
Patricia King (1993) dalam bukunya Performance Planning $
Appraisal, A How-to Book for Manager mengemukakan bahwa
kinerja adalah aktivitas seseorang melaksanakan tugas pokok yang
dibebankan kepadanya.
Mengacu dari pandangan ini dapat diinterpretasikan bahwa
kinerja sekolah sangat erat kaitan dengan peran kepala sekolah
sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader,
inovator, dan motivator (emaslim).
Dalam konteks pemberian dana BOS, maka kepala sekolah
perlu mengoptimalkan ketujuh peran tersebut secara holistik dan
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 281
profesional. Mengalirnya dana BOS tentu rentan sekali terhadap
persoalan, apabila kepala sekolah tidak transparan mengelola
keuangan. Peran kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru
ke arah yang lebih baik mutlak diperlukan. Peningkatan kualitas
pembelajaran yang bermakna merupakan muara dari kinerja guru.
Hal tersebut lantaran dana BOS dapat dimanfaatkan untuk
buku pelajaran pokok dan buku penunjang perpustakaan serta biaya
peningkatan mutu guru seperti kegiatan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), pelatihan, dan
sejenisnya.
Melalui dana BOS, mutu guru harus ditingkatkan. Setidaknya
dapat mengubah angka persentase guru yang layak mengajar. Masih
segar dalam ingatan, uji kelayakan mengajar guru yang dilakukan
Balitbang Depdiknas (2002) cukup memprihatinkan. Dalam skala
nasional, hanya 49,49% guru SD yang layak mengajar jika dilihat
dari tingkat pendidikan minimal D2. Sementara untuk SMP 66,33%
guru dinyatakan layak mengajar dilihat dari tingkat pendidikan
minimal D3. Untuk klasifikasi serupa di Provinsi Jawa Tengah, guru
SD yang layak mengajar (62,57%) sedangkan SMP (68,78%).
Setidaknya bantuan pemerintah melalui program BOS
diharapkan mampu meningkatkan mutu guru sebagai agen
pembelajaran. Tentunya pengembangan kompetensi guru menjadi
program utama selaras pemberlakuan PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan yakni pengembangan kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Selebihnya, tersedianya dana BOS akan menepis berbagai
kritik keberadaan guru, seperti guru LKS, sinis inovasi, suka
serbainstan, dan kritik lain. Kritik tersebut akan mengkristal dan
menjadi kekuatan guru untuk meningkatkan kinerja menjadi guru
profesional, yaitu guru yang mampu: (1) Menguasai kurikulum, (2)
Menguasai materi semua mata pelajaran, (3) Terampil menggunakan
282 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
multimedia pembelajaran, (4) Memiliki komitmen tinggi terhadap
tugas, (5) Memiliki kedisiplinan dalam arti seluas-luasnya.
Yang kadang luput dari sorotan publik adalah kinerja siswa,
perlu dilakukan secara terprogram. Wardiman Djojonegoro (1996)
mengatakan berbagai pembekalan yang diberikan guru kepada siswa
pada hakikatnya untuk menginternalisasikan tiga nilai dasar yakni:
(1) Membentuk siswa agar memiliki orientasi masa depan bercirikan
luwes, tanggap perubahan, dan memiliki semangat inovasi, (2)
Hasrat mengeksploitasi lingkungan dan kekuatan alam, (3) Memiliki
orientasi terhadap karya bermutu.
Internalisasi tiga nilai dasar tersebut, perlu difokuskan pada
kinerja siswa dalam hal kemampuan baca, tulis, dan hitung atau yang
lebih dikenal tiga kemampuan dasar yakni the skills of reading,
writing, and arithmetic.
Prioritas ini cukup beralasan, lantaran hasil evaluasi Bank
Dunia terhadap tiga kemampuan dasar cukup memprihatinkan.
Untuk siswa SD hanya menguasai 36,1% dari materi yang diujikan
dan berada pada peringkat 26 dari 27 negara yang disurvei,
sementara siswa SMP menguasai 51,7%.
Melalui dana BOS, beban siswa akan kewajiban membayar
iuran sekolah dan membeli seperangkat buku pelajaran setidaknya
berkurang. Karenanya, peningkatan kinerja siswa menjadi agenda
utama dalam konteks pembelajaran agar dapat meningkatkan
persentase tiga kemampuan dasar.
Kolaborasi antara siswa dengan guru dalam mencerna materi
pelajaran sangat dimungkinkan sebagai ajang akulturasi kinerja.
Guru melaksanakan kinerjanya secara profesional dan siswa
menunjukkan kompetensinya sebagai wujud aktualisasi kinerja yang
dilakukan.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 283
Komite Sekolah
Pemberdayaan kinerja komite sekolah dalam kerangka BOS
merupakan langkah preventif kemungkinan pengawasan anggaran.
Pro dan kontra mengenai komite sekolah akhir-akhir ini merupakan
peluang sekaligus tantangan bagi komite sekolah untuk meningkatan
kinerja.
Cairnya dana BOS memberi kesempatan kepada komite
sekolah untuk melakukan pengawasan kolaboratif dengan pihak tim
monitoring, selaras salah satu perannya sebagi pengontrol
(controlling agency). Apabila peran tersebut tidak berfungsi, dapat
dipastikan keberadaan komite sekolah hanya pelengkap penderita.
Ada baiknya stakeholder yang terkait BOS melakukan sosialisasi
komite sekolah sehingga ada pemahaman sinergis ketika publik
membincangkan BOS.
Jika selama ini ada kesan keberadaan komite hanya
dimanfaatkan sekolah untuk mencari dana, munculnya program BOS
dapat dijadikan momentum komite sekolah untuk memperbaiki
kinerja. Setidaknya komite sekolah lebih berani berbicara kepada
sekolah dan memiliki inovasi kerja sehingga tidak sendika dhawuh
dengan sekolah.
Dana BOS dikucurkan pemerintah. Ini berarti kegelisahan
sekolah menjadi fenomena aktual yang selalu menarik untuk
dibincangkan. Hal tersebut wajar-wajar saja sebagai pendewasaan
berpikir sekaligus dinamika kehidupan dalam dunia pendidikan.
Yang terpenting adalah stakeholder pendidikan perlu cermat
dalam menyikapi kemungkinkan munculnya pluralisme memaknai
BOS. Apabila dana BOS tidak mampu meningkatkan kinerja kepala
sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah, akan menjadi preseden
buruk bagi dunia pendidikan.
284 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Trimo, S.Pd., M.Pd., Kepala SDN 1 Magelung Kendal dan Dosen
Luar Biasa IKIP PGRI Semarang
―dimuat di koran sore Wawasan 17 November 2005.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 285
DAFTAR PUSTAKA
Budihardjo, Eko. 2010. “Paguyuban”. Gayeng Semarang.
Harian Suara Merdeka. Edisi 16 Maret 2010.
Fajarini, Ulfah. 2014. “Peranan Kearifan Lokal dalam
Pendidikan Karakter”. Jurnal Sosio Didaktika; Vol. 1, No.
2. (online).
http://journal.uinjkt,ac,id/SOSIOFITK/article/viewFile/
1225/1093. Diunduh 28 Agustus 2018.
G.S., Prie. 2013. Bubur Skotel. (online).
http://priegs.blogspot.com/2013/07/bubur-skotel.html.
Diunduh 28 Agustus 2018.
Haryanto, Joko Tri. 2013. “Kearifan Lokal Pendukung
Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger
Malang Jatim”. Jurnal Analisa. Vol. 21 No. 02. Desember
2014, halaman 201-213.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.web.id/
https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku 4,
Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan bagi Guru Pembelajar. Jakarta: Dirjen GTK
Kemdikbud.
286 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku 5,
Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan guna Mendukung
Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP).
Jakarta: Dirjen GTK Kemdikbud.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Ratna, Nyoman Kutha. 2011. Antropologi Sastra: Peranan
Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ramlan, M. 2008. Kalimat, Konjungsi, dan Reposisi dalam
bahasa Indonesia. Yogyakarta: Universitas Sanata
Dharma.
Suseno, Slamet. 2007. Teknik Penulisan Ilmiah Populer, Kiat
menulis Nonfiksi untuk Majalah. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Tantiningsih, R. “Mencari Ibu dalam Ijazah”. Koran
Wawasan. Edisi Kamis Pon, 22 Desember 2005.
Trimo. 2011. “Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah,
Pemberian Vitamin D Masihkah Berlaku?” Koran Sore
Wawasan. Edisi 14 Mei 2001.
Wibowo, Agus. 2015. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan
Lokal di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 287
TENTANG PENULIS
Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Karanganyar, 25 Oktober 1975.
Menempuh pendidikan di TK Pertiwi
Sumberejo (1982), SD Tawangsari 2
Kerjo (1988), SMPN 2 Kerjo (1991),
SMAN 1 Kerjo (1991), D2 PGSD IKIP
Negeri Semarang (1997), S1 PGSD
Universitas Negeri Semarang (2008),
dan menyelesaikan studi S2 Pendidikan
Dasar di Univeristas Negeri Semarang (2012). Mengawali
kariernya sebagai pegawai negeri sipil (guru) di SDN
Anjasmoro (sekarang SDN Tawang Mas 01) Semarang
(2005). Tahun 2018 memperoleh kepercayaan sebagai
Kepala SDN Kembangsari 01 Semarang.
Di sela-sela aktivitasnya sebagai pengajar, ibu rumah
tangga, dan beroganisasi, ibu yang rajin membaca ini masih
menyempatkan menulis karya ilmiah sebagai wujud
pengembangan profesi. Menikah dengan Trimo tahun 1995.
Dikaruniai tiga orang buah hati, yakni Harum Sunya Iswara
(1997), Yonna Aparacitta (2002), dan Rakyan Maharaja
Krishna (2009). Kelihaiannya menulis mendapat dukungan
dari sang suami yang juga aktif di dunia kepenulisan.
Beberapa karya yang sudah diterbitkan: Buku Ajar Bahasa
Indonesia Kelas VI (Penerbit Pemkot Semarang, 2006), Buku
Bina IPS Kelas III, V, VI (Penerbit Gajah Mada Jakarta, 2008),
Buku Senandung Belajar IPS (2012), Novel Langit Masih Cerah
Candra (Penerbit Iranti Mitra Utama Surabaya. 2012), Novel
Mutiara Menggandeng Awan (Penerbit Pelita Hati Surabaya,
288 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
2012), Penantian Rara-Kumpuan Cerita Pendek- (Penerbit
Dapur Buku Jakarta, 2014), 149 Jam di Perancis (2015), Belajar
di Negeri Kanguru (2016), dan Buku Pelajaran Suluh Basa
Jawa Kelas I-VI (Penerbit Duta Bandung, 2016).
Berbagai kejuaraan di bidang karya ilmiah pernah
ditorehkan dan pada tahun 2009, ibu yang aktif di berbagai
organisasi ini berhasil meraih predikat Juara 1 Guru
Berprestasi SD Tingkat Nasional (2009), juara 1 Lomba
Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional (2014), dan juara 2
Lomba Kreativitas Guru Tingkat Nasional (2015), juara 1
Lomba artikel (feature) Tingkat Nasional (2017), dan juara 1
Lomba Keluarga Sukhinah Teladan Tingkat Nasional (2018).
Pernah mendapat kesempatan studi ke Prancis (2015) dan
Australia (2016).
Saat ini aktif membantu Dinas Pendidikan Kota
Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Literasi.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 289
Trimo, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Boyolali, 28 Agustus 1970. Tidak
pernah merasakan belajar di TK, tamat
SDN Juwangi II (1982), SMPN Juwangi
(1985), SPGN Semarang (1988), D2
PGSD IKIP Negeri Semarang (1992), S1
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Unnes (2002), S2 Manajemen
Pendidikan Unnes (2004).
Mengabdikan diri menjadi guru sejak tahun 1993.
Sepuluh tahun kemudian menjadi Kepala Sekolah di
Kabupaten Kendal, dan pada tahun 2015 kembali menjadi
guru belajar bersama anak-anak negeri. Pernah menjuarai
berbagai kejuaraan tingkat nasional, di antaranya juara I
Kepala Sekolah Dasar Berprestasi (2011), juara 2 Sayembara
Penulisan Buku Pengayaan (2011), dan lain-lain. Menekuni
dunia kepenulisan sejak kuliah, menjadikan beberapa karya
pernah terbit, di antaranya buku-buku pelajaran (bahasa
Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Jawa) yang
diterbitkan beberapa penerbit, buku bidang pendidikan,
sastra, dan budaya, serta berbagai tulisan ilmiah populer di
media massa. Pernah menjadi duta Indonesia dalam
kegiatan Child Right, Classroom and Scholl Management di
Swedia dan Ethiopia. Saat ini aktif membantu Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama
dalam bidang kurikulum, PPK, dan literasi.
290 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku tulisan ilmiah populer untuk kenaikan pangkat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search