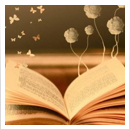dimaksudkan agar terjadi keakraban antara pembina dan anggota
Pramuka sehingga terjadi interaksi terbuka dan jujur. Dalam kondisi
seperti ini muatan edukatif dapat disampaikan kepada anak didik,
dapat juga ditanamkan berbagai sifat dan perilaku penting yang perlu
dimiliki generasi muda kita. Sikap dan perilaku penting itu bahkan
dapat dicarikan dari isu mutakhir yang sering terjadi pada kehidupan
generasi muda.
Jika pesan itu berhasil, gerakan Pramuka dapat menunjang
pendidikan di sekolah dalam menanamkan berbagai nilai positif bagi
kehidupan generasi muda. Dengan demikian, pendidikan berbasis
Pramuka akan mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan
masyarakat dengan senang hati akan mendukung. Apalagi jika
kegiatan Pramuka mampu membangkitkan siswa dalam mengukir
prestasi, niscaya makin menjadi idola kalangan masyarakat luas.
Tentu gagasan tersebut sesuai tema peringatan HUT Pramuka ke-47
yakni: “Dengan semangat kebangkitan nasional kita pacu
perkembangan gerakan Pramuka”. Dirgahayu Pramuka Indonesia
semoga tetap jaya.
__dimuat di koran sore Wawasan, 15 Agustus 2008.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 143
CITRA GURU MASA KINI
Oleh R. Tantiningsih
Sosok Ibu Guru Muslimah dalam Film Laskar Pelangi sangat
menyentuh hati. Dengan penuh kasih ia didik murid-muridnya, ia
terima semua kelebihan dan kekurangan murid-murid tersebut. Ia
mengajar penuh kelembutan dan dedikasi tinggi.
Dalam kebimbangan ia mampu menjadi motivator bagi para
muridnya. Ketika murid membutuhkan ilmu ia menjadi
transformator. Ketika harus menggali kreativitas murid ia menjadi
fasilitator. Ketulusan dan kreativitas Ibu Guru Muslimah dalam
mendidik para murid merupakan pelajaran berharga yang patut
diteladani, khususnya bagi kaum guru.
Seperti apa pun perubahan zaman dan perkembangan
teknologi, ketulusan mengabdi seorang guru tetap diperlukan demi
masa depan putra-putri bangsa. Walaupun zaman berubah, teknologi
makin maju, peradaban berkembang, nilai-nilai keluhuran budi harus
tetap dipertahankan. Seorang pendidik berkewajiban menumbuhkan
nilai-nilai kehidupan, budi pekerti, dan norma-norma pada murid-
muridnya.
Guru sebagai sosok digugu lan ditiru. Dari pameo tersebut
tersirat pandangan serta harapan masyarakat terhadap seorang guru.
Dalam kedudukan seperti itu guru tidak hanya sebagai pengajar di
kelas, tetapi juga tampil sebagai pendidik di sekolah maupun
masyarakat. Harapan ini akan menjadi rancu manakala ada oknum
guru yang menyimpang dari norma-norma berlaku. Masyarakat
menjadi ragu memercayakan pendidikan putra-putrinya kepada guru.
Bagaimana agar citra guru tetap menempati hati masyarakat?
Bukan hal mudah menjadi guru yang benar-benar guru, menjadi
anutan masyarakat, mampu mengabdi dengan tulus. Oleh karena itu
144 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
dalam rangka menyambut hari guru ke-63 kiranya para guru wajib
merenung, introspeksi diri, agar menjadi guru yang mempunyai citra
di masyarakat.
Kompetensi Guru
Kualitas guru belakangan ini banyak diragukan berbagai
kalangan. Persoalan-persoalan menyangkut generasi muda selalu
dikaitkan dengan kualitas guru yang pernah mendidiknya. Jika ada
siswa tawuran, narkoba, berutal, guru yang pertama disalahkan.
Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya
meningkatkan mutu dan profesionalisme guru sesuai amanat
perundang-undangan guru dan dosen. Berbagai upaya ini antara lain
dengan melakukan pelatihan, peningkatan pendidikan bergelar,
sertifikasi, dan pemberian tunjangan profesi guru (sambutan Menteri
Pendidikan Nasional pada Majalah Suara Guru edisi khusus Hari
Ulang Tahun PGRI ke-63). Hal ini adalah bentuk perhatian
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan citra para guru di
hati masyarakat.
Profesi guru yang dulu dipandang sebelah mata berangsur-
angsur mulai diperhitungkan kembali oleh masyarakat. Guru yang
dulunya hanya dikenal sebagai tukang mengajar kini anggapan itu
kian terkikis, sebab untuk menjadi guru harus memiliki empat
kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Kompetensi guru juga tertuang pada Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang
menyatakan bahwa guru perlu menguasai 4 kompetensi, yakni
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 145
Realitas di lapangan, 4 kompetensi tersebut belum seluruhnya
dikuasai para guru. Sebagai contoh pengembangan kurikulum, guru
enggan membuat Program Tahunan (Prota), Program Semester
(Promes), silabus bahkan sampai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP). Guru lebih senang copy paste perangkat pembelajaran yang
sudah ada tanpa mencermati lebih dalam kekurangan dan kelebihan
perangkat tersebut. Dalam bidang teknologi guru juga belum banyak
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pembelajaran. Banyak guru yang masih gaptek (gagap teknologi)
sehingga tidak pernah memanfaatkan internet untuk memperoleh
berbagai informasi dibutuhkan.
Tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas belajar wajib
dilakukan guru. Kegiatan ini tecermin dalam Penelitian Tindakan
Kelas ((PTK). Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru akan
lebih baik jika ditulis dalam bentuk karya tulis PTK. Selain untuk
memperbaiki kualitas belajar siswa, memperbaiki kualitas
pengajaran guru, juga melatih guru berpikir ilmiah. Tujuan bagus ini
tidak didukung semua guru, lantaran mereka merasa kesulitan
menyusun karya tulis, merasa tidak mampu, tetapi juga tidak mau
belajar.
Guru memang profesi mulia, kepribadiannya pun juga harus
mulia. Walaupun masih ada oknum guru menentang hukum. Bahkan
berita-berita di koran sering memuat tindak asusila yang dilakukan
oknum guru. Guru yang semula harus menjadi anutan akhirnya
menjadi bahan hinaan masyarakat. Guru yang seperti inilah yang
mencoreng citra guru.
Upaya Pemerintah
Berbagai upaya meningkatkan kualitas guru sudah dilakukan
pihak-pihak berkepentingan. Kegiatan tersebut antara lain: berbagai
bentuk pelatihan, seminar guru-guru mulai dari tingkat gugus hingga
146 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
nasional sering diselenggarakan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan
kualitas guru. Harapannya para guru memperoleh wawasan luas
dalam mengembangkan karier sehingga ilmu-ilmu yang diperolehnya
mampu diterapkan di tempat ia bekerja. Guru tidak statis, selalu
memperoleh dan mengembangkan ilmu.
Ajang bergengsi untuk guru juga digelar setiap tahun di
antaranya lomba keteladanan guru, keteladanan kepala sekolah,
lomba keberhasilan guru, dan sejenisnya. Dengan kegiatan-kegiatan
kompetitif tersebut akan mendorong guru meningkatkan kualitasnya,
selalu berinovasi, memberikan semangat dalam melaksanakan tugas.
Sehingga kompetensi guru benar-benar teruji di ajang perlombaan
tersebut.
Fasilitas belajar mengajar yang diberikan pemerintah juga
merupakan sarana meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran.
Fasilitas tersebut akan sangat membantu guru dalam menjalankan
tugasnya seperti gedung sekolah, alat peraga, buku-buku, beasiswa,
dan sebagainya. Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila
berlangsung optimal. Pembelajaran akan optimal apabila sarana dan
prasarana tercukupi. Oleh karena itu fasilitas belajar mengajar sangat
urgent keberadaannya.
Sertifikasi bagi guru merupakan bentuk perhatian pemerintah
meningkatkan kualitas, sebab persyaratan sertifikasi menggambarkan
kompetensi guru dalam menjalankan tugas. Guru yang memenuhi
syarat sertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesional. Dengan
program semacam ini para guru akan berlomba-lomba meningkatkan
kualitas diri dalam menjalankan tugas mengabdikan diri di dunia
pendidikan. Harus diakui bahwa seorang guru yang mendapat
sertifikat dalam proses sertifikasi harus mampu menunjukkan kinerja
lebih optimal. Benarkah demikian? Sebuah pertanyaan yang patut
ditindakkritisi dengan merumuskan seperangkat instrumen penilaian
untuk menilai kinerja guru yang sudah tersertifikasi.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 147
Sebagai kado HUT Guru ke-63 agaknya kita wajib
merenungkan kata-kata William Arthur Ward, “Guru biasa memberi
tahu, guru baik menjelaskan, guru ulung memperagakan, dan guru
hebat mengilhami.” Jadilah guru hebat yang mampu mengilhami
siswa sehingga mereka pemproduksi, bukan pengonsumsi gagasan.
Guru hebat akan selalu dirindukan murid-muridnya. Pembelajaran
bermakna akan selalu ditunggu kehadirannya di sekolah. Ketulusan
pengabdian akan selalu dikenang di hati masyarakat.
Akhirnya, selamat hari guru, selamat berjuang!
__dimuat di koran sore Wawasan, 24 November 2008.
148 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
GEMAR MEMBACA LAHIRKAN KARYA
Oleh Rustantinigsih
Kegiatan untuk menumbuhkan kegemaran membaca, tidak
seperti membalik telapak tangan. Sekarang diperintahkan membaca,
kegemaran membaca tidak langsung bertumbuh. Salah satu kegiatan
menumbuhkan kegemaran membaca adalah membiasakan membaca
15 menit sebelum pelajaran dimulai sebagai upaya gerakan literasi.
Upaya menumbuhkan kegemaran membaca sudah penulis lakukan
melalui aktivitas membaca 15 menit. Namun, belum semua siswa
bertahan membaca sampai 15 menit. Ada sebagian siswa yang
bersendau gurau, bermain-main dengan peralatan sekolah, atau
hanya bengong saja sambil menunggu waktu selesai.
Kondisi ini akan lebih parah lagi jika buku-buku yang tersedia
di sudut baca kurang menarik, terbatas jumlahnya, dan tidak pernah
berganti. Siswa asyik dengan kegiatannya sendiri karena kegiatan
membaca yang diwajibkan penulis kurang menarik. Kurangnya
minat baca siswa juga disebabkan tidak ada kegiatan menantang dan
dinamika aktivitas belum terarah.
Ternyata menumbuhkan kegemaran membaca para siswa
perlu teladan dari guru. Ketika siswa wajib membaca, guru juga ikut
membaca. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa guru dan siswa
mempunyai kebutuhan sama akan kegemaran membaca yang
berdampak pada perolehan ilmu, wawasan, dan pengalaman baru.
Nah, bagaimana menumbuhkan kegemaran membaca bagi
para siswa bahkan hingga mampu menghasilkan karya? Tentu saja
butuh perjuangan dan komitmen kuat dari para guru sendiri. Apalagi
guru merupakan peramu kegiatan di kelas. Analoginya, guru itu
seorang koki, enak dan tidaknya makanan tergantung pada koki yang
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 149
menyiapkan semua bahan, meracik, mengolah, hingga menyajikan
hidangan.
Kreativitas guru dalam meramu kegiatan menumbuhkan
kegemaran membaca sangat diperlukan para siswa. Sentuhan-
sentuhan halus guru, hal-hal kecil yang mungkin luput dari
pengamatan guru selama ini, dapat dilakukan untuk menggerakkan
siswa supaya gemar membaca. Seperti yang kami laksanakan di
kelas VI SD Tawang Mas 01 Semarang, upaya menumbuhkan
kegemaran membaca melalui aktivitas Baliku, Kupuku, Samisaka,
dan Pakuku.
Baliku
Kegiatan membaca 15 menit bukan kegiatan rutinitas biasa,
tetapi istimewa. Penumbuhan kegemaran membaca yang penulis
lakukan di awal bersama siswa adalah kegiatan Baliku (Baca Lima
Belas Menit Buku). Untuk memulai membaca, guru tidak langsung
menyuruh siswa membaca, tetapi memberikan pemahaman dan
praktik secara langsung cara memperlakukan buku. Buku sebagai
sumber dari semua pengetahuan hendaknya diperlakukan istimewa.
Siswa diajari cara membawa, membuka, membatasi buku jika belum
selesai dibaca secara benar. Langkah ini memang sepele, tetapi perlu
guru tanamkan kepada siswa supaya tidak ada lagi siswa yang
menaruh buku dengan cara melempar, membuka buku dengan kasar,
melipat atau menekuk buku seenaknya, dan sebagainya.
Kegiatan yang tidak luput dari perhatian penulis adalah
mengenalkan identitas buku. Siswa wajib tahu dan paham identitas
buku. Selama ini siswa kalau membaca buku biasanya hanya melihat
sampul buku, judul, dan isi. Siswa mengabaikan pengarang,
penerbit, ilustrator, dan sebagainya. Padahal pengenalan identitas
buku itu sangat penting untuk siswa.
150 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Ketika siswa membaca buku dan mengetahui identitas buku
tersebut, mereka akan menghargai pengarangnya. Mereka akan
memahami bahwa buku tersebut lahir karena pemikiran orang-orang
kreatif, orang-orang hebat yang sudah berkarya dan karyanya
bermanfaat bagi orang banyak. Terbitnya sebuah buku tidak bisa
dilakukan sendiri oleh pengarang, tetapi mereka membutuhkan orang
lain, dalam hal ini kerja tim sehingga diperlukan kerja sama,
toleransi, atau diskusi. Di samping itu siswa juga memahami banyak
profesi di sekitar buku seperti menjadi pengarang, ilustrator, editor,
dan sebagainya.
Baru kegiatan selanjutnya adalah membaca selama 15 menit.
Buku yang mereka baca adalah buku-buku cerita anak, dongeng,
cerita rakyat, novel anak, dan sejenisnya yang diambil dari sudut
baca kelas. Khusus hari Kamis kami membaca buku majalah
berbahasa Jawa. Hal ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo setiap hari Kamis wajib menggunakan bahasa Jawa.
Buku yang kami baca bersumber dari perpustakaan sekolah, koleksi
guru, koleksi anak, atau sumbangan dari orang tua siswa. Makin
banyak buku tersedia, makin banyak yang dibaca siswa, akan makin
besar investasi karakter, pengetahuan, dan pengalaman unik yang
tertanam di hati siswa.
Bagaimana dengan kegiatan guru? Siswa membaca, guru
membaca. Buku-buku yang penulis baca berupa buku cerita fiksi,
biografi, atau kisah inspirasi. Hasil dari membaca, penulis ceritakan
kepada siswa, atau kadang penulis mendongeng di hadapan mereka,
sekaligus memberikan motivasi dan penanaman karakter.
Kupuku
Begitu siswa mulai tertarik buku, penulis bersama siswa ke
samudra lebih luas yaitu perpustakaan. Kegiatan Kupuku
(Kunjungan ke Perpustakaanku) di kegiatan awal penulis lakukan
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 151
dengan memberi kesan pertama menggoda. Kesan itu penulis awali
dengan memperkenalkan mereka dengan tata tertib perpustakaan,
kewajiban mengisi buku kunjungan, perkenalkan dengan letak buku,
cara menaruh buku jika sudah selesai dibaca, cara meminjam dan
mengembalikan buku kepada petugas. Semua itu dipraktikkan siswa
secara langsung.
Penulis juga memperkenalkan jenis-jenis buku fiksi dan
nonfiksi. Selanjutnya, penulis memberi siswa kebebasan menikmati
buku-buku di perpustakaan. Waktu yang membatasi mereka untuk
berkunjung menjadikan siswa merasa kurang dan ingin berkunjung
lagi. Selanjutnya siswa diberi kewajiban mengunjungi perpustakaan
minimal seminggu sekali.
Siswa yang rajin berkunjung untuk membaca atau meminjam
buku mendapat reward dari guru. Ternyata cara ini sangat tepat
penulis lakukan. Bahkan untuk beberapa waktu petugas perpustakaan
sampai kewalahan melayani. Akhirnya penulis menjadwalkan ada
yang berkunjung pagi dan ada juga yang siang.
Sami Saka
Makin banyak membaca, mereka makin merasa haus buku.
Penulis beri mereka kebebasan membaca di setiap kesempatan, saat
istirahat, saat ada waktu luang, atau di mana pun mereka berada.
Untuk mengembangkan pengalaman mereka dalam membaca buku,
penulis memberi tugas menulis Sami Saka (Satu Minggu Satu
Karya). Siswa wajib membuat karya satu minggu satu karya, karya
tersebut berupa puisi atau cerita. Cerita yang mereka tulis adalah
pengalaman kegiatan di sekolah dalam satu minggu paling berkesan.
Karya tersebut ada yang ditulis dengan menggunakan bahasa
Indonesia maupun bahasa Jawa.
Untuk memotivasi kemauan menulis, penulis mewajibkan
siswa membaca buku-buku karya penulis, di antaranya beberapa
152 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
kumpulan cerpen, novel, catatan perjalanan, kumpulan puisi, buku
pengayaan, dan buku-buku pelajaran. Buku-buku yang penulis susun
terinspirasi dari pengalaman belajar bersama siswa. Beberapa buku
yang penulis susun pernah memperoleh kejuaraan pada kompetisi
tingkat nasional.
Penulis tanamkan pada diri siswa bahwa semua orang bisa
berkarya. Seperti dikatakan Arswendo Atmowiloto dalam bukunya
„Mengarang itu Gampang‟ (2013) bahwa mengarang itu bisa
dilakukan anak-anak, remaja, orang tua, bahkan pensiunan. Seperti
naik sepeda atau berenang, sekali menguasai bisa seterusnya. Tak
akan lupa atau menjadi tidak bisa, yang diperlukan hanya mengenal
unsur-unsur mengarang.
Keabadian karya mereka akan menjadi moment spesial jika
penulis mampu memberi penghargaan. Semua karya siswa diberi
penghargaan. Salah satu cara adalah mengumpulkan karya terbaik
siswa, dalam satu jenis yang sama contohnya puisi atau cerita.
Kumpulan karya tersebut diketik. Selanjutnya diterbitkan dalam
bentuk buku. Selama penulis mengajar di kelas VI SD Tawang Mas
01, sudah menerbitkan tiga buku karya siswa yaitu kumpulan puisi,
kumpulan cerita pengalaman berbahasa Indonesia, dan kumpulan
cerita pengalaman berbahasa Jawa.
Kejutanluar biasa ini akan memberikan pelajaran bagi mereka
untuk menghargai hasil karya sendiri dan orang lain, menumbuhkan
rasa percaya diri, kebanggaan yang tak ternilai harganya, dan sebagai
kenangan yang akan selalu abadi. Kebanggaan juga tidak hanya
datang dari siswa tetapi juga dari orang tua, guru, dan sekolah. Di
samping itu buku karya tersebut akan menjadi tambahan koleksi
buku di perpustakaan sekolah maupun di sudut baca kelas.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 153
Pakuku
Pakuku (Pemeran Buku Koleksiku) merupakan kegiatan
menarik yang penulis lakukan bersama siswa. Jika selama ini siswa
hanya melihat pameran buku yang diadakan Dinas Pendidikan,
Pemkot, maupun toko-toko buku, penulis bersama siswa
mengadakan pameran buku di kelas. Pameran buku ini dilaksanakan
waktu jeda semester. Buku yang dipamerkan adalah buku-buku
koleksi siswa dan buku karya mereka yang sudah diterbitkan.
Pengunjung pameran siswa kelas lain.
Untuk menumbuhkan jiwa kompetisi sehat, pameran kami
selenggarakan secara menarik dengan mengikutkan semua siswa
secara berkelompok dan dilombakan. Setiap kelompok wajib
membawa buku-buku koleksinya dan mendesain stand pameran
secara kreatif. Kreativitas dan jumlah buku koleksi siswa yang
dipajang, dilombakan antarkelompok. Selain itu buku karya siswa
yang sudah terbit juga dipajang di pameran tersebut.
Kelas lain secara bergiliran mengunjungi pameran tersebut.
Siswa yang berkunjung diwajibkan menulis buku tamu atau buku
kunjungan. Mereka bebas melihat atau membaca buku-buku yang
dipajang. Untuk mengasah kemampuan siswa dalam keterampilan
bertanya dan menjelaskan, pengunjung bebas bertanya pada penjaga
stand, dan penjaga stand wajib memberi penjelasan kepada para
pengunjung.
Banyak hal yang dapat dipetik dari kegiatan pameran buku,
terutama dalam penanaman karakter dan penumbuhan gemar
membaca. Nilai-nilai karakter tersebut seperti menghargai karya,
berani memberi penjelasan kepada para pengunjung, kerja sama,
berkompetsisi sehat, dan mengembangkan kreativitas siswa.
Ternyata kegiatan ini sangat menarik tidak hanya siswa yang
merasakan manfaatnya tetapi juga para guru, selain sebagai ajang
kreasi siswa juga sebagai motivasi dan inspirasi bagi guru bahwa
154 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
kegiatan penumbuhan gemar membaca tidak hanya membaca 15
menit di kelas. Namun, bisa lebih dari itu, makin guru inovatif,
siswanya juga akan kreatif.
Penumbuhan gemar membaca dan berkarya seperti uraian
tersebut memang masih ada kendala yang harus dihadapi guru.
Kendala tersebut adalah sumber bacaan yang masih terbatas dan
tugas guru yang banyak perlu pengalokasian waktu tepat untuk
membimbing siswa melaksanakan kegiatan. Untuk itu perlu adanya
kerja sama berbagai pihak yaitu guru, kepala sekolah, orang tua, dan
siswa secara intensif.
Kegiatan membaca dan berkarya sebagai kesatuan yang tidak
bisa dipisahkan. Yakinlah dengan banyak membaca pasti akan
mampu berkarya! Bahkan ada ungkapan jika ingin hidup
membacalah, jika ingin hidup seribu tahun lagi menulislah! Semoga
tulisan ini akan mampu menumbuhkan jiwa dan komitmen untuk
mengembangkan budaya membaca dan berkarya.
Merupakan naskah juara 1 lomba artikel ilmiah tingkat nasional
tahun 2018.
__dimuat di
https://www.kompasiana.com/bundatanti/59d59d77b1eb1067ac72c2
42/gemar-membaca-lahirkan-karya?page=all).
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 155
PGSD DI UUNG DURI “LUNAK”
Oleh Trimo
Menggembirakan sekaligus mengharukan ketika saya
membaca tulisan Sdr. Rasmo di Krida Wiyata Maret 1993. Hal ini
terlontar karena saya termasuk alumnus proyek besar (baca: PGSD)
yang konon segera menerima beslit. Setelah penantian berbulan-
bulan, mahasiswa PGSD yang ada di Jawa Tengah (IKIP Semarang,
UNS, Satya Wacana) sempat diberi angin segar dengan
ditempatkannya mereka di tiga provinsi, yaitu Jateng, Bengkulu, dan
Sumatra Selatan.
Bukan bermaksud menjadi seorang dissident bila saya
berpendapat bahwa tes CPNS itu hanya pupuk bawang (baca:
pelengkap). Hal itu disebabkan sebelum tes berlangsung,
pengumuman penempatan sudah disebarluaskan. Jadi, hasil tes
tersebut tidak akan berpengaruh terhadap penempatan. Akan tetapi,
dengan perasaan bangga sebagai putra Indonesia, hal semacam itu
segera hilang ditelan kegembiraan. Bayangkan, berapa ribu tenaga
wiyata bakti yang sudah bertahun-tahun mengabdi sampai sekarang
belum mendapat giliran pengangkatan, dibandingkan dengan
keluaran PGSD angkatan ke-1 yang langsung ditempatkan.
Bukankah seperti ketiban pulung! Dengan berorientasi pada
kenyataan itu, maka tak sepantasnyalah bila mereka yang kebetulan
ditempatkan di luar Jawa harus melakukan “kudeta” terhadap
pemerintah.
Sebetulnya banyak sekali hal-hal aneh dalam proses
penempatan/pengangkatan. Hal ini bisa dimaklumi karena masing-
masing perguruan tinggi penyelenggara PGSD tidak bersama-sama
dalam merampungkan program. Untuk hal ini ternyata IKIP
Semarang paling awal mewisuda mahasiswa. Sementara yang lain
156 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
masih menyelesaikan PPL. Proses penyusunan berkas pengangkatan
yang dipermudah dan dipercepat sekaligus menjawab pertanyaan:
Kapan mereka diangkat dan ditempatkan?
Siap Pindah
Lontaran Sdr. Rasmo tentang adanya pendapat pro dan kontra
bagi mereka yang diangkat di luar Jawa, sungguh merupakan
masalah besar bila mereka yang karena suatu hal tidak mungkin
pindah ke luar Jawa. Hal ini terbukti dengan wajah-wajah kusam saat
usai wawancara dengan Kanwil daerah penerima.
Kondisi semacam itu menurut saya sangat wajar. Jadi bukan
masalah besar. Luapan emosi spontanitas itu memang harus terjadi.
Ibarat seorang yang diberi makanana asing, pada mulanya orang itu
tidak mau merasakan. Akan tetapi, setelah merasakan makanan itu
nikmat, lantas menghabiskan.
Sekarang kondisi kusam itu lama hilang terkubur di dasar
perasaan putra-putra Nusantara yang siap berbakti untuk Ibu Pertiwi.
Kini mereka yang akan diberangkatkan ke luar Jawa menyatakan
siap pindah pulau dan menjadi inovator pendidikan di daerah baru
sebagai pahlawan dengan bekal tekad dan semangat memajukan
pendidikan nasional.
“Tak ada kamus kusam dalam jiwa kami. Jawa dan luar Jawa
sama saja, di sini saya bisa hidup, di sana pun saya juga bisa hidup.
Malahan saya bisa nyambi jadi seorang petani.” Demikian idealisme
yang dilontarkan Priyanto mahasiswa PGSD IKIP Semarang yang
ditempatkan ke Sumatra Selatan.
Duri Lunak
Penantian realisasi pengangkatan yang kalau boleh saya
katakan “menyedihkan”, saat ini melanda ribuan mahasiswa keluaran
PGSD. Hal ini disebabkan sampai akhir April 1993 beslit (baca: SK)
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 157
yang ramai digunjingkan itu masih “bersembunyi”. Kata “sembunyi”
memang tepat sekali memberi pengertian kepada sang penanti. Kalau
bersembunyi artinya SK itu jelas sudah ada, tinggal menunggu kapan
keluarnya.
Atas dasar pengalaman mendadaknya panggilan, mereka
memilih menunggu di kediaman masing-masing. Walaupun
menunggu melelahkan, tetapi ketegaran dan ketabahan sebagai
seorang pahlawan tanpa tanda jasa mengalahkan sikap nglokro.
Duri lunak yang terbungkus empuk dalam bandeng presto
sehingga tidak terasa duri lagi itulah nantinya yang akan menjadi
makanan pokok bagi mereka yang ditempatkan ke luar Jawa. Luar
Jawa ibarat duri, tetapi durinya luar Jawa tidaklah tajam, malah
terasa empuk dan nikmat. Hal inilah yang harus dipegang dan
ditanamkan di hati sang pahlawan.
Semester Bonus
Menanggapi isu yang menjadi kenyataan bahwa angkatan ke-2
PGSD harus menempuh lima semester, menurut saya merupakan
program internalisasi teori. Semester bonus (baca: semester lima
yang dikhususkan untuk Praktik Pengalaman Lapangan) sangatlah
tepat dan beralasan. Apalagi matakuliah yang ada judulnya Mini dan
Micro Teaching relatif kecil. Hal ini dirasakan bagi mereka yang dari
SMA di mana sebelumnya tidak pernah mengenal SP, GBPP, dan
sejenisnya. Bagi mereka yang berasal dari SPG/SGO tidak begitu
masalah, hanya tinggal mengasah kembali kompetensi yang sudah
dimiliki, baik kompetensi personal, profesional, dan sosial.
Masalah efektif tidaknya semester bonus itu, akan terasa dan
terlihat nyata setelah selesai PPL. Dalam hal ini pemerintah tidak
hanya berpikir efektif saja, tetapi kualitas dari keluaran itu harus
ditingkatmantapkan. Dalam artian perlu adanya seperangkat
kurikulum terarah demi pencapaian tujuan (efektivitas) dan output
158 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
berkualitas yang mampu menjawab tantangan pendidikan dasar 9
tahun.
Permasalahan biaya yang dilontarkan Sdr. Rasmo memang
masalah biasa terjadi, dan hal ini bukan masalah baru yang berakibat
fatal. Jer basuki mawa bea, mungkin itu yang harus disadari. Sebab
tanpa biaya, perjalanan hidup manusia tidak akan pernah meningkat.
Sekarang lepas dari pergunjingan itu, marilah dengan wajah-
wajah ceria kita tatap masa depan bangsa, sebab di sana masih
banyak sekumpulan anak-anak kecil yang menanti uluran tangan
kita. “Ibu Pertiwi selalu menanti baktimu nan suci. Di sanalah aku
berdiri jadi pandu ibuku!” Selamat berkarya!
__dimuat di Buletin Krida Wiyata, Nomor:10/TH VIII/16-31 Mei
1993.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 159
SANG GURU DALAM ERA DIKDAS 9 TAHUN
Oleh Trimo
Beberapa bulan lalu, seluruh mahasiswa PGSD angkatan ke-1
ditempatkan. Hal ini tentunya merupakan kabar sangat
menggembirakan bagi mereka. Setelah penantian sekitar 10 bulan,
beslit yang masih bersembunyi itu muncul dengan sendirinya.
Ribuan mahasiswa PGSD yang ketiban wahyu itu kini menjalani
tugas sebagai guru SD, di wilayah Jawa dan luar Jawa. Pemerataan
penempatan itu selain untuk memenuhi kekurangan guru, juga
bermaksud menilai sejauh mana output PGSD memahami pengertian
pentingnya pemahaman wawasan Nusantara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya pemahaman
tersebut harus disadari bahwa di negeri ini masih banyak sekumpulan
anak-anak kecil yang menanti luruan tangan damai.
Tidak sekadar menerima gaji, mereka yang kini berstatus
Calon Pegawai (Capeg) harus mampu mengaplikasikan teori yang
pernah didapat dari bangku kuliah menuju inovasi pendidikan yang
makin tertata dan mantap. Dalam era iptek, peran seorang guru
sangatlah dominan, di samping peranannya di sekolah sebagai
organisator, komunikator, konduktor, motivator, direktor, pencetus
ide, moderator, dan ilustrator, guru juga dituntut berperan di keluarga
serta di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Era iptek adalah era pendidikan dasar (dikdas) 9 tahun.
Keduanya merupakan era bersejarah di negeri ini. Belum rampung
adanya keresahan di kalangan mahasiswa sehubungan perubahan
gelar kesarjanaan, negeri ini kembali diguncang persepsi berbeda-
beda mengenai dikdas 9 tahun.
Banyak masyarakat beranggapan bahwa dikdas 9 tahun sama
dengan SD 9 tahun. Anggapan itu tidak hanya mewabah di kalangan
160 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
masyarakat perdesaan yang konon cuma lulus dari “sekolah angka
loro” saja, tetapi sampai pada kaum elite intelektual. Usaha
mengantisipasi beda persepsi itu, pakar-pakar pendidikan berembuk
melalui penataran, seminar, dan sejenisnya. Akan tetapi di tangan
masyarakat, hasil-hasil seminar tidak lebih sebatas uraian teoretis.
Masyarakat lebih senang dengan sikap blaka suta daripada harus
memikirkan masalah birokrasi.
Melihat kondisi tadi, guru yang dipandang orang serbabisa
harus tampil sebagai sosok penyelaras. Apalagi guru SD yang
berpredikat D2 PGSD (baca: sang guru), yang dalam bahasa saya
masih kebul-kebul dengan ilmunya. Penyebutan guru dan sang guru
hanya untuk membedakan antara guru dari non-PGSD (baca: guru)
dengan guru dari PGSD, tidak bermaksud menganggap rendah dan
melecehkan guru.
Sang guru harus mampu hidup di tengah masyarakat dan
lambat laun menyelaraskan ketidaktahuan masyarakat mengenai
wajib belajar (wajar) pendidikan 9 tahun yang akan dicanangkan
Presiden Soeharto tanggal 2 Mei 1994, bertepatan dengan Peringatan
Hari Pendidikan Nasional, dengan bahasa yang mudah dipahami
tanpa menimbulkan pengertian baru.
Beban Mental
Bagi sang guru yang kebetulan ditempatkan di perdesaan
(baca: di SD yang belum terjangkau angkutan umum) tentunya ada
tanda petik yang merupakan beban mental dan PR. Lebih-lebih bagi
sang guru yang ditempatkan di luar Jawa. Besar kemungkinan sang
guru menganggap bahwa luar Jawa seperti duri. Akan tetapi menurut
saya, durinya luar Jawa sangat empuk dan nikmat. Ibaratnya duri
terbungkus dalam bandeng presto.
Di Kabupaten Kendal misalnya, dari 35 mahasiswa yang
ditempatkan sebagai besar sudah berkeluarga dengan anak-anaknya
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 161
yang masih kecil. Beban mental mulai terasa, memikirkan bakti
untuk negeri ini, memikirkan anak rewel, suami/istri, lokasi SD yang
jauh dari transportasi, ditambah beban administrasi dan memikirkan
beban lain yang belum tertata.
Walau dengan kondisi sangat memprihatinkan sekalipun,
wajah-wajah ceria dan tekad pengabdian untuk memajukan negeri ini
harus tetap berada di garis depan. Ibarat kesatria Gatotkaca yang
baru keluar dari kawah Candradimuka. Itulah sang guru. Sang guru
harus sanggup dan mampu secara berimbang memikul beban antara
era iptek dan era dikdas 9 tahun.
Konsekuensi Logis
Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar dikemukakan, “Pendidikan dasar merupakan
pendidikan umum yang lamanya 9 tahun diselenggarakan selama 6
tahun di SD dan 3 tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau
satuan pendidikan sederajat.”
Mengacu pada hal di atas, maka sang guru mempunyai
konsekuensi logis bahwa mereka disiapkan menjadi tenaga pengajar
yang dianggap mampu dan siap menghadapi era dikdas 9 tahun.
Konsekuensi itu tentunya tidak hanya berlaku bagi sang guru, tetapi
juga guru. Memahami konsekuensi itu, sang guru dan guru harus:
Pertama, memberikan pengertian kepada masyarakat atau
orang belum paham tentang wajar dikdas 9 tahun. Pendidikan dasar 9
tahun bukan SD 9 tahun, tetapi 6 tahun di SD dan 3 tahun SLTP atau
sederajat. Ini tidak berarti bahwa SD dan SLTP bergabung jadi satu
atap melainkan tetap terpisah. Penyebutannya juga tidak mengalami
perubahan, walaupun keduanya merupakan dikdas.
Kedua, menguasai 3 kompetensi guru: personal, profesional,
dan kemasyarakatan. Kompetensi itu tidak hanya teoretis, tetapi
harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan seorang guru sebagai
162 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
makhluk Tuhan, individu, dan sosial. Kompetensi ibarat pisau, makin
diasah tentu makin tajam dan sakti.
Ketiga, guru harus tahu iptek sebab sangat berpengaruh
terhadap laju pendidikan. Ini berarti makin cepat tingkat
perkembangan iptek, laju pendidikan harus membuntuti dengan
merekayasa iptek. Secara sederhana misalnya, guru harus bisa
mengetik, lebih baik lagi bisa menggunakan komputer sebagai teman
dalam menyampaikan materi pelajaran.
Keempat, guru seyogianya tidak mengekor dan menjiplak
satuan pelajaran (SP) yang sudah didrop (entah dari mana). Bila mau
mengaku jujur, kebanyakan guru-guru SD lebih suka meniru SP sakti
daripada membuat SP hasil pemikirannya sendiri. Kebiasaan ini
tentunya tidak baik walaupun secara lahiriah bisa membantu
meringankan beban administrasi dan stres, tetapi secara batin
seharusnya tidak tega dan malu. Bukankah guru selalu mengajari
muridnya untuk tidak meniru pekerjaan orang lain? Apalagi yang
namanya guru itu katanya digugu lan ditiru atau lebih idealisnya
gegulang undhaking rasa utama. Kalau sudah begitu, di mana letak
utamanya seorang guru?
SP sakti itu kalau diteliti secara cermat banyak kekurangan
dan kekeliruan. Contohnya dalam hal perumusan Tujuan
Instruksional Khusus (TIK), kadang tidak memenuhi kriteria A
(audiens), B (behaviour), C (condition), D (degree), dan E
(experience). Yang disebut terakhir yaitu E merupakan sumbang
pikir dari almarhum Drs. Waridjan, dosen IKIP Semarang.
Menggejalanya hal itu, tentu tidak akan berlanjut bila guru dan
sang guru mendalami hakikat SP sebagai senjata menyampaikan
materi pelajaran. Apalagi dalam era dikdas 9 tahun, guru yang
meniru SP sakti akan terjerumus ketidaktahuan perkembangan iptek.
Kemungkinan (maaf) kebanyakan guru merampungkan SP-nya
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 163
hanya untuk memenuhi kredit point, sedang kesehariannya masih
menggunakan SP sakti, toh keduanya seringkali sama persis.
Jadi, guru dan sang guru dalam era dikdas 9 tahun harus selalu
tanggap sasmita terhadap perkembangan iptek dan mempunyai
tanggung jawab membangun negeri ini.
Penulis adalah mantan mahasiswa PGSD IKIP Semarang. Kini
mengajar di SD Kedungsuren 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal.
—dimuat di Buletin Krida Wiyata, Nomor:10/TH VIII/16-31 Mei
1993.
164 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
SOSIALISASI KURIKULUM PGSD 1995
Oleh Trimo
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang
mendapat tugas dan wewenang menyelenggarakan program studi D2
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), tiap tahunnya dipadati
10.000 lebih lulusan SPG/SGO/SLTA yang berharap dapat diterima
di PGSD. Meningkatkan animo masyarakat terhadap program PGSD
yang merupakan satu-satunya lembaga pencetak guru SD, diperlukan
adanya pengetahuan dasar tentang kurikulum PGSD.
Tulisan ini akan melengkapi pemahaman masyarakat tentang
keberadaan PGSD, khususnya mengenai kurikulum di mana mulai
tahun akademik 1995/1996 baru disosialisasikan (baca:
dimasyarakatkan) mengacu pada kurikulum SD 1994.
Tahun 1995, merupakan tahun kelima pemerintah
menyelenggarakan program studi D2 PGSD, sebagai upaya
peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia
(SDM). Penyelenggaraan PGSD didasari atas Surat Keputusan
Mendikbud No: 0854/U/1989 tanggal 31-12-1989 tentang kualifikasi
formal guru SD. Secara kelembagaan, hal ini berarti adanya
semacam pengalihan tanggung jawab dari Dirjen Dikdasmen kepada
Dirjen Dikti.
Tahap pertama penyelenggaraan PGSD diawali September
1990, di mana Dirjen Dikti hanya memberikan wewenang kepada 10
IKIP Negeri (Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Medan,
Padang, Surabaya, Malang, Manado, dan Ujung Pandang); 2 IKIP
swasta (PGRI Malang, Muhamadiah Jakarta); 2 FKIP Universitas
Negeri (UNS, Udayana); 3 FKIP universitas swasta (UKSW
Salatiga, Nomensen Medan, Muhamadiah Ujung Pandang).
Sedangkan 27 FKIP lain ditugasi menyelenggarakan program ini
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 165
mulai tahun ke-2 dengan jumlah mahasiswa tiap angkatan sekitar
7.000 orang agar terhindar dari ledakan jumlah lulusan. Sementara
itu, bagi guru SD ber-NIP, disalurkan lewat program penyetaraan D2
PGSD baik di LPTK yang diberikan wewenang maupun melalui
Universitas Terbuka (UT).
Merasa Berat
Memang disadari, LPTK yang dibebani menyelenggarakan
program ini merasa berat, sebab pengembangan program dan
penyiapan infrastruktur pengembangan personel, baru dilakukan
pada saat bersamaan, ketika mahasiswa angkatan pertama sudah
mengikuti program. Jadi, seperangkat kurikulum akan diberikan
belum tertata dan tersusun sistematis. Ibaratnya, mengikatkan tali
sepatu sambil lari (bootstrapping approach).
Untuk mengantisipasi keadaan tadi, Dirjen Dikti dengan
bantuan dana Bank Dunia kemudian membentuk Tim Pengembangan
Program D2 PGSD yang meliputi bidang studi kependidikan,
pendidikan IPA, IPS, bahasa, matematika, seni, dan pendidikan
jasmani, yang secara kelembagaan diambil dari dosen-dosen senior
di LPTK penyelenggara PGSD. Agar lebih memantapkan dan
memberikan wawasan komprehensif terhadap dunia pendidikan
khususnya Pendidikan Dasar, maka tim yang dibentuk
diberangkatkan ke luar negeri bersama Tim Pengembang Program S2
Pendidikan Dasar.
Sosialisasi Kurikulum
Rasanya untuk menjadi guru, entah itu SD, SLTP maupun
SLTA, guru SD yang paling sarat beban tanggung jawab. Guru SD
harus mampu menjadi sosok serbabisa dalam segala bidang studi,
dibandingkan guru SLTP/SLTA yang hanya disyaratkan mengampu
satu jenis bidang studi.
166 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Satu hal yang patut menjadi bahan renungan, guru SD adalah
figur guru yang harus mampu memerankan diri sebagai apa saja.
Sebagai ayah/ibu, tokoh disegani, MA (baca: guru Bimbingan
Penyuluhan), seniman, tukang dongeng, pekerja kantor, bahkan
sebagai anak kecil sekalipun ketika dituntut peranannya di tengah-
tengah mereka.
Dari kriteria-kriteria khas tadi, maka program PGSD
dikembangkan sistematis berdasar seperangkat kecakapan yang
dimulai dari visi individu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga tercipta pilihan nilai maupun kondisi guru SD
yang tak pernah berakhir berkarya dan bertanya. Untuk mewujudkan
seperangkat kecakapan di atas, dari tahun ke tahun pelaksanaan
kurikulum PGSD dievaluasi.
Menurut Dirjen Dikti Bambang Soehendro, dari evaluasi
pelaksanaan kurikulum PGSD mulai tahun 1990 sampai 1994,
ternyata masih ditemukan beberapa komponen penting yang belum
dikurikulumkan sebagai sarana membekali calon guru SD tersebut,
sehingga mulai tahun 1995 kurikulum PGSD baru disosialisasikan
mengacu kurikulum SD 1994.
Selanjutnya, agar masing-masing LPTK dapat melaksanakan
kurikulum tersebut dan mengambil prakarsa pengembangan, serta
dapat digunakan uji lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan di
SD yang merupakan dasar dan sarana upaya pendidikan selanjutnya.
Sesuai kurikulum IKIP, struktur kurikulum PGSD terdiri atas
tiga komponen pokok yaitu Komponen Dasar Umum, Kependidikan,
dan Bidang Studi dengan beban akademik keseluruhan 78 SKS.
Komponen dasar umum, dimaksud mengembangkan sikap dan
wawasan membetuk nilai Pancasila dan ketakwaan terhadap Tuhan.
Mata kuliah ini terdiri atas 8 SKS meliputi: Pancasila, Pendidikan
Agama, dan Kewiraan.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 167
Komponen Dasar Kependidikan, diarahkan mengembangkan
wawasan kependidikan bagi calon guru SD yang akan menjadi
landasan pengembangan kompetensi personal, profesional, dan
kemasyarakatan dalam mengambil dan melaksanakan keputusan
pendidikan sejalan perkembangan kualitas SD maupun tujuan
pendidikan SD. Mata kuliiah ini terdiri 16 SKS meliputi: Landasan
Pendidikan SD, Perkembangan dan Belajar Peserta Didik,
Manajemen Kelas, Evaluasi Pengajaran, Bimbingan, dan Strategi
Belajar Mengajar.
Komponen Bidang Studi, merupakan komponen yang
menggambarkan tingkat penguasaan bahan ajar dalam artian
kemampuan menguasai isi bidang studi seleksi, pengorganisasian,
dan penyajian yang mampu membelajarkan murid SD secara
optimal. Mata kuliahnya terdiri 47 SKS meliputi: PPKn,
Keterampilan Dasar IPS, Pendidikan IPS di SD, Perspektif Global,
Konsep Dasar IPA, Pendidikan IPA di SD, Matematika,
Keterampilan Berbahasa, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di
Kelas Rendah dan Tinggi, Seni Rupa, Seni Musik dan Seni
Tari/Drama, serta Pendidikan Jasmani Kesehatan.
Ada lagi, 2komponen yang merupakan komponen pamungkas
dari keseluruhan teori-teori yang didapat, yaitu komponen
Pembelajaran Terpadu dan Pengalaman Lapangan. Komponen
Pembelajaran Terpadu terdiri 2 SKS merupakan proses pembelajaran
bidang studi terarah dan terpadu yang memungkinkan adanya
keterkaitan antarbidang studi sebagai wahana pengembangan
kepribadian anak.
Komponen Pengalaman Lapangan atau biasa disebut Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kulminasi seluruh program
PGSD. Dalam PPL, calon guru diharapkan mampu menampilkan
seluruh kecakapan dan kemampuan melaksanakan keseluruhan
tugas-tugas profesional di SD secara utuh dan nyata (school based).
168 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Mengingat pentingnya PPL, maka pelaksanaannya dilakukan khusus
pada semester lima.
Pelaksanaan kurikulum PGSD1 1995, masih memungkinkan
LPTK mengambil prakarsa dalam melengkapi seperangkat
kompetensi yang diharapkan dimiliki calon guru. Selaras dengan itu,
IKIP Semarang misalnya, selain menerapkan kurikulum PGSD 1995
juga ada tambahan mata kuliah yang tak kalah pentingnya yaitu
Studium Generale dan Pendidikan Kepramukaan.
Sumbang Saran
Alangkah baiknya, jika kurikulum PGSD 1995 yang tersusun
sistematis itu, diikuti kesiapan pemerintah dalam hal pengangkatan.
Barangkali konsep link and match lebih tepat. Hal ini dimaksudkan
agar tidak terjadi penumpukkan lulusan PGSD. Jika pemerintah
hanya “mencetak produk” saja tanpa dibarengi acuan “pemasaran”,
sudah pasti akan terjadi penumpukkan lulusan, seperti yang pernah
terjadi pada lulusan SPG/SGO beberapa tahun lalu.
Kejadian seperti itu tentu tidak diinginkan masyarakat, maka
untuk mengantisipasi kejadian ironis, pemerintah sejak dini perlu
menerapkan konsep link and match sehingga begitu mahasiswa
PGSD lulus, begitu pula SK pengangkatan mengikutinya.
Seperti yang dialami lulusan PGSD angkatan ke-1, kini
mereka semua ditempatkan tanpa kecuali baik di Jawa maupun luar
Jawa. Kesempatan dan kebijakan seperti itu tentu juga diharapkan
lulusan PGSD berikutnya yang sampai saat ini meluluskan angkatan
ke-3. Namun penempatannya masih bertahap di mana setiap tahap
memerlukan perencanaan matang. Yang jelas, semua lulusan PGSD
akan diangkat semua apalagi mulai 1 April 1994 pemerintah
mengeluarkan instruksi bahwa pengangkatan guru SD hanya lewat
jalur PGSD, tidak akan ada lagi pengangkatan guru SD berijazah
SPG/SGO. Setidaknya, instruksi tersebut memberikan angin segar.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 169
Untuk itu bersabarlah bagi mereka yang belum mendapat
kesempatan pengangkatan.
Selamat berjuang wahai sang guru, tumbuhkan semangat
tunas-tunas muda harapan bangsa, berkarya dan berjuanglah terus
majukan negerimu agar kelak menjadi negeri indah dan damai.
Trimo, alumnus IKIP Semarang, kini mengajar di SD Kedungsuren
04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
―dimuat di koran sore Wawasan, 8 Juli 199).
170 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
PGSD BAGAI BUAH SIMALAKAMA
Oleh Trimo
Keprihatinan Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
Slamet Haryanto terhadap ribuan lulusan PGSD yang belum
terangkat beberapa waktu lalu menarik sekali untuk dicermati dan
dicarikan alternatif pemecahan. Apalagi tahun ini PGSD yang
merupakan satu-satunya lembaga pendidikan pencetak guru SD,
sudah meluluskan angkatan ke-4, sehingga data keprihatinan dari
2.000 orang akan bertambah menjadi kurang lebih 3.500 orang.
Itu baru di Jawa Tengah, belum yang terjadi di provinsi lain.
Tentu keprihatinan serupa juga dirasakan Kadis P dan K seluruh
provinsi di Indonesia. Tulisan ini semoga menjadi bahan renungan
introspeksi dan retrospeksi pihak-pihak yang bertanggung jawab
terhadap program studi PGSD.
Dahulu, untuk menjadi guru SD syarat formal lulus SPG/SGO.
Mulanya pengangkatannya lancar, tetapi menginjak tahun 1985
mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan produk bertambah,
sedangkan formasi pengangkatan relatif kecil. Mengantisipasi
keadaan itu, pemerintah lewat Mendikbud mengeluarkan Surat
Keputusan No: 0854/U/1989 tentang kualifikasi formal guru SD dari
jenjang SLTA menjadi jenjang D2. Ini berarti syarat formal guru SD
harus lulusan PGSD.
Ada yang berpendapat kebijakan itu hanya mengulur-ulur
waktu pengangkatan walaupun maksud pemerintah meningkatkan
kualitas pendidikan terutama guru agar mempunyai cukup bekal
kompetensi, baik personal, profesional, dan kemasyarakatan menuju
abad ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemudahan-
kemudahan di berbagai bidang terutama teknologi informasi seperti
digambarkan Alvin Toffler dengan gelombang ketiganya.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 171
Pengangkatan
Penyelenggaraan PGSD dimulai September 1990, 3 tahun
kemudian tepatnya 1 Maret 1993 seluruh angkatan pertama
ditempatkan. Hal ini membuktikan keraguan dan pendapat bernada
minor tidaklah benar.
Angkatan kedua dimulai tahun 1991, mereka berharap agar
konsep link and match yang diterapkan pemerintah segera
direalisasikan. Namun harapan itu tidak seperti membalik telapak
tangan. Pengangkatan dilakukan tahap demi tahap di mana setiap
tahap membutuhkan waktu.
Belum lagi angkatan kedua terangkat semua, angkatan ketiga
merampungkan studinya dan hanya bisa menanti giliran
pengangkatan. Belum selesai penantian angkatan ketiga, kini
angkatan keempat juga sudah selesai. Lengkaplah sudah keprihatinan
mereka, menjadi seorang pengantre dari ribuan barisan pengantre.
Keadaan ini memang ironis sekali. Jujur, Slamet Haryanto
mengakui Jawa Tengah masih kekurangan 40.012 tenaga guru dan
penjaga SD. Pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak karena jatah
pengangkatan dari pusat setiap periode hanya beberapa ratus saja
sehingga untuk mengentaskan barisan pengantre memerlukan waktu.
Mereka yang sampai saat ini masih setia menjadi pengantre
kadang ada yang merasa tidak kuat berdiri dan kebanyakan dihantui
pertanyaan-pertanyaan tidak ada jawaban. Kapan mereka diangkat?
Apakah harus sesuai urutan pengantrean? Ataukah dimungkinkan
adanya terobosan agar bisa mendahului barisan di depan?
Mungkinkah bagi mereka yang usianya sudah berkepala tiga masih
memenuhi syarat formal diangkat? Dan sampai kapan mereka harus
menanti?
172 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Lebih Baik Ditutup
Agaknya pemerintah mengalami ketidaktepatan perencanaan.
Kemungkinkan besar lulusan PGSD akan bernasib sama dengan
lulusan SPG/SGO tempo dulu. Barangkali kita sependapat kasus
PGSD berkaitan dengan kemampuan pemerintah akan anggaran yang
belum memadai sehingga memerlukan proses pentahapan. Oleh
karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan seperangkat kondisi
guna mencari alternatif pemecahan. Menurut penulis, alternatif yang
tepat di antaranya sebagai berikut:
Pertama, perlunya pembatasan program studi PGSD, artinya
jika dirasa kebutuhan akan guru telah cukup dalam mengisi formasi
kekurangan, lebih baik program PGSD segera ditutup agar tidak
terjadi ledakan lulusan.
Kedua, bila dalam pengangkatan diperlukan proses tahapan,
seyogianya direncanakan sistematis dan sesuai urutan. Artinya selang
tahap pengangkatan diupayakan terbuka sehingga penantian mereka
tidak sia-sia, dan tidak terjadi adanya barisan pengantre yang
meloloskan diri mendahului barisan di depan. Hal ini jelas akan
menimbulkan kecemburuan sosial.
Ketiga, perlu adanya informasi jelas dan dapat dipercaya
tentang prioritas kriteria pengangkatan. Apakah indeks prestasi yang
diperoleh sewaktu pendidikan, ataukah hasil tes CPNS atau mungkin
ada hal lain. Informasi itu sangat penting sebab pernah ada kasus
seorang mahasiswa PGSD angkatan kedua, peraih indeks prestasi
terbaik, sampai tahapan kedua pengangkatan belum terangkat.
Keempat, pemerintah perlu meninjau kembali rekrutmen
mahasiswa PGSD yang sampai sekarang masih memberikan
kesempatan kepada lulusan SLTA. Bukankah lulusan SPG saja
masih perlu ditingkatkan kemampuannya? Kalau lulusan SLTA yang
dari disiplin ilmunya tidak disiapkan menjadi guru SD, kemudian
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 173
belajar di PGSD hanya 2 tahun, apakah sudah mampu menguasai
kompetensi diharapkan?
Sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan penuh kepada
ribuan lulusan SPG yang belum tertampung di PGSD. Ibarat pemain
drama, lulusan SPG selalu menjadi figuran, kedatangan bintang tamu
dari SLTA jelas memperkecil peluang mereka menjadi pemeran
utama.
Persiapan Diri
Menyadari betapa rumitnya birokrasi pengangkatan, ada
baiknya mempersiapkan seperangkat kebutuhan, baik mental dan
fisik guna meringankan beban. Kebutuhan mental di antaranya
meliputi kesiapan kondisi terhadap kemungkinan gunjingan
masyarakat. Ini cukup beralasan, pemikiran masyarakat sederhana,
lulus PGSD langsung menjadi pegawai negeri. Mengatasi hal
tersebut, lulusan PGSD dihadapkan pada tiga pilihan.
Pertama, pulang kampung menunggu turunnya beslit. Kedua,
bekerja di luar jalur pendidikan sekadar batu loncatan. Ketiga,
mengabadi menjadi guru wiyata bakti di Sekolah Dasar.
Barangkali pilihan ketiga lebih tepat, di samping menerapkan
ilmu yang diterima juga memperkecil guncingan masyarakat adanya
lulusan PGSD yang menganggur serta dimungkinkannya kemudahan
informasi dan komunikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebutuhan fisik di antaranya meliputi surat-surat yang
diperlukan dalam pengangkatan (SKKB dari Polres, Kartu Kuning
Depnaker, foto hitam 3x4 dan 4x6, Kir Dokter) dan legalisasi ijazah
diploma, akta, maupun transkrip.
Tidak ada jeleknya apabila kebutuhan fisik mulai
dipersiapkan. Hal ini dimaksudkan apabila ada panggilan mendadak
atau kemungkinan adanya keterlambatan pos mengirim surat
174 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
panggilan, kebutuhan akan administrasi sudah tersedia. Itulah yang
harus dijadikan bahan renungan pemerintah dan calon guru.
Ibarat buah simalakama, barangkali itulah yang terjadi dalam
penyelenggaraan program studi PGSD. Ada baiknya pemerintah
segera cancut taliwanda memadamkan api keprihatinan dan ada
baiknya pula ribuan calon guru yang belum terangkat tidak bersikap
dissident terhadap pemerintah, bersabar dan senantiasa berdoa agar
pemerintah dapat segera memadamkan api keprihatinan menjadi api
kebahagiaan.
Trimo, alumnus IKIP Semarang, pendidik di Kabupaten Kendal
―dimuat di harian Suara Merdeka, 17 Juli 1996.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 175
IMPLEMENTASI BAHASA DAERAH
DALAM TINGKAH LAKU SISWA
Oleh Trimo
―Esuk-esuk kok wis teka ta, Pak?‖ (Pagi-pagi kok sudah
datang, sih, Pak?) Sebuah tanya yang sempat membuat saya kaget.
Pasalnya yang mengatakan itu adalah murid saya. Sebagai guru SD
baru, saya benar-benar tersentak dengan sapaan murid saya itu. Terus
terang saya memang tidak terbiasa dengan sapaan ngoko, apalagi
diucapkan anak kecil yang notabene adalah murid saya. Namun, saya
tidak memiliki hak memarahi murid itu, bahkan saya terima sapaan
yang lugu itu dengan senyum. “Mungkin murid-murid di desa ini
memang tidak dapat berbahasa krama inggil (bahasa Jawa halus).”
Demikian pikir saya.
Ternyata yang apa yang saya pikirkan tersebut memang
kenyataan. Hasil pengamatan beberapa hari, memang hampir semua
murid tidak dapat berbahasa krama inggil. Murid terkesan tidak
memiliki beban dan rasa ewuh pakewuh bahwa yang disapa atau
diajak berbicara itu adalah guru yang usianya jauh lebih tua dari
mereka.
Masa Bodoh
Kejadian tersebut mengingatkan ketika saya masih di SD yang
kondisinya juga sama dengan kondisi SD di mana saya mengajar.
Ketika itu semua siswa sudah lanyah (lancar) berbahasa Jawa dengan
krama dan selalu menaruh hormat (ngajeni) terhadap para guru.
Kalau ada murid berbahasa ngoko kepada guru, ada saja teman
(lingkungan) yang mengingatkan.
Pengalaman masa kecil itulah yang mengakibatkan dalam
batin saya terjadi perang. Mengapa murid-murid saya tidak dapat
176 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
berbahasa krama inggil dan terkesan tidak memiliki tata krama?
Apakah semua itu akibat kekurangtelatenan para guru mengajarkan
bahasa krama ataukah orang tua mereka dan lingkungan yang
bersikap masa bodoh?
Sikap masa bodoh tersebut, ternyata tidak hanya di tempat
saya mengajar, tetapi juga terjadi di tempat lain, di mana teman-
teman saya mendapat tugas. Sikap masa bodoh tersebut, tampak pada
sikap orang tua mereka yang membiarkan anak-anak pergi ke
sekolah tanpa sepatu. Padahal di desa tersebut, orang tua cukup
mampu. Begitu pula ketika musim tanam atau panen tiba, anak-anak
dibiarkan membantu orang tua sehingga sekolah tampak sepi.
Memang, setiap musim panen, ruang guru sarat berbagai jenis
palawija. Akan tetapi hal tersebut tak sepenuhnya dapat menghibur.
Bagi kami, lebih baik ruang kelas dipenuhi murid ketimbang ruang
guru dipenuhi palawija.
Njawani
Sikap njawani bukan berarti harus mundhuk-mundhuk, tetapi
lebih mengedepankan etika dan estetika pergaulan. Secara sederhana
dapatlah dicontohkan, anak harus dibiasakan menghormati orang
lebih tua darinya atau menempatkan orang tua sebagai narasumber,
bukan sebaliknya. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa derasnya
arus informasi dapat menghayutkan etika dan estetika.
Hanyutnya etika dan estetika, agaknya dirasakan
Ronggowarsito yang menulis pupuh Sinom, ―Amenangi zaman edan,
ewuh aya ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu
anglokoni, boya kaduman melik, kaliren wekasanipun, ndilalah
karsa Allah, beja-bejane kang lali, luwih beja kang eling lawan
waspada.‖
Tembang Sinom di atas mengandung maksud bahwa manusia
senantiasa harus mengingat Tuhan Sang Pencipta, walaupun zaman
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 177
edan, di mana makin banyak orang mengabaikan etika dan estetika
dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa.
Akibat zaman edan ini pula, banyak orang Jawa yang lali
marang jawane, lupa pada unggah-ungguh yang sebetulnya menjadi
dasar pergaulan dan tidak memiliki lagi rasa subasita. Banyak yang
menganggap budaya Jawa semacam itu merupakan hal kuno. Oleh
karena itu tidak mengherankan kalau sekarang banyak murid yang
tidak lagi memiliki unggah-ungguh atau sopan-santun.
Peran Orang Tua
Di desa, banyak orang tua yang menganggap bahwa posisi
seorang guru adalah segalanya, sehingga mereka bersikap masa
borong (terserah) terhadap pendidikan anak-anaknya kepada guru
atau sekolah. Pokoknya, hitam-putihnya anak diserahkan penuh
kepada pihak guru/sekolah. Sikap semacam ini tidak sepenuhnya
keliru, tetapi hal ini menempatkan guru dalam posisi serbasalah.
Misal, kalau anak didik berperilaku kurang ajar masyarakat
akan bertanya siapa gurunya. Bukan siapa orang tuanya. Namun
kalau anak tersebut meraih prestasi, masyarakat tidak akan bertanya
siapa gurunya, tetapi siapa orang tuanya.
Jadi, pada dasarnya peran orang tua dalam mendidik anak
seharusnya berada di garda depan, sedangkan guru berperan
melengkapi. Hal ini mengingat jumlah waktu yang dimiliki seorang
anak lebih banyak berada di lingkungan keluarga ketimbang di
sekolah. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika antara pihak orang
tua dengan guru/sekolah saling koordinasi dan mengingatkan.
Tugas Guru
Ditempatkannya Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal
(Mulok) wajib khususnya di Jawa Tengah, rasanya seperti angin
segar bagi siapa saja yang bertekad nguri-uri kabudayan Jawa,
178 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
termasuk saya sebagai guru. Melalui mulok wajib tersebut, mau tidak
mau, senang atau tidak senang, bahasa daerah harus dipelajari setiap
murid SD atau SLTP. Hanya, seyogianya pemberian pelajaran
bahasa daerah juga perlu diberikan sampai tingkat SLTA. Sebab
rasanya ada ketimpangan ketika seorang lulusan SLTA ingin
meneruskan kuliah ke jurusan Sastra Jawa, ternyata penguasaan
materi dasarnya hanya dimiliki di tingkat SD dan SLTP.
Ketimpangan tersebut barangkali berawal dari sulitnya
mengakomodasi dan mengklarifikasi rumitnya bahasa Jawa dengan
kesiapan Sumber Daya Manusia.
Memang harus diakui, bahwa dewasa ini banyak di antara
guru SD yang kurang menguasai bahasa daerah, bahkan bersikap
masa bodoh. Daripada pusing.
Mengajari menulis Jawa, unggah-ungguh, krama inggil,
sanepa, wangsalan, parikan, paribasan, dan lainnya, lebih baik
memprioritaskan mata pelajaran yang diebtanaskan. Hal ini dapat
dimaklumi, karena guru SD biasanya tidak memegang spesialisasi
materi. Maksudnya guru SD (guru kelas) dituntut menguasai
berbagai materi pelajaran.
Lain halnya dengan pelajaran bahasa Jawa di tingkat SLTP.
Biasanya penyampaian materi bahasa Jawa di tingkat SLTP tidak
begitu bermasalah, sebab pengajarnya memang khusus dan disiapkan
serta menguasai bidang sesuai dengan yang diperoleh di bangku
kuliah (dari jurusan Sastra Jawa).
Melihat kenyataan yang ada dan dilematis tersebut, maka
tugas guru SD jelas akan lebih berat. Namun tugas tersebut akan
terasa ringan kalau kita dapat melaksanakan beberapa langkah, yaitu:
(1) Membudayakan berbahasa Jawa baik dan benar sesuai situasi dan
kondisi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan
tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan, (2) Harus telaten dan
sabar membimbing para murid, aktif kreatif menyampaikan bahasa
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 179
daerah sehingga menjadi bahasa yang disenangi para murid. Hal ini
dapat dilaksanakan dengan cara menyampaikan dongeng bahasa
Jawa, (3) Harus berupaya menanamkan rasa cinta anak kepada diri
sendiri yang berbudaya di tengah arus globalisasi informasi dan
reformasi, (4) Harus dapat mengantisipasi tingkah laku anak yang
negatif dengan menanamkan dan menempatkan bahasa daerah
sebagai alternatif pemecahannya selaras fungsinya, menjaga etika
dan estetika. Satu hal lagi yang akan lebih meringankan tugas adalah
disiapkannya guru khusus bahasa daerah untuk SD. Selebihnya
memang diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan dari para
petinggi pendidikan untuk lebih meningkatkan keseriusan guru
bahasa daerah.
Pada akhirnya memang harus kita sadari bersama, bahwa
semua tugas-tugas pemasyarakatan bahasa daerah (Jawa) tersebut
tentunya tidak dapat berjalan sendiri. Namun, perlu adanya kerja
sama dan kesadaran semua pihak. Siapa lagi yang akan mencintai
dan mengembangkan bahasa Jawa kalau bukan kita sendiri? Marilah
kita bersama bangkit nguri-uri kabudayan Jawa yang adiluhung.
Jangan biarkan kebudayaan Jawa merana dan menangis karena
ditinggalkan orang Jawa.
Penulis adalah guru SDN Kedungsuren 04, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal
―dimuat di Tabloid Inspirator, Minggu IV, 23-29 Agustus 1999.
180 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
KURIKULUM BAGAI PIALA BERGILIR,
BUTUH PROSES PANJANG DAN RUMIT
Oleh Trimo
Rumor reshulffle kabinet yang konon akan dlakukan pada
Kabinet Persatuan Nasional oleh Presiden Gus Dur sekitar bulan
Juli-Agustus ini, membuat kalangan pendidik merasa cemas,
bingung, dan khawatir. Pasalnya, selama ini ada asumsi negatif
beredar, bukan saja di kalangan warga pendidik, tetapi juga di
tengah-tengah masyarakat bahwa setiap kali terjadi pergantian
kabinet, dalam hal ini pergantian atau perubahan kurikulum. Tidak
mengherankan, ketika terjadi pergantian menteri bidang pendidikan,
kalangan pendidikan dibuat jungkir balik untuk bisa beradaptasi
dengan selera menteri baru.
Masih segar dalam ingatan kita perubahan spesifikasi gelar
Mendikbud (kala itu) pada akhir masa jabatan, kemudian perubahan
kurikulum SD tahun 1994, dan yang terakhir kalangan pendidik
dibuat pusing oleh Keputusan Presiden yang secara mendadak
meliburkan sekolah selama sebulan penuh pada bulan puasa,
sehingga berdampak pada pengaturan kalender pendidikan
berikutnya.
Hal demikian tentu membuat kalangan pendidik sulit
mengembangkan estimasi minimal dari program yang dirumuskan
sebelumnya.
Piala Bergilir
Asumsi sederhana masyarakat bahwa ganti menteri pasti ganti
kurikulum, berdampak adanya istilah piala bergilir. Kurikulum
secara bergilir menjadi milik menteri. Benarkah asumsi ini?
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 181
Bagi masyarakat awam tentu ada tanda tanya besar ketika
pemerintah menentukan kebijakan baru terhadap perubahan
kurikulum atau lebih dikenal istilah Pengembangan Kurikulum.
Reaksi spontan masyarakat yang mengaitkan pengembangan
kurikulum dengan pergantian kabinet tidak bisa disalahkan begitu
saja. Namun perlu dikaji lebih lanjut. Kalau hal itu benar, yang
menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauh pengembangan
yang dilakukan itu dapat memberdayakan masyarakat.
Secara sederhana dapat ditanyakan, apakah dengan kurikulum
baru tersebut masyarakat lebih bisa menikmati jika dibanding
kurikulum sebelumnya? Tulisan ini dapat dijadikan bahan pengantar
dan renungan sekaligus jawaban dan asumsi masyarakat tentang
perubahan kurikulum.
Prinsip Umum
Menurut Peter F. Oliva (1982) setidaknya ada 10 prinsip
umum yang dijadikan landasan mengembangkan kurikulum.
Pertama, menggariskan bahwa perubahan yang dilakukan itu
memang perlu dan diinginkan masyarakat dalam menjawab
problema dan masalah-masalah krusial. Masalah-masalah tersebut
sebagaimana diidentifikasi Glen Hass meliputi pelestarian
lingkungan, krisis energi, perubahan nilai-nilai dan moralitas,
perubahan struktur dan kehidupan keluarga, krisis perkotaan dan
perdesaan, gerakan minoritas, wanita dan penyandang cacat yang
menuntut persamaan hak, dan meningkatnya angka kejahatan serta
timbul rasa terasing dan cemas yang dialami banyak orang.
Kedua, berhubungan dengan waktu. Artinya perubahan
kurikulum merupakan produk waktu atau secara sederhana dapat
dikatakan merupakan paket perubahan sosial.
Ketiga, perubahan kurikulum lazim terjadi dalam waktu sama
dan tumpang tindih antara unsur kurikulum yang lama dan baru. Hal
182 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
ini kerap terjadi dan merupakan hal biasa. Artinya, masuknya unsur-
unsur baru dilakukan berangsur-angsur, demikian pula dalam
mengeluarkan unsur-unsur lama.
Keempat, biasanya perubahan kurikulum merupakan hasil
perubahan diri dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Era
sekarang, prinsip ini merupakan hal wajar dan terjadi lantaran biru-
putihnya kurikulum sangat terletak pada pengembang.
Kelima, prinsip kerja sama dikandung maksud bahwa
perubahan kurikulum harus mengikutsertakan banyak pihak.
Keenam, prinsip pemilihan antara alternatif-alternatif dan
proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal ini adalah
memilih disiplin ilmu, pandangan, penekanan, metodologi,
organisasi, dan sebagainya.
Ketujuh, mensyaratkan bahwa pengembangan kurikulum
merupakan proses terus menerus tanpa akhir.
Kedelapan, pengembangan kurikulum adalah proses
komprehensif, sedangkan pelaksanaan pengembangan sistematis
merupakan prinsip kesembilan.
Sebagai prinsip yang terakhir (kesepuluh) bahwa perubahan
kurikulum harus dimulai dari kurikulum itu sendiri, lantaran bila
perencana kurikulum itu memulai dari kurikulum yang sudah ada,
pasti akan lebih efektif mencapai tujuan yang diharapkan
masyarakat.
Asas Kurikulum
Hal lain yang mendasari terjadinya pengembangan sebuah
kurikulum adalah asas mengacu tujuan, keluwesan, kesesuaian,
keseimbangan, kesinambungan, dan belajar aktif (Depdikbud, 1994).
Keenam hal tersebut lazim dikenal dengan sebutan asas-asas
kurikulum. Secara sederhana, keenam asas tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 183
Pertama, berorientasi pada tujuan yang mengandung
pengertian bahwa pengembangan kurikulum harus mengacu pada
tujuan instruksional dari masing-masing satuan pendidikan dan
tujuan kurikuler dari masing-masing mata pelajaran.
Kedua, asas keluwesan memberi keleluasaan lebih banyak
kepada guru dalam melaksanakan kurikulum. Dalam hal ini
menyesuaikan jumlah waktu penyajian tiap-tiap pokok bahasan,
mengatur urutan bahan pelajaran dalam satu catur wulan, memilih
pendekatan metode, serta sumber belajar.
Ketiga, asas kesesuaian (relevansi) dikandung maksud bahwa
dalam pengembangan kurikulum harus menyesuaikan tingkat
perkembangan atau kemampuan siswa, keadaan daerah, dan
perkembangan iptek.
Keempat, dengan asas keseimbangan diharapkan ada
keseimbangan antara bahan pelajaran teoretis dan praktis, sikap dan
nilai dalam mewujudkan potret pendidikan manusia seutuhnya.
Berikutnya asas kelima, kesinambungan. Dengan asas ini
diharapkan bahan pelajaran yang disusun GBPP berkesinambungan
antartingkat/kelas dalam satuan pendidikan.
Asas keenam adalah belajar aktif yang lahir dari proses CBSA
dalam pengertian perlu melibatkan siswa secara aktif dalam proses
belajar mengajar baik mental, fisik, maupun sosialnya.
Proses Panjang dan Rumit
Asas lain yang tak kalah penting menurut Ralph Tylor (1949)
adalah asas filosofis yang berakar filsafat Pancasila, asas sosiologis
yang mencakup harapan, kebutuhan, dan sejarah perkembangan
masyarakat, serta nilai-nilai yang diakui masyarakat/bangsa.
Berikutnya asas psikologis yang berkaitan dengan psikologi belajar
dan perkembangan peserta didik serta asas iptek yang merupakan
tantangan pendidikan di masa datang.
184 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Keseluruhan prinsip dan asas yang terurai di atas sudah tentu
merupakan jawaban rasionalitas perubahan kurikulum. Dengan
demikian, asumsi yang menganggap perubahan kurikulum
mencirikan kehendak seorang menteri dan mengibaratkannya sebagai
piala bergilir tidaklah sepenuhnya benar. Lantaran hal demikian
sudah melalui proses dan pentahapan yang begitu panjang dan rumit.
Yang patut menjadi bahan renungan adalah realisasi
perubahan kurikulum tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Hal
ini muncul ke permukaan lantaran rasional-rasional perubahan dan
pengembangan kurikulum bersifat teoretis saja, sehingga masih
diperlukan adanya faktor kemauan dan kesungguhan pendidik dalam
merealisasikan seperangkat kurikulum yang menjadi beban, harus
diselesaikan tuntas. Oleh karenanya, peran pendidik dalam
pengembangan kurikulum sangat signifikan dalam mewujudkan cita-
cita pendidikan manusia seutuhnya.
Guru SDN Kedungsuren 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal
—dimuat di Tabloid Inspirator Minggu II, 09-15 Juli 2000.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 185
EBTANAS,
POTRET PENGEKANGAN KREATIVITAS ANAK
Oleh Trimo
Ada sinyalemen yang berkembang akhir-akhir ini di dunia
pendidikan berkaitan penyelenggaraan Ebtanas yang diyakini sebagai
titik kulminasi dari serangkaian perjuangan peserta didik dalam
satuan jenjang pendidikan tertentu. Sinyalemen yang bergerak ke
arah kutub negatif sangat rentan terhadap harapan masyarakat yang
menginginkan arah pendidikan mensyaratkan melewati tahapan
Ebtanas. Itu berarti, ada tanda tanya besar yang perlu dijawab
petinggi pendidikan di negeri ini terhadap relevansi Ebtanas dengan
kebutuhan masyarakat.
Masih relevankah di era reformasi ini, mempertahankan
Ebtanas yang merupakan produk pengekangan kreativitas?
Pertanyaan ini mungkin bagi para petinggi pendidikan jelas
merupakan usaha mereformasi kebiasaan turun temurun yang
menurut kacamata mereka baik dan sekaligus menjadi tamparan
keras. Betapa tidak, penyelenggaraan Ebtanas yang ditandai
perolehan Nilai Ebtanas Murni (NEM) menurut petinggi pendidikan
bertujuan (1) Sebagai alat kontrol dan pendorong sekolah
meningkatkan mutu pendidikan; (2) Alat seleksi melanjutkan jenjang
pendidikan lebih tinggi; (3) Alat ukur pemberi gambaran riil
kemampuan tamatan secara individu/nasional; (4) Alat ukur pemberi
gambaran peta mutu pendidikan dan kemampuan tamatan antarjenis
satuan pendidikan dan antarwilayah dari waktu ke waktu; (5) Umpan
balik pengembangan kurikulum dan untuk pengambilan kebijakan
pendidikan mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat pusat; (6)
Masukan bagi guru dan salah satu bentuk pertanggungjawaban
kepada masyarakat sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana hasil
186 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
pendidikan di tanah air, (7) Bahan pertimbangan penentuan tamat
belajar.
Pro dan Kontra
Secara sekilas kalau kita memperhatikan tujuan
penyelenggaraan Ebtanas yang dirumuskan pemerintah dalam hal ini
Depdiknas, terbayang gambaran dalam benak kita bahwa rumusan
tersebut begitu luhur dan ideal sekali. Lantas, mengapa masyarakat
banyak yang pro dan kontra terhadap penyelenggaraan Ebtanas?
Padahal kalau ditilik dari terminologi tujuannya tidak bertentangan
dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku di negara kita.
Keraguan masyarakat akan format kualitas penyelenggaraan
Ebtanas akhir-akhir ini bukan merupakan hal baru, tetapi hal lama
yang baru dimunculkan lantaran adanya embusan angin reformasi.
Paling tidak ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap perubahan
perilaku masyarakat yang berimplikasi terhadap dilematisasi
penyelenggaraan Ebtanas.
Pertama, target kurikulum. Masyarakat berasumsi
penyelenggaraan Ebtanas hanya mengejar target kurikulum. Dengan
demikian akan berdampak bagi sistem pengajaran yang lebih
menitikberatkan pelajaran yang diebtanaskan saja, sedangkan mata
pelajaran lain sebagai pelengkap penderita. Asumsi ini memang
sangat mendasar dan beralasan lantaran dengan ditentukannya mata
pelajaran yang diebtanaskan dan yang tidak diebtanaskan akan
berdampak munculnya istilah guru mata pelajaran ebtanas dan guru
mata pelajaran nonebtanas, yang akhirnya akan memengaruhi sikap
dan tingkah laku peserta didik terhadap gurunya.
Secara sederhana dapat dicontohkan, siswa akan lebih
menghormati dan memperhatikan penjelasan guru yang mengampu
mata pelajaran Ebtanas daripada guru lain. Lantaran mata pelajaran
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 187
Ebtanas, jelas akan berpengaruh terhadap seleksi ke jenjang
pendidikan lebih tinggi.
Kedua, Ebtanas lebih dekat dengan cara-cara berpikir
konvergen daripada berpikir divergen. Berpikir konvergen, menurut
Prof. Dr. SCU Munandar adalah suatu aktivitas yang dilakukan di
mana siswa hanya menemukan satu jawaban dari permasalahan yang
dihadapi. Sedang berpikir divergen adalah segala aktivitas yang
dilakukan di mana siswa menemukan beragam alternatif jawaban
dari permasalahan yang dihadapi. Konsep berpikir divergen inilah
dalam dunia pendidikan sering disebut kreativitas yang secara
sederhana dapat diartikan kemampuan membuat kombinasi baru
berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada.
Pilihan Ganda Semua
Konsep berpikir divergen yang akan memprogram siswa
menjadi kreatif, dahulu memang pernah diterapkan dalam soal-soal
Ebtanas, walaupun kadarnya sangat kecil sekali. Biasanya berbentuk
soal-soal isian dan uraian. Namun sekarang, soal-soal Ebtanas yang
mengacu pada konsep berpikir divergen sudah direformasi. Beberapa
tahun lalu, siswa SMU yang kemudian diikuti siswa SLTP harus
berhadapan dengan soal-soal Ebtanas yang modelnya pilihan ganda
semua. Kini, mulai tahun Pelajaran 1999/2000, anak-anak SD harus
beradaptasi dengan soal-soal berbentuk pilihan ganda semua tanpa
isian dan uraian. Ironisnya, perihal pemberlakuan soal-soal pilihan
ganda secara total ini belum banyak diketahui kalangan pendidik
karena pemberlakuan dan penyebaran informasi begitu mendesak.
Mereka (guru SD) sudah terbiasa mempersiapkan anak-anak
dalam menghadapi Ebtanas dengan mengacu pada soal-soal tahun
lalu yang terdiri dari pilihan ganda (35 butir), isian (10 butir) dan
uraian (5 butir).
188 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Pemberlakuan soal Ebtanas untuk anak SD yang bentuknya
pilihan ganda semua, jelas hanya menguntungkan pihak pemeriksa
saja lantaran tidak perlu memeriksa item-item soal yang
menggunakan pikiran. Sedang secara tidak sadar, pemberlakuan
tersebut akan banyak merugikan anak lantaran tolok ukur
penilaiannya hanya benar dan salah. Hal demikian tentu makin
membenarkan asumsi masyarakat bahwa Ebtanas merupakan potret
pengekangan kreativitas anak.
Menganaktirikan Sekolah Swasta
Faktor ketiga berkaitan dengan masalah dana riskan sekali.
Sering kita mendengar dan membaca berita tentang adanya protes
dari orang tua murid terhadap pungutan/iuran penyelenggaraan
Ebtanas. Padahal, untuk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
keputusan bersama antara Kakanwil Depdiknas Provinsi Jateng,
Kadinas P dan K Provinsi Jateng dan Kakandepag Provinsi Jateng
Nomor: 0122/I03.02/PR/2000 dan Nomor: 423.7/02733 serta Nomor:
Wk/5.a/PP.01.1/1372/2000 tanggal 29 April 2000, biaya
penyelenggaraan Ebtanas untuk sekolah negeri dibebankan kepada
Dinas P dan K Provinsi Jateng (untuk SD/SLB), Depdiknas Provinsi
Jateng (SLTP, SLTPLB, SMU, SMLB dan SMK) dan Kanwil Depag
Provinsi Jateng (MI, MTA dan MA).
Sedangkan untuk sekolah swasta, beban biaya Ebtanas
dibebankan kepada sumbangan murid, tetapi tidak memberatkan,
menerapkan prinsip gotong royong dengan kepedulian tinggi untuk
ikut membantu siswa yang tidak mampu membayar. Selebihnya
penentuan besarnya biaya Ebtanas pun harus dikonsultasikan dan
disetuji lebih dahulu oleh Gubernur Jawa Tengah.
Sampai pada tahap pengucuran dana saja, sudah kelihatan
betapa ada ketimpangan signifikan sekali. Hal ini tampak pada
pemberian dana bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tak
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 189
tersentuh sedikit pun. Padahal kalau kita cermati kembali, di sekolah
swasta ada prinsip gotong royong yang konon menjadi simbol
perlawanan bangsa Indonesia ketika menghadapi penjajah, tetapi
tidak dimiliki sekolah negeri. Adanya ketimpangan menjurus sikap
menganaktirikan sekolah swasta, jelas akan memberi renungan
tersendiri bagi pengelola sekolah swasta dan masyarakat akan
validitas penyelenggaran Ebtanas.
Perjelas Komitmen
Mengacu pada uraian sederhana mengenai asumsi masyarakat
terhadap penyelenggaraan Ebtanas, ada baiknya pihak petinggi
pendidikan segera mempertegas komitmen tentang postur pendidikan
di masa datang. Dalam artian, mau dibawa ke mana arah pendidikan
anak-anak bangsa ini? Komitmen ini sangat diperlukan untuk
memberi arah jelas terhadap masa depan peserta didik dalam jenjang
pendidikan tertentu. Kekurangjelasan peserta didik, pendidik, dan
masyarakat akan rumusan postur pendidikan di masa datang akan
berdampak pada sikap apatis dan pesimis dalam upaya melibatkan
diri dalam satu sistem pendidikan nasional.
Postur pendidikan di masa datang menurut saya adalah
gambaran pendidikan mempersiapkan anak sejak dini agar dapat
berpikir divergen. Itu berarti membangkitkan kreativitas anak adalah
hal utama lantaran kreativitas pada hakikatnya merupakan suatu
proses bukan produk.
Penyelenggaraan Ebtanas yang mengekang kreativitas anak
jelas akan bertolak belakang dengan postur pendidikan di masa
datang. Oleh karena itu sudah saatnya penyelenggaraan Ebtanas
ditinjau kembali, bila perlu dihapuskan guna menumbuhkembangkan
kreativitas anak.
__dimuat di Tabloid Inspirator, Minggu I, 01-08 Agustus 2000.
190 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
PRAMUKA INDEPENDEN, MAMPUKAH?
Oleh Trimo
Jika kita sampai pada bulan Agustus, tentunya biasa
menyaksikan aktivitas yang lebih terarah. Bukan saja aktivitas yang
dilakukan anak-anak sekolah, tetapi juga masyarakat. Bulan Agustus
memang menjadi istimewa sekali bagi bangsa Indonesia, lantaran
bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Hal spesifik
lagi, bulan Agustus adalah bulan Pramuka di mana seluruh peserta
didik dan pembina juga merayakan hari jadinya.
Ada tanda tanya besar yang patut direnungsarikan, ketika para
pencinta Pramuka hendak merayakan hari ulang tahunnya di tengah-
tengah kondisi negeri babak bundhas.
Apa yang mereka rayakan? Paradigma yang akan mereka
kembangkan dengan kondisi memaksa para petinggi dari tataran
bawah sampai atas untuk menjadi majelis pembimbing Pramuka, di
era reformasi yang masih bergulir sekarang, beranikah gerakan
Pramuka independen, tidak bergantung birokrasi kekuasaan?
Pertanyaan sederhana di atas, masa orde baru (orba) menjadi
tidak begitu penting. Lantaran secara birokrasi, semua pejabat tidak
bisa luput dari organisasi yang secara nasional berdiri 14 Agustus
1961 itu. Kondisi negara yang bagai terkena revolusi di segala
dimensi kehidupan, mendadak membawa perubahan total.
Segala aspek kehidupan di negeri ini, juga terkoreksi oleh
segenap lapisan masyarakat. Begitu juga, gerakan Pramuka
mengalami hal serupa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD-ART) yang baru, setidaknya menjawab koreksi dari
berbagai pihak.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 191
Wajah Lama
Halironis adalah sinyalemen ingin berkuasanya para
fungsionaris Pramuka dari tingkat Kwartir Ranting (kecamatan)
sampai tingkat Kwartir Nasional (Kwarnas). Kondisi tersebut
memang bukan rahasia lagi, gaya kepemimpinan organisasi Pramuka
memang identik dengan gaya kepemimpinan orde baru. Estafet
kepemimpinan yang sengaja dibuat lebih lama menjadi rentan sekali
dengan adanya orang-orang yang itu-itu saja. Secara sederhana dapat
dicontohkan, ketika ada pertemuan pramuka apapun tingkatnya,
pastilah orang-orang yang muncul selalu sama.
Sinyalemen tersebut menarik untuk dicermati, lantaran di era
reformasi koreksi menuju peningkatan kualitas sebuah organisasi
sangat diperlukan. Hal yang menjadikan organisasi berlambang tunas
kelapa selalu menampilkan wajah lama, menurut saya adalah sebagai
berikut.
Pertama, figur yang senang bekerja tanpa pamrih. Jika ditilik
dari kultur budaya bangsa kita sebetulnya kerja tanpa pamrih adalah
warisan nenek moyang. Namun demikian, budaya adiluhung tersebut
menjadi tersingkirkan dengan adanya berbagai pemenuhan
kebutuhan. Singkatnya, untuk mencari pekerja Pramuka yang
memiiki jiwa sosial tinggi sangat sulit, sehingga wajah-wajah lama
yang mau menjadi langganan tetap.
Kedua, transfer kemampuan yang kurang signifikan. Para
pekerja Pramuka yang kebetulan mendapat kesempatan menimba
ilmu pengetahuan, biasanya mengalami hambatan dalam hal
sosialisasi. Bukan hanya karena sulitnya melakukan proses
sosialisasi, tetapi juga lantaran para pembina Pramuka di tingkat
bawah bersikap masa bodoh terhadap hal-hal baru. Sikap masa
bodoh pembina, secara sederhana dapat terlihat dengan kurang
tertibnya para peserta didik Pramuka dari tingkat Siaga sampai
Pandega dalam tata cara berpakaian, khususnya pemakaian tanda-
192 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku tulisan ilmiah populer untuk kenaikan pangkat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search