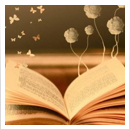tanda pengenal gerakan Pramuka. Bukan saja peserta didik, bahkan
pembina pun juga mengalami hal serupa. Banyak di antara mereka
enggan memakai setangan leher.
Ketiga, otoritas idealisme yang mengakar kuat. Perihal otoritas
idealisme berkaitan kemampuan tata cara birokrasi. Pekerja Pramuka
yang sudah getol tugas, biasanya terbiasa melewati garis-garis
birokrasi sehingga meyakinkan pejabat Pramuka di tingkat atasnya.
Bukan bermaksud menyudutkan mereka kalau dalam era reformasi
ini, perlu penyegaran agar teknik dan format kegiatan yang
dirumuskan tidak monoton.
Setiap tahun, kegiatan Pramuka dari tingkat Siaga sampai
Pandega selalu statis. Bahkan sinyalemen yang akhir-akhir ini
menjadi marak adalah adanya banyak gugus depan yang tidur dan
hanya terbangun kalau bulan Agustus. Itu pun harus melalui proses
panjang.
Paradigma Baru
Adaparadigma baru untuk meningkatkembangkan kegiatan
Pramuka, sehingga tujuan luhur yang dirumuskan AD dan ART
dapat secara optimal tercapai. Paling tidak, paradigma baru itu
nantinya akan menepis kesan bahwa Pramuka adalah sisa-sisa format
pelaksanaan orde baru. Bahkan kemungkinan akan bernasib sama
dengan format P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila),
yang juga mempunyai fondasi kuat dari tingkat bawah sampai atas.
Paradigma baru ini saya rumuskan lantaran melihat
perkembangan gerakan Pramuka pasca orde baru yang hanya bisa
bertahan. Bertahan sekadar ada dan pelengkap kondisi tempo hari.
Hal yang signifikan, adanya harapan tinggi bahwa organisasi
Pramuka adalah satu-satunya organisasi yang berhak
menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Hal ini berdampak pada
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 193
sikap ketergantungan, ujung-ujungnya membentengi arogansi
organisasi.
Setidaknya ada 5 hal pokok dalam paradigma baru menjadikan
gerakan Pramuka organisasi solid di tengah organisasi lain.
Pertama, keberanian melepaskan diri dari ikatan birokrasi.
Tantangan masa depan yang patut diacungi jempol bila gerakan
Pramuka berani melakukan hal tersebut. Tradisi, kebiasaan, dan
aturan bersifat memaksa para pejabat dari kepala desa/lurah, camat,
bupati, gubernur, dan presiden yang secara officio menjadi Majelis
Pembimbing di Kwartir-nya akan menimbulkan asumsi masyarakat
bahwa gerakan Pramuka masih bertahan dengan format lama.
Kedua, restrukturisasi organisasi. Hal ini sangat penting
berkaitan penyelenggaraan lembaga. Restrukturisasi dapat berupa
perampingan lembaga atau fungsionaris yang ada di setiap lembaga.
Hal yang patut diperhatikan dalam restrukturisasi adalah pemberian
kesempatan kepada generasi muda untuk mendesain format dan
postur Pramuka pasca orde baru yang diharapkan, dengan tidak
meninggalkan masukan pendahulu. Dengan demikian, kerja sama
antara wajah lama dengan wajah baru diharapkan dapat merumuskan
potret kondisi Pramuka yang saat ini dipandang ideal segenap lapisan
masyarakat.
Ketiga, rumuskan tujuan. Secara umum tujuan yang
dirumuskan harus terkait kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
Lantaran format lama senantiasa merumuskan tujuan bersifat idealis
semata, maka gerakan Pramuka pasca orde baru harus berani tampil
beda dengan merumuskan tujuan menyentuh langsung kebutuhan
peserta didik dan masyarakat. Rumusan tersebut paling tidak
mengandung komponen mandiri, nilai guna, ideologi, dan sosialisasi.
Keempat, merumuskan program kegiatan menarik dan
bervariasi. Format lama kegiatan Pramuka hanya berkutat hal-hal
seremonial idealis, tetapi kurang menumbuhkembangkan potensi
194 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
yang ada di tingkat bawah. Seperti contoh penyelenggaraan kegiatan
Pramuka Siaga (Pesta Siaga), Penggalang (Jambore, LT),
Penegak/Pandega (Raimuna, Perkemahan Wirakarya, Peran Saka),
dan Pembina (Karang Pamitran, Kursus Pembina). Semua kegiatan
itu hanya marak di tingkat atas, sedangkan di tingkat gugus depan
(sekolah) nyaris tak terdengar. Membangkitkan kegiatan di gugus
depan merupakan prioritas gerakan Pramuka pasca orde baru.
Kelima, menggalang kekuatan, baik dukungan dana maupun
pemikiran dari para pakar, intelektual, donatur, dengan tidak
mengikat mereka masuk koridor organisasi. Prinsip sukarela,
memang masih patut dipertahankan lantaran dengan
mengotomatiskan mereka yang memberi dukungan masuk di wilayah
gerakan Pramuka, berarti memaksa mereka bergabung.
Menjaring Angin
Memang kalau direnungkan, paradigma baru di atas bagai
menjaring angin. Namun demikian, sejarah membukktikan kalau kita
meraih sesuatu dengan usaha kerja keras tak kenal lelah, tentu
hasilnya akan memuaskan dan berkembang permanen. Pramuka
pasca orde baru tidak boleh mengulangi kesalahan format orde baru
yang hanya bisa bertahan, tetapi tidak mempuyai fondasi kuat.
HUT Pramuka ke-39 ini, saatnya utuk menggalang dan
merapatkan kembali barisan menyongsong era kemandirian dengan
memprioritaskan kegiatan yang ada di gugus depan. Akhirnya,
dirgahayu gerakan Pramuka. Semoga menjadi organisasi independen.
Trimo, alumnus IKIP Semarang, sekretaris Kwartir Ranting
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
―dimuat di koran Wawasan 14 Agustus 2000.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 195
SISTEM GUGUS TERPADU
UNTUK MENGEEFEKTIFKAN KELOMPOK KERJA GURU
Oleh Trimo
Berbicara peningkatan mutu pendidikan khususnya di Sekolah
Dasar bukan hal baru di kalangan pendidik lantaran tolok ukur
kemampuan yang disyaratkan selalu berawal dari Sekolah Dasar
yang merupakan satuan pendidikan formal pertama, mempunyai
tanggung jawab mengembangkan sikap dan kemampuan, memberi
pengetahuan dan keterampilan dasar.
Secara signifikan, hal tersebut juga termaktub dalam tujuan
pendidikan nasional yaitu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia Indonesia yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian,
disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas,
dan terampil serta sehat jasmani rohani.
Mengacu tujuan tersebut, Direktorat Pendidikan Dasar
berupaya melakukan berbagai usaha peningkatan mutu personel atau
peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan
yaitu dengan mengadakan rintisan Sistem Pembinaan Profesional
guru, meningkatkan mutu personel tenaga kependidikan yang
diharapkan dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar,
ditandai dengan penguasaan kompetensi guru.
Realisasi dari program tersebut dijabarkan dalam bentuk gugus
sekolah yang terdiri satu sekolah sebagai SD Inti dan SD lain sebagai
SD imbas, sehingga satu gugus sekolah paling banyak terdiri atas 8
SD. Pada SD Inti dibentuk Pusat Kegiatan Guru (PKG) yang di
dalamnya terdapat kegiatan berupa Kelompok Kerja Guru (KKG),
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Kelompok Kerja
Pengawas Sekolah (KKPS). Kelompok kerja ini berfungsi sebagai
196 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
wadah peningkatan mutu profesional guru dan tenaga kependidikan
dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Datang Duduk Dengar Makan Canda Pulang
Secara ringkas PKG berfungsi sebagai sanggar kerja guru dan
pusat kegiatan KKG, KKKS, dan KKPS. Sebagai sanggar kerja guru
seharusnya PKG merupakan tempat yang dicintai guru, bukan
semata-mata tempat pertemuan tiap Sabtu. Namun keberadaan PKG
disyaratkan mampu menjadi sentral aktivitas guru dalam lingkup
makro yang dikemas sistem pembinaan profesional. Tujuan PKG dan
sistem pembinaan profesional sebetulnya sudah mengarah
peningkatan kemampuan guru dalam proses kegiatan belajar
mengajar. Realisasi dari tujuan luhur tadi akan bermuara pada titik
kompetensi yang diharapkan dikuasai guru.
Oleh karena itu sudah tentu keberadaan PKG harus benar-
benar eksis dan memiliki sarana memadai, seperti ruang
perpustakaan guru, ruang kerja/praktik dan ruang pertemuan.
Idealnya lagi semua hasil karya dan kerja guru, kepala dan pengawas
sekolah dapat dipresentasikan sehingga PKG berfungsi sebagai
bengkel kerja, sanggar kegiatan, pusat sumber belajar dalam
meningkatkan profesi.
Ditinjau dari validitas tampang (face validity) keberadaan
PKG memang ada dengan ditandai papan nama PKG di masing-
masing SD Inti. Namun, jika dilihat lebih khusus dari sisi validitas isi
(content validity) terkadang sistem dan format pelaksanaannya
kurang efektif sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai
optimal.
Kegiatan KKG yang lazim diadakan tiap hari Sabtu ternyata
masih tanda tanya besar bagi guru yang menganggap kegiatan KKG
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 197
hanya serangkaian kegiatan klasik: datang, duduk, dengar, makan,
canda, dan pulang, tanpa membawa hasil.
Ketidakefektifan pelaksanaan KKG dapat dilihat dari antusias
guru dalam mengikuti kegiatan tersebut. Banyak guru yang
mengikuti KKG hanya karena “takut” kepada kepala sekolah, bukan
karena ada motivasi intrinsik untuk pengembangan kompetensi.
Setidaknya ada lima hal yang menyebabkan taraf signifikansi KKG
baru sebatas face validity yakni: (1) Kurangnya variasi materi yang
disampaikan KKG, (2) Waktu pelaksanaan terlalu sering, (3) Sentral
pelaksanaan statis, baik waktu dan tempat, (4) Kurangnya sarana
prasarana, (5) Kurangnya narasumber, (6) Minimnya kreativitas guru
dalam mengembangkan materi.
Kompetensi Guru
Adanya sinyalemen yang bergerak negatif terhadap
pelaksanaan KKG memang menarik untuk dicermati lantaran
pelaksanaan cenderung monoton menjadikan sebagian peserta KKG
enggan mengikuti sungguh-sungguh. Padahal pada awalnya
perumusan format kegiatan KKG yang merupakan kegiatan inti dari
PKG diharapkan mampu menambah wawasan guru mengenai
berbagai masalah yang muncul dalam proses KBM untuk dapat
meningkatkan kompetensi guru.
Menurut Waridjan (1984:20) kompetensi diartikan
seperangkat tindakan inteligen (tindakan yang didasari pemikiran
rasional dan sebelumnya dipelajari) dengan penuh tanggung jawab
yang harus dimiliki seseorang untuk dianggap mampu melaksanakan
tugas-tugas bidang pekerjaan. Pendekatan kompetensi memberikan
tekanan khusus kepada pembentukan kompetensi secara langsung
dan sistematis yaitu mengkaji dan menguji kaitan antara persyaratan
tugas dan kompetensi serta pengalaman belajar. Kompetensi yang
dimaksud adalah kompetensi personal, profesional, dan sosial.
198 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Secara ringkas dapat diartikan bahwa kompetensi profesional
merupakan penguasaan bidang akademik yang terpadu dengan
penguasaan metodologi pengajaran. Kompetensi personal adalah
sikap pribadi yang dijiwai filsafat hidup, sedangkan kompetensi
sosial berhubungan dengan kemampuan guru dalam bergaul dan
menyesuaikan diri pada lingkungan masyarakat.
Menurut T. Raka Joni (1980:12) kompetensi yang harus
dimiliki tenaga pendidik yaitu kompetensi profesional, personal, dan
sosial. Kompetensi profesional meliputi: (a) Memiliki daya
pengertian, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan luas dan
mendalam tentang anak didik melalui ilmu teoretis maupun
pengalaman, (b) Mantap ilmu pengetahuannya, (c) Mampu
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d)
Mampu mendidik yang berarti harus menguasai materi, metode,
kondisi anak, tujuan pendidikan, memotivasi anak, menilai hasil
belajar dan membimbingnya, (e) Mempunyai bakat mendidik, sabar,
dan penuh inisiatif kreatif.
Kompetensi personal meliputi: (a) Mempunyai latar belakang
dan reputasi baik, (b) Berpandangan luas, berhati jujur, tulus, sportif,
dan simpatik, (c) Bebas dan bersih dari sombong dan egois, (d)
Berjiwa matang dan dinamis, (e) Panjang akal, sabar, tabah, dan mau
bekerja dalam arti membaktikan diri demi tugas, (f) Bersih dari sifat
pilih kasih pada murid, dan (g) Mempunyai kewibawaan di mata
murid.
Kompetensi sosial meliputi: (a) Berpikiran, berperasaan,
berbuat pantas dan layak di masyarakat, (b) Bertanggung jawab
terhadap anak didik, (c) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat
secara lebih luas demi kepentingan pendidikan.
Ketiga kompetensi di atas idealnya harus dikuasai guru agar
acuan peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan retorika
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 199
belaka. Forum KKG merupakan ajang mewujudkan ketiga
kompetensi yang harus dimiliki guru.
Gugus Terpadu
KKG berorientasi pada peningkatan kualitas pengetahuan,
penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru dan murid,
metode mengajar, dan lain-lain yang berfokus pada penciptaan
kegiatan belajar mengajar efektif. Format lama kegiatan KKG selalu
dilaksanakan setiap Sabtu usai pelajaran, pada waktu dan tempat
yang sama. Hal tersebut akan membuat guru menjadi jenuh lantaran
kerap terjadi pengulangan materi. Kondisi tersebut kadang
diperparah dengan tutor atau penyampai materi yang tidak
menguasai bahan sehingga menjadikan proses KKG hanya ajang
datang, duduk, dengar, makan, canda, dan pulang.
Untuk mewujudkan seperangkat kompetensi, ada baiknya
KKG dengan format lama perlu direformasi agar pelaksanaannya
dapat dinamis. Menurut saya, format ideal pelaksanaan KKG adalah
sistem gugus terpadu.
Sistem gugus terpadu didasari pemikiran bahwa keefektifan
peran dan fungsi PKG dalam sistem pembinaan profesional sebagai
upaya meningkatkan kompetensi guru dengan memajukan
pelaksanaan KKG tingkat gugus dan kecamatan. Sebagai gambaran
ideal KKG dengan paradigma baru lebih mengutamakan kualitas.
Pelaksanaan setiap dua minggu sekali dengan ketentuan minggu
pertama berada di masing-masing gugus mandiri di mana tempat
pelaksanaannya bergiliran. Sedangkan minggu kedua dilaksanakan
terpadu seluruh gugus di suatu tempat gugus terpadu.
Permasalahan yang muncul di KKG tingkat gugus mandiri
selanjutnya dibahas dalam KKG tingkat gugus terpadu. Masalah-
masalah yang muncul diklarifikasi untuk dipilih sebagai materi pada
pertemuan KKG berikutnya. Masalah yang dipilih difokuskan pada
200 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
masalah aktual dan bersifat inovatif untuk meningkatkan kompetensi
guru.
Narasumber
Yang lebih spesifik lagi dalam format KKG ini selalu
mendatangkan narasumber kompeten untuk masalah yang akan
dibahas sehingga diharapkan penguasaan kompetensi guru dapat
terwujud signifikan. Narasumber menjadi salah satu komponen
penting dalam memecahkan persoalan sehingga format KKG dengan
sistem gugus terpadu dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap
materi secara valid dan reliabel.
Paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk
merealisasikan format KKG dengan sistem gugus terpadu yaitu: (a)
Restrukturisasi organisasi, KKG yang berada di tingkat kecamatan,
(b) Refungsionalisasi peran, (c) Penyediaan sarana dan prasarana
memadai, (d) Komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab antara
guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
Sudah tentu untuk mencapai kondisi ideal seperti yang
diharapkan dalam format sistem gugus terpadu membutuhkan sarana
dan prasarana memadai. Oleh karena itu, koordinasi dan negoisasi
berbagai komponen pendidikan akan membuat format gugus terpadu
menjadi solid dan layak dijadikan acuan pelaksanaan KKG yang
akhirnya berakhir sebagai conditio sine qua non (keharusan kondisi
yang tidak dapat dielakkan). Dengan demikian, kompetensi
profesional, personal, dan sosial yang diharapkan dimiliki guru juga
dapat tercapai optimal.
Alumnus IKIP Semarang, guru SDN Sarirejo 01, Kaliwungu, Kendal
―dimuat di Tabloid Inspirator, Minggu I, 01-08 Februari 2001.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 201
PENYELENGGARAAN TES SUMATIF
GURU HANYA TUKANG MENGAJAR
Oleh Trimo
Pada pekan ini, lembaga pendidikan formal disibukkan urusan
evaluasi, yang di telinga masyarakat lebih akrab dengan istilah
testing. Secara ideal, testing dimaksudkan mengetahui sejauh mana
penguasaan materi pelajaran yang diberikan guru sesuai target
kurikulum yang dibebankan. Karenanya, muncul istilah tes formatif,
sumatif, diagnostik, dan penempatan.
Tes formatif merupakan tes yang diberikan guru setiap akhir
pokok bahasan materi pelajaran. Tes sumatif merupakan gong
penilaian berbagai pokok bahasan, yang diadakan setiap akhir catur
wulan. Sementara tes diagnostik berorientasi pada upaya guru
mengungkap kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Jika tes
yang diberikan untuk menempatkan siswa sesuai kemampuan dan
karakteristik individualnya, tes yang tepat adalah tes penempatan.
Fokus dari uraian ini adalah penyelenggaraan tes sumatif yang
secara signifikan perlu mendapat perhatian, lantaran format dan
pelaksanaannya cenderung monopoli sentralistik. Pada rentang
tingkat sekolah (SD, SLTP dan SMU), terkontaminasi menjadi 3
catur wulan. Hal itu berarti setiap sekolah perlu mengadakan tes
sumatif selama 3 kali. Lantas, berbagai pertanyaan muncul implisit
dan eksplisit: sudahkah tes sumatif yang selama ini diadakan bisa
mewakili kepentingan, kebutuhan, dan kreativitas anak secara
makro? Format penyelenggaraan yang kerap diborong (dijadikan
bisnis) apakah sudah menjadi tolok ukur bahwa sekolah yang
bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan tes mandiri? Lantas,
paradigma apa yang perlu dikembangkan untuk mendesain
penyelenggaraan tes sumatif agar sekolah mempunyai otonomi luas
202 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
dalam pengembangan kreativitas menuju peningkatan kompotensi
guru?
Tukang Mengajar
Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan cermin penindasan hak
yang selama ini tidak dirasakan pendidik. Bahkan secara ironis,
pendidik merasa lega dan tidak terbebani pelaksanaan tes sumatif.
Oleh karena itu ada sinyalemen yang berkembang bahwa pendidik
hanya menjadi tukang mengajar bukan pendesain kegiatan belajar
mengajar.
Sebagai tukang, pendidik hanya bekerja dengan format dan
pola klasik cenderung monoton yaitu mengajar dan menilai dalam
terminologi tes formatif. Itu artinya pendidik seperti tidak
mempunyai kewajiban mendesain format dan gambaran ideal dari
penilaian tes sumatif. Akan berbeda jika peran pendidik menjadi
pendesain kegiatan belajar mengajar. Ia (pendidik) akan secara total
dan komprehensif bekerja dengan pola sesuai tingkat kreativitas dan
kejelian pendidik dalam mengembangkan seperangkat kurikulum.
Teknik penilaian sumatif akan menjadi menarik bagi pendidik
ketika fungsi otoritas, baik pribadi maupun lembaga sekolah diberi
penuh menyelenggarakan tes sumatif secara mandiri dengan
berpedoman kurikulum. Bukan dikelola kelompok tertentu, seperti
format dan pola yang lazim dipakai kalangan SD di mana tes sumatif
semester I dikelola Gugus Sekolah (gabungan beberapa SD atau
Depdiknas Kecamatan) dan semester II (Depdiknas Kabupaten/Kota
Madya).
Format lama yang akhirnya menjadi pola abadi itu secara
umum memang merupakan produk perjalanan sejarah pendidikan
kita tempo dulu. Padahal sekarang kita berada dalam era yang
memerlukan adanya sumbang pikir. Ketika bertahan dengan format
lama, kita hanya bisa bertahan. Bertahan menjadi seorang tukang
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 203
mengajar yang hanya menyiapkan peserta didik menjadi robot dan
bertahan sekadar menyelamatkan kerancuan pola yang tanpa sadar
merampas otoritas dan legalitas profesional.
Target Kurikulum
Secara jujur sebetulnya kerancuan pola tes sumatif harus
dirasakan pendidik ketika sebagai seorang manajer tiba-tiba
mendapati peserta didiknya tidak optimal dalam memenuhi produk
yang diharapkan. Bahkan tidak jarang pendidik tidak habis pikir
ketika mengetahui soal-soal yang ada dalam tes sumatif belum
sempat dibahas detail. Akan lebih parah lagi ketika pendidik hanya
terpukau dalam kegelisahannya sementara ia mengerti bahwa soal-
soal tes sumatif yang dikerjakan peserta didik akan lebih bermutu
jika ia sendiri yang mendesain.
Kondisi ironis penyelenggaraan tes sumatif lantaran tidak
adanya satu garis lurus yang saling berhubungan antara guru dan
siswa didasari target dan beban kurikulum. Sistem penyelenggaraan
pendidikan di negara kita sarat akan muatan kognitif saja yang
membawa dampak bagi pendidik untuk bekerja borongan. Peserta
didik selalu dijejali materi metode drill agar target kurikulum
terselesaikan. Ironisnya lagi, beban tersebut mau tidak mau mutlak
dilaksanakan pendidik, padahal kondisi masing-masing daerah
berbeda.
Perbedaan kondisi daerah inilah yang seharusnya dijadikan
bahan renungan agar formatif tes sumatif diberi penuh pada pendidik
di masing-masing sekolah. Hal ini cukup beralasan lantaran pendidik
di suatu sekolahlah yang mengetahui batas kemampuan anak
terhadap seperangkat target kurikulum yang dibebankan. Bukan
pendidik di sekolah lain, apalagi orang-orang di belakang meja.
Karakteristik dan kebutuhan yang diharapkan peserta didik sangat
majemuk. Karenanya pengembalian otoritas penyusunan tes sumatif
204 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
akan menghidupkan kembali kebekuan alam berpikir pendidik
sehingga lebih kreatif dalam mengevaluasi materi pelajaran
disyaratkan.
Pemikiran ini sekaligus menjadi tantangan bagi sekolah untuk
menyiapkan sejak dini adanya otonomi yang juga terkesan
dipaksakan. Sedangkan bagi Depdiknas, format ini menjadikan
lembaga tersebut independent dan sekaligus menepis anggapan
bahwa tes sumatif bukan lahan bisnis.
Otonomi Sekolah
Gambaran format ini setidaknya menjadi paradigma baru
dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri kita. Menurut saya,
untuk mencapai kondisi ideal di mana otonomi sekolah (khususnya
perihal tes sumatif) menjadi kebutuhan primer ada beberapa hal yang
patut dikaji dan dianalisis.
Pertama, perampingan kurikulum yang lebih dilandasi
karakteristik dan kebutuhan peserta didik, bukan target. Ada baiknya
sekolah diberi keleluasaan memilih berbagai alternatif pokok
bahasan yang disajikan pemerintah, dengan pengelompokkan wajib
dan pilihan. Wajib dalam arti materi itu harus diajarkan lantaran
merupakan fondasi menuju pemahaman selanjutnya, sedangkan
pilihan lebih mengacu pada karakteristik dan kebutuhan peserta
didik.
Kedua, uji tolok ukur yang dimaksudkan menyiapkan
gambaran ideal yang diharapkan mampu dimiliki peserta didik ketika
menyelesaikan materi pelajaran. Dalam pengertian sederhana, paling
tidak ada perolehan minimal yang disyaratkan atas proses
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tolok ukur
keberhasilan inilah yang nantinya akan memberi warna pluralitas
kemajemukan pendidikan di negara kita. Majemuk dalam pengertian
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 205
format pendidikan kita akan kaya berbagai variasi materi yang
dilegalkan pemerintah.
Ketiga, uji otoritas yang berkaitan kemampuan personal
pendidik dan sekolah untuk mendesain segala bentuk kegiatan
belajar mengajar makro. Lebih spesifik lagi otoritas penyelenggaraan
tes sumatif yang merupakan titik kulminasi serangkaian perjalanan
yang ditempuh peserta didik.
Keempat, uji pengawasan yang lebih dekat peran Depdiknas
dalam mengarahkan penyelenggaraan otonomi tes sumatif agar soal-
soal yang dirumuskan pendidik dapat reliabel (diakui kebenarannya),
sahih (valid) dan praktis. Selebihnya legalitas dari Depdiknas sangat
diperlukan guna meningkatkembangkan kompetensi guru yang
meliputi personal, profesional, dan kemasyarakatan.
Ada pepatah Jawa, ―Jer Basuki Mawa Bea‖ barangkali itulah
yang terjadi jika otonomi penyelenggaraan tes sumatif disentralkan
ke sekolah. Oleh karena itu kemampuan sekolah dalam
penyelenggaraan tes sumatif juga memerlukan pemikiran baik moral
dan materiil. Sejarah membuktikan, tidak ada keberhasilan secara
tiba-tiba, tetapi memerlukan proses dan dimensi waktu panjang.
Kesungguhan dan kecermatan pendidik dalam
menumbuhkembangkan potensi peserta didik akan menelurkan
postur anak-anak bangsa yang dapat menjadi tulang punggung
pembangunan negeri.
__dimuat di Tabloid Inspirator, Minggu III, 16-22 Maret 200).
206 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
PEMBERIAN VITAMIN D MASIHKAH BERLAKU?
Oleh Trimo
Sebuah organisasi tentu memiliki sejumlah komponen
terintegrasi terpadu. Efisiensi dan efektivitas tiap komponen biasanya
bersimbiosis bebas sesuai peran yang disyaratkan untuk tujuan
tertentu. Organisasi dalam lingkup pendidikan misalnya, senantiasa
berhubungan bebas dengan pluralitas komponen untuk mewujudkan
visi dan misi serta target lembaga pendidikan tersebut. Karenanya,
kemajemukan komponen dalam melakukan transaksi edukasi
diperlukan seorang pemimpin yang mempunyai totalitas kompetensi.
Dalam lingkup lembaga pendidikan formal, terdapat seorang
pemimpin yang lazim disebut kepala sekolah. Sedangkan dalam
dunia perguruan tinggi, sebutan kepala sekolah dikenal dengan
rektor. Antara kepala sekolah dan rektor sebetulnya tidak ada
perbedaan berarti. Keduanya sama-sama merupakan pemimpin
lembaga pendidikan. Perbedaan yang tampak adalah lamanya
mekanisme pemegang jabatan.
Jabatan rektor adalah sampiran tidak abadi, artinya seorang
rektor dapat kembali menjadi dosen seperti sediakala jika dalam
komunitas lembaga tersebut sudah mempunyai atau memilih orang
lain. Dengan demikian jabatan rektor dibatasi waktu. Sedangkan
dalam dunia pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, jabatan kepala
sekolah boleh dikatakan seumur hidup. Mereka (kepala sekolah)
tidak akan kembali bertugas menjadi guru, walau yang bersangkutan
sebetulnya sudah tidak mampu melakukan aktivitasnya secara total.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 207
Abadi
Pemungsian jabatan kepala sekolah secara abadi akan
berdampak pada penurunan kinerja dan proses transaksi edukasi
menjadi statis. Kepala sekolah yang memasuki usia tua, kebanyakan
tidak cukup andal mengelola lembaga pendidikan. Hal ini bisa dilihat
dari minimnya aktivitas, prestasi, dan etos kerja dari lingkup
pendidikan yang dipimpinnya. Apalagi kalau jabatan kepala sekolah
yang disandangnya didapat layaknya mengarbit pisang muda, tentu
malapetaka lambat laun menghiasi dunia pendidikan kita.
Ironisnya, ketika muncul fenomena kepala sekolah yang
cenderung diam di kursinya, produk hukum pendidikan kita tidak
mampu memberi pelajaran tegas. Hal ini lantaran seorang kepala
sekolah berasumsi bahwa ia tidak mungkin dicopot jabatannya.
Fenomena ini kerap terjadi, bukan di dunia pendidikan
perdesaan/pinggiran kota saja, tetapi juga perkotaan.
Kepala sekolah di daerah perdesaan/pinggiran kota biasanya
hanya duduk, menunggu jam pulang berdentang. Kadang bisa
berangkat telat dan pulang gasik lantaran jauh dari pengawasan.
Berbeda bila kepala sekolah berada di perkotaan, pada mulanya aktif
mengintegrasikan berbagai komponen demi kemajuan sekolah yang
dipimpinnya. Namun lambat laun lantaran banyak celah bernuansa
uang, terjadi pergeseran pemikiran. Mengemban tugas bukan lagi
berpikir memajuan sekolah, tetapi bagaimana mendapat peluang
bisnis dengan para penerbit Lembar Kegiatan Siswa (LKS) atau
perusahaan lain yang dapat memberi keuntungan material.
Pergeseran Tugas
Itulah potret kepala sekolah di dunia pendidikan kita. Walau
tidak semua kepala sekolah menunjukkan adanya pergesaran tugas
dan tanggung jawab, tetapi fakta empiris kebanyakan para kepala
208 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
sekolah khususnya SD menunjukkan kecenderungan berspekulasi
bisnis di bidang yang seharusnya tidak layak dijadikan ajang bisnis.
Lantas muncul serangkaian pertanyaan, mengapa sinyalemen
itu bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Mekanisme
rekrutmen yang bagaimana sehingga menelurkan kepala sekolah
karbitan? Masihkah budaya vitamin D (baca: duit) masih dilestarikan
di iklim negara yang memasuki era reformasi? Masih adakah celah-
celah KKN dalam pengangkatan dan penempatan kepala sekolah?
Sebetulnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan
interogated yang sekiranya mampu mengungkap selubung budaya
eufimistik warisan perjalanan sejarah. Namun paling tidak
pertanyaan di atas dapat mewakili permasalahan yang harus segera
dituntaskan demi peningkatan kualitas pendidikan nasional dan
moral serta mentalitas para penyelenggara pendidikan.
Seorang teman yang kebetulan gagal dalam rekrutmen kepala
Sekolah Dasar, menceritakan panjang lebar perihal proses perjalanan
kegagalannya. Hal menarik dari cerita teman saya tadi adalah adanya
persaingan mencari dukungan yang ujung-ujungnya pada budaya
pemberian vitamin D yang harus diberikan kepada oknum-oknum
yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen.
Tidak bisa dimungkiri, budaya pemberian vitamin D seperti
menjadi keharusan yang tidak diwajibkan. Ironisnya, walau tidak
diminta secara langsung dan tegas, orang-orang yang berambisi
menduduki jabatan kepala sekolah, tahu diri dan ewuh pakewuh
sehingga dengan kesadaran rela berdarma vitamin D. Bahkan ada
yang merasa pemberian vitamin D untuk memuluskan jalan menjadi
kepala sekolah merupakan upeti, layaknya kawula yang “pasrah
bulu bekti, glondhong pengareng-areng, peni-peni raja peni, guru
bakal-guru dadi‖ kepada rajanya.
Mentalitas para penentu kebijakan pengangkatan dan
penempatan kepala sekolah perlu dipertanyakan. Apalagi dengan
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 209
dalih bahwa vitamin D yang dimaksud bukan kehendaknya dan itu
tidak bisa dibuktikan lantaran tidak ada tanda bukti pembayaran.
Mereka selalu berasumsi bahwa vitamin D yang diterima merupakan
rezeki tidak boleh ditolak.
School Master dan Head Teacher
Fenomena pentingnya vitamin D sebagai data pendukung
utama proses rekrutmen kepala sekolah sudah jelas akan
mengaburkan fungsi utama seorang kepala sekolah sebagai school
master dan head teacher. Sebagai school master, kepala sekolah
diharapkan mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan
mengerahkan segala sumber daya yang ada di lingkungan sekolah
yang dibina bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar efektif dan
efisien.
Sedangkan sebagai head teacher, seorang kepala sekolah
disyaratkan mampu menguasai manajerial, merancang,
melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar.
Selebihnya diharapkan mampu menampung keinginan masyarakat
yang berkaitan peningkatan mutu sekolah yang dipimpinnya.
Ditinjau dari satu sudut fungsi saja, sudah terlihat betapa ada
ketimpangan yang signifikan sekali. Seorang kepala sekolah yang
diangkat dengan berbasis dukungan vitamin D akan kesulitan
memerankan fungsinya sebagai school master dan head teacher. Hal
ini lantaran kepala sekolah yang bersangkutan hari-harinya akan
selalu diliputi pemikiran bagaimana mengembalikan vitamin D yang
pernah dikeluarkan, bukan berpikir bagaimana
meningkatkembangkan potensi dan sumber daya sekolah yang
dikelola.
Kondisi dilematis inilah akhirnya melahirkan bisnis
pendidikan dengan objek peserta didik yang harus membeli berbagai
produk pelajaran di luar batas. Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang
berada di perkotaan (SD misalnya), seringkali mewajibkan peserta
210 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
didiknya membeli berbagai lembar kegiatan siswa (LKS) yang
sebetulnya bukan bermaksud menambah wawasan anak, tetapi
semata-mata untuk keuntungan sekolah.
Lebih parah lagi, apabila beberapa LKS yang dibeli tidak
dibahas secara tuntas, hanya dikerjakan anak sementara materi yang
ada belum sempat diterangkan pendidik. Sedangkan pendidik sendiri
merasa tidak ada beban sama sekali, lantaran memegang kunci
jawaban dari LKS tersebut.
Transparan Penilaian
Ilustrasi di atas merupakan wujud nyata mekanisme
pengangkatan kepala sekolah yang kurang qualifaid. Oleh karena itu
perlu dirumuskan mekanisme transparan sehingga dapat menekan
seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang melahirkan KKN
gaya baru. Menurut saya, ada beberapa mekanisme yang perlu
ditempuh.
Pertama, tahap perencanaan yang ditandai dengan penyiapan
seperangkat aturan dan penilaian proses rekrutmen, khususnya yang
berkaitan administrasi. Aturan tersebut disebarluaskan dan hasil
penilaian rekrutmen juga harus disampaikan transparan sehingga
kepala sekolah yang diangkat benar-benar memenuhi aturan yang
ditetapkan perolehan nilai tertentu.
Secara rinci, aturan tersebut meliputi: (1) Masa kerja, tiap 1
tahun mendapat nilai 1, pangkat/golongan ruang (minimal III a
dengan bobot nilai 20, selisih satu tingkat terpaut 5 nilai); (2) Basis
pendidikan (minimal D II bobot nilai 40, S1 (75), S2 (110), dan S3
(150); (3) Prestasi guru/guru teladan/lomba kreativitas guru (tingkat
Kec. bobot nilai 15, Kab/Kota (25), Provinsi (75), dan Nasional
(100); (4) Karya ilmiah/makalah/artikel/hasil penelitian, tiap karya
dihargai 5; (5) Keaktifan dalam organisasi profesi dan masyarakat,
dengan bobot nilai 5 (Kec), 10 (Kab/Kota), 15 (Provinsi), 25
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 211
(Nasional); (6) Keikutsertaan penataran, seminar, dan sejenisnya,
tiap sertifikat dihargai 2 (Kec), 5 (Kab/Kota), 5 (Provinsi), 10
(Nasional).
Kedua, tahap uji penguasaan kompetensi melalui tes tertulis
dan wawancara yang mengacu pada pemahamam fungsi dan tugas
kepala sekolah sebagai school master dan head teacher. Tes tertulis
perlu didesain dengan mengaktualisasikan domain kognitif, afektif,
dan psikomotor. Dengan demikian format yang cocok adalah tes
uraian, bukan pilihan ganda.
Dengan mengacu aturan main tadi, seorang pendidik yang
mencalonkan kepala sekolah harus berlomba-lomba meraih nilai
tertinggi yang tidak dapat dimanipulasi. Hasil penilaian baik
administrasi dan tes tertulis/wawancara pada akhirnya ditabulasi
transparan, didistribusikan ke masing-masing sekolah. Paradigma ini,
nantinya akan menepis anggapan bahwa pengangkatan kepala
sekolah harus menggunakan vitamin D sebagai uang pelicin.
Selebihnya, keberanian penyelenggara pendidikan untuk
menerbitkan aturan mengenai pembatasan masa jabatan kepala
sekolah sangat diharapkan agar seorang kepala sekolah yang
diangkat dapat memungsikan diri sebagai shool master dan head
teacher secara optimal dalam menumbuhkembangkan potensi dan
prestasi sekolah yang dipimpinnya.
__dimuat di koran sore Wawasan, 14 Mei 2001.
212 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
PRAMUKA AGUSTUSAN, MASIHKAH?
Oleh Trimo
Hari ini 14 Agustus, seluruh anggota gerakan Pramuka
memperingati hari ulang tahunnya ke-40. Di usiannya yang masih
produktif, gerakan Pramuka dewasa ini menghadapi tantangan begitu
kompleks. Era informasi dan globalisasi yang dibarengi reformasi
melanda di berbagai bidang kehidupan dan berdampak pada generasi
muda. Kondisi bangsa yang tidak menentu menjadikan nuansa
dekadensi moral menjadi rentan terhadap berbagai perilaku agresi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menyadari adanya hal tersebut, pemerintah bersama
masyarakat perlu cancut taliwanda bergerak cepat dengan segala
kemampuan memadamkan api dekadensi moral menjadi api
kebangkitan, di antaranya melalui berbagai organisasi massa seperti
karang taruna, olahraga, kesenian, PMR, Pramuka, dan lain-lain.
Dari sekian banyak organisasi, hanya Pramuka yang dapat
menampung dan menyediakan tempat bagi masyarakat luas.
Mereka yang berumur 7-10 tahun dibina dalam Pramuka
Siaga, 11-15 tahun di Pramuka Penggalang, 16-20 tahun mengikuti
Pramuka Penegak, 21-25 tahun termasuk golongan Pramuka Pandega
dan 25 tahun ke atas termasuk golongan Pramuka Pembina. Selain
itu gerakan Pramuka juga membina Pramuka luar biasa, gugus depan
di berbagai instansi pemerintah, satuan karya, gugus depan
perwakilan RI di luar negeri dan menyediakan tempat bagi mereka
yang berusia senja dalam Pandu Wreda dan Hiprada. Dengan
kemampuan dan kekuatan merata, mampukah gerakan Pramuka
menjadi payung penyelamat generasi muda dan sekaligus menjawab
tantangan dekadensi moral? Lalu bagaimana dengan kesiapan
Pramuka, baik kuantitas maupun kualitas?
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 213
Obor Belarak
Tak perlu diragukan lagi, gerakan Pramuka mempunyai tugas
pokok menumbuhkan tunas-tunas bangsa agar menjadi generasi
muda berkekuatan batin, berpancasila, berwatak luhur, cerdas,
terampil, kuat, dan sehat serta mampu menyelenggarakan
pembangunan. Tugas pokok amat berat tadi, agaknya masih
dipandang sebelah mata kebanyakan generasi muda. Ada semacam
anggapan, mengikui Pramuka adalah kampungan dan tidak nge-trend
sehingga pencapaian tugas pokok gerakan Pramuka tersendat-sendat
karena kurangnya dukungan generasi muda. Mengapa generasi muda
seperti antipati Pramuka?
Dalam konteks aplikatif, ada beberapa alasan kurangnya minat
dan perhatian generasi muda (peserta didik di bangku sekolah)
terhadap gerakan Pramuka.
Pertama, kurangnya pengembangan materi kepramukaan yang
berdampak adanya istilah Pramuka obor belarak dalam artian
keikutsertaan dalam kegiatan Pramuka hanya tahap awal. Biasanya
latihan pertama peserta didiknya masih banyak, tetapi lambat laun
berkurang. Jika gugus depan/sekolah yang bersangkutan
menyelenggarakan kegiatan perkemahan, hampir seluruh peserta
didik yang tadinya pasif kegiatan menjadi aktif mendadak.
Kedua, kebanyakan pembina pramuka di suatu gugus depan
baik Siaga, Penggalang, Penegak/Pandega kurang aktif membina.
Mereka (Pembina) merasa lebih enak menyerahkan pembinaannya
kepada pembina dari luar. Hal seperti ini dapat menimbulkan rasa
enggan dan malas karena kurang adanya pengawasan.
Ketiga, di samping sikap antipati generasi muda, gerakan
Pramuka juga menghadapi kendala dalam hal kuantitas sehubungan
adanya realitas semu, artinya ada ketidaksesuaian antara data
anggota gerakan Pramuka yang berada di tiap-tiap kwartir dengan
kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, gugus depan A menurut data
214 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
di Kwartir Ranting anggota Pramuka Penegak ada 300 orang, tetapi
dalam latihan Pramuka yang berangkat tidak ada separuh. Realitas
semu seperti inilah kadang bisa menimbulkan adanya kuantitas tanpa
kualitas.
Keempat, adanya kesan Pramuka agustusan atau Pramuka
musiman. Kebanyakan masyarakat awam berasumsi begitu karena
mereka mengetahui kegiatan-kegiatan kepramukaan ketika bulan
Agustus, selain bulan itu hampir tidak pernah mendengar dan melihat
aktivitas Pramuka.
Kompetensi Pembina
Kendala kompleks tadi merupakan bahan ujian bagi gerakan
Pramuka, sejauh mana mempersiapkan seperangkat antisipasi guna
menetralisasi keadaan. Kendala tersebut memang betul-betul ada di
lapangan sehingga perlu sikap lapang dada dan kesadaran akan
berbagai kekurangan guna peningkatan, baik segi kuantitas dan
kualitas.
Menurut penulis, gerakan Pramuka perlu berbenah agar tidak
baik luarnya saja, tetapi juga baik dalam dirinya. Pramuka obor
belarak tidak boleh terjadi. Antisipasi tepat adalah perlu adanya
keikutsertaan guru dalam proses pembinaan guna mendukung
keaktifan anak sebab secara rasional anak akan pekewuh jika tidak
berangkat latihan. Selain itu Pembina perlu memperbanyak kegiatan
di lapangan, wide game, penjelajahan lingkungan sekitar, dan
berkemah sehingga peserta didik tidak jenuh dan menghilangkan
kesan bahwa Pramuka itu bisanya tepuk-tepuk saja. Artinya,
Pembina perlu memiliki kompetensi.
Kompetensi personal meliputi kesiapan diri seorang Pembina,
baik materi maupun mental. Secara materi seorang Penegak yang
diberi tanggung jawab membina Pramuka baik Siaga, Penggalang
maupun Penegak, tentu menguasai materi, tetapi secara mental masih
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 215
perlu penataan terutama dalam hal emosi yang grafiknya masih
cenderung naik dan sama dengan yang dibina.
Kompetensi profesional menyangkut syarat formal seorang
Pembina Pramuka, di mana harus melalui suatu pendidikan dari
Kursus Mahir Dasar (KMD), Kursus Mahir Lanjutan (KML), Kursus
Pelatih Dasar (KPD) dan Kursus Pelatih Lanjutan (KPL). Sudah
tentu seorang Pembina yang belum melalui pendidikan, tidaklah
lengkap dalam pembinaannya. Oleh karena itu bagi pembina yang
sudah melalui pendidikan agar aktif membina dan selalu
mendampingi pembantu Pembina menyampaikan materi agar tidak
terjadi penyimpangan, serta sesuai Prinsip-Prinsip Dasar Metode
Pendidikan Kepramukaan (PDMPK).
Pemantauan dari kwartir baik tingkat ranting sampai tingkat
nasional terhadap agenda kegiatan dan data anggota Pramuka sangat
diperlukan sehingga realitas semu dapat ditekan sekecil mungkin.
Apalagi gerakan Pramuka mendapat dukungan dari segenap unsur
pemerintah lantaran secara ex officio/otomatis dari kepala desa,
camat, bupati/wali kota, gubernur, menteri-menteri sampai dengan
presiden merupakan majelis pembimbing Pramuka di kwartirnya,
sehingga memudahkan pemantauan, di antaranya dengan lomba
antarkwartir.
Memasyarakatkan Pramuka dan mempramukakan masyarakat
merupakan hal signifikan sebagai wahana penataan dan
pengembangan sumber daya manusia. Keberadaan Satuan Karya di
hampir seluruh dimensi kehidupan merupakan wujud nyata peran
serta Pramuka dalam memberikan setitik bakti untuk negeri
Indonesia.
Pluralitas Kegiatan
Untuk mencapai suatu kondisi ideal di mana peran serta
Pramuka dapat efektif maka kualitas Pembina Pramuka perlu
216 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
ditingkatkan, di antaranya melalui berbagai penataran dan loka karya
pembina (Pentaloka), kursus-kursus, karang pamiran yang
merupakan pertemuan besar bagi para Pembina guna mendapat
masukan teknik-teknik membina yang menarik dan mengandung
pendidikan. Pluralitas kegiatan perlu dikembangtingkatkan seperti
kegiatan teknologi tepat guna, PBB dengan kolone tongkat,
kreativitas menyampaikan semapore dan morse, pioneering, berbagai
lagu dan permainan serta teknik penyelenggaraan kegiatan di
lapangan seperti berkemah, penjelajahan, pengembaraan, dan lain-
lain.
Sebelum bergulirnya perjalanan bangsa yang tidak menentu,
gerakan Pramuka pernah mencanangkan Sapta Karsa Utama Gerakan
Pramuka yang merupakan paradigma baru mengenai postur gerakan
Pramuka tahun 2000 dengan segala upaya peningkatan kuantitas dan
kualitas. Kuantitas diharapkan pada tahun 2000 gerakan Pramuka
minimal beranggotakan 10% dari jumlah penduduk seumur,
sedangkan kualitas diharapkan seluruh anggota gerakan Pramuka
berupaya belajar dan membekali diri agar dapat membangun diri
sendiri serta mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa.
Namun dalam perjalanan, kendala reformasi mengadang
paradigma tersebut sehingga postur gerakan Pramuka tahun 2000,
tidak dapat terwujud seperti harapan semula. Oleh karena itu,
suasana yang secara evolusif sudah menunjukkan titik terang ini,
gerakan Pramuka diharapkan mampu memacu semangat anggotanya,
terutama generasi muda sebagai penerima dan pelanjut estafet
kepemimpinan bangsa. Apalagi bergulirnya otonomi daerah
memberikan peluang dan tantangan kemampuan Pramuka untuk
mandiri.
Dalam terminologi umum, para Pembina Pramuka perlu
berupaya mengaktualisasikan seluruh kompetensi sehingga mampu
menjadikan Pramuka sebagai payung lebar yang damai, tahan hujan,
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 217
badai dan panas, kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati,
mengajak dan merangkul generasi muda dengan tangannya yang
damai agar mereka tidak terdekadensi moralnya dan menemukan
kedamaian, seperti ditulis Boden Powell di bukunya Scouting For
Boy: “Memandulah terus, suatu saat akan kautemukan sesuatu yang
indah dan damai.”
Untuk itu gerakan Pramuka berharap kepada seluruh generasi
muda, ikutlah kegiatan Pramuka! Kepada seluruh anggota gerakan
Pramuka agar melakukan introspeksi dan retrospeksi agar di
kemudian hari gerakan Pramuka dapat meningkat baik segi kuantitas
maupun kualitas. Semoga di HUT Pramuka ke-40 ini, gerakan
Pramuka bertambah dewasa sehingga tidak akan istilah pramuka
obor belarak yang hanya menyala sebentar kemudian mati, tidak ada
ungkapan pramuka agustusan yang hanya terlihat aktivitasnya setiap
bulan Agustus, dan tidak akan ada anggota pramuka yang aras-
arasen. Semua “saeiyeg saeka kapti, sengkut gumregut” bersatu
bersama-sama meletakkan landasan kuat sebagai titik tolok Pramuka
dalam membina generasi muda.
Dirghayu Pramuka! Galang dan rapatkan barisanmu!
Semaikan tunas-tunas muda bangsamu! Negeri ini menanti setitik
baktimu! Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku!
__dimuat di koran Radar Semarang, 14 Agustus 2001.
218 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
MBG, MEWUJUDKAN PRAMUKA MANDIRI
Oleh Trimo
Bulan Agustus merupakan bulan keramat bagi bangsa
Indonesia, lantaran keberadaannya menjadi titik kulminasi
perjuangan bangsa yaitu kemerdekaan. Bulan Agustus juga menjadi
bulan sakral bagi anggota gerakan Pramuka, karena seluruhnya
memperingati hari jadi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan
HUT Pramuka ke-40 tahun ini masih terpola lagu lama. Kegiatan
renungan/ulang janji malam 14 Agustus, ziarah ke makam pahlawan
dan upacara apel besar Pramuka seakan-akan menjadi tradisi
Pramuka yang belum mengalami evolusi.
Halberbeda barangkali adalah terpilihnya Megawati sebagai
presiden, sehingga secara ex offisio menjadi Ketua Majelis
Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Itu berarti, ada harapan
cerah bagi pengembangan organisasi gerakan Pramuka menuju titik
kemandirian dan kreativitas.
Orang sudah tahu, bahwa gerakan Pramuka dibangun untuk
memberi bekal kepada peserta didik untuk mandiri dan kreatif. Akan
tetapi, orang menjadi tidak tahu, ketika kemandirian dan kreativitas
yang dimaksud merupakan hal-hal terpola. Memasak misalnya,
orang berasumsi bahwa dengan memasak sendiri dalam berkemah,
anggota Pramuka akan mandiri. Akan tetapi bagaimana realitas
kemandirian itu? Pramuka sekarang berbeda dengan pramuka zaman
dulu (Pandu). Mereka berkemah dibekali uang saku banyak sehingga
untuk memasak mereka tidak pernah berpikir bahkan yang akhir-
akhir sedang aktual adalah kemah catering, artinya berkemah yang
segala keperluan konsumsinya ditanggung catering.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 219
Pola Kekawatiran
Sinyalemen ini berkembang menarik ketika lunturnya
kemandirian justru didukung upaya Pembina untuk membantu
peserta didiknya, dalam berbagai hal. Hal tersebut tampak nyata
dalam kegiatan berkemah, fungsi Pembina beralih menjadi penjual
nasi dan pelayan warung. Mengapa ada semacam kekhawatiran
Pembina, ketika makanan yang dibagi tidak merata, jika bukan
Pembina sendiri yang membagikan? Mengapa peserta didik tidak
dilatih belajar mengendalikan diri demi kebersamaan?
Pola-pola kekhawatiran tersebut justru akan mendidik gerakan
Pramuka menjadi robot yang hanya akan bergerak ketika diprogram.
Dampak yang sangat terasa adalah terpolanya kekhawatiran serupa di
tingkat bawah (gugus depan) yang bermuara pada kurang
antusiasnya peserta didik dalam mengikuti kegiatan Pramuka.
Karenanya, muncul pola pemaksaan anak untuk masuk dan
mengikuti gerakan Pramuka.
Di gugus depan yang berpangkalan SD, kegiatan pramuka
merupakan conditio qua sine non dan hukumnya wajib. Artinya
seluruh peserta didik dipaksa berpramuka. Hal serupa juga terjadi
pada gugus depan SLTP dan SLTA, hanya bedanya rentang waktu
pemaksaan. Fenomena tersebut tentu bertentangan dengan prinsip
sukarela dalam gerakan Pramuka.
Jika dikaji mendalam, proses pemaksaan peserta didik untuk
berpramuka akan melahirkan siklus, dari “suka paksa-paksa rela-
suka rela”. Suka paksa merupakan trik awal yang dilakukan dengan
memaksa peserta didik dengan ancaman sehingga mau tidak mau
harus suka pada kegiatan Pramuka. Paksa rela merupakan buntut dari
pola kondisi peserta didik yang secara evolusif menyukai Pramuka.
Artinya, mereka menjadi rela dipaksa berpramuka, yang pada
ujungnya menjadi suka rela.
220 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Produk dari terpola siklus tersebut lambat laun akan memola
hal sama pada tahap pengembangan gerakan Pramuka. Lantaran
bernaung di bawah prinsip suka rela, maka dalam aktivitasnya
gerakan Pramuka perlu didukung peserta didik, pembina, dan majelis
pembimbing yang mempunyai akuntabilitas tinggi terhadap
kelangsungan Pramuka.
Sayangnya, pengotomatisan pejabat di negara Indonesia untuk
berpramuka dan menduduki jabatan dalam Pramuka terkesan
simbolis belaka. Seorang camat misalnya, ia secara otomatis menjadi
Ketua Majelis Pembimbing Ranting, terlepas ia suka atau tidak suka
terhadap Pramuka. Hal tersebut tentu akan berimplikasi pada
efektivitas dan efisiensi kegiatan Pramuka.
Ada wacana menarik, bagaimana seandainya keberadaan
Pramuka tidak memaksa para pejabat untuk berpramuka? Pertanyaan
sederhana ini, secara implisit memberi peluang dan tantangan
terhadap gerakan Pramuka agar tidak terlalu terbuai dalam nina bobo
lagu Pramuka siapa yang punya 3x, yang punya kita semua.
Dalam terminologi umum, ada semacam kekhawatiran
gerakan Pramuka bila tidak mendapat dukungan (terutama dalam hal
dana) dari pemerintah. Kekhawatiran ini diterjermahkan para
petinggi Pramuka dengan menggalang kekuatan peserta didik di
seluruh lapisan masyarakat. Artinya, gerakan Pramuka mempunyai
senjata pamungkas mencari dukungan seluruh pihak guna
mewujudkan kemandirian dan kreativitas nyata dalam
sumbangsihnya terhadap bangsa Indonesia.
MBG
Selaras bergulirnya Otonomi Daerah (Otda) maka tentu
kemandirian dan kreativitas merupakan hal mutlak yang harus
dimiliki gerakan Pramuka. Langkah awal kiranya dapat dilakukan
dengan menerapkan Manajemen Berbasis Gugus Depan (MBG).
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 221
Artinya segala sesuatu yang menyangkut maju mundurnya gugus
depan Pramuka, sangat tergantung pada upaya gerakan Pramuka
dalam rangka memperkuat diri dan bertahan dalam pluralitas
berbagai organisasi yang ada di masyarakat.
Menurut saya, setidaknya ada lima hal yang jika disingkat
menjadi 5K, jika gerakan Pramuka hendak menerapkan Manajemen
Berbasis Gugus Depan (MBG).
Pertama, kesungguhan yang mengacu pada antusias Pembina
dalam suatu gugus depan untuk mengelolakembangkan gerakan
Pramuka secara sukarela.
Kedua, kemandirian yang menitikberatkan pada kemampuan
Pembina dalam sebuah gugus depan untuk mandiri, baik dalam hal
penggalangan iuran/dana maupun pengembangan gerakan Pramuka
dengan berpedoman pada AD/ART.
Ketiga, kreativitas berhubungan dengan aktualisasi potensi
peserta didik yang perlu dikembangtingkatkan Pembina dengan
serangkaian kegiatan menarik dan mengembangkan cara berpikir
divergent pada anggota Pramuka.
Keempat, kekompakan yang menekankan pada hubungan kerja
sama dan koordinasi seluruh anggota Pramuka dalam sebuah gugus
depan, sehingga tercipta suatu iklim kondusif dalam rangka
mewujudkan cita-cita luhur gerakan Pramuka. Hal ini sangat penting
lantaran kekompakan dalam organisasi akan menjadikan orang-orang
terlibat ikut handarbeni dan mendukung segala upaya demi
kemajuan organisasi tersebut.
Kelima, keefektifan ditandai dengan ketercapaian tujuan
program kegiatan Pramuka yang dirumuskan. Secara sederhana,
sebuah gugus depan yang mempunyai program kegiatan lomba
galang misalnya, dapat dikatakan efektif jika secara kuantitas jumlah
peserta banyak dan secara kualitas pesertanya mampu meraih standar
nilai minimal yang ditetapkan. Sudah tentu, ketercapaian kuantitas
222 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
dan kualitas akan dibarengi dengan efisiensi, baik waktu, tenaga dan
pembiayaan.
Mandiri dan Kreatif
Jika ditelaah detail dan mendalam, MBG dengan 5K, pada
saatnya nanti akan memberi jawaban terhadap segala permasalahan
gerakan Pramuka. Masih banyaknya gugus depan yang hanya
berpramuka pada Agustus saja merupakan bukti nyata, penting, dan
mendesaknya penerapan manajemen berbasis gugus depan.
Pola-pola kekhawatiran dan pemaksaan dengan memanfaatkan
proses siklus suka paksa–paksa rela―suka rela), akan lebur dengan
sendirinya ketika manajemen berbasis gugus depan diterapkan.
Konsekuensi logisnya, seluruh anggota Pramuka dalam gugus depan
tersebut harus bersatu padu merealisasikan potret gerakan Pramuka
yang mandiri dan kreatif. Mandiri dalam segala bentuk aktivitas dan
kreatif dalam hal aktualisasi potensi yang perlu
dikembangtingkatkan.
Oleh karena itu, di HUT Pramuka ke-40 ini, gerakan Pramuka
diharapkan lebih membuka diri terhadap kritik dan saran dari
segenap pihak dan belajar memahami segala bentuk pluralitas yang
terjadi di masyarakat sebagai wahana penempaan diri. Akhirnya,
Dirgahayu Gerakan Pramuka! Selamat memandu anak negerimu!
Trimo, Pendidik dan Andalan Cabang Kwarcab Kabupaten Kendal
―dimuat di koran Wawasan, 14 Agustus 2001.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 223
PGRI, PUNYA SIAPA?
Oleh Trimo
Sebuah komunitas tentu memiliki ikatan mempersatukan
beragam nuansa pluralitas di kalangannya. Tidak terkecuali pendidik,
secara umum diberi predikat orang yang mentransfer ilmu
pengetahuan kepada orang lain (peserta didik, khususnya). Ikatan
yang lama berdiri sejak zaman kemerdekaan, untuk mewadahi
komunitas pendidik itu bernama PGRI (Persatuan Guru Republik
Indonesia). Wadah tersebut seakan-akan memberikan pemahaman
sejajar antara berbagai jenis tenaga pengajar, seperti dosen dan guru.
Dalam terminologi luas, masyarakat sudah tahu bahwa PGRI
merupakan rumah guru, sebagai tempat melindungi guru dari
berbagai permasalahan yang sering muncul. Selebihnya PGRI
diharapkan menjadi kampus guru, untuk meningkatkan kompetensi
personal, profesional, dan kemasyarakatan.
Rumah dan Kampus Guru
Fungsi PGRI sebagai rumah guru, agaknya belum teruji
kredibilitasnya. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan secara
komprehensif, tetapi sepak terjang PGRI masih terbatas pada
anggota komunitasnya yang mengalami permasalahan. Bukan
menjemput bola, tetapi menanti datangnya bola. Seperti tempo hari,
kasus seorang guru di Ungaran, dan berbagai bantuan yang diberikan
kepada guru yang mengalami musibah.
Sedangkan fungsi PGRI sebagai kampus guru, sudah
mendekati taraf signifikan yang boleh dikatakan optimal. Melalui
PGRI, guru-guru diberi kemudahan melanjutkan studi karena PGRI
memiliki perguruan tinggi bahkan sudah mampu melebarkan sayap
di berbagai daerah. Yang menjadi persoalan mendasar sekarang
224 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
adalah bagaimana PGRI mampu menjadi pemersatu komunitas
pendidik sehingga mereka merasa terwadahi dan terlindungi?
Pertanyaan sederhana di atas muncul lantaran berembusnya
era baru di negara Indonesia yang berimbas ke seluruh dimensi
kehidupan, tak terkecuali pendidikan, mendatangkan keberanian baru
bagi guru untuk berkata tidak. Dahulu, sebelum kata tidak menjadi
tolok ukur keberanian guru, semua guru hanya mempunyai satu kata
pilihan, yaitu ya. Mereka selalu patuh memakai seragam PGRI setiap
Sabtu, dan juga tidak pernah mempertanyakan besarnya potongan
PGRI tiap bulan, dengan kontribusi yang didapat.
Sikap sendika dawuh itulah yang secara evolusif membentuk
opini publik tersendiri di kalangan guru. Mereka secara tidak sengaja
belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada di tubuh PGRI, yang
kemudian menggalang kekuatan memisahkan diri, dan membentuk
kelompok baru. Tentu para pendidik masih ingat, munculnya
Persatuan Guru Swasta dan yang terakhir munculnya Forum Guru
Wiyata Bakti yang sempat berselisih paham dengan PGRI mengenai
dana insentif.
Prasangka Sosial
Dalam teori Psikologi Sosial, munculnya kelompok di atas
akibat adanya jarak sosial (social distance) yang ditandai adanya
prasangka sosial. Kimball Young mengatakan bahwa prasangka
timbul akibat adanya pertentangan antara kelompok yang ditandai
oleh kuatnya in group dan out group. Hal senada juga dikatakan
Sherif bahwa prasangka sebagai suatu sikap tidak simpatik terhadap
kelompok luar (out group).
Mengacu teori itu, lantas muncul pertanyaan, siapa yang
berprasangka dan mengapa prasangka itu harus muncul? Jika
ditelaah lebih mendalam, dua pertanyaan tersebut merupakan sumber
utama munculnya pertanyaan terdahulu, yang mau tidak mau PGRI
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 225
harus bersikap arif dan bijaksana dalam memberikan jawaban
integral (bukan sepihak) sehingga kalangan pendidik dan masyakarat
memahami perbedaan yang ada merupakan wujud keberagamaan
yang akan menambah kesolidaritasan organisasi guru tersebut.
Setidaknya ada berbagai sebab munculnya prasangka sosial dalam
tubuh PGRI.
Pertama, legalitas profesi, yang merupakan substansi
kuantitatif dalam komunitas PGRI. Ada sinyalemen yang berasumsi
bahwa PGRI hanya milik guru yang berstatus pegawai negeri.
Sinyalemen tersebut makin benar ketika secara data sebagian besar
jumlah anggota PGRI adalah pegawai negeri. Bahkan semua PNS
(dosen dan guru), secara otomatis menjadi anggota PGRI. Sedangkan
anggota di luar pegawai negeri, jumlahnya relatif sedikit.
Kedua, tersumbatnya kepentingan yang mengacu kontribusi
PGRI terhadap para anggotanya. Sering terdengar lontaran anggota
bahwa PGRI bisanya hanya memotong gaji guru tanpa memberi
kontribusi nyata terhadap iuran yang diberikan. Lontaran tersebut
menjadi benar ketika para anggota PGRI, tidak pernah mengetahui
aktivitas pengurusnya, pada tataran bawah (kecamatan).
Kecenderungan yang ada, pengurus PGRI kecamatan kurang mampu
menunjukkan sepak terjang memungsikan PGRI sebagai rumah dan
kampus guru.
Ketiga, arogansi kekuasaan yang berhubungan sikap para
petinggi PGRI (dalam setiap tataran) yang kurang mampu
mengakomodasi gagasan dan kebutuhan anggotanya. Arogansi
tersebut bermula dari sikap para pengurus PGRI yang merasa lebih
mampu dibanding anggotanya, sehingga menganggap segala
kebijakan organisasi merupakan buah pikir semata.
Keempat, sosialisasi kebijakan yang kurang transparan.
Indikator tersebut tampak jelas di tubuh PGRI khususnya tataran
bawah yang secara signifikan sebenarnya merupakan titik sentral
226 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
kegiatan. Berbagai kebijakan yang ditelurkan PGRI yang
menyangkut berbagai upaya pemecahan masalah kerap terlambat,
bahkan tidak mengerti anggota. Seperti keputusan PGRI untuk tetap
mempertahankan Ebtanas. Hal ini lantaran mekanisme pengambilan
keputusan PGRI masih menganut sistem sentralistik.
Pendekatan Planajemen
Keempat hal di atas, merupakan titik awal munculnya social
distance di antara anggota PGRI. Siapa yang lebih dulu
berprasangka? Yang jelas bisa kedua-duanya, artinya bisa kelompok
in door (dalam PGRI) maupun out door (anggota PGRI yang
berseberangan dengan pengurus). Antisipasi awal jelas melalui
dialog melancarkan tersumbatnya berbagai arus informasi. Namun
demikian, saat ini ada semacam kecenderungan dialog mayoritas,
artinya yang menguasai alur pikir dan jalannya pengambilan
keputusan sangat tergantung pada kelompok mayoritas yang ada di
dalamnya.
Ada pendekatan yang mampu membangkitkan PGRI dalam
mempersatukan berbagai permasalahan intern dan ekstern
anggotanya, yaitu pendekatan planajemen. Menurut James Lewis
seperti dikutip Pidarta (1990:79), planajemen adalah proses
mengintegrasikan seni dan ilmu (art and science) untuk
memindahkan konsep ke dalam realitas melalui metode praktis.
Secara kontekstual, ada empat langkah yang dapat ditempuh melalui
pendekatan planajemen.
Pertama, mengumpulkan semua informasi, fakta, dan data
tepat tentang masalah yang dihadapi. Langkah ini dapat ditempuh
PGRI dengan mengakomodasi berbagai masalah yang dihadapi
anggota, melalui informasi, fakta, dan data akurat sehingga cara
pemecahannya mempunyai akuntabilitas yang tinggi terhadap
anggota.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 227
Kedua, menganalisis data secara ilmiah, dilengkapi intuitif dan
pertimbangan matang untuk melahirkan asumsi-asumsi yang
mendasari pemecahan masalah. Menganalisis data sangat penting
untuk menghindari sekecil mungkin pelanggaran yang terjadi dalam
praktik penyelenggaraan pendidikan. Kasus yang masih hangat
adalah adanya manipulasi data pengangkatan guru SD tahun lalu dan
adanya guru wiyata bakti yang menerima insentif dobel. Di sinilah,
PGRI dituntut keberaniannya meluruskan berbagai informasi dengan
menganalisis data.
Ketiga, mengambil keputusan menyelesaikan masalah.
Keputusan yang baik, menyangkut orang banyak. Artinya, anggota
PGRI merasa ikut bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Oleh karena itu, koordinasi, kerja sama, dan musyawarah sangat
diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan.
Keempat, mengembangkan program strategi konsolidasi.
Sudah saatnya PGRI berparadigma baru, dengan mengembangkan
fungsi sebagai rumah dan kampus guru tanpa membedakan status
keanggotaan. PGRI harus selalu berupaya menyamakan pelayanan
anggota, baik mereka yang PNS maupun bukan PNS. Jika
memungkinkan, PGRI harus berani memperjuangkan anggota yang
bukan PNS agar dapat menjadi PNS, dengan menganalisis berbagai
peraturan berlaku.
Akhirnya, selamat memperingati HUT PGRI ke-56. Teiring
doa dan harapan semoga PGRI lebih eksis dalam aktivitasnya
memperjuangkan rekan-rekan guru menghadapi berbagai fenomena
yang berkembang di dunia pendidikan, serta mampu menjadi
pemersatu para guru. Semoga pula, PGRI menjadi milik bersama
guru-guru di Indonesia.
__dimuat di koran sore Wawasan, 24 November 2001.
228 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
GURU BERPRESTASI, APA YANG KAUCARI?
Oleh Trimo
Mendengar kata prestasi, orang tentu akan memahaminya
dalam konteks hasil yang dicapai. Siswa berprestasi tentu merupakan
siswa yang berhasil dalam menempuh serangkaian kegiatan di setiap
jenjang pendidikan, baik kegiatan akademik maupun nonakademik,
yang dinyatakan dengan kuantitatif (angka) maupun kualitatif (kata-
kata). Lantas, bagaimana dengan guru berprestasi? Apa yang menjadi
tolok ukur seorang guru berprestasi? Hasil apa yang menandai bahwa
seorang guru layak disebut berprestasi?
Tulisan ini hendak menelaah secara mendalam mengenai
fenomena aktual yang berkembang dalam pemilihan guru
berprestasi, yang sudah dan hendak dilaksanakan secara
berkelanjutan.
Dalam konteks pemahaman guru berprestasi, kebanyakan
orang awam menyamakan dengan guru teladan. Memang, kedua
istilah tersebut hampir sama. Bahkan, istilah guru teladan lebih
merakyat di telinga guru-guru. Maka, wajarlah bila sebagian besar
guru berasumsi sama.
Sebenarnya tidak demikian, guru teladan merupakan guru
terbalut aturan-aturan lama. Ia harus memiliki pendidikan, dedikasi,
loyalitas, dan tidak tercela (PDLT), yang kesemuanya merupakan
substansi dari indikator guru teladan. Guru teladan harus sosok yang
memiliki pikiran, ucapan, dan tindakan baik. Ia harus aktif di
organisasi pendidikan, lembaga masyarakat dan sering mengikuti
diklat/penataran. Bahkan, guru teladan tidak boleh merokok dalam
kehidupan sehari-hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 229
Sedangkan guru berprestasi adalah guru yang memiliki
kemampuan melaksanakan tugas, keberhasilan melaksanakan tugas,
memiliki kepribadian yang sesuai profesi guru, dan memiliki
wawasan pendidikan. Guru berprestasi harus mampu meningkatkan
mutu proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan melebihi yang
dicapai guru lain sehingga dapat dijadikan anutan siswa, sejawat,
maupun masyarakat sekitarnya (Pedoman Pemilihan Guru
Berprestasi Tingkat Nasional, 2002: 3).
Lebih lanjut dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa
kriteria pemilihan guru berprestasi adalah guru yang memiliki
prestasi dalam bidang pendidikan dengan menunjukkan hasil nyata
berupa kemajuan/peningkatan prestasi belajar siswa melalui: 1)
Inovasi pembelajaran/bimbingan, 2) Penemuan teknologi tepat guna,
3) Penulisan buku/esai/karangan ilmiah dalam bidang pendidikan, 4)
Penciptaan karya seni dan sastra, serta olahraga.
Peluang Sama
Paparan di atas setidaknya akan membantu para pembaca
dalam menarik opini mengenai perbedaan subtansial antara guru
teladan dan guru berprestasi. Guru teladan berorientasi pada
kepemilikan PDLT tinggi, sedangkan guru berprestasi orientasi pada
hasil karya.
Banyaknya aturan prinsipil dalam pemillihan guru teladan
tempo dulu, menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah sehingga
mulai tahun 2002 pemerintah mengganti istilah guru teladan menjadi
guru berprestasi.
Penggantian istilah tersebut tentu diikuti dengan materi dan
aturan main yang sedikit berbeda, seperti larangan merokok. Pada
pedoman guru teladan, jelas-jelas dinyatakan guru teladan tidak
pernah merokok yang dibuktikan dengan surat dokter. Namun pada
pedoman pemilihan guru berprestasi, aturan tersebut tidak ada
230 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
sehingga memberikan peluang yang sama kepada semua guru untuk
mengikuti pemilihan guru berprestasi.
Rambu-rambu pemilihan guru berprestasi yang lebih ramping
dari guru teladan, merupakan wujud penghargaan nuansa pluralistis
di kalangan guru. Namun demikian, perampingan aturan main
tersebut tentu tidak keluar dari potret guru masa depan yang harus
mampu mengembangkan kompetensi personal, profesional, dan
kemasyarakatan.
Pertanyaan sederhana lantas mengemuka, “Buah apa yang
dipetik, setelah seorang guru berhasil menjadi guru berprestasi?”
Sebagian besar guru, tentu memberikan jawaban sama bahwa guru
berprestasi akan diberi bonus menjadi kepala sekolah.
Secara aklamasi, jawaban guru-guru di atas bermuara pada
penghargaan (reward) yang pantas diberikan untuk guru berprestasi.
Hal tersebut dikarenakan menjadi guru berprestasi harus menempuh
serangkaian ujian dan kegiatan sarat implementasi fungsi guru dalam
menumbuhkembangkan potensi peserta didik. Seperti kata Khalil
Gibran bahwa pendidikan bukan menyemaikan benih dalam dirimu,
tetapi membuat benihmu tumbuh.
Reward Kepala Sekolah
Sebagian guru, menjadi kepala sekolah sebagai penghargaan
keberhasilan menjadi guru berprestasi merupakan hal diidamkan.
Namun demikian, ada juga yang memiliki pandangan berbeda.
Dalam konteks pemahaman mengenai reward yang akan diberikan
kepada guru berprestasi, penulis berpandangan bahwa guru
berprestasi tidak harus menjadi kepala sekolah atau dijanjikan bonus
tertentu yang orientasinya jabatan.
Mengapa demikian? Fakta menunjukkan, banyak di antara
guru yang berprestasi dan dijadikan kepala sekolah justru tidak
mampu menunjukkan kemampuan dan memiliki power membentuk
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 231
opini publik yang berhubungan kemajuan pendidikan di
lingkungannya. Ia cukup puas dengan jerih payah yang dilakukan
dengan reward yang diberikan. Seperti dalam istilah Jawa: ―Wong
yen dipangku, mesthi mati‖ yang secara konotatif dapat diartikan
ketika orang dibuat senang dengan pemenuhan keinginannya, lambat
laun ia tidak akan berkembang.
Pemberian reward memang salah satu bagian proses
pendidikan yang bertalian erat antara input, proses, dan output. Potret
pendidikan di negeri kita hanya melingkar di antara ketiga hal
tersebut. Padahal, masih ada satu hal yang patut ditindakkritisi
setelah pencapaian output yakni outcame atau dampak hasil yang
dicapai dalam suatu kegiatan jangka panjang.
Pemberian reward menjadi kepala sekolah memang wujud
nyata dari output seorang guru yang berhasil dalam pemilihan guru
berprestasi, dan itu layak diberikan. Namun, mengapa setelah guru
berprestasi tersebut menjadi kepala sekolah, ia tidak lagi
menunjukkan prestasi? Bahkan, cenderung mengalir seperti kepala
sekolah lainnya yang selalu menungggu petunjuk dari atasan.
Fenomena inilah yang barangkali memperparah kualitas
sumber daya manusia di negeri ini. Bangsa ini hanya mampu
mencetak dan menghasilkan sesuatu, tetapi kurang mampu
memberdayakan hasil agar memberi kontribusi dinamis dalam setiap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tentunya kita masih ingat laporan United Nation Development
Pragramme (UNDP) tahun 1996 mengenai kualitas sumber daya
manusia, di mana menempatkan bangsa Indonesia pada urutan ke-
102 dari 174 negara. Jika dicermati laporan tersebut sangat
memprihatinkan bagi kelangsungan masa depan bangsa Indonesia.
Apalagi negara-negara tetangga kita berada jauh di atas bangsa
Indonesia, seperti Singapura berada pada urutan ke-34, Brunei
Darussalam 36, Thailand 52, dan Malaysia pada peringkat 53.
232 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Sebatas Wacana
Laporan UNDP tersebut seakan-akan melengkapi proses
pendidikan di negeri kita yang cenderung sebatas wacana. Bangsa
ini, selalu menelurkan ide-ide inovatif dalam bidang pendidikan,
tetapi lupa melakukan evaluasi. Indikasi yang bisa dilihat adalah
adanya sesuatu yang baru dalam kurikulum setiap ganti menteri,
penerapan kurikulum muatan lokal yang hanya baik isinya, tetapi
mentah dalam pelaksanaanya, penerapan manajemen berbasis
sekolah yang masih dilematis, penghapusan Ebtanas SD/MI yang
menimbulkan permasalahan baru, dan sebagainya.
Produk pendidikan yang mengedepankan wacana, tentu
berdampak pada kualitas tenaga pendidik. Ironisnya, pada tataran
bawah kepala sekolah yang seharusnya berinisiatif meng-counter
kebijakan, justru larut dalam tradisi dan warisan perjalanan
pendidikan yang dijalani sebelumnya. Seperti dikatakan BJ Habibie
ketika melakukan persidangan secara video conference bahwa ia juga
mewarisi kebiasaan lama yang sudah berjalan dalam lembaga yang
dipimpinnya.
Dalam konteks lebih sempit, pewarisan kebiasaan lama yang
selalu memberikan reward kepada guru berprestasi dalam bentuk
jabatan kepala sekolah makin menambah beban kelangsungan masa
depan pendidikan di negeri ini. Di masa depan, dunia pendidikan
membutuhkan para guru berprestasi yang secara dinamis senantiasa
memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas
pendidikan.
Kontribusi nyata yang merupakan kristalisasi dari penguasaan
kompetensi guru, hendaknya menjadi pijakan dan bahan renungan
bagi guru berprestasi bahwa tugas dan tanggung jawab berat
menanti. Dengan demikian yang dicari guru berprestasi bukan
jabatan kepala sekolah, tetapi kedinamisan dalam memberikan setitik
bakti untuk negeri Indonesia.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 233
Guru berprestasi ibarat mutiara, yang jika terbakar api tetaplah
mutiara, tenggelam di laut tetap mutiara, hilang di kegelapan malam
tetap menjadi mutiara, dan jatuh di lumpur sekali pun tetaplah
mutiara.
Trimo, S.Pd., Guru Berprestasi I Kelompok SD/MI, Pendidik di
Kabupaten Kendal
―dimuat di koran sore Wawasan, Selasa 9 Juli 2002.
234 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
MENGAPA PEJABAT HARUS JADI PRAMUKA?
Oleh Trimo
"Pramuka siapa yang punya, pramuka siapa yang punya,
pramuka siapa yang punya, yang punya kita semua." Nyanyian
tersebut sering menggema di telinga masyarakat, bukan hanya
anggota Pramuka, melainkan juga semua orang yang berada di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dicermati, kata kita pada
lagu di atas seakan-akan memberikan pemahaman, Pramuka milik
seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.
Dalam konteks aplikatif, pemakaian kata kita juga
mengandung muatan pemaksaan kepada setiap orang, mau tidak
mau, suka tidak suka, harus mengakui Pramuka memang milik
semua.
Benarkah demikian? Bukankah hal tersebut hanya lagu?
Sejauh manakah pemaksaan tersebut mengkristal dalam gerakan
Pramuka? Setidaknya, pertanyaan tersebut patut disikapi kritis
karena fenomena yang berkembang di lapangan, Pramuka bukan
milik kita semua, melainkan hanya milik kami.
Dalam konteks pemahaman pemaksaan yang menggejala di
tubuh gerakan Pramuka, saya memahami hal itu sebagai sesuatu
yang membelenggu sehingga membuat satu-satunya organisasi yang
berhak menyelenggarakan pendidikan kepanduan tersebut, hanya
menjadi robot.
Secara sederhana pemaksaan yang mudah dilihat adalah
jabatan majelis pembimbing. Seorang camat wajib menjadi Ketua
Majelis Pembimbing Ranting, bupati/wali kota wajib menjadi Ketua
Majelis Pembimbing Cabang, gubernur wajib menjadi Ketua Majelis
Pembimbing Daerah, dan presiden wajib menjadi Ketua Majelis
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 235
Pembimbing Nasional, terlepas suka atau tidak suka, mau atau tidak
mau, mampu atau tidak mampu, serta mencintai dunia Pramuka.
Cari Dukungan
Pemaksaan pejabat teras di suatu wilayah secara otomatis
menjadi ketua majelis pembimbing gerakan Pramuka sebenarnya
merupakan upaya Pramuka mendapat dukungan dari berbagai pihak
dan menjadi superhero di antara organisasi lain.
Kemudahan dalam birokrasi dan kucuran dana, itulah
sebenarnya yang merupakan muara pemaksaan para pejabat tersebut.
Bukan hanya itu, gerakan Pramuka juga melebarkan sayap ke
berbagai dimensi kehidupan. Mereka yang senang di bidang
kedirgantaraan dibina di Saka Dirgantara, pariwisata dibina Saka
Panduwisata, kepolisian dibina Saka Bayangkara, kehutanan dibina
Saka Wanabakti, pertanian dibina Saka Taruna Bumi, dan saka-saka
lain.
Dalam dunia pendidikan pun, sekolah diwajibkan memiliki
gugus depan, baik itu SD, SLTP, SMU/SMK, maupun perguruan
tinggi. Bahkan di desa, gerakan Pramuka menyediakan tempat
pembinaan di gugus depan teritorial walau banyak kepala
desa/kelurahan tak paham hal tersebut. Orang-orang lanjut usia pun
diberi wadah khusus dalam pembinaannya dalam Pandu Wreda dan
Hiprada.
Kekuatan yang merata secara kuantitatif itulah yang
menjadikan Pramuka selalu berbangga diri. Apalagi kenyataan di
lapangan, tidak ada satu organisasi pun yang mampu mengungguli
Pramuka dalam hal keanggotaan, keterlibatan pejabat pemerintah,
dan dukungan dana.
Kepemimpinan Kekuasaan
Dalam konteks pemahaman organisasi, D Hampton dalam
Cribbin (1990) mengatakan, paling tidak ada enam jenis organisasi,
236 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
yakni (1) Kebapakan yang menempatkan pemimpin sebagai
pembantu, pengayom, dan manipulator halus, (2) Birokratis yang
mensyaratkan pemimpin sebagai pemelihara, (3) Autokratis,
merupakan potret pemimpin yang mau berkuasa, (4) Berwenang
berhubungan dengan pemimpin sebagai direktur eksekutif, (5)
Konsultatif, mencirikan pemimpin dalam organisasi sebagai
katalisator, pendukung, suka mempermudah, dan (6) Inovatif
menempatkan pemimpin sebagai penggiat dan integrator.
Jika ditelaah mendalam, gerakan Pramuka merupakan
perpaduan jenis organisasi kebapakan dan konsultatif. Hal tersebut
diindikasikan keberadaan yang lebih memercayakan suatu
kepemimpinan berdasarkan kekuasaan, karisma, kepercayaan, dan
keteladanan. Bukan berdasarkan keahlian dan persetujuan rasional
layaknya jenis organisasi inovatif.
Menurutsaya, sudah saatnya gerakan Pramuka berparadigma
baru dengan mengelola organisasi secara inovatif dengan
mementingkan kualitas, partisipasi, tekad bersama, dan
mengoptimalkan peran gugus depan di setiap tingkatan Pramuka. Hal
ini karena stakeholder gerakan Pramuka adalah orang-orang yang
memahami komprehensif terhadap tata nilai yang berlaku di
dalamnya, bukan mereka yang dipaksa memahami tata nilai tersebut
dalam rentang waktu relatif pendek dan mendadak.
Paradigma baru gerakan Pramuka dengan format inovatif tentu
memerlukan pemahaman rasional, bukan emosional. Hal tersebut
dilandasi perkembangan gerakan Pramuka ke depan, harus mandiri
dan terbebas belenggu ikatan kekuasaan. Format baru inovatif
tersebut berakar pentingnya kreativitas gerakan Pramuka dalam
merumuskan segala bentuk kegiatan.
Arti penting kreativitas dalam pembinaan Pramuka juga
didasari keminiman keterampilan Pembina dalam
menumbuhkembangkan kemampuan anggota. Sering kita lihat,
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 237
ketika seorang Pembina Pramuka berada di tengah-tengah peserta
didik dan hendak menyanyi bersama sebagai pembuka pertemuan,
sudah pasti lagu yang muncul adalah "di sini senang, di sana senang,
di mana-mana hatiku senang". Mengapa harus itu? Tidakkah ada
lagu lain?
Kreativitas
Pramuka dengan paradigma baru menekankan kreativitas
merupakan wujud penerapan nilai-nilai dasar gerakan Pramuka.
Paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika gerakan
Pramuka ingin memberikan kontribusi nyata terhadap kelangsungan
pembangunan.
Pertama, keberanian mandiri dan terlepas ikatan kekuasaan.
Walaupun terasa berat, hal tersebut merupakan upaya awal dalam
menumbuhkan kreativitas gerakan Pramuka sehingga tidak dicap
sebagai organisasi milik pemerintah. Konsekuensi logisnya adalah
tidak perlu mewajibkan pejabat pemerintah menjadi ketua majelis
pembimbing.
Kedua, memperkuat keberadaan gugus depan yang merupakan
inti segala bentuk pembinaan Pramuka dengan memberikan
kebebasan dan kreativitas dalam merumuskan kegiatan bermanfaat.
Ketiga, membekali Pembina Pramuka dengan kegiatan kreatif,
inovatif, dan menyenangkan sehingga tidak terpaku pada pola-pola
kebiasaan lama. Berbagai variasi teknik pembinaan, nyanyian, dan
tepuk yang merupakan inti pembinaan Pramuka perlu dikembangkan
dan ditingkatkan berkala dengan pertemuan Pembina (Karang
Pamitran).
Keempat, mengaktifkan peran serta masyarakat sebagai salah
bentuk membudayakan Pramuka dengan serangkaian kegiatan bakti
sehingga memberikan kontribusi nyata pembangunan kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
238 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Empat hal di atas dapat dijadikan pijakan dalam paradigma
baru gerakan Pramuka sehingga dapat meningkatkan eksistensi
menuju kemandirian dan kreativitas. Saptakarsa Utama Gerakan
Pramuka memang pernah dirumuskan pada tahun 2000 sebagai
wujud paradigma baru. Namun, pada tahap implementasi paradigma
tersebut tidak berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan.
__dimuat di harian Suara Merdeka, 14 Agustus 2002.
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 239
MENGAPA GURU GOLONGAN IVA, MENTOK?
Oleh Trimo
Dalam konteks pemahaman profesi guru, orang beranggapan
bahwa profesi tersebut saat ini mengalami perkembangan signifikan.
Pada dekade 1980-an, profesi tersebut dihargai dengan nominal
kurang dari seratus ribu rupiah. Menginjak tahun 1990-an, menjadi
lebih dari seratus ribu rupiah, dan pada tahun 2000-an gaji guru rata-
rata satu juta rupiah.
Angka kasar tersebut jika dipahami merupakan personifikasi
tugas utama guru yang begitu berat dan rumit. Bayangkan saja, untuk
meraih golongan setingkat di atasnya seorang guru harus mampu
memenuhi angka kumulatif disyaratkan. Itu artinya, guru dihadapkan
pada peluang dan tantangan berprestasi meningkatkan kompetensi
yang dimiliki.
Peluang diberikan kepada setiap guru yang mampu mencapai
angka kumulatif dengan pengajuan kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi minimal 2 tahun. Sedangkan tantangan merupakan rambu-
rambu yang membatasi guru sehubungan kriteria pengajuan kenaikan
pangkat.
Pengembangan Profesi
Menyoal peluang dan tantangan yang dihadapi guru dalam
pengajuan angka kredit untuk kenaikan pangkat memang merupakan
hal aktual. Hal ini lantaran pada golongan ruang I, II, dan III perihal
kenaikan pangkat tidak begitu bermasalah. Namun, ketika seorang
guru sudah berada dalam golongan ruang IV maka ada satu
tantangan yang secara conditio sine qua non harus dilakukan, yakni
pengembangan profesi.
240 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
Pengembangan profesi merupakan kegiatan guru dalam rangka
pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan
peningkatan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan
profesionalisme tenaga kependidikan maupun menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan.
Unsur-unsur yang termasuk pengembangan profesi meliputi:
1) Melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah, 2) Menemukan
teknologi tepat guna, 3) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau
bimbingan, 4) Menciptakan karya seni, dan 5) Mengikuti kegiatan
pengembangan kurikulum (Kepmendikbud nomor 025/O/1995).
Secara spesifik karya tulis ilmiah diklarifikasi menjadi: 1)
Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi
di bidang pendidikan, 2) Karya tulis atau makalah yang berisi
tinjauan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pendidikan, 3)
Tulisan ilmiah pupuler di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
disebarluaskan melalui media massa, 4) Prasarana berupa tinjauan,
gagasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, 5) Buku
pelajaran atau modul, 6) Diktat pelajaran, dan 7) Karya
penerjemahan buku pelajaran/karya ilmiah yang bermanfaat bagi
pendidikan.
Ketujuh indikator pengembangan profesi tersebut memiliki
bobot angka kredit tersendiri. Yang terpenting bagi guru yang akan
mengajukan kenaikan tingkat (dari golongan ruang IV a ke IV b
misalnya) harus memiliki minimal 12 nilai/angka kredit dari unsur
pengembangan profesi. Tanpa 12 nilai tersebut maka kenaikan
tingkat seorang guru tidak dapat diajukan, walaupun guru tersebut
sudah berada dalam golongan ruang IV a lebih dari 4 tahun.
Kedinamisan Guru
Fenomena di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan
statis bagi guru yang sudah berada pada aras lebih baik, yakni
Tulisan Ilmiah Populer untuk Kenaikan Pangkat 241
golongan ruang IV a. Dalam pengertian, guru sudah puas dengan
golongan ruang IV a sehingga tidak pernah berpikir mengenai
pengembangan profesi. Kondisi ini menjadikan ratusan guru di tiap-
tiap kecamatan, golongan ruangnya mentok sampai IV a saja.
Padahal, jika ditelaah mendalam banyak fenomena di bidang
pendidikan yang seharusnya dapat dibedah oleh guru melalui tulisan
ilmiah populer/artikel, justru diwacanakan oleh orang-orang yang
tidak berkecimpung langsung dalam dunia pendidikan. Banyak
contohnya, seperti orang menulis tentang School Based Management
yang muluk-muluk tanpa mengetahui kondisi nyata di lapangan,
orang yang bukan guru berbicara mengenai format pembelajaran
yang efektif padahal tidak berpengalaman menjadi guru, dan
sebagainya.
Jika seorang guru memiliki keinginan menjadi tenaga pengajar
dinamis, mengembangkan profesi dapat dilaksanakan secara
insidental tanpa mengganggu rutinitas kegiatan belajar mengajar.
Gagasan mengembangkan profesi dapat muncul setiap saat ketika
guru sedang mengajar.
Berbagai kesulitan dan permasalahan guru dapat ditulis dalam
bentuk artikel, kemudian dikirimkan ke media massa. Sekadar
memberi tahu, sebuah artikel bidang pendidikan yang dimuat di
media massa memiliki nilai/angka kredit 2 (dua). Hal itu berarti, jika
seorang guru golongan ruang IV a hendak mengajukan kenaikan
tingkat ke golongan ruang IV b, cukup menulis artikel di media
massa sebanyak 6 kali.
Kesulitan dan Kemalasan
Berdasar pengamatan penulis kepada guru-guru bergolongan
ruang IV a, diperoleh pemahaman bahwa kestatisan mereka yang
memilih adem ayem dengan tidak mau berusaha melakukan
pengembangan profesi, dikarenakan:
242 Rustantiningsih, S.Pd., M.Pd. & Trimo, S.Pd., M.Pd.
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku tulisan ilmiah populer untuk kenaikan pangkat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search