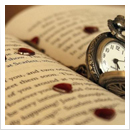NGANDJOEK
Era Prasejarah – Masa Hindu Budha
Penulis :
Rudi Handoko, S.S.
Sukadi, S.Pd, M.M.Pd.
Amin Fuadi, S.E., M.M.
Penerbit :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Nganjuk
Jalan Diponegoro No. 47 Nganjuk
Email : [email protected]
Tahun 2021
i
Ngandjoek Era Prasejarah – Masa Hindu Budha
Pengarah :
Putu Winasa, S.H., M.M.
Penanggung Jawab :
Agus Zainal Abidin, S.Kep. Ners.
Purwo Bujono, S.Hut
Prasulistyo Rahayu Pujowati, S.E., M.Si.
Penulis :
Rudi Handoko, S.S.
Sukadi, S.Pd, M.M.Pd.
Amin Fuadi, S.E., M.M.
ISBN : 978-623-94002-1-7
Editor :
Damari, S.Sos
Aries Trio Effendy, S.Ag
Dokumentasi :
Fakhriza Palaivi, S.IP.
Fitria Yuli Nurmasari
Pendika Cahyo A.
Design Sampul dan Tata Letak :
Wartinem, S.H., M.M.
Samsul Hadi, S.Sos.
Tri Purwanti
Duwi Setiyowati
Penerbit :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
Redaksi :
Jalan Diponegoro No. 47 Nganjuk
Telp. (0358) 321704 Fakx (0358) 321704
Email : [email protected]
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari penerbit
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami munajatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa. Karena hanya atas berkat dan rahmad-Nya, Tim Penyusun
dapat menyelesaikan kegiatan Penelusuran Sejarah dalam rangka
penyusunan Buku Sejarah Ngandjoek Era Prasejarah - Masa Hindu
Budha.
Adapun kegiatan penelusuran sejarah ini dilaksanakan
untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan dan untuk menyelamatkan dokumen - dokumen
arsip yang bernilai guna history untuk kepentingan generasi yang
akan datang.
Penerbitan buku ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan
dan dorongan moril dari berbagi pihak terkait. Oleh karena itu
dalam kesempatan ini ijinkanlah kami menyampaikan ucapan
terima kasih kepada :
1. Bupati Nganjuk yang telah turut memberi dorongan baik yang
berupa moril maupun spiritual yang tertuang dalam DPA Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2021 ;
2. Para Nara Sumber yang telah memberikan keterangan dan
informasi yang terkait dengan penelusuran sejarah Ngandjoek
Era Prasejarah – Masa Hindu Budha ;
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu
persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan buku
ini.
iii
Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam
penyusunan buku ini, untuk itu kami mengharap kritik dan saran
yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan buku
ini.
Akhirnya dengan segala kekurangannya kami
persembahkan buku ini mudah - mudahan ada guna manfaatnya.
Nganjuk, Juni 2021
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK
PUTU WINASA, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199103 1 009
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN ...................................................................... hal
KATA PENGANTAR ..................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................... v
1
A. Latar Belakang .......................................................... 1
B. Tujuan Penulisan ..................................................... 1
C. Metode Penelitian ................................................. 2
BAB II ERA PRASEJARAH .................................................... 3
A. Mitos Balung Buto .................................................. 3
B. Bentuk Fisik Pulau Jawa........................................... 4
C. Potensi Tinggalan Paleontologis Dan Arkeologis Di
7
Nganjuk ....................................................................
BAB III KEHIDUPAN MANUSIA PURBA PRA SEJARAH 25
35
DI INDONESIA ......................................................... 36
A. Pengertian Manusia Purba ...................................... 41
B. Jenis Dan Ciri Manusia Purba Di Pulau Jawa ........ 41
BAB IV PERADABAN MATARAM KUNO DI NGANJUK 41
A. Persaingan Wangsa Sanjaya Dan Syailendra........... 42
B. Syailendra Berkuasa Di Jawa Tengah......................
C. Sanjaya Restorasi (Pemulihan) 856 M .....................
v
D. Permusuhan Latent Jawa - Sumatra (Abad IX - 44
XIV) ................................................................... 46
E. Peradaban Mataram Medang Di Jawa Timur ....... 62
F. Perpindahan Kerajaan Mataran Medang Ke Jawa 68
Timur .................................................................. 72
G. Struktur Pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno . 139
H. Prasasti Candilor 937 Masehi (Cikal-Bakal Nama 150
158
Anjukladang) ...................................................... 159
I. Agama Dan Sosial .............................................. 216
J. Keistimewaan Sima Anjukladang ........................ 217
BAB V PENUTUP ....................................................................
LAMPIRAN ...................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................
BIODATA PENULIS .....................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan diketemukannya fosil-fosil hewan laut yang sudah
membatu peninggalan peradapan pada masa Purba di wilayah
utara Kabupaten Nganjuk terutama diwilayah Tritik Kecamatan
Rejoso Kabupaten Nganjuk, maka mengundang hipotesa
bahwa Nganjuk pada masa lalu merupakan hamparan lautan
atau pesisir lautan. Hal ini menjadi pijakan untuk melakukan
penelitian (Penelusuran) sejarah untuk mengungkap apakah
terdapat peradapan manusia purba disekitar wilayah Tritik yang
dapat digali data dan informasinya untuk merekonstruksi
peristiwa yang terjadi pada Era Prasejarah di Kabupaten
Nganjuk. Data-data yang dibutuhkan adalah berupa fosil
manusia, alat-alat perburuan, alat rumah tangga, peribadatan,
alat masak - masak dan lain sebagainya yang dapat mendukung
terselenggaranya kelangsungan hidup manusia purba di
Nganjuk.
Demikian juga pada masa Hindu Budha banyak sekali
prasasti - prasasti yang telah diketemukan di wilayah Kabupaten
Nganjuk mengungkap peristiwa atau kejadian yang
menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
dan kehidupan bermasyarakat waktu itu. Data dan informasi
tersebut terpahat pada batu yang mewakili informasi pada
jamannya dengan bahasa dan ukuran huruf yang berbeda saat
ini. Untuk itu dibutuhkan penerjemah guna mengetahui isi
yang terkadung didalam prasasti tersebut untuk merangkai
butiran makna menjadi peristiwa sejarah yang dapat dinikmati
alur dan hikmahnya bagi penikmat informasi.
B. TUJUAN PENULISAN
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang
keadaan wilayah Kabupaten Nganjuk pada Era Prasejarah
sampai masa Hindu Budha ;
1
2. Memberikan informasi bagi generasi muda tentang
peristiwa masa lalu agar dapat dijadikan suri tauladan dalam
menjalani kehidupan saat ini dan menyusun pola dan
prinsip hidup dimasa depan ;
C. METODE PENELITIAN
1. Wawancara dengan nara sumber
Tehnik ini digunakan untuk menggali data yang bersifat data
awal yang didasarkan pada penelitian lapangan.
2. Observasi langsung pada obyek
Tehnik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung
data dan informasi yang tertuang pada artefak, prasasti,
benda - benda yang digunakan untuk keperluan sehari hari
pada jamannya.
3. Literatur Perpustakaan
Data perpustakaan yang digunakan untuk bukti tertulis dan
teori maupun pendapat para ahli sejarah.
4. Dokumen Sejarah
Sumber sejarah yang diperlukan dalam penulisan sejarah
diantaranya :
a. Korespondensi ;
b. Bukti/dokumen konkrit yang bisa dipertanggung
jawabkan ;
c. Referensi.
2
BAB II
ERA PRASEJARAH
A. MITOS BALUNG BUTO
Pada tahun 1891, Eugen Dubois telah menemukan
Pithecanthropus erectus yang terkenal itu di Desa Trinil
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur.
Namun demikian jauh sebelumnya, pulau Jawa telah dikenal
dengan potensi paleontologisnya. Masyarakat Jawa telah lama
menyadari banyaknya fosil-fosil yang diperoleh dari endapan-
endapan tanah purba pada berbagai tempat yang berbeda-beda
terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka
menyebut fosil - fosil besar itu dengan istilah “Balung Buto”
atau “tulang raksasa”. Hal ini tercermin dari adanya cerita
wayang yang menggambarkan bahwa tanah Jawa menjadi
tempat pertempuran perang besar para raksasa yang dikemas
dalam perang Mahabharata. Cerita itu selanjutnya telah
menjadi mitos yang berkembang di masyarakat yaitu bahwa
balung buto adalah tulang dari para peserta perang yang mati,
kemudian berserakan terbawa situasi alam dan dengan
berjalannya waktu akhirnya menjadi fosil.
Dari mitos itulah diantaranya yang menjadikan para
peneliti tertarik untuk meneliti temuan palaeontologis yang ada
di pulau Jawa. Adalah Franz Wilhem Junghuhn pada tahun
1809-1864 melakukan eksplorasi dan penelitian dan
menemukan fosil gajah purba dari daerah Gunung Patiayam di
Kudus. Hasil penelitiannya ditulis dalam makalah dengan judul
“Pulau Jawa : Bentuk, Permukaan dan Susunan Dalamnya”.
Karyanya tersebut juga dilengkapi dengan peta pertama pulau
Jawa. Demikian pula Raden Saleh yang merupakan seniman
lokal lulusan pendidikan Belanda, juga mengadakan penelitian
pada tahun 1811-1880 di daerah Patiayam Kudus dan
Kedungbrubus Madiun. Pada tahun 1860 menulis artikel yang
akhirnya mempengaruhi para peneliti Eropa memulai
melakukan eksplorasi dan penggalian di Pulau Jawa. Dari mitos
3
balung buto menjadikan peranan Pulau Jawa dalam penemuan
fosil - fosil binatang maupun manusia purba yang berusia jutaan
tahun lalu cukup signifikan. Dengan kata lain, endapan purba
di Pulau Jawa telah dihidupi oleh fauna-fauna tertua baru
berikutnya dihuni manusia. Bukti-bukti kehidupan itu telah
digambarkan secara gamblang oleh Franz Wilhem Junghuhn,
Raden Saleh dan Eugen Dubois. Sehingga dapat dikatakan
bahwa Pulau Jawalah yang telah memiliki bukti-bukti telah
adanya kehidupan sejak jutaan tahun lalu dari fakta-fakta
penemuan fosil tersebut. Fosil-fosil itu terbentuk diantaranya
sebagai akibat material vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung
berapi, yang mampu mengkonversi tulang belulang fauna dan
manusia purba menjadi fosil dari masa apapun.
B. BENTUK FISIK PULAU JAWA
Pada tahun 1949, seorang ahli Geologi terkenal yaitu
R.W. Van Bemmelen, telah menerbitkan peta geologi Pulau
Jawa. “The Geology of Indonesia” adalah peta yang sangat
lengkap dan informatif. Sebenarnya peta itu terwujud
sebenarnya merupakan permintaan dari G.J. Wally yang
menjadi Kepala Jawatan Pertambangan yang dikerjakan oleh
R.W. Van Bemmelen dari tahun 1947 hingga 1949. Peta karya
Bemmelen telah menjadi rujukan para Geolog maupun kaum
akademisi dunia dalam mempelajari geologi regional
Indonesia.
Dari peta karya Bemmelen terlihat fisiografi pulau Jawa
dari ujung Barat Pandeglang hingga Blambangan di ujung
Timur. Demikian pula tampilan dataran alluvial sepanjang
pantai utara Jawa dan dataran kars sepanjang deretan pantai
selatan. Peta tersebut juga telah menggambarkan adanya
gunung, lembah, bukit maupun batuan yang membentuk
morfologinya. Sebagian besar permukaan Pulau Jawa terdiri
dari endapan vulkanik dan sedimen kuarter terutama
berhubungan dengan aktivitas vulkanik maupun tektonik yang
masih berlangsung hingga saat ini. Konfigurasi pulau Jawa yang
4
demikian merupakan hasil dari sebuah proses panjang yaitu
meliputi proses pengangkatan permukaan dasar laut sebagai
akibat pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi,
pelipatan jajaran pegunungan. Kejadian lainnya bisa jadi adalah
fluktuasi permukaan air laut akibat proses interglasial pada
zaman Es yang terjadi cukup panjang selama lebih dari 2 juta
tahun sejak akhir masa Pleosin. Laut-laut yang tidak terlalu
dalam seperti laut Jawa yang hanya sekitar 40-60 m akan
mengering dan menyebabkan daratan semakin melebar. Untuk
pulau Jawa terjadi penaikan permukaan secara parsial diawali
dari Paparan Sunda. Selain itu pengeringan tersebut mampu
menghubungkan daratan Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Asia
Tenggara. Jembatan darat ini memungkinkan terjadinya migrasi
mamalia termasuk manusia, dari dataran Asia ke Pulau Jawa
dan pulau-pulau lainnya.
F. Semah (1986) mencatat bahwa Jawa bagian Barat yang
terangkat duluan dari muka laut, sementara Jawa Tengah dan
Jawa Timur masih berupa lautan dangkal. Selanjutnya
pengangkatan Jawa Tengah dan Jawa Timur diakibatkan oleh
penurunan permukaan laut, aktifitas gunung berapi dan juga
pelipatan Pegunungan Kendeng Utara. Kejadian tersebut
diperkirakan pada 1,65 juta tahun yang lalu. Sehingga dalam
hal ini dapat dikatakan bahwa usia teoritis dari migrasi mamalia
termasuk manusia pasti terjadi setelahnya. Data palaentologis
menggambarkan bahwa adanya penghuni berupa mamalia di
Pulau Jawa terjadi pada masa akhir Pleosin, jauh sebelum
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan daerah Indonesia bagian
Timur lainnya. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya temuan-
temuan fosil oleh H.G. Stehlin pada tahun 1925 di Kali
Glagah F.H. van der Marel pada tahun 1032 maupun G.H.R.
Koenigswald pada tahun 1935 di daerah Bumiayu Jawa Tengah
berupa fosil mastodon sp. atau gajah purba tetralophadon
bumiayuensis yang berusia sekitar 1,5 juta tahun lalu. Jenis
lainnya adalah kuda air (Hexaprotodon) dan kura-kura raksasa
5
(Geochelon). Temuan-temuan berikutnya terjadi di daerah
Kali Cisaat, Kali Biuk dan Kali Gintung.
Dari gambaran diatas terlihat bahwa sebagai akibat proses
yang panjang, pada akhirnya Pulau Jawa terbentuk sedemikian
rupa hingga seperti sekarang. Demikian pula makhluk hidup
yang mendiami juga akan berkembang seiring waktunya. Dari
daerah Bumiayu inilah dimungkinkan merupakan pintu
masuknya sebaran mamalia menuju kearah Timur yaitu Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Migrasi dimungkinkan karena jejak
palaentologis mengarah ke Timur sesuai urutan masa
terbentuknya bumi Jawa. Situs Patiayam di Kudus, situs
Sangiran antara Solo dan Sragen, situs Trinil di Ngawi, situs
Kedung Brubus dan Sumberbendo Caruban di Madiun, situs
Tritik di Nganjuk hingga situs Perning di Mojokerto
merupakan sebaran temuan mamalia termasuk manusia purba
yang potensial menjadi bahan kajian penelitian.
Menurut Unggul pada tulisannya dalam buku “Matar”,
menulis bahwa pada saat memasuki Pleistosen Tengah hingga
Pleistosin Atas aktifitas gunung-gunung disekitar Lembah Solo-
Madiun seperti Gunung api Lawu dan Wilis umumnya naik.
Naiknya aktifitas gunung api-gunung api ini juga diiringi dengan
munculnya gunung api baru. Salah satu gunung api kecil yang
baru muncul adalah Gunung api Pandan yang berada di
sebelah utara dari Gunung api Wilis. Kemunculan gunung api
ini menjadi penting karena aliran lahar yang keluar dari
Gunung Pandan mengerah keselatan dan bertemu dengan
aliran lahar dari Gunung Wilis yang mengarah ke utara.
Pertemuan dari kedua aliran lahar gunung api tersebut
membentuk bendungan yang membendung Sungai Bengawan
Solo yang dulunya mengarah ke timur ke arah Mojokerto dan
Surabaya. Bendungan yang disebabkan oleh aliran lahar
tersebut juga membentuk danau yang sangat luas yang
kemudian disebut Lembah Madiun. (Tim Peneliti Situs Matar,
2015:36). Seiring berjalannya waktu permukaan air danau
semakin tinggi dan meluap mengalir ke utara hingga ke
6
Lembah Cepu. Luapan air danau tersebut menyebabkan aliran
Sungai Bengawan Solo purba yang mengarah ketimur berubah
arah menjadi berbelok ke utara dan daerah perbelokan sungai
tersebut sekarang disebut sebagai daerah Ngawi tepatnya Ngawi
bagian utara. Dalam kurun waktu 10 ribu tahun terakhir hingga
sekarang akhirnya didapatkan pola aliran Sungai Bengawan
Solo yang seperti sekarang ini. (Tim Peneliti Situs Matar,
2015:36).
Nganjuk
Peta 01 : Pola aliran sungai Bengawan Solo
(Sumber : Dokumen Tim Peneliti Situs Matar)
C. POTENSI TINGGALAN PALEONTOLOGIS DAN
ARKEOLOGIS DI NGANJUK
Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten di Jawa
Timur yang memiliki berbagai macam potensi tinggalan masa
lalu yang cukup banyak. Secara spesifik untuk temuan
paleontologis banyak sekali ditemukan pada daerah Nganjuk
belahan Utara, yang mendekati daerah perbatasan dengan
Kabupaten Bojonegoro. Temuan paleontologis yang ada
diantaranya adalah fosil-fosil hewan mamalia, reptilia, bivalvia
maupun gastropoda. Salah satu contoh adalah temuan Gading
Gajah purba pada wilayah hutan di Desa Sambikerep
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
7
Peta 02. Lokasi penemuan fosil (tanda merah) berada sekitar 1 km arah
barat laut Balai Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
(sumber: googlemap).
Lokasi penemuan fosil di Nganjuk berada di bagian utara
dari kota Nganjuk mendekati daerah perbatasan dengan
Kabupaten Bojonegoro, daerah tersebut berada pada cekungan
diantara dua gunung yaitu Gunung Pandan pada sisi utara dan
Gunung Wilis pada sisi Selatan. Sebagai contoh fosil yang
ditemukan di Desa Sambikerep dan dari hutan Tritik, berada
pada lapisan tanah pasir yang pada dahulu pengendapannya
melalui aliran air dalam waktu yang lama. Berdasarkan material
pasir tempat pengendapan fosil tersebut dapat diinterpretasikan
bahwa daerah tersebut dahulu terdapat sungai atau paling tidak
ada aliran air dalam waktu lama melewati daerah tersebut
seperti pada lokasi situs - situs manusia purba yang selama ini
dijumpai pada aliran Sungai Bengawan Solo Purba seperti Situs
Sambungmacan, Trinil, Matar, Kedungbrubus hingga sampai
di Bojonegoro.
Daerah di sekitar Kabupaten Nganjuk-Bojonegoro seperti
halnya Sangiran, merupakan bagian dari Mandala Kendeng
sehingga menunjukkan beberapa persamaan litologis. Struktur
batuan di Kabupaten Nganjuk tersusun dari endapan alluvium
dan satuan batuan berumur Pleistosen. Formasi batuan
8
berumur Pleistosen dari tua ke muda yang tersingkap adalah
Formasi Pucangan, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Breksi
Gunung Pandan, dan Formasi Notopuro. Berdasarkan peta
geologi regional, lokasi penemuan fosil di Desa Sambikerep
dan hutan Tritik Kecamatan Rejoso masuk dalam litologi
Formasi Kabuh. Formasi Kabuh tersingkap di daerah utara
Kabupaten Nganjuk. Formasi Kabuh di daerah ini tersusun
atas konglomerat, batu pasir, dan pada beberapa tempat
bersisipan lempung. Temuan fosil gading gajah purba di
Sambikerep berada pada endapan pasir berwarna abu - abu
coklat kehitaman, masa dasar berukuran butir pasir sedang
hingga kasar, fragmen kerikil, sortasi buruk, struktur sedimen
berupa silang siur mempunyai tipe planar-tabular. Pasir
berstruktur silang-siur seperti yang ditemui di lokasi tersebut
merupakan ciri khas Formasi Kabuh (Laporan Penelitian
BPSMP Sangiran, Januari, 2019).
Foto 01. : Lapisan tanah pada kali Genduk Ds, Tritik Kecamatan Rejoso
(Dokumen Balar Jogja)
Adanya fosil binatang vertebrata di daerah ini sebenarnya
telah diulas dalam sebuah penelitian geologi yang dilakukan
oleh Louis Jean Chretien Van Es pada tahun 1931. Van Es
9
melakukan penelitian berdasarkan laporan Dubois 1907
tentang penemuan fosil binatang vertebrata di sekitar daerah
antara Tritik-Bangle. Hal ini sesuai dengan keterangan yang
disampaikan penemu fosil yang disimpan di Museum Anjuk
Ladang yang menyatakan bahwa banyak sekali menemukan
fosil di daerah hutan Tritik. Dalam penelitiannya, Van Es
(1931:101) menyebutkan bahwa lapisan yang mengandung
temuan fosil yang sama dengan Trinil tersingkap di selatan
Pegunungan Kendeng, yaitu di selatan Gunung Pandan.
Lapisan ini memanjang dari Barat ke Timur dan ketebalannya
meningkat di dekat daerah Tritik.
Kota Nganjuk
Peta 03. Lokasi penemuan fosil (titik merah) dalam peta geologi regional.
Sumber: Peta Geologi Lembar Bojonegoro (H. Pringgoprawiro dan Sukido,
1992) dan peta Geologi Lembar Madiun (U. Hartono dkk, 1992).
Dari hasil peninjauan awal Tim Balai Pelestarian Situs
Manusia Purba (BPSMP) Sangiran, fosil-fosil yang dianggap
mampu mewakili jenis fauna yang ditemukan di Kabupaten
Nganjuk dan dalam kondisi utuh sebagaimana tertera dalam
10
tabel di bawah ini. Total fosil yang dapat dianalisis awal di
museum Anjuk Ladang berjumlah 74 buah fosil dan
diperkirakan berasal dari 14 jenis hewan purba. Fosil - fosil
tersebut telah dilakukan identifikasi dan selanjutnya dilakukan
konservasi baik secara mekanis maupun kimiawi. Hasil
konservasi selanjutnya disimpan dan sebagian dipamerkan
pada ruang pamer prasejarah.
Tabel 1. Hasil analisis fosil fauna pada kegiatan peninjaun
temuan di Museum Anjuk Ladang Kabupaten
Nganjuk (Sumber : Dokumen Balar Jogja)
Jenis fauna Tingkat Takson Jumlah fosil
Bola batu Artefak (?) 1
15
Bibos palaeosondaicus Species 1
1
Bubalus paleokerabau Species 1
2
Epileptobos (?) Species 6
2
Sus sp. Species 1
1
Rhinoceros sp. Species 1
1
Stegodon sp. Species 1
1
Elephas sp. Species 11
5
Ostrea digitata (?) Species 3
16
Ostrea sp. Species 1
3
Anadara sp. Species 74
Tridacna gigas Species
Tridacna maxima Species
Telescopium sp. Species
Bovidae Familia
Cervidae Familia
Hippopotamidae Familia
Proboscidea Ordo
Testudinata Ordo
Mamalia Kelas
JUMLAH
11
Dalam peninjauan di lokasi Tim BPSMP Sangiran selain
menemukan fosil-fosil juga menemukan artefak lithic berupa
satu buah bola batu berfaset (polyhedric) secara in situ. Batu
lithic juga telah ditemukan sebelumnya oleh Tim dari Dinas
Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
Kabupaten Nganjuk pada saat melakukan survey dan verifikasi
lokasi. Bola batu merupakan salah satu jenis peralatan yang
terpenting dalam kehidupan manusia purba. Bola batu
bersama dengan kapak genggam (handaxe), kapak pembelah
(cleaver) merupakan ciri utama budaya Acheulean yang
berkembang di Afrika sejak sekitar 1,6 juta tahun yang lalu.
Budaya paleolitik seperti itu berkembang di Afrika, Eropa,
hingga India Peninsula (Simanjuntak, 2011:15-16). Karena
persebarannya yang luas tersebut maka artefak ini banyak
ditemukan di beberapa situs hominid di dunia, termasuk pula
di Indonesia.
Menurut Widianto dan Simanjuntak (2009:99),
keberadaan bola batu sebenarnya masih dalam perdebatan.
Sebagian ahli beranggapan bahwa bola batu bukanlah buatan
manusia melainkan terbentuk secara alamiah akibat pelapukan
membola, dan sebagian lainnya beranggapan sebagai hasil
pengerjaan manusia. Terlepas dari perbedaan pandangan
tersebut, bola - bola batu yang ditemukan di situs-situs hominid
di Indonesia sebagian besar menampakkan bekas-bekas
pengerjaan atau pemakaian. Ciri pengerjaan dapat berupa
bekas-bekas pangkasan, sementara ciri pemakaian dapat
berupa luka-luka pada bagian tertentu di permukaan batu
akibat benturan yang kemungkinan disebabkan pemukulan.
12
Foto 02 : Bola batu berfaset (polyhedric) yang ditemukan di lokasi (Sumber
: Dokumen Balar Jogja)
Sebaran fosil-fosil maupun peralatan budaya manusia
purba yang terdapat pada wilayah hutan yang secara
administratif terletak di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso,
Kabupaten Nganjuk. Secara geografis fosil banyak ditemukan
pada bukit-bukit yang terdapat pada gunung Pandan. Vegetasi
yang mendominasi situs ini adalah pohon jati. Selain temuan
fosil, sebetulnya di lokasi ini juga banyak ditemukan beberapa
sebaran struktur bata merah, fragmen tembikar dan stoneware
yang diperkirakan dari periode kerajaan Majapahit atau
sebelumnya (Abad XI-XV Masehi) serta temuan-temuan masa
megalitik berupa situs : Menhir, Watu Ulo, Watu Dakon,
Punden Berundak, Kubur Kalang, Punden Joko Dolog, Kubur
Kawak. Memperhatikan berbagai jenis artefak yang ditemukan,
menggambarkan bahwa proses panjang kehidupan yang terjadi
di daerah Nganjuk terjadi mulai era prasejarah, masa klasik
atau hindu-budha, hingga masa mataram islam.
Situs Kubur Kalang Talun Gangsir adalah nama yang
diberikan masyarakat lokal saat ini untuk menyebut sebuah
struktur kubur kalang dari susunan batu besar. Situs ini secara
administratif terletak di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso,
Kabupaten Nganjuk. Lokasi struktur megalitik ini terletak di
kawasan hutan RPH Tritik, BKPH Tritik, KPH Nganjuk.
Sedangkan secara geografis terletak pada sebuah lereng bukit
13
yang miring ke arah selatan, dan terletak dekat dengan aliran
sungai bernama Talun Gangsir.
Foto 03 : Struktur salah satu Kubur Kalang Talun Gangsir yang relatif
masih utuh (Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, 2020)
Situs selanjutnya adalah Watu Ulo, karena masyarakat
lokal saat ini sudah tidak mengetahui nama asli situs tersebut,
maka peneliti memberi nama demikian. Situs ini secara
administratif terletak di Desa Bendoasri (dulu Dusun
Bendosewu yang termasuk bagian dari Desa Tritik),
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Lokasi struktur
megalitik ini terletak di tepi kawasan hutan RPH Bendosewu,
BKPH Tritik, KPH Nganjuk. Secara geografis terletak pada
sebuah ujung lereng bukit yang miring ke arah Tenggara masuk
wilayah Perhutani. Pada situs Watu Ulo, terdapat pula menhir
kotak dan lumpang dari batu utuh yang jumlahnya cukup
banyak. Bahkan ada beberapa lubang lumpang dalam satu batu
besar. Ada juga lumpang yang berada di tengah struktur batu
temu gelang merupakan pindahan dari loji kemantren (Kantor
Kemantrian) Jeruk. Menurut informasi dari Kepala Desa
Bendoasri dahulu kala Dusun Bendosewu yang merupakan
cikal bakal desa tersebut, penduduknya merupakan pindahan
14
dari Dusun Jeruk. Menhir berukuran 95 x 40 x 20 cm
berbahan batu andesit. Pada salah satu sisi tebal menhir
terdapat relief motif hias manusia kangkang yang dibuat dengan
teknik pahat yang masih sangat sederhana. Tidak ada hiasan
detail pada relief manusia tersebut, seperti misalnya mata,
hidung, dan mulut. Lumpang batu juga terbuat dari batu
andesit, berukuran lumpang diameter 70 cm dan tebal 27 cm,
dengan ukuran lubang berdiameter 25 cm dan kedalaman 25
cm.
Foto 04 : Menhir Berelief Manusia Foto 05 : Menhir Berukir Kepala Ular
Kangkang dan Lumpang Batu dalam Struktur Temu Gelang
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, (Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta,
2020) 2020)
Menhir Kepala Ular atau Watu Ula merupakan nama
yang diberikan masyarakat karena menhir ini berbentuk seperti
kepala ular. Menhir berukuran Panjang 150 cm, lebar bagian
bawah 80 cm, lebar bagian atas atas 40 cm, dan tinggi 120 cm.
Menhir tersebut diukir dengan relief berbentuk kepala ular,
dilengkapi dengan mata, mulut, dan sisik kepala dengan teknik
gores. Pada bagian bawah di sekeliling menhir kepala ular
tersebut terdapat struktur dari boulder batu andesit yang belum
terganggu. Selain temuan arkeologis tersebut, di dekat lokasi ini
juga terdapat dua sumber mata air yang selalu mengeluarkan air
meski di musim kemarau. Menurut penduduk setempat,
15
sumber tersebut diberi nama Belik Tanggal Sanga dan Belik
Sendang Bangle.
Punden Joko Dolog adalah nama yang diberikan
masyarakat lokal saat ini untuk menyebut sebuah struktur
punden dari bahan batu-batu besar, yang secara administratif
terletak di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten
Nganjuk. Lokasi struktur megalitik ini terletak di kawasan
hutan RPH Turi, BKPH Tritik, KPH Nganjuk. Secara
geografis terletak pada sebuah puncak bukit yang tidak terlalu
tinggi sekitar 20 meter dari permukaan tanah di sekitarnya, dan
bukit ini masih berada pada jajaran Pegunungan Kendeng.
Vegetasi yang mendominasi situs Punden Joko Dolog adalah
pohon jati dan sono keling yang tumbuh di sekitar sela-sela
struktur punden.
Foto 06 : Menhir di Punden Joko Dolog
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, 2020)
Menurut informasi mantri hutan setempat, dahulu kala
pada bagian puncak bukit petilasan ini terdapat dua struktur
16
semacam “kursi batu”, namun karena kurangnya kesadaran
masyarakat, banyak batu-batu bagian dari struktur yang diambil
untuk perkuatan jalan, penanda tanaman dan tujuan lainnya.
Oleh karena itu, maka saat ini hanya tersisa satu struktur di
bagian Timur, sedangkan struktur di bagian Barat tinggal sisa-
sisanya saja. Dua struktur yang disebut masyarakat seperti
“kursi batu” sesungguhnya adalah dua menhir dengan batu
datar untuk menaruh sesaji. Pada struktur di sebelah timur
yang masih relatif utuh terdapat sebuah menhir dilengkapi
dengan sebuah batu datar yang dikelilingi oleh batu-batu
boulder dari bahan batu andesit dan breksi vulkanik. Orientasi
menhir ke arah Timur, padahal di sebelah Utara dari petilasan
ini terdapat Gunung Panggung. Belum dapat diketahui secara
pasti periodesasi dan fungsi dari petilasan ini. Tidak adanya
temuan lepas di permukaan area situs menyulitkan untuk
memperkirakan usia bangunan di situs ini. Namun masyarakat
sekitar masih mensakralkan dengan melaksanakan prosesi doa
keselamatan sebelum menanam dan panen hasil bumi yang
ditanam di sekitar area hutan. Selain itu juga ada oknum-
oknum yang datang khusus untuk melakukan ritual mencari
inspirasi tertentu.
Situs Kubur Kawak yang bermakna “Kuburan Lama”
dalam Bahasa Jawa, adalah nama yang diberikan masyarakat
lokal saat ini untuk menyebut sebuah struktur kubur batu temu
gelang. Situs ini secara administratif terletak di Desa Tritik,
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Lokasi struktur
megalitik ini terletak di kawasan hutan RPH Kedungrejo,
BKPH Tritik, KPH Nganjuk. Secara geografis terletak pada
sebuah dataran, dan terletak dekat dengan sumber air bernama
Belik Netes.
Pada lokasi ini terdapat sekitar lima belas sisa struktur
kubur kuna, namun hanya sekitar lima struktur yang
kondisinya masih agak utuh. Struktur kubur tersebut berbentuk
melingkar atau oval, yang terbuat dari bahan susunan batu
boulder andesit dan batu pasir tufaan yang merupakan lapukan
17
dari Formasi Kabuh, berukuran diameter antara 20-30 cm,
dengan ukuran diameter struktur sekitar 2 meter. Orientasi
struktur kubur yang bentuknya agak oval adalah arah Timur-
Barat. Hal ini berbeda dengan bentuk kubur periode
sesudahnya (Islam) yang berorientasi arah Utara-Selatan.
Estimasi periodesasi Situs Kubur Kawak mungkin dapat
dilakukan berdasarkan temuan lepas beberapa jenis artefak
yang ditemukan di lokasi tersebut. Pada permukaan lokasi
Situs Kubur Kawak banyak ditemukan fragmen tembikar
berciri dari sekitar periode kerajaan Majapahit. Selain itu juga
banyak ditemukan fragmen batu bata kuna berukuran 32 x 19
x 6 cm. Berdasarkan pada temuan tersebut dapat diperkirakan
bahwa usia Situs Kubur Kawak minimal telah digunakan sejak
periode Majapahit, sekitar abad XIII-XV Masehi.
Pada saat ini Situs Kubur Kawak sudah ditinggalkan dan
tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat sekitar, sehingga situs
ini telah kehilangan konteks kulturalnya. Namun terdapat dua
(seharusnya empat) buah patok area kubur yang ditempatkan
oleh Perhutani sehingga membuat area ini mendapat predikat
sebagai "Lokasi Dengan Tujuan Istimewa" di dalam lahan milik
Perhutani.
Foto 07 : Struktur salah satu Kubur Kawak yang relatif masih utuh
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, 2020)
18
Selanjutnya situs boto-boto terletak di Desa Tritik, tepatnya
di area perhutani. Boto-boto merupakan nama suatu tempat di
dalam hutan jati PT Perhutani. Secara geografis terletak di
sebelah selatan calon genangan Waduk Semantok. Disebut
demikan karena di tempat tersebut ditemukan banyak serakan
bata merah ukuran besar, di antaranya masih terlihat sisa-sisa
struktur seperti batur bangunan berdenah segi empat. Di utara
sisa batur terlihat serakan pecahan gerabah dan keramik asing,
juga serakan batu sungai yang di antaranya masih terlihat
membentuk denah segi empat seperti kubur kalang.
Di antara pecahan keramik asing dapat diidentifikasi
berbahan abu-abu dan berglasir seladon seperti keramik Cina,
Thailand, dan Vietnam. Kisaran masa berdasarkan analisis
pecahan keramik tersebut adalah antara abad ke-13 hingga 15.
Menurut petugas dari PT Perhutani, banyak juga ditemukan
pecahan gerabah di seputaran lokasi ini pada area sekitar 3 ha.
Berdasarkan hasil analisis pecahan keramik yang menunjukkan
kisaran abad 13-15, situs ini termasuk ke dalam masa kerajaan
Majapahit. Namun demikian, penelitian lebih mendalam masih
diperlukan untuk mengungkap lebih banyak tentang
keberadaan situs Boto-boto yang lokasinya tergolong jauh dari
situs-situs yang semasa.
19
Foto 08 : Serakan bata dan artefak berbahan batu, tembikar dan
keramik di situs Boto-boto.
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, 2020)
20
Foto 09 : Atas kiri : tutup wadah warna seladon, Thailanad abad 14-15, asal
Sawankhalok; Atas kanan: pasu glasir hijau kecoklatan, Cina dinasti Yuan
abad 13-14 asal Guangdong; Bawah: pasu stoneware cokelat kekuningan,
Vietnam, abad 14-15.
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, 2020)
21
Foto 10. Serakan bata dan artefak berbahan Foto 11. Atas kiri: bentuk cepuk, Cina
batu, tembikar dan keramik di situs Boto- dinasti Yuan abad 13-14, asal Fujian; Atas
boto. (Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, kanan: mangkuk, Cina dinasti Yuan abad 13-
14 asal Longquan; Bawah: mangkuk, Cina
2020) dinasti Yuan, abad 13-14, asal Guangdong.
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta,
2020)
Foto 12 Atas kiri: tutup wadah warna seladon, Foto 13. Atas kiri: mangkuk seladon, Cina
Thailanad abad 14-15, asal Sawankhalok; dinasti Yuan abad 13-14, asal Longquan;
Atas kanan: pasu glasir hijau kecoklatan, Cina Atas kanan: mangkuk glasir cokelat
dinasti Yuan abad 13-14 asal Guangdong; kekuningan, Vietnam abad 14-15; Bawah
Bawah: pasu stoneware cokelat kekuningan,
Vietnam, abad 14-15. kiri: mangkuk glasir putih kebiruan
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, (qingpai) Cina dinasti Yuan, abad 13-14,
2020) asal Fujian/Guangdong; Bawah kanan:
piring puith- hitam bawah-glasir, motif ikan,
Thailand abad 14- 15, asal Sukothai.
(Dok. Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta,
2020)
22
Penemuan fosil di Kabupaten Nganjuk ternyata sudah
terjadi beberapa tahun lalu tepatnya mulai tahun 1999, namun
belum pernah dilaporkan oleh para penemu dan baru tahun
2012 mulai dilaporkan namun belum memperoleh perhatian
serius pemerintah daerah sehingga belum pernah ada
penelitian mengenai fosil yang ditemukan di Nganjuk. Barulah
mulai tahun 2016, peninjauan yang dilakukan oleh Balai
Pelestari Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran merupakan
awal dari identifikasi mengenai potensi cagar budaya yang ada
di Nganjuk terutama mengenai tinggalan fosil yang memiliki
nilai historis yang panjang dan berhubungan dengan situs situs
manusia purba yang ada di Pulau Jawa. Dari peninjauan terlihat
bahwa potensi tinggalan purba yang ada di Nganjuk sangat luar
biasa dari fauna yang ada serta benda yang diduga hasil budaya
manusia pendukung masa lalu sehingga dapat dirunut
mengenai lingkungan dan budaya waktu itu. Penelitian lain juga
dilakukan oleh Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta dan telah
diperoleh gambaran kondisi temuan fosil yang ada.
Gambaran umum kondisi geologis daerah temuan fosil
dapat dilihat pada lokasi Petak 47- 49 terdapat dua singkapan
dari periode Kuarter, yaitu: Formasi Kabuh berupa batu pasir
krikilan di bagian atas, dan Formasi Pucangan di bagian bawah
berupa lapisan lempung abu-abu. Temuan fosil di lokasi ini
berasal dari anatomi gigi, tengkorak, tulang panjang dan
astragalus. Kemudian identifikasi jenis-jenis fauna berdasarkan
anatomi fosil yang tersisa berhasil mengidentifikasi fauna dari
kelompok Proboscidae (hewan berbelalai), Bovidae (kerbau-
sapi), dan Cervidae (rusa).
23
Foto 2.3. Singkapan Formasi Kabuh di Foto 2.4. Temuan Fosil Gigi Bovidae
Petak 47-49 di Petak 47-49
(Dok. Balai Arkeologi D.I. (Dok. Balai Arkeologi D.I.
Yogyakarta, 2020) Yogyakarta, 2020)
24
BAB III
KEHIDUPAN MANUSIA PURBA PRA SEJARAH DI
INDONESIA
Membahas kehidupan manusia, khususnya dalam wilayah
prasejarah, tentu tidak akan bisa lepas dari lingkungan alam dan
budaya. Hal ini disebabkan bahwa aspek lingkungan ini merupakan
salah satu unsur penting pembentuk suatu budaya masyarakat.
Manusia masa prasejarah masih sangat menggantungkan hidupnya
pada alarn, oleh karena itu hubungan yang begitu dekat antara
manusia dengan lingkungan membawa konsekuensi bahwa manusia
harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang ditempati.
Salah satunya tercermin dari hasil budayanya. Untuk mendapatkan
penjelasan tentang kehidupan manusia masa prasejarah maka perlu
mengintegrasikan antara tinggalan manusia, tinggalan budaya dan
lingkungan alamnya. Dengan demikian studi tentang hubungan
antara manusia, budaya, dan lingkungan alam masa prasejarah
merupakan topik yang tetap aktual menarik dan perlu
dikembangkan dalam disiplin ilmu arkeologi. Nilai-nilai budaya
masa prasejarah artinya konsep-konsep umum tentang masalah-
masalah dasar yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan
masyarakat prasejarah di Indonesia. Konsep-konsep umum dan
penting itu hingga kini masih tersebar luas di kalangan masyarakat
Indonesia. Nilai-nilai budaya masa prasejarah Indonesia itu masih
terlihat dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut:
1. Mengenal Astronomi
Pengetahuan tentang astronomi sangat penting dalam
kehidupan mereka terutama pada saat berlayar waktu malam
hari. Astronomi juga, penting artinya dalam menentukan musim
untuk keperluan pertanian.
2. Mengatur Masyarakat
Dalam kehidupan kelompok masyarakat yang sudah menetap
diperlukan adanya aturan-aturan dalam masyarakat. Pada
masyarakat dari desa-desa kuno di Indonesia telah memiliki
aturan kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat ditunjukkan
25
dalam musyawarah dan mufakat memilih seorang pemimpin.
Seorang pemimpin yang dipilih itu diharapkan dapat
melindungi masyarakat dari gangguan masyarakat luar maupun
roh jahat dan dapat mengatur masyarakat dengan baik. Bila
seorang pemimpin meninggal, makamnya dipuja oleh
penduduk daerah itu.
3. Sistem Macapat
Sistem macapat ini merupakan salah satu butir dari 10 butir
penelitian J.L.A. Brandes tentang keadaan Indonesia menjelang
berakhirnya zaman prasejarah. Sistem macapat merupakan
suatu tatacara yang didasarkan pada jumlah empat dan pusat
pemerintah terletak di tengah-tengah wilayah yang dikuasainya.
Pada pusat pemerintahan terdapat tanah lapang (alun-alun) dan
di empat penjuru terdapat bangunan-bangunan yang penting
seperti keraton, tempat pemujaan, pasar, penjara. Susunan
seperti itu masih banyak ditemukan pada kota-kota lama.
4. Kesenian Wayang
Munculnya kesenian wayang berpangkal pada pemujaan roh
nenek moyang. Jenis wayang yang dipertunjukkan adalah
wayang kulit, wayang orang dan wayang golek (boneka). Cerita
dalam pertunjukkan wayang mengambil tema tentang
kehidupan pada masa itu dan setelah mendapat pengaruh
bangsa Hindu muncul cerita Mahabarata dan Ramayana.
5. Seni Gamelan
Seni gamelan digunakan untuk mengiringi pertunjukkan wayang
dan dapat mengiringi pelaksanaan upacara.
6. Seni Membatik
Seni membatik merupakan kerajinan untuk menghiasi kain
dengan menggunakan alat yang disebut canting. Hiasan gambar
yang diambil sebagian besar berasal dari alam lingkungan
tempat tinggalnya. Di samping itu ada seni menenun dengan
beraneka ragam corak.
7. Seni Logam
Seni membuat barang-barang dari logam menggunakan teknik a
Cire Perdue. Teknik a Cire Perdue adalah cara membuat
26
barang-barang dari logam dengan terlebih dulu membentuk
tempat untuk mencetak logam sesuai dengan benda yang
dibutuhkan. Tempat untuk mencetak logam sesuai dengan
benda yang dibutuhkan. Tempat untuk mencetak logam itu ada
yang terbuat dari batu, tanah liat dan sebagainya. Pada tempat
cetakan itu dituang logam yang sudah dicairkan dan setelah
dingin cetakan itu dipecahkan, sehingga terbentuk benda yang
dibutuhkannya. Barang-barang logam yang ditemukan sebagian
besar terbuat dari perunggu.
Pada zaman plestosin sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, di
Indonesia diperkirakan telah dihuni oleh manusia. Manusia yang
hidup pada zaman itulah yang disebut sebagai Manusia Purba. Jadi
yang dimaksud dengan manusia purba yaitu manusia yang hidup
pada zaman purba/zaman prasejarah/zaman pra-aksara/zaman
nirleka. Adapun ciri-ciri manusia purba adalah sebagai berikut :
Berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya
Memiliki akal dan volume otak yang lebih besar daripada
primata lain.
Mengenal bahasa/ dapat berbicara.
Hidup berkelompok dan mengenal pembagian tugas/kerja.
Memiliki peradaban.
Kehidupan manusia indonesia pada zaman prasejarah adalah
kehidupan dimana dengan berjalannya waktu kemudian mengenal
dan berkembang pada berbagai bidang kehidupan seperti :
ekonomi, sosial dan budayanya. Pada kehidupan ekonomi
kemudian berkembang pesat tampak dari upayanya dalam
memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Diantaranya
mengenal berbagai cara dalam memenuhi kebutuhannya seperti
berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam dan
perundagian. Oleh karenanya kehidupan manusia prasejarah
indonesia pada akhirnya semakin beragam.
Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih
sangat bergantung kepada alam lingkungan. Untuk memenuhi
27
kebutuhan, mereka tinggal menggunakan apa saja yang tersedia di
sekitar mereka, tanpa mengolah lebih lanjut. Kebutuhan akan
makanan dipenuhi dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan
yang bisa dimakan. Mereka berburu binatang dalam hutan,
menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai.
Mereka mengumpulkan (memungut) umbi-umbian, daun-daunan
dan biji-bijian dari lingkungan sekitar. Kebutuhan akan tempat
tinggal dipenuhi dengan cara membuat tempat berlindung dari
daun-daunan. Pada perkernbangan berikutnya, mereka rnenghuni
gua-gua. Tempat yang dipilih dekat dengan sumber air atau sungai
yang terdapat sumber makanan. Tempat tersebut akan ditinggalkan
dan pindah ke tempat baru, apabila tidak tersedia lagi sumber
makanan.
Gambar : Gambaran pemanfaatan batu untuk berbagai sarana kehidupan
manusia purba. Dokumen internet : artini
Pada masa bercocok tanam, manusia prasejarah tidak
bergantung sepenuhnya pada alam lingkungan. Mereka sudah
mampu mengolah bahan yang disediakan alam untuk memenuhi
28
kebutuhannya. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara
berladang dan beternak. Mereka membabat hutan dan semak
belukar untuk ditanami keladi, ubi-ubian dan beberapa jenis buah-
buahan. Merekapun beternak ayam, kerbau maupun babi serta
memelihara anjing. Selain untuk dimakan, hewan ternak digunakan
sebagai binatang korban. Meskipun telah bercocok tanam,
perburuan binatang di hutan sesekali tetap dilakukan. Kebutuhan
akan tempat tinggal dipenuhi dengan membuat rumah sederhana
dan kecil beratapkan daun-daunan. Atap rumah berbentuk bulat
sampai ke tanah. Pada perkembangan berikutnya, bentuk rumah
semakin besar dan dibangun di atas tiang-tiang. Tujuannya untuk
menghindari banjir dan serangan binatang buas. Kebanyakan
rumah mereka dibangun berdekatan dengan ladang. Selain
memenuhi kebutuhan primer, manusia prasejarah telah mulai
mengenal perdagangan barter. Sungai beserta perahu dan rakit
memegang peranan penting dalam lalu-lintas perdagangan.
Pada masa perundagian, masyarakat prasejarah telah mampu
mengatur kehidupannya. Mereka melakukan kegiatan bukan lagi
sekadar memenuhi kebutuhan primer, melainkan untuk
meningkatkan kesejahteraan. Kebutuhan akan makanan dipenuhi
dengan cara bertani di ladang dan di sawah. Pertanian menjadi mata
pencaharian tetap. Agar tidak sepenuhnya bergantung pada air
hujan, dalam persawahan dilakukan pengaturan air. Selain bertani,
peternakan tetap dilanjutkan. Bahkan hewan yang diternakkan lebih
beragam. Manusia prasejarah telah mampu beternak kuda dan
berbagai jenis unggas. Kebutuhan akan tempat tinggal dipenuhi
dengan membangun pedesaan yang teratur. Teknik pembuatan
rumah sudah lebih maju dibandingkan masa bercocok tanam.
Masyarakat purba mulai memilih tempat yang tepat dan menetap di
daerah pegunungan, dataran rendah maupun tepi pantai.
Perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau
tempat-tempat yang lebih jauh bahkan antar pulau. Barang yang
dipertukarkanpun semakin beragam, seperti alat pertanian, alat
upacara dan hasil kerajinan.
29
Dari sisi kehidupan sosial, manusia prasejarah masa berburu
dan mengumpulkan makanan hidup berpindah dan tempat yang
satu ke tempat yang lain (nomad). Kehidupan berpindah-pindah
seperti itu mengakibatkan pengaturan masyarakat masih amat
sederhana. Masyarakat tersusun menurut kelompok berburu. Tiap
kelompok merupakan keluarga kecil dengan pembagian kerja yang
jelas. Kaum laki-laki bertugas melakukan perburuan. Kaum
perempuan bertugas mengumpulkan makanan (food gathering).
Perempuan juga bertugas mengurus anak serta memilih tumbuh-
tumbuhan untuk diramu. Setelah api ditemukan, perempuan
mendapat tambahan tugas memelihara api agar tetap menyala.
Komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia lain
dilakukan melalui bahasa yang masih amat sederhan seperti bahasa
isyarat.
Kehidupan di sekitar sungai menunjukkan pola kehidupan
manusia purba yang hidup di alam terbuka. Manusia purba
memiliki kecenderungan untuk menghuni wilayah terbuka di
sekitar aliran sungai. Kecenderungan ini muncul mengingat sungai
menyediakan air, kesuburan tanah dan hewan buruan yang
melimpah. Manusia purba juga memiliki kecenderungan
memanfaatkan gua–gua sebagai tempat berlindung. Namun
mengingat mobilitas manusia purba yang tinggi tidak
memungkinkan untuk selamanya menetap di gua. Pada
perkembangannya gua hanya dihuni sementara sehingga tidak
banyak meninggalkan jejak pada kita saat ini.
Hal penting yang perlu diketahui adalah ketika masa transisi
dari nomaden dan tinggal menetap pada manusia purba. Manusia
purba di Indonesia diperkirakan hidup secara nomaden (berpindah
– pindah) dalam jangka waktu yang lama. Mereka mengumpulkan
bahan makanan dalam lingkup wilayah tertentu dan berpindah –
pindah. Manusia purba hidup dalam skala kelompok kecil dengan
mobilitas yang tinggi. Keterisolasian dalam hutan tropis di
Indonesia serta ketiadaan kontak dengan dunia luar membuat
manusia di Indonesia menutup diri dari adopsi budaya luar. Ketika
suatu tempat sudah tidak menjanjikan bahan makanan, maka
30
mereka melakukan perpindahan ke wilayah lain mencari wilayah
persinggahan baru yang memberikan lebih banyak bahan makanan.
Pada masa bercocok tanam, manusia telah menetap dalam
perkampungan sederhana. Kehidupan menetap memberi
kesempatan bagi mereka untuk menata kehidupan secara lebih
teratur. Masyarakat tersusun menurut kelompok bertani. Mereka
membangun perkampungan secara bergotong royong. Gotong
royong dirasakan penting peranannya bagi kesejahteraan
perkampungan. Pembagian kerja semakin jelas. Pekerjaan yang
menghabiskan banyak tenaga dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti
membuka hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, dan
membangun rumah. Kaum perempuan menabur benih, merawat
rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga lainnya. Gotong
royong menumbuhkan kesadaran akan pentingnya seorang
pemimpin kampung. Orang yang dipilih sebagai pemimpin
biasanya adalah orang paling tua yang berwibawa. Pemimpin
berperan menjaga agar gotong royong di antara sesama warga
kampung tetap berlangsung. Aturan hidup bermasyarakat mulai
diberlakukan, sehingga kehidupan bersama dalam perkampungan
memungkinkan perkembangan bahasa sebagai alat komunikasi
menjadi lebih majemuk.
Pada masa perundagian, manusia prasejarah tinggal dalam
perkampungan yang semakin besar dan teratur. Jumlah warga yang
semakin banyak membuat perlunya penataan masyarakat yang tegas
dan ketat. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang majemuk.
Ada kelompok petani, pedagang, dan tukang
(undagi=tukang/pengrajin). Masyarakat semakin terbagi menurut
keahlian yang dimiliki.
Semakin terbaginya masyarakat membuat pembagian kerja
semakin tegas. Pada masa sebelumnya seseorang dapat melakukan
beragam pekerjaan, seperti bercocok tanam, membuat alat dan
mengerjakan kerajinan. Pada masa perundagian, seseorang bekerja
menurut keahlian yang dimiliki. Pembagian masyarakat yang
semakin majemuk mengakibatkan adanya perbedaan status.
Seseorang diperlakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Seorang
31
pemimpin kampung diperlakukan berbeda dengan pemimpin
upacara kepercayaan dan warga biasa. Perbedaan status itu
diperlukan agar aturan dapat ditegakkan. Walaupun demikian,
gotong royong tetap terjalin.
Kehidupan berbudaya manusia prasejarah tampak dalam
kemahiran membuat alat, mengembangkan kesenian dan
membangun kepercayaan. Kemahiran membuat alat masih sangat
sederhana. Alat yang dihasilkan masih kasar bentuknya. Alat itu
digunakan untuk berburu dan meramu makanan. Pada
perkembangan berikutnya, jenis alat yang dihasilkãn tetap sama,
namun lebih halus buatannya. Alat batu yang dihasilkan pada masa
ini berciri palaeolitik kemudian mesolitik.
Kesenian masih terbatas pada seni lukis. Seni lukis baru
dikenal setelah masyarakat prasejarah tinggal dalam gua-gua.
Lukisan di dinding gua menggambarkan manusia dalam berbagai
kegiatan, binatang, matahari, cap tangan, dan bangun geometris.
Corak kepercayaan tampak dan lukisan dan penguburan. Corak
kepercayaan baru terlihat pada tingkat lanjut. Lukisan dinding gua
mengungkapkan kepercayaan masyarakat prasejarah akan kekuatan
magis. Lukisan cap tangan, misalnya, melambangkan kekuatan
pelindung dan serangan roh jahat. Kemudian penguburan
mengungkapkan penghormatan masyarakat prasejarah terhadap
nenek moyang dan kehidupan sesudah kematian (alam baka).
Penghormatan tersebut diungkapkan juga melalui upacara
kesuburan, memperingati peristiwa penting dan upacara lainnya.
Kemahiran membuat alat semakin berkembang. Alat yang
dihasilkan sudah halus buatannya. Alat itu digunakan untuk
berladang dan perlengkapan upacara. Alat batu yang dihasilkan dan
masa ini berciri neolithik. Selain alat batu, masyarakat prasejarah
(khususnya perempuan) mampu membuat alat rumah tangga dan
tanah liat seperti gerabah. Kerajinan tersebut diwariskan turun-
temurun. Kesenian telah mencakup bidang kerajinan dan bangunan
dan batu besar (megahitik). Selain seni lukis, manusia prasejarah
telah mampu membuat perhiasan dari batu pilihan dan kulit
kerang. Hasil kerajinan itu berupa gelang dan manik-manik.
32
Bangunan megalitik diperlukan untuk kegiatan yang berhubungan
dengan kepercayaan seperti menhir, watu ulo, punden berundak
dsb.
Seiring dengan perkembangan kemampuan berfikir manusia-
manusia purba. Mereka mulai mengenal kepercayaan terhadap
kekuatan-kekuatan lain di luar dari dirinya. Sehingga mereka
melakukan upacara atau ritual khusus untuk menjalankan
kepercayaan yang diyakininya memberi kekuatan. Sistem
kepercayaan yang di percaya manusia pada masa praaksara atau
masa prasejarah antara lain animisme, dinamisme, totemisme.
1. Animisme, adalah percaya pada roh nenek moyang maupun
roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya
yang dilakukan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu adalah
dengan memberikan sesaji.
2. Dinamisme, adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-
benda yang mempunyai sifat gaib. Manusia purba melakukanya
dengan cara menyembah batu atau pohon besar, gunung, laut,
gua, keris, jimat, dan patung.
3. Totemisme, adalah percaya pada binatang yang dianggap suci
dan memiliki kekuatan. Dalam melakukan upacara ritual
pemujaan manusia purba membutuhkan sarana atau tempat.
Mereka membangun bangunan dari batu yang dipahat dengan
ukuran yang besar. Masa ini di sebut sebagai kebudayaan
Megalitikum (kebudayaan batu besar).
Kehidupan manusia purba saat zaman mengenal kepercayaan,
sebagai berikut : Melaksanakan upacara-upacara khusus, untuk
bukti adanya kekuatan yang melebihi mereka dan mulai terdapat
bangunan-bangunan besar untuk dijadikan sebagai tempat
melakukan pemujaan maupun upacara.
Corak kepercayaan tampak pada benda-benda jimat,
penguburan dan bangunan megalitik. Kepercayaan manusia
prasejarah dan masa ini melanjutkan kepercayaan dan masa
sebelumnya, namun telah diperkaya dengan beragam bentuk
kegiatan upacara. Misalnya, upacara penguburan semakin rumit.
Jenasah dibekali dengan bemacam-macam barang agar perjalanan
33
ke alam baka terjamin. Kemudian, jenasah dikuburkan ke arah
tertentu agar perjalanan kealam baka tidak tersesat.
Pada tahapan masa selanjutnya, kemahiran membuat alat
sudah menggunakan teknologi. Alat yang dihasilkan terbuat dari
logam, yakni perunggu dan besi. Alat itu digunakan untuk bertani,
bertukang, peralatan rumah tangga dan perlengkapan
upacara. Begitu pula, kesenian mencakup berbagai bidang, yakni
seni lukis, kerajinan, seni ukir/pahat, seni patung, dan arsitektur
(bangunan). Kemampuan kesenian ditunjang oleh teknologi dan
spesialisasi dalam masyarakat. (Munculnya golongan
undagi/pengrajin mendukung munculnya golongan
seniman). Demikian juga, corak kepercayaan tampak dan benda-
benda logam yang digunakan sebagai perlengkapan upacara.
Kepercayaan manusia prasejarah dan masa ini melanjutkan
kepercayaan dari masa sebelumnya, dengan aturan yang semakin
jelas dan ketat. (Ada hukuman terhadap pelanggaran tertentu).
Lantas bagaimana kira-kira kondisi manusia prasejarah di
Nganjuk? Hal ini membutuhkan jawaban yang cukup sulit karena
masih terbatasnya artefak prasejarah terutama fosil manusia
purbanya. Namun demikian apabila ditinjau dari artefak yang sudah
ditemukan diantaranya : batu bola/batu lithik/batu lontar untuk
berburu, menhir (tugu batu yang dibangun untuk pemujaan
terhadap arwah-arwah nenek moyang), dolmen (meja batu tempat
meletakkan sesaji untuk upacara pemujaan roh nenek moyang),
sarchopagus (keranda atau peti mati berbentuk lesung bertutup),
punden berundak (tempat pemujaan bertingkat), kubur batu (peti
mati yang terbuat dari batu besar yang dapat dibuka-tutup), manik-
manik bekal kubur serta arca/patung batu (simbol untuk
mengungkapkan kepercayaan), dapat ditarik sebuah kesimpulan
bahwa kehidupan manusia purba sudah ada pada masa Neolitikum
dan Megalitikum. Adapun corak kehidupanya secara sosial,
ekonomi dan budaya sebagaimana yang digambarkan pada
paragraf-paragraf di atas.
Selanjutnya, batas antara zaman prasejarah dengan zaman
sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu
34
pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya
tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan.
Berakhirnya zaman prasejarah atau dimulainya zaman sejarah
untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dari peradaban
bangsa tersebut. Salah satu contoh yaitu bangsa Mesir sekitar tahun
4000 SM masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat
itu, bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Zaman
prasejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya
Kerajaan Kutai sekitar abad ke-5, dibuktikan dengan adanya
prasasti yang berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai
Mahakam Kalimantan Timur, yang selanjutnya dapat disebut baru
memasuki era sejarah. Oleh karena tidak terdapat peninggalan
catatan tertulis dari zaman prasejarah, keterangan mengenai zaman
ini diperoleh melalui bidang-bidang seperti paleontologi, astronomi,
biologi, geologi, antropologi dan arkeologi. Dalam artian bahwa
bukti-bukti prasejarah hanya didapat dari barang-barang dan tulang-
tulang di daerah penggalian situs sejarah.
A. PENGERTIAN MANUSIA PURBA
Manusia purba sering disebut dengan manusia prasejarah
atau manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia
purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih
dari 4 juta tahun yang lalu. Maka dari itu, para ahli sejarah
menyebutnya sebagai Prehistoric People atau manusia
prasejarah. Manusia purba banyak ditemukan diberbagai bagian
dunia, tapi lebih banyak ditemukan di negara Indonesia. Fosil-
fosil yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah
satunya ada yang sudah berumur jutaan tahun yang lalu.
Untuk mengetahui keberadaan kehidupan manusia purba
lebih dalam. Anda bisa melihat sisa-sisa tulang manusia, hewan
dan tumbuhan yang sudah menjadi batu atau jadi fosil. Atau
bisajuga melalui peninggalan-peninggalan peralatan yang
digunakan oleh manusia purba. Seperti, peralatan rumah
tangga, senjata, bangunan, atau perhiasan. Eugena Dobois,
adalah orang yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba
35
di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari
B.D Von Reitschoten yang menemukan tengkorak di Wajak,
Tulung Agung Jawa Timur. Fosil itu dinamai Homo
Wajakensis, karena termasuk dalam jenis Homo Sapien
(manusia yang sudah berpikir maju). Fosil lain yang ditemukan
adalah : Pithecanthropus Erectus (Phitecos = kera, Antropus =
Manusia, Erectus = berjalan tegak) yang ditemukan di daerah
Trinil, pinggir Bengawan Solo, dekat Ngawi, tahun 1891.
Penemuan ini sangat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan.
Peneliti berikutnya adalah G.H.R Von Koeningswald.
Hasil penemuannya adalah : fosil tengkorak di Ngandong,
Blora. Kemudian pada tahun 1936 ditemukan tengkorak anak
di Perning, Mojokerto. Pada tahun 1937 – 1941 ditemukan
tengkorak tulang dan rahang Homo Erectus dan Meganthropus
Paleojavanicus di Sangiran, Solo. Penemuan lain tentang
manusia purba : tengkorak, rahang, tulang pinggul dan tulang
paha manusia Meganthropus, Homo Erectus dan Homo
Sapien di lokasi Sangiran, Sambung Macan (Sragen),Trinil,
Ngandong dan Patiayam (Kudus).
Penelitian tentang manusia Purba oleh bangsa Indonesia
dimulai pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Prof. DR. T.
Jacob dari UGM, di daerah Sangiran dan sepanjang aliran
Bengawan Solo.
B. JENIS DAN CIRI MANUSIA PURBA DI PULAU JAWA
Di Indonesia penelitian tentang manusia purba sudah
lama dilakukan, yaitu sejak abad ke-18 M. Penelitian manusia
purba di Indonesia dipelopori oleh Eugene Dubois, beliau
adalah seorang dokter dari Belanda. Penelitian tersebut
dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis manusia purba yang ada
di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penemuan-penemuan
fosil yang ditemukan di daerah Solo, Pacitan, Ngandong,
Mojokerto, Sangiran dan masih banyak lagi lainnya. Setelah
melakukan banyak penelitian mengenai manusia purba yang
berada di berbagai daerah di Indonesia, para Ahli kemudian
36
membagi manusia purba di Indonesia menjadi tiga jenis. yaitu,
Meganthropus (Manusia besar), Pithecanthropus (Manusia kera
yang berjalan tegak), dan Homo Erectus (Manusia yang
berpikir).
Para ilmuwan sejarah di seluruh belahan dunia, sebagian
besar menganut teori evolusi kera atau yang lebih dikenal
dengan teori Australopithecus yang sudah punah sebagai ras
nenek moyang manusia. Sebenarnya teori tersebut terjadi
banyak perbedaan yang sangat signifikan. Serta jauh sekali tidak
ada hubungannya antara manusia dan kera. Perbedaan tersebut
tidak bisa dijelaskan oleh penganut teori Australopithecus,
dengan peristiwa yang hilang atau lebih dikenal dengan sebutan
missing link.
Manusia purba Meganthropus Palaejavanicus adalah
manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia.
Manusia purba ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari
Belanda yang bernama Van Koenigswald. Ia merupakan orang
yang pertama kali menemukan fosil di daerah Sangiran pada
tahun 1936. Meganthropus Palaeojavani memiliki arti manusia
besar tua yang berasal dari Jawa. Ini unsur-unsur namanya yang
terdiri dari kata megan berarti besar, anthropus = manusia,
paleo = tua, dan javanicus = berasal dari Jawa. Diperkirakan
Meganthropus Palaeojavanicus hidup sejak 1 juta sampai 2 juta
tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dari fosil yang
ditemukan yang telah diuji dengan teknik peluruhan karbon
sehingga dari itu, usia dari fosil tersebut dapat diketahui.
Berikut ini adalah ciri-ciri manusia purba jenis
Meganthropus Palaeojavanicus :
Memiliki tulang pipi yang sangat tebal;
Memiliki otot rahang yang kuat sekali;
Tidak memiliki dagu dan memiliki hidung yang lebar;
Memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang
sepanjang pelipis;
Memiliki tulang kening menonjol dan mempunyai otot
kunyah, gigi, serta rahang yang besar kuat;
37
Memiliki tinggi badan sekitar 165 – 180 cm;
Berbadan tegap dan volume otok 900 cc;
Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan.
Pithecanthropus merupakan manusia purba yang fosilnya
banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada tiga
jenis manusia purba ini dan yang sudah ditemukan. Diantaranya
adalah Pithecanthrophus Erectus, Pithecanthrophus
Mojokertensis dan Pithecanthropus Soloensis. Manusia purba
ini diperkirakan hidup di Indonesia sejak satu sampai dua juta
tahun yang lalu. Pithecanthropus Erectus ditemukan oleh
seorang dokter dari Belanda yaitu Eugene Dubois. Pada
awalnya dia mengadakan penelitian di Sumatera Barat, tetapi
tidak menemukan fosil disana. Kemudia dia berpindah ke
pulau Jawa, ia pun berhasil menemukan fosil Pithecanthrophus
Erectus di desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada
tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa
tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Fosil tersebut
ditemukan pada masa kala Pleistosen tengah. Pithecanthrophus
Erectus hidup dengan cara berburu hewan-hewan. Kemudian
mereka mengumpulkan makanan dan hidup secara nomaden
atau berpindah-pindah tempat. Untuk mencari sumber bahan
makanan dari satu tempat ke tempat lain. Berikut ini adalah
ciri-ciri manusia purba Pithecanthrophus Erectus :
Memiliki Volume otaknya sekitar 750 – 1350 cc;
Memiliki tinggi badan sekitar 165 – 180 cm;
Memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap
meganthropus;
Mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang
sangat kuat;
Mempunyai hidung yang tebal;
Memilik tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi;
Memiliki wajah menonjol ke depan serta dahinya miring ke
belakang;
Pada bagian belakang kepala terlihat menonjol;
38
Memiliki alat pengunyah dan alat tengkuk yang sangat kuat.
Pada tahun 1889, fosil dari manusia purba Homo
Wajakensisi telah ditemukan di daerah Wajak, di dekat
Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur dan ditemukan oleh
Eugene Dubois. Penemuan tersebut, berupa tulang paha,
rahang atas dan bawah, tulang kering. Fragmen tengkorak yang
ditemukan mempunyai volume sekitar 1.600 cc. Dalam
penelitian diperkirakan manusia purba jenis ini sudah dapat
membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang. Serta
sudah mengerti caranya untuk memasak. Dibawah ini adalah
ciri-ciri manusia purba Homo Wajakensis, sebagai berikut :
Memiliki muka datar dan lebar;
Memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol;
Dahinya sedikit miring dan diatas mata terdapat kerutan
dahi yang nyata;
Pipinya menonjol ke samping;
Berat badan sekitar 30 – 150 kg;
Tinggi badan sekitar 130 - 210 cm;
Jarak antara hidung dan mulut masih jauh;
Berdiri dan berjalan sudah tegak.
Pithecanthropus Soloensis merupakan salah satu jenis
manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil-fosil
manusia purba ini dapat ditemukan di wilayah sekitar Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Pithecanthropus Soloensis ditemukan
oleh sejarawan, yaitu Oppenort, Ter Harr, dan G.H.R.
Koenigswald di wilayah Ngandong, Jawa Tengah.
Pithecantropus Soloensis adalah salah satu manusia purba khas
Indonesia. Yang memiliki beberapa ciri khusus yang tidak
dimiliki oleh semua manusia purba pada umumnya. Berikut ini
ciri dari pithecantropus soloensis.
Makanannya berupa hewan buruan dan tumbuhan;
Mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat;
Bentuk hidung lebar dan tidak berdagu;
39
Terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di
sepanjang pelipis;
Volume otak sekitar 750-1350 cc;
Berbadan tegap;
Tinggi tubuh sekitar 165-180 cm.
40
BAB IV
PERADABAN MATARAM KUNO DI NGANJUK
A. PERSAINGAN WANGSA SANJAYA DAN SYAILENDRA
Menurut de Casparis, di Jawa mula-mula berkuasa wangsa
raja-raja yang beragama Siwa, tetapi setelah kedatangan raja dari
Na-fu-na1 yang berhasil menaklukannya, di Jawa Tengah
terdapat dua wangsa raja-raja, yaitu raja-raja dari wangsa Sanjaya
yang beragama Siwa, dan para pendatang baru, yang
menamakan dirinya wangsa Syailendra yang beragama Budha.
Nugroho Notosusanto, (2009 : 115)
Pada tahun 1965 ditemukan prasasti Sajamerta di
Pekalongan yang kemudian menimbulkan polemik tentang
keberadaan Dinasti Sanjaya dan Syilendra di Jawa Tengah.
Sebelumnya keberadaan Sanjaya yang kemudian dipenetrasi
dan dikuasai oleh Syailendra berdasarkan prsasti Kalasan 778
M tidak terbantahkan. Akan tetapi dengan adanya prasasti
Sajamerta berhuruf Dewa Nagari, beberapa ahli berpendapat
bahwa lebih tua dari prasasti yang ada di Sriwijaya keluarga
Syailendra. Ini memberi bukti bahwa pada awal abad VIII di
Jawa Tengah ada dua dinasti yang berkuasa. Salah satu dari
kedua dinasti tersebut; Syailendra dari 778 M - 856 M berkuasa
di Jawa Tengah (Selatan). Sanjaya kemudian seakan tenggelam,
sampai terjadinya restorasi (pemulihan) yang dilakukan oleh
Raka i Pikatan pada tahun 856 M.
B. SYAILENDRA BERKUASA DI JAWA TENGAH
Bila Raka i Panangkaran mengeluarkan prasasti Kalasan
pada tahun 778 M maka sebelumnya Bhanu dari dinasti
Syailendra telah menjadi raja di Mataram (752-775 M).
Sehingga, Bhanu sebagai penguasa pendahulu Panangkaran,
atau bahkan telah menjadi vazalnya. Adapun penguasa
Syailendra lainnya, yaitu; Wisnu (775-782 M), Indra (782-
812M), Samarottungga (812-833M), dan Balaputra Dewa (833-
856M).
41
Karya-karya besarnya dalam bidang keagamaan Budha
Mahayana tercermin pada bangunan-bangunan suci; Kalasan,
Sari, Pawon, Mendut, Bharabudur, Sewu dan Plaosan.
Dalam kekuasaan tampaknya, dinasti Sanjaya meskipun
tenggelam tetapi tidak sampai runtuh, cukup menjadi penguasa
di daerah atau kerajaan kecil di bawah supremasi dan tunduk
kepada kekuasaan Syailendara dengan gelar "Raka i", artinya
yang dituakan (kakak), penguasa di (?), kepala daerah di (?).
Misalnya; Sanjaya, Panangkaran, Warak, Garung, Pikatan,
Kayuwangi dan Raka i Balitung. Daftar ini dibuat oleh Raka i
Balitung tercantum dalam prasasti Kedu 907 M. bahwa
pembuatnya merasa perlu adanya legitimasi hubungan
genealogisnya dengan Sanjaya.
R. Ng. Poerbotjaroko, Sanjaya dan keturunannya ialah
raja-raja dari wangsa Syailendra, asli Indonesia, semula
beragama siwa, sejak Raka i Panangkaran menjadi raja,
berpindah agama Budha Mahayana. Nugroho Notosusanto,
(2009 : 116)
C. SANJAYA RESTORASI (PEMULIHAN) 856 M
Samarattungga, yang berdasarkan prasasti Karang Tengah
(824 M) adalah pendiri Candi Bharabudur, memiliki 2 putera,
Pramodhawardani atau Sri Kahulunan dan adiknya Balaputera
Dewa. Pramodhawardani kemudian diperistri oleh Raka i
Pikatan
Berdasarkan prasasti Ratu Boko 856 M, terjadilah
peperangan terbuka antara Pikatan dengan Balaputera Dewa,
yang berakhir dengan terusirnya Balaputra Dewa ke Sriwijaya.
Pada tahun 860 M, Balaputera Dewa telah mengeluarkan
prasasti Nalanda sebagai raja di Sriwijaya. Tampaknya
persaingan ini juga meliputi masalah keagamaan, bila Syailendra
penganut Budha Mahayana, sedang Sanjaya adalah pemeluk
agama Hindu Syiwa. Terbukti dari peninggalannya seperti
Candi-candi Prambanan, Banon, dan Candi Ijo.
42
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
BUKU SEJARAH NGANJUK ERA PRASEJARAH
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search