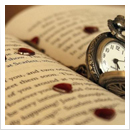Selanjutnya para pengganti Pikatan, untuk menghindari
serangan balasan Syailendra di Sumatra, kemudian menggeser
ke arah timur pada masa Kayuwangi dan Balitung serta sama
sekali memindahkan wilayah serta kekuasaannya ke Jawa
Timur.
Dalam prasasti Sang Hyang Wintang (832 M), Rakai
Patapan pu Palar menyebut daerah kekuasaannya dengan “yang
rajya direksa iya sabanaka yang desa itas tatah purwwa daksima
uttara itas tatah.”
Rakai pu Palar memberikan tanah-tanahnya sebagai sima
pembangunan candi oleh Samaratungga, kemudian ia
berambisi untuk menjadi raja. Dalam hal ini, rupa-rupanya lalu
diadakan perkawinan dengan Raka i Pikatan, anak Rakai
Patapan pu Palar.
Setelah Samaratungga meninggal, Raka i Pikatan resmi
menggantikan sebagai maharaja di Medang.
De Casparis berpendapat, Rakai Patapan pu Palar ialah
anggota Sanjayawangsa. Dialah yang mulai memberontak
melawan penjajakan wangsa Syailendra dengan mengeluarkan
prasasti Sang Hyang Wintang. Karena takut menghadapi
Sanjayawangsa, Samaratungga, raja wangsa Sailrendra
menyerahkan anak perempuannya, bernama Pramodawardhani
untuk dikawinkan dengan anak Rakai Patapan pu Palar, yaitu
Raka i Pikatan. Kemudian, Raka i Pikatan menggantikan duduk
di atas tahta kerajaan di Jawa.
Mengetahui keadaan seperti itu, adik Pramodawardhani,
yaitu bernama Balaputra Dewa, yang ibunya bernama Tara dari
Sriwijaya mengadakan perlawanan, menyerang Raka i Pikatan.
Namun ia dapat dikalahkan, kemudian kembali Sumatera
menjadi raja di Sriwijaya.
Sejak itu, Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya yang merasa
sebagai trah wangsa Syailendra di Jawa terus-menerus menebar
api permusuhan dengan trah wangsa Syailendra di Jawa.
43
Setelah Raka i Pikatan berhasil mengalahkan Balaputra
Dewa, ia membangun candi induk percandian Loro Jonggrang,
lantas ia mengundurkan diri jadi raja, untuk menjadi petapa.
Kemudian, pemerintahan diserahkan kepada anaknya, bernama
Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi.
D. PERMUSUHAN LATENT JAWA - SUMATRA (ABAD IX
- XIV)
Persaingan yang telah berkembang menjadi permusuhan
itu ternyata berawal dari peperangan antara Sumatera
(keturunan Syailendra/Sriwijaya) dan Jawa Tengah serta Jawa
Timur (keturunan Sanjaya). Permusuhan antara dua dinasti
tersebut berkembang menjadi permusuhan abadi (latent).
Peristiwa tersebut berlangsung dari pertengahan abad IX -
Balaputera melawan Pikatan, abad X - Sindok /Sri Icana
melawan Melayu, awal abad XI – Dharmawangsa Teguh
melawan Haji Wurawari, abad XIII terjadi expedisi Pamalayu
oleh Kartanegara melawan Sriwijaya yang bersekutu dengan
kekuasaan Mongol di Cina, pada pertengahan kedua abad XIV
yaitu pada 1377, Sriwijaya dihancurkan oleh armada Majapahit
karena kerajaan besar ini telah menjadi sarang bajak-bajak laut
China yang juga berkeliaran di kawasan Asia Tenggara lainnya.
Selanjutnya, kondisi keamanan di Jawa terus memburuk.
Setiap terjadi pergantian pimpinan, sering disertai dengan
pertikaian dan intrik politik. Hingga, Dyah Wawa naik tahta
menggantikan Dyah Tulodhong dengan cara kudeta. Nama
Dyah Wawa yang bergelar Rakai Sumba tercatat dalam prasasti
Culanggi tanggal 7 Maret 927 M, menjabat sebagai Sang Pamgat
Momahumah, yaitu semacam pegawai pengadilan.
Dalam prasasti Wulakan tanggal 14 Februari 928 M, Dyah
Wawa mengaku sebagai anak Kryan Landheyan sang Lumah ri
Alas (putra Kryan Landheyan yang dimakamkan di hutan).
Nama ayahnya ini mirip dengan Rakryan Landhayan, yaitu ipar
Rakai Kayuwangi yang melakukan penculikan dalam peristiwa
Wuatan Tija.
44
Saudara perempuan Rakryan Landhayan yang menjadi
istri Rakai Kayuwangi bernama Rakryan Manak, dialah yang
melahirkan Dyah Bhumijaya. Ibu dan anak itu suatu hari
diculik Rakryan Landhayan, namun keduanya berhasil
meloloskan diri di desa Tangar. Anehnya, Rakryan Manak
memilih bunuh diri di Desa Taas, sedangkan Dyah Bhumijaya
ditemukan para pemuka desa Wuatan Tija dan diantarkan
pulang ke hadapan Rakai Kayuwangi.
Makam Rakryan Landhayan sang pelaku penculikan
diberitakan terdapat di tengah hutan. Mungkin ia akhirnya
tertangkap oleh tentara Medang dan dibunuh di dalam hutan.
Peristiwa tersebut terjadi tahun 880 M. Mungkin saat itu Dyah
Wawa masih kecil. Jadi, Dyah Wawa merupakan sepupu dari
Dyah Bhumijaya, putra Rakai Kayuwangi (raja Medang 856–
890 M).
Dengan demikian, Dyah Wawa tidak memiliki hak atas
tahta Dyah Tulodhong. Sejarawan Boechari berpendapat bahwa
Dyah Wawa melakukan kudeta untuk merebut tahta Kerajaan
Medang.
Kemungkinan besar kudeta yang dilakukan oleh Dyah
Wawa mendapat bantuan dari Pu Sindok, yang kemudian naik
pangkat menjadi Rakryan Mapatih Hino. Sebelumnya, yaitu
pada masa pemerintahan Dyah Tulodhong, Pu Sindok
menjabat sebagai Rakryan Halu, sedangkan Rakai Hino dijabat
oleh Pu Ketuwijaya.
Peninggalan sejarah Dyah Wawa berupa prasasti
Sangguran tanggal 2 Agustus 928 M tentang penetapan desa
Sangguran sebagai sima swatantra (daerah bebas pajak) agar
penduduknya ikut serta merawat bangunan suci di daerah
Kajurugusalyan.
Tampaknya, intrik politik dalam istana tidak terbatas pada
satu kejadian itu saja. Terbukti setelah Rakai Kayuwangi, ada
beberapa raja penggantinya yang memerintah dalam kurun
waktu yang singkat. Misalnya, Dyah Tagwas, memerintah dalam
waktu 8 bulan, Rake Panuwungan Dyah Dewandra memerintah
45
selama 1 tahun 4 bulan karena digulingkan dari tahta, dan Rake
Gurunwangi Dyah Bhadra yang hanya memerintah 28 hari
sebelum ia melarikan diri dari keratonnya.
E. PERADABAN MATARAM MEDANG DI JAWA TIMUR
Jauh sebelum pusat pemerintahan Kerajaan Mataram
Medang di Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur (929
Masehi), di Jawa Timur telah berdiri kerajaan-kerajaan dan
peradaban kuno.
Bukti sejarah berupa prasasti telah menguatkan adanya
kerajaan dan peradaban pada era abad ke VIII hingga XII di
Jawa Timur.
1. Prasasti Dinoyo, 682 Saka (=760 Masehi)
Prasasti Dinoyo, ditemukan di Desa Dinoyo, sekitar 5
kilometer arah barat laut Kota Malang. Prasasti yang hingga
sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta itu ditulis
dengan Bahasa Sansekerta dalam huruf Jawa Kuno. (R.
Pitono, 1961).
Isi Prasasti Dinoyo tentang peresmian bangunan suci
bagi Arca Agastya yang dilaksanakan pada bulan
Marggaśirsa tahun 682 Śaka (November, 760 Masehi).
Prasasti Dinoyo juga mengungkapkan informasi penting
terkait silsilah penguasa Kerajaan Kanjuruhan.
Silsilah penguasa Kerajaan Kanjuruhan itu dimulai dari
Devasiṃha yang memiliki putera bernama Limwa. Setelah
diangkat menjadi raja Kanjuruhan menggantikan ayahnya,
nama Limwa berganti menjadi Gajayana. Limwa memiliki
puteri bernama Uttajana yang menikah dengan Jananiya.
Merujuk pada kajian Sri Soejatmi Satari dalam "Upacara
Weda di Jawa Timur: Telaah Baru Prasasti Dinoyo" yang
terbit melalui Jurnal Penelitian dan Pengembangan
Arkeologi (Volume 27, No 1 Tahun 2009: hlm. 38), ketika
Prasasti Dinoyo ditulis, Raja Gajayana sebenarnya telah
wafat.
46
Fakta ini terlihat dari keberadaan kata "smṛtaḥ" di
belakang nama Gajayana yang berarti: "seperti yang diingat
orang." Selain itu, upacara penggantian arca Agastya dari
kayu cendana menjadi batu hitam serta pendirian bangunan,
yang tercatat di prasasti Dinoyo, dilaksanakan oleh A-nanah
yang merupakan anak Uttajana, alias cucu Gajayana.
Slamet Sujud dalam artikel bertajuk "Eksplorasi Nilai-
Nilai Pendidikan Bangsa dari Sejarah Lokal Malang Mulai
Zaman Prasejarah Sampai Masa Hindu-Budha Abad XI"
yang terbit di Jurnal Sejarah dan Budaya UM (Volume 8,
2014: 88), menjelaskan bahwa sudah ada struktur sosial-
politik yang mapan di kawasan Malang, Jawa Timur, pada
abad ke-8 Masehi.
Pada saat itu, Kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin
seorang raja bernama Liswa atau Limwa dengan
abhisekanama (gelar) Gajayana, telah memiliki sistem
pemerintahan yang tertata, serta susunan masyarakat yang
teratur seperti golongan petani, punggawa, dan bangsawan.
Sementara Rully Dwi dalam "Kajian Historis tentang Candi
Badut di Kabupaten Malang" yang terbit di
Jurnal Pancaran (Volume 2, 2013: 204-205), memberikan
penafsirannya terkait dengan isi dari Prasasti Dinoyo.
Menurut dia, Kerajaan Kanjuruhan awalnya dipimpin oleh
raja bernama Dewasimha. Sepeninggal Dewasimha kerajaan
tersebut dipimpin oleh anaknya Liswa dengan gelar
Gajayana.
Selanjutnya, sekitar 742 hingga 755 M sepeninggal
Dewasimha, Liswa (Gajayana) memindahkan ibu kota
Kanjuruhan dari sebelah barat Gunung Kelud ke sebelah
timur Gunung Kawi.
Rully mengutip pendapat W. J. Van der Meulen,
bahwa pemindahan ibu kota Kanjuruhan berkaitan dengan
serangan angin ribut yang menampar dari arah barat.
47
Perpindahan itu juga disebut sebagai strategi terbaik
Gajayana, karena letak geografis Kanjuruhan yang berada di
wilayah Tumapel yang dipagari barisan gunung.
Keruntuhan dari Kanjuruhan sebenarnya bukan
disebabkan invasi dari kerajaan lain, melainkan karena
munculnya sebuah kerajaan baru yang dipimpin oleh
keturunan Raja Mataram Kuno, yakni Balitung, Daksa,
Tulodong dan Wawa.
Balitung (898-910) saat itu memilih memusatkan
kerajaan di Kediri daripada di Malang. Sejak saat itulah
Kerajaan Kanjuruhan hanya sebuah kerajaan bawahan yang
tidak terlalu penting.
Sementara pendapat lainnya menyatakan Kerajaan
Kanjuruhan diperkirakan telah ditaklukkan oleh Mataram
dan rajanya dianggap sebagai raja bawahan dengan gelar
Rakai Kanuruhan (Sumadio, 2008: 127).
Nama Kanuruhan pertama kali disebutkan dalam
Prasasti Wurandungan B. Prasasti berangka tahun 865 Saka
tersebut menyebutkan sebuah daerah bernama Watek
Kanuruhan. Pada masa Jawa Kuno, watek atau watak
merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa wanua
(desa) dan dipimpin oleh seorang rakai atau rakarayān
(rakryan).
Jadi, pada periode abad ke-VIII, di Jawa Timur telah
ada kerajaan dan peradaban bersamaan pemerintahan
Mataram Medang di Jawa Tengah. Peradaban berlangsung
hingga periode-periode berikutnya. Diduga, merupakan
kerajaan dan peradaban di bawah kekuasaan Mataram
Medang di Jawa Tengah.
2. Periode abad ke IX dan X di Nganjuk
Di wilayah Nganjuk pada periode abad ke IX dan X
juga ditemukan bukti peradaban yang kuat. Yaitu berupa
48
bangunan prasasti dan bekas kampung kuno, ditemukan di
beberapa wilayah di Nganjuk.
a. Prasasti Bangle (I)
Periode tahun 830 Saka (=908 Masehi) – peradaban
kuno muncul di Banyu Umbul, Lereng Gunung Sili,
Desa Bangle, Kecamatan Lengkong. Di area hutan jati ini
ditemukan prasasti Bangle (I) dan banyu umbul berasa
asin. Pada saatnya, banyu umbul ini bisa menyembul
berupa lumpur dari dalam tanah, bila diteriaki atau
ditepuk-soraki semakin bertambah tinggi. Mirip bleduk
yang menyembur di Desa Kuwu, Jawa Tengah.
Prasasti Bangle (I) era Mataram Medang raja Dyah
Balitung, menceritakan tentang penetapan sima desa
setempat untuk para bhiksu agama Budha.
Di sekitar area banyu umbul ini ditemukan banyak
pecahan kreweng (genteng), maka disebut warga sebagai
Gunung Kreweng. Steen, vroeger stannde te bangle (afd.
Berbek, res. Kediri), en wel volgens verbeek p. 255 bij de
warme zoutbronnen Bnjoe Oemboel. In de inventarisatie
Kediri in Rapp. 1908 wordt hij niet meer vermeld. Een
abklatsch komt Notulen 1859 Bijl. N.; Oudheidk.
Bureau No. 400
Prasasti Bangle (I) terletak di Desa Bangle, (afdeling
Berbek, Residen Kediri), di area sumber mata air hangat
yang mengandung garam, Banjoe Oemboel (Kecamatan
Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur). Pertama
ditemukan oleh Brandes 1859 dan dicatat dengan nomor
400.
Menurut Slamet Wiyono, (2017) juru pelihara
prasasti Bangle (I) pernah diteliti oleh ahli arkeologi dari
Belanda, menyebutkan sebagai prasasti pertemuan para
Bhiksu tahun 830 Saka atau 908 Masehi, Era Mataram
Kuno Raja Dyah Balitung.
Keterangan mengenai prasasti ini dapat ditemukan
dalam sumber: oud-javaansche oorkonden. Nagalaten
49
transsripties van wijlen Dr. J. L. A. Brandes, uitgegeven
door Dr. N. J. Krom. 1913, inhoud CXIV (halaman
248).
b. Prasasti Kinawe
Pada tahun 849 Saka (=927 Masehi), peradaban Era
Mataram Medang Raja Dyah Wawa muncul di Wanua
Kinawe, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot,
Nganjuk.
Saat pertama kali ditemukan, Kinawe masuk
wilayah Berbek, Residen Kediri (Verbeek, Oudheden:
255-266; Not.1889:33). Hanya, tahun 1889, prasasti
dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta dengan
nomor inventaris D.66.
Sebagian besar isi prasasti sekarang tidak bisa dibaca
lagi karena rusak. Isinya tentang Rake Gunung Dyah
Muatan ibu dari Dyah Bingah - Desa Kinawe agar
ditetapkan menjadi sima pada tahun 849 Saka atau 927
Masehi. Prasasti ini juga menyebut Sri Maharaja Wawa
dan Rakryan Mapatih Pu Sindok. Abklats prasasti ini
disimpan di Dinas Purbakala dengan nomor inventaris
388 dan 476 (Rao 1911:59). Prasasti ini dikenal juga
sebagai prasasti Tanjungkalang.
Isi prasasti menyebutkan bahwa Dyah Muatan
memohon kepada Raja Wawa melalui Samgat
Momahumah Anggehan bernama Pu Kundala dan
Samgat Landayan bernama Pu Wudyang agar Desa
Kinawe miliknya dibatasi dan ditetapkan sebagai tanah
sima.
Permohonan diterima, kemudian Raja Wawa
memerintahkan Rakryan Mapatih Pu Sindok Isana
Wikrama untuk diteruskan kepada Samgat Momahumah
Anggehan bernama Pu Kundala dan Samgat Landayan
bernama Pu Wudyang agar menetapkan Desa Kinawe
menjadi sima. Dengan syarat, persembahan kepada Sri
50
Maharaji Dyah Wawa, sebanyak 1 kati emas [mas ka 1]
sepasang kain untuk laki-laki jenis tangkilan [wdihan
tankalan, yu 1], dan sebentuk cincin jenis prasada seberat
.... suwarna emas ... [simsim prasada woh 1 ma brat su
...].
Informasi warga Dusun Balaikambang, Desa
Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot pernah ditemukan
banyak arca di tanah pekarangan Mbah Nyaman alias
Mbah Budo. Lokasi artefaks ditumbuhi pohon asam
besar, umur ratusan tahun. Bukti artefaks berupa arca
agastya, siwa, parwati, nandi, lingga yoni, lumpang batu,
umpak, batu bata besar, dll.
Artefaks sengaja dihancurkan warga tahun 1960-an,
karena di situs asem gede dianggap musrik. Benda-benda
bersejarah tersebut dibuang ke sungai dan sebagian
dikubur dalam sumur di situs Mbah Budo. Di lokasi
asem gede ini, dulunya ada bangunan candi, lokasi
dimana Prasasti Kinawe pernah ditemukan.
Menurut cucu Mbah Budo, Muntamah, (50), warga
Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, kakeknya
adalah keturunan wong kalang. Memiliki kesaktian dan
dapat mengobati segala penyakit. Hanya, kesehariannya,
Mbah Budo tidak pernah mengenakan pakaian dan suka
berendam di sungai.
Di Desa Tanjungkalang banyak keturunan wong
kalang yang dikenal memiliki kesaktian luar biasa, ahli
pembuat candi, hidup sebagai tuha kalang (penjaga
hutan/blandong) dan ahli di bidang perkayuan.
Wong kalang dikenal pekerja keras, mahir di
bidang perniagaan. Pada era Mataram Kuno hingga
Majapahit, kelompok wong kalang dikenal sebagai
prajurit paling berani. Dalam perang, wong kalang biasa
berada di garis depan, memiliki prinsip hidup sulit diatur
dan hanya tunduk kepada pemimpinnya.
51
Jaman modern, wong kalang sudah mulai sulit
dikenali. Mereka sudah menyatu dengan masyarakat
modern, dan perlahan mereka meninggalkan tradisi
wong kalang. Wong kalang dari bumi Kinawe tersebut
dipercaya masyarakat sebagai cikal bakal nama Desa
Tanjungkalang.
Di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot,
Kabupaten Nganjuk juga ditemukan sebuah lingga
beserta yoninya, berada di tengah area persawahan. Oleh
Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga dan
Kebudayaan (Parporabud) Nganjuk dicatat sebagai lingga
dan yoni paling besar dalam sejarah penemuan benda
cagar budaya di Nganjuk
Lingga berukuran panjang sekitar 1,10 m dengan
garis tengah lingga 40 cm. Yoni berukuran 1,10 m x 1,10
m, luas lubang tengah 40 cm x 50 cm dan penjang jerat
depan 40 cm.
Kondisi antara lingga dan yoni masih menancap
pada posisi aslinya. Tapi hampir seluruh tubuh lingga
tertatam dalam tanah.
Diperkirakan, benda bersejarah ini peninggalan era
Mataram Kuno, ditempatkan di area persawahan sebagai
simbol kesuburan Dewi Sri.
c. Prasasti Hring
Prasasti Hering ditemukan di Desa Kujonmanis,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
Pertamakali ditemukan, Desa Kujonmanis masih masuk
distrik Berbek, Residen Kediri tahun 1889 (Not. p. 64
disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor
inventaris D. 67). Abklats disimpan Dinas Purbakala
dengan nomor: 387 dan 421. Brandes mengatakan
prasasti ini berasal dari raja Pu Sindok tahun 859 Saka
atau 937 Masehi. Tapi oleh Damais dibetulkan bahwa
52
angka tahun yang benar adalah 856 saka atau 934
Masehi.
Prasasti berbentuk segi empat dengan sisi bagian
atas dibentuk alokade (kurawal). Pada bagian tepi-tepinya
banyak bagian yang rusak sehingga menghilangkan
beberapa aksara. Pada sisi muka bagian bawah terdapat
12 lubang segi empat, yang tidak diketahui fungsinya.
Tinggi 145 cm, lebar 79 cm, tebal atas 27 cm, tebal
bawah 33 cm.
Prasasti ditulis pada keempat sisinya dalam aksara
dan bahasa Jawa Kuno dengan tipe tegak dan persegi (ciri
aksara abad ke-X Masehi). Ukuran aksara tidak merata
di beberapa tempat antara 10-15mm. Aksara-aksara yang
tertulis di sisi muka terlihat besar-besar dan jarak
antarbaris (spasi) cukup lebar, tetapi makin ke bawah
ukuran aksara makin kecil dan jarak antar baris terlihat
rapat. Sementara ukuran aksara makin kecil dan jarak
antarbaris terlihat sama besar, sekitar 10 mm. Sisi muka
ditulisi 36 baris tulisan, pada beberapa bagian, terutama
bagian tepi dan bawah ada yang rusak dan aus sehingga
sulit dibaca (baris ke-36). Sisi belakang ditulisi 35 baris
tulisan, mulai baris pertama hingga baris ke-8 tulisan
sudah aus dan sulit dibaca. Sisi kiri 45 baris tulisan dan
beberapa aksara ada yang aus/rusak. Sisi kanan tertulis 47
baris, dan tulisan pada baris terakhir sulit dibaca.
Akibatnya ada beberapa baris tulisan yang harus ada
dalam prosedur penulisan prasasti tentang penetapan
sima, tidak ditemukan dalam empat sisi Prasasti Hering.
Misalnya, penulisan isi prasasti tentang sukhadukha
beserta dandakudanda-nya, upacara manusuk sima, pesta
makan, minum dan hiburan, serta nama citralekha tidak
disebut dalam isi prasasti. Melihat ketidakakuratan
penulisan isi prasasti, mungkinkah Prasasti Hering yang
ditemukan di Desa Kujonmanis, Kecamatan
Tanjunganom yang sekarang disimpan di Museum
53
Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D. 67) adalah
prasasti tinulad? Lantas, prasasti yang asli di mana? Perlu
kajian lebih lanjut.
Prasasti Hering dikeluarkan pada tanggal 7
paroterang, bulan Jesta tahun 856 Saka, atau dalam
tarikh Masehi beretepatan tangga 22 Mei 934 Masehi.
Isi prasasti menceritakan Raja Sindok
memerintahkan kedua pejabat bawahannya
(mahamantri), Rake Hino Pu Sahasra dan Rake Wka Pu
Baliswara, diteruskan kepada salah satu pejabat tinggi
kerajaan bernama Kanuruhan Pu Da untuk diterima oleh
Samgat Marganung Pu Danghil dan istrinya Dyah Pendel
yang telah membeli sebidang tanah beserta rumahnya
untuk dibangun sebuah wihara. Kemudian sebidang
tanah beserta rumahnya tersebut dimintakan kepada Raja
Sindok agar ditetapkan sebagai sima, bebas dari
kewajiban membayar pajak. Kemudian Raja Sindok
mengabulkan permohonan Samgat Marganung Pu
Danghil dan istrinya Dyah Pendel kemudian
menetapkan sebidang sawah kakatikan di Desa Hering
yang masuk wilayah Watek Marganung, tetapi di bawah
kekuasaan Wahuta Hujung, dan tanah perumahan
menjadi sima. Yaitu tanah sawah dengan luas 6 tampah
dan 1 suku dan tanah beserta rumahnya seluas 1 tampah
dan 1 suku yang dibeli oleh Samgat Marganung Pu
Danghil dari beberapa warga Desa Hering seharga 5 kati
9 suwarna emas. Disamping itu, istri Samgat Marganung
Pu Danghil bernama Dyah Pendel juga ikut berderma
(berbuat amal) dengan membeli tanah biara seharga 16
suwarna emas.
Prasasti Hring ditemukan in-situ, di antara
reruntuhan bekas bangunan wihara pada tahun 1889, di
Desa Kujonmanis. Sekarang menjadi kompleks
pemakaman umum. Di tengah kompleks makam ini ada
bekas bangunan suci agama Budha, disebut wihara. Jejak
54
bangunan wihara masih terlihat dengan jelas. Berupa
profile-profile batu andesit berukuran besar dan batu-
batu isian bangunan wihara.
Kondisinya, tersebar kemana-mana, dalam area
kompleks makam. Sebagian dijadikan bancik, sebagian
lain dimanfaatkan warga sebagai batu nisan. Namun tak
sedikit pula yang berserakan kema-mana hingga ke
rumah-rumah warga.
Bahkan, batu wihara sejenis dengan bekas
bangunan suci agama Budha ditemukan di tengah
perkampungan warga Desa Sidoharjo, Kecamatan
Tanjunganom. Berjarak sekitar 1 kilometer arah barat
situs makam Kujonmanis.
Eko Jarwanto (2021) dalam bukunya, “Nganjuk
dalam Lintasan Sejarah Nusantara,” menyebut sebagian
peneliti berpendapat bahwa nama Hring dapat
disamakan dengan Keringan, sedangkan kata Marganung
disamakan pula dengan nama Ganung. Mengenai hal ini,
tentunya daerah Hring justru lebih cocok jika
ditempatkan pada daerah asal temuan prasasti, yaitu
Warujayeng (Jayeng), sedangkan kata Marganung lebih
cocok ditempatkan pada kata Tanjunganom. Hal ini
karena posisi prasasti bersifat in-situ ketika pertama kali
ditemukan pada tahun 1869.
Sedangkan daerah Keringan dan Ganung yang
diidentifikasikan dengan kata Hring dan Marganung
posisinya justru sangat jauh dari temuan asal prasasti,
yaitu kurang lebih dari 20 kilometer ke arah barat dari
posisi asal temuan prasasti, sehingga sulit untuk
dihubungkan keterkaitannya meskipun terdapat sedikit
kemiripan nama.
Dalam hal ini, nama Marganung (Marganong)
merupakan kosakata Jawa Kuno (dari serapan
Sansekerta), yaitu Marga-anong. Marga bermakna
tanah/jalan/lahan/bumi, sedangkan Anong (anom)
55
bermakna muda/baru. Jadi Marganung bermakna
tanah baru/lahan baru. Makna ini ternyata sesuai
dengan kata Tanjunganom dalam bahasa Jawa. Tanjung
bermakna tanah/daratan dan Anom bermakna
baru/muda. Di sisi lain, kata Hring bisa jadi bergeser
menjadi Haring/Haying/Hayeng. Kata ini lebih dekat
dengan Jayeng, dimana ada Waru Jayeng. Kata
Jayeng bermakna Kemenangan.
d. Struktur Bata di Klurahan
Sugeng Riyanto, peneliti arkeologi klasik, Balai
Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta saat melakukan
peninjauan objek yang diduga sebagai cagar budaya di
kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur, 27 - 30 Oktober 2020, menyampaikan
adanya sisa struktur bata berbentuk seperti batur
ditemukan di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot,
Kabupaten Nganjuk, di sekitar titik koordinat 7o 38’ 34,5”
LS dan 1120 3’ 14,3” BT.
Peninggalan tersebut ditemukan ketika dilakukan
pengerukan sungai oleh pemerintah desa setempat
beberapa bulan sebelum peninjauan objek, untuk
normalisasi sungai. Struktur bata sisi utara dan barat
langsung bersentuhan dengan aliran sungai. Panjang sisi
utara dari sudut barat laut ke sudut timur laut struktur
497 cm, sedangkan panjang sisi barat yang terlihat 297
cm. Tinggi struktur bata sisi barat yang muncul di atas
permukaan air 71 cm, sedangkan yang sisi timur 57 cm.
Ketebalan struktur bata belum dapat diketahui tetapi
terlihat bahwa bahan isian di bagian dalamnya adalah
tanah. Salah satu contoh bata berukuran panjang 33 cm,
lebar 21 cm, dan tebal 7 cm. Pada permukaannya
terdapat tiga garis cekungan memanjang yang mungkin
sekali dibuat dengan menekan dan menggerakkan secara
mendatar tiga jari ketika bata masih lunak.
56
Hal menarik bahwa orientasi sisi-sisi empat lapis
bata bagian atas tidak sejajar dengan orientasi sisi-sisi
struktur bata di bawahnya. Sumbu utara-selatan empat
lapis bata di atas 345o U, sedangkan sumbu utara-selatan
struktu bata di bawahnya 355o U. Menurut informasi, di
sekitar tinggalan struktur bata pernah ditemukan pecahan
gerabah dan uang logam.
Diperkirakan, temuan yang semula diduga sebuah
jagang baluwarti ini memiliki hubungan dengan temuan
bangunan talud di Dusun Sumbergayu, Desa Klurahan,
berjarak sekitar 1 kilometer arah timur. Diduga,
bangunan talud Sumbergayu sejaman dengan era pra-
Majapahit.
Situs Jagang Baluwerti Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot
e. Struktur Bata di Situs Sumbergayu
Struktur bata ditemukan juga di Dusun
Sumbergayu, Desa Klurahan, di sekitar titik koordinat 7o
39’ 6,2” LS dan 1120 4’ 15,2” BT. Struktur tersebut
ditemukan oleh BPCB Jawa Timur melalui ekskavasi
pada tahun 2018.
Struktur bata mulai terlihat pada kedalaman sekitar
200 cm. Struktur bata yang ditemukan adalah sudut
57
baratdaya dengan sebagian kecil sisi selatan struktur dan
sisi barat struktur sepanjang 26,70 m yang terlihat masih
berlanjut ke arah utara.
Sementara itu tinggi struktur bata dari permukaan
tanah 126 cm, dan tebal 67 cm. Salah satu contoh bata
berukuran panjang 40,1 cm, lebar 24 cm, dan tebal 8 cm,
sedangkan bata contoh lainnya berukuran panjang 42 cm,
lebar 23 cm, dan tebal 9 cm.
Di ladang penduduk yang terletak di utara struktur
banyak ditemukan pecahan gerabah. Menurut informasi,
sekitar 300 m di utara struktur bata pernah ditemukan
satu buah lingga dan yoni dari batu yang sekarang
disimpan oleh penduduk. Sementara itu, sekitar 200
meter dari struktur ke timur pernah ditemukan kolam
yang dibangun dari bata berukuran sekitar 70 m x 40 m,
tetapi kemudian dibongkar oleh penduduk untuk
keperluan lahan persawahan. Di kolam tersebut pernah
juga ditemukan satu buah jaladwara terakota, tetapi tidak
diketahui lagi keberadaannya. Kolam tersebut sekarang
termasuk Dusun Tamansari, Desa Dadapan, Kecamatan
Ngronggot.
Wicaksono Dwi Nugroho, SS, Ketua Tim Eskavasi
Penyelamatan Situs BPCB Jawa Timur di Nganjuk
menyampaikan, kegiatan Ekskavasi penyelamatan
temuan yang dimulai, Kamis, 20 Nopember 2019 hingga
22 Nopember 2019 lalu. Dia menyebut, struktur bata
yang berhasil diekskavasi adalah bekas bangunan talud,
yaitu semacam bangunan tembok untuk menyangga
bangunan utama di dekatnya.
Melihat ukuran dimenasi bata penyusun, seorang
arkeolog BPCB Jawa Timur itu memperkirakan struktur
bata di lokasi ini berasal dari masa pra-Majapahit sekitar
abad 10-11 Masehi, karena ukuran bata penyusun
struktur lebih besar dari bata penyusun dari masa
majapahit yang biasanya berukuran panjang 33 cm, lebar
58
22 cm, dan ketebalan 5-6 cm. Namun demikian, masih
diperlukan temuan dari data artefak lain untuk
memastikan hal tersebut.
Situs Sumbergayu di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot
f. Situs Rejoagung
Struktur bata ditemukan di Dusun Rejoagung, Desa
Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, di sekitar titik
koordinat 7o 40’ 1,6” LS dan 1120 3’ 33,5” BT. Struktur
bata berada di tengah ladang jagung dan rumput gajah
milik penduduk. Struktur bata yang terlihat berukuran
panjang 400 cm dan lebar 200 cm. Di tengahnya digali
oleh penduduk sehingga terbentuk lubang segi empat
membujur arah utara-selatan berukuran panjang 375 cm,
lebar 105 cm, dan kedalaman 300 cm. Pada kedalaman
tersebut struktur bata masih ada.
Sugeng Riyanto, Balai Arkeologi Provinsi D.I.
Yogyakarta saat mengadakan penelitian di sisa bangunan
dengan batu bata menyerupai ukuran batu bata di
bangunan talud Sumbergayu, diperkirakan memiliki
masa yang sama di antara keduanya. Melihat kondisi sisa
struktur bangunan yang sangat besar, dulunya merupakan
tembok utama suatu kompleks sangat besar pula.
59
dimungkinkan, di dalamnya ada pemerintahan dengan
bangunan-bangunan kecil di dalamnya, seperti talud di
Sumbergayu.
Di sekitar lokasi bangunan, tidak ditemukan
artefaks pendukung, seperti pecahan gerabah, koin
China, atau pecahan keramik. Sehingga sulit untuk
mendapatkan data yang akurat untuk menyebutkan
kronologis periode masanya.
Hanya, peneliti arkeologi klasik Balai Arkeologi
Provinsi D.I. Yogyakarta memprediksi, bila di antara
bangunan tembok besar ini memiliki hubungan yang kuat
dengan talud Sumbergayu, dimungkinkan memiliki masa
yang sama. Yaitu, sekitar masa peralihan kotaraja
Mataram Medang dari Jawa Tengah era Pu Sindok Ke
Jawa Timur, bahkan bisa berlanjut ke masa-masa
berikutnya, seperti Darmawangsa Teguh, Airlangga,
hingga Kadiri. Bila semua data menguatkan, di daerah
Ngronggot dulunya ada sebuah keraton, bagian dari
kerajaan Pu Sindok, atau setelahnya, bagian dari
pemerintahan saat itu.
g. Situs Mindi
Di situs ini ditemukan struktur bata dan artefak dari
bahan batu, tembikar, dan keramik. Situs Mindi masuk
ke dalam wilayah Dusun Mindi, Desa Kelutan,
Kecamatan Ngronggot, di sekitar 7o 41’ 12” LS dan 1120
4’ 21” BT. Struktur bata tersebut berada di tengah
perkebunan tebu. Ditemukan dalam keadaan tidak utuh
karena situs digali oleh penduduk untuk diambil tanah
pasirnya. Bagian sudut struktur bata ditemukan dengan
sisi utara-selatan berukuran 20 m dan sisi timur-barat 22
m. Selain itu ditemukan pula pecahan gerabah, keramik
asing, umpak batu, dan pipisan batu. Penduduk
mengenal lokasi penemuan struktur bata tersebut dengan
60
nama tanah “͞ banjardowo”. Nama tersebut belum
diketahui artinnya.
Beberapa arkeolog dari Balai Arkeologi Provinsi
D.I Yogyakarta saat mengadakan survey di lokasi yang
berdekatan dengan bantaran sungai Brantas itu melihat
struktur bangunan berbahan dari batu bata merah.
Ukuran batu batanya sangat besar, tebal dan panjang.
Struktur membentuk bekas tembok sangat panjang,
namun kondisinya terpotong-potong, tapi sebenarnya
satu dengan yang lain saling berhubungan.
Dari bagian yang tersingkap, tampak dari utara ke
selatan sepanjang 20 meter dan timur - barat 25 meter
serta membentuk satu kesatuan. Ini menunjukkan,
dulunya adalah suatu komplek yang luas, digunakan
sebagai permukiman sangat padat penduduk. buktinya,
seluruh kegiatan permukiman ditemukan di lokasi yang
saat ini ditumbuhi tanaman tebu itu.
Selain itu, seluruh sisa-sisa aktifitas permukiman
ditemukan di situs ini. seperti sumur dari bata yang
melengkung, apabila disusun akan membentuk
lingkaran.
Tim dari Dinas Balar Yogyakarta juga menemukan
benda kuno berupa pipisan, lumpang batu, perkakas
untuk aktifitas sehari-hari terbuat dari bahan tembikar
dan keramik. jumlahnya sangat banyak. untuk perkakas
dari keramik diperkirakan sejaman dinasti song dan
yuan, sekitar abad X, XI dan XIV.
Menurut Sugeng Rianto, berdasarkan beberapa
lokasi yang pernah diteliti, menunjukkan karakter situs
hampir sama, ada yang tebal dan ada yang panjang. Ada
tembok utama dan ada tembok pembagi. Ini
membuktikan bahwa di dalam tembok utama tersebut
ada kehidupan pada waktu itu.
Bila dikaitkan dengan peta sebaran yang akan
dianalisis nantinya, antara situs di Rejoagung, Desa
61
Banjarsari dan Sumbergayu, Desa Klurahan, bila
dianalogikan dengan situs Tondowongso, merupakan
bagian pemerintahan saat itu. Yaitu antara era Sindok,
pasca Sindok, Darmawangsa Teguh, Airlangga hingga era
Kadiri. Kendati demikian, tentu sebelum era Sindok
maupun pasca Sindok, sudah ada peradaban yang
mendahului.
Situs Mindi, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot berupa peradaban
kuno era Mataram Medang
F. PERPINDAHAN KERAJAAN MATARAN MEDANG KE
JAWA TIMUR
Ada beberapa pendapat ahli yang menguatkan sebab-
sebab perpindahan istana kotaraja Mataram Medang ke Jawa
Timur. Novo Indarto (2021) dalam Sejarah Kerajaan Medang
menyebut sebab-sebab perpindahan kotaraja Mataram Medang
ke Jawa Timur, diantaranya :
1. Karena sering terjadi bencana, terutama Gunung Merapi
2. Karena serangan Sriwijaya
3. Wabah epidemi
4. Politik dan perebutan kekuasaan
5. Motif keagamaan
6. Motif ekonomi
62
Van Benmmelen menyampaikan teori yang didukung oleh
Prof. Boechori, bahwa perpindahan pusat kerajaan disebabkan
letusan gunung Merapi yang hebat. Bukti letusan tersebut dapat
dilihat dari banyknya candi yang terkubur material vulkanik,
seperti Candi Sambisari, Candi Morangan, Candi Kedulan,
Candi Kadisona, dan Candi Kimpulan.
(Nugrohonotosusanto, dkk, 2009), kerajaan Mataram di
Jawa Tengah mengalami kehancuran karena letusan Gunung
Merapi yang maha dahsyat, sehingga dalam anggapan para
pujangga, hal itu dianggap sebagai pralaya (kehancuran dunia
pada akhir masa Kaliyuga). Sesuai landasan kosmologi,
kerajaan-kerajaan kuno harus dibangun kerajaan baru dengan
wangsa baru pula.
Oleh karena itu, Pu Sindok, yang membangun kembali
kerajaan di Jawa Timur, dianggap sebagai cikal bakal wangsa
baru, yaitu wangsa Isana.
B. Schrieke menyampaikan teori tentang politik yang
secara tidak sengaja dilakukan oleh rakyat Medang. Kerajaan
Medang di era tengah banyak mendirikan proyek mercusuar
berupa candi-candi megah. Dalam mendirikan candi
dibutuhkan waktu yang panjang, dan tenaga kerja yang massive.
Rakyat yang dikerahkan untuk membangun candi tidak bisa
mengolah lahan pertanian dan melakukan aktivitas ekonomi
lainnya. Akibatnya banyak rakyat yang melakukan migrasi
massive ke Jawa bagian timur.
Motif ekonomi menjadi salah satu kemungkinan alasan
banyak diperkirakan para pakar. Pesisir timur laut dan wilayah
delta sungai Brantas sangat menarik untuk mendapatkan
keuntungan secara ekonomi sehingga pusat kerajaan dipindah
mendekati lokasi tersebut (Munoz, Paul Michel, 2009,
Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan
Semenanjung Malaysia).
Pendapat berikutnya, meskipun di Jawa Tengah, dinasti
Syailendra telah berakhir, namun di Sumatera masih ada dinasti
Syailendra. Perpindahan kerajaan Mataram Medang ke arah
63
timur dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menjauhi dinasti
Syailendra yang berkuasa di Sumatera (Darmosoetopo, 2003).
Peristiwa itu dikaitkan dengan kata malaga (prasasti
Anjukladang, 937 Masehi) yang berarti usaha dari dinasti
Syailendra menyerang Pu Sindok. Peristiwa perang terjadi di
Nganjuk, Pu Sindok dibantu penduduk setempat hingga
mencapai kemenangan.
Beberapa ahli berpendapat di Jawa Timur sudah berdiri
kerajaan kecil di bawah kekuasaan Mataram Medang di Jawa
Tengah, yaitu Kanuruhan di daerah Malang (Prsasti Dinoyo,
746 Masehi) dan peradaban lain di sejumlah daerah. Bukti
sejarah peradaban dibuktikan adanya sejumlah prasasti abad ke
VIII dan X era sebelum Pu Sindok dinobatkan Raja Mataram
Medang di Jawa Tmur tahun 929 Masehi. Diantaranya, prasasti
Bangle (I) tahun 908 Masehi, prasasti Kinawe 927 Masehi,
prasasti Kampak 928 Masehi dan sebagainya. Dapat
disimpulkan bahwa wilayah Jawa Timur secara kewilayahan
masih dalam satu kekuasaan Mataram Medang di Jawa Tengah.
Pu Sindok memilih Desa Tawmlang (wilayah Jombang),
karena letaknya strategis sebagai pusat pemerintahan. Di
samping letaknya dekat aliran sungai Brantas yang dikenal
sebagai sarana transportasi perniagaan yang ramai tingkat dunia
juga letak geografisnya jauh dari Gunung Merapi yang sering
meletus.
Seperti halnya di Nganjuk, sistem pemerintahan sudah
terbentuk sejak era Mataram Medang abad IX dan berlanjut ke
periode-periode berikutnya.
Kisah perjalanan Pu Sindok sebelum menjabat sebagai raja
Medang i Bhumi Mataram di Tamwlang, Jawa Timur 929
Masehi (Prasasti Turyyan), dimulai masa pemerintahan Dyah
Wawa menjabat sebagai Raja Mataram di Jawa Tengah (927 –
928 Masehi), bergelar Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa
Sri Wijayalokanamottungga. Dyah Wawa adalah raja terakhir
Kerajaan Medang periode Jawa Tengah.
64
Dyah Wawa naik tahta menggantikan Dyah Tulodhong.
Nama Rakai Sumba Dyah Wawa tercatat dalam prasasti
Culanggi tanggal 7 Maret 927 Masehi, menjabat sebagai Sang
Pamgat Momahumah, yaitu semacam pegawai pengadilan.
Selain bergelar Rakai Sumba, Dyah Wawa juga bergelar Rakai
Pangkaja.
Dalam prasasti Wulakan tanggal 14 Februari 928 Masehi,
Dyah Wawa mengaku sebagai anak Kryan Landheyan sang
Lumah ri Alas (putra Kryan Landheyan yang dimakamkan di
hutan). Nama ayahnya ini mirip dengan Rakryan Landhayan,
yaitu ipar Raka i Kayuwangi yang melakukan penculikan dalam
peristiwa Wuatan Tija.
Saudara perempuan Rakryan Landhayan yang menjadi
istri Rakai Kayuwangi bernama Rakryan Manak, yang
melahirkan Dyah Bhumijaya. Ibu dan anak itu suatu hari
diculik Rakryan Landhayan, namun keduanya berhasil
meloloskan diri di Desa Tangar. Rakryan Manak memilih
bunuh diri di Desa Taas, sedangkan Dyah Bhumijaya
ditemukan para pemuka Desa Wuatan Tija dan diantarkan
pulang ke hadapan Rakai Kayuwangi.
Makam Rakryan Landhayan sang pelaku penculikan
diberitakan terdapat di tengah hutan. Mungkin ia akhirnya
tertangkap oleh tentara Medang dan dibunuh di dalam hutan.
Peristiwa tersebut terjadi tahun 880 Masehi. Mungkin saat itu
Dyah Wawa masih kecil. Jadi, Dyah Wawa merupakan sepupu
dari Dyah Bhumijaya - putra Rakai Kayuwangi (Raja Medang
856–890-an Masehi).
Dengan demikian, Dyah Wawa tidak memiliki hak atas
tahta Dyah Tulodhong. Sejarawan Boechari berpendapat bahwa
Dyah Wawa melakukan kudeta untuk merebut tahta Kerajaan
Medang.
Kemungkinan besar, kudeta yang dilakukan oleh Dyah
Wawa mendapat bantuan dari Pu Sindok, yang naik pangkat
menjadi Rakryan Mapatih Hino. Sebelumnya, yaitu pada masa
pemerintahan Dyah Tulodhong, Pu Sindok menjabat sebagai
65
Rakryan Halu, sedangkan Rakai Hino dijabat oleh Pu
Ketuwijaya.
Berdasarkan keterangan status jabatan Sri Maharaja Rakai
Sumba Dyah Wawa Sri Wijayalokanamottungga sebagai raja
Mataram tidak menunjukkan bahwa Rakryan Halu Pu Sindok
naik jabatannya lantas menjadi Rakryan Mapatih Hino. Karena,
antara kedua tokoh tersebut memang tidak berangkat dari garis
keturunan yang sama. Artinya, Rakai Sumba Dyah Wawa
menjadi raja secara tidak sah, melalui kudeta terhadap
pemerintahan Dyah Tulodhong.
Sehingga jabatan dalam istana kerajaan, seperti Rakai Hino
(putra mahkota), Rakai Halu, Rakai Sirikan, Rakai Wka
(pangeran atau adik putra mahkota), dan lain-lain tidak serta
merta ditentukan oleh status jabatan segaris lurus dari seorang
raja.
Status jabatan Rakai Hino (putra mahkota) dalam istana
tidak segaris juga ditemukan pada masa pemerintahan Rakai
Watukara Dyah Balitung. Dyah Balitung memerintah selama 12
tahun (898-910 Masehi) sebagai Raja Mataram, sering
mengalami intrik politik dan gangguan keamanan kerajaan. Saat
itu, Daksa atau Sri Daksattama Bahubajra Pratipaksaksaya, yang
menjabat sebagai Rakryan Mahamantri i Hino (putra mahkota)
ternyata bukan anak Rakai Watukara Dyah Balitung, melainkan
adik iparnya.
Daksa adalah trah Wangsa Sanjaya yang berhak atas tahta
Kerajaan Mataram, sehingga ia tetap berusaha agar dapat
menduduki di atas tahta singgasana kerajaan Mataram sebagai
pewaris yang lebih berhak. (Nugrohonotosusanto, 2009:175).
Sedangkan istilah wangsa Isana dijumpai dalam prasasti
Pucangan, di bagian yang berbahasa Sansekerta. Prasasti ini
dikeluarkan oleh raja Airlangga pada tahun 963 Saka (1041
Masehi). Bagian yang berbahasa Sansekerta itu dimulai dengan
penghormatan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang disusul
dengan penghormatan kepada raja Airlangga. Selanjutnya
dimuat silsilah raja Airlangga, mulai dari raja Sri Isanatungga
66
atau Pu Sindok. Sri Isanatungga mempunyai anak perempuan,
bernama Sri Isanatunggawijaya, yang menikah dengan Sri
Lokapala, dan mempunyai anak bernama Sri
Makutawangsawardhana, yang dalam bait ke-9 sengaja disebut
keturunan wangsa Isana.
Seperti yang dapat dilihat dari silsilah tersebut maka
pendiri wangsa Isana adalah Pu Sindok Sri Isnawikrama
Dharmotunggadewa. Mengingat kedudukannya dalam masa
pemerintahan Rakai Layang Dyah Tulodhong dan Rakai
Sumba Dyah Wawa, yaitu berturut-turut sebagai rakryan
mapatih i halu dan rakryan mapatih i hino, yang biasanya hanya
dapat dijabat oleh kaum kerabat raja yang dekat, tentulah ia
masih anggota wangsa Syailendra. Namun, karena kerajaan
Mataram di Jawa Tengah mengalami kehancuran karena
letusan Gunung Merapi yang maha dahsyat, sehingga dalam
anggapan para pujangga, hal itu dianggap sebagai pralaya
(kehancuran dunia pada akhir masa Kaliyuga), sesuai dengan
landasan kosmologi, kerajaan-kerajaan kuno harus dibangun
kerajaan baru dengan wangsa baru pula. Oleh karena itu, Pu
Sindok, yang membangun kembali kerajaan di Jawa Timur,
dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu wangsa Isana.
Meskipun di Jawa Tengah, dinasti Syailendra telah
berakhir, namun di Sumatera masih ada dinasti Syailendra.
Perpindahan kerajaan Mataram Medang ke arah timur
dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menjauhi dinasti
Syailendra yang berkuasa di Sumatera (Darmosoentopo, 2003).
Peristiwa itu dikaitkan dengan kata malaga (prasasti Candi
Lor, 937 Masehi) yang berarti yaitu usaha dari dinasti Syailendra
menyerang kerajaan Sindok.
Tetapi, de Casparis dalam Darmosoentopo, 2003, dalam
pidato pengukuhannya menjadi Guru Besar mengatakan bahwa
kehancuran (pralaya) kerajaan Darmawangsa Tguh pada 1016
Masehi karena diserang oleh haji Wurawari, negara vatsal dari
dinasti Syailendra. Dalam prasasti Candilor, tidak ada kata yang
dapat diartikan perang. Isi prasasti Candi Lor ialah penetapan
67
sawah kakatikan menjadi sima untuk Bhatara di bangunnan
keagamaan (prasada) tempat kebaktian milik pejabat Samgat
yaitu pu Anjukladang. Demikian juga haji Wurawari tidak perlu
dikaitkan dengan vatsal dinasti Syailendra yang ada di Sumatera
sebab daerah Wurawari berada di Jawa Tengah.
G. STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN
MATARAM KUNO
Berikut penjelasan struktur pemerintahan jaman kerajaan
Mataram kuno, sebagaimana disebutkan dalam Nugroho
Notosusanto, dkk., 2009. Sejarah Nasional Jilid II, bahwa raja
merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang.
Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar Ratu. Pada
zaman itu istilah Ratu belum identik dengan kaum perempuan.
Gelar ini setara dengan Datu yang berarti "pemimpin".
Keduanya merupakan gelar asli Indonesia.
Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Syailendra
berkuasa, gelar Ratu dihapus dan diganti dengan gelar Sri
Maharaja. Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan
Sriwijaya dimana raja-rajanya semula bergelar Dapunta Hyang,
dan setelah dikuasai Wangsa Syailendra juga berubah
menjadi Sri Maharaja.
Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan Medang tetap
dilestarikan oleh Rakai Pikatan meskipun Wangsa
Sanjaya berkuasa kembali. Hal ini dapat dilihat dalam daftar
raja-raja versi Prasasti Mantyasih yang menyebutkan hanya
Sanjaya yang bergelar Sang Ratu.
Jabatan tertinggi sesudah raja ialah Rakryan Mahamantri i
Hino atau kadang ditulis Rakryan Mapatih Hino. Jabatan ini
dipegang oleh putra atau saudara raja yang memiliki peluang
untuk naik takhta selanjutnya. Misalnya, Pu
Sindok merupakan Mapatih Hino pada masa
pemerintahan Dyah Wawa.
Jabatan Rakryan Mapatih Hino pada zaman ini berbeda
dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit. Patih zaman
68
Majapahit setara dengan perdana menteri namun tidak berhak
untuk naik tahta.
Jabatan sesudah Mahamantri i Hino secara berturut-turut
adalah Mahamantri i Halu dan Mahamantri i Sirikan. Pada
zaman Majapahit jabatan-jabatan ini masih ada namun hanya
sekadar gelar kehormatan saja. Pada zaman Wangsa
Isana berkuasa masih ditambah lagi dengan jabatan Mahamantri
Wka dan Mahamantri Bawang.
Jabatan tertinggi di Medang selanjutnya ialah Rakryan
Kanuruhan sebagai pelaksana perintah raja. Mungkin semacam
perdana menteri pada zaman sekarang atau setara
dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit.
Jabatan Rakryan Kanuruhan pada zaman Majapahit memang
masih ada, namun kiranya setara dengan menteri dalam negeri
pada zaman sekarang.
Kasta brahmana, kasta tertinggi dapat menduduki jabatan
dalam struktur birokrasi tingkat pusat atau tingkat watek, dapat
juga di tingkat desa (wanua), tetapi dapat juga tidak mempunyai
suatu jabatan.
Ada juga seorang kesatrya yang dapat menduduki jabatan
keagamaan di tingkat pusat, seperti sang pamgat tiruan, dan juga
dapat menjadi pertapa dan tinggal di suatu biara.
Di dalam istana, berdiam raja dan keluarganya, yaitu
permaisuri, selir-selir, dan anak-anaknya yang belum dewasa,
dan para hamba istana (hulun haji, watek i jero).
Di luar istana, masih dalam lingkungan dinding kota,
terdapat kediaman putra mahkota (rake hino), dan tiga orang
adiknya (rakai halu, rakai sirikan, dan rakai wka), dan kediaman
para pejabat tinggi kerajaan.
Para pejabat tinggi kerajaan terdiri, pejabat keagamaan dan
kehakiman, yaitu mereka yang bergelar sang pamgat (samgat)
dan pejabat sipil yang bergelar rakai.
Sedangkan pada masa Mataram Kuno terdiri atas daerah
pusat kerajaan, yaitu ibu kota kerajaan dengan istana sri
69
maharaja dan tempat tinggal para putra raja dan kaum kerabat
dekat, para pejabat tinggi kerajaan dan para abdi dalem.
Selanjutnya adalah daerah watak, yaitu daerah yang
dikuasai oleh rakai dan para pamgat, disusul wanua yaitu desa-
desa yang diperintah oleh para pejabat desa (rama).
Di antara para rakai dan pamgat itu ada yang
berkedudukan sebagai pejabat tinggi kerajaan, dan ada yang
sebagai kepala daerah secara turun temurun. (Nugroho
Notosusanto, 2009:226).
Dalam lingkungan tembok kota (di luar istana) juga tinggal
pejabat sipil yang lebih rendah, yaitu mangilala drawya haji
(pejabat penarik pajak) jumlahnya sekitar 300 orang, bersama
keluarga mereka.
Di antara mangilala drawya haji sebagian besar adalah abdi
dalem keraton, diantaranya; pasukan pengawal istana
(mangalah, mamanah, mangandi), para pandai emas, pandai
perunggu, pandai tembaga, pandai besi, dan lain-lain.
Putra mahkota, para pangeran yang lain dan pejabat tinggi
kerajaan – kecuali pangkur, tawan dan tirip – mempunyai
daerah lungguh di luar ibu kota kerajaan, sebagaimana ternyata
dari adanya daerah-daerah yang disebut watak hino (daerah
lungguh putra mahkota), watak halu (daerah lungguh rakai
halu), watak sirikan, watak wka, watak dalinan,watak widhiati
dan watak makudur. Mereka tidak memiliki puri, karena
kedudukan mereka dapat diganti sewaktu-waktu oleh raja.
Di luar tembok istana, ada penguasa daerah yang bergelar
rakai, pamgat, haji, atau samya haji, yang tidak merupakan
pejabat tinggi kerajaan. Tetapi mereka memiliki puri di daerah,
karena kedudukan mereka sebagai penguasa daerah bersifat
turun-temurun. Di dalam puri tersebut, masing-masing
penguasa hidup sebagai raja kecil, termasuk di dalam puri
terdapat dayang-dayang, seniman (penari, pesinden), penabuh
gamelan, dal lain-lain, citralekha, pasukan pengawal, dan lain-
lain.
70
Dalam kerajaan kecil tersebut, mereka juga mempunyai
pejabat-pejabat yang mengurusi segala segi pemerintahan, baik
segi keagamaan maupun segi sipil, dalam wilayah kekuasaannya.
Ibu kota kerajaan kecil tersebut juga dikelilingi oleh tembok
sebagai pusat kebudayaan di daerah.
Di luar kota-kota kerajaan kecil tersebut terdapat desa-desa
(wanua), yang diatur oleh para pejabat desa (rama). Para
penduduk desa (anak wanua, anak thani) pada umumnya hidup
dari bertani, berdagang kecil-kecilan, dan mengusahakan atau
menjadi hamba (hulun, dasa/dasi).
Dalam suatu watek terdapat pejabat tinggi utama, yaitu, 2
patih, 1 juru kanayakan dan 1 wahuta.
Patih membawahi tunggu durung (penunggu lumbung
padi) dan parujar. Juru Kanayakan membawahi tuhan i
lampuran. Dan Wahuta membawahi tunggu durung, wahuta
winkas wkas, wahuta lampuran dengan pihujung-nya
(perwakilan).
Jabatan lain yang penting adalah citralekha, matandha, dan
parujar. Pemungut pajak, juru ning wadwa rarai, juru ning
kalula, juru ning mangrakat, dan juru ning mawuat haji
(pemimpin yang mengurusi orang-orang yang harus bekerja
bakti untuk kepentingan kerajaan atau kepentingan umum),
semua diurusi oleh tuhan ning kanayakan. Setoran pajak dan
upeti dalam bentuk yang lain diurusi oleh pejabat mangaseaken
atau amasangaken.
Penghasilan daerah watak dilakukan di bawah pengawasan
patih, dalam hal ini oleh pejabat parttaya atau pratyaya. Patih
juga memiliki parujar sendiri.
Namun, pengelolaan lumbung-lumbung padi diurusi oleh
ketiga pejabat utama (patih, kanayakan dan wahuta), karena
ketiganya memiliki tunggu durung.
71
H. PRASASTI CANDILOR 937 MASEHI (CIKAL-BAKAL
NAMA ANJUKLADANG)
1. Sima
Kata 'sima' berasal dari bahasa Sansekerta 'siman' yang
berarti batas, tapal batas (sawah, tanah, desa dan
sebagainya). Dalam hal ini, yang dimaksud ‘sima’ adalah
sebidang tanah yang dibatasi.
Dalam akun facebook Puguh Novi Arsito, sumber
narasi: Timbul Haryono, 1999, jurnal Humaniora No.12 .
September - Desember 1999. UGM, disebutkan bahwa,
“Sima adalah sebidang tanah sawah atau kebun yang telah
diubah statusnya menjadi wilayah perdikan atau swatantra
sehingga para petugas pemungut pajak tidak boleh
melakukan kegiatannya di wilayah tersebut.”
a. Jenis tanah yang diubah menjadi sima
Ada beberapa jenis tanah yang diubah menjadi
sawah, kemudian ditetapkan menjadi sima. (Riboet
Darmosoentopo : 2003), padang rumput di Jurungan
dari watak Pagarwesi setelah diubah menjadi sawah,
kemudian ditetapkan menjadi tanah sima untuk prasada
yang yang terletak di Gununghyang.
...lmah ning sukat i jurungan watek pagar wsi sima
ni kanang prasada i gunung hyang... lua nikang lmah an
sampun ginawai sawah tampah 6 ... (Jurungan 798 C).
Padang rumput di Jurungan dari watak Pagarwesi
dijadikan tanah sima bagi prasada yang terletak di
Gununghyang ... luas padang rumput yang telah
dijadikan sawah 6 tampah.
Kebun di Mamali dari watak Mamali setelah
dijadikan sawah, kemudian ditetapkan menjadi tanah
sawah sima untuk prasada Rakarayan i Sirikan yang
terletak di Gununghyang.
...tatkala ni kanag lmah ning kbuan kara man i
mamali watak mamali winli rakarayan i sirikan ri kanang
72
mas ka 1 sima ni kanang prasada nira i gunung hyang ...
(Mamali 800 C = 878 Masehi).
Ketika tanah kebun milik para rama di Mamali
dari watak Mamali dibeli oleh Rakarayan i Sirikan 1 ka
emas, dijadikan sima bagi prasada-nya yang terletak di
Gununghyang.
Tegal di Kwak dari watak Wka setelah dijadikan
sawah, kemudian ditetapkan menjadi sima untuk
prasada milik Raryan Wka pu Catura yang terkenal di
Kwak.
... tatkala ajna sri maharaja rake kayuwangi
tumurun i rakarayan i kangnap hino watu tibang bawang
sirikan umanugrahakna i kanang tgal i kwak watak wka...
gawayan sawah maparaba sima ni kanang prasada i kwak
dham rakarayan wka pu catura ... (Kwak I, 801 C = 879
Masehi).
Ketika perintah Sri Maharaja Rake Kayuwangi
kepada Rakarayan Kangnap hino, watu tibang, bawang,
sirikan menganugerahkan tegal di Kwak dari watak Wka
... dijadikan sawah (serta dijadikan) sima untuk prasada
di Kwak, bangunan keagamaan milik Rakarayan Wka
pu Catura.
Rakarayan Sirikan menetapkan sawah Taragal dan
padang rumput, keduanya terletak di Ruhutan dari
watak Trab menjadi tanah sima.
... tatkala rakarayan i sirikan sumusuk ikanang
sawah ing taragal..muang lmah ing sukat kapua lmah
ruhutan watak trab pomahana nikanang kumamit ikang
sawah muang waitanya pari ... (Taragal 802 C = 890
Masehi).
Ketika Rakarayan i Sirikan menetapkan sawah di
Taragal ... dan padang rumput semuanya tanah di
Ruhutan dari watak Trap hendaknya ditempati untuk
menjaga sawah dan padi.
73
Atas perintah Raja Kayuwangi, rakryan Halu pu
Catura mengubah hutan menjadi sawah dan ditetapkan
menjadi tanah sima untuk dharmma-nya yang terletak di
Pastika.
... kumonakan i kanang dharmma ing pastika
dharma rakarayan halu pu catura panusukna lmah alas
daya sawah simanya i kanang lmah i ramwi watak halu ...
(Ramwi, 804 C = 892 Masehi).
Ada juga tanah sima berupa padang rumput tanpa
diubah menjadi sawah. Padang rumput di Mulak watak
Wka ditetapkan menjadi tanah sima untuk prasada yang
terletak di Upit.
... manusuk manil lmah sukat ... muang sawah ... i
mulak watak wka sima ni prasada i y umpit . (Mulak I,
802 C, Mulak II, 800 C, Tunahan, 794 C).
Menetapkan sima padang rumput ... dan sawah di
Mulak dari watak Wka, bagi prasada yang terletak di
Upit.
Jadi ada beberapa jenis tanah yang diubah menjadi
sawah, kemudian ditetapkan menjadi sima, diantaranya;
padang rumput, kebun, tegal, sawah, hutan, dan padang
rumput tanpa diubah menjadi sawah. Untuk mengubah
status tanah tegalan, padang rumput, padang ilalang,
hutan, dan lain-lain untuk menjadi sawah, terlebih
dahulu harus mendapat ijin dari kerajaan. Hal demikian
dimaksud untuk menyeimbangkan lingkungan, karena
tegalan, padang rumput ataupun padang ilalang sangat
diperlukan pada waktu itu.
Profesor Doktor H. Aminudin Kasdi dalam FGD
DPRD Nganjuk 2020 tentang Penelusuran Sejarah Hari
Jadi Dewan Pertama Nganjuk menyebut, Kakatikan
servant (Modj. katik, stable boy, groo,, esp. a grass cutter
for horses (Wrh, sang hyang atma kaharan lembu
manirid kan ratha, bathara iswara kaharan sarathi,
kuumon ikan lembumangirid kang ratha tan angaya tan
74
lakwakena makon (r. pakon, ), ya ta matang yan
kapurihan ika ng katik, see un (Zoet. 822)
Kakatikan, sawah kakatikan - reserve for the katik,
see also under kadik-a piece of ground (measure, page.
763 ) or = katik. OJO 26 (907) 14 : ma sawah a lamwit
6 katik ( OJO 47 (934) vo 38 : umulah-ulah ikang lmah
sawah sima kakatikan. See kakatikan under katik I and
cf. OJO 48 (943) ro 6 : lemah kanayakan tan kakatikan.
(Zoet. 764)
Katik - Jawa baru tertinggal pakatik = batur (tukang
nuntun jaran)(engg. Kn -enggon-enggonan kn, kromo-
ngoko). Lihat Boesastra Djawa (dengan berpedoman
Serat Bausastra Dawa-Belanda oleh DR. Th. Pigeaud,
dari Yogyakarta WJS Poerwadarminta, dibantu oleh CS.
Harjosudarmo & J.CHR. Pujasudira), JB. Wolters,
Groningen-Batavia, 1939, halaman 458.
Sawah kakatikan - umulah-ulah ikang lmah sawah
sima kakadikan - lamah kanayakan tan kakatikan -
ladang pemggembalaan - yang diolah tanah (lahan) yang
telah dibebaskan (sima) - tanah pejabat yang tidak boleh
dijadikan penggembalaan .
Dalam UUPA (landreform) tahun 1960 bahkan
sampai tahun 1975 tentang penggunaan tanah di Daerah
Tingkat I Jawa Timur masih terdapat tanah
penggembalaan dari : tanah pertanian rakyat, settlement,
perkebunan, hutan, kolam, waduk, telaga, rawa, tanah
rusak, tanah tandus, penggaraman, tambak, lain-lain dan
penggembalaan (Sumbar, Monografi Daerah Jawa
Timur I Buku I, hlm, 234.
Jadi sawah kakatikan adalah sebidang tanah atau
lahan milik pejabat yang telah dibebaskan untuk
menjadi sima, yang kemudian tidak lagi boleh dijadikan
area pengembalaan. Mungkin yang dimaksud adalah
binatang kuda (katik).
75
Sedangkan lemah sawah kakatikan iy-anjukladang
berarti sebidang tanah atau lahan milik pejabat di
Anjukladang yang setelah ditetapkan sebagai sima, tidak
lagi boleh dijadikan area penggembalaan kuda.
b. Jenis nama sima
Ada beberapa jenis penyebutan nama sima pada
era Mataram Medang. Darmosoentopo, 2003
menyebutkan, sebutan untuk tanah sima sebagai
berikut:
(1) Sima makudur, yaitu sĩma diberikan kepada
Makudur yang telah berjasa kepada raja.
Seorang makudur bila berjasa kepada raja,
mendapat anugerah berupa tanah sima. Tanah sima
ini selanjutnya disebut sima makudur.
(2) Sima kapatihan yaitu tanah Sĩma yang diberikan
oleh raja kepada patihnya secara bergantian setiap
tiga tahun sekali.
Contohnya, kelima patih dari Mantyasih
karena berjasa besar pada waktu pernikahan Raja
Balitung dan juga mereka berhasil mengamankan
jalannya pernikahan dari kerusuhan, selalu
mengadakan pemujaan kepada Bhatara di Malang
kuceswara, di Puteswara, di Kutusan, di
Cilabhedeswara, dan di Kuleswara setiap tahun,
maka mereka mendapat tanah sima dari Raja
Balitung. Tanah sima itu karena dimiliki para patih
disebut sima kapatihan.
(3) Sĩma kamulan yaitu tanah sĩma yang diberikan
kepada mereka yang memikul tugas mengamankan
desa dan jalan dari segala kerusuhan agar
menghilangkan ketakutan warga.
(4) Sima pinanduluran, yaitu sima yang diberikan
kepada patih secara bergantian.
76
Tanah sima yang diberikan oleh Raja Balitung
kepada kelima patih di Mantyasih, penguasaannya
secara bergantian setiap tiga tahun sekali, oleh
karena itu disebut sima pinanduluran.
(5) Sĩma kajurugusalyan yaitu sĩma yang dianugerahkan
kepada pande besi atau logam sebagai tempat
peribadatan. Keperluan dianugerahkan wilayah
tersebut menjadi Sĩma yaitu memelihara bangunan
ibadah.
Misalnya, juru gusali adalah pengelola atau
tukang, yang membidangi pandai besi, pandai emas,
pandai dang, pandai kawat, pandai tembaga, pandai
kuningan, dan pandai dadap. Pandai gusali
digunakan untuk satuan aktivitas pandai.
Dalam masyarakat Jawa Kuno, para juru gusali
tersebut memiliki bangunan peribadatan sendiri.
Tanah sima ini tidak dipungut pajak oleh para
mangilala drawyahaji karena telah didermakan untuk
bhatara yang ada di prasada. Tanah sima ini
selanjutnya disebut sima kanjurugusalyan.
(6) Sĩma punpunan yaitu tanah sĩma yang diberikan
untuk menunjang bangunan keagamaan.
Pu Sindok, Raja Mataram Medang di Jawa
Timur menetapkan lemah sawah kakatikan iy-
Anjukladang dengan luas 6 lamwit sebagai sima
punpunan.
marpanakna / i / bhatara / i / sang hyang prasada
kabhaktyan / i / dharma / samgat / pu anjukladang /
…….. dipersembahkan / kepada / bhatara / di / sang
hyang prasada kabhaktian / untuk / dharmma /
pejabat samgat /bernama pu anjukladang /
……. sri maharaja / i / sri jayamrta / …. / sima /
punpunana / bhatara
……. sri maharaja / kepada / sri jayamrta /
….(sebagai) / sima / (tempat) pemujaan / bhatara /
77
c. Status tanah kakatikan iy-anjukladang sebelum
ditetapkan menjadi sima
Sawah kakatikan, “umulah-ulah ikang lmah sawah
sima kakatikan - lemah kanayakan tan kakatikan”
(ladang pemggembalaan - yang diolah tanah (lahan) yang
telah dibebaskan (sima) - tanah pejabat yang tidak boleh
dijadikan penggembalaan).
Maksudnya, ladang penggembalaan yang telah
diolah menjadi tanah sawah, milik pejabat, setelah
ditetapkan sebagai sima, tidak boleh lagi dijadikan
ladang penggembalaan.
...sanya / ajna / sri maharaja pu sindok / sri
isanawikrama dharmmotunggadewa / tinadah / rakryan
mapinghai kalih (ra) (turun / perintah / Sri Maharaja Pu
Sindok / Isana Wikrama Dharmmotunggadewa /
diterima oleh dua pejabat rakryan / yaitu pejabat ra -)
(ke hino pu sahasra / rake) wka pu baliswara /
umingso / i / rakai kanuruhan pu da / kumonakan /
ikanang / lmah sawah kakatikan /
(ke / hino yaitu pu sahasra / pejabat rake wka yaitu
pu baliswara / turun / kepada / pejabat rakai
kanuruhan yaitu pu da / (sri maharaja)
memerintahkan / agar / tanah sawah kakatikan / )
……. marpanakna / i / bhatara / i / sang hyang
prasada kabhaktyan / i / dharma / samgat / pu
anjukladang /
(…….. dipersembahkan / kepada / bhatara / di /
sang hyang prasada kabhaktian / untuk / dharmma
/ pejabat samgat /bernama pu anjukladang /)
……. sri maharaja / i / sri jayamrta / …. / sima /
punpunana / bhatara
……. sri maharaja / kepada / sri jayamrta /
….(sebagai) / sima / (tempat) pemujaan / bhatara /
78
Maksudnya, Sri Maharaja Pu Sindok / Sri
Isanawikrama Dharmmotunggadewa memerintahkan
kepada dua pejabat rakryan, Rake Hino yaitu Pu
Sahasra dan pejabat Rake Wka yaitu Pu Baliswara,
diturunkan kepada pejabat Rakai Kanuruhan yaitu Pu
Da, agar tanah sawah kakatikan di Anjukladang untuk
dipersembahkan kepada bhatara di sang hyang prasada
kabhaktian untuk dharmma pejabat samgat bernama Pu
Anjukladang.
Perubahan status tersebut terjadi atas perintah
seorang raja atau pejabat tinggi, misalnya seorang rakai
atau seorang pamgat.
Penetapan tanah menjadi sima merupakan
peristiwa yang amat penting di dalam kehidupan
masyarakat Mataram Medang, karena sejak saat itu
terjadi perubahan status pertanggungjawaban. Semula
penduduk bertanggung jawab kepada raja atau rakai,
setelah tanahnya ditetapkan menjadi sima, maka mereka
bertanggungjawab kepada kepala sima (rama). Karena
itu, untuk penetapan keputusannya dilaksanakan dengan
upacara ritual yang disebut dengan istilah 'manusuk
sima'.
Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau
pengubahan di kemudian hari, dibuat piagam keputusan
berupa prasasti. Dengan diterbitkannya surat keputusan
tersebut diharapkan bahwa di kemudian hari tidak ada
orang yang melanggarnya. Pada prinsipnya tanah sima
berlaku untuk selama-lamanya.
"mne hlam tka dlaha ping dlaha".
Sejak ditetapkan menjadi daerah swatantra
tersebut maka para petugas kerajaan yang disebut
dengan istilah 'sang mangilala drawya haji' tidak lagi
79
diizinkan memasuki wilayah tersebut untuk memungut
pajak atau penghasilan.
“Tan katamana daning saprakara ning mangilala
drabya haji'”
Istilah 'sang mangilala drawya haji' dapat
ditafsirkan dengan pejabat yang mengelola milik raja
atau kelompok petugas pengumpul pajak.
Hal ini dapat diasumsikan bahwa sebelum
sebidang tanah ditetapkan menjadi sima, rakyat
diwajibkan untuk menyetorkan pajak dan kewajiban
lainnya kepada raja. Setelah tanah ditetapkan menjadi
sima, kewajiban tersebut tidak lagi dilaksanakan.
Sedangkan, kelompok petugas pengumpul pajak
tersebut jenisnya cukup banyak dengan spesialisasi
tugasnya masing-masing.
Untuk bisa ditetapkan sebagai sima, ada dua
kemungkinan. Pertama, atas permintaan rakyat wanua,
karena memiliki prestasi yang istimewa, sehingga
mereka mengajukan kepada sang raja untuk
menetapkan sebagai sima. Kedua, karena atas perintah
sang raja langsung, karena rakyat wanua berjasa terhadap
kerajaan.
Selama pemerintahan Pu Sindok menjabat sebagai
Raja Medang di Jawa Timur, kelanjutan dari Mataram
Medang, ditemukan dua peristiwa penetapan sima atas
perintah raja, yaitu wanua Linggasutan menjadi sima
Linggasutan dan sawah kakatikan di Anjukladang
menjadi sima Anjukladang. (Nugroho Notosusanto,
2009: 187).
Dalam prasasti Linggasutan, (929 Masehi),
disebutkan bahwa raja telah memerintahkan agar wanua
Linggasuttan yang termasuk wilayah Rakryan Hujung
dengan penghasilan pajak sebanyak 3 suwarna emas dan
kewajiban kerja bakti seharga 2 masa setiap tahunnya
80
ditetapkan menjadi sima. Penghasilan pajak tersebut
untuk menambah biaya pemujaan kepada bhatara di
Walandit setiap tahunnya.
Sedangkan dalam prasasti Candi Lor disebutkan
bahwa Pu Sindok telah memerintahkan agar sawah
kakatikan iy-anjukladang sebagai dharma pejabat
Samgat Pu Anjukladang dengan luas 6 lamwit (sekitar 81
– 92 hektare), serta penghasilan pajak uang emas
sebanyak 4 suwarna dan kewajiban kerja bakti (katik)
seharga uang emas 12 massa setiap tahunnya, ditetapkan
menjadi sima. Penghasilan pajak tersebut untuk
menambah biaya pemujaan kepada bhatara di Sri
Jayamerta.
……. pratidina / mangkana / …. / sri maharaja /
rikanang / sawah kakatikan
……. setiap hari / demikianlah / …… / sri maharaja /
kepada sawah kakatikan.
……....................................... n / i / bhatara / i / sang
hyang / i / sang hyang prasada kabhaktyan / i / sri
jayamrta mari ta / yan / lmah sawah kakati(ka)
...............................................n / kepada / bhatara /
di / sang hyang prasada kabhaktyan / untuk / sri
jayamerta / selesailah / jika tanah sawah kakatikan /
n / iy-anjukladang / tutugan-i / tandha / sambandha /
ikanang / rama / iy-anjukladang / tutugan-i / tanda /
kanugrahan / de / sri maharaja /manglaga /
(milik) anjukladang/ sampai ke pejabat / tanda /
alasannya pejabat rama juga anjukladang / sampai ke
pejabat Tanda / diberi anugerah / oleh / sri maharaja
/ karena berjuang
81
…….. i / saprana / i / satahun / matangnyan / papinda
/ lamwit 6 / (?) / ikanang sawah / kakatikan / iy-
anjukladang / tutuga
…….. di seluruh kehidupan di setiap tahun, itulah
sebabnya luas sawah kakatikan (milik) anjukladang 6
lamwit sampai ke pejabat Tanda
……. (n)i / tan / wuang / i / tani / rama / dumadyakan
/ ikanang / katik / smangkana / ya / ta / matangyan /
inanugrahan / ikanang / rama / iy-anjukladang /
……. (sehingga) tidak (lagi) / berhak / terhadap /
warga / rama /dijadikan / pembantu / demikianlah /
sebabnya dianugerahinya / kepada / pejabat rama
(pemimpin) / yaitu anjukladang /
…….. / katik / de / sri maharaja / tamolaha / magawi /
ma / 4 / madrwyahaji / irin / mas / su 12 / i /
satahun satahun /
........../ budak (oleh) sri maharaja / tetap melakukan
/ kerja bhakti seharga / masa / 4 / penghasilan
pajaknya /12 / suwarna uang emas / setiap tahun /
2. Prasasti
Prasasti dapat disamakan dengan surat ketetapan, yaitu
ketetapan pendirian sima. (Riboet Darmosoentopo :
2003). Tulisan prasasti dapat digoreskan pada batu, emas,
perak, tembaga, tanah liat, kayu, dan daun lontar. Ketetapan
ini disahkan dan diumumkan dengan upacara keagamaan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 786)
prasasti berarti piagam (yang tertulis pada batu, tembaga,
dan sebagainya). Prasasti adalah tulisan yang dipahatkan
pada batu berisi catatan peristiwa penting kerajaan. Fungsi
prasasti adalah memberikan peringatan atas peristiwa
penting kepada generasi berikutnya.
82
Menurut uraian di atas prasasti merupakan artefak
bertulis yang dipahatkan pada batu, logam, tanah liat, lontar,
atau kayu yang memberikan berbagai macam informasi atas
suatu peristiwa penting bagi generasi selanjutnya. Di
Indonesia sendiri telah banyak ditemukan berbagai macam
prasasti sebagai benda peninggalan bersejarah.
Prasasti-prasasti pertama daerah Jawa Tengah, yang
muncul pada awal abad VIII, mengungkapkan persaingan
antara sesama raka atau rakaryan, yaitu penguasa yang telah
berhasil menguasai sejumlah wanua atau “komunitas desa”
dan berusaha meningkatkan prestise-nya dengan
memperbanyak bangunan suci.
Sementara di Jawa Timur wangsa yang dianggap
berkuasa pada masanya adalah wangsa Isana yang didirikan
oleh Pu Sindok. Istilah wangsa Isana ditemukan dalam
prasasti Pucangan, di bagian yang berbahasa Sansekerta.
Prasasti itu dibuat era pemerintahan raja Airlangga pada
tahun1041 M.
(Windi Ika Diahing Sari * AnjarMukti Wibowo, Jurnal
Agastya Vol7 No 1 Januari 2017).
a. Macam-macam prasasti
Beberapa macam prasasti yang menunjukkan
pengaruh Hindu-Budha adalah:
(1) Sima, yaitu prasasti yang berisi maklumat raja atau
bangsawan dalam rangka pengukuhan daerah
menjadi sima. Contoh: prasasti Candilor atau
Anjukladang, 937 Masehi.
(2) Jayapattra, yaitu prasasti yang berisi keputusan
hukum untuk pihak yang memenangkan suatu
perkara. Contoh: prasasti Guntur 907 Masehi.
(3) Suddhapattra, yaitu prasasti yang berisi keputusan
ikatan hutang-piutang, pelunasan, atau proses gadai.
Contoh: prasasti Guntur 907 Masehi.
83
(4) Mantra-mantra, Hindu dan Budha, pada
umumnya dipahatkan di atas lempengan tanah liat.
Contoh: prasasti Jragung.
Darmoseontopo, (2003), membagi isi prasasti
sebagai berikut; prasasti hukum terdiri;
1) Hutang piutang, jual beli tanah, kewarganegaraan,
soal luas tanah, dan gadai tanah;
2) Pembuatan bendungan
3) Pembuatan rumah dan perahu
4) Anugerah kepada orang
5) Menunjang bangunan; prasada, dharmma, kabikuan,
bihara, patapan, parhyangan, caitya, dan cala.
6) Punya, payung dan genta
7) Untuk Bhatara
8) Peneguhan kembali
b. Fungsi prasasti
Sebagai penghormatan kepada dewa, baik dalam
agama Hindu maupun Budha. Ciri prasasti seperti ini
biasanya terdapat kata “ong” selanjutnya nama dewanya
dalam agama tersebut.
Dari angka-angka dalam prasasti merupakan
sumber sejarah yang sangat penting dan dapat digunakan
sebagai referensi dalam penelitian. Angka dan tahun di
dalam prasasti biasanya diawali dengan kata "Swasti Cri
Cakawarsatita". Isi prasasti biasanya menyebut nama
raja-raja dari masanya.
Prasasti juga bisa digunakan sebagai simbol atau
suatu batas wilayah kerajaan tertentu. Contoh prasasti
Mataji, batas antara Jenggala dan Panjalu ditemukan di
dekat Gunung Taji, Bangle, Kecamatan Lengkong
84
3. Jayastamba
Jayastamba (Sansekerta), “jaya” berati penaklukan,
kemenangan, seruan kemenangan, dan “stamba”, berarti
tonggak, pilar, tiang, batang (Zoetmulder, 1994). Dalam
Prasasti Anjukladang, [……..] ya tka ing dlaha ning dlaha
parnnahan-ikanang lmah uggwani sang hyang prasada
ateher-ang / jayastamba [......]
……. )ya sampai akhir zaman statusnya tanah yang
ditempati oleh sang hyang prasada kemudian dijadikan
sebagai tonggak (tugu) kemenangan.
Pendirian suatu bangunan; stambha, tugu, monumen
untuk menengarai suatu peristiwa penting dalam siklus
kehidupan manusia, dilakukan sejaka zaman purba hingga
saat ini.
Misalnya, (1) untuk memperingati kematian para
leluhur didirikanlah Menhir (mijnheer), sebagai lambang
kemaskulinan dari tokoh yang meninggal. Besar-kecil, tinggi
rendah Menhir tergantung status sang tokoh. Selain itu,
Menhir juga digunakan untuk mengikat binatang korban
(biasanya kerbau). Setelah zaman megalitikum sebagai
phalus, patung, kemudian pada zaman Islam disebut
mahesan (tempat mengikat kerbau sebagai binatang korban
sebagai tunggangan si mati. (2) Maharaja Ashoka (275-245
SM) dari dinasti Maurya setiap berhasil menaklukan suatu
kerajaan didirikanlah tugu kemenangan (monumen);
Torana dengan patung singa bertahta diatasnya sebagai
simbol kerajaan Magada. (3) Pada abad awal, Kaisar
Napoleon Bonaparte setiap mendapat kemenangan juga
mendirikan monumen atau pintu gerbang, yang terkenal di
Paris, (4) Pada zaman modern; untuk memperingati Hari
Pahlawan Pertempuran 10 November 1945 dibangun Tugu
Pahlawan di Surabaya, Monumen Yogya Kembali di Yogya,
dan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta.
Jadi tugu peringatan atas suatu peristiwa kemenangan
telah terjadi, sejak pada zaman kuno hingga modern.
85
Diantaranya; Jayastamba (tiang, tugu kemenangan) dan
Jayamerta (pemandian suci sebagai tanda kemenangan).
Pada Prasasti Anjukladang juga disebut adanya
Jayastamba dan Jayamerta, keduanya sebagai simbol
peringatan kejayaan/kemenangan.
4. Sistematika Penetapan Sima
Sebagian besar prasasti yang ditemukan di Jawa berisi
pemberian anugerah raja kepada orang atau kelompok
orang yang berjasa berupa Sima (daerah yang dibebaskan
dari sebagian besar pembayaran pajak). (Boechari, 2012:6)
Prasasti-prasasti tersebut memperingati sebidang tanah
- suatu daerah sebagai sima, daerah perdikan, sebagai
anugerah raja kepada seorang pejabat yang telah berjasa
kepada kerajaan atau sebagai anugerah raja untuk
kepentingan suatu bangunan suci. (Boechari, 2012:7)
Penetapan suatu sima dianggap penting karena
menyangkut perubahan status sebidang tanah yang dalam
masyarakat, mempunyai hubungan religius-magis dengan
penduduk yang tinggal di atasnya.
Sebagaimana penetapan sima, berisi pemberian
anugerah Raja Medang Pu Sindok kepada rakyat Kakatikan
iy-Anjukladang, sebagai daerah yang dibebaskan dari
pembayaran pajak. Kemudian, penetapan sima diperingati
dengan membangun sebuah prasasti sebagai daerah
perdikan, anugerah raja kepada seorang pejabat samgat
bernama Pu Anjukladang, karena telah berjasa kepada
kerajaan dan sekaligus anugerah raja untuk kepentingan
suatu bangunan suci “sang Hyang Persada Sri Jayamerta”.
Adapun sistematika yang harus ada pada prasasti penetapan
sima adalah sebagai berikut;
a. Maǹggala (seruan kepada dewa)
Dalam Prasasti Candi Lor disebutkan seruan kepada
para dewa “... naksatra baruna dewata brahmayoga
86
kolawakarana irika di (wa)” (….. naksastra, dewata
baruna, yoga brahma, karana kala-a ketika).
b. Unsur-unsur Penanggalan
Keterangan panjang lebar mengenai hari, bulan,
tanggal, tahun. “Swasti sakawarsatita 859 caitramasa tithi
dwadasisuklapaksa” (Selamat tahun 859 saka yang telah
berlalu, pada bulan caitra tanggal 12 paro terang (10
April 937M)).
Unsur penanggalan yang berkaitan dengan prasasti
Candi Lor, terdapat dua versi yang berbeda, khususnya
tentang angka tahun. Dr. Brandes membacanya 857
Saka, Suklapaksa atau paro terang. (Brandes, 1913 : 84).
Hasil bacaannya itu kemudian dikoreksi oleh L.C.
Damais, bahwa prasasti Candi Lor dikeluarkan pada
tahun 859 Saka bertepatan dengan Krsnapaksa. Ia juga
berhasil menemukan unsur hari pekan (wara) yaitu
(HA) riyang, dalam konteks tanggal 12 bulan Caitra.
Dalam hal ini kedua pakar itu tidak berbeda pendapat.
kecuali yang menyangkut saat siklus hari edar bulan
antara Suklapaksa dan Krsnapaksa. .
Dengan membandingkan seluruh prasasti semasa
pemerintahan Pu Sindok yang dikeluarkan pada bulan
Caitra Sukla tanggal 1, dan tanggal 12, dalam
padanannya dengan tarikh Masehi, dapat disimpulkan
sebagai berikut;
Tanggal 1 (satu) Sukla bulan Caitra tahun 857 Saka
bersamaan dengan tanggal 8 Maret 935 Masehi. Pada
tanggal 12 Krsnapaksa bulan Caitra, bertepatan dengan
hari HA KA SU 3 April 935 atau tanggal 4 April WU U
SA. Sementara itu tanggal 1 Sukla bulan Caitra tahun
859 Saka, bertepatan dengan tanggal 15 Maret 937
Masehi, sedang tanggal 12 Krsnapaksa bulan Caitra
tahun 859 Saka, jatuh pada tanggal 10 April 937 Masehi,
dengan hari pekan HA PO SO atau WU WA ANG.
87
Dalam prasasti Candi Lor ini unsur hari pekannya
terbaca Ha atau Hari yang dalam pekan Sadwara, atas
dasar data itu bersesuaian dengan PO atau Pon pekan
Saptawara, serta bertepatan dengan hari SO atau Soma
pekan Saptawara. Dengan demikian berdasarkan data
penanggalan yang tercantum pada prasasti Candi Lor
yaitu tanggal 12 bulan Caitra dengan hari pekan Hari
yang jika tahunnya dibaca 857 Saka menurut Brandes,
terdapat ketidak sesuaian antara unsur hari pekannya
antara Sadwara, Paneawara dan Saptawara.
Oleh karena itu dengan menggunakan rumus
perhitungan yang disusun oleh L.C. Damais, hari
pertama tahun Saka 859, menurut siklus Wuku dengan
sistim hari-hari pertama dimulai hari Tu = Tunglai
Sadwara, PA = Pahing Pancawara, dan A = Aditya
Saptawara, maka hari pertama tahun 937, jatuh pada
hari kedua sesuai dengan Ha Sadwara, atau PO
Pancawara, atau SO Saptawara. Atas dasar perhitungan
tersebut, data penanggalan prasasti Candi Lor tanggal 12
Krsnapaksa Ha bulan Caitra tahun 859 Saka,
bersesuaian dengan 10 April 937 Masehi. (Damais 1955
: 156 – 158).
c. Nama raja atau pejabat yang mengeluarkan prasasti
“Sanya ajna sri maharaja pu sindok sri isana
wikrama dhramamogunggodewa” (telah turun perintah
raja Sri Maharaja Pu Sindok Sri Isana Wikrama
Dhramamogunggodewa).
Berarti, pejabat yang mengeluarkan prasasti Candi
Lor adalah Sri Maharaja Pu Sindok Sri Isana Wikrama
Dhramamogunggodewa, yaitu Raja Mataram Medang.
d. Pejabat tinggi pemerintah yang menerima perintah raja
“tinadah rakryan mapinghai kalih (ra) (ke hino pu
sahasra, rake) wka pu baliswara umingso i rakai
88
kanuruhan pu da” (diterima dua pejabat tinggi
pemerintah Rake Hino Pu Sahasra dan Rake Wka Pu
Baliswara). Diperkirakan, Rake Hino Pu Sahasra dan
Rake Wka Pu Baliswara adalah putra dari Dyah Wawa.
Pejabat tinggi pemerintah Kerajaan Mataram
Medang era Raja pu Sindok yang menerima perintah
untuk mengeluarkan prasasti Candi Lor adalah dua
orang pejabat tinggi (mapinghai kalih), Rake Hino Pu
Sahasra dan Rake Wka Pu Baliswara.
e. Perintah raja atau pejabat untuk menetapkan sima
“umingso / i / rakai kanuruhan pu da /
kumonakan / ikanang / lmah sawah kakatikan /”
turun / kepada / pejabat rakai kanuruhan yaitu pu
da / (sri maharaja) memerintahkan / agar / tanah sawah
Kakatikan / ?/
Berarti, pejabat kerajaan yang diperintahkan untuk
menetapkan sima adalah pejabat Kanuruhan bernama
Pu Da.
f. Pejabat daerah yang menerima keputusan raja
Perintah raja atau pejabat untuk menetapkan sima
di Kakatikan iy-anjukladang adalah seorang pejabat
tinggi kerajaan Mataram Medang bernama Rakai
Kanuruhan Pu Da diperuntukkan kepada pemimpin
sima (kepala rama) di Kakatikan iy-anjukladang, pejabat
Samgat bernama Pu Anjukladang.
“ ........ kumonakan / ikanang / lmah sawah kakatikan / “
memerintahkan / agar / tanah sawah kakatikan /
“……. marpanakna / i / bhatara / i / sang hyang prasada
kabhaktyan / i / dharma / samgat / pu anjukladang”
…….. dipersembahkan / kepada / bhatara / di / sang
hyang prasada kabhaktian / untuk / dharmma / pejabat
samgat /bernama pu anjukladang /
89
g. Keterangan hasil pajak sima sebelumnya
“... i saparana i satahun matangnyan papindu
lamwit 6 (?) ikanang sawah kakatikan iyanjukladang
tutugani tan wuang i thani ramang dumadyakan ikanang
katik smangkana ya matangyan manugrahan ikanang
rama iyanjukladang.
(… seorang setiap tahun, karena jumlah sawah
kakatikan iy-anjukladang 6 lamwit ……. (sehingga) tidak
(lagi) berhak terhadap warga dan rama yang dijadikan
katik, demikianlah dianugerahinya rama
(pemimpin)(dan|atau) anjukladang).
Dalam Riboet Darmosoentoro (2003)
menyebutkan bahwa ada beberapa nama satuan luas
tanah khususnya tanah yang berjenis sawah. Nama-nama
satua luas sawah sebenarnya berasal dari satuan jumlah
benis yang akan ditanam sebab nama satuan ukuran luas
selalu didahului kata “banyak benihnya” (kwaih
winihnya). Diantara nama—nama satuan luas adalah
lamwit dan tampah.
1 lamwit = 20 tampah, 1 tampah luasnya antara
6750 meter persegi hingga 7680 meter persegi. Luas 1
tampah sekitar 1 bahu masa sekarang.
Bila luas tanah sawah Kakatikan Sri Jayamerta yang
dibebaskan dari kewajiban membayar pajak adalah 6
lamwit, maka luasnya (6 x 20 x 66750m2) = 810.000 m2 =
81 hektar atau (6 x 20 x 7680m2) = 921,600m2 = 92,12
hektar.
Sedangkan besarnya hasil pajak yang harus dibayar
kepada raja sebelumnya adalah:
……. (n)i / tan / wuang / i / tani / rama / dumadyakan /
ikanang / katik / smangkana / ya / ta / matangyan /
inanugrahan / ikanang / rama / iy-anjukladang /
……. (sehingga) tidak (lagi) / berhak / terhadap / warga /
rama / dijadikan / pembantu / demikianlah / sebabnya
90
dianugerahinya / kepada / pejabat rama (pemimpin) /
yaitu anjukladang /
…….. / katik / de / sri maharaja / tamolaha / magawi / ma
/ 4 / madrwyahaji / irin / mas / su 12 / i / satahun
satahun /
........../ budak (oleh) sri maharaja / tetap melakukan /
kerja bhakti seharga / masa / 4 / penghasilan pajaknya
/12 / suwarna uang emas / setiap tahun /
…….. / mangkana / ( )nn( ) / ny-anugraha / sri maharaja /
irikanang / rama iy-anjukladang / tutugan-i / tanda tlas /
mapageh / tan / kolahulaha /
…….. / demikianlah / ( ) nn ( ) / anugerah / si maharaja /
kepada / pejabat rama / yaitu anjukladang / sampai ke
pejabat tanda sudah / diputuskan / tidak boleh /diganggu
/
…….. yakapa( )ya / tka / i / dlahaningdlaha / parnnahan-
ikanang / lmah / uggwani / sang hyang prasada / ateher-
ang / jayastama
……. yakapa(....)ya sampai / akhir / zaman / statusnya
tanah yang ditempat oleh sang hyang prasada) /
kemudian menjadi tonggak kemenangan
…….. / muang / ikang / sawah / kakatikan / iyanjukladang
/ tutugani / tanda / swatantra / tan / kataman / dening /
winawa / sang mana / katrini / pangkur /
........ dan sawah kakatikan (milik) anjukladang itu
sampai ke pejabat Tanda berstatus swatantra, tidak
boleh dimasuki oleh ketiga (katrini) pejabat yang
berkuasa, yaitu pangkur
Jadi, dalam prasasti Candi Lor, disebutkan bahwa
raja Pu Sindok telah memerintahkan agar sawah
kakatikan iy-anjukladang dengan luas 6 lamwit (sekitar
81 – 92 hektare), serta penghasilan pajak uang emas
senilai 4 suwarna dan kewajiban kerja bakti (katik)
seharga uang emas 12 massa setiap tahunnya ditetapkan
menjadi sima. Penghasilan pajak tersebut untuk
91
menambah biaya pemujaan kepada bhatara di Sri
Jayamerta.
h. Maksud dan tujuan penetapan sima
Berdasarkan isi prasasti tentang penetapan sima
yang pada umumnya diawali dengan manggala yaitu
seruan kepada dewa, yang dilanjutkan dengan
penyebutan unsur-unsur penanggalan yang memuat
keterangan tentang kapan prasasti dikeluarkan,
keterangan tentang nama raja atau pejabat yang
mengeluarkan prasasti, dilanjutkan dengan nama-nama
pejabat yang menerima perintah. Selanjutnya, dimuat
keterangan untuk keperluan apa sebuah sima itu
ditetapkan, pejabat yang hadir, serta proses pelaksanaan
upacara. Ada bermacam-macam pertimbangan
pemberian tanah sima dan bermacam-macam orang
yang menerima anugerah dan seterusnya, sebagaimana
disebut di atas, maka menyebabkan ada bermacam-
macam sebutan nama tanah sima. Klasifikasi sebutan
untuk tanah sima sebagai berikut; :
1) Sima makudur yaitu sima yang diberikan kepada
seorang makudur yang telah berjasa kepada raja;
2) Sima kapatihan yaitu sima yang diberikan kepada
patih yang berjasa kepada raja. Dalam hal ini,
misalnya, kelima patih dari Mantyasih yang telah
berjasa besar pada waktu pernikahan Raja Balitung,
dan telah mengamankan dari kerusuhan (prasasti
Poh 827 Saka);
3) Sima pinaduluran yaitu tanah simayang diberikan
oleh Raja Balitung kepada kelima patih di Mantyasih
secara bergantian setiap tiga tahun sekali (prasasti
Mantyasih 1 829 Saka);
4) Sima kamulan yaitu tanah sima yangdiberikan
kepada mereka yang memikul tugas mengamankan
desa dan jalan dari kerusuhan.
92
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
BUKU SEJARAH NGANJUK ERA PRASEJARAH
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search