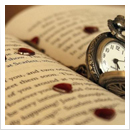"...... sambhan danyan inanugrahan sima de rakryan,
maka phala karaksanikanang ha wangeng iadanyan.
katakutan, yata matangnyan simakamulan
ngaranya.....”
Artinya :alasan diberi tanah sima oleh Rakryan,
berhasil menunaikan tugas menjaga jalan besar
sehingga menghilangkan ketakutan. Oleh karena itu,
tanah yang dijadikan sima disebut sima kamulan;
5) Sima kajurugusalyan. "Juru gusali" adalah pengelola
pekerjaan pande logam yang membidangi pandai
wesi, pandai mas, pandai dang, pandai kuningan,
pandai dadap. Masyarakat pande logam tersebut
tampaknya memiliki bangunan peribadatan
tersendiri, yaitu tempat pemujaan para pande.
Tanah sima dianugrahkan kepada mereka untuk
keperluan pemeliharaan bangunan pemujaan
tersebut.
6) Sima punpunan yaitu tanah sima yang diberikan
untuk menunjang bangunan keagamaan.
……. marpanakna / i / bhatara / i / sang hyang
prasada kabhaktyan / i / dharma / samgat / pu
anjukladang /
…….. dipersembahkan / kepada / bhatara / di / sang
hyang prasada kabhaktian / untuk / dharmma /
pejabat samgat /bernama pu anjukladang /
……. sri maharaja / i / sri jayamrta / …. / sima /
punpunana / bhatara
……. sri maharaja / kepada / sri jayamrta /
….(sebagai) / sima / (tempat) pemujaan / bhatara /
……. pratidina / mangkana / …. / sri maharaja /
rikanang / sawah kakatikan
……. setiap hari / demikianlah / …… / sri maharaja /
kepada sawah kakatikan.
93
……....................................... n / i / bhatara / i / sang
hyang / i / sang hyang prasada kabhaktyan / i / sri
jayamrta mari ta / yan / lmah sawah kakati(ka)
...............................................n / kepada / bhatara /
di / sang hyang prasada kabhaktyan / untuk / sri
jayamerta / selesailah / jika tanah sawah kakatikan /
n / iy-anjukladang / tutugan-i / tandha / sambandha /
ikanang / rama / iy-anjukladang / tutugan-i / tanda /
kanugrahan / de / sri maharaja /manglaga /
(milik) anjukladang(/ sampai ke pejabat / tanda /
alasannya pejabat rama juga anjukladang / sampai ke
pejabat Tanda / diberi anugerah / oleh / sri maharaja
/ karena berjuang.
Jadi maksud dan tujuan penetapan sima
Anjukladang adalah anugerah raja Sindok kepada
kakatikan iy-anjukladang berupa tanah perdikan agar
rakyat kakatikan bebas dari sebagian besar
kewajiban membayar pajak karena telah berjasa
membantu perang melawan musuh kerajaan.
Sebagian besar pajaknya kemudian diperuntukan
untuk keperluan bangunan suci (punpunan).
i. Hak serta kewajiban penduduk
Anugerah penetapan tanah sĩma mengandung
beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, sĩma
dapat diberikan atas permintaan (dapat juga diberikan
atas inisiatif raja) sebagai suatu penghargaan. Kedua,
penerima sĩma memiliki berbagai kewajiban yang tidak
hanya berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan, tetapi
juga tugas-tugas keamanan. Selain itu, penerima sĩma
juga memiliki bermacam hak yang mencerminkan
adanya simbol-simbol yang menempatkan dirinya
sebagai perluasan kekuasaan pusat di daerah (Suhadi,
1994).
94
1) Sukhadukha umumnya ditafsirkan sebegaia ‘segala
tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan
daerah perdikan yang harus dikenai hukuman
denda’.
2) Bunga pinang yang tidak sampai menjadi buah atau
dengan ungkapan lain yaitu mayang tan tka ring
wwah, mungkin yang dimaksud adalah tan
kasahuraning pihutang (=tidak membayar hutang).
Ada yang mengartikan, “mayang” adalah bunga
jambe yang biasa disimbulkan untuk wanita. “tan tka
ring wwah” diartikan memiliki anak tanpa seorang
ayah atau hamil di luar nikah.
3) Walu rumambat ring natar (tanaman labu yang
menjalar di halaman), mungkin yang dimaksud
adalah kahucapananing wates atau ‘persengketaan
mengenai batas-batas tanah’ (Bambang Soemadio,
ed. II, 1984:231; Boechari, 1986184, cat. 5).
4) Orang mati yang mayatnya berembun, ini adalah
sejenis tindak pidana tentang terjadinya suatu
pembunuhan pada waktu malam hari dan mayatnya
di ladang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kalau
pemilik ladang itu telah mengetahui peristiwa
tersebut tetapi tetap tinggal diam (atau lalai
melaporkan) sampai hari berikutnya sehingga
mayatnya terkena embun maka orang itu dapat
dikenai denda. Keterangan ini dijumpai di dalam
beberapa naskah hukum, sebagai contoh di dalam
naskah agama pasal 66 (Jonker, 188549) dijelaskan
sebagai berikut: ‘wanke ginenan de ning dusta
amateni wong ring desa ning adesa kala ning wni,
nora weruh kang adrewe lmh denda nikang adrewe
lmh yen mulat mneng dene kasalahanwanke yen
kawanen ikang wanke dendane rong laksa de nira
amawa bhumi, sapakara mane milu kadenda, arane
katmu wanke kabunan’
95
5) Darah yang terhambur di jalan, maknanya mungkin
sama seperti suatu tindak pidana yang mana korban
sampai menumpahkan darah. Orang yang
melakukan atau menetahui peristiwa itu tetapi tidak
melaporkannya dapat dikenai denda.
6) Mencaci maki di dalam naskah agama disebut wak
parusya, dengan arti anumanuman. Salah satu pasal
misalnya pasal 220b (Jonker, 1885:81) menjelaskan
bahwa seseorang brahmana yang mencaci maki
seseorang ksatriya dendanya lebih besar daripada
kalau ia mencaci maki seorang waisya, dan
seterusnya. Bunyi pasal itu sebagai berikut; ‘ring
parusya ucapen mangke, ring ksatriya anumanuman
brahmana de sang prabu, sang brahmana yen
anumanuman ing ksatriya denda ning brahmana
sewu sang brahmana anumanuman ing wong tani
dendanen sang brahmana limang atus, brahmana
anumanuman ing wong adagang sang brahmana
dendanen satak sawe’.
7) Menuduh, memukul dengan tangan, mengeluarkan
senjata tajam, dijumpai pula di dalam naskah hukum
Sarasamuccaya pasal 3 dengan istilah amijilaken
sanjata, yaitu tindakan mengancam orang dengan
mengeluarkan senjata tajam.
8) Mengamuk, di dalam naskah hukum istilah
(m)amuk atau ‘mengamuk’ ini diberu rumusan yang
sedikit berbeda. Di dalam naskah Sarasamuccaya
(MS.Lor, 5037) dijelaskan sebagai berikut; “----
yapwan amijilken sanjata kalih amrana lingnya danda
su 1 ma 9, patidaharasa naranya yapwan amrang
danda su 3 ma 2, amun apunggung aranya, yapwan
amrang tang wwang patyana ika mankana, amuk
aranya---“.
9) Memperkosa wanita, di dalam naskah agama pasal
135 (Jonker 1885:62) dijelaskan bahwa orang yang
96
ketahuan memperkosa wanita dapat divonis
hukuman mati, yaitu sebagai berikut; “wong
amungpang rabi ning arabi, den tut maring gnah ing
wong wadon ika, wet ning repe kang amungpang,
dosane kang amungpang dosa pati de nira sang
amawa bhumi”.
10) Ludan dan tutan mungkin dari pokok kata lud dan
tut; kedua kata ini sama artinya dengan konotasi
yang agak berbeda. Maknanya mungkin mengejar
orang (atau lawan dalam perkelahian) yang tak
berdaya dengan maksud menyakiti (membunuh).
11) Pukul memukul, mungkin juga suatu istilah lain dari
denda parusya di dalam naskah agama ini, yaitu
segala macam pelanggaran|tindak kekerasan, yang
dapat dikenal hukuman. Di dalam naskah agama
pasal 225 (Jonker, 1885:82) dijelaskan sebagai
berikut; “denda parusya ucapen mangke, ring wong
amuk(u)l, anuduk ing kayu, angitaki (baca: anggitik
ing) watu, anglarani, angemu getih, atatuha kuneng,
anugelaken, anikelaken balung, matadi (baca:
makadi) yen amatenana sarwwa sato, yen wong
edine araning ulah wiwijinen, salah tunggale (i)ka
denda parusya arane ----dan seterusnya“.
12) Bhandihaladi, sebetulnya yang lebih banyak
dijumpai di dalam prasasti-prasasti ialah bentuk
mandihaladi istilah ini belum ditemukan
perumusannya di dalam naskah-naskah hukum.
Dari arti katanya, mandihala mungkin maksudnya
adalah tindak kejahatan dengan menggunakan bisa
(ular) atau racun, sedangkan akhiran adi pada kata
itu tyang berarti ‘dan lain sebagainya’ menunjukkan
bahwa macam sukhadukha itu masih jauh lebih
banyak lagi.
Bila peristiwa sukhadukha tersebut terjadi di
sebuah sima, maka yang berhak memberikan sanksi
97
adalah bhatara di prasada atas semua denda yang
menjadi milik raja itu. Mungkin yang dimaksud
adalah, semua sanksi hukumnya diserahkan kepada
raja sebagai perwakilan bathara (dewa).
Jadi pejabat penerima sĩma kakatikan iy-
anjukladang menyadari bahwa melalui penganugerahan
sĩma melekat suatu kewajiban, yakni memelihara
bangunan suci yang didirikan di atas tanah sĩma
miliknya. Bentuk pemeliharaaan yang paling nyata
adalah dengan memberikan sebagian hasil pajaknya
untuk kepentingan bangunan suci yang berada di daerah
sĩma, yaitu berupa candilor dan petirtaan Sri Jayamerta.
Kewajiban lainnya yaitu gotong royong untuk
perbaikan bangunan (buncang haji) dan sarana umum,
serta kewajiban mengadakan upacara keagamaan
dengan menanggung seluruh biayanya. Upacara
keagamaan ini dilakukan secara berkala dengan biaya
yang tidak sedikit.
Kepala sĩma kakatikan iy-anjukladang juga diberi
kewajiban untuk menjaga keamanan daerah dari para
perusuh. Kewajiban yang lebih penting sebagai kepala
sĩma adalah mengatur jalannya pemerintahan di wilayah
sĩma, terutama yang berkaitan dengan masalah pajak.
Kepala sĩma bertanggung jawab atas penarikan segala
macam jenis pajak (tanah, perdagangan, dan usaha) di
wilayahnya dan membagikannya kepada pihak-pihak
yang berhak, yakni raja, bangunan suci yang ada di
wilayah sĩma dan dirinya sendiri. Kepala sĩma
berkewajiban pula menetapkan besar-kecilnya denda
bila terjadi pelanggaran (sukhaduhka) di wilayahnya.
Pelanggaran tersebut meliputi gangguan terhadap
ketetapan sĩma maupun peristiwa kriminal di wilayah
sĩma.
98
j. Pemberian pasak-pasak
Salah satu unsur upacara pada penetapan sima
yang disebutkan adalah pemberian pasek-pasek kepada
mereka yang hadir di dalam upacara sebagai saksi.
Pasek-pasek adalah semacam hadiah atau pisungsung
yang berupa uang, barang, atau binatang. Istilah lain
adalah "page pageh" (prasasti Wanua Tengah).
Pemberian yang berupa barang, antara lain, berbentuk
kain bebed (wdihan, kain, salimut), cincin (simsim).
Jumlah dan kualitas barang yang dibagikan
didasarkan atas urutan kepangkatan dan tinggi-
rendahnya kedudukan mereka. Jenis-jenis kain yang
disebutkan di dalam prasasti bermacam-macam,
diantaranya yang sering dijumpai di dalam prasasti
adalah: wdihan pilih magong, wdihan jaga, wdihan bira,
wdihan ragi, wdihan rangga, wdihan pilih angsit, wdihan
angsit, wdihan kalyaga, wdihan ganjar patra, wdihan
ganjar patra sisi, wdihan jaro gulung-gulung, wdihan buat
kling(bebed buatan orang Keling), wdihan buat pinilai,
kain jaro, ken buat wetan (kain buatan dari timur), bwat
lor (buatan dari derah utara), dan salimut (selimut).
Barangkali macam-macam istilah tersebut menunjukkan
pola atau motif hias yang berbeda-beda.
Satuan ukuran untuk jenis kain tersebut adalah
yugala (di dalam prasasti disingkat yu), hlai (lembar),
atau wlah untuk jenis kain biasa.
Tampaknya pemilihan jenis kain tergantung
kepada siapa kain tersebut diberikan. Sebagai contoh
dapat dikutipkan, di dalam prasasti Sangsang 829 Saka:
"pasambah i sri maharaja wdihan pilih magong yu 1
wdihan jaga yu 1 mas su 1 mara rakryan mapatih i hino
inangsian wdihan kalyaga yu 1"
Persembahan kepada Sri Maharaja berupa kain
wdihan pilih magong ukuran 1 yugala dan wdihan jags 1
yugala, sedangkan kepada Rakryan Mapatih i Hino
99
diberikan kain wdihan kalyaga 1 yugala. Di sini tampak
bahwa meskipun kedua pejabat tersebut mendapat
pasak-pasak kain dalam ukuran yang sama (1 yugala),
jenisnya lain sesuai dengan tinggi-rendahnya jabatan.
Jenis wdihan pilih magong khusus hanya diberikan
kepada maharaja.
Pasak-pasak berupa emas diberikan dalam jumlah
yang berbeda menurut tinggi rendahnya jabatan. Satuan
untuk berat mas dinyatakan dengan masa (disingkat ma),
suwarna (disingkat su), kati (disingkat ka), sedangkan
satuan untuk perak dinyatakan dengan kati, dharana,
masa, kupang dan disingkat menjadi ka, dha, ma, dan
ku).
Para peneliti berbeda-beda dalam mengkonversi
satuan berat emas. Menurut Stuttereim; 1 su = 1 tahil =
16 masa = 64 kupang dengan berat 1 su = 0,038601 kg;
1 ma = 0,002414 kg; 1 ku = 0,000603 kg.
Adapun Robert Sicks berkesimpulan bahwa 1 kati
= 16 suwarna; 1 suwarna = 16 masa 64 kupang; 1 masa =
4 kupang dengan rincian berat 1su = 38,601 gram; 1 ma
= 2,414 gram; 1 ku = 0,603 gram.
Pasak-pasak berwujud binatang dijelaskan dalam
prasasti Poh 827 Saka sebagai berikut: "patih i kiniwang
nayaka sang rakawu si drping rama ni pangalah muang
sang gegel rama ni tunggang kapua winaihhan pasak-
pasak wdihan yu 1 mas ma 4 kbo 1 wdus 5 . . . ."
Artinya : "patih di Kiniwang nayaka Sang Rakawu
(bernama) Si Drping, ayahnya Pangalah, dan Sang Gegel
ayahnya Tunggang, semuanya diberi pasak-pasak bebed
1 yugala emas 4 masa kerbau 1 ekor dan kambing 5
ekor ..."
Dengan memperhatikan dan menghitung jumlah pasak-
pasak yang diberikan diperoleh gambaran tentang
berapa kira-kira jumlah biaya yang dikeluarkan. Dari
beberapa prasasti diperoleh kesan bahwa besarnya biaya
100
tiap penetapan sima tidak sama. Hal tersebut
bergantung pada jumlah yang hadir dan menerima
pasak-pasak, serta besar kecilnya upacara. (Timbul
Haryono, 1999, Jurnal Humaniora No.12 Sept-Des
1999, UGM, Yogyakarta.)
Berikut adalah para pejabat yang menerima pasak-
pasak dalam penetapan sima di wanua kakatikan iy-
anjukladang beserta jenis dan ukurannya, tertulis dalam
Prasasti Candi Lor, bait ke-29 hingga 49, prasasti bagian
depan dan bait ke-23, prasasti bagian belakang.
Bagian depan:
29. / laladrwya haji / i rikanang / kala / mangaseakan /
samgat anjukladang / pasambah / i / sri maharaja / ma
/ ka / 1 / wdihan / ganjarhaji / yu / 1 / rakyan
(mapinghai)
untuk pemungut pajak. Perajin saat itu
mempersembahkan untuk Samgat Anjukladang,
kemudian dipersembahkan kepada Sri Maharaja uang
emas 1 kati dan sepasang kain jenis ganjar haji 1
yugala / pejabat rakiyan
30. / (kalih) / rakai hino pu sahasra / rakai wka pu
baliswara/ inangseakan / pasek pasek / mas su / 1 /
ma / 8 / wdihan / yu / 1 / sowang sowang / rakai
sirikan pu ma[.....]
Berdua, rakai hino pu sahasra / dan rakai wka pu
baliswara / masing-masing diberi / hadiah uang emas 1
suwarna 8 masa / kain 1 yugala / pejabat rakai sirikan
pu ma
31. [……..] / rakai kanuruhan pu ta / inangsean / pasak
pasak / mas / su / 1 / ma / 4 / wdihan / yu / 1 / sowang
sowang / samgat pikatan pu sa ……. tiruan /
……. pejabat rakai kanuruhan pu ta / masing-masing
diberi / hadiah / uang emas / 1 / suwarna / 4 / masa /
101
kain / 1 yugala / pejabat samgat pikatan pu sa ………
tiruan /(bernama)
32. / [.......] / taritip / halaran / pu bingu / pulung watu
pu kikas / inangsian / pasak pasak / mas / 1 / wdihan /
yu / 1 / sowang sowang / juru siki / pu bawlu amr[…....]
pu manak / (ti
/ ……… (dapu)nta / taratis / pejabat tataran / bernama
pu bingu / pejabat pulung watu bernama pu kikas /
masing-masing diberi / hadiah uang / emas / 1 / dan
sepasang kain / 1 / yugala / pejabat juru siki bernama
pu bawlu, pejabat amr / …….. bernama pu manak /
33. limpik pu wayan / manghuri pu suduya / inangsian /
pasak pasak / ma / 1 / wdihan / yu / 1 / sowang
sowang / pu kuba / hawang kuyalangka pu babra / anju
sanda pu dula / [.......]
…….. mpit bernama pu wayan / pejabat manghuri
bernama pu saduya / masing-masing diberi / hadiah /
uang emas / 1 masa / dan sepasang kain / 1 yugala /
pu kuba / pejabat hawas kuyalangka bernama pu
babra /pejabat anju sanda bernama pu dula /
34. / inangsean / pasak pasak / mas / 4 / wdihan / yu / 1
/ sowang sowang / wadihati pu dinakara / akudur pu
dwaja / inangsean / pasak pasak / ma /1 / wdihan / yu /
1 / sowang sowang
/ masing-masing diberi / hadiah / uang emas / 4 masa /
kain / 1 yugala / pejabat wadihati bernama pu dinakara
/ pejabat akudur bernama pu dwaja / masing-masing
diberi / hadiah uang emas 1 masa / sepasang kain / 1
yugala
35. tuhan / i / wadihati /i / mirahmirah / sang tambalang
/ halaran / sang dulang tuhan / i / makudur basa
tpusan / salulahan / winaih / pasak pasak / ma 1 /
wdihan / yu / 1
/ pejabat tuhan wadihati / ….. / pejabat mirahmirah /
bernama sang tambalang, pejabat halaran / bernama
102
sang dulang / pejabat tuhan di makudur besatpu
bernama Sang Saluluhan/ masing-masing diberi /
hadiah / uang emas / …..masa /dan sepasang kain / 1
yugala /
36. / sowang sowang / pangurung / i / wadihati / sang
parapak / manunggu / sang basu / pagurang / i /
makudur / sang rakwel / […...] / saturung / winaih /
pasakpasak / mas / 1 / wdihan / yu / 1 / sowang /
pejabat pangurang di wadihati / bernama sang parapak
/ pejabat manunggu / bernama sang basu / pejabat
pangurang di makudur / bernama sang rakwel / .../
saturung / masing-masing diberi / hadiah uang emas /
….masa / dan sepasang kain 1 yugala
37. sowang / sang tuhan / ing / pakaranan / makabaihan
/ juru / kanayakan / i / haji pu kunda / juru wadwa rare
/ rakai sumbun juru kalang /[......]
/ sang tuhan / di / pakaranan / semuanya / juru /
kanayakan / yaitu / bernama haji pu kunda /pejabat
juru Wadwa Rare, Pejabat Rakai Sumbun, Pejabat
juru Kala /
38. ri / citralekha / walu pu dangha / an / parujar / i /
hino kandamuhi / dang-acaryya / jale / i / wka
wiridhih / dang-acryya / nanaya / i / sirikan / [.......]
…….. / pejabat citralekha Walu bernama pu denghaan
/ pejabat parujar di hino, pejabat kandamuhi /
bernama dang acaryya jale / pejabat di / wka biriwih /
bernama dang acaryya / nanaya / di / sirikan /
39. […..] / madander / dang-acaryya / prdu / i / bawang /
dang-acaryya / netra / i kanuruhan / sang rama / […..] i
/ tiruan / […...] / wadihati / [.....]
……../ pejabat madander / bernama dang acaryya
prdu / pejabat di / bawang / bernama dang acaryya
netra /pejabat di i / kanuruhan bernama sang rama /
…. / pejabat di / tiruan /….. /pejabat wadihati
(pemimpin upacara seperti makudur)/
103
40. ……k i / pakudan / sang rakwil / satagan / durang /
winaih / pasakpasak/ mas su / 1 / ma / 4 / kinabaihan
/ nira / sang citralekha / i / sri maharaja / trawaruk /
/ ………pejabat d i / pakudan / bernama sang rakwil/
pejabat kring dikerahkan dari jauh / mereka semua
diberi / phadiah / berupa uang emas / 1 / suwarna / 4
/ masa / sang citralekha / di / sri maharaja / trawaruk /
41. / kadudut / wimala / balukit / winaih / pasakpasak /
mas / su / 1 / ma / 4 / kinabaihan / nira / pinghe kalih
/ […...] / sang kuci sang / kini […...] / winaih / pasakpa
/ kadudut / wimala / balukit / mereka semua diberi /
hadiah berupa uang / emas / 1 / suwarna / 4 / masa /
dua pejabat yaitu sa(ng) kuci, sang / kini .... / masing-
masing diberi
42. sak / mas (ma) / 2 / ku / 2 / wdihan / yu / 1 / sowang
sowang / parujarnya / pingsor / hyang si pakudan /
paskaran / si badug / winaih / ma(s)/ […...] ku / 1 /
wdihan / hlai / sowang
hadiah uang emas 2 / masa / 2 kupang /dan sepasang
kain / 1 yugala / pejabar parujar bawahan dari Hyang
yaitu Si Pakundan, pejabat Paskaran yaitu Si Badug,
masing-masing diberi hadiah / berupa uang emas / 1
kupang / dan sehelai kain
43. sowang / wahu / i kidul ning / turus / sang gutul / ning /
kutesabi intik / winaih / pasak / mas / 1 / ku / 4 /
wdihan / yu 1 / sowang sowang / pangangkat i ma
/ wahu /yang ada di sebelah selatan / pagar / yaitu
sang gutul / …. / kutasabintik / masing-masing diberi /
hadiah berupa uang emas 1 masa / 4 kupang / dan
sepasang kain / …. / pejabat pengangkat
44. kudur / ma / su / 1 / ma / 4 / wdihan / yu / 1 / saji /
sang hyang brahma / mas / 10 kaharan / simsim /
prasada / mas / 1 / angsun / buah / kunda / mas /[ .….]
saji / sang hyang /
104
hyang kudur / diberi hadiah uang emas / 1 suwarna / 4
masa / dan sepasang kain / 1 yugala / sesaji / untuk
sang hyang brahma / diberi hadiah uang emas / 10
masa/ dan sebentuk cincin emas jenis persada /
mempersembahkan bejana buah dari emas sesaji
untuk sang Hyang
45. / wungkal / susuk / wdihan / yu / 4 / (?) / saji / sang
hyang kalumpang / wdihan / yu / 4 / saji / sang hyang
prthiwi / …. kan / wlah / 1 / kulambi / 1 / …. / 1 / saji
/sang / hyang / a
/ wungkal / susuk / berupa kain / 4 yugala / sesaji /
untuk sang hyang kulumpang / berupa kain / 4 yugala
/ sesaji / untuk sang hyang prthiwi / …. /sehelai kain
dan sehelai baju / sesaji untuk sang hyang a
46. kasa / wdihan / 1 / pangisi / tambukur / ma / 1/ [
…...] / 1 saji / sang hyang caturddesa / su / 1 / daksina
/ ma/ 8/ dhinarmma / sang hyang kudur / ma / 4 /
wdihan / yu / 1 [......]
akasa / sepasang kain, untuk pengisi / tempat beras
berupa uang emas 1 masa / sesasji / untuk sang hyang
caturddesa/ persembahan berupa uang emas 1
suwarna dan 8 masa / didarmma untuk sang hyang
kudur /berupa uang emas 4 / masa / sepasang kain
47. k / mandala / su / 1 / ma / 4 / karamannire / wadihati
/ su / 1 / mara / karamanire / makudur / su / 1 / ma /
4 / saji / ning / momahumah / wsi / samarja / tambaga
/ ga /
k untuk sang Hyang Mandala / 1 suwarna / 4 masa /
karamannya / wadihati / 1 / suwarna / untuk /
Karaman / makudur / 1 suwarna / 4 masa / sesaji
untuk rumah-rumah, barang dari besi, samarja,
tembaga, perunggu /
48. ngsa / prakara / in(m)as / samasanya / su / 2 / ma /
12 / ku 2 / pinakamanggalya / rikang / susukan / sima /
sira / mpu mahaguru / i / sang hyang dharmmaya /
105
gangsa / jumlah uang emasnya 2 suwarna / 12 masa /
tu……. / menjadikan kesejahteraan bagi sima yang
dibatasi, ia / mpu mahaguru / di / sang hyang
dharmmaya /
49. / ing / kasaiwan / ing / tajung / muang / sira / mpu
goksandha/ i / sang hyang dharma / i / jayamrta /
pangapanya / i / sang hyang wihantan / iy anjukladang
/ di Kasaiwan / yang ada di / tajung / dan / ia mpu
Goksandha / di / sang hyang dharmma / di /jayamrta /
pangapa ….. / di sang hyang wihantan / di /
anjukladang/
Sisi Belakang
1. [ ..........]
2. [ ..........]
3. [ ..........]
4. [ ..........]
5. [ ..........]
6. [ ..........]
7. [ ..........]
8. [ ..........]
9. [ ..........]
10. [ ..........]
11. [ ..........]
12. [ ..........]
13. [ ..........]
14. [ ..........]
15. [ ..........]
16. [ ..........]
17. [ ..........]
18. [ ..........]
19. [ ..........]
20. [ ..........]
21. [ ..........]
22. [ ..........]
106
23 . / ….. / bhuwur / dandal / marggana yikdola
lambo / winaih / pasak / ma / 1 / sowang / i /
tlasning / mawaih / pasak-pasak / i / tanda /
rakyan / muang / pinghai / wahuta / rama /
/ ……. / bhuwur / dandal / bepergian naik tanda dengan
pengawal masing-masing / diberi / hadiah/ berupa uang
emas emas / 1 / masa / setelah selesai/ memberikan /
hadiah/ kepada pejabat / tanda / rakryan / dan / pejabat
pinghai / wahuta rama.
Jadi, selama prosesi penetapan kakatikan iy-
anjukladang menjadi sima, kepala rama Anjukladang
yaitu Samgat Pu Anjukladang mebagi-bagikan hadiah
(pasek-pasek) kepada semua hadirin yang ikut
menyaksikan jalannya upacara manusuk sima. Terutama
para pejabat kerajaan, pejabat desa, dan para saksi,
terutama para pejabat desa yang berbatasan dengan
tanah sima (rama tpi siring). Bahkan, para saksi yang
datang dari jauh diberi semacam uang jalan ("sangunira
mulih" - sangu untuk pulang).
Besar-kecilnya pasak ditentukan sesuai tinggi-
rendahnya jabatan. Yaitu berupa emas, perak, dalam
tera massa (disingkat ma), suwarna (disingkat su), kati
(disingkat ka), sedangkan satuan untuk perak dinyatakan
dengan kati, dharana, masa, kupang dan disingkat
menjadi ka, dha, ma, dan ku), dan yugala dan hlai untuk
ukuran kain atau bebed.
CATATAN: Pada bait 1 samapai dengan 22, sisi
belakang tidak bisa dibaca sama sekali. Namun bila
dilihat dari bait terakhir (49) pada sisi depan dan bait 23
sisi belakang, masih membahas tentang pemberian
hadiah kepada siapa saja yang hadir, dapat dianalogikan
bahwa bait-bait yang tidak dapat dibaca, kurang lebih
mencatat tentang proses pemberian hadiah. Hal ini,
107
sebagaimana tertulis pada prasasti-prasasti penetetapan
sima era Pu Sindok yang lain, pada urutan-urutannya,
tertulis tentang pemberian hadiah.
k. Pejabat kerajaan dan daerah penguasa sebelumnya
Mungkin yang dimaksud pejabat tinggi kerajaan
dan pejabat daerah yaitu para pejabat yang ditugaskan
oleh raja untuk mengawasi dan ikut mengatur sistem
pemerintahan di kakatikan iy-anjukladang sebelum
ditetapkan sebagai sima, yaitu pejabat-pejabat pemungut
(penarik) pajak yang sejak ‘dikeluarkannya prasasti tidak
lagi diperkenankan memasuki desa yang telah dijadikan
desa suci (sakral) atau desa otonom (perdikan) bebas
pajak dan disebut Sima Swatantra. Pejabat pemungut
pajak tersebut jumlahnya cukup banyak dalam prasasti
Candi Lor disebutkan lebih dari 60 pejabat, diantaranya
yang terkenal adalah : Pangkur, Tawan, Tirip.
l. Pejabat sima dan pejabat desa sekelilingnya
Para pejabat desa sebelum ditetapkan sebagai sima
yang dimaksud adalah para pejabat yang sebelumnya
menjabat di Kakatikan iy-anjukladang dan para penarik
pajak sesuai bidangnya masing-masing.
Dalam Prasasti Candi Lor, pada bait ke 16 hingga
21 bahwa para petugas kerajaan penarik pajak terhadap
para pelaku usaha sebagai berikut;
16. (tawan tirip) / muang / saprakara / ning / mangilala
drwya haji / ing / dangu / misra paramisra / wulu
wulu / prakara pangurang / kring / padam /
manimpiki / paranakan / limus galuh / [.....]
(tawan, tirip) / dan / jenis / petugas pajak / sejak
waktu sebelumnya / seperti para perajin, berbagai
pungutan antara lain pemungut pajak, kring /
108
pemadam api/ perajin benda seni / golongan
keturunan (orang asing) / perajin emas/
17. [……..] / pangaruhan / taji / watu tajam / sukun / halu
warak / rakadut / pininglay / katanggaran / tapahaji /
airhaji / malandang / [.....]
……. / pembuat / senjata tajam / tukang gerinda
/tabib/dukun / pemimpin pertunjukkan seni /
rakadut / pininglay / juru masak istana / golongan
pendeta / golongan agama / pengatur arena
perjudian /
18. [……..] / tangkil / [……..] / saluit / watu walang /
pamanikan / maniga / sikpan / rumban wilang
wanua / wiji / kawah tingkes / mawi manambangi /
[……..] / juru [.....]
…….. / hamba yang selalu dekan dengan raja /……. /
salwit / batu menhir / perajin permata / tukang patri
/ pembuat anyaman di hulu pedang / inang
pengasuh / pencatat tanah / wiji / kawah tingkes /
petugas perahu tambangan /.......….. .../ ahli …..
19. [……..] / tuha judi / juru jalir / pasibar / pagulung /
pawungkunung / pulung padi / tuhadagang / misra
hino / wli hapu / wli wadung / wli tambang / wli
panjut / wli harg /
…….. / pengawas perjudian / mucikari / peternak /
tukang pedati / pawungkunung / petugas pertanian /
pemimpin dagang / misra hina / penjual/pembeli
apu / penjual/pembeli kapak / penjual/pembeli
tambang / penjual/pembeli kayu untuk obor /
penjual/pembeli arang /
20. […….] urutan / dampulan / tpung kawung / sungsung
/ pangurang / pasuk-alas / payungan / sipat wilut /
kalangkang / panginangin / pamawasya / hopan /
trrpan /[.....]
…… tukang uruta/ dampulan, pembuat tepung aren
/ penyambut tamu / penarik pajak / petugas hutan /
109
pembawa payung / sapan wilut ……. nkung pembuat
kapas / petugas upacara menjelang bulan baru
termasuk ( hopan …..n)
21. Skartahun / panusuh / mahaliman kdi / walyan /
mapadahi / widu mangidung / sambal sumbul /
hulun haji / pamrsi watek i jro / ityewamadi / tan /
[.....]
……. / panasuh / pemelihara gajah / dukun bayi /
mapadahi / pengidung (pesiden) / sumbal sumbul /
abdi kerajaan / pencuci baju di watek dalam/
selanjutnya / tidak
Penjelasan pejabat desa yang ditetapkan
menjadi sima dan pejabat-pejabat desa sekelilingnya
1) Rakai adalah pemimpin daerah. Di masa sekarang
mungkin bisa dikatakan merupakan jabatan yang
lebih besar dari bupati namun di bawah gubernur.
Pada periode klasik Jawa Tengah (abad 7 – 10)
para penguasa lokal bergelar rakai, rakryan i atau
rakarayan i, kemudian diikuti oleh toponim atau
nama daerah yang dipimpinnya. (Timbul Haryono,
2021. Sistem Pemerintahan dan Organisasi
Kemasyarakatan”, Medang dalam Lintasan Sejarah
Indonesia Kuno), Contohnya adalah Rakai Garung
(raja di garung), Rakai Watuhumalang (raja di
Watuhumalang), Rakai Pikatan (raja di Pikatan),
Samgat Bawang (pemimpin di Bawang), Samgat
Puluwatu (pemimpin di Puluwatu, Samgat
Anjukladang (pemimpin di Anjukladang), Samgat
Marganung (pemimpin di Marganung), dan
seterusnya.
2) Rama adalah pemimpin wanua (desa). Mantan
lurah disebut Rama marata, sementara lurah yang
masih aktif menjabat disebut Rama Magaman.
110
3) Karaman adalah Dewan para para Rama (Karaman
= tanah para Rama).
4) Ratu / Sri Maharaja adalah penguasa tertinggi
Kerajaan Medang. Ratu dipakai oleh Sanjaya sang
pendiri Kerajaan Medang. Sejak raja kedua, anak
Sanjaya yaitu Panangkaran mulai menggunakan
gelar Sri Maharaja.
5) Rakryan Binihaji adalah jabatan istri raja.
6) Rakryan Kanuruhan adalah Perdana Menteri
7) Rakryan Mahamantri i Hino adalah semacam putra
mahkota atau pejabat yang kelak menggantikan
sebagai raja. (Timbul Haryono, 2021. Sistem
Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan”,
Medang dalam Lintasan Sejarah Indonesia Kuno)
8) Rakryan Mahamantri i Halu adalah jabatan tertinggi
setelah raja
9) Rakryan Mahamantri i Sirikan adalah jabatan
tertinggi setelah raja.
10) Rakryan Mahamantri i Wka adalah jabatan tertinggi
setelah raja.
11) Rakryan adalah jabatan tinggi kerajaan yang
menerima perintah langsung dari raja, kemudian
mereka meneruskan perintah tersebut ke pejabat di
bawahnya untuk pelaksanaan operasionalnya.
Setelah jabatan Rakryan Mahamantri i Hino atau
putra mahkota ada jabatan watuhumalang, sirikan,
wk, samgat bawang, samgat tiruan, samgat
manghuri, samgat dalinan, samgat wadihati, samgat
makudur, rake halaran, rake panggilhyang, rake
wlahan, rake langka, rake tanjung, rake pagerwsi,
rake kalungwarak, pangkur, tawan, tirip, lampi, dan
sikhalan.
12) Patih atau pinghe ialah pejabat-pejabat tingkat
watak, pembantu para rakai dan pamgat yang
111
mempunyai kekuasaan atas suatu wilayah
(Boechari, 1981:72).
13) Wahuta adalah nama suatu jabatan, sering
dirangkaikan dengan titel lain, misalnya sang
wahuta hyang kudur, wahuta i kanuruhan, dan lain-
lain. Seperti halnya patih, ia pun pejabat tingkat
watak, pembantu para rakai dan pamgat.
14) Nayaka, secara harfiah berarti pemimpin. Di sini
yang dimaksud dengan istilah itu ialah para rakai
dan pamgat, yaitu para pejabat tinggi kerajaan yang
mempunyai daerah lungguh dan para penguasa
daerah (Boechori. 1981:72).
15) Pratyaya, dalam artian umum ialah pejabat yang
mengurusi pajak atau pendapatan kerajaan
(Boechari, 1981:82, cat. No. 18).
16) Pamgat (dari kata pegat yang artinya putus) secara
harfiah berarti orang yang memberi
keputusan|ketetapan. Jabatan pamgat, seperti yang
terbayang dalam prasasti, lebih akrab dengan hal-
hal yang bersifat keagamaan, hukum, dan lain-lain.
Prof. Dr. Aminidun Kasdi menyebut pamgat
sebagai seseorang yang sudah putus (lulus) ilmu
pengetahuannya. Artinya, memiliki pengetahuan
yang luas.
17) Menurut stutterheim (1925), tidak semua orang
yang tergolong manilala drabya haji itu adalah para
pemungut|pengumpul pajak kerajaan. Sepanjang
arti katanya dapat diketahui jelas bahwa sebagian
dari manilala drabya haji itu ialah ‘abdi dalem
kraton’ yang tidak mempunyai ‘daerah lungguh’
sehingga hidupnya tergantung dari ‘gaji’ yang
diambil dari perbendaharaan kerajaan atau drabya
haji (Boechari, 1977 : 13).
18) Misra paramisra (bentuk jamak dari misra?) ialah
suatu kelompok jabatan yang termasuk golongan
112
manilala drabya haji. Termasuk di dalam kelompok
ini diduga ialah misra hino, misraninanin, dan
sebagainya (Zoetmoulder I, 1982: 1143). Kata
misra yang terdapat di dalam ungkapan: ---- kunong
misra manambul, manawring, manglakha, manapus
---- dan sebagainya, sering ditafsirkan sebagai pajak
usaha kerajinan (Boechari, 1981:67). Barangkali
misra paramisra adalah para petugas yang
memungut pajak usaha kerajinan.
19) Wulu wulu adalah golongan orang dari status sosial
rendah atau orang yang mempunyai kedudukan |
jabatan yang dianggap rendah (Zoetmulder II,
1982:2326). Di antara manilala drabya haji, orang-
orang seperti hulun haji, pandak, jenggi, bhondan,
pamrsi, widu, manidung, dan lain-lain mungkin
dapat digolongkan sebagai wulu wulu.
20) Panurang kring adalah pendeta yang meminta-
minta (Wojowasito, 1977:47).
21) Kadang-kadang ditulis padam apuy, yaitu denda
yang dikenakan terhadap orang yang membakar
milik raja (Stutterheim, 1925:247). Kemungkinan
besar padam (apuy) adalah petugas pemadam
kebakaran yang juga menarik pajak denda terhadap
orang yang melakukan pembakaran.
22) Manimpiki adalah orang yang menciptakan sesuatu
yang indah misalnya dalang, tukang ukir, dan lain-
lain (Sutterheim, 1925:250).
23) Mungkin sama dengan ‘peranakan’ dalam bahasa
Jawa baru atau bahasa Sunda sekarang yang berarti
anak hasil perkawinan dari dua bangsa yang
berbeda. Bisa jadi yang dimaksud dengan
peranakan di sini adalah anak hasil perkawinan
campuran antara dua kasta yang berbeda dan hidup
di dalam lingkungan istana (Titi Surti Nastiti, et.al.,
1982:42, cat. No. 29).
113
24) Menurut Sutterheim (1925:248) panaruhan adalah
tukang emas. Seperti yang dinyatakan dalam
Prasasti Salingsingan tahun 802 Saka (Cohen Stuart,
KO, X), Sang Panaruhan Pu catra mendapat
pesanan dari raja Kayuwangi untuk membuatkan
payung perak dengan puncak berlapis emas.
25) Kadang kala ditulis rataji (ra = prefix honorefix?).
Taji artinya benda dari logam yang tajam yang biasa
dikaitkan pada kaki ayam sabungan (Stuttrheim,
1925:40; Zoetmulder II, 1982:1902). Mungkin
(ra)taji adalah orang yang pekerjaannya membuat
taji atau bertugas memungut pajak dari sabung
ayam.
26) Watu tajam menurut Stutterheim (1925:249)
adalah ‘batu asahan’. Di sini maksudnya adalah
tukang asah senjata tajam.
27) Sukun (=dukun?) adalah sebutan lain untuk balian
yang memohonkan kesembuhan kepada dewa
untuk si sakit (Stutterheim, 1925:249).
28) Malandang (Bali:mlandang) adalah petugas yang
mengatur arena perjudian atau sabung ayam serta
menarik pajak 10% darinya (Zoetmulder I,
1982:1093; Stutterheim, 1925:251). Di daerah Jawa
Barat pun dikenal istilah mlandang, yaitu petugas
arena ‘adu bagong’ yang berupaya agar tontonan
tersebut tetap menarik perhatian.
Catatan: Di wilayah kecamatan Pace, Kabupaten
Nganjuk arah Tenggara Desa Candilor ada nama
Desa Mlandangan, jarak tidak jauh dari Kakatikan
iy-Anjukladang. Mungkinkah nama desa
Mlandangan memiliki hubungan nama (toponimi)
dengan Malandang atau mlandang, perlu kajian
lebih lanjut.
29) Lca menurut Stutterheim (1925:252) adalah
pinggiran dari arena sabung ayam. Barangkali
114
masih ada hubungannya dengan malandang, yaitu
petugas yang mengatur arena sabung ayam.
Catatan : Sisi barat Desa Mlandangan ada wilayah
Loceret, yaitu wilayah dimana Kakatikan iy-
Anjukladang berada. Mungkinkah, kata Loceret
memiliki kemiripan toponimi dengan kata Lca,
perlu kajian lebih lanjut.
30) Tankil, kata bentukannya adalah tankilan, yaitu
tempat alat musik gendang (padahl) dibuat.
(Zoetmulder II, 1982:1943). Di dalam prasasti
Linggasutan juga ada ungkapan: A. 23 ---- padahl
tlung tankilan ---- Mungkin tankil adalah petugas
yang menarik pajak atas pembuat-pembuat
gendang.
31) Trpan, seperti dijumpai di dalam prasasti Barsahan
(JBG, V, 1938:119-120) adalah nama sejenis
pungutan (pajak) atau orang yang diserahi tugas
mengumpulkan buncang haji. Ungkapannya sebagai
berikut: a 12. ---- kinawnanakan yang paka purwwa
sthiting mawwat karung siki mijil ankan manatag i
sira wineh trpan. Samankana denya samgat trpan
kalih, pu sudhasaya, muang |3| pu omo ----
32) Saluit, dengan variasi kata; salwit, salyut, dan
mungkin juga salukat adalah sejenis alat musik tiup
(stutterheim, 925:253). Mungkin saluit adalah
peniup seruling istana.
33) Mangrumbai oleh Juynboll (1923:475) ditafsirkan
sebagai orang yang pekerjaannya memuja dan
berdoa.
34) Manggunjai adalah orang yang pekerjaannya
membuat alat-alat untuk pemujaan (Stutterheim,
1925:254).
35) Watu Walang menurut Stutterheim, 1925:254)
dapat ditafsirkan sebagai watu madeg (=menhir?),
yaitu tempat dewa atau arwah leluhur
115
bersemayam|dipuja. Mungkin yang dimaksud
dengan ungkapan itu adalah petugas yang
mengurusi tempat-tempat keramat di mana
‘menhir’ itu berada.
36) Sikpan, mungkin dari kata sikep yang artinya
peralatan / persenjataan (Zoetmulder II,
1982:1763). Mungkin sikpan adalah orang yang
bertugas merawat benda-benda pusaka keraton
seperti keris, tombak, pedang dan lain-lain, atau
bisa juga ditafsirkan sebagai petugas yang menarik
pajak atas pembuatan alat-alat senjata.
37) Sering juga ditulis menjadi limbah kawah. Limbah
kurang lebih berarti ‘buangan’, sedangkan kawah
mungkin sama dengan ‘air kawah’ dalam bahasa
Indonesia, yaitu cairan (darah) yang keluar pada
saat melahirkan. Jadi wiji kawah (mungkin
seharusnya bukan wiji tetapi wijik dalam bahasa
Jawa Baru artinya ‘membasuh’) secara harfiah
berarti ‘mandi nifas’ (stutterheim, 1925:257-258).
Mungkin yang dimaksud ‘dukun beranak’ yang
menerima upah atas pekerjaannya itu.
38) Tinkes (=tikes?), oleh Stutterhem (1925:257)
ditafsirkan ‘tameng’ atau ‘perisai’. Di sini mungkin
yang dimaksud adalah prajurit atau pasukan
pengawal kerajaan yang berperisai.
39) Misra hino mungkin dapat diartikan sebagai misra
dari rakai hino. Misra, seperti pada catatan no. 18,
adalah pajak usaha kerajinan. Misra hino dapat
diartikan sebagai bawahan rakai hino yang bertugas
memungut pajak usaha kerajinan.
40) Palamak, dari kata lamak (Jawa Baru:lemekan)
artinya alas, tatakan (di atas meja) atau tikar.
Mungkin palamak adalah orang yang pekerjaannya
membuat alas kaki, tatakan atau tikar.
116
41) Pohon murbei yang diambil daunnya ini telah lama
dikenal sebagai makanan ulat-ulat sutera yang
sengaja dipelihara untuk menghasilkan benang-
benang halus, kemudian diolah menjadi kain
sutera. Dengan kata lain, pabisar (=pabesar) adalah
pembuat kain sutera juga.
42) Paninanin (=misraninanin?), barangkali dari pokok
kata aninanin yang artinya arus angin yang
ditimbulkan dari suatu hembusan (Zoetmulder I,
1982:102). Mungkin pekerjaan paninanin ada
hubungannya dengan pertukangan logam (pandai
wsi, pandai mas, pandai tamwaga, dan lain-lain),
yaitu orang yang bertugas memompakan udara dari
ububan ke tungku pembakaran.
43) Panawasya, mungkin berasal dari kata bahasa
sansekerta amavasya, artinya ‘bulan baru’
(Zoetmulder I, 1928:57; Stutterheim, 1925:262-
264). Mungkin pamawaya adalah orang yang ahli
dalam menentukan bulan baru. Perlu diketahui
bahwa untuk menentukan pergantian bulan,
misalnya dari bulan Phalguna ke Caitra, harus
memiliki pengetahuan tentang peredaran bulan
mengelilingi bumi dari satu fasa ke fasa yang lain.
Periode dan bulan baru ke bulan baru berikutnya
disebut 1 bulan sinodik (=29,53059 hari).
44) Hopan adalah nama sejenis pungutan|pajak. Di
dalam prasasti Kiringan (AMB Jones, 1984:195)
misalnya, dijumpai ungkapan: 1.3. ---- tan kna ing
hopan bwat haji awur prakara ---- ungkapan itu
menunjukkan bahwa pejabat-pejabat tertentu tidak
diperkenankan lagi memungut hopan di daerah
perdikan.
45) Turun turun adalah nama sejenis pajak. Di dalam
beberapa prasasti ada disebutkan dua jenis pajak
turun turun, yaitu turun sakupang satak di dalam
117
prasasti Kalagen tahun 959 Saka (OJO, LXI), dan
turun turun sagem sarakut di dalam prasasti
Sendang Sedati tahun 395 Saka (Bosc, 1922:22-27).
Hanya sayang belum diketahui keterangan
mengenai itu.
46) Panranan, dari kata srang (?) yang artinya ‘cepat-
cepat, mendesak, buru-buru’ (Wojowasito,
1977:249). Mungkin panranan adalah seseorang
yang menjalankan tugasnya harus selalu cepat,
misalnya petugas pembawa berita atau kurir.
47) Skartahun menurut Stutterheim, (1925:262-263)
adalah rente (bunga) tahunan atau upeti tahunan.
Di sini maksudnya adalah pejabat pemungut upeti
tahunan.
48) Sambal sumbul, yang kemudian menjadi ‘umbul
umbul?’ (Stutterheim, 1925:265), ialah semacam
bendera kerajaan yang biasa dibawa ketika ada
arak-arakan (prosesi). Sambal sumbul mungkin
adalah orang yang ditugasi membawa umbul-umbul
ini.
49) Watak i jro adalah para abdi raja yang tinggal di
dalam lingkungan tembok kota (jero benteng) dan
di dalam lingkungan tembok istana. Termasuk ke
dalam golongan ini adalah antara lain pujut, jenggi,
pandak, rawanahasra, juru padahi, widu, manidung,
dan mapayungan.
50) Juru Wadwa Rare adalah petugas yang menangani
kelompok pemuda (seperti: karang taruna)
Jadi, para pejabat sebelum ditetapkan sebagai sima
diantaranya; Pejabat samgat bernama Pu Anjukladang,
menjabat kepala rama, tokoh agama, dan sang pamegat
(pemutus perkara) di lemah sawah Kakatikan iy-
anjukladang. Mpu Mahaguru, menjabat sebagai
dharmamaya di Kasaiwan Tajung (penanggungjawab
118
perguruan keagamaan agama Hindu aliran Shiwa). Mpu
Goksandha, menjabat sebagai dharmmaya dan wihantan
di lemah sawah Kakatikan iy-anjukladang, (sebagai
orang yang mengurusi bangunan suci ‘prasada
kabhaktyan’ agama Hindu (dharmmaya) dan Budha
(wihantan).
Juga para pejabat desa yang mengurusi sistem
pemerintahan dan para petugas pemungut pajak di
kakatikan iy-anjukladang. Sedangkan para pejabat desa
sekelilingnya, adalah pejabat desa tpisiring (tetangga)
yang diundang dalam proses penetapan sima. Karena
mereka ikut menyaksikan jalannya upacara manusuk
sima sekaligus sebagai tamu undangan.
m. Saji-sajian
Sajian untuk watu kulumpang, sajian ini berupa
peralatan atau benda-benda tertentu yang memiliki arti
simbolik tertentu. Benda tersebut jika dikelompokkan
menjadi perlengkapan dapur dari bahan tembaga dan
perunggu, peralatan makan minum, perlengkapan
pertanian, perkebunan dan pertukangan, binatang hidup
serta kepala kerbau, alat senjata, beras dan jajan pasar,
serta lima jenis bahan upacara diantaranya kemenyan
dan bunga (Haryono, 1999).
Rahardjo (2011:306) menambahkan setidaknya
ada 42 jenis benda sajian untuk watu kulumpang.
n. Upacara penetapan sumpah
Penetapan tanah sĩma merupakan hal yang sakral.
Tidak semua daerah dengan mudah mendapat anugerah
Sĩma. Untuk melegalkan suatu daerah menjadi Sĩma,
diperlukan upacara khusus. Ritual upacara tersebut
menurut Haryono (1999:16) terdiri dari beberapa
urutan sebagai berikut: 1) pemberian pasek-pasek; 2)
perlengkapan sesaji; 3) pendeta memimpin upacara
119
ditandai dengan Sang Makudur memotong leher ayam
dan memecah telur; 4) Sang Makudur menyembah
kepada Sang Syang Watu Sĩma; 5) pengucapan sumpah
kutukan kepada mereka yang melanggar; dan 6) pesta
makan minum.
Pembagian pasek-pasek pada awal upacara
diberikan oleh penerima Sĩma kepada saksi-saksi, terdiri
dari para pejabat pusat, pejabat desa, dan warga desa.
Harta kekayaan yang dibagikan berupa hadiah,
umumnya berupa pakaian laki-laki, pakaian wanita (kain
atau ken), logam mulia dalam bentuk perak dan emas.
Jumlah pasek yang diberikan tidak sama, nilainya
disesuaikan dengan tingkat jabatan dan status sosial
individu yang menerima hadiah. Pejabat yang lebih
tinggi akan menerima pasek-pasek dengan kualitas lebih
tinggi daripada yang kedudukannya lebih rendah.
Upacara penetapan Sĩma dipimpin oleh Sang
Makudur (yang mengurusi bidang keagamaan). Dalam
prosesinya, pemimpin upacara duduk mengelilingi
obyek utama yaitu Sang Hyang Watu Sĩma dan
Kulumpang. Keduanya merupakan batu yang diletakkan
di tengah-tengah tempat upacara. Batu tersebut ditanam
oleh Sang Makudur. Kedua batu tersebut mempunyai
fungsi utama dan sakral karena menjadi pusat proses
pelaksanaan upacara, selain itu ada pula batu yang
sangat penting sebagai tanda batas tanah. “...
sinunukanya ya watu Sĩma srang du... “, artinya:
ditancapi batu Sĩmadi sudut-sudut tanah Sĩma. Batu
tersebut yaitu wungkal susuk Sĩma yang ditanam pada
titik-titik batas daerah ditetapkannya Sĩma.
Pengucapan mantra dan sumpah, merupakan
pernyataan simbolis yang ditujukan kepada siapa saja
yang melanggar ketentuan Sĩma. Ritual ini dibarengi
dengan memotong kepala ayam dan membanting telur.
Maksud dari ritual tersebut adalah agar terdapat
120
hubungan magis simbolis terhadap orang-orang yang
di kemudian hari mengganggu keberadaan tanah Sĩma.
Dalam prasasti dinyatakan bahwa orang yang
mengganggu keberadaan Sĩma akan mendapatkan mala
petaka.
Isi kutukan Pu Sindok melalui Sang Makudur
dalam penetapan Sima iy-Anjukladang, seperti tertuang
dalam Prasasti Candi Lor bait ke-24 hingga ke-36, sisi
belakang, sebagai berikut;
24 / [……] / ing / dangu / pinarnnah / ikanang / saji / i /
sang / makudur / i / sor / ning / witana / i / tngah / ni /
paglaran / sawidhi widhana / sakramaning / manusuk
/
/ …... / sejak/dahulu / berkenaan/ sesaji / kepada /
sang / makudur / di / bawah / di / bangsal / di /
tengah / upacara mengatur pelaksanaan jalannya
upacara penetapan /
25 / [……] / mangaskara / sang / hyang / susuk / watu /
kulumpang / mamuja / i / sang / hyang / brahma /
malawu / ing / dasadesa / mangdiri / ta / sang /
makudur / ma ….. / li mottarasangga /[….] / bandhana
/ ta
/ … / menghormat / sang / hyang / susuk / watu /
kulumpang / memuja / kepada / sang / hyang /
brahma / yang menguasai / 10 desa / berdirilah / sang
/ makudur / ma……./ li berebut mendukung/… /
ikatlah / ta
26 / […..] / lawan / sang / wadihati / manganjali / i/ sang /
hyang teas / malungguh / i / sor / ning / witana / ma(
)lan padahumarepakan / sang / hyang / susuk / watu /
kulumpang / hinarep /
/ … / dan/ sang / wadihati / menyembah /kepada sang
/ hyang teas / duduk / di / bawah / bangsal / semua /
121
menghadap / kepada sang / hyang / susuk / watu /
kulumpang / di hadapannya /
27 / [……] / pinghai / wahuta / rama / tpi siring / kapua /
mapangalih sopacara manguyut / ta / sang makudur /
manetek / gulu / ni(ng) / hayam / linandesakakan /
ing / kulumpang / mamantingakan /
/ …… / pejabat pinghai / wahuta, kepala desa di
sekitar / semuanya/ juga mengikuti upacara / mulailah
/ sang makudur / memenggal / kepala ayam /
berlandaskan / pada / kulumpang / membantingkan
/
28 / hantlu / ing / watu sima / mamangmang /
manapathe / saminangmang / nira / ring / dangu / i /
kateguhakna / sang hyang/ watu sima / ikana ling nira
indah / ta / kita kamung / hyang i sri haricandana /
a(ga)
/ telur / di / batu sima / menyumpah / mengutuk /
seperti yang dikutukkan oleh mereka sejak dahulu
saat meneguhkan sang hyang watu sima di sana
katanya dengarlah olehmu Hyang di Sri
Haricandana, A(ga)
29 sti / maharsi / purwa / daksina / pascimottaramaddya
/ urddhamadhah / rawisasiksiti / jala pawana /
yajamanakasa / dharmma / ahoratra / […..] / yahwu /
jaya / yaksa / raksa
sti, maharsi / purwa / daksina / pascimottaramaddhya
/ urddhawamadhah / rawisasiksiti / jalapawana /
yajamana / akala / dharma / ahoratra /…… / yahwu (?)
jaya / yaksa / raksa
30 sa / pisaca / pretasura / garuda / gandharwwa / bhuta /
kinnara / mahoraga / catur …. / kapila / yamabaruna /
kuwera / basawa / muang / putradewata / pancakusika
/ nandiswara / ma
sa / pisaca / pretasura / garuda / gandharwwa / bhuta /
kinnara / mahoraga / catur ……….. / kapila /
122
yumabaruna / kuwera / basawa / dan / putradewaata
/ pancakusika / nandiswara / ma
31 [………] / nagaraja / durggadewi / caturasra/ ananta /
surendra / ananta / hyang / kala / mrtyu / gana / bhuta
/ kita / praiddha / mangraksa / kadatuan / rahyang / ta
/i/
……….. / nagaraja / durggadewi / caturasra / ananta /
surendra / ananta / hyang / kala / mrtyu / gana / bhuta
/ anda / semua / yang / menjaga / kerajaan / para /
raja /di /
32 / mdang / i / bhumi / mataram / i [watugaluh] / kita /
umilu / manarira / umasuk / i / sarwwasarira / kita /
sa(ka)la / saksibhuta / tumon / madoh / lawan /
mapare / ing / rahina / ing / wngi / at renge
/ mdang / di / bhumi / mataram / di / ………… engkau
/ yang / ikuti menjilma memasuki / ke segala /
makhluk / engkau / semua yang menjadi saksi,
melihat / jauh / dan / dekat / di siang hari / maupun /
malam hari / dengarlah! /
33 (akan ta) iking / samaya / sapatha / sumpah /
pamangmang / mami / i / kita / hiyang / kabeh / yawat
/ ikanang / wang / duracara / tan / magam / tan /
makmit / irikang / […..] / hakani /[......]
…………../ yang / berjanji / mengutuk / inilah /
sumpahku / kepada / kamu / dewa semua / …………/
jika ada orang yang berniat jahat tidak melaksanakan
dan melindungi kepada / ………. / hakani /
34 [………] / hyang / kudur / brahmana / ksatriya / wesya
/ sudra / hajuan/ hulun / matuha / raray / lakilaki /
wadwan / wiku / grhasta / pinghai / wahuta / rama /
nayaka / [......]
……… / hyang / kudur / brahmana / ksatryan / wesya /
sudra / bangsawan / tua / muda / laki-laki /
perempuan / biksu / kepala keluarga / pejabat
pinghai / wahuta / rama / nayaka /
123
35 [……] / umulahulah ike / lmah / sawah / kakatikan /
iy-anjukladang / tutugan-i / tanda / sima / inarpanakan
/ i / samgat / anjukladang / [......]
……………………. / mengganggu / tanah / sawah /
kakatikan (milik) / anjukladang / sampai dengan
Tanda sima dipersembahkan oleh pejabat samgat
bernama anjukladang
36 [………] / i / bhatara / sang / hyang / prasada /
kabhaktyan / i / sri jayamrta / ing / dlaha / hlam / an
babaka(n) / [......]
……………………….. kepada bhatara / sang / hyang /
prasada / kabhaktyan / untuk / sri jayamrta/ sampai
akhir masa
37. [ ..........]
38. [...........]
39. [...........]
40. [...........]
41. [...........]
42. [...........]
43. [...........]
44. [...........]
45. [...........]
46. [...........]
47. [...........]
48. [...........]
49. [...........]
50. [...........]
Sisi Kanan:
(aus tak terbaca)
Sisi Kiri:
(aus tak terbaca)
124
Sumber terjemahan: Edhie Wurjantoro, 2018. Anugerah Sri
Maharaja Kumpulan Alihaksara dan alih bahasa prasasti-
prasasti Jawa Kuno dari abad VIII-XI; oud-javaansche
oorkonden Nagelaten Transscrities Van Wijlen Dr. J.L.A.
Brandes, Uitgegeven door Dr. N.J. Krom,1818, Batavia,
albrecht & Co.; P.J.Zoetmulder & S.O. Robson, 1994.
Kamus Jawa Kuno Indonesia, Jakarta; PT. Gramedia
Pustaka Utama; Sumber alih bahasa: Museum Nasional.
o. Upacara penetapan sima dengan makan - minum dan
bermacam pertunjukan
Proses terakhir upacara penetapan sima ditandai
dengan makan, minum dan bermacam-macam
pertunjukkan. Sebagaimana tertulis pada prasasti
penetapan sima Gulunggulung (581 Saka atau 929
Masehi), kurang lebih upacara penetapan sima diakhiri
kegiatan sebagai berikut;
[----------]
yan lingnira ri tlas ning manusuk
(lu)mkas ta makurn kurn ni sira ka
baih ma(ng)glar kawung skul paripurna
(hara) hara sankap wulu ka
ndari kadiwas deng hanang deng
hasil slar capa capa, ruma
han hurang bilunglung hala ha
la hantiga inari, wulu ning ga
(na)n misaka atak sisir
takih kasyan litlit ga
nan tlu saranak alap alap
irahirah kuluban tetis
lumkas ta sira kabaih manadah ma
manahapparka cinca twari pranadi tka
ring pinda pitiga winuwuhan ta sira ta
(mbu)l pa-------------------
125
[---------]
[---------]
baih washiata ganan wineha
n ta sira jnu skar, tlas sankap mu
wah ta sira manadah yatha su
kha menmen rakyan
kahanan rikang kala ka
pua umitonakan wana
nya matapukan cucup pramukha
winaih ma 4 kinabaihanya ma
wayang kalunasu, srawana wi
naih ma 4 kinabaihanya, aba
nol si liwuhan hi
tip pramukha winaih ma
4 kinabaihanya, (cihna)
(nya) tlas mapageh --------
[---------]
Demikian katanya. Selesai membatasi (tanah perdikan)
Segeralah mereka semua berkumpul
Menghamparkan (tikar dari) daun pohon enau dan
meletakkan) nasi paripurna.
Di tanah lapang, lengkap (dengan lauk pauk) wulu
Kandari (?), ikan kadiwas, dendeng tawar|tak
berbumbu, dendeng
asin, ikan selar, capa capa (?), ikan kembung,
udang, ikan bilunglung, ikan hala hala,
telur rebus (?), sayur pucuk bambu muda|rebung,
misaka (?), kacang, sisir (?),
takih, kasyan (?), litlit,
Sayur tlu, saranak (?), daging burung alap-alap
Irahirah (?), kuluban, dan tetis
Mulailah mereka semua makan dan
Minum arak (?), cinca, dan tuak. (Mereka) menenggak
minuman keras sampai
126
Sebanyak tiga kali. Disodorkanlah tambahan untuk
mereka
Lauk pauk -------------
[ ------------- ]
[ -------------]
Semua membasuh tangan dan diberikan
Kepada mereka bedak dan kembang wangi. Sudah siap
Mereka kembali makan sepuas-puasnya
(sambil menyaksikan) tarian topeng. (Para) Rakryan
Kebetulan waktu itu semuanya (ikut)
Mempertunjukkan tariannya.
Para penari topeng (dengan) pucuk pemimpinnya
Diberi hadiah uang emas) 4 masa kesemuanya.
Pemain wayang|dalang (bernama) Kalunasu dan
Srawana
Diberi (hadiah uang emas) 4 masa kesemuanya.
Para pelawak (bernama) si Liwuhan dan Hitip sebagai
pemimpinnya diberi hadiah uang emas
4 masa kesemuanya. [inilah tandanya]
Telah menjadi kukuh -------------
[ ----------- ]
Keterangan:
Nasi paripurna adalah nasi yang lengkap. Mungkin nasi
yang dimaksud adalah nasi tumpeng yang sering
disediakan pada waktu upacara selamatan (TS Nastiti,
et.al, 1982:51 cat.132).
‘Takih’, mungkin sejenis makanan yang dibungkus daun
kelapa (semacam ketupat?)
‘Litlit’ artinya ‘serbuk’; bubuk; butir-butir halus’
(Wojowasito, 1977:157). Mungkin yang dimaksud
adalah makanan yang berupa bubuk, misalnya kacang-
kacangan seperti kacang tanah, kedelai, dan sebagainya
yang ditumbuh halus.
127
‘Kuluban’ adalah sejenis lalapan rebus yang hingga
sekarang masih dikenal masyarakat Jawa. Biasanya
berupa sayuran kangkung, tauge, kacang panjang, dan
lain-lain, yang diurap bersama kelapa parutan.
‘Tetis’ adalah sejenis sambal atau petis
‘Cinca’ (Skrt: cinca) adalah sejenis minuman ringan
semacam sirup yang dibuat dari buah ---- (Zoetmulder I,
1982:873).
Hanya saja di dalam Prasasti Anjukladang, bait-bait yang
menyebutkan tentang upacara penetapan sima dengan
makan, minum dan bermacam pertunjukan tidak bisa
dibaca karena tulisan rusak. Yang seharusnya, bait-bait
terakhir ini tertulis dalam sisi kanan dan kiri prasasti.
Namun demikian dapat dianalogikan bahwa isi prasasti
pada pemerintahan Mataram Medang era Pu Sindok ini
memiliki karakteristik dan sistematika yang sama.
p. Citralekha
Citralekha adalah petugas pencatatan atau orang
yang mengurusi dokumen resmi. Juga sebutan bagi
orang yang berwenang untuk membuat prasasti. Seperti
yang telah diketahui, prasasti adalah tulisan yang
diguratkan di media yang tahan lama, contohnya batu
dan logam. Jika pada masa sekarang, setiap orang
memiliki gaya tulisannya sendiri-sendiri, begitu juga
dengan citralekha. Tulisan pada prasasti walau sepintas
terlihat sama, namun ternyata memiliki ciri khasnya
masing-masing tergantung dengan gaya sang citralekha
itu sendiri. Sebelum memahat tulisan di media,
citralekha terlebih dahulu menulisnya menggunakan
arang atau kapur. Kemudian prasasti baru diukir
menggunakan alat ukiran seperti tatah.
Darmosoentopo, (2003), proses penetapan sima
didahului dengan pembahasan di dalam lembaga
kerajaan yang disebut “lembaga sima”. Setiap kali raja
128
atau penguasa akan memberi anugerah atau mencabut
status sima, raja atau penguasa memberi tahu pimpinan
lembaga sima untuk mengatur dan mempersiapkan
sesgala sesuatunya.
Kemudian, lembaga sima menugaskan pejabat
wilang thani (petugas sensus) untuk mencatat status
kependudukan tanah yang akan dijadikan sima.
Selanjutnya, menentukan empat atau delapan titik sudut
desa di sekilingnya, yang pada saat upacara manusuk
sima akan ditanpai batu patok atau watu susuk sima.
Lembaga sima juga menugaskan pejabat penarik
pajak, mangilala drwaya haji untuk menghitung
penghasilan tanah sima, yaitu berupa hasil pajak tanah,
perdagangan, usaha, kerajinan, keluarga, orang asing,
dan pengabdian wajib (buatthaji).
Lembaga sima juga mencatat, siapa yang akan
menerima anugerah sima, baik perorangan maupun
untuk menyokong bangunan suci.
Lembaga sima juga mengatur penetapan sima
dengan berbagai persiapannya. Diantaranya, persiapan
pejabat yang mengurus prosesi manusuk sima, serta
sarana dan prasarananya.
Terakhir, lembaga sima juga mengatur arsip yang
akan dijadikan media untuk menuliskan isi prasasti.
Diantaranya, dari bahan emas, perak, perunggu, atau
batu.
Untuk memutuskan proses penetapan sima,
tentunya melibatkan banyak pihak. Mereka adalah
wilang thani, citralekha, petugas penarik pajak,
penduduk desa, para wajib pajak, pemimpin catur desa
atau panastta desa, calon penerima anugerah sima, dan
lain-lain.
Sebagaimana penetapan lemah sawah Kakatikan i-
yanjukladang menjadi sebuah sima, tentu saja melalui
129
proses yang sama, sebelum keputusan raja dituliskan
pada prasasti.
Nugroho Notosusanto, dkk., menyebutkan, titah
raja itu pertama-tama diterima oleh putra mahkota dan
para pangeran, lalu diteruskan kepada pejabat eksekutif.
Dalam penetapan sima, dibuatkan surat keputusan yang
ditulis oleh citralekha kerajaan di atas daun lontar
(ripta). Surat keputusan berupa prasasti di atas daun
lontar itu kemudian dibawa oleh pejabat daerah yang
datang menghadap bersama para rama ke desa yang
ditetapkan menjadi sima. (2009:248-249)
Dalam prasasti tersebut menyebutkan bahwa raja
yang memerintah adalah Pu Sindok, raja Mataram
Medang. Sedangkan pejabat di bawah raja yang
diperintah adalah mapinghai kalih Rakai Hino Pu
Sahasra dan Rakai Wka Pu Baliswara.
Perintah raja tersebut dilaksanakan kepada seorang
pejabat eksekutif (pelaksana) bernama Rakai Kanuruhan
Pu Da agar tanah sawah Kakatikan iy-anjukladang
dipersembahkan kepada Bhatara di prasada kabhaktian
sebagai dharmma pejabat Samgat bernama Pu
Anjukladang. (Prasasti Anjukladang, 937 M).
Tampak di sini peran citralekha sangat penting,
karena ia bertugas untuk menuliskan isi keputusan sima
pada ripta sebelum kemudian digoreskan pada media
prasasti, seperti tembaga atau batu.
5. Anugerah Sima Anjukladang
Merujuk kepada pernyataan de Casparis tentang
peristiwa perpindahan kerajaan Mataram Medang dari Jawa
Tengah ke Jawa Timur dikaitkan dengan kata malaga
(prasasti Candi Lor, 937 Masehi) yang berarti yaitu usaha
dari dinasti Syailendra menyerang kerajaan Sindok.
Darmosoentopo, karena kerajaan Mataram di Jawa
Tengah mengalami kehancuran karena letusan Gunung
130
Merapi yang maha dahsyat, sehingga dianggap sebagai
pralaya (kehancuran dunia pada akhir masa Kaliyuga),
sesuai dengan landasan kosmologi, kerajaan-kerajaan kuno
harus dibangun kerajaan baru dengan wangsa baru pula,
sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu wangsa Isana.
Sedangkan Harimintadji, (2009) dan Komunitas
Pecinta Sejarah Nganjuk (Kotasejuk) menyimpulkan bahwa
perpindahan kerajaan Mataram Medang dari Jawa tengah ke
Jawa Timur, selain akibat letusan Gunung Merapi yang
maha dahsyat dan penyerangan dari dinasti Syailendra
kepada kerajaan Sindok, juga terjadi akibat sistem
perekonomian yang terus melemah serta rong-rongan dari
kerajaan vasal di Jawa Tengah, yang bersekutu dengan
dinasti Syailendra di Sumatera.
Penyerangan dinasti Syailendra dari Sumatera (928 –
929 Masehi) terjadi hingga di Jawa Timur, disebutkan
dengan kata malaga (prasasti Anjukladang) dan bukti tugu
kemenagan jayastambha. Di Jawa Timur, penyerangan
terjadi di bumi Kakatikan iy-anjukladang hingga mencapai
kemenangan.
Kepada rakyat kakatikan iy-anjukladang, lantas Pu
Sindok menganugerahkan sebuah tanah perdikan
(swatantra) bebas dari kewajiban membayar pajak atas
jasanya membantu mengalahkan musuh dari dinasti
Syailendra Sumatera.
Hal menarik yang perlu mendapat kajian adalah:
a. Saat perang melawan dinasti Syailendra dari Sumatera,
Mataram Medang dalam kondisi masa kaliyuga, artinya
kerajaan dalam kondisi kehancuran, akibat Gunung
Merapi meletus, kalah perang di Jawa Tengah, rong-
rongan kerajaan vatsal, dan faktor ekonomi. Namun
diceritakan, pasukan Pu Sindok dibantu rakyat sipil dari
Kakatikan iy-anjukladang dapat mengalahkan musuh.
131
b. Tampaknya ada suatu misteri kekuatan luar biasa yang
dimiliki oleh rakyat sipil kakatikan iy-anjukladang,
sehingga dapat mengalahkan musuh (malayu) yang
notabene-nya memiliki jumlah prajurit lebih terlatih,
berpengalaman perang dengan senjata dan perbekalan
lengkap.
c. Mengapa Pu Sindok memberikan anugerah penetapan
tanah sima atau hak swantaran, bebas dari pembayaran
pajak, bukan atas permohonan rakyat kakatikan iy-
anjukladang, melainkan atas inisiatif raja pu Sindok
sendiri? (Nugroho Notosusanto, 2009).
d. Mengapa pemberian prasasti penetapan sima tidak
langsung diberikan kepada rakyat kakatikan iy-
anjukladang setelah perang (928 – 929 Masehi), dan baru
8 tahun kemudian, tahun 937 Masehi?
Pernahkah terpikirkan bahwa keberadaan kerajaan-
kerajaan besar di Nusantara, seperti Kahuripan, Kadiri,
Singosari, Majapahit, Mataram Islam, dan kerajaan-kerajaan
segaris keturunannya berkat jasa rakyat kakatikan iy-
anjukladang yang ada di Desa Candirejo, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur?
Penulis mencoba menggali potensi sejarah yang
sempat terlupakan, kendati mulai terungkap fakta-fakta
sejarah dan bukti pendukung yang menyebutkan bahwa
lemah sawah kakatikan iy-anjukladang sebagai tonggak
sejarah kelanjutan trah Mataram dan berdirinya kerajaan-
kerajaan di Jawa setelah wangsa Isana, di antaranya Kerajaan
Kahuripan, Kediri, Singosari, Majapahit, Mataram Islam,
dan seterusnya.
Tidak terbantahkan bila Pu Sindok bersama
pengikutnya yang masih tersisa akibat kalah perang kaliyuga
(928 M – 929 M) melawan prajurit Swarnadwipa Sriwijaya
dan sekutunya ketika sampai di kakatikan iy-anjukladang
132
juga mengalami kekalahan yang sama dan Pu Sindok
terbunuh?.
Niscaya, trah Mataram Medang telah berakhir pada
saat perang di bumi kakatikan iy-anjukladang saat itu juga.
Sehingga tidak mungkin lagi ada Kerajaan Kahuripan,
Kediri, Singosari, Majapahit, Mataram Islam, serta
keturunan kelanjutan trah Mataram Medang lain yang
segaris. Dimungkinkan yang terjadi, muncul trah-trah
wangsa yang lain, bukan segaris dengan Mataram Medang.
Beruntung, Pu Sindok dengan sisa-sisa kekuatannya
dibantu rakyat sipil kakatikan iy-anjukladang dapat menang
perang ketika menghadapi musuh. Sehingga di kakatikan
ini, sejarah mencatat sebagai bumi kemenangan, yaitu
kemenangan rakyat kakatikan iy-anjukladang membantu
laskar Pu Sindok melawan musuh kerajaan, sebagaimana
disimboliskan sebagai jayastambha dalam Prasasti
Anjukladang.
Saat menghadapi musuh kuatnya, Pu Sindok dapat
mempersatukan rakyat kakatikan iy-anjukladang yang
memiliki latar belakang sosial yang berbeda, yaitu mereka
adalah penganut agama Hindu, Budha, dan penganut
kepercayaan lain. (kata: kasaiwan agama Hindu, wihantan
agama budha, watu walang penganut kepercayaan lain)
Bukan hanya perbedaan agama yang harus
dipersatukan untuk menggalang kekuatan, namun strata
sosial juga telah dipersatukan. Yaitu, strata kasta brahmana
di pihak Mpu Mahaguru dan Mpu Goksandha, kasta
kesatriya di pihak Pu Sindok dan para pengikutnya, serta
kasta sudra di pihak rakyat sipil kakatikan iy-anjukladang.
Atau, tanpa memandang status sosial antara pejabat dengan
rakyat biasa, antara si kaya dengan si miskin, antara laki-laki
dengan perempuan, dan atau antara pemuda dengan orang
tua. Mereka dapat dipersatukan untuk mencapai satu
tujuan, yaitu menghadapi musuh kerajaan.
133
Di antara tanah yang statusnya ditinggikan menjadi
sima, hanya ada dua tanah yang mendapat anugerah
langsung atau atas inisiatif dari raja Sindok, yaitu kakatikan
iy-anjukladang mendapat anugerah sebagai sima swatantra,
terbebas dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan,
dan wanua Linggasutan diberi anugerah sebagai sima agar
rakyat sima setempat turut merawat makam mertua Pu
Sindok (ayah Parameswari Dyah Kebi) bernama Pu
Srawana.
Ini berbeda dengan pemberian prasasti kepada wanua
yang lain berdasarkan permohonan dari penduduk atau
pejabat setempat.
Pejabat samgat bernama Pu Anjukladang (bait 5
Prasasti Candilor) adalah pemimpin sima kakatikan iy-
anjukladang, disebut rama. Karena ketokohannya, dia
menjadi kepala rama yang terkenal. Sehingga nama Pu
Anjukladang berkembang menjadi nama Nganjuk setelah
mendapat awalan “N” dan “G” di depannya.
Dengan dibangunnya tugu kemenangan berupa
jayastambha, diperkirakan sebagai tanda dharma dari rama
(pejabat setingkat desa yang dapat menurunkan perintah)
pejabat samgat bernama Pu Anjukladang bersama rakyat
kakatikan iy-anjukladang ketika membantu laskar Pu
Sindok, mengalahkan prajurit sekutu Swarnadwipa
Sriwijaya. Seiring berjalannya waktu, diperkirakan
ketokohan Samgat Pu Anjukladang lebih dikenal oleh
masyarakat luas daripada nama kakatikan. Sehingga nama
Anjukladang sering disebut dan berkembang dengan
sebutan Nganjuk setelah mengalami nasalisasi “ng” di depan
kata “anjuk”, sebagai nama suatu daerah atau tempat hingga
sekarang.
6. Anjukladang, nama tempat atau orang?
Kata Anjukladang yang tertulis beberapa kali dalam
prasasti Candilor masih menjadi perdebatan.
134
Sebagian menyebut, anjukladang adalah nama orang
sebagaimana dicatat pertama kali dalam isi prasasti Candilor
bait ke-5,
“……. marpanakna / i / bhatara / i / sang hyang prasada
kabhaktyan / i / dharma / samgat / pu anjukladang”
…….. dipersembahkan / kepada / bhatara / di / sang hyang
prasada kabhaktian / untuk / dharmma / pejabat samgat
/bernama pu anjukladang / (Edie Wurjantoro, 2010).
Sebagian lain menyebut, anjukladang adalah nama
tempat sesuai nama Nganjuk yang berasal dari kata “anjuk”,
setelah mendapat awalan “ng” berubah menjadi Nganjuk.
Bahkan dalam prasasti Candilor, kata anjukladang muncul
didahuli huruf i atau iy- di depannya. Diasumsikan, huruf i
atau iy- menunjukkan kata depan yang berarti “di”. Sehingga
i anjukladang atau iy-anjukladang diasumsikan sebagai
tempat. Seperti Mataram Medang i Tawlang, Mataram
Medang i Watugaluh, Mataram Medang i Poh Pitu, dan
sebagainya. Yang berarti, istana kotaraja Mataram Medang
berada di Tawmlang, di Watugaluh, atau di Poh Pitu.
Ada yang menyebut pada era Mataram Medang,
penyebutan nama orang lazim memakai unsur asli. Nama
asli ini biasanya diberikan sejak seseorang lahir. Jaman
sekarang disebut nama kecil, jaman Mataram Medang
disebut “garbhanama”.
(Darmosoentopo, 2003), dalam penyebutan nama
kecil bagi orang biasa didahului kata si atau sang.
Sedangkan, bagi bangsawan didahului kata pu atau dyah.
Misalnya Pu Sindok dan Dyah Wawa.
Sedangkan seorang raja dan hino terdiri dari tiga unsur
nama, yaitu; unsur nama ke-rakai-annya, toponimi, dan
abhisekanama.
Nama ke-rakai-an diawali dengan kata rakai, misalnya
Rakai Pikatan, berarti ia penguasa di Pikatan. Nama Pikatan
adalah nama tempat dan menjadi sebutan nama orang
disebut nama toponimi. Nama toponimi sudah melekat erat
135
dengan pemakainya sehingga meskipun ia menjadi raja,
nama toponimi tetap disebut dalam gelarnya.
Nama abhiseka, yaitu nama yang diberikan saat
seseorang dinobatkan menjadi raja yang selalu diawali
dengan kata Sri, misalnya nama Sri Maharaja Pu Sindok
Isana Wikramadharmmotunggadewa.
Sedangkan bangsawan yang memegang lungguh
memiliki dua unsur nama, yaitu nama ke-lungguh-annya
diawali dengan kata rakai atau pamgat, lalu garbhanama-nya
diawali dengan pu atau dyah. Misalnya, Samgat Pu
Anjukladang, terdiri dari dua unsur nama. Samgat (Sang
Pamgat) adalah nama lungguh dan pu adalah nama garbha.
Bila Samgat Pu Anjukladang adalah seorang bangsawan,
berarti ia memiliki dua unsur nama, yaitu Samgat (nama
lungguh) dan pu (nama garbha) dan Anjukladang adalah
nama asli.
Mungkinkah kata “anjukladang” menunjukkan nama
tempat dan menjadi sebutan nama orang yang disebut nama
toponimi, seperti yang melekat pada nama raja? Sehingga
nama toponimi yang sudah melekat erat dengan
pemakainya sehingga meskipun ia menjadi kepala rama,
nama toponimi anjukladang tetap disebut dalam gelarnya,
yaitu Samgat Pu Anjukladang.
Dalam kehidupan modern sering terjadi penyebutan
nama orang yang didasarkan asal domisilinya. Misalnya,
seorang tokoh terkenal tinggal di Kelurahan Bogo. Karena
ketokohannya, lantas dia dipanggil bukan nama garbha-nya,
melainkan nama “Mbah Bogo”, tempat dimana ia tinggal.
Contoh lain, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan
Ampel, sunan-sunan yang lain, lebih dikenal nama tempat
tinggal mereka daripada nama aslinya.
Atau, apabila Samgat Pu Anjukladang (baik ke-5
prasasti Candilor) adalah benar seorang bangsawan, berarti
ia memiliki dua unsur nama, yaitu Samgat (nama lungguh)
136
dan pu (nama garbha). Sehingga Anjukladang adalah nama
asli, bukan nama tempat.
Jadi kata anjukladang, antara sebagai nama tempat atau
orang tidak berpengaruh dalam legitimasi penyebutannya.
J.G. de Casparis, anjukladang diartikan, anjuk berarti
tinggi, tempat yang tinggi atau dalam arti simbolis mendapat
kemenangan yang gilang gemilang, sedangkan ladang berati
tanah atau daratan. Lantas oleh Harimintaji, dkk dalam
Nganjuk dan Sejarahnya, bahwa Nganjuk diinterpretasikan
nama Nganjuk diambil dari nama sebuah tempat atau desa
“anjukladang”. Karena memiliki sejarah heroik, prajurit-
prajurit di bawah pimpinan Pu Sindok dapat menaklukkan
bala tentara dari Kerajaan Sriwijaya, maka Nganjuk”
diabadikan sebagai nama daerah/wilayah yang lebih luas.
Kemudian Nganjuk yang diambil dari kata Anjuk diartikan
“kemenangan dan kejayaan”.
Seperti dijelaskan Eko Jarwanto dalam bukunya,
Nganjoek dalam Lintasan Sejarah Nusantara, 2021,
menurut catatan dan kajian para peneliti sebelumnya
dijelaskan bahwa kata Nganjuk ini awalnya berasal dari kata
Anjukladang. Kata Anjuk bermakna tinggi dan ladang
/daratan / dataran yang bermakna tanah. Dengan demikian,
maka secara harfiah arti kata dari Anjukladang adalah tanah
yang tinggi. Namun demikian menurut para ahli nampaknya
juga dapat dipahami dengan makna simbolis. Kata
Anjukladang ini oleh para peneliti ditafsirkan dengan makna
tanah kemenangan. Bahkan, lebih jauh lagi penjelasan
makna Anjukladang ini juga dikaitkan dengan terjadinya
peristiwa kemenangan Pu Sindok dalam upaya menangkal
serangan pasukan dari Melayu yang telah sampai pula di
daerah Nganjuk pada abad ke-10. Pada saat itu
digambarkan bahwa telah terjadi sebuah pertempuran
antara Pu Sindok bersama pasukannya yang dibantu oleh
segenap masyarakat Anjukladang yang berperang hebat
melawan pasukan Melayu. Akhir pertempuran itu
137
dimenangkan oleh pasukan Pu Sindok. Berkat adanya
kemenangan dan bantuan masyarakat Anjukladang inilah
maka Pu Sindok memberikan hadiah berupa status sima
swatantra kepada segenap masyarakat di Anjukladang,
sebagai balas jasa atas keikutsertaan masyarakat saat itu
dalam berjuang mempertahankan wilayahnya dari serangan
musuh. Namun demikian, di sisi lain rupanya dapat pula
dijelaskan bahwa kata Nganjuk dapat juga berasal dari kata
Anjuk saja, tanpa adanya tambahan kata ladang. Kata Anjuk
dapat dimaknai dengan arti muka, di muka, terkemuka, di
depan, atau terdepan. Maknanya, daerah Anjuk adalah
wilayah yang ada di muka, di depan, terkemuka, atau
wilayah terdepan. Kata ini ternyata juga masih ditemui
dalam kosakata Bahasa Jawa, Sunda, serta Banyumasan
yang kurang lebih memiliki makna yang sama. Jika benar
demikian, maka munculnya kata Anjuk atau Anjukladang
tersebut jelas tidak ada hubungannya sama sekali dengan
peristiwa kemenangan Pu Sindok dalam upaya menangkal
serangan pasukan Melayu. Hal ini karena penyebutan nama
daerah Anjuk atau Anjukladang jauh lebih lama ada atau
sudah tercipta periode waktunya sebelum peristiwa
peperangan itu terjadi, atau
Memang harus diakui bahwa sampai saat ini bukti-
bukti tertua atau catatan tertulis terkuno yang menyebut kata
Nganjuk (Anjuk/Anjukladang) hanya terdapat pada isi
Prasasti Anjukladang. Prasasti Anjukladang sendiri
merupakan prasasti yang ditulis padaperiode Pu Sindok
tahun 859 Saka (937 Masehi). Prasasti ini ditemukan di
dekat reruntuhan Candilor, sehingga nama Prasasti
Anjukladang juga sering disebut dengan Prasasti Candilor.
Adanya temuan kata Anjukladang dalam isi prasasti
tersebutlah yang dianggap sebagai awal mula atau cikal bakal
dari nama Nganjuk saat ini. Perubahan kata Anjuk menjadi
kata Nganjuk menurut peneliti hanya lebih karena faktor
morfologi bahasa atau pergeseran pelafalan ucapan dari
138
masyarakat Jawa. Seperti halnya pada kata Awi menjadi
Ngawi, Aliman menjadi Ngliman dan sebagainya.
Semakin tidak jelas makna kata Nganjuk maupun
Anjukladang. Beberapa pendapat menyimpulkan dengan
argumennya masing-masing, dan tampaknya sama-sama
menonjolkan bahwa pendapatnya adalah yang paling benar.
Seperti J.G. de Casparis menyebut anjukladang sebagai
daratan tinggi dalam arti simbolis mendapat kemenangan
yang gilang gemilang, tanpa memberikan penjelasan lebih
rinci.
Bila memahami isi prasasti Candilor, disebutkan
bahwa luas area yang ditetapkan sebagai sima swatantra
adalah 6 lamwit (= + 81 – 92 hektare), berati luas tanah
kakatikan iy-anjukladang tidak lebih dari 1km X 1 km. Bila
Candilor dianggap sebagai titik tengah, berati panjang ke
selatan – utara dan timur – barat tidak lebih dari dari 500
meter.
I. AGAMA DAN SOSIAL
Hubungan strata sosial antar umat seagaman dan
beragama di kakatikan iy-anjukladang secara implisit sudah
tercermin dalam isi prasasti Candilor. Sehingga, pada saat
prajurit Pu Sindok yang berstatus kesatriya, dua Brahmana
kakatikan iy-anjukladang - Mpu Mahaguru dan Mpu
Goksandha, serta seluruh rakyat dapat bekerjasama, bahu-
membahu untuk bersatu, membentuk satu kekuatan. Rasa
kebhinnekaan telah terjalin pada masa itu.
Saat itu, Pu Sindok dan pengikutnya adalah para penganut
agama Hindu aliran Syiwa, sedangkan penduduk kakatikan
banyak yang menganut agama Budha. Dengan ditemukannya
ratusan pantheon di kompleks Candilor, menunjukkan bahwa
rakyat kakatikan, sebagian adalah penganut agama Budha.
Penyataan ini dibuktikan oleh N.J. Krom seperti dikutip
Eko Jarwanto (2021) bahwa Candilor ini pada awalnya
susunannya bertingkat dan bersifat Siwais. Di dalam Candilor
139
terdapat beberapa area relung diantaranya untuk penempatan
arca Ganesha dan Nandi. Meskipun keadaannya sudah rusak,
dapat diperkirakan bahwa candi ini dahulunya mempunyai
ruang dalam yang berbentuk segi empat. Hal ini terlihat adanya
sudut siku-siku yang masih tampak di sudut timur laut ruang
dalam candi ini.
Di sebelah barat Candilor saat ini juga terdapat dua arca
yang semuanya sudah tanpa kepala, yang satu diperkirakan arca
Ganesha dan arca yang lain Siwa Mahadewa. Di sebelah barat
arca terdapat Lingga dan Yoni, yang keadaannya telah rusak. Di
sebelah baratnya lagi terdapat bekas pondasi pintu gerbang
masuk bangunan candi. Letaknya berada di kanan dan kiri di
tengahnya terdapat bekas trap, seperti tangga untuk menuju
bangunan suci di atasnya. Di sisi utara pondasi bekas pintu
gerbang ini ada dua buah makam yang oleh penduduk diyakini
sebagai makam Eyang Karta dan Eyang Kerti, yaitu abdi kinasih
Mpu Sindok. Hanya mengingat sebutan nama dan bentuk
makam, kedua makam tersebut nampaknya bukan makam
orang yang sejaman era Pu Sindok. Mungkinkan mereka orang
yang berjasa sebagai juru pelihara Candilor pada era-era
setelahnya, perlu kajian lebih lanjut.
Khusus benda-benda kuno yang ditemukan di area candi,
menurut Eko Jarwanto, jika benar asli dari Candilor, maka
dapat dikatakan bahwa Candilor bersifat Siwa (Hindu). Candi
Lor sekaligus menjadi sebuah tempat peribadatan bagi pemeluk
agama Hindu di Anjukladang (Nganjuk) saat itu. Selain temuan
Prasasti Anjukladang dan juga bangunan Candilor serta
beberapa artefak keagamaan, di sekitar tempat tersebut juga
pernah ditemukan banyak arca berbahan perunggu yang
memiliki nilai citarasa seni yang tinggi. Salah satu kelompok
arca perunggu ditemukan tahun 1913 di area persawahan
sekitar Candilor. Arca-arca tersebut menggambarkan Pantheon
Budhisme, diantaranya adalah:
140
1. Tara Musik, berukuran 7,8 cm yang menggambarkan
seseorang sedang memainkan kecapi yang terbuat dari rotan
dalam ekspresi menyanyi dan menari, dengan tugas memuja
Dhyani Budha.
2. Bodhisattwa yang berukuran 7,8 cm. Dalam konsep Budha
Mahayana, Bodhisattwa dianggap sebagai calon Budha.
Tiap-tiap Dhyani Buddha dikelilingi oleh Bodhisattwa. Di
sini Dhyani Budha dikelilingi oleh empat Bodhisattwa yang
disebut Vajradathu Mandala
3. Dhupa Tara dan Puspha Tara dengan ukuran 9 cm. Kedua
arca ini digambarkan ramping dan sangat indah. Yang satu
digambarkan sama dengan Tara Musik serta yang satunya
digambarkan sebagai Dhupa Bunga
4. Amitābha Buddha Utama yang berukuran hampir sama
dengan Pantheon Budhisme yang lain dalam sekte Tanah
Murni banyak berkembang terutama di Asia Timur,
termasuk di tanah Jawa. Menurut kitab ini, Amitābha
menjadi Buddha dikarenakan dari perbuatan baik atas
kehidupan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya
sebagai Bodhisattva bernama Dharmakāra. "Amitābha" dapat
diterjemahkan sebagai "Cahaya tidak terbatas", karena itu
Amitabha sering disebut sebagai "Buddha dengan Cahaya
tidak terbatas". (sumber : wiki)
Menurut ceritanya, arca-arca perunggu yang ditemukan di
dekat Candilor jumlanya mencapai 100 buah lebih ini sangat
penting jika ditinjau dari segi artistik dan ikonografinya.
Susunan pantheonnya yang sangat khas, yaitu mengungkapkan
tradisi kerajaan-kerajaan dengan patung Budha yang
menghadap kepada keempat penjuru arah mata angin.
Beberapa patung perunggu ini setelah diteliti dan dianalisis oleh
para ahli menjadi suatu daya ketertarikan tersendiri. Bahkan,
karena keindahannya pernah juga dipamerkan di Arena
Pameran Benda Seni Negeri Jajahan di Paris, Perancis pada
tahun 1931. Seorang ahli sejarah kuno Indonesia yang sangat
terkenal, yaitu Dr. F.D.K. Bosch yang tertarik dengan patung
141
tersebut pernah membandingkan arca-arca perunggu dari
Nganjuk tersebut dengan temuan patung Budha Liran Singon di
Jepang. Sedangkan, ciri-cirinya yang sangat indah pada arca
Nganjuk dapat dibandingkan dengan gambaran naskah
ikonografi Budha di Bali. Adanya penemuan berbagai arca
berbahan perunggu yang bercorak Budha, sedangkan posisi
bangunan Candi Lor sendiri yang bercorak Hindu
menunjukkan adanya sebuah kerukunan dan keharmonisan
kehidupan umat beragama saat itu di wilayah Nganjuk pada
abad ke-10 Masehi. Masyarakat yang memeluk agama Hindu
dan juga yang memeluk agama Budha hidup saling
berdampingan satu sama lain di wilayah Nganjuk pada abad ke-
10 Masehi. Keharmonisan hidup bermasyarakat ini juga
dibuktikan dari temuan-temuan artefak lainnya yang tersebar di
berbagai wilayah Nganjuk saat ini. Kebijakan politik Raja Pu
Sindok selanjutnya juga tercurah di beberapa wilayah Nganjuk
lainnya.
Salatunya di wilayah Kakatikan Anjukladang sudah
memiliki sistem pemerintahan, meskipun setingkat sima,
sehingga birokrasi dapat berjalan dengan baik. Sudah ada
seorang kepala pemerintahan (rama), yaitu Samgat Pu
Anjukladang, para dwryahaji (pejabat pemungut pajak),
citralekha (juru tulis), parujar (juru bicara), samgat / pamgat
(pejabat yang ahli di bidang keagamaan, kehakiman, dan
pemerintahan), wadihati (ahli agama pemimpin upacara),
makudur (ahli agama pemimpin upacara), serta para juru dan
tuha lain, mereka para ahli di bidangnya masing-masing.
Sepertinya, jiwa nilai-nilai seperti yang ada dalam Pancasila
sekarang ini, sudah berkembang di Kabupaten Nganjuk sejak
era Mataram Medang.
Hal ini seperti tertuang dalam isi prasasti Candilor, yang
menyebutkan bahwa kelima isi sila Pancasila sudah menjiwai
kehidupan rakyat Nganjuk pada masa pemerintahan Pu Sindok.
Secara tersurat, isi prasasti menyebutkan seruan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, yakni berupa seruan kepada para dewa,
142
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
BUKU SEJARAH NGANJUK ERA PRASEJARAH
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search