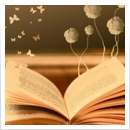KOMPONEN BIOTIK DAN ABIOTIK EKOSISTEM SAWAH DI DESA NGALANG
KECAMATAN GEDANGSARI
Oleh: Eka Ramadhani Sholihah
NIM. 2020015073
A. Analisis Situasi
Desa Ngalang berada di wilayah kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Desa Ngalang adalah 14,82 Km², atau setara dengan
21,75% dari luas kecamatan Gedangsari. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan adalah
±4 km, sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten adalah ± 17 km. Ketinggian tanah
di Desa Ngalang rata-rata 100 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata
7,8 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada
bulan Desember sampai dengan bulan Februari tiap tahunnya. Suhu udara berkisar
antara 27oC sampai dengan 34oC.
Salah satu hal yang akan dianalisis berdasarkan konsep IPA yaitu mengenai
Komponen Biotik dan Abiotik Ekosistem Sawah di Desa Ngalang Kecamatan
Gedangsari.
Gambar 1.1 Persawahan Ngalang Gambar 1.2 Suasana Sawah
B. Penjelasan Konsep IPA
Analisis pada konsep IPA, bahwa komponen ekosistem sawah yang ditemukan di
Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari tersusun atas komponen abiotik yang terdiri sinar
matahari, batu, tanah, air, suhu dan kelembaban dan komponen biotik yang terdiri dari
flora dan fauna, seperti: padi, rumput/kalanjana, bekicot, capung, belalang. Hasil
pengkajian/penelaahan temuan tersebut untuk menjadi sumber belajar telah memenuhi
persyaratan sumber belajar yang mencakup kejelasan potensi, kesesuaian dengan
tujuan pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan
pedoman penelitian, kejelasan perolehan yang diharapkan, sehingga mampu
menghantarkan siswa pada:
147
1) Perolehan kognitif yaitu siswa mampu menggunakan cara berpikir tingkat tinggi untuk
mendapatkan pengetahuan melalui kegiatan inquiry discovery.
2) Perolehan afektif, siswa akan memiliki sikap-sikap ilmiah yang positif dalam ikut
serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan alam dan lingkungan untuk tujuan-
tujuan kebaikan.
3) Perolehan psikomotirik, siswa memiliki keterampilan-ketrampilan seperti
keterampilan menggali informasi, menganalisis, berkomunikasi, dan lain sebagainya
yang lebih pada melatih kemandirian siswa untuk bisa mengimplementasikan ilmu
yang diperoleh disekolah saat berada ditengah-tengah masyarakat dan
lingkungannya.
Berikut komponen-komponen yang saya temui saat survey di ekosistem sawah
Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari:
a. Komponen Abiotik
Gambar 1.3 Pengairan Sawah
Gambar 1.4 Tanah di Sawah
b. Komponen Biotik
148
Gambar 1.5 Tumbuhan Padi
Gambar 1.6 Tumbuhan Kalanjana
Gambar 1.7 Hewan Belalang
Gambar 1.8 Hewan Capung
149
Gambar 1.9 Hewan Bekicot
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Keterkaitan konsep dengan Pembelajaran IPA di SD yaitu pembelajaran IPA yang efektif
di SD adalah Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan berorientasi pada
aktivitas siswa dengan menekankan pada keterampilan IPA melalui mengamati, menilai,
meneliti, menganalisis, mengklarifikasi berdasarkan data hasil pengamatan. Pembelajaran
yang berorientasi pada siswa melakuakan pembelajaran secara mandiri dan berkreasi
secara bebas maka siswa akan merasa senang dan bersemangat untuk belajar sendiri.
Pembelajaran IPA dengan materi ekosistem di Sekolah Dasar pada materi kelas V akan
lebih efisien jika menggunakan pendekatan kontekstual yang memberikan pengalaman
langsung bagi siswa SD yang berada pada taraf operasional konkrit. Materi ekosistem dapat
disampaikan dan dirancang dengan melihat obyek langsung yang berada dilingkungan
sekolahnya ataupun dengan model ekosistem yaitu terrarium.
Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi, bila komponen-komponennya dalam
jumlah yang berimbang. Komponen-komponen ekosistem mencakup: Faktor Abiotik,
Produsen, Konsumen dan Dekomposer (Pengurai). Di antara komponen-komponen
ekosistem terjadi interaksi, saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi
sumber penghidupannya. Tuhan menciptakan faktor abiotik untuk mendukung kehidupan
tumbuh-tumbuhan sebagai produsen; kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi
mendukung kehidupan organisme lainnya (binatang dan manusia) sebagai konsumen
maupun detritivora, dan akhirnya dekomposer (bakteri dan jamur) mengembalikan
unsurunsur pembentuk makhluk hidup kembali ke alam lagi menjadi faktor-faktor abiotik,
demikian seterusnya terjadilah daur ulang materi dan aliran energi di alam secara
seimbang.
Adanya saling ketergantungan antara faktor abiotik dengan faktor biotik, dan hubungan
antarkomponen di dalam faktor biotik sendiri, menunjukkan bahwa kehidupan manusia
bergantung kepada kehidupan makhluk lainnya maupun kehidupan antar manusia sendiri.
Beranekaragam tumbuhan yang menyusun taman kota memberikan dampak positif bagi
150
lingkungan kehidupan kota itu maupun lingkungan lainnya. Belakangan ini diketahui bahwa
berbagai tanaman hias dapat menyerap racun yang ada di udara, air, maupun di tanah,
seperti tanaman tapak dara, senseivera, palem kuning dan lain-lain.
D. Daftar Pustaka
Dr. RAMLAWATI, M., Drs. H. HAMKA L, M., SITTI SAENAB, S. M., & SITTI RAHMA
YUNUS, S. M. (2017). SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017 MATA
PELAJARAN IPA BAB VI EKOLOGI.
Sulthon. (2016). PEMBELAJARAN IPA YANG EFEKTIF DAN MENYENANGKAN BAGI
SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI). Vol. 4 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2016, 39-54.
Susilo, M. J. (2013). POTENSI SUMBER BELAJAR BIOLOGI SMA KELAS X VERSI
KURIKULUM 2013 UNTUK MATERI EKOSISTEM SAWAH DI SEKITAR GUNUNG
PUYUH PUNDONG KABUPATEN BANTUL. 1032-1038.
HUBUNGAN POHON JAMBU AIR DENGAN TANAMAN KEMLADEAN
Oleh: Ani Setyaningsih
NIM. 2020015074
A. Analisis Situasi
Dusun Sejaran merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Selomartani,
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jarak
Dusun Sejaran dengan ibukota Kecamatan Kalasan sekitar 8 km, jarak ke ibukota
Kabupaten Sleman sekitar 17 km, dan jarak ke ibukota provinsi DIY sekitar 21 km.
Gambar 1. Lokasi dusun Sejaran dari pusat kota Yogyakarta
151
Sekitar Dusun Sejaran terdapat area persawahan yang saat ini ditanami padi dan
sayuran, sungai yang berfungsi sebagai saluran irigasi persawahan, dan interaksi antara
makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup ada yang menguntungkan dan merugikan.
Gambar 2. Area persawahan di Dusun Sejaran
B. Penjelasan Konsep IPA
Makhluk hidup saling berkegantungan, banyak makhluk hidup yang berhubungan
dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya
disebut simbiosis. Terdapat tiga jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme,
dan komensalisme.
1. Simbiosis Mutualisme
Menurut Herlina (2008:67) simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang
terjadi antara dua makhluk atau lebih yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak
ada satu pihak pun yang dirugikan. Contohnya, kerbau dengan burung jalak, tumbuhan
berbunga dengan lebah, tanaman polong-polongan dengan bakteri Rhizobium, alga
dengan jamur yang membentuk lumut kerak, rayap dengan Flagellata, semut dengan
kutu buah, dan lainnya.
Gambar 3. Kupu-kupu dan bunga
Simbiosis mutualisme terjadi pada hubungan antara kupu-kupu dengan bunga.
Kupu-kupu hinggap pada bunga untuk menghisap nektar. Ketika para kupu-kupu pergi,
kupu-kupu membawa serbuk sari dan menjatuhkannya ke bunga lain sehingga
152
membantu penyerbukan bunga. Baik kupu-kupu maupun bunga mendapat keuntungan,
kupu-kupu mendapat makanan dan bunga mengalami penyerbukan.
2. Simbiosis Komensalisme
Menurut Herlina (2008:68) simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang
terjadi antara dua makhluk atau lebih yang tidak saling merugikan. Dalam hal ini satu
makhluk diuntungkan dan makhluk yang lain tidak dirugikan. Contohnya, hubungan
tanaman sirih dengan inangnya, ikan remora yang berenang menempel pada ikan hiu,
ikan badut dengan anemone laut, dan lainnya.
Gambar 4. Tumbuhan anggrek dan pohon inangnya
Simbiosis komensalisme terjadi pada hubungan antara tumbuhan anggrek dan
pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat
menumpang hidup pada pohon dan selama menumpang tersebut anggrek tidak
merugikan pohon.
3. Simbiosis Parasitisme
Menurut Herlina (2008:68) simbiosis parasitisme merupakan hubungan yang
terjadi antara dua makhluk atau lebih tetapi salah satu makhluk merugikan makhluk
yang lainnya. Makhluk yang diuntungkan disebut parasit sedangkan makhluk yang
dirugikan disebut inang. Contohnya, hubungan manusia dengan cacing perut, benalu
dengan pohon, tali putri dengan pohon teh, kutu dengan hewan piaraan, dan lainnya.
153
Gambar 5. Pohon jambu biji dan kemladean/benalu
Gambar 6. Tanaman kemladean/benalu
Simbiosis parasitisme terjadi pada hubungan antara pohon jambu air dan
kemladean. Kemladean memiliki nama lain benalu. Benalu dapat hidup subur karena
menghisap zat makanan dari pohon jambu air yang ditumpanginya sehingga pohon
jambu air lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati.
Menurut Chamidah (2017) benalu merupakan tanaman pengganggu yang
bersifat parasit bagi tanaman inangnya. Keberadaan benalu dalam jumlah banyak akan
mengganggu pertumbuhan dari suatu tanaman, akan tetapi seringkali benalu dilupakan.
Walaupun bersifat parasit benalu berpotensi sebagai tumbuhan obat.
Benalu bermanfaat untuk mengobati penyakit kanker, tumor ganas, darah tinggi,
jantung, liver, dan baik untuk menjaga stamina tubuh.
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Pada pembelajaran IPA di SD materi simbiosis terdapat pada kelas 5 tema 5
subtema 2 pembelajaran 5. Buku tematik tema 5 membahas tentang ekosistem dan pada
subtema 2 membahas tentang hubungan antarmakhluk hidup dalam ekosistem.
Berdasarkan Buku Guru Tema 5 Ekosistem Tematik Terpadu Kurikurlum 2013 Kelas V
(2017) KD IPA yang dibahas pada tema 5 subtema 2 yaitu :
3.5. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di
lingkungan sekitar.
154
4.5. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem.
Berdasarkan Buku Siswa Tema 5 Ekosistem Tematik Terpadu Kurikulum 2013
Kelas V (2017) materi simbiosis pada buku siswa kelas 5 yaitu :
Gambar 7. Materi simbiosis pada buku siswa
D. Daftar Pustaka
Buku Guru Tema 5 Ekosistem Tematik Terpadu Kurikurlum 2013 Kelas V. (2017). Jakarta
: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
Buku Siswa Tema 5 Ekosistem Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas V. (2017). Jakarta:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
Chamidah, D. (2017). Jenis-jenis Benalu dengan Tanaman Inang Pada Ruang Terbuka
Hijau Kota Surabaya. Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, 2 (2), 85-
92.
Herlina, R. (2008). Intisari IPA (Biologi) SMP . Jakarta Selatan: PT Kawan Pustaka.
EKOSISTEM KOLAM DI DUSUN JIWAN, ARGOMULYO, CANGKRINGAN,SLEMAN,
YOGYAKARTA
Oleh: Rifki Wahyu Nugroho
NIM. 2020015075
A. Analisis Situasi
155
Dusun jiwan merupakan salah satu dusun yang berada di desa Argomulyo, Kecamatan
Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Beberapa masyarakat dusun jiwan
memanfaatkan lahan pekarangannya menjadi kolam ikan. Hal tersebut dikarenakan
masyarakat memanfaatkan perairan bersumber dari sungai yang berada di dekat dusun
jiwan. Masyarakat yang memiliki kolam lebih memilih memelihara ikan nila dan lele
daripada ikan lainnya, karena masyarakat lebih suka mengkonsumsi ikan tersebut dan
pemeliharaannya lebih mudah, misalnya ikan nila dan bawal tidak hanya makan pellet ikan
tetapi daun lompong, daun singkong, sayur-sayuran sisa dari pasar.
B. Penjelasan Konsep IPA
Dari konsep analisis seseorang dapat mempelajari pengetahuan IPA mulai ekosistem
kolam, peran air kolam untuk makhluk hidup yang ada di kolam, perkembangbiakan ikan,
alat pernafasan ikan, rantai makanan dan lain sebagainya. Rantai makanan adalah urutan
letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan , untuk bertahan
hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukan hubungan antara produsen,
konsumen, dan pengurai. Panah berfungsi untuk menunjukan pergerakan energi melalui
rantai makanan. Rantai makanan memiliki tingkatan salam ekosistem disebut dengan
tingkat trofik. Tingkatan trofik rantai makanan adalah produsen, konsumen primer,
konsumen sekunder, konsumen puncak.
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Kaitkan konsep yang dianalisis dengan materi pembelajaran atau kurikulum IPA di
Sekolah Dasar adalah berkaitan dengan materi ekosistem yang diajarkan di kelas 5.
Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungannya. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan
156
biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk atau benda hidup.
Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari makhluk atau benda
mati. Jika fungsi setiap komponen tidak terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem
akan terjaga.
1. Komponen biotik yaitu semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem.
Ada dua macam komponen biotik yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof.
Organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis
makanannya sendiri dengan bantuan energy matahari melalui proses fotosintesis.
Organisme autotrof berperan sebagai produsen, contohnya adalah semua organisme
yang mengandung klorofil. Sedangkan organisme heterotrof adalah semua organisme
yang tidak dapat membuat makanan sendiri, organisme ini memanfaatkan bahan-
bahan organic dari organisme lain sebagai makanannya. Ada tiga tingkatan organisme
heterotrof yaitu pertama konsumen, yang secara langsung memakan organisme lain.
Kedua pengurai, yang mendapatkan makanan dari pengurai organisme mati. ketiga
detritivor merupakan pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk.
2. Komponen abiotik yaitu benda-benda tak hidup yang ada di dalam suatu ekosistem,
terdiri atas benda-benda tak hidup yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti tanah,
air, matahari, udara, dan energi.
Ekosistem dibagi menjadi 2 yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah
ekosistem yang terbuat tanpa campur tangan dari manusia, contohnya ekosistem laut,
pantai, sungai. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dengan
adanya campur tangan manusia, contohnya ekosistem kolam, sawah, kebun.
D. Daftar Pustaka
1. Juwitaningsih, desi. 2018. Lingkungan Hidup Kita.
http://rumahbelajar.id/Media/Dokumen/5cff79ecb646044330d686d4/1f96675e25df308
91f31827a39486b98.pdf. Diakses 25 Maret 2022 pukul 22.00
2. Maknun, Djohar. 2017. Ekologi: Popolasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus
Hijau Asri, Islami dan Ilmiah. Cirebon: Nurjati Press. http://repository.syekhnurjati.ac.id.
Diakses 13 Maret 2022 pukul 23.03.
3. Utomo, Sayud Warno, Ir Sutriyono, Reda Rizal. 2012. Pengertian, Ruang Lingkup
Ekologi dan Ekosistem. Jakarta : Universitas Terbuka.
https://scholar.google.com/scholar?q=related:r2cl4-
svQI8J:scholar.google.com/&scioq=komponen+ekosistem+kolam&hl=id&as_sdt=0,5#d
=gs_qabs&u=%23p%3Dr2cl4-svQI8J. Diakses 13 Maret 2022 pukul 23.30.
157
PENGELOLAAN LAHAN HIJAU DI DAERAH BANTARAN SUNGAI WINONGO
TEJOKUSUMAN YOGYAKARTA
Oleh: Carolina Anya Azalia Putri
NIM. 2020015076
A. Analisis Situasi
Sungai Winongo merupakan salah satu sungai penting di Yogyakarta, mempunyai
bentuk memanjang, dengan panjang ± 41, 3 Km, luas daerah aliran sungai ± 118 Km2,
bermata air di Lereng Gunung Merapi dan bermuara di Sungai Opak. Sungai Winongo dari
hulu ke hilir melalui tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta,
dan Kabupaten Bantul. Sungai Winongo sendiri memiliki 3 hulu yaitu Sungai Denggung
Sungai Doso dan Sungai Duren yang keberadaannya berada di wilayah kecamatan Turi
dan baru menjadi nama Sungai Winongo ketika sudah memasuki wilayah kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman. Ditengah Aliran sungai yang masuk ke kota ada aliran sungai kecil yang
juga masuk ke dalam Sungai Winongo yang disebut dengan Sungai Buntung.
Gambar 1 (Sungai Winongo di wilayah Tejokusuman)
Sungai Winongo yang diobservasi terletak di wilayah Ngampilan yang merupakan
sebuah kelurahan yang berada di pusat Kota Yogyakarta. Di daerah ini adalah tempat
tinggalnya para abdi dalem Ngampil atau para penabuh gamelan kerajaan. Maka tempat
para abdi dalem Ngampil ini tinggal disebut dengan nama Ampilan. Meskipun lokasinya
berada di pusat kota, perkampungan di Ngampilan ini masih erat dengan budayabudaya
guyub/berkumpul yang menjadi ciri khas karakter masyarakat kampung.
158
Gambar 2 (Penampakan wilayah Tejokusuman dan sungai Winongo melalui Google Map)
Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan permukiman kota (kampung)
menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan penurunan kualitas hidup
yang menurun. Fenomena kepadatan penduduk yang tinggi ini terjadi di Kota Yogyakarta
yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi.
Kecamatan Ngampilan merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan
tertinggi. Pada tahun 2021 berdasarkan data kependudukan Provinsi D. I Yogyakarta,
tercatat wilayah kecamatan Ngampilan memiliki jumlah penduduk 18.374 jiwa, dan
diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya.
Ditinjau dari keadaan fisik rumah di RW 04 Ngampilan ini merupakan permukiman padat
di bantaran kali dengan tipe rumah pada lahan terbatas yang saling berhimpitan dan tidak
teratur. Jarak antara tepian sungai (tanggul / talud) dengan rumah penduduk di sepanjang
bantaran sungai yang tidak lebih dari 2 meter menyebabkan masyarakat tidak memiliki
lahan hijau yang luas.
Gambar 3 (Pemanfaatan talud sebagai lahan hijau masyarakat bantaran sungai Winongo)
Oleh karena itu masyarakat di sepanjang sungai Winongo memanfaatkan lahan sempit
tersebut semaksimal mungkin. Dengan memanfaatkan daerah tepian (tanggul / talud) dan
159
pinggiran rumah sebagai lahan hijau. Lebar tepian sungai (tanggul / talud) di sepanjang
sungai Winongo wilayah Tejokusuman, Ngampilan kira-kira 50 cm – 1 m. Walau memiliki
lahan sempit, masyarakat tetap memaksimalkan ruang tersebut sebagai lahan hijau,
mayoritas masyarakat menanam sayuran, tanaman hias, dan tanaman buah di sepanjang
tepian sungai, tetapi tetap menyisakan ruang kosong agar masyarakat tetap bisa
menggunakannya. Pemerintah juga membangun tiang-tiang untuk ditanami tanaman
rambat, seperti markisa, telang, dan lain-lain.
Gambar 4 (Pemanfaatan tembok samping rumah untuk wall planter)
Selain memanfaatkan tepian sungai, masyarakat wilayah Tejokusuman juga
menggunakan pot gantung dan wall planter (pot kantong). Biasanya ditanami tanaman
berukuran kecil sampai sedang, daik itu tanaman bunga maupun sayuran. Teknik menanam
tersebut adalah teknik menanam dengan vertical garden susunan tanaman yang disusun
sedemikian rupa dalam bidang yang tegak lurus atau mendekati tegak lurus sebagai taman
dalam waktu yang relatife lama. Dalam penataannya tetap memadukan unsur softscape
(tanaman) dan unsur hardscape (bebatuan, besi, stepping stone, dan lain-lain).
B. Penjelasan Konsep IPA
Sains merupakan cara mencari tahu tentang alam sekitar secara sistematis untuk
mengusai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep prinsip-prinsip, proses penemuan, dan
memiliki sikap ilmiah. Menurut Rohani (1997) Sumber Belajar (learning resources) adalah
segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang
memungkinkan (mempermudah) terjadinya proses belajar “Lingkungan” dalam
pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai “ segala sesuatu yang ada di sekolah atau tempat
tinggal siswa yang temasuk di dalamnya mahluk hidup maupun benda mati yang dapat
dijadikan sebagai sumber belajar”, dengan maksud lebih lanjut bahwa lingkungan tersebut
dapat menjadi objek pengamatan,sarana atau tempat melakukan percobaan/penyelidikan
dan sebagai tempat mendapatkan informasi. Maka dengan pengertian tersebut
“lingkungan” merupakan sesuatu yang sangat penting baik sebagai wahana maupun
sebagai objek pembelajaran IPA.
160
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. .Nilai dari suatu lingkugan
sebagai sumber belajar bergantung kepada kecakapan memanfaatkannya. Lingkungan
sekitar yaitu lingkungan rumah, sekolah, sawah atau hutan,dapat digunakan sebagai
sumber belajar yang baik. Oleh karena itu dalam mempelajari lingkungan, sejauh mungkin
mencari kesempatan untuk bisa belajar dari alam.
Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 24) dalam Retno Utaminingsih (2015 :217-218)
ada beberapa alasan yang menjadikan lingkungan itu sangat penting dalam interaksi belajar
mengajar,yaitu sebagai berikut.
1. Sebagai sasaran belajar
Lingkungan merupakan salah satu sasaran dalam proses pembelajaran. Salah satu
tujuan pendidikan di SD, antara lain agar anak dapat mengenal, mengetahui dan
mempelajari alam sekitar. Alam sekitar ini tentunya termasuk lingkungan. Jadi
segala sesuatu yang ada disekitar anak termasuk lingkungan merupakan objek
belajar yang akan diajarkan kepada anak didik kita, atau dengan kata lain lingkungan
merupakan sasaran belajar bagi anak SD.
2. Sebagai sumber belajar
Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi siswa. Ada
berbagai macam sumber belajar, seperti guru, buku-buku, labolatorium, tenaga ahli,
serta lingkungan alam sekitar. Lingkungan alam sekitar seperti kebun sekolah,
apotik hidup, sungai dan sebagainya merupakan sumber belajar yang tidak habis-
habisnya yang memberikan pengetahuan kepada kita. Semakin banyak kita gali
semakin banyak yang kita dapatkan, tidak hanya bagi IPA itu sendiri tetapi juga
berupa sumber dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya.
3. Sebagai sarana belajar
Dalam proses pembelajaran kita memerlukan sarana dalam proses belajar
mengajar. Lingkungan merupakan suatu sarana belajar yang baik, bahkan
lingkungan yang alamiah menyediakan bahan-bahan yang tidak perlu dibeli, misal
udara, cahaya matahari, pepohonan, air sungai, rerumputan dan sebagainya. Jadi
lingkungan adalah suatu sarana belajar yang praktis dan ekonomisy ang
memudahkan kita untuk belajar.
Dalam hal inidapat dikatakan bahwa pemanfaatan lingkungandapat meningkatkan produk,
proses, keterampilandan meningkatkan kinerja para siswa SD dalampembelajaran IPA.
Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah dikuasai siswa
melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak positif dari diterapkannya
pemanfaatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa keingintahuannya tentang
sesuatu yang ada dilingkungannya. Ada empat pilar pendidikan yakni learning to know
161
(belajar untuk mengetahui), learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya),learning to do
(belajar untuk mengerjakan sesuatu) dan learning to life together (belajar untuk bekerja
sama) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan yang
dikemas sedemikian rupa oleh guru. Bekerja dan belajar yang berbasis lingkungan sekitar
memberikan nilai lebih, baik bagi si pembelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.
D. Daftar Pustaka
M. Taufiq, dkk. 2014. Pengembangan Media Pembelajaran Ipa Terpaduberkarakter Peduli
Lingkungan Tema “Konservasi”Berpendekatan Science-Edutainment. Jurnal Pendidikan
IPA Indonesia. 3 (2), 140-145
Utaminingsih R. (2015). Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Laboratorium Alam pad
Pembelajaran IPA SD. Trihayu : Jurnal Pendidikan Ke-SD-an. 2 (1), 217-218.
Rohani. 1997. Media Instruksional Edukatif. Rineka Cipta, Jakarta
Darmodjo, Hendro dan Kaligis, Jenny R.E. (1993). Pendidikan IPA 2. Jakarta: Depdikbud Dirjen
Dikti
162
BAGIAN-BAGIAN TANAMAN PADI KECAMATAN PAKEM, SELEMAN, YOGYAKARTA
Oleh: Alfarezi
NIM: 2020015077
A. Analisis Situasi
Pakem adalah sebuah kapanewon di Kabupaten Seleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Kapanewon Pakem berada di sebelah Utara dari Ibu kota Kabupaten
Seleman. Jaran Ibu kota Kecamatan Pakem ke Pusat Pemerintahan (Ibu kota)
Kabupaten Seleman adalah 14 Km. Lokasi Ibu kota Kecamatan Pakem berada di
77.6678’ LS dan 110.42011’ BT. Kecamatan Pakem mempunyai luas wilayah 4.384,04
Ha. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pakem adalah Petani.
Gambar 1. Lokasi Kecamatan Pakem
Di kecamatan Pakem terdapat sungai yang di pinggirnya dimanfaatkan oleh
orang-orang setempat untuk menanam tanaman pangan salah satunya adalah padi.
Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah di temukan, apalagi kita
yang tinggal di pedesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi.
Sebagian besar menjadikan padi sebagai sumber bahan makanan pokok. Padi
merupakan tanaman yang termasuk genus Oryza L. yang meliputi kurang lebih 25
spesies, terbesar di daerah tropisdan di daerah subtropis, seperti Asia dan Afrika. Padi
yang sekarang ada merupakan persilangan antara Oryza officianalis dan Oryza sativa
F.Ina (Mubaroq, 2013).
163
Gambar 2: Tanaman padi
B. Penjelasan Konsep IPA
Tanaman padi terdiri dari dua bagian utama yaitu, bagian vegetatif (fase
pertumbuhan) dan bagian generatif (fase reproduktif). Bagian vegetatif tanaman padi
antara lain daun, batang dan akar, sedangkan bagian generatif tanaman padi meliputi
bunga, malai dan gabah. Daun tanaman padi muncul pada buku-buku dengan susunan
berseling dan berbentuk lanset (sempit memanjang) serta memiliki pelepah daun. Tiap
buku tumbuh satu daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun (auricle), telinga daun
dan lidah daun (ligule) (Purwono dan Purnamawati, 2007).
Batang tanaman padi berbentuk bulat, berongga dan beruas. Antara ruas yang
satu dengan yang lain dipisahkan oleh satu buku. Ruas batang tanaman padi sangat
pendek dan rapat pada awal pertumbuhan dan akan memanjang ketika memasuki fase
produktif. Batang sekunder tumbuh pada bagian buku paling bawah dan batang
sekunder akan menjadi batang tersier (Meiliza, 2006).
Gambar 3: Bagian tanaman padi
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
164
Keterkaitan konsep analisis dengan materi pembelajaran IPA di Sekolah Dasar
adalah berkaitan dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan
tumbuhan termasuk pada pembelajaran IPA Kelas 4 Tema 3. Padi termasuk tanaman
semusim atau tanaman berumur pendek, kurang dari satu tahun dan hanya sekali
berproduksi, setelah berproduksi akan mati atau dimatikan. Menurut Aak (1995),
tanaman padi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
1. Bagian Vegetatif
a. Akar, merupakan bagian tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan zat
makanan dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Akar
tanaman padi dapat dibedakan menjadi akar tunggang, akar serabut, akar rambut
dan akar tajuk.
b. Batang, padi mempunyai batang yang beruas-ruas. Padi Ciherang mempunyai
batang yang tingginya berkisar antara 107-115 cm dan warna batangya hijau.
c. Anakan, tanaman padi akan membentuk rumpun dengan anakannya, biasanya
anakan akan tumbuh pada dasar batang. Pembentukan anakan terjadi secara
bersusun yaitu anakan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Padi Ciherang
mempunyai anakan produktif sekitar 14-17 batang.
d. Daun, ciri khas daun padi adalah sisik dan telinga daun. Daun padi Ciherang
dibagi menjadi beberapa bagian yakni helaian daun, pelepah daun, dan lidah
daun. Daun berwarna hijau, muka daun sebelah bawah kasar, posisi daun tegak
dan daun benderanya tegak.
2. Bagian Generatif
a. Malai, merupakan sekumpulan bunga padi (Spikelet) yang keluar dari buku paling
atas. Bulir padi terletak pada cabang pertama dan kedua. Panjang malai
tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara menanamnya.
b. Buah padi (Gabah), merupakan ovary yang sudah masak, bersatu dengan palea.
Buah ini adalah hasil penyerbukan dan pembuahan yang mempunyai bagian-
bagian seperti embrio (lembaga), endosperm, dan bekatul. Bentuk gabah padi
Ciherang adalah panjang ramping dan warna gabah kuning bersih. Gabah yang
sudah dibersihkan kulitnya disebut dengan beras. Beras mengandung berbagai
zat makanan yang penting untuk tubuh, antara lain: karbohidrat, protein, lemak,
serat kasar, abu, dan vitamin.
D. DAFTAR PUSTAKA
Aak, 1995. Berbudidaya Tanaman Padi. Kanisius, Yogyakarta.
165
Meiliza, Rika (2006). “Pengaruh Pupuk Terhadap Optimasi Produksi Padi
Sawah di Kabupaten Deli Serdang (Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam)”,
Skripsi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatra Utara.
Mubaroq, I.A., 2013. Kajian Potensi Bionutrien Caf dengan Penambahan Ion
Logam Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Padi. Universitas
Pendidikan Indonesia, Jakarta.
Purwono dan Heni Purnamawati. 2007. Budidaya 8 Jenis Pangan Unggul.
Depok: Penebar Swadaya.
166
PEMANFAATAN MATAHARI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF DALAM
MENGERINGKAN PAKAIAN DI SURYODININGRATAN, MANTRIJERON,
YOGYAKARTA
Oleh: Juliardi Saputra
NIM: 2020015078
A. Analisis Situasi
Suryodiningratan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan
Mantrijeron, Yogyakarta. Jarak kelurahan Suryodiningratan menuju kecamatan
Mantrijeron adalah 300m, jarak menuju kota Yogyakarta adalah 4,0 km, dan jarak
menuju provinsi DIY sekitar 14,8 km. Berikut ini adalah gambaran peta kelurahan
Suryodiningratan menuju kecamatan Mantrijeron.
Gambar 1. Lokasi Kelurahan Suryodiningratan dari Kecamatan Mantrijeron
Indonesia merupakan negara dengan daerah dengan iklim tropis. Di sekitar
daerah Suryodiningratan, matahari bersinar dengan terik menyinari seluruh benda yang
berada pada jangkauannya. Tanaman menggunakan panas dan cahaya matahari untuk
proses fotosintesis dan membuat makanan. Sedangkan warga memanfaatkan sumber
daya tak terbatas ini untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah mengeringkan
pakaian di halaman belakang rumah yang terpapar panas sinar matahari. Berikut ini
adalah gambar baju yang dijemur oleh seorang warga di keluarahan Suryodiningratan.
Gambar 2. Baju yang dijemur dibawah Sinar Matahari
B. Penjelasan Konsep IPA
167
Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di jagat raya ini. Matahari
mempunyai ukuran yang sangat besar dan suhu yang sangat tinggi. Sebagian besar
penyusun matahari berupa gas yang memiliki kerapatan massa sangat padat (Mardiyah:
Jadi matahari merupakan salah satu bintang yang terdiri dari susunan gas dengan
massa rapat serta memiliki ukuran besar dan suhu yang sangat tinggi,
Gambar 3. Gambar matahari
Energi matahari merupakan salah satu energi alternatif. Ada banyak cara untuk
memanfaatkan energi dari matahari. Istilah “tenaga surya” mempunyai arti mengubah
sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik.
Matahari bukan sekedar menerangi alam ini dengan cahayanya yang terang itu,
tetapi matahari memberi tenaga kepada kita dan menggerakkan seluruh proses yang
ada di planet bumi kita ini.
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Sesuai dengan materi pelajaran tematik Kelas 4 SD Tema 2 Subtema 2 tentang
Manfaat Energi dan Subtema 3 tentang Energi Alternatif, Analisis ini memuat tentang
bagaimana manfaat dari matahari sebagai energi alternatif. Energi matahari yaitu energi
panas dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan digunakan sebagai
alternatif sumber cahaya.
Gambar 4. Pembelajaran Kelas 4 Tema 2
Analisis ini juga sejalan dengan materi Perubahan Wujud Benda pada Kelas 3
Tema 6. Perubahan wujud ketika menjemur pakaian dibawah matahari adalah ketika
168
baju yang basah menerima energi panas dari matahari maka air yang ada pada baju
akan menguap sehingga perubahan yang terjadi adalah dari cair menjadi gas.
Gambar 5. Perubahan
D. Daftar Pustaka
Mardiyah, H. (2016). Menyelidiki Matahari. Jakarta: PT Musi Perkasa Utama.
Sidopesko, S. (2011). STUDI PEMANFAATAN ENERGI MATAHARI SEBAGAI PEMANAS
AIR. Berkala Fisika. Vol. 14 No 1, 23-26.
Subarjo, A. H., Mardwianta, B., & Wibowo, T. (2020). PENINGKATAN PENGETAHUAN
PEMANFAATAN ENERGI MATAHARI UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
PADA KELOMPOK PEMUDA DI SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN.
KANCANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Vol. 3, No. 2, 147-154.
.
169
EKOSISTEM PEKARANGAN RUMAH DI DESA SRIMARTANI
Oleh: Margiyanti Palupi
NIM: 2020015080
A. Analisis Situasi
Desa Srimartani merupakan desa yang terletak di bagian timur kecamatan
Piyungan. Sebagian wilayah Desa Srimartani yaitu bagian timur merupakan dataran tinggi
karena berbatasan langsung dengan pegunungan kidul dan hal ini sangat cocok untuk
kegiatan-kegiatan seperti pertanian dan perkebunan terutama untuk padi, sayuran, buah-
buahan, ataupun berbagai jenis bunga, sedangkan bagian baratnya merupakan dataran
rendah dan hal ini cocok untuk ditanami seperti kangkung, kacang panjang ataupun
terong.
Gambar 1. 1 Peta maps desa Srimartani
Desa Srimartani terdiri dari 17 dusun yaitu Dusun Mandungan, Piyungan, Pos
Piyungan, Wanujoyo Kidul, Wanujoyo Lor, Munggur, Mutihan, Daraman, Kwasen,
Mojosari, Kembangsari, Petir, Sanansari, Bulusari, Rejosari, Kemloko, dan Umbulsari.
Mata pencaharian warga di Desa Srimartani beragam pekerjaan yang terdiri dari petani,
peternak, dan lain sebagainya. Desa Srimartani memiliki luas lahan yang berbeda dan ini
tentunya juga membawa konsekuensi pada pemanfaatan pekarangan yang juga
berbeda-beda. Terdapat banyak tanaman ataupun tumbuhan yang ditanam di sekitar
170
pekarangan rumah di Desa Srimartani. Sebagian besar adalah untuk tanaman semusim
baik yang ditanam di polybag atapun di tanah seperti padi, jagung, berbagai jenis bunga
dan tumbuhan lainnya.
Gambar 1. 2 Tumbuh-tumbuhan
Terdapat beberapa hewan yang bisa ditemukan di lingkungan
rumah dan sekitarnya seperti kucing, ayam, burung, serangga,
cicak ataupun kadal kebun. Kebersihan rumah dan lingkungan
sekitarpun cukup terjaga dari sampah
Gambar 1. 3 Hewan-hewa
171
B. Penjelasan Konsep IPA
Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungannya. Menurut Irianto, K (2016) secara struktural ekosistem terdiri dari
komponen biotik dan abiotik. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen
(tumbuhan hijau), konsumen (herbivora, karnivora, dan omnivora), dan dekomposer/
pengurai (mikro-organisme). Komponen biotik ekosistem meliputi; sumber daya
tumbuhan, sumber daya hewan, jasad renik, dan sumber daya manusia. Komponen
abiotik ekosistem meliputi; sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya energi
fosil, udara, serta cuaca dan iklim. Masing-masing komponen yang menjadi bagian dari
ekosistem tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan erat. Organisme
dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu
sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga
memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup.
Ekosistem pekarangan adalah hubungan antara beberapa populasi baik itu
binatang dan tumbuhan serta mahluk hidup lainnya yang hidup dalam suatu kawasan
pekarangan serta membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang
dinamis yang mengadakan interaksi baik secara langsung maupun tak langsung dengan
lingkungannya dan antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Tanaman
pekarangan banyak ragamnya. Keanekaragaman ini menguntungkan, tidak saja dilihat
dari segi hama dan penyakit, melainkan juga dilihat dari segi penggunaan oleh cahaya
matahari oleh tanam-tanaman. Pekarangan adalah taman sederhana yang bersifat
pribadi, dengan hubungan yang erat antara manusia, tanaman, dan hewan. Pekarangan
memiliki banyak fungsi; pekarangan menyediakan banyak jenis tanaman dan binatang
peliharaan yang mana dapat dijual untuk kebutuhan pemilik, sebagai apotik hidup,
mengumpul bersama keluarga, tempat bermain dan sebagainya.
Proyek ekosistem dan komponennya kali ini dilakukan di sekitar pekarangan
rumah. Pada lokasi tersebut diamatilah berbagai macam komponen-komponen
penyusunnya yaitu komponen abiotik dan biotik. Berikut ini adalah komponen abiotik
ekosistem pekarangan rumah:
Suhu dan kelembaban
Pada pengamatan yang dilakukan, suhu dipekarangan rumah sedang karena di pagi
hari pada jam kurang lebih sekitar 10. 00 WIB dengan cuaca yang cerah.
Intensitas cahaya
172
Intensitas cahaya cukup bagus karena pekarangan berada didepan rumah dan letak
permukiman tidak terlalu padat sehingga cahaya tidak terhalang dan bisa masuk
dengan baik, sehingga tumbuhan akan tumbuh dengan baik.
pH Tanah
pH tanah di ekosistem pekarangan rumah cocok dengan tumbuhan yang ada karena
banyak tumbuhan yang subur.
Temperatur
Memiliki temperature normal karena intensitas cahaya di pekarangan juga cukup dan
bagus. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Tabel Pengamatan Rantai Makanan di Suatu Ekosistem
Komponen Rantai Makanan
No. Ekosistem Produsen Konsumen Konsumen Penguraian
I II
Pekarangan Jagung Ulat Ayam Belatung
1.
rumah
Pepaya Kelelawar Ular Belatung
buah
Tabel Pengamatan Simbiosis
Pihak Yang Dirugikan Pihak Yang Diuntungkan
Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
Hubungan Makhluk Kerugian Makhluk Keuntungan
Hidup Hidup
Pohon pete Produksi Benalu Menyerap
dengan Benalu Pohon pete makanan makanan dari
berkurang dan pohon pete
tidak bisa
berbuah
173
Kutu pada Kucing Terhisap Kutu kucing Menghisap
kucing darah kucing
darahnya dan
Memakan
gatal daun tanaman
cabe
Ulat pada Tanaman Kehilangan Ulat
daun tanaman cabe
Cabe daun
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Menurut Nurdyansyah, & Amalia, F (2018) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah, yang mana dapat memberikan peranan
dan pengalaman bagi siswa. IPA adalah salah satu mata pelajaran yang berkaitan
dengan pengetahuan alam secara sistematis. IPA bukan hanya pengetahuan berupa
fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Pendidikan IPA di Sekolah Dasar diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk
mempelajari dirinya sendiri dan alam di sekitarnya.
Lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh terhadap
berlangsungnya proses pembelajaran. Lingkungan yang ada di sekitar seperti
pekarangan rumah siswa merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan
dalam proses pembelajaran. Lingkungan sekitar mempunyai keterkaitan penting dalam
proses pembelajaran IPA di Sekolah Dasar karena lingkungan dapat berfungsi sebagai
sasaran belajar, sumber belajar, maupun sarana belajar IPA. Pada dasarnya anak usia
Sekolah Dasar taraf perkembangan intelektualnya termasuk katagori operasional konkret.
Melalui pemanfaatan lingkungan sekitar seperti mengamati ekosistem di pekarangan
rumah dalam proses pembelajaran IPA, maka siswa dapat memperoleh pengalaman
konkret sehingga diharapkan lebih mudah dalam memahami konsep IPA. Sehingga, jika
guru mengajar dengan memanfaatkan lingkungan seperti dipekarangan rumah ataupun
sekolah sebagai sumber belajar maka akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan
pada kenyataan dan peristiwa yang sebenarnya.
Menurut Muchtiar, Y & Mufti, D. (2018) Penggunaan lingkungan sekitar dalam
proses pembelajaran mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar
siswa, membantu keefektifan proses pembelajaran, mengarahkan perhatian siswa untuk
berkonsentrasi pada isi pelajaran, memperlancar pencapaian tujuan, untuk memahami
dan mengingat informasi yang diberikan, pembelajaran menjadi lebih menarik, membawa
variasi baru bagi belajar siswa sehingga siswa tidak bosan dan bersifat pasif, serta dapat
mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu dengan menghadirkan gambaran objek
yang sedang dipelajari di luar kelas.
174
D. Daftar Pustaka
Irianto, K. (2016). Ilmu Lingkungan. Denpasar: PT. Percetakan Bali.
Muchtiar, Y., & Mufri, D. (2018). Optimasi Penggunaan Pekarangan Sekolah Sebagai
Media Pembelajaran. JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK JPMT, 1,
1-9.
Nurdyansyah, & Amalia, F. (2018). Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada
Pembelajaran IPA Materi Komponen Ekosistem. UMSIDA, 1-8.
175
KARAKTER MORFOLOGIS TANAMAN SALAK DI DUSUN DUSUN KRADENAN
SELATAN, DESA KRADENAN, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN
MAGELANG
Oleh : Nova Dwi Irawan
NIM : 2020015336
A. Analisis Situasi
Dusun Kradenan Selatan merupakan salah satu wilayah di Desa Kradenan,
Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang terletak di koordinat 7°36'27.5"S
110°19'34.0"E. Luas wilayah Dusun Dusun Kradenan Selatan sebesar 232.445,67 m²
(2.502.024,35 kaki²). Pulau. Dusun Kradenan Selatan sebagai salah satu pusat
perkebunan salak mempunyai potensi yang cukup besar untuk menghasilkan varietas-
varietas unggul yang lebih bernilai ekonomis dan kompetitif (Darmadi, 2001). Produksi
buah salak hanya untuk Dusun Kradenan Selatan mencapai 1000 ton per tahun.
Perkebunan salak di Dusun Kradenan Selatan dikelola langsung oleh masyarakat
(Statistik Kantor Kecamatan, 2012). Di Dusun Kradenan Selatan salak yang ditanam
adalah salak pondoh, Penanaman salak pondoh ini menyebar luas di Dusun Kradenan
Selatan.
Di Indonesia terdapat beberapa varietas salak yang dibudidayakan petani, oleh
karena itu pengkajian mengenai karakter morfologis perlu diketahui. Informasi
mengenai keragaman sangat diperlukan dalam program pemuliaan tanaman karena
dengan semakin tersedianya informasi tersebut, semakin mudah dalam menentukan
kedudukan atau kekerabatan antar varietas yang dapat dijadikan sebagai dasar
seleksi tanaman (Puslitbanbun, 2007). Penelitian Karakter morfologis bertujuan untuk
mendapatkan data sifat dasar sehingga dapat dibedakan fenotip dari setiap aksesi
dengan cepat dan mudah, dengan menduga seberapa besar keragaman genetik yang
dimiliki (Bermawie, 2005). Karakteristik morfologis tanaman salak dapat dilihat
berdasarkan ciri vegetatif maupun ciri generatifnya yang berguna untuk mendapatkan
deskripsi dan klasifikasi tanaman salak sehingga dapat mempermudah dalam
menentukan varietas tanaman salak. Pada masa mendatang masih ada kemungkinan
ditemukan varietas baru, mengingat terjadinya penyerbukan silang (Santoso 1990).
Pengamatan morfologis berguna untuk mengetahui pengembangan budidaya
tanaman salak melalui pemuliaan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi morfologis
tanaman salak. Informasi mengenai karakteristik salak. Di Dusun Kradenan Selatan
sampai saat ini belum pernah ada sebelumnya. Informasi tersebut penting untuk
diketahui guna pengembangan budidaya tanaman salak di Dusun Kradenan Selatan.
176
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian
mengenai karakteristik morfologis tanaman salak di Dusun Kradenan Selatan yang
merupakan sentra perkebunan salak di Kecamatan Srumbung.
Penelitian dilaksanakan di salah satu kebun petani yaitu Samukri pemilik kebun
salak pondoh yang sudah berumur 36 tahun, dengan cara memperbanyak salak
pondoh melalui proses cangkok. Aktifitas penelitian dilaksanakan dalam waktu sehari.
Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman salak
mentega dan salak Pondoh di Dusun Kradenan Selatan yaitu kamera, parang,
meteran, dan alat tulis. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode survei pada
salah satu kebun petani. Diambil satu pohon salak pondoh untuk diamati. Karakter
yang diamati meliputi : 1) Morfologi batang : tinggi tanaman dan lingkar batang; 2)
Morfologi daun : panjang pelepah, jumlah anak daun, panjang ibu tangkai daun dan
panjang helai anak daun; 3) Morfologi buah : warna kulit buah, bentuk buah, jumlah
buah per tandan, dan jumlah tandan perpohon.
B. Penjelasan Konsep IPA
Dalam menentukan karakteristik morfologi salak pondoh Dusun Kradenan
Selatan dilakukan pengamatan dan pengukuran. Pengamatan dan pengukuran terdiri
atas 10 karakter yaitu :
1. Morfologi Batang
Tinggi tanaman dalam satuan meter (m). Tinggi tanaman diukur dari
leher akar sampai ujung daun termuda yang sudah mekar sempurna. Untuk
mempermudah pengukuran digunakan bambu atau galah.
2. Morfologi Daun
Yang pertama yaitu susunan anak daun diamati dengan mengamati
karakteristik daun tersebut sesuai dengan kriteria susunan anak daun. Yang
kedua ukuran daun (cm) diukur pada bagian tengah helaian daun yang terlebar
dengan menggunakan alat ukur meteran. Selanjutnya warna daun diamati
dengan cara visual yaitu mengetahui warna bagian atas dan bagian bawah
daun. Warna pelepah daun diamati adalah dengan cara visual dengan
mengetahui warna pelepah pada tanaman. Panjang pelepah daun diukur
dengan menggunakan meteran dari pangkal pelepah sampai ujung, pelepah
yang diambil adalah pelepah yang memiliki kondisi normal serta tidak
mengalami kerusakan akibat hama. Diamati warna duri pada tangkai-tangkai
dan batang salak yang dilakukan secara visual
3. Morfologi Bunga
177
Pengamatan bunga pada tanaman diamati dengan mengetahui bentuk
dan jenis bunga pada tanaman salak tersebut sesuai dengan karakteristik
pedoman yang telah ditentukan. Pengamatan warna bunga dilakukan dengan
cara visual dengan mengetahui warna kelopak, mahkota, kepala putik dan
benang sari. Bunga yang diamati adalah bunga betina dan bunga jantan pada
tanaman salak. Pengamatan pada kedudukan bunga salak dilakukan dengan
mengamati secara visual dengan melihat letak atau posisi bunga yang terdapat
pada ketiak pelepah pada tanaman salak tersebut. Panjang tongkol bunga (cm)
dengan meluruskan tongkol bunga dan di ukur dengan menggunakan meteran
dari bawah tongkol bunga sampai ujung tongkol bunga. Pengamatan jumlah
tongkol bunga dilakukan dengan menghitung jumlah tongkol bunga per tandan
pada tanaman salak setiap sampel. Warna seludang bunga diamati dengan
cara visual dengan mengetahui warna seludang tersebut. Panjang seludang
bunga salak dengan meluruskan seludang bunga yang membungkus bunga
salak yang akan berbuah, kemudian diukur dengan menggunakan meteran
dari bawah seludang bunga sampai ujung seludang bunga.
4. Morfologi Buah
Jumlah tandan dihitung berdasarkan tandan yang terdapat pada setiap
tanaman sampel. Tandan buah yang dihitung adalah tandan dengan buah
salak sudah terbentuk sempurna mencakup buah yang masih muda sampai
buah yang sudah tua. Pengukuran berat buah salak dilakukan dengan
menggukan timbangan pada masing-masing buah salak yang dijadikan
sebagai sampel peneltian. Warna kulit buah salak diamati secara visual sesuai
dengan warna kulit salak. Warna daging buah salak diamati secara visual
setelah kulit buah dikupas kemudian diamati warna daging buah tersebut
sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Tebal daging buah diukur
dengan menggunakan jangka sorong pada potongan melintang dan membujur
pada buah salak. Rasa daging buah salak diukur dengan mengambil pada
buah yang tua.
5. Morfologi Biji
Pengamatan warna biji salak yang tua dilakukan dengan membuka kulit
dan daging buah salak untuk melihat warna biji yang terdapat pada salak.
Pengamatan bobot biji tua dilakukan dengan membersihkan seluruh daging
buah yang menempel pada biji kemudian menimbangnya.
Karakterisasi morfologi tanaman salak dilakukan dengan mengamati
parameter yang telah ditentukan berdasarkan SK. Menteri Pertanian
No.12/kpts/SR.130/D/8/2019. Berikut ini disajikan tabel pengamatan karakter
178
morfologis tanaman salak pondoh dengan sampel pemilik Samukri di Dusun Kradenan
Selatan, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
Tabel karakter morfologis tanaman salak pondoh
No Parameter Karakter
1 Tinggi tanaman 572 cm
2 Bentuk batang Bulat
3 Panjang pelepah 610 cm
4 Susunan anak daun Menyirip
5 Warna daun bagian atas Hijau tua
6 Warna daun bagian bawah Hijau keabuan
7 Warna pelepah daun Hijau kecoklatan
8 Ukuran daun tua Panjang 68 cm, lebar 4,5 cm
9 Warna duri Hitam
10 Warna bunga Merah
11 Kedudukan bunga Di ketiak pelepah
12 Panjang tongkol bunga 14 cm
13 Jumlah tongkol bunga 4 tandan
14 Panjang seludang bunga 26 cm
15 Warna seludang bunga Coklat
16 Jumlah tandan buah 2 tandan
17 Bentuk buah Bulat lonjong
18 Bobot buah 82,26 gram
19 Warna kulit buah Coklat kehitaman
20 Warna daging buah Putih
21 Tebal daging buah 10,2 mm
22 Tekstur daging buah Berserat halus
23 Rasa daging buah Manis Asam
24 Kandungan air buah Basah
25 Bobot biji tua 7,71 gram
26 Warna biji tua Coklat
179
(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
(g) (h) (i)
Gambar karakter morfologis tanaman salak pondoh : (a) pohon, (b) seludang
bunga, (c) tandan buah, (d) daun, (e) bunga, (f) buah dengan kulit, (g)
potongan membujur buah, (h) potongan melintang buah, (i) biji
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
180
Keterkaitan pengamatan morfologi salak pondoh di Dusun Kradenan Selatan
dengan pembelajaran IPA di SD yaitu adanya pembahasan mengenai morfologi dalam
pembelajaran kelas 4 SD, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 mengenai
pengamatan dan identifikasi (morfologi) bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya
(tumbuhan yang ada di sekitar yaitu padi). Pembelajara kelas 4 SD, tema 3, subtema
1, pembelajaran ke-1 memiliki kompetensi dasar yang berkaitan sebagai berikut :
1. 3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada
hewan dan tumbuhan.
2. 4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian
tubuh hewan dan tumbuhan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian morfologi salak pondoh berkaitan
dengan pembelajaran yang ada di SD. Pada kegiatan pembelajaran di SD nantinya
peserta didik akan diminta untuk mempelajari lalu menjelaskan bentuk luar tumbuhan
dan fungsinya kemudian menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar tumbuhan
serta fungsinya. Peserta didik juga dituntuk dapat menjelaskan bentuk luar tumbuhan
dan fungsinya setelah mengamati gambar.
D. Daftar Pustaka
Anggari, A. S., Afriki, Retno, D., & Puspitawati, N. (2017). Peduli Terhadap Makhluk
Hidup Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 3. Jakarta: Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
Darmadi. (2001.). Tingkat kematangan Salak. Skripsi.
Fatimah, S. (2013). Analsis Morfologi dan Hubungan Kekerabatan Sebelas Jenis
Tanaman Salak. Universitas Trunojoyo Madura Agrovigor .
H, P. (2010). Budidaya Salak Pondoh. Semarang: PT. Pabelan.
Lestari, R. E.–K. (2011). Growth and Physiological responses of Salak Cultivars
(Salacca zalacca (Gaertn) Voss) to Different Growing Media. J. Agric. Sci. , 4 (3),
261-271.
Pertanian, T. B. (2019). Salak (Salacca edulis). Jakarta: Deputi Menegristek Bidang
Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
RI, K. P. (2019). Teknis Penyusunan Deskripsi Dan Pengujian Kebenaran Varietas
Tanaman Hortikultura. No. 12/kpts/SR.130/D/8/2019.
181
Santoso, H. (1990). Salak Pondoh. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
182
PUPUK ORGANIK DARI DAUN KERING
Oleh : Azminatun Bidiyah
NIM. 2020015337
A. Analisis Situasi
Dusun Malangrejo merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak , Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), jarak Dusun Malangrejo dengan Ibukota Kecamatan Ngemplak sekitar
7 km, jarak ke Ibukota Kabupaten Sleman sekitar 13 km, dan jarak ke Ibukota Provinsi
DIY sekitar 15 km. Gambar 1 menunjukkan lokasi Dusun Malangrejo dari pusat kota
Yogyakarta.
Gambar 1. Lokasi Dusun Malangrejo
Penduduk Dusun Malangrejo terdiri dari 240 kepala keluarga (KK) atau sekitar 600
jiwa. Mata pencaharian masyarakat Dusun Malangrejo sebagian besar adalah sebagai
petani. Pemuda di Dusun Malangrejo aktif dan selalu berantusias dalam komunitas
dengan kegiatan yang positif seperti karang taruna dan organisasi kerohanian islam atau
remaja masjid. Para pemimpin di Dusun Malangrejo juga sangat aktif terhadap kegiatan
yang memberikan dampak baik untuk kemajuan desa.
Selain adanya potensi sumber daya manusia, dusun ini memiiki potensi lainnya
yaitu sumber daya alam berupa pemandangan dusun yang sejuk, area kebun, area
persawahan, budidaya peternakan, tradisi budaya yang masih jalan sampai saat ini dan
berbagai potensi lainnya. Berbagai potensi alam ini dapat digunakan sebagai sarana untuk
mempelajari IPA karena pada hakikatnya seseorang akan belajar IPA dari apa yang
183
mereka temui di kehidupan nyata. Seorang belajar IPA berdasarkan permasalahan yang
ditemui sehari-hari, mencoba memberikan solusi berdasarkan teori lalu menerapkan
kembali solusi terebut di masyarakat.
Di Dusun Malangrejo ini masih terdapat area kebun yang banyak ditumbuhi pohon-
pohon rimbun yang menjulang tinggi. Sehingga pastinya akan ada banyak daun yang
berguguran dari pohon-pohon tersebut.
Gambar 2. Kebun Pohon Rimbun
Daun-daun kering ini merupakan permasalahan dan dianggap sangat
mencemarkan gangguan kelestarian alam. Daun-daun yang berguguran tersebut
dimanfaatkan oleh warga sekitar, yaitu diolah untuk dijadikan pupuk organik atau pupuk
kompos yang nantinya dapat digunakan masyarakat sebagai media tanam untuk
menanam tumbuhan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Seorang anak bisa
mempelajari IPA dari proses pembuatan dan penggunaan pupuk organik ini.
184
Gambar 3. Pupuk Organik dari Daun Kering
B. Penjelasan Konsep IPA
Daun-daun kering yang dianggap sampah sangat berpotensi menjadi pupuk
organik dengan diperkaya EM-4 (mikroba). Pupuk organik yang telah jadi dapat
menyumbangkan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, sehingga dapat
meningkatkan produksi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan dan
tanaman tahunan. (Neni Marlina, 2021 : 109)
Kompos merupakan pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik, seperti daun
dan Jerami yang membusuk. Pembusukan bahan-bahan organik ini disebut dengan
proses dekomposisi. Sejak abad ke 17 M jauh sebelum manusia menemukan pupuk kimia,
masyarakat sudah mengenal kompos yakni pemanfaatan limbah untuk dijadikan sebagai
penyubur alami tumbuhan. (Nisa, 2016 : 3)
Cara pengaplikasian pupuk organik di lapangan yaitu dengan berbagai cara yaitu
cara sebar, tugal, larikan, lingkaran. Pupuk organik disebarkan ke lahan secara merata
185
kemudian ditutup dengan tanah agar terhindar dari penguapan dan tercuci oleh air hujan,
kalau tanaman ditanam di polybag cukup diberikan secara lingkaran atau tugal di polybag,
sedangkan larikan diberikan diantara tanaman.
Gambar 4. Menanam di polybag
Penggunaan kompos sebagai bahan pembenah tanah (soil conditioner) yang
dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah (berupa sifat fisika, kimia dan biologi
tanah) sehingga mampu untuk mempertahankan kesehatan dan menambah kesuburan
tanah. Karakteristik umum yang dimiliki kompos yaitu sebagai berikut : (Triyanto, 2020)
1. Mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah bervariasi tergantung bahan asal.
2. Menyediakan unsur hara secara lambat (slow release) dan dalam jumlah terbatas.
3. Mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah.
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Materi mengenai sumber daya alam dipelajari di kelas IV yaitu pada KD 3.8 dan
KD 4.8. KD 3.8 yaitu Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian
sumber daya alam di lingkungannya. Sedangkan KD 4.8 yaitu Melakukan kegiatan upaya
pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya.
Pembelajran IPA SD berkaitan dengan materi ini bisa dirancang melalui
pengamatan, penugasan, eksperimen, tanya jawab, dan diskusi. Dalam pembelajaran IPA
di SD penerapannya tidak jauh berbeda dengan konsep pembelajaran pada mata
pelajaran lainnya hanya tekanannya harus sesuai dengan hakikat IPA itu sendiri, bahwa
belajar IPA harus terjadi proses sains, menghasilkan produk sains dengan melakukan
186
eksperimen/percobaan mengenai pupuk organik. Pembelajaran IPA tidak bisa
menggunakan cara menghafal atau mendengarkan guru terlalu sering pada saat
penyampaian materi, peserta didik sendiri yang harus melakukan pembelajaran melalui
percobaan, pengamatan maupun eksperimen secara aktif.
D. Daftar Pustaka
Eliyani, O. dkk. (2022). PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPA
SEKOLAH DASAR DENGAN PERTUMBUHAN KANGKUNG DARAT
MENGGUNAKAN PUPUK. Griya Cendikia, 14-20.
Neni Marlina, dkk. (2021 : 109). Pemanfaatan Serasah Daun Kering sebagai Pupuk
Organik di Dusun Talang Ilir Kelurahan Sukamoro Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. International Journal of Community Engagement, 108-113.
Nisa, K. dkk. (2016 : 3). Memproduksi Kompos & Mikro Organisme Lokal (MOL). Jakarta
Timur: Bibit Publisher.
Triyanto. (2020). Membuat Pupuk Kompos dengan Sederhana. Jakarta : PT Elek Media
Komputin.
187
KOMPONEN BIOTIK DAN ABIOTIK EKOSISTEM SUNGAI DI DUSUN
KEDUNGWANGLU
Oleh: Ainun Min Safarina
NIM. 2020015338
A. Analisis Situasi
Dusun Kedungwanglu merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa
Banyusoco, Kecamatan Playen, Kebupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Jarak Dusun Kedungwanglu dengan Ibu Kota Wonosari sekitar 21 km
dan jarak ke ibukota provinsi DIY sekitar 31 km.
Gambar 1.1 Peta jarak dusun kedungwanglu ke ibukota wonosari
( Sumber: Dokumen Pribadi )
188
Gambar 1.2 Sungai Prambutan
( Sumber: Dokumen Pribadi )
Padukuhan Kedungwanglu juga terkenal dengan Bumi Perkemahan Ngebrak.
Sebuah tanah lapang hijau yang dikelilingi hutan dan sungai ini akan memanjakan
pengunjung dengan pemandangan indah dan suasana sejuknya. Begitu dekatnya
bumi perkemahan ini dengan sungai, pengunjung dapat sewaktu-waktu bermain di
sungai ketika menginap disini.
Padukuhan Kedungwanglu dikelilingi Sungai Prambutan dan Oya. Sungai
Prambutan mengalir dari sisi timur dan membelah Kedungwanglu menjadi dua
bagian. Alirannya bermuara di Kali Oya yang berada di barat padukuhan. Sungai yang
bedekatan dengan Bumi Perkemahan Ngebrak yaitu Sungai Prambutan.Ekosistem
sungai dengan berbagai interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan
juga lingkungannya yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. ekosistem
sungai meliputi interaksi komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen
biotik dan abiotik ini merupakan komponen- komponen yang dimiliki oleh semua jenis
ekosistem, termasuk ekosistem sungai Sungai Prambutan memiliki berbagai macam
komponen baik biotik dan abiotik.
B. Penjelasan Konsep IPA
Menurut (Suryanti, 2013) dalam (Odum 1993) sungai merupakan ekosistem air
tawar yang mengalir, yang mempunyai ciri khas yaitu adanya arus yang merupakan
faktor yang mengendalikan dan merupakan faktor pembatas di sungai. Menurut
(Suryanti, 2013) dalam (Fachrul, 2007) ekosistem sungai merupakan kumpulan dari
komponen abiotik (fisika dan kimia) dan biotik (organisme hidup) yang berhubungan
satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu struktur fungsional.
Menurut (Rahmatullah Djunaid, 2018) Komponen biotik meliputi seluruh makhluk
hidup di bumi. Antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan
tingkat tinggi, hewan Invertebrata dan hewan Vertebrata termasuk manusia.
Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu
ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan.
Komponen abiotik meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu,
kelembapan dan derajat keasaman (pH).
1. Komponen Biotik
Komponen biotik merujuk pada komponen di dalam ekosistem yang berupa
makhluk hidup, sebagai berikut:
a. Lumut
189
Lumut biasanya tumbuh pada tempat-tempat yang lembab, seperti sungai. Dalam
ekosistem lumut memiliki peran yaitu sebagai penghasil oksigen.
Gambar 2.1 Tumbuhan Lumut
( Sumber : http://saswinhtml.blogspot.com/2012/04/2.html )
b. Siput
Siput sering dijumpai disungai yang tenang. Siput sungai memiliki banyak
jenis dan digemari oleh beberapa kalangan masyarakat.
Gambar 2.2 Siput Sungai
( Sumber: https://titiknol.co.id/gaya-hidup/manfaat-siput-sungai-yang-perlu-
diketahui/ )
c. Serangga
Di sungai tedapat berbagai jenis serangga salah satunya anggang-anggang.
Anggang-anggang sering ditemui diarea sungai yang tenang. Serangga ini
menyerupai laba-laba dan bisa berjalan diatas air.
190
Gambar 2.3 Serangga Anggang-anggang
( Sumber: https://www.greeners.co/flora-fauna/anggang-anggang-serangga-
berjalan-air/ )
d. Ikan
Ikan memiliki berbagai jenis dengan berbagai karakter yang berbeda. Salah
satu jenis ikan sungai yaitu ikan nila. Selain dijumpai di sungai ikan nila juga
banyak dikembangbiakkan di kolam oleh masyarakat. Ikan nila banyak digemari
oleh kalangan masyarakat karena memiliki daging yang tebal.
Gambar 2.4 Ikan Nila
( Sumber: https://www.greeners.co/flora-fauna/ikan-nila/ )
2. Komponen Abiotik
Komponen abiotik merujuk pada komponen didalam ekosistem berupa benda
mati. Komponen ini meliputi tanah, air, udara, batu dan sinar matahari.
a. Tanah
Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem.
Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh
makhluk hidup.
191
Gambar 3.1 Tanah
( Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Aluvial )
b. Air dan Batu
Dalam ekosistem sungai air merupakan komponen abiotik yang penting bagi
makhluk hidup. Air berperan sebagai habitat dari berbagai makhluk hidup di
sungai. Air berfungsi untuk menjalankan metabolisme makhluk hidup, sebagai
pelarut sitoplasma, dan mencegah sel dari kekeringan. Batuan berperan sebagai
tempat tinggal organisme sungai.
Gambar 3.2 Air dan Batu
( Sumber: Dokumen Pribadi )
c. Udara
Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas
lainnya. Oksigen diperlukan oleh makhluk hiudp untuk bernapas. Nitrogen
merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan oleh makhluk hidup
untuk membentuk protein dan senyawa lainnya.
d. Sinar matahari
Matahari merupakan sumber energi bagi setiap makhluk hidup di bumi salah
satunya organisme yang ada di sungai. Jika tidak ada matahari, bumi akan gelap
gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Akibatnya,
192
tumbuhan akan mati. Jika tidak ada tumbuhan yang hidup, maka hewan dan
manusia pun tidak pernah ada di bumi ini. Karena tidak ada bahan makanan.
Gambar 3.3 Sinar Matahari
( Sumber: Dokumen Pribadi )
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Materi ekosistem terdapat dalam materi kelas V (lima) SD dalam tema 5 ekosistem
subtema 1 komponen ekosistem. Sebagai salah satu muatan dalam tematik, materi IPA
menjadi satu pembahasan yang penting. Dalam materi IPA, peserta didik diajak untuk
mengenal alam sekitar dengan segala pengetahuan di dalamnya. Berikut merupakan
kompetensi inti dan kompetensi dasar IPA kelas V (lima) SD dalam buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013:
1. Kompetensi Inti Kelas V (lima)
a) Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
b) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangga, dan negara.
c) Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan
tempat bermain.
d) Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan
193
anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan
tahap perkembangannya.
2. Kompetensi dasar dalam materi IPA SD
3.5 Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di
lingkungan sekitar.
4.5 Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem.
D. Daftar Pustaka
Karitas, D. P. (2017). Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Rahmatullah Djunaid, H. S. (2018). Gastropoda di Perairan Budidaya Rumput
Laut (Eucheuma sp) Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Jurnal
Bionature, 37.
Suryanti, S. R. (2013). KUALITAS PERAIRAN SUNGAI SEKETAK SEMARANG
BERDASARKAN KOMPOSISI DAN KELIMPAHAN FITOPLANKTON .
JOURNAL OF MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES, 39.
194
PEMANFAATAN HUKUM ARCHIMEDES DALAM PARIWISATA GETHEK RAKSASA
DIROWO JOMBOR, KRAKITAN, BAYAT, KLATEN, JAWA TENGAH
Oleh: Satria Ari Putra
NIM. 2020015339
A. Analisis Situasi
Rowo Jombor merupakan tempat wisata yang terletak di Dukuh Jombor, Desa
Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Jarak Rowo Jombor dari pusat Kota
Klaten kurang lebih 8 Km (delapan kilometer).
Gambar 1. Lokasi Rowo Jombor dari pusat kota Klaten.
Rawa Jombor mempunyai fungsi utama yaitu untuk menampung air dari sungai-
sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk
mengoncori sawah-sawah di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga
dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pariwisata dan perikanan. Salah satu sarana
pariwisata yang dikelola warga sekitar rowo jombor adalah wisata Perahu Gethek
Raksasa.
Gambar 2. Gethek raksasa yang ada di rowo jombor
195
Gethek atau rakit bambu yang biasanya digunakan untuk menyebrangi sungai
sekarang digunakan sebagai sarana pariwista. Dikarenakan bentuknya yg unik gethek
raksasa dapat menarik minat para pengunjung. Disamping itu saat kita menaiki gethek
tersebut kita akan dibawa keliling Rowo Jombor untuk melihat dan menikmati keindahan
Rowo Jombor dengan jelas. Selain digunakan untuk pariwisata hal itu juga dapat
membantu perekonomian warga sekitar dan menambah pemasukan desa.
B. Penjelasan Konsep IPA
Seseorang dapat mempelajari IPA melalui peristiwa mengapungnya gethek rawa
jombor. peristiwa mengapungnya gethek disebabkan karena adanya gaya Archimedes
yang dapat membuat gethek mengapung.
hukum archimedes berperan dalam mengapungnya gethek karena massa gehtek
lebih kecil daripada massa air. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka berat
benda atau gaya berat benda dilawan oleh gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair.
Gaya berat memiliki arah ke bawah dan gaya zat cair memiliki arah ke atas. Berdasarkan
besarnya gaya berat dan gaya ke atas (gaya apung), posisi benda dalam zat cair
digolongkan menjadi tiga yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung (Sukabdiyah,
2012: 69).
C. Keterkaitan Konsep dengan Pembelajaran IPA di SD
Hukum Archimedes merupakan suatu hukum yang menyatakan bahwa setiap benda
yang tercelup ke dalam suatu zat cair ataupun fluida sebagian maupun seluruh
bagiannya, maka benda tersebut akan memiliki gaya dorong ke atas atau yang biasa
disebut gaya apung. Gaya dorong yang diterima tersebut besarnya akan sama dengan
berat cairan ataupun fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Terdapat tiga
kemungkinan yang akan terjadi, yakni benda tersebut mengapung, melayang, atau
tenggelam (Calloni et al, 2016).
Bunyi hukum archimedes tak jauh dari pengertiannya. Ia menyatakan bahwa “Jika
sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan
gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya”. Persamaannya dapat
dinyatakan berbanding lurus dengan massa jenis fluida, percepatan gravitasi, serta
volume benda (Say, 2018).
Saat benda dicelupkan ke dalam zat cair, terdapat tiga kemungkinan yang akan
terjadi. Yakni benda dapat mengapung, dimana merupakan kondisi saat massa jenis zat
cair lebih besar dari massa jenis benda. Kemudian dapat pula melayang, dimana
merupakan kondisi saat massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dapat
pula tenggelam, dimana merupakan kondisi saat massa jenis benda lebih besar daripada
196
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku proyek 1 IPA Terpadu SD hasil observasi dari mahasiswa kelas 4B semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
Buku Proyek 1 IPA Terpadu SD ini yang berjudul "Pendidikan IPA di Lingkungan Tempat Tinggalku" telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai keterkaitan lingkungan sekitar dengan konsep IPA terpadu.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search