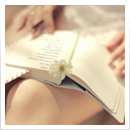i
ii REKAYASA HIDROLOGI Dr. Ir. Susilawati Cicilia Laurentia, MscHE.
iii REKAYASA HIDROLOGI Penulis : Dr. Ir. Susilawati Cicilia Laurentia, MscHE Desain cover : Krismawanti Editor: Esa Fajar Amirullah, S.Kom. Ukuran: Jml hal 187, Uk: 15.5 x 23 cm ISBN: 978-623-88428-3-4 Cetakan Pertama: Februari 2023 Hak Cipta 2022, Pada Penulis lsi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2022 by UNTAG Press All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT UNTAG PRESS Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Contact Person : +62 896-9711-3975 (krismawanti) +62 857-1250-0634 (M. Fahd Diyar Husni) Website: https://untag-press.untagsmg.ac.id Email: [email protected] Kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas dana Bantuan Program Pengabdian Masyarakat Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Hasil Penelitian PTS 2022
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI iv KATA PENGANTAR Buku ajar Rekayasa Hidrologi ini dibuat untuk menjadikan pegangan bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Rekayasa Hidrologi. Sistematika penyusunan buku ajar ini dibuat sedemikian rupa merupakan rangkaian yang berlanjutan. Pertama-tama dibahas mengenai pengertian hidrologi, latar belakang dan sejarahnya. Kemudian diperkenalkan siklus hidrologi dan wawasan persediaan air di bumi, keseimbangan air dan beberapa istilah dalam hidrologi. Awal mula dari siklus hidrologi adalah hujan atau dalam istilah hidrologi lebih dikenal dengan presipitasi dengan berbagai bentuknya, begitu juga jenis-jenis hujan. Kemudian diperkenalkan alat penakar hujan. Selanjutnya akan dibahas terkait karakter hujan dan bagaimana memroses data hujan. Air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan tanah sebagai limpasan permukaan, meskipun sebagian ada juga yang meresap ke dalam tanah. Diperkenalkan pula hubungan dan proses air hujan yang jatuh dan menjadi limpasan permukaan. Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan air hujan yang jatuh, mengalir dan meresap kedalam tanah, antara lain istilah intersepsi, tampungan depresi, infiltrasi dan perkolasi. Oleh pengaruh sinar matahari, angin dan suhu udara, air hujan yang jatuh tersebut akan mengalami penguapan atau dikenal dengan istilah evaporasi untuk yang ada dalam tampungan terbuka atau dari permukaan tanah. Istilah transpirasi dikenal untuk menyebutkan kandungan air dalam tanaman yang menguap. Ganbungan antara proses evaporasi dan transpirasi dikenal dengan istilah evapotranspirasi. Air yang terkumpul dan mengalir di permukaan menuju ke sungai yang dikenal sebagai aliran air atau streamflow. Akan diperkenalkan definisi dari streamflow, kemudian cara mengukur dan menganalisisnya. Dalam melakukan analisis hidrologi tak dapat tidak perlu memahami statistic dalam hidrologi. Beberapa konsep statistik diperkenalkan. Sebelum data hidrologi digunakan dalam analisis maka perlu diuji kelayakan data tersebut. Hal ini akan dibahas dalam topik
KATA PENGANTAR BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI v tersendiri yaitu uji kelayakan data atau data screening. Kemudian diperkenalkan berbagai metode analisis hidrologi. Salah satu metode yang terkenal dalam analisis hidrologi adalah hidrograf. Diperkenalkan pengembangan dari relasi hidrograf, unit hidrograf dan aplikasinya. Hal yang paling menjadi gangguan dalam kehidupan ini adalah terjadinya banjir atau air yang berlebihan dan tidak diharapkan. Konsep dari perancangan banjir, analisisnya, juga menelusurinya akan memberikan wawasan bagaimana mengatasinya, baik secara struktural maupun non struktural. Penelusuran banjir ini dapat dilakukan dari segi hidrologisnya maupun hidrolikanya. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau mempunyai karakter hidrologi yang khas. Tantangan-tantangan apa yang ditimbulkannya, sekaligus peluang-peluang yang diberikan dalam suatu hidrologi kepulauan. Konsep pengelolaan air hujan menjadi peluang yang perlu dikembangkan agar dalam situasi air berlebihan dan diatasi dengan mengkonservasinya untuk dapat dimanfaatkan di kemudian hari saat air kurang. Pengelolaan air hujan ini dapat dilakukan dalam skala daerah tangkapan besar, sedang maupun kecil. Pembahasan rekayasa hidrologi ini akan ditutup dengan memperkenalkan beberapa aplikasi hidrologi yang ada. Buku ajar ini disusun sedemikian rupa diikuti dengan tugas-tugas terstruktur yang harus dikerjakan mahasiswa, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mempelajari pengetahuan rekayasa hidrologi dengan santai secara pribadi dan bersama kelompok mendiskusikan dan mengungkapkan dalam suatu kreatifitas dan inovasi. Segala masukan sangat diharapkan, sehingga akan menjadikan buku ajar ini lebih baik dan semakin sempurna. Terima kasih untuk partisipasi dan bantuan yang boleh terjadi atas penyelenggaraan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah hidup ini. Semarang Februari 2023 susilawati
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI vi DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................................. iv Daftar Isi.......................................................................................................................... vi Daftar Tabel..................................................................................................................... ix Daftar Gambar................................................................................................................. xi Bab 1 - Introduction.......................................................................................................... 1 1.1 Pengertian Hidrologi .............................................................................................. 1 1.2 Latar Belakang dan Sejarah .............................................................................. 2 1.3. Siklus Hidrologi................................................................................................. 3 1.4. Persediaan Air di Bumi...................................................................................... 9 1.5. Keseimbangan Air ............................................................................................. 9 1.6. Beberapa Istilah ............................................................................................... 10 Tugas 1 ....................................................................................................................... 10 Bab 2 – Precipitation-Rainfall ........................................................................................ 11 2.1 Pengertian Precipitation-Rainfall..................................................................... 11 2.2. Bentuk-bentuk Presipitasi................................................................................ 12 2.3. Jenis-jenis Hujan.............................................................................................. 12 1. Jenis Awan Tinggi.............................................................................................. 13 2. Jenis Awan Sedang............................................................................................. 14 3. Jenis Awan Rendah ............................................................................................ 15 2.4. Penakar Hujan (Raingauge)............................................................................. 19 2.5. Karakter Hujan................................................................................................. 23 2.6. Memroses Data Hujan ..................................................................................... 24 Tugas 2 ....................................................................................................................... 30 Bab 3 – Rainfall-Runoff................................................................................................. 31 3.1 Rainfall-Runoff Relationship and Process....................................................... 31 3.2. Interception-Depression Storage-Infiltration-Percolation ............................... 33 3.2.1. Profil Kelembaban Tanah (Soil-Moisture Profile)....................................... 35 3.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Infiltrasi ...................................... 37 3.3. Evaporation-Transpiration-Evapotranspiration ............................................... 41 3.3.1. Pengukuran Evaporasi .................................................................................. 42
DAFTAR ISI BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI vii 3.3.2. Penaksiran Besarnya Evaporasi.................................................................... 43 3.4. Rainfall-Runoff Analysis................................................................................. 48 Tugas 3: ...................................................................................................................... 57 Tugas 4: ...................................................................................................................... 57 Tugas 5: ...................................................................................................................... 58 Bab 4 - Streamflow......................................................................................................... 59 4.1 Streamflow Definition ..................................................................................... 59 4.2. Streamflow Measurement................................................................................ 64 4.3. Streamflow Analysis........................................................................................ 66 Tugas 6: ...................................................................................................................... 71 Bab 5 – Hydrology Statistic ........................................................................................... 72 5.1. Beberapa Konsep Statistik ............................................................................... 72 5.2. Data Screening................................................................................................. 72 5.3. Hydrology Data Analysis................................................................................. 74 Tugas 7 ....................................................................................................................... 75 Bab 6 - Hydrograph ........................................................................................................ 78 6.1. Development of Hydrograph Relations........................................................... 78 6.2. Unit Hydrograph .............................................................................................. 83 6.3. Application of Unit Hydrograph...................................................................... 87 Tugas 8: ...................................................................................................................... 92 Bab 7 – Flood Design ..................................................................................................... 93 7.1 Design Flood Concept ..................................................................................... 95 7.2. Design Flood Analysis..................................................................................... 97 7.2.1. Hujan Maksimum Rencana ........................................................................ 107 7.2.2 Banjir Rencana ....................................................................................... 110 Tugas 9: .................................................................................................................... 116 Bab 8 – Flood Routing ................................................................................................. 117 8.1. Hydrology Flood Routing.............................................................................. 118 8.2. Hydraulics Flood Routing.............................................................................. 127 Tugas 10 ................................................................................................................... 131 Bab 9 – Island Hydrology............................................................................................. 134 9.1. Islands Hydrology Characteristics................................................................. 134 9.2. The Challenges and The Opportunities of Islands Hydrology ...................... 136 Tugas 11: .................................................................................................................. 140 Bab 10 – Rainwater Management ................................................................................ 141 10.1. Rainwater Management Concept ............................................................... 141 10.2. Rainwater Management on Sub-Watershed............................................... 144
DAFTAR ISI BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI viii 10.3. Rainwater Management in Small Scale ..................................................... 147 Tugas 12. .................................................................................................................. 150 Bab 11 – Hydrological Application.............................................................................. 151 Daftar Pustaka .............................................................................................................. 171
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI ix DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Kondisi daerah berdasarkan derajat hujan dan intensitas hujan ..........2.17 Tabel 2. 2 Keadaan curah hujan berdasarkan intensitas curah hujan ......................2.18 Tabel 3. 1 Insolation at the edge of the Earth atmosphere → S0 (mm/day)...........3.46 Tabel 3. 2 Mean daily duration of maximum possible sunshine hours for different months and latitude (after Doorenbos and Pruitt, 1977) → N (h/d).......................3.47 Tabel 3. 3 The function F (T) = T4 (mm/d) as a function of temperature, T (/C) ...............................................................................................................................................................3.48 Tabel 3. 4 The weighting function, 1-W, as a function of temperature (/C) and altitude (m) (modified from Doorenbos and Pruitt, 1977)...........................................3.48 Tabel 3. 5 Koefisien limpasan untuk metode Rasional ...................................................3.52 Tabel 3. 6 Koefisien aliran untuk metode Rasional (dari Hassing, 1995)................3.53 Tabel 3. 7 Values of roughness factor n.................................................................................3.54 Tabel 3. 8 Rumus-rumus waktu konsentrasi......................................................................3.54 Tabel 3. 9 Effective roughness parameter for overland flow .......................................3.55 Tabel 4. 1 Wet line correction, W (%) untuk sudut ......................................................4.67 Tabel 4. 2 Pengukuran kecepatan ...........................................................................................4.69 Tabel 4. 3 Perhitungan Besarnya Kecepatan ......................................................................4.69 Tabel 5. 1 Serial data maksimum permukaan air tahunan............................................5.74 Tabel 6. 1 Tabulasi dan metode matriks untuk konvolusi.............................................6.85 Tabel 6. 2 Bentuk umum persamaan konvolusi hidrograf satuan..............................6.85 Tabel 6. 3 Hyetograf hujan efektif dan hidrograf limpasan permukaan ..................6.85 Tabel 6. 4 Hidrograf satuan yang diturunkan.....................................................................6.86 Tabel 6. 5 Analisis hidrograf satuan – limpasan permukaan........................................6.86 Tabel 6. 6 Tabel debit-baseflow jam-jam an .......................................................................6.88 Tabel 6. 7 Debit-baseflow-DRO-UH ........................................................................................6.88 Tabel 6. 8 SCS dimensionless unit hidrograph ordinates...............................................6.89
DAFTAR TABEL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI x Tabel 6. 9 Perhitungan Tp dan qp .............................................................................................6.90 Tabel 6. 10 Runoff curve number for urban areas............................................................6.91 Tabel 7. 1 Kala ulang banjir rancangan untuk bangunan di sungai ...........................7.96 Tabel 7. 2 Tahapan analisis hidrologi untuk banjir rancangan....................................7.98 Tabel 7. 3 Contoh intensitas hujan dengan kala ulang 5, 10 dan 25 tahun .......... 7.100 Tabel 7. 4 Data partial duration series hujan harian di Duri ..................................... 7.101 Tabel 7. 5 Beberapa rumus empiris hitungan waktu konsentrasi........................... 7.105 Tabel 7. 6 Reduced variate ( yt), metode Gumbel........................................................... 7.107 Tabel 7. 7 Reduced mean (yn), metode Gumbel.............................................................. 7.108 Tabel 7. 8 Reduced standard deviation (sn), metode Gumbel ................................... 7.108 Tabel 7. 9 Standar variabel (u) untuk return periode (T)........................................... 7.109 Tabel 7. 10 Koefisien kemiringan sample (Cs)................................................................ 7.110 Tabel 7. 11 Harga komponen C oleh faktor intensitas curah hujan Cp.................. 7.112 Tabel 7. 12 Harga komponen C oleh faktor topografi Ct............................................. 7.112 Tabel 7. 13 Harga komponen C oleh tampungan permukaan Co............................. 7.112 Tabel 7. 14 Harga komponen C oleh faktor infiltrasi Cs .............................................. 7.112 Tabel 7. 15 Harga komponen C oleh penutup lahan Cc ............................................... 7.112 Tabel 8. 1 Penelusuran hidrologis dengan K = 2,5 jam dan X = 0,4......................... 8.126 Tabel 9. 1 Negara kepulauan dengan luas wilayah-jumlah penduduk-garis pantainya ....................................................................................................................................... 9.134
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI xi DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Siklus hidrologi menurut Dozier (1992)................................................... 1.3 Gambar 1. 2 Siklus hidrologi menurut Donge (1973)................................................... 1.4 Gambar 1. 3 Model sederhana siklus hidrologi............................................................. 1.4 Gambar 1. 4 Sirkulasi air............................................................................................... 1.5 Gambar 1. 5 Skematik siklus hidrologi ......................................................................... 1.5 Gambar 1. 6 Ilustrasi siklus hidrologi Max Planck (Institut for Meteorology)............. 1.6 Gambar 1. 7 Siklus hidrologi pendek (kecil)................................................................. 1.7 Gambar 1. 8 Siklus hidrologi sedang............................................................................. 1.8 Gambar 1. 9 Siklus hidrologi panjang (besar)............................................................... 1.8 Gambar 1. 10 Keseimbangan air dari suatu danau/waduk dan suatu DPS.................. 1.10 Gambar 2. 1 Bentuk-bentuk presipitasi (Geograph88, 2015)...................................... 2.12 Gambar 2. 2 Jenis-jenis awan dan ketinggiannya (Mughnifar Ilham, 2020) .............. 2.13 Gambar 2. 3 Awan Cirrus............................................................................................ 2.13 Gambar 2. 4 Awan Cirrostratus................................................................................... 2.13 Gambar 2. 5 Awan Cirrocumulus................................................................................ 2.14 Gambar 2. 6 Awan Altocumulus................................................................................. 2.14 Gambar 2. 7 Awan Nimbostratus................................................................................ 2.15 Gambar 2. 8 Awan Altostratus.................................................................................... 2.15 Gambar 2. 9 Awan Cumulus ....................................................................................... 2.15 Gambar 2. 10 Awan Stratus......................................................................................... 2.16 Gambar 2. 11 Awan Cumulonimbus........................................................................... 2.16 Gambar 2. 12 Awan Stratocumulus............................................................................. 2.16 Gambar 2. 13 Penakar hujan biasa .............................................................................. 2.20 Gambar 2. 14 Penakar hujan rata tanah....................................................................... 2.20 Gambar 2. 15 Penakar hujan Inggris........................................................................... 2.20 Gambar 2. 16 Interm reference precipitation gauge .................................................... 2.21 Gambar 2. 17 Pencatat jungkit .................................................................................... 2.21
DAFTAR GAMBAR BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI xii Gambar 2. 18 Alat ukur hujan otomatis jenis sifon..................................................... 2.22 Gambar 2. 19 Pencatat hujan tipe pelampung ............................................................. 2.22 Gambar 2. 20 Hasil catatan dari pencatat pelampung ................................................. 2.22 Gambar 2. 21 Hasil catatan yang dibuat grafik lengkung massa................................. 2.23 Gambar 2. 22 Posisi letak penempatan alat ukur hujan............................................... 2.23 Gambar 2. 23 Gambar polygon Thiessen .................................................................... 2.25 Gambar 2. 24 Gambar Isohyet..................................................................................... 2.26 Gambar 2. 25 Lengkung massa dari pencatat hujan.................................................... 2.27 Gambar 2. 26 Contoh lokasi-lokasi pencatat hujan..................................................... 2.27 Gambar 2. 27 Gambar lengkung massa ganda ............................................................ 2.28 Gambar 3. 1 Persentase dari limpasan permukaan (runoff) pada berbagai permukaan ..................................................................................................................................... 3.31 Gambar 3. 2 Proses fisik terkait pembentukan limpasan permukaan (runoff)............ 3.32 Gambar 3. 3 Jalur air limpasan bawah permukaan pada lereng bukit (Kirkby, 1978) 3.33 Gambar 3. 4 Interception, depression storage and infiltration .................................... 3.34 Gambar 3. 5 Depression storage, superficial storage, swamp, flooded plains and lake ..................................................................................................................................... 3.34 Gambar 3. 6 Penampang lapisan tanah........................................................................ 3.35 Gambar 3. 7 Profil kelembaban tanah ......................................................................... 3.36 Gambar 3. 8 Alat neutron probe .................................................................................. 3.37 Gambar 3. 9 Alat infiltrometer .................................................................................... 3.37 Gambar 3. 10 Double ring infiltrometer...................................................................... 3.38 Gambar 3. 11 Testplot (petak uji)................................................................................ 3.38 Gambar 3. 12 Alat Lysimeter ...................................................................................... 3.39 Gambar 3. 13 Springkling test (petak uji) ................................................................... 3.39 Gambar 3. 14 Hubungan curah hujan dan limpasan.................................................... 3.40 Gambar 3. 15 Grafik keseimbangan kadar air tanah dan relasinya dengan runoff ..... 3.41 Gambar 3. 16 Proses evapotranspirasi dan relasinya dengan infiltrasi-perkolasi ....... 3.42 Gambar 3. 17 Alat pengukur evaporasi atmometer..................................................... 3.42 Gambar 3. 18 Macam-macam alat Panci Evaporasi.................................................... 3.43 Gambar 3. 19 Critical moisture states in a soil column............................................... 3.45 Gambar 3. 20 Pengaruh bentuk DAS pada aliran permukaan..................................... 3.49 Gambar 3. 21 Pengaruh kerapatan parit/saluran pada hidrograf aliran permukaan .... 3.50 Gambar 3. 22 Penggunaan metoda tergantung ketersediaan data ............................... 3.50
DAFTAR GAMBAR BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI xiii Gambar 3. 23 Hubungan curah hujan dengan aliran permukaan untuk durasi hujan beda ..................................................................................................................................... 3.52 Gambar 3. 24 Rasional method-effect of catchment shape ......................................... 3.55 Gambar 3. 25 Langkah-langkah rumus Rasional ........................................................ 3.56 Gambar 4. 1 Klasifikasi sungai menurut sumber airnya ............................................. 4.60 Gambar 4. 2 Pola aliran radial sentrifugal dan sentripetal .......................................... 4.61 Gambar 4. 3 Klasifikasi sungai menurut pola alirannya ............................................. 4.62 Gambar 4. 4 Klasifikasi sungai menurut arah alirannya ............................................. 4.62 Gambar 4. 5 Klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologinya ............................... 4.63 Gambar 4. 6 Gambar penampang jenis genetika sungai: C (konsekuen), S (subsekuen), O (obsekuen), R (resekuen)......................................................................................... 4.64 Gambar 4. 7 Alat ukur papan duga air......................................................................... 4.66 Gambar 4. 8 Alat ukur papan duga air otomatis (AWLR) .......................................... 4.66 Gambar 4. 9 Pemasangan AWLR................................................................................ 4.67 Gambar 4. 10 Alat pengukur kedalaman air................................................................ 4.67 Gambar 4. 11 Alat Pengukur Kecepatan Aliran .......................................................... 4.68 Gambar 4. 12 Lokasi pengukuran current meter......................................................... 4.68 Gambar 4. 13 Segmen dalam penampang sungai........................................................ 4.69 Gambar 5. 1 Diagram alir penyaringan data................................................................ 5.73 Gambar 5. 2 Plot data pada kertas grafik..................................................................... 5.74 Gambar 5. 3 Grafik plotting position........................................................................... 5.75 Gambar 6. 1 Hidrograf muka air ................................................................................. 6.80 Gambar 6. 2 Hidrograf debit........................................................................................ 6.80 Gambar 6. 3 Grafik lengkung aliran............................................................................ 6.81 Gambar 6. 4 Komponen dari metode hidrograf........................................................... 6.81 Gambar 6. 5 Langkah-langkah dalam pengembangan dan penerapan metode hidrograf ..................................................................................................................................... 6.82 Gambar 6. 6 Metode pengembangan hidrograf........................................................... 6.83 Gambar 6. 7 Respon DAS terhadap masukan hujan efektif........................................ 6.84 Gambar 6. 8 Pemakaian proses konvolusi pada hidrograf satuan ............................... 6.84 Gambar 6. 9 Hidrograf limpasan permukaan dengan hujan efektif jam-jaman berturutturut 30 mm, 50 mm, dan 20 mm ................................................................................ 6.87 Gambar 6. 10 Grafik DRO dan UH............................................................................. 6.88 Gambar 6. 11 Metode SCS hidrograf.......................................................................... 6.89
DAFTAR GAMBAR BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI xiv Gambar 7. 1 Grafik ilustrasi pengertian kala ulang..................................................... 7.96 Gambar 7. 2 Penentuan kala ulang banjir rancangan secara hidro-ekonomi............... 7.97 Gambar 7. 3 Kurva IDF di Duri dengan kala ulang 5, 10 dan 25 tahun.................... 7.100 Gambar 7. 4 Tipikal bentuk hidrograf banjir cara Rasional...................................... 7.101 Gambar 7. 5 Karakter DAS dan intensitas hujan....................................................... 7.103 Gambar 7. 6 Skema hitungan hidrograf satuan cara analitis..................................... 7.103 Gambar 7. 7 Tahapan hitungan hidrograf banjir rancangan metode hidrograf satuan ................................................................................................................................... 7.105 Gambar 8. 1 Sketsa penelusuran banjir pada saluran terbuka (tampak penampang), Sivapalan, (1997)....................................................................................................... 8.118 Gambar 8. 2 Konsep penelusuran pada waduk.......................................................... 8.119 Gambar 8. 3 Grafik hubungan antara outflow dan tampungan terhadap elevasi ...... 8.120 Gambar 8. 4 Tampungan prismatik dan tampungan baji (segitiga) .......................... 8.121 Gambar 8. 5 Hubungan antara debit dan tampungan terhadap waktu....................... 8.121 Gambar 8. 6 Hubungan antara inflow dan outflow ................................................... 8.123 Gambar 8. 7 Translasi tampungan yang terjadi......................................................... 8.124 Gambar 8. 8 Tampungan prisma dan tampungan baji............................................... 8.124 Gambar 8. 9 Penetapan nilai K dengan x = 0,4; 0,2 dan 0,1 ..................................... 8.125 Gambar 8. 10 Penelusuran hidrograf dengan K = 2,5 jam dan X = 0,4 atau X = 0,2 8.125 Gambar 8. 11 Penelusuran hidrograf dengan K = 5 jam dan X = 0,4 atau X = 0,2 .. 8.126 Gambar 8. 12 Bagan Konsep Flood Early Warning System (FEWS)....................... 8.130 Gambar 9. 1 Jumlah pulau menurut propinsi di Indonesia........................................ 9.135 Gambar 9. 2 Lensa air tanah pada pulau kecil (Falkland, 2010)............................... 9.135 Gambar 9. 3 Analisis hidrologi-hidrolika mengatasi bencana banjir dan kekeringan9.138 Gambar 9. 4 Populasi dan distribusi air permukaan di Indonesia ............................. 9.138 Gambar 9. 5 Kondisi air tanah sebelum dan sesudah ekstraksi dengan pompa ........ 9.139 Gambar 9. 6 Mitigasi dan adaptasi dalam konsep pengelolaan terpadu.................... 9.140 Gambar 10. 1 Sketsa pengaliran air hujan yang ditampung dan diresapkan........... 10.142 Gambar 10. 2 Kerangka pikir pengelolaan air hujan untuk pertanian pada pulau kecil ................................................................................................................................. 10.142 Gambar 10. 3 Teknologi pemanenan air hujan........................................................ 10.143 Gambar 10. 4 Sketsa hidrolika dari jebakan air berantai......................................... 10.144 Gambar 10. 5 Penampang melintang dari pulau kecil koral (Falkland, 2002)........ 10.145 Gambar 10. 6 Prinsip dasar pemanenan air hujan untuk meningkatkan pertanian.. 10.145
DAFTAR GAMBAR BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI xv Gambar 10. 7 Bagian dari air hujan yang jatuh, menghilang dan tinggal dalam tanah ................................................................................................................................. 10.146 Gambar 10. 8 Aliran air hujan – limpasan permukaan – kolam tampung............... 10.147 Gambar 10. 9 Kelola air hujan untuk kehidupan memenuhi kebutuhan air baku ... 10.148 Gambar 10. 10 Kelola air hujan pada skala kompleks rumah tinggal..................... 10.148 Gambar 10. 11 Kelola air hujan skala kecil untuk pertanian................................... 10.149 Gambar 10. 12 Infrastruktur kelola air hujan skala kecil rumah tinggal................. 10.149 Gambar 10. 13 Infrastruktur kelola air hujan berupa kolam lahan.......................... 10.150
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 1 BAB 1 - INTRODUCTION 1.1 Pengertian Hidrologi Hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan keterdapatan dan penyebaran air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi, termasuk sifat-sifat kimia dan fisikanya, serta interaksinya dengan lingkungan (WMO/UNESCO, 1992). UNESCO (1979), mendefinisikan hidrologi sebagai ilmu geofisik yang mempelajari tentang: kejadian, sifat peredaran dan distribusi air di bumi: sifat-sifat fisik dan kimianya dan reaksinya terhadap lingkungan, termasuk hubungannya dengan kehidupan. Hal ini erat hubungannya dengan siklus hidrologi yang mengilustrasikan 4 macam proses: presipitasi, evaporasi, infiltrasi, limpasan permukaan (surface run off), dan limpasan air tanah (sub surface run off). Berbagai macam air dapat kita lihat di sekitar kita, misalnya air sumur, air sungai, air hujan, air rawa, air telaga, air danau, air laut, air es, dan sebagainya. Permukaan bumi lebih banyak ditutupi oleh air daripada daratan. Bumi sebagai tempat tinggal merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang hampir tiga perempat permukaannya tertutup oleh air, baik air yang ada di darat maupun yang ada di laut. Lapisan air yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Lapisan ini akan membentuk samudera, laut, rawa, telaga, danau, sungai, tumpukan es, awan, uap, dan sebagainya. Air permukaan tanah dan air tanah yang dibutuhkan untuk kehidupan dan produksi adalah air yang terdapat dalam proses daur/siklus hidrologi. Jika peredaran siklus hidrologi atau siklus air tidak merata (hal mana memang terjadi demikian), maka akan terjadi berbagai kesulitan. Peredaran air yang berlebih dapat mengakibatkan permasalahan banjir, untuk ini harus diupayakan segera pengendalian banjir. sementara itu jika peredaran air sedikit/kurang dapat mengakibatkan permasalahan kekeringan. Untuk mengatasinya maka kekurangan air ini harus ditambah dalam suatu usaha pemanfaatan air. Berdasarkan uraian di atas, Hidrologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, proses terjadinya, peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhlukmakhluk hidup (International Glosary of Hidrology dalam Seyhan, 1995). Hidrologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari presipitasi (precipitation), evaporasi dan transpirasi (evaporation), aliran permukaan (surface streamflow), dan air tanah (groundwater) (Suyono, 1977). Dalam perkembangannya hidrologi menjadi ilmu dasar dari pengelolaan sumberdaya air (rumah tangga air) yang merupakan pengembangan, agihan, dan penggunaan sumberdaya air secara terencana. Ruang lingkup hidrologi mencakup: 1. Pengukuran, mencatat, dan publikasi data dasar. 2. Deskripsi propertis, fenomena, dan distribusi air di daratan. 3. Analisa data untuk mengembangkan teori-teori pokok yang ada pada hidrologi. 4. Aplikasi teori-teori hidrologi untuk memecahkan masalah praktis.
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 2 Hidrologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi ada hubungan dengan ilmu lain, seperti meteorologi, klimatologi, geologi, agronomi, kehutanan, ilmu tanah, dan hidrolika. Menurut The International Association of Scientific Hydrology, hidrologi dapat dibagi menjadi: 1. Potamologi (Potamology), khusus mempelajari aliran permukaan (surface streams) 2. Limnologi (Limnology), khusus mempelajari air danau 3. Geohidrologi (Geohydrology), khusus mempelajari air yang ada di bawah permukaan tanah (mempelajari air tanah = groundwater) 4. Kriologi (Cryology), khusus mempelajari es dan salju 5. Hidrometeorologi (Hydrometeorology), khusus mempelajari problema-problema yang ada antara hidrologi dan meteorologi. 1.2 Latar Belakang dan Sejarah Hidrologi adalah ilmu tentang seluk beluk air di bumi, kejadiannya, peredarannya dan distribusinya, sifat alam dan kimianya, serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungan dengan kehidupan (Federal Council for Science and Technology, USA, 1959 dalam Varshney, 1977). Hidrologi adalah cabang Geografi Fisis yang berurusan dengan air di bumi, sorotan khusus pada propertis, fenomena, dan distribusi air di daratan. Khususnya mempelajari kejadian air di daratan, deskripsi pengaruh bumi terhadap air, pengaruh fisik air terhadap daratan, dan mempelajari hubungan air dengan kehidupan di bumi (Linsley et al, 1949). Wisler and Brater, (1959) dalam Varshney 1977, menyatakan bahwa Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses yang mengatur pengurangan dan penambahan sumber daya air dari wilayah daratan bumi. Lebih jauh Ray K. Linsley dalam Yandi Hermawan (1986), menyatakan pula bahwa Hidrologi ialah ilmu yang membicarakan tentang air yang ada di bumi, yaitu mengenai kejadian, perputaran dan pembagiannya, sifat-sifat fisik dan kimia, serta reaksinya terhadap lingkungan termasuk hubungannya dengan kehidupan. Singh, 1992 menyatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air bumi, termasuk didalamnya kejadian, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen. Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air, baik di atmosfer, di bumi, dan di dalam bumi, tentang perputarannya, kejadiannya, distribusinya serta pengaruhnya terhadap kehidupan yang ada di alam ini. Secara umum hidrologi dimaksudkan sebagai ilmu yang menyangkut masalah air. Akan tetapi dengan alasan-alasan praktis hanya dibatasi pada beberapa aspek saja. Konsep pokok untuk ilmu hidrologi adalah siklus hidrologi. Ilmu-ilmu yang terkait dalam hidrologi: meteorologi dan klimatologi, ilmu tanah, mekanika fluida, statistik dan fisika melayang, dan juga memperkenalkan bentuk kalkulus differensial sebagai bagian dari analisisnya. Hidrologi mulai dikenal sejak abad 16 di Perancis. Pierre Parrault (1608-1680), melakukan pengukuran hujan, limpasan permukaan (run off) dan debit selama tiga tahun di daerah aliran sungai Seine. Kemudian disusul oleh Edme Marlotte tahun 1620, serta Edmund Halley (1656-1742) pada tahun 1656, menunjukkan bahwa evaporasi dari air laut cukup untuk mengisi sungai-sungai yang akan mengalir kembali ke laut (Yandi Hermawan, 1986). Ven Te Chow dalam Yandi Hermawan 1986, mencatat sejarah hidrologi sebagai berikut: 1) Periode spekulasi sampai tahun 1400; periode observasi antara tahun 1400 – tahun 1600; periode pengukuran antara tahun 1600 sampai dengan tahun 1700; periode eksperimentasi dari tahun 1700 sampai dengan tahun 1800; periode modernisasi antara tahun 1800 sampai dengan tahun 1900; periode empiris antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1930; periode rasionalisasi antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1950; dan periode teoritis antara tahun 1950 sampai dengan sekarang. 2) Lebih jauh dia menyatakan bahwa sejak 1000 SM masalah air selalu dipertanyakan dari mana asalnya dan kesemuanya pernah dijawab oleh Homer, Thales, Plato, Aristoteles, akan tetapi tidak pernah memuaskan para penanya pada saat itu.
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 3 1.3. Siklus Hidrologi Daur hidrologi atau siklus hidrologi adalah siklus yang menunjukkan gerakan air di permukaan bumi (Asdak, 2007). Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti tersebut, air akan tertahan sementara di sungai, danau/waduk, dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia atau mahluk hidup lainnya untuk berbagai keperluan. Dalam daur hidrologi, masukan berupa curah hujan akan didistribusikan melalui beberapa cara yaitu: air lolos (throughfall), aliran batang (streamflow), dan air hujan, yang langsung sampai ke permukaan tanah, untuk kemudian terbagi menjadi air larian/limpasan (run off), evaporasi, dan infiltrasi. Gabungan evaporasi dan uap air hasil proses transpirasi dan intersepsi dinamakan evapotranspirasi, sedangkan air larian dan air infiltrasi akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran (discharge). Sirkulasi yang kontinu antara air laut dan air daratan berlangsung secara terus-menerus. Sirkulasi ini dapat tidak merata, karena kita melihat perbedaan besar jumlah presipitasi dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, dan juga dari wilayah ke wilayah yang lain. Sirkulasi air ini dipengaruhi oleh kondisi meteorologi (suhu, tekanan atmosfer, angin, dan lain-lain) dan kondisi topografi. Kondisi meteorologi adalah faktor-faktor yang paling menentukan. Dozier (1992) memberikan gambaran yang modern tentang siklus hidrologi sebagai berikut: Gambar 1. 1 Siklus hidrologi menurut Dozier (1992) Catatan: angka dalam kotak menunjukkan volume dalam 103 km3, sedang angka yang diikuti tanda panah menunjukkan besaran dalam 103 km3 per tahun Precipitation (107) Evaporation & Transpiration (71) mixed layer (50.000) thermocline (460.000) abyssal (890.000) Land Ocean Terrestrial atmosphere (4,5) Marine atmosphere (11) Ice & Snow (43.400) Surface water (360) Underground water (15.300) Rivers etc. (36) Biomass (2) Evaporation (434) Precipitation (398) Wind (35)
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 4 Donge (1973) memberikan skematik siklus hidrologi dalam sistem notasi sebagai berikut: Gambar 1. 2 Siklus hidrologi menurut Donge (1973) Catatan: P = precipitation F = infiltration E = evaporation R = recharge = deep percolation Q = river flow C = capillary rise Gambar 1. 3 Model sederhana siklus hidrologi
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 5 Gambar 1. 4 Sirkulasi air Gambar 1. 5 Skematik siklus hidrologi
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 6 Gambar 1. 6 Ilustrasi siklus hidrologi Max Planck (Institut for Meteorology) Dengan adanya penyinaran matahari, maka semua air yang ada dipermukaan bumi akan berubah wujud berupa gas/uap akibat panas matahari dan disebut dengan penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Uap ini bergerak di atmosfer (udara) kemudian akibat perbedaan temperatur di atmosfer dari panas menjadi dingin maka air akan terbentuk akibat kondensasi dari uap menjadi cairan (from air to liquid state). Bila temperatur berada di bawah titik beku (freezing point) kristal-kristal es terbentuk. Tetesan air kecil (tiny droplet) tumbuh oleh kondensasi dan berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara turbulen sampai pada kondisi yang cukup besar menjadi butir-butir air. Apabila jumlah butir sir sudah cukup banyak dan akibat berat sendiri (pengaruh gravitasi) butir-butir air itu akan turun ke bumi dan proses turunnya butiran air ini disebut dengan hujan atau presipitasi. Bila temperatur udara turun sampai dibawah 0º Celcius, maka butiran air akan berubah menjadi salju (Chow dkk., 1988). Salju jadi persoalan penting di tempat atau negara yang mempunyai perbedaan temperatur yang besar pada waktu musim panas (summer) temperatur bisa mencapai + 35ºC, namun pada waktu musim dingin (winter) temperatur bisa mencapai - 35º (bahkan lebih). Hujan jatuh ke bumi baik secara langsung maupun melalui media misalnya melalui tanaman (vegetasi). Di bumi air mengalir dan bergerak dengan berbagai cara. Pada retensi (tempat penyimpanan) air akan menetap untuk beberapa waktu. Retensi dapat berupa retensi alam seperti darah-daerah cekungan, danau tempat-tempat yang rendah dan sebagainya, maupun retensi buatan seperti tampungan, sumur, embung, waduk dan sebagainya. Secara gravitasi (alami) air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dari gunung-gunung, pegunungan ke lembah, lalu ke daerah yang lebih rendah, sampai ke daerah pantai dan akhirnya akan bermuara ke laut. Aliran air ini disebut aliran permukaan tanah karena bergerak di atas muka tanah. Aliran ini biasanya akan memasuki daerah tangkapan atau daerah aliran menuju kesistem jaringan sungai, sistem danau atau waduk. Dalam sistem sungai aliran mengalir mulai dari sistem sungai kecil ke sistem sungai yang besar dan akhirnya menuju mulut sungai atau sering disebut estuary yaitu tempat bertemunya sungai dengan laut. Air hujan sebagian mengalir meresap ke dalam tanah atau yang sering disebut dengan infiltrasi, dan bergerak terus ke bawah. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian menguap (evaporasi dan transpirasi) dan membentuk uap air. Sebagian lagi mengalir masuk ke dalam tanah (infiltrasi, perkolasi, kapiler). Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 7 terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah dan di dalam retak-retak dari batuan. Dahulu disebut air lapisan dan yang terakhir disebut air celah (fissure water). Aliran air tanah dapat dibedakan menjadi aliran tanah dangkal, aliran tanah antara dan aliran dasar (base flow). Disebut aliran dasar karena aliran ini merupakan aliran yang mengisi sistem jaringan sungai. Hal ini dapat dilihat pada musim kemarau, ketika hujan tidak turun untuk beberapa waktu, pada suatu sistem sungai tertentu aliran masih tetap dan kontinyu. Sebagian air yang tersimpan sebagai air tanah (groundwater) yang akan keluar ke permukaan tanah sebagai limpasan, yakni limpasan permukaan (surface runoff), aliran intra (interflow) dan limpasan air tanah (groundwater runoff) yang terkumpul di sungai yang akhirnya akan mengalir ke laut kembali terjadi penguapan dan begitu seterusnya mengikuti siklus hidrogi. Penyimpanan air tanah besarnya tergantung dari kondisi geologi setempat dan waktu. Kondisi tata guna lahan juga berpengaruh terhadap tampungan air tanah, misalnya lahan hutan yang beralih fungsi mejadi daerah pemukiman dan curah hujan daerah tersebut. Sebagai permulaan dari simulasi harus ditentukan penyimpangan awal (initial storage). Hujan jatuh ke bumi baik secara langsung maupun melalui media misalnya melalui tanaman (vegetasi), masuk ke tanah begitu juga hujan yang terinfiltrasi. Sedangkan air yang tidak terinfiltrasi yang merupakan limpasan mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengalir ke danau dan tertampung. Dan hujan yang langsung jatuh di atas sebuah danau (reservoir) air hujan (presipitasi) yang langsung jatuh diatas danau menjadi tampungan langsung. Air yang tertahan di danau akan mengalir melalui sistem jaringan sungai, permukaan tanah (akibat debit banjir) dan merembes melalui tanah. Dalam hal ini air yang tertampung di danau adalah inflow sedangkan yang mengalir atau merembes adalah outflow. Daur hidrologi atau siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: siklus kecil, siklus sedang dan siklus besar. 1. Siklus Air Pendek (Kecil) Akibat adanya pemanasan oleh sinar matahari, air di laut/lautan akan menguap dan membubung di udara. Di udara uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian (setiap naik 100 meter, suhu udara turun 0,50C). Dengan demikian semakin ke atas suhu udara semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi (pengembunan). Uap air berubah menjadi butir-butir air dan terkumpul menjadi awan atau mendung dan akhirnya jatuh ke permukaan laut/lautan sebagai hujan. Gambar 1. 7 Siklus hidrologi pendek (kecil)
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 8 2. Siklus Air Sedang Uap air yang berasal dari laut/lautan ditiup oleh angin dan bergerak sampai di atas daratan, kemudian bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air akan berkondensasi membentuk butir-butir air dan terkumpul menjadi awan dan jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan yang jatuh di daratan mengalir kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah dan melalui resapan di dalam tanah. Gambar 1. 8 Siklus hidrologi sedang 3. Siklus Air Panjang (Besar) Uap air yang berasal dari laut/lautan setelah sampai di atas daratan karena dibawa oleh angin bergabung dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, rawa, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya. Uap yang telah bergabung tersebut tidak saja berkondensasi tetapi juga membeku, membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Kristal-kristal es turun ke daratan sebagai salju, salju mencair dan mengalir sebagai gletser kemudian akhirnya kembali lagi ke laut. Gambar 1. 9 Siklus hidrologi panjang (besar)
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 9 1.4. Persediaan Air di Bumi Air di bumi → 97 % air laut → 3 % air tawar → terdiri dari: es dan glacier = 75 % air bawah tanah = 24.5 % air danau = 0.3 % air sungai = 0.003 % kandungan air dalam tanah (lengas) = 0.16 % air di atmosfir = 0.03 % Total air dunia: ± 1357,50 juta km3 (97% saline water and 3% fresh water) 97%, air laut (saline water), ± 1320 juta km3. 3%, air tawar (fresh water), ± 37,50 juta km3. Sebaran air tawar (terhadap ± 37,5 juta km3). 29,00 juta km3, 77,33%, berada di kutub utara/selatan berupa es dan glasier 4,15 juta km3, 11,06%, berada antara 0-800 m dari permukaan tanah 4,15 juta juta km3, 11,06%, berada antara -800 m dari permukaan tanah ke bawah 0,120 juta km3, 0,32%, di danau-danau, rawa-rawa, tampungan buatan dan sungai 0,067 juta km3, 0,18%, kandungan air tanah dan rembesan 0,013 juta km3, 0,04% di atmosfir dan uap air. 1.5. Keseimbangan Air Siklus hidrologi merupakan sistem tertutup (closed system), artinya: tak ada penambahan maupun kehilangan air dari siklus. Ada beberapa kejadian dimana seorang ahli hidrologi harus berhadapan pula dengan suatu sistem terbuka (open system) dimana dapat dijelaskan dalam suatu keseimbangan air (water balance). Perbedaan antara pemasukan (input = I) dan pengeluaran (output = Q) berhubungan dengan perubahan dari tampungan (storage = dS) dalam interval waktu: dt. I − Q = dS dt perlu diperhatikan yang disebut kontrol volume a. Keseimbangan air dari suatu danau/waduk → [Qin + Gin + P] − [Qout+Gout + E] = dS dt
INTRODUCTION BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 10 b. Keseimbangan air dari suatu DPS → [Gin + P] − [Qout+Gout + E] = dS dt Gambar 1. 10 Keseimbangan air dari suatu danau/waduk dan suatu DPS 1.6. Beberapa Istilah Beberapa istilah dalam hidrologi yang berkaitan dengan proses terjadinya limpasan permukaan (surface run off): 1. interception →bagian air yang tertahan sebelum mencapai tanah, oleh bangunan, pohon dan sebagainya 2. surface detention → tampungan air yang membentuk lapisan air di permukaan tanah 3. depression storage → tampungan air yang disebabkan oleh cekungan saluran, rawa dan sebagainya 4. infiltrasi → bagian air yang meresap ke dalam tanah 5. kapasitas infiltrasi (fp) → kapasitas maximum dari suatu jenis tanah dimana air masih dapat meresap melalui permukaan, selebihnya akan menjadi run off 6. field capacity (kapasitas lapang) → jumlah air maximum yang dapat tinggal dalam massa tanah terhadap pengaruh grafitasi 7. soil moisture → air dalam pori-pori tanah dan merupakan bagian dari tanah Tugas 1 1. Tuliskan secara skematik pengertian hidrologi, kemudian tampilkan juga dalam vlog! 2. Jelaskan ulang siklus hidrologi (cari gambar atau penjelasan lebih sederhana dan mudah di internet), kemudian tampilkan juga dalam vlog! 3. Kunjungan ke lapangan untuk melihat secara nyata beberapa pengertian yang telah dijelaskan, tampilkan dalam vloq!
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 11 BAB 2 – PRECIPITATION-RAINFALL 2.1 Pengertian Precipitation-Rainfall Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian presipitasi yang berasal dari kata pre·si·pi·ta·si atau présipitasi, dalam konteks geografi diartikan sebagai proses pengendapan, baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Dalam konteks meteorologi, diartikan sebagai kandungan kelembaban udara yang berbentuk cairan atau bahan padat, seperti hujan, embun salju. Dalam konteks meteorologi buatan diartkan sebagai hujan yang berasal dari berbagai jenis awan yang dipilih sebagai hasil usaha manusia. Menurut Sigit Ari Wibowo (2015), presipitasi didefinisikan sebagai suatu kejadian jatuhnya air dari atmosfer mengarah ke permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun bisa dalam bentuk embun, salju, kabut dan hujan. Menurut Sosrodarsono (1976), presipitasi didefinisikan sebagai nama umum dari uap yang mengkondensasi dan jatuh ke tanah dalam rangkaian proses siklus hidrologi. Secara umum, jumlahnya selalu dinyatakan dengan dalamnya presipitasi (mm). Apabila uap air yang jatuh berupa cair dinamakan dengan hujan (rainfall) dan jika berbentuk padat dinamakan salju (snow). Menurut Triatmodjo (2008), presipitasi didefinisikan sebagai turunan air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dapat terdiri dari embun, salju, hujan es dan hujan. Presipitasi untuk daerah tropis, hujan memberikan peran atau fungsi yang besar. Hal ini terlihat dimana biasanya hujanlah yang dianggap presipitasi. Definisi presipitasi menurut Wikipedia adalah setiap produk dari kondensasi uang air di atmosfer. Ia terjadi pada saat atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut (terpresipitasi). Definisi presipitasi menurut Wibowo dkk. (2015), adalah suatu kejadian jatuhnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun itu dapat berupa salju, hujan, kabut, dan embun. Sedangkan definisi presipitasi menurut Chay Asdak (2010), adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Presipitasi dalam siklus hidrologi didefinisikan sebagai turunnya air dari atmosfer bumi menuju permukaan bumi berupa bentuk yang berbeda-beda, merupakan sebuah kejadian klimatik yang sifatnya alamiah, artinya presipitasi adalah perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat dari proses kondensasi. Presipitasi sering digunakan untuk menyebut hujan, yang merupakan masukan utama dari daur hidrologi dalam suatu DAS (daerah aliran sungai). Presipitasi (juga dikenal sebagai satu kelas dalam hidrometeor, yang merupakan fenomena atmosferik) adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer (yang merupakan suatu larutan gas raksasa) menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut (terpresipitasi). Udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, and hujan es. Presipitasi adalah salah satu komponen utama dalam siklus air, dan merupakan sumber utama air tawar di planet ini.
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 12 Dampak kegiatan pembangunan terhadap proses hidrologi sangat dipengaruhi oleh intensitas, lama berlangsungnya, dan lokasi hujan. Karena itu perencana dan pengelola DAS harus memperhitungkan pola presipitasi dan sebaran geografinya. 2.2. Bentuk-bentuk Presipitasi Bentuk-bentuk presipitasi yang ada di bumi dapat berupa: 1. Hujan, merupakan bentuk yang paling penting 2. Embun, merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah/tumbuh-tumbuhan dan kondensasi di dalam tanah 3. Kondensasi di atas lapisan es, yang terjadi jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es 4. Kabut, merupakan partikel-partikel air yang diendapkan di atas permukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan 5. Salju dan es Bentuk-bentuk presipitasi ini diilustrasikan seperti dalam Gambar II.1. berikut ini. Gambar 2. 1 Bentuk-bentuk presipitasi (Geograph88, 2015) 2.3. Jenis-jenis Hujan Sebelum memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis hujan, terlebih dahulu dijelaskan pengertian hujan. Apabila awan yang terbentuk di angkasa terus naik akan menjadi butirbutir halus dan berubah menjadi butir-butir air yang besar-besar dan akhirnya jatuh ke bumi sebagai air hujan. Jadi hujan dapat didefinisikan sebagai peristiwa jatuhnya butirbutir air dari langit ke permukaan bumi. Hujan juga dapat diartikan sebagai presipitasi yang berbentuk cair (presipitasi: semua bentuk hasil konsumsi uap air yang terkandung di atmosfer). Awan merupakan gumpalan uap air yang terbentuk dari serangkaian adanya proses siklus hidrologi atau daur air di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melewati keadaan titik jenuh. Awan ini merupakan tanda akan terjadinya hujan. Awan, yang merupakan proses awal terjadinya hujan, mempunyai beberapa jenis, seperti digambarkan pada gambar berikut ini.
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 13 Gambar 2. 2 Jenis-jenis awan dan ketinggiannya (Mughnifar Ilham, 2020) Mughnifar Ilham (2020) juga menjelaskan jenis-jenis awan ini sebagai berikut: 1. Jenis Awan Tinggi Jenis awan ini dapat dikatakan awan tinggi jika awan tersebut terbentuk pada ketinggian >20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan tinggi ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu: Awan Cirrus, Awan Cirrostratus dan Awan Cirrocumulus. Gambar 2. 3 Awan Cirrus Awan cirrus memiliki serat yang halus seperti serat bulu burung, sering juga, pada awanawan yang berbentuk cirrus ini tampak kristal es, meskipun sebenarnya tipe awan cirrus tidak menimbulkan hujan bagi wilayah di bawahnya. Awan cirrus ini biasanya berdiri dengan ketinggian lebih dari lima kilo meter. Bentuknya yang serupa dengan kristal es, dan berada pada tempat yang tinggi ini membuktikan bahwa suhu yang ada pada awan ini sangat rendah, walaupun muncul di musim panas. Gambar 2. 4 Awan Cirrostratus
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 14 Jenis awan cirrostratus ini tampak seperti kelambu putih halus yang mengental. Awan ini dapat menutup langit secara total atau keseluruhan dengan warna yang cerah. Apabila diperhatikan, maka awan cirrostratus ini sekilas akan terlihat sama seperti anyaman dengan bentuk yang tidak teratur. jika musim kemarau. awan ini bisa menimbulkan lingkaran bulat yang mengelilingi matahari dan bulan. Gambar 2. 5 Awan Cirrocumulus Jenis awan cirrocumulus ini memilki karakteristik tersendiri karena bentuknya yang menyerupai ombak di pasir pantai, dan awan ini juga menyerupai bulatan-bulatan kecil berwarna putih yang berbaris atau berkelompok sehingga akan tampak seperti sekelompok domba. Awan ini dapat di lihat di langit yang terdegradasi dari awan cirrostratus. dan awan cirrus 2. Jenis Awan Sedang Awan sedang berada di bawah dari awan tinggi, yakni terletak pada ketinggian 6.500 – 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan sedang ini juga dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni Awan Altocumulus, Awan Nimbostratus, dan Awan Altostratus. Gambar 2. 6 Awan Altocumulus Awan ini berwarna putih / abu-abu dengan lembaran berlapis dan berserat. Adapun awan ini terdiri dari satu lapisan pada bagian tengahnya yang menjadikan awan ini terlihat lebih tebal, Sementara pada bagian sisinya terlihat lebih tipis. Awan ini juga sering berkumpul dan tampak saling berikatan.
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 15 Gambar 2. 7 Awan Nimbostratus Awan Nimbostratus, merupakan awan yang dihasilkan dari penebalan altostratus, warnanya relatif abu-abu gelap. Awan ini bisa menghasilkan hujan deras. Adapun bentuk dari awan ini berupa tepi yang compang-camping atau tidak beraturan dan awan ini cukup tebal sehingga bisa menutupi seluruh lapisan langit dan juga karena warna gelap dan ketebalannya ini, sehingga dapat membuat sinar matahari tertutupi dengan gelap. Gambar 2. 8 Awan Altostratus Awan Altostratus, berwarna abu-abu kebiruan dengan rupa lembaran berserat menutupi langit secara total ataupun sebagian merupakan ciri dari jenis awan ini. Awan ini juga dapat menjadi penyebab hujan ringan apabila terakumulasi cukup tebal. Adapun awan altostratus ini muncul pada siang bahkan malam hari dan menghilang pada saat matahari terbit. 3. Jenis Awan Rendah Awan rendah berada pada ketinggian < 6.500 kaki di atas permukaan laut. Awan ini terbagi menjadi empat jenis, yakni: Awan cumulus, stratus, cumulonimbus, dan stratocumulus. Gambar 2. 9 Awan Cumulus
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 16 Karateristik awan cumulus ini padat bergaris tajam yang biasanya berkembang secara vertikal (ke atas) dengan pertambahan jumlah tumpukan melalui penggelembungan di bagian atasnya yang seperti bentuk kembang kol. Apabila awan ini terkena sinar matahari, maka awan ini akan terlihat putih cerah, Sedangkan sisi yang lain terlihat gelap secara horizontal. Awan ini sering kali muncul saat pagi hari apabila langit tidak mendung, tumbuh, kemudian bertambah atau berkurang ukurannya ketika malam hari. Gambar 2. 10 Awan Stratus Jenis awan stratus ini memiliki kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 2 km saja. Biasanya akan terlihat di ujung lautan dengan tekstur tipis dan berlapislapis. Adapun awan stratus ini tidak tumbuh secara vertikal, awan ini berkembang mengikuti arah angin yang menyebabkan udara akan terkondensasi pada ketinggian yang rendah. Gambar 2. 11 Awan Cumulonimbus Jenis awan cumulonimbus ini adalah jenis awan yang berat dan padat dan berbentuk vertikal yang merupakan ciri dari awan cumulonimbus. Bentuk awan ini juga menyerupai sebuah gunung, Di bagian atasnya terlihat berserat dan hampir selalu rata, sedangkan pada bagian bawahnya sering sangat gelap. Jika di dunia penerbangan, Jenis awan ini menjadi jenis awan yang sangat ditakuti, karena dapat membuat pesawat kecelakaan. Gambar 2. 12 Awan Stratocumulus
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 17 Awan jenis ini memiliki bentuk yang serupa dengan sarang lebah dan dan sering kali menjadi penyebab hujan lokal yang merupakan ciri dari awan ini, Apabila awan ini terakumulasi dan lebih padat, awan ini akan menyebabkan hujan lokal yang deras. Hujan merupakan salah satu gejala cuaca yang memiliki peranan penting bagi kehidupan di bumi (hujan sebagai sumber air tawar). Jumlah curah hujan yang diterima oleh suatu daerah di samping tergantung sirkulasi uap air, juga tergantung dari faktor-faktor: 1. Letak garis lintang 2. Ketinggian tempat 3. Jarak dari sumber-sumber air 4. Posisi daerah terhadap benua/daratan 5. Arah angin terhadap sumber-sumber air (menjauhi/mendekati) 6. Hubungannya dengan deretan gunung 7. Suhu nisbi tanah dan samudera yang berbatasan. Curah hujan yang diperlukan dalam penyusunan peta Isohiet untuk suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah atau daerah dan dinyatakan dalam milimeter (mm). Distribusi curah hujan wilayah atau daerah (regional distribution) adalah persebaran intensitas curah hujan yang dihitung dengan mengacu pada pengukuran curah hujan di stasiun–stasiun meteorologi dengan menggunakan metode tertentu (Asdak, 2007). Keragaman hujan di Indonesia berkisar antara 2.000-3.000 mm/tahun. Untuk mendapatkan data curah hujan yang akurat maka data lapangan harus diperiksa dan diteliti kebenarannya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keperluan penyelesaian masalahmasalah hidrologis. Pemeriksaan data curah hujan dapat ditanyakan langsung kepada petugas pencatat di stasiun meteorologi. Untuk mencirikan jumlah curah hujan yang jatuh pada suatu wilayah/daerah, para ahli hidrologi membutuhkan 4 (empat) unsur di bawah ini: 1. Derajat hujan dan Intensitas hujan Derajat hujan adalah jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu. Biasanya satuan yang digunakan adalah mm/jam. Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan dalam waktu relatif singkat (biasanya dalam waktu 2 jam). Besarnya curah hujan tidak bertambah sebanding dengan waktu. Jika waktu ditentukan lebih lama, maka penambahan curah hujan itu adalah lebih kecil dibandingkan dengan penambahan waktu, karena curah hujan dapat berkurang ataupun berhenti. Derajat curah hujan sangat membantu dalam melihat kondisi suatu wilayah, terutama tentang keadaan tanahnya, sehingga untuk ke lapangan perlu antisipasi peralatan yang dibutuhkan. Derajat curah hujan juga berguna untuk melihat keadaan curah hujan yang berlangsung. Berikut ini disajikan kondisi daerah berdasarkan derajat hujan dan intensitas hujan (Tabel II.1) dan keadaan curah hujan berdasarkan intensitas hujan (Tabel II.2). Tabel 2. 1 Kondisi daerah berdasarkan derajat hujan dan intensitas hujan Derajat hujan Intensitas hujan (mm/menit) Kondisi Hujan sangat lemah < 0,02 Tanah agak basah atau dibasahi sedikit Hujan lemah 0,02 – 0,05 Tanah menjadi basah semuanya, tetapi sulit membuat pudel Hujan normal 0,05 – 0,25 Tanah dapat dibuat pudel dan bunyi curah hujan kedengaran Hujan deras 0,25 – 1 Air tergenang di seluruh permukaan tanah dan bunyi keras hujan kedengaran dari genangan Hujan sangat deras > 1 Hujan seperti ditumpahkan, sluran dan drainase meluap
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 18 Tabel 2. 2 Keadaan curah hujan berdasarkan intensitas curah hujan Keadaan curah hujan Intensitas curah hujan (mm) 1 jam 24 jam Hujan sangat ringan < 1 < 5 Hujan ringan 1 – 5 5 – 20 Hujan normal 5 – 20 20 – 50 Hujan lebat 10 – 20 50 – 100 Hujan sangat lebat > 20 > 100 2. Klasifikasi hujan berdasarkan prosesnya Hujan dapat diklasifikasikan berdasarkan proses, bentuk, dan modelnya. Berdasarkan prosesnya hujan dibedakan menjadi hujan orografik, hujan frontal, hujan konveksi, dan hujan konvergen. a. Hujan Orografik Hujan orografik adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan (hujan pegunungan). Prosesnya udara yang mengandung uap air akan bergerak naik ke atas pegunungan. Akibat adanya penurunan suhu, udara terkondensasi dan turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Daerah lereng lain tempat turunnya hujan yang miskin uap air dan kering disebut daerah bayangan hujan (shadow rain). b. Hujan Frontal Hujan frontal terjadi jika massa udara yang panas naik di atas suatu tepi frontal yang dingin (udara dingin). Ketika udara naik temperatur menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi dan jatuh menjadi hujan frontal. Udara dingin berasal dari kutub dan udara panas berasal dari khatulistiwa. Hujan ini biasanya terjadi di daerah sedang. Laju hujan yang terjadi adalah sedang dan seringkali berlangsung lama. c. Hujan Konveksi Hujan konveksi terjadi di daerah tropis, dan disebut juga hujan zenithal. Prosesnya, uap air di daerah ekuator naik secara vertikal akibat adanya pemanasan air laut secara terus-menerus. Akhirnya uap air tersebut berkondensasi dan menurunkan hujan konveksi. Hujan ini biasanya turun pada sore hari setelah mendapat pemanasan maksimum (pemanasan maksimum umumnya pukul 12.00-14.00). d. Hujan Konvergen Hujan Konvergen adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya arus konvergensi udara atau pengumpulan awan oleh angin. Faktor angin cukup berpengaruh dalam jenis hujan ini. Arus konvergensi adalah arus udara yang bergerak akibat adanya tekanan udara yang sangat rendah di suatu tempat sehingga massa udara basah akan bergerak dengan cepat dan menimbulkan hujan disertai dengan angin. 3. Klasifikasi hujan berdasarkan bentuknya Berdasarkan bentuknya hujan dapat dibedakan menjadi hujan air, hujan salju dan hujan es. a. Hujan air (rain) Hujan air berupa air yang jatuh dalam bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. Di wilayah Indonesia hujan ini sering terjadi dan biasa disebut dengan rain karena berbentuk cair. Ukuran diameter butir hujan berkisar antara 0,5 - 4 mm. b. Hujan salju (snow) Hujan salju merupakan jumlah salju basah yang jatuh dalam suatu periode terbatas. Salju adalah kristal-kristal kecil air yang membeku dalam butiran kecil yang secara langsung dibentuk dari uap air di udara bila suhunya pada saat kondensasi < 00C (00C: titik beku air). Proses terbentuknya adalah antar butir air saling bertumbukan tetapi
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 19 tidak menyatu (hanya menempel) sehingga jika hujan jatuh tidak teratur bentuknya. Diameter butir berkisar < 0,5 mm, dan dapat terjadi pada suhu 60C . c. Hujan es (hail stone) Adanya panas akan mengakibatkan uap air terangkat ke atas dan semakin ke atas butiran air akan semakin besar. Uap air tersebut selanjutnya berkondensasi dan akhirnya jatuh menjadi hujan es. Hujan es sering terjadi di daerah sedang dan peluang terjadi di daerah tropis juga besar, akan tetapi karena di daerah tropis untuk membeku awan harus naik setinggi 5000 m, maka akibat ketinggian tersebut es yang jatuh ke bawah sudah tidak berbentuk es lagi tetapi berbentuk cair. Ukuran diameter butir hujan berkisar > 4 mm. 4. Klasifikasi hujan berdasarkan modelnya Berdasarkan modelnya, hujan dapat dibedakan menjadi hujan homogen, hujan advanced, hujan intermediate, dan hujan delay. a. Hujan Homogen Hujan homogen adalah hujan yang dari awal sampai akhir terjadinya hujan deras dan kemudian berhenti. b. Hujan Advanced Hujan advanced adalah hujan yang di awal terjadinya hujan sangat deras kemudian semakin berkurang derasnya dan berhenti. c. Hujan Intermediate Hujan intermediate adalah hujan yang terjadi semakin meningkat derasnya sampai pada titik tertentu (pertengahan) dan kemudian menurun derasnya sampai akhirnya berhenti. d. Hujan Delay Hujan delay adalah hujan yang di awal terjadinya hujan sedikit (tidak begitu deras) dan semakin deras di belakang. 2.4. Penakar Hujan (Raingauge) Dalam praktek, kita mengenal 2 macam alat untuk mengukur curah hujan yaitu penakar hujan dan pencatat hujan. 1) alat ukur hujan biasa → penakar hujan (manual rain gauge): a) penakar hujan biasa b) penakar hujan rata tanah c) penakar hujan inggris d) interm reference precipitation gauge
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 20 Gambar 2. 13 Penakar hujan biasa Gambar 2. 14 Penakar hujan rata tanah Gambar 2. 15 Penakar hujan Inggris
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 21 Gambar 2. 16 Interm reference precipitation gauge 2) Pencatat hujan atau alat ukur hujan otomatis, dimana pencatat hujan (recording gauge) biasanya dibuat sedemikian sehingga dapat bekerja secara otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan melakukan pencatatan setiap saat, sehingga intensitas hujan pada saat-saat tertentu dapat diketahui pula. Di pasaran telah diproduksi beberapa tipe, antara lain: a. pencatat jungkit (tiping bucket) → dibagi dalam 2 ruangan yang diatur sedemikian rupa jika yang satu terisi kemudian menjungkit dan menjadi kosong, lalu menyebabkan ruangan lainnya berada di posisi yang akan diisi oleh corong. Setiap jungkit menunjukkan suatu tinggi hujan d. Pencatatannya secara otomatis dan bertahap. Gambar 2. 17 Pencatat jungkit b. pencatat pelampung (floating gauge) → curah hujan tertangkap corong (1) tertumpah ke dalam penampung (2). Dengan terisinya penampung maka pelampung (3) akan terangkat. Pelampung dihubungkan dengan alat penulis yang dapat membuat grafik pada drum pencatat yang diputar dengan pertolongan pegas jam (4). Jika penampung menjadi kosong yang sekaligus membawa alat penulis turun ke posisi nol.
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 22 Gambar 2. 18 Alat ukur hujan otomatis jenis sifon Gambar 2. 19 Pencatat hujan tipe pelampung Gambar 2. 20 Hasil catatan dari pencatat pelampung Dengan cara ini kertas pencatat yang dililitkan pada drum pencatat, dapat diganti setiap minggu atau setiap bulan, tergantung pada alat pencatat tersebut merupakan tipe mingguan atau bulanan. Dari hasil pencatatan ini dapat dibuat lengkung massa seperti yang tertihat pada gambar berikut ini:
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 23 Gambar 2. 21 Hasil catatan yang dibuat grafik lengkung massa Dari hasil catatan (a) dapat dibuat grafik lengkung massa (b) Beberapa syarat pemasangan alat ukur hujan: a. tinggi alat dibuat sedemikian rupa sehingga pengaruh angin sekecil mungkin (Indonesia dan WHO = 120 cm) b. penempatan alat ukur dihindarkan dari lindungan pohon atau bangunan dan lain-lain c. terlindung dari gangguan luar (binatang, anak-anak dan lain-lain) d. dekat dengan tenaga pengamat e. syarat teknis harus dipenuhi (terhadap bocoran, pena macet, tinta dan lainlain) Posisi letak penempatan alat ukur hujan dijelaskan seperti dalam gambar berikut ini. Gambar 2. 22 Posisi letak penempatan alat ukur hujan 2.5. Karakter Hujan Beberapa istilah yang berhubungan dengan hujan: a. intensitas hujan – i: laju curah hujan = tinggi air per satuan waktu (mm/menit; mm/jam; mm/hari) b. durasi hujan – t : lamanya curah hujan yang terjadi (menit atau jam) c. frekwensi hujan – f: frekwensi kejadian terjadinya hujan, biasanya dinyatakan dengan waktu ulang (return period): T (sekali dalam T tahun)
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 24 d. Luas – A: l uas geografis curah hujan (km2) e. Tinggi hujan – d: jumlah hujan → ketebalan air di atas permukaan datar (mm) 1. Intensitas hujan Kalau kita diminta untuk menyiapkan perencanaan teknis bangunan air, pertamatama yang harus ditentukan adalah berapa debit yang harus diperhitungkan, atau yang lazim disebut debit (banjir) perencanaa. Besarnya debit (banjir) perencanaan ditentukan oleh intensitas hujan. i = d t dimana: d = tinggi hujan, dan t = waktu. Jika tidak ada waktu untuk mengamati besarnya intensitas hujan atau karena disebabkan tidak adalanya alat untuk mengamati, maka intensitas hujan dapat dicari dengan menggunakan rumus empiris: (1) Talbot (1881) i = a t+b (2) Sherman (1905) i = a t n , rumus ini cocok untuk t < 2 jam (3) Ishiguro i = a √t+b (4) Mononobe i = d24 24 ( 24 t ) m dengan: i = intensitas hujan t = waktu (durasi) hujan, menit untuk (1) – (3) dan jam untuk (4) a, b, m, n = konstante d24 = tinggi hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 2. Lama hujan/durasi hujan Lama hujan/durasi hujan adalah periode waktu selama hujan berlangsung. Durasi hujan dapat dinyatakan dengan satuan menit, jam, dan hari, tergantung dari pencatatan yang dilakukan. Hampir setiap stasiun penakar hujan akan mencatat lama hujan setiap hari dengan bantuan alat pengukur otomatis, dengan menganalisis kertas rekam atau grafik yang telah tergores di tinta pencatat. 3. Frekuensi hujan Frekuensi hujan adalah harapan hujan yang akan jatuh dalam waktu tertentu. Frekuensi hujan dapat diperkirakan dengan beberapa analisis data hujan hari-hari terdahulu, karena frekuensi hujan setiap hari, bulan, dan tahun akan berbeda-beda. 4. Luas Areal Luas areal adalah penyebaran hujan menurut ruang. Luas areal dapat dilihat dengan peta isohiet yang dibuat dengan data-data curah hujan yang diperoleh dari stasiun hujan/meteorologi daerah yang akan diteliti. Hujan dapat bersifat lokal dan dapat juga bersifat menyeluruh dalam suatu daerah, tergantung dari potensi awan yang akan menjadi hujan. Peta isohiet akan membantu daerah-daerah yang mempunyai curah hujan yang sama dengan bantuan stasiun penakar hujan yang berdekatan dengan suatu daerah. 2.6. Memroses Data Hujan Dengan melakukan penakaran atau pencatatan, kita hanya mendapat data curah hujan di suatu titi tertentu (point rainfall). Jika di dalam suatu areal terdapat
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 25 beberapa alat penakar atau pencatat curah hujan, maka dapat diambil nilai ratarata untuk mendapatkan nilai curah hujan areal. Ada 3 macam cara yang berbeda dalam menentukan tinggi curah hujan rata-rata pada areal tertentu dari angka-angka curah hujan di beberapa titik pos penakar atau pencatat: cara tinggi rata-rata, cara poligon Thiessen dan cara Isohyet. 1. Cara arithmatic mean – rata-rata aljabar Tinggi rata-rata curah hujan didapatkan dengan mengambil nilai rata-rata hitung (arithmatic mean) pengukuran hujan di pos penakar-penakar hujan di dalam areal tersebut. d = d1+d2+d3+........+dn n = ∑ di dn n i=1 dengan: d = tinggi curah hujan rata-rata d1, d2 .......... dn = tinggi curah hujan pada pos penakar 1,2, ........ n n = banyaknya pos penakar Cara ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya jika pos-pos penakarnya ditempatkan secara merata di areal tersebut dan hasil penakaran masing-masing pos penakar tidak menyimpang jauh dari nilai rata-rata seluruh pos di seluruh areal. 2. Cara poligon Thiessen Cara ini berdasarkan rata-rata timbang (weighted average). Masing-masing penakar mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegaklurus terhadap garis penghubung di antara dua buah pos penakar. Gambar 2. 23 Gambar polygon Thiessen d = A1d1+A2d2+A3d3+............+Andn A1+A2+A3+.................+An = ∑ Aidi A n i=1 atau d = ∑ pidi n i=1 dimana: Ai A = pi ; A = luar areal d = tinggi curah hujan rata-rata areal
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 26 d1, d2, d3 ........ dn = tinggi curah hujan pada sta 1,2,3,......n A1, A2, A3 .......An = luas daerah pengaruh sta 1,2,3,.........n 3. Cara Isohyet Dalam cara ini kita harus menggambar terlebih dahulu kontur tinggi hujan yang sama (isohyet). Kemudian luas bagian di antara isohyet-isohyet yang berdekatan diukur, dan nilai rata-ratanya dihitung sebagai nilai rata-rata timbang nilai kontur sebagai berikut: Gambar 2. 24 Gambar Isohyet d = d0+d1 2 A1+ d1+d2 2 A2+............+ dn−1+dn 2 An A1+A2+....................+An = ∑ di−1+di 2 Ai n i=1 A dimana: A = A1+A2+..............+An = luas areal total d = tinggi curah hujan rata-rata areal d0,d1,d2.......................dn = curah hujan pada isohyet A1, A2, .... An = luas areal yang dibatasi oleh isohyet-isohyet yang bersangkutan Pemrosesan data hujan juga meliputi data hujan yang tidak lengkap, seperti metode menambah hasil pencatatan penakar hujan yang ada kekurangan/kosong datanya, menambah data yang hilang dalam tahun tertentu, trend/kecenderungan data, dan lengkung massa ganda 1. Menambah hasil pencatatan penakar hujan Misalnya A dan B merupakan pos-pos pencatat curah hujan yang dapat mencatat tinggi hujan setiap saat sehingga lengkung massanya dapat dibuat. C adalah penakar hujan biasa (non recording gauge) yang menghasilkan tinggi hujan dc dalam 1 hari. Jika distribusi hujan di C dianggap sama dengan distribusi hujan di pos penakar yang berdekatan, maka lengkung masa C dapat dinterpolasikan (atau diekstrapolasikan) dengan lengkung massa A dan B.
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 27 Gambar 2. 25 Lengkung massa dari pencatat hujan Menggambar lengkung massa dari penakar biasa C, terjadi interpolasi (ekstrapolasi) lengkung massa dari pencatat hujan A dan B 2. Menambah data yang hilang dalam tahun tertentu Data yang hilang atau kesenjangan (gap) data suatu pos penakar hujan, pada saat tertentu, dapat diisi dengan bantuan data yang tersedia pada pos-pos penakar di sekitarnya pada saat yang sama. Cara yang dipakai dinamakan ratio normal. Syarat untuk menggunakan cara ini adalah tinggi hujan rata-rata tahunan pos penakar yang datanya hilang harus diketahui, di samping dibantu dengan data tinggi hujan rata-rata tahunan dan data pada pos-pos penakar di sekitarnya. A dx = 1 n ∑ di ∗ Anx Ani n i=1 B X C dengan: n = banyaknya pos penakar di sekitar x yang dipakai untuk mencari data x Anx= tinggi hujan rata-rata tahunan di x Ani = tinggi hujan rata-rata tahunan di pos-pos penakar di sekitar x yang dipakai untuk mencari data x yang hilang 3. Trend Trend adalah perubahan gradual (perubahan naik atau turum) faktor iklim dan hidrologi terhadap waktu. Trend dapat digambarkan jika kita mempunyai hasil pengamatan (penakaran atau pencatatan) dalam jangka panjang (long term observation). Adanya osilasi, siklik atau bentuk lain dalam trend dapat dihaluskan dengan pertolongan nilai rata-rata progresif atau nilai rata-rata bergerak (progressive or moving average) yang ditentukan sebagai berikut: yn+1 2 = x1+x2+...........+xn n yn+3 2 = x2+x3+...........+xn+1 n Gambar 2. 26 Contoh lokasi-lokasi pencatat hujan
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 28 yn+5 2 = x3+x4+...........+xn+2 n ...........dst.......... dimana: y = nilai rata-rata progresif n = jumlah data yang dirata-ratakan] xi = hasil pengamatan, yang disusun menurut kejadiannya dengan i = 1,2,3,...n (misalnya: tinggi curah hujan) 4. Lengkung Massa Ganda (double mass curve) Jika data hujan tidak konsisten karena perubahan atau gangguan lingkungan di sekitar tempat penakar hujan dipasang, misalnya: penakar hujan terlindung oleh pohon, terletak berdekatan dengan gedung tinggi, perubahan cara penakaran dan pencatatan, pemindahan letak penakar dan sebagainya, memungkinkan terjadi penyimpangan terhdap trend semula. Hal ini dapat diselidiki dengan menggunakan lengkung massa ganda. C C’ B 45/ A Kalau kita diminta untuk menyiapkan perencanaan teknis bangunan air, pertamatama yang harus ditentukan adalah berapa debit yang harus diperhitungkan, atau yang lazim disebut debit (banjir) perencanaa. Besarnya debit (banjir) perencanaan ditentukan oleh intensitas hujan. i = d t dimana: d = tinggi hujan, dan t = waktu. Jika tidak ada waktu untuk mengamati besarnya intensitas hujan atau karena disebabkan tidak adalanya alat untuk mengamati, maka intensitas hujan dapat dicari dengan menggunakan rumus empiris: (1) Talbot (1881) i = a t+b (2) Sherman (1905) i = a t n , rumus ini cocok untuk t < 2 jam (3) Ishiguro i = a √t+b Gambar 2. 27 Gambar lengkung massa ganda Curah hujan tahunan rata-rata akumulatip (mm) Curah hujan tahunan rata-rata beberapa pos penakar yang berdekatan (mm)
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 29 (4) Mononobe i = d24 24 ( 24 t ) m dengan: i = intensitas hujan t = waktu (durasi) hujan, menit untuk (1) – (3) dan jam untuk (4) a, b, m, n = konstante d24 = tinggi hujan maksimum dalam 24 jam (mm)
PRECIPITATION-RAINFALL BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 30 Tugas 2 1. Tuliskan secara skematik dan gambarkan pengertian precipitation dan rainfall (secara individu)! Ungkapkan juga dalam bentuk vlog kelompok! 2. Sebutkan dalam vlog, bentuk-bentuk presipitasi, jenis-jenis hujan dan karakter hujan (termasuk bermacam-macam awan yang menyebabkannya)! 3. Carilah dari internet, berbagai bentuk dan macam alat ukur curah hujan, dan sebutkan pula spesifikasinya (optional: harganya) dan cara kerjanya. Hasilnya susun dalam laporan kelompok yang menyertai vlog kelompok. 4. Latihan soal polygon Thiessen (secara individu), hitung intensitas hujan wilayah dari 4 stasiun hujan yang posisinya seperti gambar berikut ini. Hitung intensitas hujan wilayah area luasan 10 km x 15 km di atas!
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 31 BAB 3 – RAINFALL-RUNOFF 3.1 Rainfall-Runoff Relationship and Process Rainfall atau lebih dikenal sebagai hujan yang jatuh di atas tanah, tidak semuanya diserap ke dalam air tanah ataupun menguap, melainkan ada yang mengalir di atas permukaan tanah. Limpasan atau runoff, dapat digambarkan sebagai bagian dari siklus air yang mengalir di atas permukaan tanah ini, sebagai air permukaan, bukannya diserap ke dalam air tanah atau menguap. Menurut Geologi A.S. Survey (USGS), runoff adalah bagian dari presipitasi, salju yang mencair, atau air irigasi yang mengalir sebagai aliran permukaan, sungai, saluran air, atau selokan yang tidak terkendali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi runoff, antara lain: jumlah curah hujan, jumlah salju yang mencair, permeabilitas tanah, vegetasi permukaan tanah dan kelerengan permukaan tanah. Jumlah curah hujan secara langsung mempengaruhi jumlah runoff. Semakin banyak hujan lebih banyak mencapai tanah, lebih banyak curah hujan akan berubah menjadi runoff. Demikian juga semakin banyak jumlah salju yang mencair dalam periode waktu singkat, maka akan semakin besar jumlah runoff. Kemampuan permukaan tanah untuk menyerap air (permeabilitas) maka akan berpengaruh pada banyaknya runoff atau limpasan permukaan yang terjadi. Semakin sedikit air yang dapat diserap oleh tanah, maka semakin banyak runoff di permukaan tanah. Permukaan dengan kemampuan penyerapan yang tinggi, artinya memiliki permeabilitas yang tinggi, dan permukaan dengan kemampuan penyerapan rendah, artinya memiliki permeabilitas rendah. Vegetasi membutuhkan air untuk bertahan hidup, dan sistem akar tanaman dirancang untuk menyerap air tanah. Ada lebih sedikit runoff di daerah yang sangat bervegetasi karena air digunakan oleh tanaman. Kemiringan permukaan juga penting dalam analisis jumlah runoff yang akan ada. Lebih curam permukaan, maka semakin cepat ia akan menuruni lereng. Permukaan tanah yang curam tidak memungkinkan waktu bagi air untuk menyerap. Gambar di bawah ini menunjukkan tingkat permeabilitas untuk berbagai jenis permukaan. Gambar 3. 1 Persentase dari limpasan permukaan (runoff) pada berbagai permukaan
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 32 Sementara runoff dipengaruhi oleh berbagai hal seperti jumlah curah hujan dan vegetasi, terlalu banyak dapat memiliki efek buruk pada lingkungan juga. Beberapa contoh termasuk erosi dan polusi. Saat runoff berkembang, ia dapat mengumpulkan hal-hal yang menghalangi, mengangkutnya, dan menjatuhkannya ke suatu tempat di hilir ketika air melambat. Pada suatu sungai atau aliran, air yang bergerak adalah kekuatan yang kuat yang mampu menggerakkan benda-benda yang ada. Runoff kecil mampu memindahkan bendabenda ringan seperti dedaunan dan kerikil, sedangkan runoff besar, seperti banjir akan mampu menyapu mobil dan bahkan rumah. Runoff juga dapat membawa polusi dari limbah yang ada sepanjang perjalanannya. Radhika Kumari, Mohit Mayoor, Somnath Mahapatra, P.K. Parhi, H.P. Singh (2019), menuliskan bahwa curah hujan adalah parameter meteorologi yang paling penting untuk hidrologi, karena mengontrol proses lain seperti infiltrasi, limpasan, penyimpanan detensi, dan evapotranspirasi. Ketika curah hujan jatuh di atas daerah tangkapan air, proses-proses ini harus dipenuhi sebelum air hujan menjadi limpasan. Infiltrasi adalah aliran turun dari curah hujan, ke arah vertikal ke tanah, kemudian ke bawah tanah sebagai perkolasi menjadi imbuhan air tanah. Proses ini tergantung pada jenis tanah, porositas, dan permeabilitas. Limpasan, yang berupa aliran air hujan pada permukaan tanah yang terjadi ketika ada curah hujan berlebih di suatu daerah. Limpasan diproduksi ketika air hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Hubungan yang paling penting untuk setiap daerah aliran sungai adalah hubungan antara curah hujan dan limpasan. Hubungan ini tergantung pada beberapa faktor seperti karakteristik curah hujan, limpasan, dan infiltrasi. Meskipun faktor-faktor memiliki dampak besar pada volume limpasan, namun ada korelasi yang konsisten antara curah hujan dan limpasan permukaan. Korelasi ini digambarkan dalam analisis grafis, dengan nilai koefisien korelasi Pearson (r) hampir sama dengan +1, yang merupakan korelasi positif yang hampir sempurna, menandakan bahwa kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Ini juga menandakan bahwa kedua variabel yang dibandingkan memiliki hubungan positif sempurna; hal ini berarti bahwa keduanya sangat terkait. Dituliskan pula bahwa infiltrasi dan limpasan sebagian besar berkorelasi. Gambar 3. 2 Proses fisik terkait pembentukan limpasan permukaan (runoff) Jalur air yang bergerak sebagai aliran diilustrasikan dalam Gambar III.2 di atas. Curah hujan bisa dalam bentuk hujan atau salju, akan jatuh di atas tanah dan pada tanaman yang menahan sebagian kecil dari hujan tersebut. Hujan yang menembus vegetasi disebut sebagai throughfall yang terdiri dari dua bentuk: yang disadap oleh tanaman dan langsung jatuh ke tanah. Sebagian besar dari air yang disadap biasanya diuapkan kembali ke atmosfer, sebagai transpirasi, dan ada pula penguapan dari tanah dan badan air sebagai evaporasi. Masukan air permukaan yang tersedia untuk pembentukan limpasan terdiri dari throughfall dan curah hujan yang mengisi cekungan (depression storage), terus mengalir sebagai aliran permukaan, bergabung dengan aliran dalam tanah (interflow) dan aliran dasar (baseflow), menuju ke sungai dan mengalir kembali ke laut.
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 33 Lintasan air di bawah permukaan tanah pada lereng bukit, diilustrasikan seperti dalam gambar berikut ini. Gambar 3. 3 Jalur air limpasan bawah permukaan pada lereng bukit (Kirkby, 1978) Gambar III.3 menggambarkan penampang memanjang lereng bukit yang terbuka sehingga detail jalur air yang meresap dan mengalir di bawah permukaan dapat terlihat. Air mengalir melalui butiran tanah yang memiliki pori-pori (micropores) yang dapat ditembus dan juga dapat mengalir melalui rongga yang lebih besar (macropores). Rongga ini berfungsi sebagai pipa di dalam tanah yang terjadi disebabkan oleh akar yang membusuk dan galian dari binatang kecil dalam tanah. Rongga ini menjadi jalur utama aliran bawah permukaan yang dikenal sebagai interflow. 3.2. Interception-Depression Storage-Infiltration-Percolation Interception-depression storage-infiltration-percolation adalah bentuk-bentuk kehilangan air hujan (rainfall losses). Kehilangan ini tidak hanya merugikan karena berkurangnya intensitas hujan, tetapi lebih menguntungkan karena mengurangi dampak negatif daya rusak air hujan. Intersepsi adalah hujan yang jatuh di atas pohon dimana sebagian melekat pada tajuk daun maupun batang, yang merupakan tampungan/simpanan. Intersepsi ini akhirnya segera menguap. Secara sederhana, intersepsi didefinisikan sebagai proses pengambilan air pada vegetasi (daun, kulit kayu, rumput, tanaman, dll.). Curah hujan yang ditahan, menjadi tidak tersedia untuk limpasan atau infiltrasi, tetapi sebaliknya dikembalikan ke atmosfer melalui penguapan. Besar kecilnya intersepsi dipengaruhi oleh sifat hujan (terutama intensitas hujan dan lama hujan), kecepatan angin, jenis pohon (kerapatan tajuk dan bentuk tajuk). Simpanan intersepsi pada hutan pinus di Italia utara sekitar 30% dari hujan (Allewijn, 1990). Intersepsi tidak hanya terjadi pada tajuk daun bagian atas saja, intersepsi juga terjadi pada daun-daun kering di bawah pohon. Intersepsi akan mengurangi hujan yang menjadi run off. Hasil penelitian intersepsi di hutan pinus berumur 18 tahun
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 34 dengan jarak pohon 3m x 4m dan kerapatan tegakan 670 batang/Ha, tinggi ratarata tegakan 17,5m dan penutupan tajuk 45%, hasil intersepsi terukur dengan rata-ratanya berkisar 27% - 38% dari total hujan. (Fakultas Kehutanan UGM, 1993). Gambar 3. 4 Interception, depression storage and infiltration Depression storage, adalah suatu genangan air pada cekungan permukaan tanah. Ketika air hujan jatuh ke permukaan tanah, maka sebagian tertahan pada cekungan-cekungan permukaan tanah. Bila curah hujan dengan intensitas besar atau deras, maka akan terjadi superficial storage sebelum masuk ke sungai, dan juga dapat membentuk rawa (swamp), sementara juga mengisi danau, situ atau embung yang ada (Gambar III.5). Gambar 3. 5 Depression storage, superficial storage, swamp, flooded plains and lake
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 35 Proses berlangsungnya air masuk ke permukaan tanah kita kenal dengan infiltrasi, sedang perkolasi adalah proses bergeraknya air melalui profil tanah karena tenaga gravitasi. Laju infiltrasi dipengaruhi tekstur dan struktur, kelengasan tanah, kadar materi tersuspensi dalam air juga waktu. Pada umumnya tanah yang tertutup hutan tak terganggu mempunyai laju infiltrasi dan perkolasi tinggi dan hal ini ada kaitannya dengan aktifitas biologi dalam tanah, sistem perakaran, sampah organik hutan dalam DAS mengakibatkan struktur tanah granular dan sarang (porous) yang mengakibatkan infiltrasi cepat Infiltrasi adalah perpindahan air dari atas ke dalam permukaan tanah, atau pergerakan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah, menuju ke bawah permukaan tanah. Sedangkan perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh, yang terletak di antara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah (zona jenuh). Perbedaan infiltrasi dan perkolasi dijelaskan seperti dalam Gambar III.6 berikut ini. P Land surface Water table perkolasi Daya infiltrasi: fP → laju infiltrasi maximum yang dimungkinkan → besarnya (mm/jam atau mm/hari) ditentukan oleh kondisi permukaan tanah termasuk lapisan atas tanah. Daya perkolasi: pP → laju perkolasi maximum yang dimungkinkan → besarnya dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam zona tidak jenuh. Perkolasi terjadi setelah tanah dalam zona tidak jenuh mencapai kapasitas lapang (field capacity) Hal yang berhubungan dengan infiltrasi: a. Proses limpasan (run off) → oleh hujan b. Pengisian kembali lengas tanah (soil moisture) dan air tanah 3.2.1. Profil Kelembaban Tanah (Soil-Moisture Profile) Profil kelembaban tanah dapat digambarkan di bawah ini yang menunjukkan bahwa kadar air sebagai fungsi kedalaman pada saat yang berturutan dari t0 sampai t6. infiltrasi Gambar 3. 6 Penampang lapisan tanah