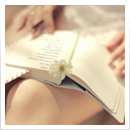RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 36 Gambar 3. 7 Profil kelembaban tanah Untuk tanah homogen → kadar air di zona tidak jenuh pada saat t = t0 adalah w0. Akibat dari adanya infiltrasi selama turun hujan dari t0 sampai t1, kadar air di lapisan atas naik menjadi w1. Bila hujan berhenti pada t = t1, maka airnya akan bergerak ke bawah di dalam tanah dengan lengas air yang terjadi pada waktu t2, t3, t4, dan t5. Akhirnya pada t = t6, lengas tanahnya mencapai kapasitas lapang di seluruh kedalaman. Kadar lengas tanah dapat diteliti dengan 2 cara: 1. Dengan mengambil contoh tanah → ditimbang, dikeringkan kemudian ditimbang lagi → kadar air dalam tanah ditemukan. Cara ini bersifat merusak, artinya tidak mungkin mengulangi pengamatan di tempat yang sama. 2. Dengan alat Neutron Probe → terdiri dari sumber radium berilium dan detektor, yang ditempatkan dalam tabung dengan diameter sebesar beberapa cm dan panjangnya 740 mm, yang dapat diperpanjang dan dimasukkan ke dalam pipa aluminium, yang dipasang secara permanen di dalam tanah, dengan memakai kabel. Di dalam tanah neutron yang cepat dikirimkan oleh sumber, yang kemudian bertabrakan dengan ion-ion H lengas tanah. Bergantung pada kadar lengas tanah ada beberapa neutron lambat yang dipantulkan, Banyaknya netron lambat diterima oleh detektor dalam jangka waktu 1 menit dicatat oleh pesawat penghitung yang dihubungkan oleh kabel dengan neutron probe tersebut. Pengukuran ini dapat diulang-ulang pada berbagai kedalaman, misalnya pada setiap penurunan 0.5 m. Hasil pembacaan dapat diterjemahkan ke dalam kadar lengas tanah melalui lengkung kalibrasi. Lengkung kalibrasi tersebut berhubungan erat dengan jenis tanah, komposisi kimia lengas tanah dan besar serta bentuk tabung. Cara ini tidak bersifat merusak, pembacaannya dapat dilakukan pada titik yang sama dan hasilnya dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 37 Gambar 3. 8 Alat neutron probe 3.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Infiltrasi Faktor-faktor yang mempengaruhi daya infiltrasi: a. Dalamnya genangan di atas permukaan tanah (surface detention) dan tebal lapisan jenuh b. Kadar air dalam tanah c. Pemampatan oleh curah hujan → pukulan butir air d. Tumbuh-tumbuhan → partikel humus e. Lain-lain misalnya: rekahan tanah, mengembangnya tanah (lempung) Daya infiltrasi tergantung pula pada: tipe tanah, adanya tumbuh-tumbuhan, cara pengerjaan tanah maupun kadar air. Daya infiltrasi menurun selama waktu hujan karena: a. pemampatan permukaan tanah oleh pukulan butir-butir hujan b. mengembangnya tanah liat dan partikel-partikel humus oleh lembabnya tanah c. tersumbatnya pori-pori oleh masuknya butir-butir tanah yang lebih kecil d. terperangkapnya udara dalam pori-pori tanah. 3.2.3. Pengukuran Daya Infiltrasi Daya infiltrasi dapat diukur dengan cara: a. Infiltrometer → dalam bentuknya yang paling sederhana terdiri atas tabung baja yang ditekankan ke dalam tanah. Gambar 3. 9 Alat infiltrometer Permukaan tanah di dalam tabung diisi air. Tinggi air dalam tabung akan menurun, karena proses infiltrasi. Kemudian banyaknya air yang
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 38 ditambahkan untuk mempertahankan tinggi air dalam tabung tersebut diukur. Makin kecil diameter tabung makin besar gangguan akibat aliran ke samping di bawah tabung. Efek aliran ke samping ini sebagian dapat dihilangkan dengan memasang tabung konsentrik di luarnya dan ke dalam kedua tabung tersebut diisi air. Dengan cara ini daya infiltrasinya dapat dihitung dari banyaknya air yang ditambahkan ke dalam tabung sebelah dalam per satuan waktu. Gambar 3. 10 Double ring infiltrometer b. Testplot → infiltrometer skala besar Pengukuran daya infiltrasi dengan infiltrometer hanya dapat dilakukan terhadap luasan yang kecil saja, sehingga sukar untuk mengambil kesimpulan terhadap daya infiltrasi bagi daerah yang lebih luas. Untuk mengatasi hal ini dipilih tanah datar yang dikelilingi tanggul dan digenangi air. Daya infiltrasi didapat dari banyaknya air yang ditambahkan agar permukaan airnya konstan. Baik infiltrometer maupun testplot masih dianggap gagal dalam menirukan infiltrasi akibat adanya hujan. Namun apa yang didapatkan dari pengukuran ini dapat dipakai sebagai perbandingan. Gambar 3. 11 Testplot (petak uji) c. Lysimeter → berupa tangki beton yang ditanam dalam tanah diisi tanah dan tanaman yang sama dengan sekelilingnya, dilengkapi dengan fasilitas drainase dan pemberian air. Dengan persamaan neraca air (water balance): P + I = D + E ± S dimana: I = pemberian air D = air yang dikeluarkan (drainase) E = penguapan (evapotranspirasi) S = tampungan air dalam tanah
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 39 Lysimeter Lysimeter Timbang Gambar 3. 12 Alat Lysimeter Untuk mengusahakan penaksiran besarnya infiltrasi yang baik maka digunakan lysimeter timbang dimana besarnya infiltrasi dengan kondisi curah hujan yang sebenarnya dapat dipelajari. Curah hujan harus diukur pula dengan alat pencatat hujan yang ditempatkan di dekat lysimeter. d. Test penyiraman/springkling test Di atas sebidang tanah diberikan hujan tiruan dengan intensitas yang diketahui dan konstan. Permukaan tanah dibuat agak miring sehingga terjadi limpasan permukaan. Gambar 3. 13 Springkling test (petak uji) e. Dari hubungan curah hujan dengan limpasan, dalam daerah pengaliran kecil Tinggi total seluruh kehilangan bila dibagi oleh durasi hujan, adalah sama dengan intensitas kehilangan rata-rata dan dinamakan Φ-indeks Dalam daerah pengaliran yang lebih besar, cara Φ-indeks ini sulit untuk diterapkan karena distribusi hujan yang tidak merata di atas daerah pengaliran tersebut dimana distribusi kehilangannyapun juga tidak merata.
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 40 Gambar 3. 14 Hubungan curah hujan dan limpasan Contoh: Diketahui curah hujan total sebesar 75 mm (gb. a dan b) dan besarnya limpasan permukaan sebesar 33 mm; tentukan Φ-indeks! Dari gambar (a) dengan memisalkan Φ > 7 mm/jam didapat: (18 – Φ) + (25 – Φ) + (12 – Φ) + (10 – Φ) = 33 4 Φ = 32 → Φ = 8 mm/jam Dari perhitungan di atas diperoleh Φ = 8 mm/jam, jadi Φ > 7 mm/jam yang berarti pemisalan kita adalah benar. Dengan cara yang sama dapat ditemukan harga Φ untuk gambar (b) yaitu sama dengan 9 mm/jam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah hujannya sama dan besarnya limpasan permukaan juga sama, tetapi jika distribusi hujannya tidak sama akan diperoleh harga Φ-indeks yang berbeda.
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 41 Gambar 3. 15 Grafik keseimbangan kadar air tanah dan relasinya dengan runoff 3.3. Evaporation-Transpiration-Evapotranspiration Evaporasi adalah proses perpindahan molekul air ke dalam atmosfir dari permukaan air bebas, tanah maupun air yang terhadang oleh tumbuh-tumbuhan. Evaporasi merupakan faktor penting dalam studi tentang pengembangan sumbersumber daya air. Evaporasi sangat mempengaruhi debit sungai, besarnya kapasitas waduk, besarnya kapasitas pompa untuk irigasi, penggunaan konsumtif tanaman dan lain-lain. Faktor meteorologi yang berpengaruh terhadap evaporasi: a. Radiasi matahari → energi berupa panas laten, membantu perubahan zat cair ke dalam uap air b. Angin → kecepatan angin, menggerakkan lapisan jenuh dan diganti udara kering → peranan penting dalam proses evaporasi c. Kelembaban relatif → kelembaban relatif yang meningkat akan mengurangi kemampuan udara menyerap air → evaporasi menurun d. Suhu → menambah energi untuk mengubah air menjadi uap air.
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 42 Gambar 3. 16 Proses evapotranspirasi dan relasinya dengan infiltrasi-perkolasi 3.3.1. Pengukuran Evaporasi Beberapa alat pengukuran evaporasi antara lain: a) Atmometer → alat standar untuk mengukur evaporasi dari permukaan tanah. Ada 2 jenis alat ini: Atmometer Piche dan Atmometer Livingstone Atmometer Piche kehilangan air (cm3/day) → ukuran laju evaporasi Atmometer Livingstone bola porselin berpori diisi air untuk memberikan permukaan evaporasi Gambar 3. 17 Alat pengukur evaporasi atmometer b) Panci Evaporasi Di atas permukaan tanah Ditanam dalam tanah
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 43 US class A pan → koef = 0.8 Colorado Sunken Pan → koef = 0.75 – 0.86 Mengambang di atas air Floating Pan Gambar 3. 18 Macam-macam alat Panci Evaporasi Pengukuran ini dimaksudkan untuk memperhitungkan pengaruh massa uap air di atas permukaan air bebas. Besarnya evaporasi yang terukur di panci dan terjadi di danau dihitung dengan rumus: Epan = c(esp − ea)(1 + 0.25u); Edanau = c(esd − ea )(1 + 0.25u) Edanau = (esd−ea ) (esp−ea) ∗ Epan atau = ∗ c = konstanta esp = tekanan uap air jenuh pada temperatur air di dalam panci esd = tekanan uap air jenuh di danau ea = tekanan uap air nyata pada temperatur udara u = kecepatan angin (m/det) 3.3.2. Penaksiran Besarnya Evaporasi Prinsip dasar untuk menaksir besarnya evaporasi dapat secara tidak langsung didekati dari observasi standar meteorologi termasuk perubahan massa, budget energi dan metoda kombinasi serta beberapa macam metoda empiris. Metoda perubahan massa berdasar pada persamaan DALTON (1800): E0 = f(u)(es − ed ) Dimana: f(u) = a" + b" . u = Nm . u f(u) = fungsi dari kecepatan angin es = saturated vapour pressure at the water surface temperature, Ts ed = actual vapour pressure of the overlying air a" dan b" = konstanta yang tergantung pada lokasi Nm= mass transfer coefficient es = 2.749 ⋅ 10 8 exp ( −4278.6 Ts+242.8 ) dimana es dalam mbar dan Ts dalam 0C
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 44 Dalam metoda kombinasi → persamaan di atas dimodifikasi menjadi: Ea = f(u) ⋅ (ea − ed ) dimana: ea = saturated vapour pressure at the air temperature, Ta PENMAN (1948) memberikan persamaan: E0 = w ⋅ Rn + (1 − w) ⋅ Ea dimana : Rn = Ri ⋅ (1 − r) − R0 Rn = net radiation Ri = incoming short wave r = albedo → r = 0.05 untuk open water r = 0.25 untuk short grass R0 = net outgoing long wave radiation Ri = S0 ⋅ (a + b ⋅ n N ) S0 = insolation at the edge of the Earth’s atmosphere a dan b = konstanta tergantung dari lokasi n/N = ration of the measured to the max possible sunshine hours Doorenbos dan Pruitt (1977) memberikan penyelesaian pada persamaan Penman: R0 = σT 4 ⋅ (c − d√ed) (a′ + b′ ⋅ n N ) a’, b’, c dan d → konstanta yang tergantung pada lokasi T4 → dalam mm/day → tabel Doorenbos&Pruitt (1977) Thornthwaite Method → the monthly potential evaporation, PE (mm) PE = 16N ⋅ ( 10T I ) a dimana: N = faktor koreksi sehubungan dengan lama penyinaran T = temperatur rata-rata (/C) I = annual heat index = ∑ im = ∑ ( T 5 ) 12 1 1.514 a = 6.75 * 10-7 I 3 + 7.71 * 10-5 I 2 + 1.79 * 10-2 I + 0.492 Ada 3 hal penting dari kemampuan tanah memegang kandungan air untuk menaksir besarnya Evaporasi Potensial. saturation gravitational water rapid drainage field capacity available moisture capillary water slow drainage permanent wilting point
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 45 unavailable moisture hygroscopic water essentially no drainage BLANEY – CRIDLE METHOD → monthly consumptive use, U → diaplikasikan untuk irigasi di Mexico. U = ks Tp 100 dimana: ks = koefisien tanaman T = temperatur rata-rata (/F) p = persentase lama penyinaran tahunan DOORENBOS & PRUITT (1977) menyempurnakan rumus di atas yang dikenal sebagai Blaney – Criddle/FAO method sebagai Ecrop (evaporasi untuk tanaman tertentu) dari Er (evaporasi untuk tanaman referensi: short grass) Er = c[p(0.46T + 8)] dan Ecrop = kc ⋅ Er dimana: c = konstanta tergantung dari kelembaban relatif minimum, lama penyinaran dan kecepatan angin p = persentase lama penyinaran tahunan T = temperature rata-rata (/C) kc = koefisien tanaman → perbedaannya dari koef. tanaman asli: ks PENMAN (1948) dan DOORENBOS & PRUITT (1977) → monthly reference crop evaporation (mm/day): Er = C[W(Ri − R0 ) + (1 − W)f(u)(ea − ed )] (pottential evaporation was estimated as a propotion of open water evaporation by reduction factor): = 0.8 (may – august) 0.6 (nov – feb) 0.7 (all other months) short grass → reference crop → r = 0.25 ALLEN and PRUITT (1991) memberikan: f(u) = 0.27 (1 + u 100) Ri = 0.75 ⋅ S ⋅ (0.25 + 0.75 n N ) R0 = σT 4 ⋅ (0.34 − 0.044√ed) (0.1 + 0.9 n N ) TURC’S METHOD → memberikan penaksiran besarnya evaporasi aktual: Eact = P+A+V √1+( P+A L + V 2L) 2 dimana: L = T+2 16 √Ri dan V = 25√ Mc Z p = presipitasi (mm/10 day period) A = evaporasi dari tanah gundul sampai max 10 mm/10 day period L = kapasitas evaporasi udara Gambar 3. 19 Critical moisture states in a soil column
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 46 T = temperature rata-rata (/C) Ri = incoming radiation (cal/cm2/day) V = crop faktor M = dry matter production (102 kg/ha) c = crop constant Z = growing season length in numbers of 10 day periods Bila L > 10 → A = 10 dan V = 70 dan L < 10 → A = 10 dan V = 0 PIKE (1964) → mengaplikasikan metoda ini untuk menentukan keseimbangan air dari suatu daerah tangkapan yang luas di Malawi. Evapotranspirasi dapat juga dihitung dengan menggunakan program komputer ETo calculator (FAO, 2009). Tabel 3. 1 Insolation at the edge of the Earth atmosphere → S0 (mm/day)
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 47 Tabel 3. 2 Mean daily duration of maximum possible sunshine hours for different months and latitude (after Doorenbos and Pruitt, 1977) → N (h/d)
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 48 Tabel 3. 3 The function F (T) = T4 (mm/d) as a function of temperature, T (/C) Tabel 3. 4 The weighting function, 1-W, as a function of temperature (/C) and altitude (m) (modified from Doorenbos and Pruitt, 1977) 3.4. Rainfall-Runoff Analysis Limpasan permukaan dihasilkan oleh badai hujan, dimana kejadian dan jumlahnya tergantung pada karakteristik curah hujan, yaitu intensitas, durasi dan distribusi. Selain itu, ada faktor-faktor penting lain yang mempengaruhi proses banyaknya limpasan permukaan. Curah hujan di zona kering dan semi-kering sebagian besar dihasilkan dari mekanisme awan konvektif, yang menghasilkan badai dan biasanya berdurasi pendek, intensitas relatif tinggi dan luas areal terbatas. Intensitas curah hujan didefinisikan sebagai rasio jumlah total hujan (kedalaman curah hujan) yang turun dalam periode dengan durasi tertentu, dinyatakan dalam satuan kedalaman per satuan waktu, biasanya dalam mm/jam. Analisis hujan dengan metode statistik akan dijelaskan dalam sub-bab lain. Dari analisis hujan ini, dapat dilakukan analisis limpasan lebih lanjut dengan metode rasional, yang diperlukan data luasan daerah tangkapan hujan atau daerah aliran sungai (DAS).
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 49 Faktor yang mempengaruhi besarnya limpasan dijelaskan sebagai berikut: 1. Faktor meteorologi: a) Intensitas hujan. Pengaruh intensitas hujan thd limpasan sangat tergantung pada laju infiltrasi. Jika intensitas hujan lebih besar dari laju infiltrasi, maka akan terjadi limpasan yang besarnya juga dipengaruhi oleh adanya penggenangan di permukaan tanah b) Durasi hujan. Total limpasan berkaitan langsung dengan durasi hujan. Setiap DAS mempunyai satuan durasi hujan atau lama hujan kritis. Jika hujan yang terjadi lamanya kurang dari lama hujan kritis, maka lamanya limpasan akan sama dan tidak tergantung pada intensitas hujan. c) Distribusi hujan. Laju dan volume limpasan dipengaruhi oleh distribusi dan intensitas hujan di seluruh DAS. Laju dan volume limpasan maksimum bila seluruh DAS memberikan kontribusi aliran. Namun demikian, intensitas hujan yang tinggi dapat menghasilkan limpasan yang lebih besar dibandingkan dengan hujan biasa yang meliputi seluruh DAS. Jika kondisi topografi, tanah, dsb. di seluruh DAS seragam, untuk jumlah hujan yang sama, maka curah hujan yang distribusi merata akan menghasilkan debit puncak paling minimum. 2. Faktor karakteristik DAS: a) Luas dan bentuk DAS. Laju dan volume aliran permukaan bertambah besar seiring dengan bertambah luasnya DAS. Namun apabila aliran tidak dinyatakan sebagai jumlah total DAS melainkan sebagai laju dan volume persatuan luas, besarnya aliran permukaan akan berkurang dengan bertambahnya luas DAS. Ini berkaitan dengan waktu kritis aliran dan penyebaran atau intensitas hujan. Bentuk DAS berpengaruh terhadap pola aliran pada sungai khususnya bentuk hidrograf aliran. Gambar 3. 20 Pengaruh bentuk DAS pada aliran permukaan b) Topografi. Topografi lahan yang meliputi kemiringan lahan, kerapatan saluran, dan bentuk cekungan lainnya berpengaruh terhadap laju dan volume aliran permukaan. Semakin curam lahan dan rapat saluran pada suatu DAS menghasilkan laju dan volume aliran yang lebih besar.
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 50 Gambar 3. 21 Pengaruh kerapatan parit/saluran pada hidrograf aliran permukaan c) Tata guna lahan. Pengaruh tata guna lahan terhadap aliran permukaan dinyatakan dalam koefisien limpasan. Koefisien limpasan merupakan indikator untuk menentukan kondisi fisik suatu DAS. C=0 → semua air hujan terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah. C=1 → semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. C mendekati 1 → kondisi DAS semakin kritis. Analisis limpasan permukaan (runoff) merupakan analisis debit banjir. Metode yang digunakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data (Gambar III.22.). Gambar 3. 22 Penggunaan metoda tergantung ketersediaan data
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 51 Dalam praktis, perhitungan debit banjir dilakukan dengan beberapa metode dan penentuan debit banjir rencana didasarkan pada pertimbangan teknis (engineering judgement). Secara umum, metode perhitungan debit banjir yang sering digunakan adalah metode rasional dan metode hidrograf satuan. Metode analisis debit banjir yang akan dijelaskan adalah metode Rasional. Metode Rasional, umumnya digunakan dalam memperkirakan laju aliran permukaan atau limpasan DAS/lahan dalam perencanaan drainase adalah metode rasional. Metode rasional sangat sederhana dan mudah dalam aplikasinya perhitungannya. Metode rasional digunakan untuk lahan kecil atau < 250 - 300 hektar (Goldman et.al, 1986). DAS kecil digambarkan dengan karakteristik sbb: a) Hujan dapat dianggap terdistribusi merata dari segi waktu dan ruang. b) Durasi hujan biasanya melebihi waktu konsentrasi. c) Limpasan terutama berasal dari aliran permukaan (Overland flow). d) Tampungan saluran dapat diabaikan . Pada DAS kecil respon limpasan dapat dilukiskan menggunakan hubungan paramater yang sederhana, dengan memasukkan semua pengaruh proses hidrologi ke dalam beberapa parameter kunci seperti intensitas hujan dan luas DAS/lahan. Batasan luasan maksimum DAS/lahan kecil sulit untuk ditentukan: a) Tergantung oleh variasi kemiringan DAS /lahan, tumbuhan penutup lahan, dsb. b) Tergantung waktu konsentrasi dan luas DAS /lahan. c) Ada yang menentukan untuk DAS/lahan kecil apabila tc < 1 jam. d) DAS/lahan dikategorikan kecil bila luas DAS/lahan < 250 hektar (2,5 km2). Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh DAS dengan durasi hujan minimum sama dengan waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi (tc) suatu DAS adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke titik outlet setelah tanah menjadi jenuh dan depresi-depresi kecil terpenuhi. Metode Rasional tidak memasukkan proses berikut: a) Variasi waktu dan ruang dari curah hujan efektif. b) Waktu konsentrasi jauh lebih besar dari durasi hujan. c) Sebagian besar aliran mengalir dalam saluran. d) Kondisi kelengasan tanah (AMC). Metode Rasional hanya menghasilkan nilai debit puncak Qp, walaupun bila tidak ada proses difusi, bisa menghasilkan hidrograf berbentuk segitiga sama kaki, dengan tinggi Qp dan lebar dasar 2 tc. Karena merupakan black box model, hubungan antara curah hujan dan aliran permukaan tidak dapat dijelaskan dalam bentuk hidrograf. Secara matematik, besarnya debit puncak aliran permukaan dinyatakan sebagai: Q=0,278 C I A Dimana: Q (m3/dt), I (mm/jam), dan A (km2).
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 52 Gambar 3. 23 Hubungan curah hujan dengan aliran permukaan untuk durasi hujan beda Koefisien limpasan C, didefinisikan sebagai perbandingan antara puncak aliran permukaan thd intensitas hujan. Koefisien limpasan merupakan parameter yang paling menentukan dalam perhitungan debit banjir sehingga pemilihan nilai C yang tepat mutlak memerlukan pengalaman hidrologi yang luas. Faktor yang mempengaruhi nilai C antara lain, kondisi dan sifat tanah (porositas dan derajat kepadatan tanah), laju infiltrasi tanah, persentasi lahan kedap air, kemiringan lahan, tanaman penutup lahan, intensitas hujan, dan kondisi air tanah. Tabel 3. 5 Koefisien limpasan untuk metode Rasional Dilanjutkan….
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 53 Lanjutan….. Tabel 3. 6 Koefisien aliran untuk metode Rasional (dari Hassing, 1995) Jika DAS terdiri atas beberapa jenis tata guna lahan dengan C berbeda, maka nilai koefisien limpasan komposit dapat dihitung dengan persamaan berikut: CDAS = ∑ Ci ⋅ Ai n i=1 ∑ Ai n i=1 Parameter lain yang juga berpengaruh dalam perhitungan debit banjir berdasarkan metode rasional adalah besarnya intensitas curah hujan. Salah satu metode untuk memperkirakan besarnya waktu konsentrasi adalah metode Kirpich (1940) dimana tc (jam), L (km), dan S (m/m). tc = ( 0,87 ⋅ L 2 1000 ⋅ S ) 0,385 = ( 0,066287 ⋅ L 0,77 S 0,385 ) Metode lain yang juga digunakan untuk memperkirakan besarnya waktu konsentrasi adalah metode Hathaway dimana tc (jam), L (km), dan S (m/m). Koefisien n merupakan koefisien kekasaran lahan. tc = ( 0,606 ⋅ (L ⋅ n) 0,467 S 0,234 )
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 54 Tabel 3. 7 Values of roughness factor n Tabel 3. 8 Rumus-rumus waktu konsentrasi Besarnya intensitas curah hujan juga dapat ditentukan berdasarkan waktu pengaliran air di atas lahan (to) dan waktu pengaliran air di dalam saluran (td). to = ( 2 3 ⋅ 3,28 ⋅ L ⋅ n √S ) menit td = Ls 60v menit dimana n : koef Manning, L dan Ls : panjang lintasan aliran di atas lahan dan di dalam saluran (m), v : kecepatan aliran di dalam saluran (m/dt).
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 55 Gambar 3. 24 Rasional method-effect of catchment shape Namun sering kali to dihitung menggunakan rumus tc metode Kirpich. Tabel 3. 9 Effective roughness parameter for overland flow
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 56 Gambar 3. 25 Langkah-langkah rumus Rasional
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 57 Tugas 3: 1. Jelaskan pemahaman anda tentang gambar berikut ini, berikan contoh tempat seperti apa yang pernah anda temui….susun dalam vlog kelompok! Tugas 4: 2. Lengkapi tabel di bawah ini….sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Jawaban merupakan kelompok, tampilkan dalam vlog kelompok!
RAINFALL-RUNOFF BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 58 Tugas 5: 3. Buat eksperimen evaporasi (penguapan air) di rumah masing-masing dengan mengisikan air pada wadah transparan, pagi hari jam 7.00 catat ketinggian air, kemudian sore jam 18.00 catat kembali. Penurunan air di catat dalam tabel, kemudian isi kembali air sampai pada ketinggian tertentu….dan ulangi pengamatan selama 10 hari. Masing-masing individu yang melakukan eksperimen digabungkan dalam kelompok untuk disusun sebagai vlog kelompok. Ungkapkan pula kesan anda akan eksperimen ini. 4. Amati gambar di bawah ini….komponen apakah yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi ini? jawaban individu disatukan dalam vlog kelompok! Selamat bekerja….tinggal di rumah saja…..doaku selalu….
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 59 BAB 4 - STREAMFLOW 4.1 Streamflow Definition Streamflow atau sering dikenal dengan sungai adalah massa air yang secara alami mengalir melalui suatu lembah. Kebanyakan mengalir di permukaan bumi ke tempat yang lebih rendah dan sebagian meresap di bawah permukaan tanah. Alirannya tidak tetap, kadang deras dan kadang lambat, tergantung pada kemiringan sungai. Alirannya mengikuti saluran tertentu yang di kanan kirinya dibatasi tebing yang curam. Air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian besar akan menjadi aliran permukaan dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Aliran permukaan berkumpul dan mengalir ke daerah-daerah yang rendah kemudian menuju parit, selokan, anak-anak sungai, dan sungai. Sungai mengalir dengan kemiringan yang berbeda-beda. Di daerah pegunungan kemiringan sungai cukup curam, sedang di daerah lembah kemiringannya lebih landai dan di daerah dataran kemiringannya hampir rata. Air sungai bersumber dari aliran air permukaan dan air tanah. Air sungai yang melimpah di daerah hilir atau muara berasal dari kumpulan air di daerah hulu yang pada awalnya berupa alur-alur kecil, kemudian membentuk parit, selokan, dan anak-anak sungai. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antara lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi). Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang disekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Pada umumnya setiap aliran sungai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah dan hilir. Menurut Wikipedia, sungai adalah aliran air alami, biasanya air tawar, mengalir menuju samudera, laut, danau atau sungai lain. Dalam beberapa kasus sungai mengalir ke tanah dan menjadi kering di ujungnya tanpa mencapai genangan air lainnya. Sungai-sungai kecil dapat disebut menggunakan nama-nama seperti aliran, anak sungai, sungai kecil, anak sungai. Menurut National Geographic, sungai adalah aliran besar air alami yang mengalir. Sungai ditemukan di setiap benua dan di hampir setiap jenis tanah. Beberapa mengalir sepanjang tahun. Lainnya mengalir secara musiman atau selama bulan-bulan basah. Sebuah sungai mungkin hanya beberapa kilometer panjangnya. Menurut Brierly, 2005., sungai adalah fitur alami dan integritas ekologis, yang berguna bagi ketahanan hidup. Menurut Dinas PU, sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. sedangkan PP No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 60 pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Menurut Hamzah, 2009., sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Menurut Yodi Isnaini, 2006., bantaran sungai berbeda dengan sempadan sungai. Bantaran sungai adalah areal sempadan kiri-kanan sungai yang terkena/terbanjiri luapan air sungai. Fungsi bantaran sungai adalah tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir (high water channel). Menurut UU No. 35 1991 tentang sungai, menyebutkan pengertian bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sehubungan dengan itu maka pada bantaran sungai di larang membuang sampah dan mendirikan bangunan untuk hunian (Polantolo, 2008). Menurut Sobirin, 2003., sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai. Sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah. Di samping itu, sempadan sungai merupakan daerah tata air sungai yang padanya terdapat mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air tanah. Proses inflow outflow tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah pada umumnya. Secara ekologis sempadan sungai merupakan habitat di mana komponen ekologi sungai berkembang Klasifikasi Sungai Sungai dapat diklasifikasikan menurut sumber air, kontinuitas aliran/debit air, pola aliran, arah aliran, dan struktur geologinya. Klasifikasi sungai menurut sumber airnya 1. Sungai Hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan atau sumber mata air. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di pulau Jawa dan Nusa Tenggara. 2. Sungai Gletser, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es. Contoh sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja (ansich) boleh dikatakan tidak ada, namun pada bagian hulu sungai Gangga di India (yang berhulu di Peguungan Himalaya) dan hulu sungai Phein di Jerman (yang berhulu di Pegunungan Alpen) dapat dikatakan sebagai contoh jenis sungai ini. 3. Sungai Campuran, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es (gletser), dari hujan, dan dari sumber mata air. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Digul dan sungai Mamberamo di Papua (Irian Jaya). Gambar 4. 1 Klasifikasi sungai menurut sumber airnya
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 61 Klasifikasi sungai menurut kontinuitas aliran/debit airnya 1. Sungai Permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relative tetap. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito dan Mahakam di Kalimantan. Sungai Musi, Batanghari dan Indragiri di Sumatera. 2. Sungai Periodik, adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. Contoh sungai jenis ini banyak terdapat di pulau Jawa misalnya sungai Bengawan Solo, dan sungai Opak di Jawa Tengah. Sungai Progo dan sungai Code di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sungai Brantas di Jawa Timur. 3. Sungai Episodik, adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kalada di pulau Sumba. 4. Sungai Ephemeral, adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakekatnya sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja pada musim hujan sungai jenis ini airnya belum tentu banyak. Klasifikasi sungai menurut pola alirannya Pola aliran sungai cenderung dipengaruhi oleh adanya bentuk lahan, contohnya di daerah dome, basin, plato, pegunungan lipatan, blok dan lain sebagainya. Arah aliran akan terkontrol oleh bentuk lahan tersebut. Berikut ini beberapa pola aliran sungai: 1. Pola aliran radial/menjari. Pola aliran radial dibedakan menjadi pola radial sentrifugal dan pola aliran radial sentripetal. Radial sentrifugal adalah pola aliran yang meninggalkan pusat, contohnya di daerah vulkan/gunung berbentuk kerucut. Radial sentripetal adalah pola aliran yang menuju pusat, contohnya pada daerah basin/ledokan atau danau (Gambar IV.2). Gambar 4. 2 Pola aliran radial sentrifugal dan sentripetal 2. Pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik adalah pola aliran yang tidak teratur, biasanya terdapat di dataran atau daerah pantai. 3. Pola aliran trellis. Pola aliran trellis merupakan pola aliran sungai yang berbentuk sirip daun atau trellis, biasanya terdapat di daerah pegunungan lipatan.
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 62 4. Pola aliran rectangular. Pola aliran rectangular merupakan pola aliran berbentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku, biasa terdapat di daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda. 5. Pola aliran annular. Pola aliran annular merupakan pola aliran sungai yang melingkar biasanya terdapat di daerah kubah (domes). 6. Pola aliran pinnate. Pola Pinnate adalah aliran sungai yang mana muara anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Sungai ini biasanya terdapat pada bukit yang lerengnya terjal Pola aliran ini dijelaskan lebih rinci seperti pada Gambar IV.3 berikut ini. Gambar 4. 3 Klasifikasi sungai menurut pola alirannya Klasifikasi sungai menurut arah alirannya Arah aliran sungai dikontrol oleh formasi batuan, jenis batuan, jenis tanah, kemiringan lereng yang mengakibatkan adanya belokan atau pelurusan sungai akibat faktor-faktor tersebut. Beberapa jenis sungai berdasarkan arah aliran adalah sebagai berikut: 1. Sungai konsekuen (K) adalah sungai yang mengalir sesuai dengan kemiringan batuan daerah yang dilaluinya, contohnya: Sungai Progo ketika menuruni lereng Gunung Merapi. 2. Sungai subsekuen (S) adalah sungai yang alirannya tegak lurus pada sungai konsekuen dan bermuara pada sungai konsekuen, contohnya Sungai Opak Yogyakarta. 3. Sungai obsekuen (O) adalah sungai yang mengalir berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan daerah tersebut dan merupakan anak sungai subsekuen. 4. Sungai resekuen (R) merupakan anak sungai subsekuen dan alirannya searah/sejajar dengan sungai konsekuen. 5. Sungai insekuen (I) adalah sungai yang alirannya teratur dan tidak terikat dengan lapisan batuan yang dilaluinya Gambar 4. 4 Klasifikasi sungai menurut arah alirannya
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 63 Klasifikasi sungai menurut struktur geologi Berdasarkan struktur geologi, sungai dikontrol oleh adanya perubahan struktur geologi yang terjadi akibat adanya proses geomorfologi berupa patahan, pengangkatan, lipatan, dan proses geomorfologi yang lain. Beberapa jenis sungai yang dikontrol oleh struktur geologi adalah: 1. Sungai anteseden. Sungai anteseden adalah sungai yang dapat mengimbangi pengangkatan daerah lapisan batuan yang dilaluinya sehingga setiap terjadi pengangkatan maka air sungai akan mengikisnya, contohnya adalah Sungai Oyo di Yogyakarta yang mengikis Plato Wonosari. 2. Sungai reverse. Sungai reverse adalah sungai yang tidak dapat mengimbangi adanya pengangkatan, contohnya Sungai Bengawan Solo yang dulunya bermuara di Laut Selatan, sekarang muaranya di Laut Jawa. Berdasarkan struktur geologinya, sungai dapat dibedakan juga menjadi 5: 1. Sungai anteseden. Sungai antiseden adalah sungai yang tetap mempertahankan arah alirannya walaupun ada struktur geologi yang melintang (mampu mengimbangi pengangkatan karena adanya pengikisan di dasar sungai). 2. Sungai superposed. Sungai superposed adalah sungai yang melintang, struktur dan prosesnya ditentukan oleh lapisan batuan yang menutupinya. 3. Sungai reverse. Sungai reverse adalah sungai yang kekuatan erosi ke dalamnya tidak mampu mengimbangi pengangkatan. 4. Sungai komposit. Sungai komposit adalah sungai yang mengalir pada daerah yang berlainan struktur geologinya. 5. Sungai compound. Sungai compound adalah sungai yang membawa air dari daerah yang berlawanan geomorfologinya. Gambar 4. 5 Klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologinya Beberapa jenis genetika sungai antara lain: 1. Sungai Konsekuen. Apabila mengalir searah dengan kemiringan mulai dari daerah Kubah, pegunungan blok yang baru terangkat, dataran pantai terangkat mula-mula memiliki sungai konsekuen. 2. Sungai Subsekuen. Mengalir dan membentuk lembah sepanjang daerah lunak. Disebut juga ’strike stream’ karena mengalir sepanjang jurus lapisan. 3. Sungai Obsekuen. Mengalir berlawanan arah dengan arah kemiringann lapisan dan juga berlawanan dengan arah aliran sungai konsekuen. Biasanya pendek dengan gradient tajam, dan merupakan sungai musiman yang mengalir pada gawir. Umumnya merupkan cabang dari sungai subsekuen. 4. Sungai Resekuen. Mengalir searah dengan sungai konsekuen dan searah dengan kemiringan lapisan.
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 64 5. Sungai Insekuen. Merupakan sungai yang tidak jelas pengendaliannya tidak mengikuti struktur batuan, dan tidak jelas mengikuti kemiringan lapisan. Pola alirannya umumnya dendritik. Banyak menyangkut sungai – sungai kecil. 6. Sungai Superimpos. Merupakan sungai yang mula – mula mengalir diatas suatu daratan aluvial atau dataran peneplain, dengan lapisan tipis yang menutupinya sehingga sehingga lapisan dibawahnya tersembunyi. Jika terdapat rejuvenasi maka sungai tersebut kemudian mengikis perlahan-lahan endapan aluvial atau lapisan penutup tersebut dan menyingkapkan lapisan tanpa mengubah banyak pola aliran semula. 7. Sungai Asteseden. Sungai yang mengalir tetap pada pola alirannya meskipun selama itu terjadi perubahan – perubahan struktur misalnya sesar, lipatan,. Ini dapat terjadi jika struktur terbentuk atau terjadi perlahan – lahan. 8. Anaklinal dipergunakan untuk sungai anteseden didaerah yang mengalami pengangkatan sedemikian sehingga kemiringannya berlawanan dengan arah aliran sungai. 9. Compound Streams mengairi daerah dengan umur geomorfik yang berbedabeda, ‘compound streams’ mengairi daerah dengan struktur geologi yang berlainan. Banyak sungai-sungai besar dapat dimasukan kedalam compound ataupun comporite streams misalnya sungai Bengawan solo, Citarum, Asahan, dan sebagainya. Gambar 4. 6 Gambar penampang jenis genetika sungai: C (konsekuen), S (subsekuen), O (obsekuen), R (resekuen) 4.2. Streamflow Measurement Aliran air diukur sebagai jumlah air yang melewati titik tertentu dari waktu ke waktu. Unit yang digunakan di Amerika Serikat adalah kaki kubik per detik (ft3/s), sedangkan di sebagian besar negara lain digunakan meter kubik per detik (m3/det). Satu ft3 sama dengan 0,028 m3. Ada berbagai cara untuk mengukur debit aliran atau kanal. Pengukur aliran memberikan aliran terus menerus dari waktu ke waktu di satu lokasi untuk pengelolaan sumber daya air dan lingkungan atau tujuan lain. Nilai aliran adalah indikator yang lebih baik daripada mengukur kondisi ketinggian sepanjang sungai. Pengukuran aliran dilakukan setiap enam minggu oleh personel United States Geological Survey (USGS). Mereka menyeberang ke sungai untuk melakukan pengukuran atau melakukannya dari perahu, jembatan, atau kereta gantung di atas sungai. Untuk setiap stasiun pengaliran, hubungan antara tinggi pengukur dan aliran ditentukan oleh pengukuran simultan dari ketinggian pengukur dan aliran di atas rentang alami aliran (dari aliran yang sangat rendah ke banjir). Relasi ini menyediakan data kondisi arus dari stasiun itu. Untuk tujuan yang tidak memerlukan pengukuran aliran terus menerus, dapat digunakan alat meter arus atau profiler kecepatan
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 65 Doppler akustik. Untuk aliran kecil - lebar beberapa meter atau lebih kecil – dapat dipasang bendung untuk pengukurannya. Pengukuran dari aliran permukaan misalnya suatu sungai atau saluran dapat berupa pengukuran tinggi muka air dan kecepatan aliran. Dari kedua pengukuran tersebut dapat ditaksir besarnya debit aliran yang mengikuti hubungan: Q = f (H, S) ………………………………………………………………. (4.1) dimana: Q = debit H = kedalaman air S = kemiringan dasar saluran Untuk memberikan gambaran dipakai persamaan yang umum dipakai yaitu persamaan Chezy ataupun Manning Menurut Chezy → Q = A ∙ C ∙ √RS …………………………………………………………………… (4.2) dimana: Q = debit A = luas penampang basah C = koefisien kekasaran Chezy R = jari-jari hidrolis = A/O O = keliling basah S = kemiringan dasar saluran Dalam persamaan Manning → C = R 1 6 n ……………………………………………………………………. (4.3) dimana: n = koefisien kekasaran Manning Untuk kasus saluran yang lebar, dianggap bahwa jari-jari hidrolis: R adalah mendekati kedalaman rata-rata penampang saluran: D, dalam persamaan: A = K ∙ D m …………………………………………………………………………………….. (4.4) dimana: K = konstanta m = eksponen Maka rumus Chezy dapat dituliskan sebagai: Q = k ⋅ D n ⋅ √S ……………………………….… (4.5) dimana: n = m + 0.5 k = K.C Persamaan di atas memperlihatkan bahwa untuk kedalaman yang konstan pada suatu penampang, debit akan lebih tinggi daripada aliran normal ketika kemiringan permukaan air melebihi kemiringan dasar saluran. Sebaliknya, debit
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 66 akan berkurang dari aliran normal ketika kemiringan permukaan air dibawah kemiringan dasar saluran. Salah satu metode informal yang memberikan perkiraan aliran yang disebut Metode Orange atau Metode Float yaitu: Ukur panjang aliran, dan tandai titik awal dan akhir. Tempatkan benda yang dapat mengapung di titik awal dan ukur waktu untuk mencapai titik akhir dengan stopwatch. Ulangi pengukuran ini minimal tiga kali dan buatlah ratarata waktu pengukuran. Kecepatan dalam meter per detik adalah panjang dibagi dengan waktu. Jika pengukuran dilakukan pada midstream (kecepatan maksimum), kecepatan aliran rata-rata adalah sekitar 0,8 dari kecepatan yang diukur untuk kondisi dasar yang kasar (berbatu) dan 0,9 dari kecepatan yang diukur untuk kondisi dasar yang halus (lumpur, pasir, lapisan dasar). 4.3. Streamflow Analysis Analisis aliran, pada dasarnya merupakan suatu analisis untuk menemukan atau menaksir besarnya debit aliran. Beberapa metode penaksiran debit, akan dijelaskan sebagai berikut. Penaksiran dari debit aliran Untuk mengetahui fluktuasi debit diperlukan pencatatan tinggi muka air secara terus menerus dan diikuti pula dengan pengukuran kecepatan aliran. Pencatat tinggi muka air dibedakan 2 macam: a. Papan duga air biasa (staff gauge) b. Papan duga air otomatis (automatic water level recorder) Gambar 4. 7 Alat ukur papan duga air Gambar 4. 8 Alat ukur papan duga air otomatis (AWLR)
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 67 Gambar 4. 9 Pemasangan AWLR Pengukuran kedalaman air Pengukuran kedalaman air dapat dilakukan pula dengan menggunakan tali yang diberi pemberat (wading rod) untuk kedalaman yang dangkal atau “hand line” untuk yang dalam (dengan pemberat yang berbunyi). Kedalaman yang terukur perlu dikoreksi karena pengaruh kemiringan maupun akibat tali yang terendam air seperti dalam gambar berikut: Kedalaman yang terukur: AE – AB akibat kemiringan → air line correction akibat rendaman air → wet line correction Tabel 4. 1 Wet line correction, W (%) untuk sudut W W W W 4 0.06 12 0.72 20 2.04 28 4.08 6 0.16 14 0.98 22 2.48 30 4.72 8 0.32 16 1.28 24 2.96 10 0.50 18 1.64 26 3.50 A B C D F d E Gambar 4. 10 Alat pengukur kedalaman air
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 68 Contoh: Survey untuk mengukur kedalaman dilakukan dari sebuat jembatan terletak 6.3 m di atas permukaan air dengan menggunakan sebuah “hand – line and sounding weight”. Kemiringan tali: diukur sama dengan 10O. Tali terukur sepanjang 17.4 m sebelum pemberat yang berbunyi menyentuh dasar. Tentukan kedalaman air yang sesungguhnya! Lihat gambar → AB = 6.3 m = 10O air line correction: AD – AC = CD = 6.3 (sec - 1) = 0.097 m kedalaman observasi: DE = 17.4 – 6.397 = 11.003 m untuk = 10O → tabel wet line correction: W = 0.5 % jadi kedalaman air yang sesungguhnya: d = DE . (1 – 0.5%) = 11.003 . (1 – 0.005) = 10.948 m Pengukuran kecepatan aliran: Pengukuran kecepatan aliran dapat dilakukan dalam 2 cara: a. Pelampung dan pencatat waktu b. Alat ukur arus (current meter) → ada 2 macam: cup – type propeller – type Gambar 4. 11 Alat Pengukur Kecepatan Aliran Kecepatan aliran dihitung berdasarkan jumlah putaran dari persamaan: V = a.n + b …….(4.6) dimana: a, b = konstanta standart n = jumlah putaran tiap satuan waktu (menit) V = kecepatan aliran Gambar 4. 12 Lokasi pengukuran current meter Cup type Propeller type
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 69 Perhitungan debit Perhitungan debit dapat dilakukan dengan membagi penampang dalam segmensegmen yang diikuti dengan pengukuran kedalaman air dan kecepatan aliran. gambar a gambar b Gambar 4. 13 Segmen dalam penampang sungai Ada 2 metode yaitu: a. “mean section method” (gambar a) → tiap segment bentuknya mendekati trapesium, maka perhitungan debit didapat dari persamaan: Q = ∑ q = ∑ Un−1+Un 2 ⋅ dn−1+dn 2 ⋅ (bn−1 − bn ) N−1 n−1 ………………..……………… (4.7) dimana: b = jarak dari tepi d = kedalaman U = kecepatan aliran b. “mid section method” (gambar b) → perhitungan debit didapat dari persamaan: Q = ∑ q = ∑ Un ⋅ dn ⋅ bn+1+bn−1 2 N−1 n−1 ………………………………………………… (4.8) Contoh: Tabel berikut memberikan detail dari pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan current meter. Perkirakan debit yang ada dengan menggunakan “mid section method” Tabel 4. 2 Pengukuran kecepatan Jarak Kedalaman Kec. Jarak Kedalaman Kec. Jarak Kedalaman Kec. 4 0 0 19 1.34 0.344 34 1.28 0.256 9 0.87 0.223 24 1.67 0.356 39 0.89 0.174 14 1.12 0.287 29 1.78 0.389 44 0 0 Perhitungan dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut: Tabel 4. 3 Perhitungan Besarnya Kecepatan Jarak m Lebar: b m Kedalaman:d m Kecepatan: U m/det U . d M2/det b . d . U m3/det 4 0 0 0 0 0 9 5 0.87 0.223 0.194 0.970 14 5 1.12 0.287 0.321 1.605 19 5 1.34 0.344 0.461 2.305 24 5 1.67 0.356 0.595 2.975 29 5 1.78 0.389 0.692 3.460 34 5 1.28 0.256 0.328 1.640
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 70 39 5 0.89 0.174 0.155 0.774 44 0 0 0 0 0 Q = 13.729 Selain dari pada metode di atas, pengukuran debit dapat juga dilakukan dengan membangun bangunan pengukur debit seperti: bendung, cipolleti dan sebagainya. Besarnya debit dapat dicari juga dengan menggunakan “chemical dilution gauging” Suatu cairan kimia yang berwarna diteteskan dalam frekuensi tertentu ke atas permukaan air yang mengalir. Cairan berwarna tersebut akan mengalir sesuai dengan kecepatan aliran permukaan air. Lokasi cairan berwarna sampai pada pengamatan pencatatan waktu mempunyai jarak yang tertentu. Dari waktu perjalanan cairan berwarna sampai jarak tertentu tersebut dicatat. Kecepatan aliran adalah jarak dibagi dengan waktu yang ditempuh.
STREAMFLOW BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 71 Tugas 6: 1. Jelaskan ulang secara skematik: definisi, klasifikasi jenis-jenis aliran air atau sungai (tugas individual) 2. Lakukan eksperimen pengukuran debit suatu aliran (sungai atau selokan yang mengalir di sekitar anda) dengan berbagai metode seperti dijelaskan dalam materi bab 4 ini (tugas kelompok dengan menampilkannya dalam vlog atau presentasi)
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 72 BAB 5 – HYDROLOGY STATISTIC Semua proyek direncanakan untuk keperluan masa mendatang, yang ada saat perencanaan dibuat tidak diketahui secara pasti keadaan yang sebenarnya pada waktu proyek tersebut dioperasikan. Seorang perencana bangunan air lebih merasa tidak pasti lagi mengenai berapa besar debit yang harus diperhitungkan untuk keperluan penyediaan air minum atau untuk irigasi dan ia juga harus memperkirakan berapa besar debit banjir untuk menentukan ukuran bangunan air tersebut. Untuk mengatasi ketidak pastian dalam perencanaan ini biasanya diterapkan ilmu statistik untuk menentukan debit andalan (dependable discharge) dan debit perencanaan (design discharge). Perhitungan hujan berpeluang maksimum (probable maximum precipitiation = PMP) juga termasuk dalam kategori ini. 5.1. Beberapa Konsep Statistik Dasar-dasar ilmu statistik yang diperlukan untuk menganalisa data-data hidrologi antara lain: mean atau rata-rata, standart deviasi dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan: Data → perlu dicek: stationary or non-stationary inconsistency dengan menggunakan non homogeneity screening procedure Jika OK → dilakukan analisa frekuensi yaitu probabilitasnya dan estimasinya 5.2. Data Screening Gambar V.1. diagram alir di bawah ini menunjukkan prosedur dari penyaringan data yang disarankan oleh Dahmen and Hall (1990). Mengikuti suatu penyaringan secara kasar dari observasi harian, jumlah biasanya dihitung dalam tahun musim (water year). Data kemudian diadakan inspeksi secara visual dimana mungkin membutuhkan beberapa petunjuk seperti dimana “time series”nya mungkin akan dipisahkan untuk aplikasi dari pencatatan yang terpisah dalam prosedur selanjutnya.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 73 Gambar 5. 1 Diagram alir penyaringan data
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 74 Contoh aplikasi dari test individu: Serial data dari maksimum permukaan air tahunan pada sungai Chao Phraya di Bang Sai Thailand untuk tahun musim 1995 – 1974 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Plotkan data dan adakan suatu inspeksi visual. Tabel 5. 1 Serial data maksimum permukaan air tahunan Tahun Level, m Tahun Level, m Tahun Level, m Tahun Level, m 1 2.49 6 2.3 11 1.88 16 3.16 2 2.8 7 3.14 12 2.54 17 1.78 3 2.78 8 3.2 13 1.98 18 1.76 4 1.95 9 2.92 14 1.42 19 2.04 5 3.29 10 3.51 15 2.63 20 2.31 Jawab: Plot data: Gambar 5. 2 Plot data pada kertas grafik Nilai maksimum dari seluruh periode terjadi pada tahun ke-10 sebesar 3.51 m. Nilai yang melebihi level 3.0 m dari 10 data berikutnya setelah 10 tahun pertama hanya satu yaitu 3.16 m. Dari sini dapat dilihat suatu indikasi bahwa sesuatu telah terjadi sekitar tahun 1965. 5.3. Hydrology Data Analysis Pengolahan data dilakukan untuk menemukan suatu kemungkinan terlampaui 20 % (tahun basah), terlampaui 50 % (tahun normal) dan terlampaui 80 % (tahun kering). Pemrosesan curah hujan tahunan kemungkinan terlampaui 20 %, 50 %, 80 % menggunakan nilai probabilitas berdasarkan persamaan sebagai berikut: Fa = 100 ∙ m N+1 dimana: N = jumlah data yang tercatat m = nomer urutan ranking Fa = ploting posisi Nilai kemungkinan terlampaui 20 %, 50 %, 80 % dapat diplotkan pada kertas grafik log-normal seperti yang tertera pada grafik. 0 1 2 3 4
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 75 Cara “Plotting Position” data curah hujan adalah sebagai berikut: a. Masukan nilai curah hujan pada tabel yang tersedia . b. Jumlahkan nilai curah hujan untuk satu tahun. c. Hitung nilai probabilitas sesuai formula Fa = 100 ∙ m N+1 d. Urut nilai curah hujan tahunan dari yang besar sampai yang terkecil.. e. Masukan dalam grafik data probabilitas dan data curah hujan tahunan pada poin d, di mana data probabilitas pada sumbu X dan data curah hujan tahunan pada sumbu Y. f. Skalakan sumbu X dengan logaritma. g. Tarik garis ploting potitionnya. h. Catat jumlah nilai curah hujan tahunan terlampaui 20 %, 50 %, 80 %. i. Lanjutkan perhitungan nilai curah hujan pada tahun basah, tahun normal dan tahun kering. Besarnya nilai curah hujan bulanan dhitung dengan menggunakan persamaan : a. Bulan kering: Pidry = Piav ∙ Pdry Pav b. Bulan normal: Pinor = Piav ∙ Pnor Pav c. Bulan basah: Piwet = Piav ∙ Pwet Pav Tugas 7 "PLOTTING POSITION" DATA CURAH HUJAN STA.NAIBONAT - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 100,00 10,00 1,00 PLOTTING POSITION TOTAL CURAH HUJAN TAHUNAN P20 = 2775 mm P50 = 2075 mm P80 = 1600 mm Prata = 2131 mm Gambar 5. 3 Grafik plotting position
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 76 Buatlah analisis hidrologi untuk data iklim berikut ini: Plotting JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES Posisi 1 1989 252,5 189,5 465,0 199,5 63,0 101,5 44,0 0,0 7,5 51,0 110,0 126,0 1609,5 4,7619 2684 2 1991 263,0 572,0 41,5 228,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 197,0 1317,5 9,5238 2430 3 1992 257,0 123,0 255,3 105,0 106,5 0,0 0,0 13,0 9,0 46,0 72,0 224,0 1210,8 14,286 2402 4 1993 515,0 246,0 165,0 168,0 22,0 25,5 6,0 0,0 0,0 0,0 122,0 283,0 1552,5 19,048 2382 5 1994 332,0 514,0 348,0 53,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 411,6 1719,6 23,81 2236 6 1999 302,0 505,0 248,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 253,0 397,0 2130,0 28,571 2130 7 2000 489,0 146,0 377,0 401,3 254,0 0,0 0,0 16,0 0,0 15,0 386,0 298,0 2382,3 33,333 2093 8 2001 318,0 260,0 368,0 253,0 0,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309,0 325,0 2000,0 42,857 2058 9 2003 318,0 266,0 368,0 254,0 0,0 167,0 0,0 0,0 17,0 29,0 71,0 299,0 1789,0 42,857 2000 10 2004 367,0 386,0 590,0 0,0 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 28,0 90,0 325,0 1886,0 47,619 1956 11 2005 238,0 558,2 256,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,0 198,0 348,0 1956,2 52,381 1886 12 2010 330,0 233,0 122,0 369,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 409,0 225,0 226,0 2093,0 57,143 1855 13 2011 657,0 344,0 401,0 399,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0 122,0 303,0 2430,0 61,905 1852 14 2012 307,0 308,0 328,0 85,0 185,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,5 75,0 431,0 1737,5 66,667 1794 15 2013 556,0 553,0 225,0 115,0 189,0 254,0 24,0 0,0 0,0 54,0 183,0 531,0 2684,0 71,429 1738 16 2014 483,0 633,0 350,0 231,0 62,0 12,0 25,0 0,0 0,0 0,0 31,0 409,0 2236,0 76,19 1720 17 2015 700,0 284,5 253,0 346,0 12,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 190,0 1851,5 80,952 1610 18 2016 329,0 302,0 204,0 67,0 211,0 60,0 15,0 0,0 173,0 46,5 262,0 388,0 2057,5 85,714 1553 19 2017 378,0 625,0 403,0 189,0 14,0 2,0 0,0 0,0 13,0 48,5 229,0 500,0 2401,5 90,476 1318 20 2018 564,0 342,0 202,0 130,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,4 292,0 318,0 1855,4 95,238 1211 Rerata 397,8 369,5 298,5 206,7 74,1 41,1 5,7 2,3 11,4 57,0 154,4 326,5 1945,0 NO TAHUN Jumlah Ranking BULAN
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 77 Bantuan perhitungan dengan excel terlampir! Pdry 1600 P80 Pwet 2300 P20 Pnor 1950 P50 Pav 1945 Pav JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Total Pidry 327 304 246 170 61 34 5 2 9 47 127 269 1600 Piwet 470 437 353 244 88 49 7 3 14 67 183 386 2300 Pinor 399 370 299 207 74 41 6 2 11 57 155 327 1950 av dry i dry i av P P P = P av nor i nor i av P P P = P av wet iwet i av P P P = P
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 78 BAB 6 - HYDROGRAPH 6.1. Development of Hydrograph Relations Presipitasi atau hujan yang tidak ditangkap (diintersepsi) oleh tanaman atau bangunanbangunan lain di atas bumi, dapat menguap (evaporation), meresap (infiltration) atau menempati suatu tampungan (depression storage). Kelebihan air hujan ini mengikuti hukum gravitasi mengalir di atas permukaan bumi menuju saluran air (stream chanel) terdekat. Arus air dalam aliran menuju sungai dan aliran sungai akan berakhir di laut (muara sungai). Bila hujan yang jatuh deras dan atau lama, maka kelebihan limpasan permukaan menjadi lebih besar, saluran-saluran dan sungai tidak dapat menampung seluruh air yang datang, tetapi saluran hanya terisi penuh maka akan terjadi luapan air. Hal ini mendatangkan kerugian pada aktivitas manusia, terutama: 1. Terjadinya erosi (terbawanya lapisan tanah bagian atas yang subur), merusak tanaman. 2. Terjadinya kerusakan pada daerah perkotaan, daerah irigasi, terjadinya polusi pada persediaan air, membahayakan jiwa manusia. 3. Terputusnya hubungan antar daerah, serta dapat menyebabkan kelaparan. Masalah yang berhubungan dengan limpasan ini dapat diatasi dengan melakukan tindakan atau pendekatan awal yaitu: menganalisa atau memberi jawaban terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan antara lain: 1. Seberapa sering banjir akan terjadi 2. Beberapa besar banjir yang akan terjadi 3. Beberapa sering musim kering (drought) akan terjadi 4. Berapa lama musim kering akan berlangsung. Masalah-masalah di atas dapat dijawab dengan: 1. Membuat grafik hubungan antara frequensi dan duration dari debit limpasan-limpasan extreem selama pengamatan jangka panjang, walaupun beberapa pengamatan tidak tersedia, maka pendekatan harus tetap dilakukan dengan berbagai kemungkina atau probabilitas. 2. Membuat grafik-grafik hubungan lain, misalnya rating curve, grafik hubungan hujan dan limpasan dan lain sebagainya. 3. Meramalkan debit banjir berdasarkan rumus empiris yang tersedia. 4. Mempelajari debit air rendah, debit rata-rata, dan lain-lain. Di dalam melakukan analisa data hidrologi di atas, diperlukan pula: 1. Menentukan debit limpasan suatu sungai, bila tinggi M.A. (muka air) banjir diketahui, dengan melakukan pengukuran limpasan jangka panjang. 2. Menentukan cara untuk dapat memperkecil volume limpasan. 3. Membandingkan biaya pencegahan banjir terhadap kerusakan yang akan timbul bila tidak dilakukan pencegahan ini. 4. Menentukan nilai (penting atau tidaknya) penyimpanan air banjir sebagai persediaan air musim kemarau dalam waduk.
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 79 Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan 1. Elemen meteorologi, meliputi: a) Jenis presipitasi: salju dan hujan b) Intensitas curah hujan. Bila intensitas curah hujan > kapasitas infiltrasi, maka limpasan permukaan besar. Peningkatan curah hujan tidak sebanding dengan peningkatan limpasan, karena efek penggenangan di permukaan tanah c) Lamanya curah hujan. Makin lama duration hujan, makin besar limpasan, karena menurunnya kapasitas infiltrasi d) Distribusi curah hujan dalam D.A.S. (persentasi daerah yang mengalami hujan terhadap D.A.S.) e) Curah hujan sebelumnya dan kelembaban tanah (soil moisture). Bila kandungan kelembaban tanah >>, kapasitas infiltrasi <<, maka limpasan menjadi besar. f) Kondisi-kondisi meteorologi lainnya. 2. Elemen D.A.S.: a) Kondisi permukaan tanah (landuse) karena tanaman memperbesar intersepsi, infiltrasi, soil moisture sehingga limpasan kecil b) Kondisi topografi dan bentuk D.A.S. akan mempengaruhi volume air yang tertampung dalam saluran, di samping kemiringan memperkecil infiltrasi c) Jenis tanah menentukan kapasitas infiltasi d) Faktor-faktor lain misal karakteristik jaringan sungai Pengertian dasar hidrograf limpasan Beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait dengan pengertian dasar hidrograf limpasan: 1 Limpasan (run-off). Adalah semua air yang mengalir Iewat satu sungai bergerak meninggalkan daerah tangkap sungai (D.A.S.) tersebut tanpa memperhatikan asal atau jalan yang ditempuh sebelum mencapai saluran (surface atau subsurface). Karena terjadinya air limpasan ini merupakan gabungan dari aliran air permukaan (surface flow) dan aliran tanah pada waktu m.a. tanah tinggi, atau merupakan gabungan dari aliran air permukaan dan aliran bawah permukaan (sub surface flow) pada waktu m.a. tanah rendah. Limpasan ini diukur pada tempat-tempat di sepanjang saluran dengan alat pengukur yang disebut stream gauging station (stasiun pengamat aliran air). 2 Limpasan permukaan (surface run off atau direct run off). Adalah limpasan yang selalu mengalir melalui permukaan (sebelum dan sesudah mencapai saluran). 3 Aliran dasar (base-flow). Adalah debit/limpasan minimum yang masih ada, karena adanya aliran keluaran/lepasan (Out Flow/Discharge) dari akifer. 4 Debit aliran (discharge of flow = Q). Q adalah volume air yang melalui suatu penampang saluran (sungai, pipa, goronggorong) persatuan waktu. 5 Lipasan bulanan (monthly run-off = V). V adalah Volume limpasan selama satu bulan tertentu. Volume ini dapat dinyatakan dalam satuan tinggi (depth) = = = ∫ ∙ Dengan A = Luas daerah pengaliran, sehingga dengan satuan volume dapat membandingkan nilai run off terhadap nilai presipitasi dan evaporasi, infiltrasi dan kelembaban tanah. 6 Limpasan tahunan (anual run-off). V adalah Volume limpasan selama satu tahun tertentu: = = ∫ ∙
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 80 7 Limpasan bulanan atau tahunan rata-rata (mean monthly/annual run off). Nilai rata limpasan bulanan atau limpasan tahunan selama pengamatan jangka panjang. 8 Debit banjir (= peak discharge). Debit limpasan, pada saat air banjir (M.A. melebihi keadaan normal). Tinggi muka air pada saluran. Didefinisikan sebagai elevasi M.A. yang diukur relative terhadap suatu bidang datum horizontal tertentu (bench mark). Bench mark (titik tetap) yang lazim dipakai adalah patok-patok yang dipasang di pantai dan tingginya sudah tertentu terhadap tinggi muka air laut. Misal: a) Bench mark untuk Jabar adalah Peil Periok. b) Bench mark untuk Jatim adalah Peil Tanjung Perak dan lain sebagainya. 9 Hidrograph (hydrograph) adalah: grafik hubungan antara waktu atau duration dengan unsur-unsur aliran (tinggi M.A. atau Debit) Hubungan waktu (t) dan tinggi M.A. (H) disebut hidrograf muka air (stage hydrograph) Gambar 6. 1 Hidrograf muka air Hubungan waktu (t) dan Debit (Q) disebut hidrograf debit (discharge hydrograph). Gambar 6. 2 Hidrograf debit 10 Periode Pemusatan (time of concentration) = Tc, adalah waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir dari titik terjauh dalam suatu D.A.S. sampai di stasiun pengukuran tertentu. t H
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 81 11 Kurva/garis massa (mass curve) adalah: penyajian secara grafis aliran kumulatif terhadap fungsi waktu. 12 Hujan Effektif (Effective Precipitation): adalah sebagian dari total presipitasi, yang sesungguhnya terdistribusi di permukaan bumi. 13 Lengkung aliran (rating curve). Adalah grafik hubungan antara elevasi M.A. suatu sungai atau saluran terhadap debitnya pada salah satu penampang sungai. Gambar 6. 3 Grafik lengkung aliran 14 Hidrometri: didefinikan secara umum sebagai ilmu untuk mengukur air atau ilmu untuk mengumpulkan data dasar bagi analisis hidrologi. Komponen dari metode hidrograf dijelaskan seperti dalam Gambar VI.4. berikut ini. Gambar 6. 4 Komponen dari metode hidrograf Langkah-langkah untuk mengembangkan dan menerapkan metode hidrograf dijelaskan seperti pada Gambar VI.5 berikut ini.
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 82 Gambar 6. 5 Langkah-langkah dalam pengembangan dan penerapan metode hidrograf Hidrograf didefinisikan sebagai hubungan antara salah satu unsur aliran terhadap waktu, seperti disebut sebagai hidrograf muka air dan hidrograf debit aliran. Dalam praktis yang umumnya disebut sebagai hidrograf adalah hidrograf debit aliran. Hidrograf debit terdiri atas komponen aliran permukaan, dan baseflow terhadap waktu. Hidrograf aliran langsung (DRO) diperoleh dengan memisahkan hidrograf dari baseflow. Ada 3 metode dalam pengembangannya (Gambar VI.6): 1 Metode Garis Lurus Garis lurus ditarik dari titik terendah resesi hidrograf (A) sampai titik di sisi hidrograf yang ditinjau (B). Titik B merupakan titik penyimpangan terendah garis tersebut thd garis lurus yang dianggap mewakili saat terjadinya baseflow. 2 Metode Panjang Dasar Tetap Dalam metode ini diperhatikan adanya perbedaan kecepatan respon antara air permukaan dan air bawah permukaan. Pada saat air permukaan naik, aliran dasar turun sampai dianggap mencapai titik terendah di bawah puncak aliran permukaan. 3 Metode Kemiringan Berbeda Metode ini merupakan gabungan dari kedua metode sebelumnya. Penentuan aliran dasar antara titik A dan C relatif lebih sulit.
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 83 Gambar 6. 6 Metode pengembangan hidrograf 6.2. Unit Hydrograph Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung yang dihasilkan oleh hujan efektif yang terjadi merata di seluruh DAS dengan intensitas sama selama satuan waktu tertentu (hujan satuan = 1 cm). Hidrograf satuan digunakan untuk memperkirakan hubungan antara hujan efektif dan aliran permukaan. Sherman (1932) menyatakan bahwa suatu sistem DAS memiliki sifat khas yang menyatakan respon DAS terhadap suatu masukan tertentu berdasarkan 3 prinsip dasar: 1. Pada hujan efektif berintensitas seragam pada suatu daerah aliran tertentu, intensitas hujan yang berbeda tetapi memiliki durasi yang sama, akan menghasilkan limpasan dengan durasi yang sama meskipun jumlahnya berbeda. 2. Pada hujan efektif berintensitas seragam pada suatu DAS tertentu, intensitas hujan yang berbeda tetapi memiliki durasi sama, akan menghasilkan hidrograf limpasan dimana ordinatnya pada sembarang waktu memiliki proporsi yang sama dengan proporsi intensitas hujan efektifnya. 3. Prinsip superposisi pada hidrograf yang dihasilkan oleh hujan efektif berintensitas seragam yang memiliki periode-periode yang berdekatan dan/atau tersendiri. Ketiga asumsi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa tanggapan atau respon DAS terhadap hujan adalah linier, walaupun sebenarnya kurang tepat. Namun demikian, penggunaan hidrograf satuan telah banyak memberikan hasil yang memuaskan untuk berbagai kondisi.
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 84 Gambar 6. 7 Respon DAS terhadap masukan hujan efektif Dengan diperolehnya hidrograf satuan, besarnya limpasan permukaan untuk sembarang hujan badai dapat diperkirakan melalui proses konvolusi (Gambar VI.8). Gambar 6. 8 Pemakaian proses konvolusi pada hidrograf satuan
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 85 Tabel 6. 1 Tabulasi dan metode matriks untuk konvolusi Tabel 6. 2 Bentuk umum persamaan konvolusi hidrograf satuan Persamaan konvolusi hidrograf satuan (n=1,2,….,N; N = jumlah pulsa debit, m = 1,2,3,…..,m; m = jumlah hyetograf hujan efektif) Tabel 6. 3 Hyetograf hujan efektif dan hidrograf limpasan permukaan