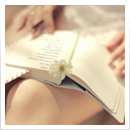ISLANDS HYDROLOGY BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 136 Kondisi geografi sangat menentukan karakteristik iklim suatu wilayah, khususnya karakteristik dari hujan yang meliputi durasi, intensitas, dan sebaran hujan selama musim hujan. Karakteristik hujan ini dapat berupa durasi hujan yang singkat tetapi intensitasnya tinggi, curah hujan tahunan yang rendah, dan lama musim hujan yang berlangsung hanya beberapa bulan saja, dengan kemarau panjang. Kondisi topografi yang terjal, berpotensi menimbulkan limpasan permukaan yang besar, dimana air limpasan permukaan langsung mengalir terbuang ke laut – tidak sempat meresap ke dalam tanah sebagai air tanah, dan akan menimbulkan bencana banjir. Di lain pihak, topografi yang landai dengan intensitas hujan tinggi, berpotensi menimbulkan situasi waterlogging, yaitu kondisi dimana tanah sangat jenuh air, yang akan mengakibatkan produksi tanaman menurun atau bahkan mati. Curah hujan tahunan yang rendah dengan lama musim hujan yang singkat beberapa bulan saja dan kemarau yang panjang, berpotensi menimbulkan situasi kekeringan yang panjang, terbatasnya ketersediaan sumber daya air, yang akan menimbulkan bencana alam kekeringan. Sebaran hujan selama musim hujan, berupa jumlah hari kejadian hujan dengan durasi dan intensitasnya, berpotensi menimbulkan kejadian waterlogging, ataupun kejadian dry spells, yaitu situasi kekeringan singkat dalam musim hujan karena jangka waktu tidak turunnya hujan yang cukup lama, yang akan mengakibatkan turunnya produksi tanaman atau bahkan mati (Susilawati, 1999, Falkenmark et.al, 2001). Kondisi fisik pulau-pulau kecil di kawasan kering mempunyai ciri khas ketersediaan air yang terbatas, sumber daya alam yang rawan, terancam bencana perubahan iklim maupun naiknya permukaan air laut, terisolir secara geografis, transportasi dan komunikasi yang terbatas, serta daerah pantai yang terancam polusi. Air hujan merupakan sumber utama air tawar tetapi singkat dan terbatas sehingga beresiko terjadinya kekeringan yang panjang. Pertanian yang mengandalkan air hujan beresiko mengalami kekeringan dalam musim hujan (dryspell) ataupun kejenuhan (waterlogging) karena karakteristik hujan yang spesifik (Susilawati, 2011). 9.2. The Challenges and The Opportunities of Islands Hydrology Beberapa masalah yang menjadi tantangan antara lain: 1. Karakteristik hidrologi yang menimbulkan masalah terkait dengan topografi wilayah, berpengaruh pada sistem hidrologi sungai atau alur drainase alam yang ada. Keadaan ini menyebabkan air hujan yang jatuh cepat melimpas terbuang ke laut, dan hanya sebagian kecil yang meresap ke dalam tanah (Susilawati, 2006). Kombinasi antara situasi topografi dan geologi, akan memunculkan masalah erosi dan sedimentasi, banjir dan kekeringan, yang berkaitan erat dengan usaha konservasi tanah dan air. 2. Pulau-pulau kecil secara umum mempunyai karakter geografis yang terisolir dari wilayah lain, sehingga menimbulkan situasi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan. Hal ini nampak dengan jelas sebagai akibat dari terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi. Keterbatasan ini berakibat pada sistem lembaga pemerintah, interaksi sosial masyarakat, dan perkembangan ekonomi. Peningkatan potensi sosial ekonomi akhirnya bermuara pada masalah pengembangan sumber daya air, khususnya air hujan, agar dapat memberikan kepastian cukupnya kelembaban tanah bagi tanaman untuk mencapai produksi yang optimal. Peningkatan kegiatan sosial ekonomi berpengaruh pula pada kualitas air untuk kehidupan, yaitu bahaya menyusupnya air laut karena pengambilan sumber air tanah yang tak terkendali, maupun polusi air buangan/limbah dari kegiatan tersebut. 3. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki pulau-pulau kecil tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Pulau pulau kecil tidak hanya memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan yang salah satu faktornya disebabkan karena pengelolaan yang salah dan tidak bijaksana tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Keunggulan yang dimiliki pulau-
ISLANDS HYDROLOGY BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 137 pulau kecil berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional, antara lain perikanan, pemukiman, pelabuhan, dan pariwisata. Pembangunan di beberapa sektor tersebut menjadi potensi besar sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan pulau-pulau kecil. 4. Kebijakan pemerintah yang menjadikan pulau-pulau kecil di Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan air tawar yang sesuai dengan peruntukannya (fresh water). Sumber air tawar di pulau-pulau kecil sepenuhnya berasal dari air hujan atau air meteorik karena wilayah tangkapan yang terbatas, sehingga kapasitas atau daya tampung pulau-pulau kecil dalam penyimpanan air hujan juga sangat terbatas. Isu perubahan iklim dan peningkatan muka air laut semakin mengancam keberadaan sumber daya air tawar di pulau-pulau kecil (Masterson et al., 2013; Rasmussen, Sonnenborg, Goncear, & Hinsby, 2013; White et al., 2007). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air tawar di pulau-pulau kecil Indonesia menjadi suatu keharusan. 5. Ancaman lain juga datang dari faktor lingkungan dunia. Salah satu masalah lingkungan yang memiliki ancaman paling nyata saat ini adalah perubahan iklim global. Iklim bumi sebenarnya bersifat dinamis dan selalu berubah sepanjang waktu. Namun dalam beberapa dekade belakangan ini, iklim bumi mengalami perubahan ke arah yang cenderung konstan, yaitu meningkatnya temperatur global. Faktor utama yang secara signifikan membuat temperatur bumi cenderung naik adalah adanya pertambahan populasi manusia di dunia dengan segala aktivitas yang dilakukannya. Penggunaan bahan bakar fosil, berkurangnya lahan hijau, dan efek industrialisasi menyebabkan semakin banyak gas buang yang menjadi kontribusi bagi efek gas rumah kaca di bumi. Dan salah satu masalah utama yang timbul karena peningkatan temperatur global ini adalah naiknya permukaan air laut, dimana masalah ini menjadi ancaman yang nyata bagi daratan yang ada di bumi, terutama di daerah pantai. 6. Kenaikan permukaan air laut terhadap daerah pantai diantaranya akan menyebabkan adanya daratan yang hilang, kerusakan ekosistem di pantai, kerusakan infrastruktur dan bangunan di pantai, ancaman terhadap populasi penduduk di daerah pantai, yang semuanya tentu akan menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Ancaman langsung terhadap daerah pantai ini tentu saja akan berdampak sangat besar bagi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Hilangnya daratan berarti terjadi kemunduran garis pantai lebih menjorok ke daratan, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pula bagi penghitungan batas laut teritorial negara. Tantangan tersebut merupakan kesempatan lebih lanjut untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan terpadu, khususnya pada pulau-pulau kecil. 1. Menangani banjir tidaklah semata untuk mengalirkan air banjir ke tempat yang aman, sehingga tidak mengganggu pemukiman maupun areal pertanian. Dengan demikian masalah kekeringan akan tetap terjadi, karena tidak adanya imbuhan cadangan air tanah saat musim hujan, sehingga saat musim kering cadangan air tanah akan habis. Masalah banjir dan kekeringan ini perlu ditangani dan diatasi secara terpadu. Ketika musim hujan dan air hujan berlebihan, maka hal penting yang perlu dilakukan adalah mengelola air hujan yang jatuh itu dengan menerapkan teknologi sederhana yang didasarkan pada pendekatan secara ekologis. Sebaliknya ketika tidak ada hujan yang terjadi, maka dapat memanfaatkan air hujan yang dikelola dalam musim hujan tersebut guna memenuhi kebutuhan air yang ada. Pengelolaan air hujan yang dilakukan saat musim hujan, juga akan menjaga cadangan air tanah yang ada karena mendapat imbuhan yang cukup, sehingga saat musim kemarau, tidak terjadi bencana kekeringan. Artinya, teknologi sederhana dan terapan ini akan mampu menangani banjir sekaligus mampu mengatasi kekeringan secara terpadu. Konsep teknologi terapan untuk mengatasi bencana banjir dan kekeringan melalui upaya pengelolaan air hujan dalam skala rumah tangga. Yang menjadi prinsip dasar dari
ISLANDS HYDROLOGY BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 138 konsep ini adalah air hujan yang jatuh di area kompleks rumah tangga, yaitu di atas atap rumah dan pekarangan (bila ada) dikelola dengan baik agar sesedikit mungkin mengalir keluar dari kompleks rumah tangga. Air hujan yang jatuh di atap rumah, ditangkap oleh selokan penangkap air hujan, dialirkan untuk proses mineralisasi ke dalam kolam tampung air bersih untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Air hujan yang melimpas di pekarangan rumah, dikendalikan dengan menangkap dan mengalirkannya ke dalam kolam tampung air pertanian untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, atau lainnya. Secara jelasnya konsep ini diilustrasikan seperti dalam Gambar IX.3. Gambar 9. 3 Analisis hidrologi-hidrolika mengatasi bencana banjir dan kekeringan 2. Langkah awal dalam melakukan pengelolaan sumber daya air tawar di pulau-pulau kecil dapat ditempuh dengan melakukan estimasi daya dukung sumber daya air tawar yang ada di pulau kecil tersebut. Estimasi ini perlu dilakukan untuk mengatur pola pemanfaatan dan konservasinya agar keberlanjutan sumber daya airnya dapat berkelanjutan. Gambar IX.4. mengilustrasikan ketersediaan air permukaan dibandingkan dengan populasi penduduk di Indonesia. Gambar 9. 4 Populasi dan distribusi air permukaan di Indonesia 3. Peluang memanfaatkan air tanah dari kawasan pulau-pulau kecil sangatlah tidak direkomendasikan karena keterbatasan karakteristik hidrologi pulau-pulau kecil yang
ISLANDS HYDROLOGY BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 139 telah dijelaskan tersebut di atas. Gambar IX.5. mengilustrasikan kondisi air tanah pada pulau kecil dalam keadaan normal dan setelah dilakukan ekstraksi air tanah. Gambar 9. 5 Kondisi air tanah sebelum dan sesudah ekstraksi dengan pompa 4. Dalam konteks perubahan iklim, karakteristik pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh sebagian besar wilayah perairan laut mengindikasikan bahwa daerah ini sangat dipengaruhi variabilitas iklim dan cuaca, khususnya kawasan pesisir yang merupakan peralihan daratan dan laut, sangat rentan terhadap ancaman perubahan iklim, seperti abrasi, dan kenaikan muka air laut, terutama pulau-pulau kecil yang berada di perairan laut dalam. Panduan dalam Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, menjelaskan konsep pengelolaan sumber daya alam dengan tiga prinsip dasar yaitu: keselamatan manusia dan alam, produktivitas sosial untuk memenuhi kualitas hidup, serta keberlanjutan layanan alam. Strategi tercapainya sektor ekonomi prioritas, meliputi sektor energi, industri, kehutanan, pertanian-perikanan, dan infrastruktur harus dirumuskan bukan saja lewat optimasi internal masing-masing sektor ekonomi tersebut, namun juga harus mempertimbangkan wilayah mitigasi sosial ekologis demi keberlangsungan lintas sektoral dalam wilayah tersebut dan tercapainya tiga prinsip dasar di atas. Selain mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan aspek kunci yang harus menjadi agenda pembangunan nasional dalam rangka mengembangkan pola pembangunan yang tahan (resilience) terhadap dampak perubahan iklim. Konsep mitigasi dan adaptasi ini dijelaskan seperti dalam Gambar IX.6.
ISLANDS HYDROLOGY BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 140 Gambar 9. 6 Mitigasi dan adaptasi dalam konsep pengelolaan terpadu 5. Salah satu kritik atas konsep pariwisata konvensional telah diajukan Cherem (1988) dengan mengajukan konsep pariwisata yang tepat. Menurutnya, pariwisata yang tepat adalah pariwisata yang secara aktif membantu dalam menjaga keberlangsungan suatu daerah kebudayaan, sejarah dan alam. Paradigma pariwisata sekarang ini lebih mementingkan fleksibilitas, segmentasi, dan integrasi diagonal sebagai bentuk inovasi dari kecenderungan special interest dan ecotourism yang menghendaki pengendalian motif ekonomi ke arah konservasi sumberdaya alam dan pelestarian social budaya. Dengan kelemahan konsep sebelumnya, dirumuskan pendekatan new tourism yaitu melalui deklarasi Piagam Pariwisata berkelanjutan yang berbunyi: Pengembangan pariwisata didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang secara ekologis harus dikelola dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Menurut Frans Mardi Hartanto (2003), beberapa pemahaman yang perlu diinternalisasikan kepada semua stakeholder antara lain: a) Pariwisata berkelanjutan mengandung semangat konservatif, bukan eksploitatif (mencegah komersialisasi alam dan budaya) b) Kegiatan pariwisata adalah suatu proses ekonomisasi pengalaman, dimana terkait dengan pemuasan kebutuhan manusia yang mampu memberi melebihi ekspektasi c) Pariwisata berkelanjutan diarahkan agar berkembang dengan adil bersama masyarakat, dimana mereka diperankan sebagai pelaku utama dalam kegiatan kepariwisataan d) Pariwisata berkelanjutan tumbuh secara alamiah yang berbasis masyarakat, lingkungan alam dan sosial-budaya, masyarakat harus menjadi bagian integral dari kegiatan pariwisata, karena inti kegiatan pariwisata adalah masyarakat itu sendiri; Tugas 11: Tugas individu: Buatlah sebuah tulisan singkat yang mengungkapkan keistimewaan kepulauan di Indonesia, dengan karakter hidrologis, masalah dan tantangannya, serta peluang pengembangannya yang berkelanjutan (Tugas individu ditulis tangan) Tugas kelompok: Satukan tugas-tugas individu di atas dalam suatu tugas kelompok dan disusun dalam bentuk presentasi (file PPT).
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 141 BAB 10 – RAINWATER MANAGEMENT Pengelolaan air hujan dijelaskan sebagai upaya mengelola air hujan yang jatuh tidak sebatas hanya memanen, mengumpulkan, mengalirkan dan menampungnya untuk kemudian dapat menggunakannya saat diperlukan, tetapi lebih dalam artian ketika terjadinya dalam besaran, waktu dan sebaran yang tidak menguntungkan. Hal ini sering dialami dan ditemui dalam konteks pemenuhan kebutuhan air untuk tanaman atau dalam konteks irigasidrainase pertanian agar mencapai hasil produksi yang optimal. Saat musim hujan, sering terjadi dalam jumlah yang besar dengan waktu berturut-turut, sehingga berakibat pada kondisi tanah dalam lahan pertanian menjadi jenuh air (waterlogging) yang mengancam pertumbuhan dan hasil produksi tanaman, bahkan mati dan gagal panen. Sebaliknya saat musim hujan, sering terjadi tidak adanya hujan yang turun dalam waktu yang cukup untuk terjadinya situasi kekeringan singkat (dryspell), yang berakibat pada penurunan produksi hasil panen atau gagal panen. Pemanenan air hujan adalah teknik pengumpulan dan penyimpanan air hujan ke reservoir atau tangki alami, atau infiltrasi air permukaan ke dalam akuifer bawah permukaan (sebelum hilang sebagai limpasan permukaan). Salah satu metode pemanenan air hujan adalah pemanenan atap. Dengan pemanenan atap, sebagian besar permukaan apa pun - ubin, lembaran logam, plastik, tetapi bukan rumput atau daun palem - dapat digunakan untuk mencegat aliran air hujan dan memberi rumah tangga air minum berkualitas tinggi dan penyimpanan sepanjang tahun. Kegunaan lain termasuk air untuk kebun, ternak, dan irigasi. Alasan menggunakan sistem pemanenan ataupun pengelolaan air hujan adalah menjawab tiga pertanyaan: 1. Apa: Pemanenan air hujan akan meningkatkan pasokan air, produksi makanan, dan pada akhirnya ketahanan pangan. 2. Siapa: Rumah tangga yang tidak aman air atau individu di daerah pedesaan akan mendapat manfaat paling besar dari sistem panen air hujan. 3. Bagaimana: Karena panen air hujan mengarah pada pasokan air yang mengarah pada ketahanan pangan, ini akan sangat berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Dalam bab ini akan dijelaskan meliputi: konsep pengelolaan air hujan, kerangka pikirnya, kemudian pengelolaan air hujan dalam suatu sub-DAS dan dalam skala kecil atau rumah tangga. 10.1. Rainwater Management Concept Konsep pengelolaan air hujan untuk pertanian, dengan prinsip pokok yaitu (Gambar X.1): 1. Menangkap air hujan yang jatuh, meresapkannya ke dalam tanah sebagai imbuhan bagi cadangan air tanah dan/atau menampungnya untuk dapat digunakan pada waktu musim kering. 2. Mengeringkan kelebihan air dalam tanah waktu curah hujan tinggi (dengan sistem drainase), menampungnya untuk dapat digunakan pada waktu musim kering.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 142 Gambar 10. 1 Sketsa pengaliran air hujan yang ditampung dan diresapkan Pengelolaan air hujan perlu mendapat perhatian khusus karena ciri khas sistem hidrogeologi dari pulau kecil. Ciri khas ini menyangkut keterpaduan hidrologis dimana ketersediaan air tanah berupa air hujan. Permasalahan yang muncul adalah air hujan ini memiliki siklus pendek untuk terbuang ke laut karena ukuran pulau yang kecil, dan terjadinya kondisi yang disebut sebagai dry spell dan waterlogging. Air tanah pada pulau kecil biasanya berupa lensa air yang rentan terhadap penyusupan air laut. Ciri khas pulau kecil yang lain adalah menyangkut kondisi sosial – budaya dan ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah pulau kecil ini biasanya terisolir dengan komunikasi terbatas. Sumber daya alam pendukung yang rendah dan sumber daya manusia juga terbatas. Perkembangan ekonomi sangat terbatas karena kendala akan ketersediaan air. Kerangka pikir pengelolaan air hujan pada pulau kecil di kawasan kering Indonesia diilustrasikan pada Gambar X.2. Kerangka pikir ini dipilih untuk mengatasi beberapa permasalahan yang telah diungkapkan di atas. Permasalahan yang menyangkut keterpaduan hidrologis yaitu pendeknya daur hidrologi dan upaya memperpanjangnya, ketersediaan dan kebutuhan air, serta penyimpanan air di permukaan dan di dalam tanah. Permasalahan pokok akan ketersediaan air untuk mencapai suatu ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan, perkembangan ekonomi dan akhirnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pada pulau kecil tersebut, dicoba diselesaikan melalui keterpaduan dalam pengelolaan air hujan untuk pertanian. Gambar 10. 2 Kerangka pikir pengelolaan air hujan untuk pertanian pada pulau kecil UMPAN BALIK Ciri khas sistem hidrogeologi: ▪ Air hujan, mempunyai siklus pendek untuk terbuang ke laut ▪ Situasi dryspell & waterlogging ▪ Air tanah berupa lensa air ▪ Rentan terhadap penyusupan air laut Ciri khas sosial – budaya – ekonomi: ▪ Terisolir – komunikasi terbatas ▪ Sumber daya alam pendukung rendah ▪ Sumber daya manusia terbatas ▪ Perkembangan ekonomi terkendala akan ketersediaan air Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pada pulau kecil di kawasan kering Ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan Ketersediaan air untuk pertanian dan domestik secara berkelanjutan Perkembangan ekonomi MASUKAN PROSES KELUARAN
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 143 Kerangka pikir pengelolaan air hujan untuk pertanian pada pulau kecil di kawasan kering memiliki tiga unsur yaitu: masukan, proses, dan keluaran. Unsur masukan menentukan proses yang terjadi. Akhirnya unsur proses ini menghasilkan unsur keluaran yang diharapkan. Dari unsur keluaran menjadi umpan balik bagi unsur masukan yang menentukan proses dan keluaran. Begitu seterusnya untuk mencapai semakin sesuai, terpadu dan berkelanjutan. 1. Unsur masukan merupakan ciri khas sistem hidrogeologi dan sosial – ekonomi – budaya dari pulau kecil. Ciri khas sistem hidrogeologi menyangkut: (1) air tanah yang bersumber dari air hujan, dengan siklus pendek untuk terbuang ke laut, (2) air tanah berupa lensa air yang tipis dan rentan terhadap penyusupan air laut, dan (3) situasi terjadinya dryspell dan waterlogging. Ciri khas sosial – ekonomi – budaya menyangkut: (1) daerah yang terisolir secara geografis, dengan komunikasi yang terbatas, (2) sumber daya alam pendukung yang rendah, (3) sumber daya manusia terbatas, dan (4) perkembangan ekonomi yang menemui banyak kendala. 2. Unsur keluaran merupakan kondisi daerah yang diharapkan yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pulau kecil tersebut. Kemandirian masyarakat tersebut meliputi ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan seharihari. Ketahanan pangan ini sangat ditentukan oleh ketersediaan air, baik untuk keperluan pertanian maupun pemenuhan kebutuhan domestik. Hal lain yang menjadi faktor tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adalah perlindungan lingkungan, baik daerah pantai maupun biodiversiti. Ketersediaan air dan perlindungan lingkungan tersebut diharapkan berkelanjutan sehingga perkembangan ekonomi dapat diharapkan secara terus menerus. 3. Unsur proses merupakan pengelolaan sumber daya air terpadu khususnya dalam pengelolaan air hujan untuk pertanian di kawasan kering. Proses ini ditentukan oleh keempat kategori sistem yang telah ditemukan yaitu: (1) sistem prasarana, (2) operasi dan pemeliharaan, (3) sistem kelembagaan, dan (4) pemberdayaan masyarakat. Keempat kategori sistem ini saling berkaitan secara spiral dan tidak lepas dari pentingnya sistem informasi yang mendukung dalam proses pengelolaan sumber daya air terpadu khususnya dalam pengelolaan air hujan untuk pertanian pada pulau kecil di kawasan kering. Teknologi pengelolaan air hujan dapat dilakukan seperti halnya dalam teknologi pemanenan air hujan, yang meliputi pemanenan dari atap, in situ, aliran air permukaan, mengisi kembali air tanah (groundwater recharge) ataupun menangkapkan dari kabut/embung (Gambar X.3). Gambar 10. 3 Teknologi pemanenan air hujan
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 144 Pengelolaan air hujan dari atap dapat dilakukan dengan tanpa menggunakan talang atap, tetapi membiarkan air langsung jatuh ke tanah, yang ditangkap oleh saluran penangkap air hujan dan mengolahnya melalui teknik sederhana dengan mengalirkan air hujan tersebut ke dalam saluran penangkap yang diisi dengan batu kericak sekitar tiga perempat kedalamannya sehingga dapat berfungsi sebagai aliran air tanah secara artifisial. Pengelolaan air hujan in situ dilakukan dengan menjebak aliran dan mengalihkan aliran menuju ke bak tampung yang telah disiapkan, demikian pula pengelolaan air limpasan permukaan diarahkan pada saluran penangkap yang dialirkan ke dalam bak tampung. Pengelolaan air hujan dengan teknologi meresapkan air hujan ke dalam tanah melalui teknik sumur resapan ataupun bak tampung konservasi, dimaksudkan untuk mengisi ulang air tanah, sehingga tetap dapat dimanfaatkan waktu musim kering melalui sumur-sumur dangkal. Teknologi pengelolaan air hujan dengan menangkap kabut ataupun embun, perlu dilengkapi dengan alat penangkap kabut/embun tersebut, kemudian dialirkan menuju saluran dan akhirnya sampai pada bak tampung. 10.2. Rainwater Management on Sub-Watershed Suatu waduk atau embung adalah contoh upaya pengembangan sumber daya air dengan memanen air hujan yang jatuh dalam suatu wilayah daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan untuk wilayah yang lebih kecil, seperti sub-DAS dapat dilakukan dengan cara membendung dan menampung dalam kolam-kolam, atau membendung sebagai jebakan, yang berturut-turut (series). Dalam konteks pulau yang kecil pengelolaan air hujan pada sub-DAS dilakukan dalam upaya memperpanjang perjalanan air hujan yang jatuh untuk sampai ke laut. Upaya memperpanjang perjalanan air hujan yang jatuh untuk sampai ke laut atau dikenal sebagai daur hidrologi, pada prinsipnya mengusahakan agar air hujan yang jatuh ke daratan pulau, selama mungkin berada di daratan pulau, tidak cepat terbuang ke laut. Pada alur-alur aliran alam dibangun suatu jebakan air berantai agar aliran limpasan air permukaan terhambat dan tidak cepat terbuang ke laut. Air yang terbendung pada jebakan dibiarkan meresap ke dalam tanah sehingga menjadi imbuhan bagi cadangan air tanah. Sedangkan air yang melimpas di sekitar jebakan air dapat difungsikan untuk mengairi tanaman di sekitar jebakan tersebut. Sketsa hidrolika dari jebakan air berantai ini diilustrasikan dalam Gambar X.4. Gambar 10. 4 Sketsa hidrolika dari jebakan air berantai Air hujan yang jatuh di daratan pulau akan cepat terbuang ke laut karena jarak tempuh aliran limpasan permukaan yang pendek sesuai dengan ukuran pulau. Hal ini dapat dilihat dari daur hidrologi pada pulau kecil seperti dalam Gambar X.5. Penampang melintang dari m.a.t Laut Laut
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 145 pulau kecil koral (Falkland, 2002). Air hujan yang cepat terbuang ke laut tersebut mengakibatkan sumber air tawar di daratan pulau menjadi sangat terbatas. Gambar 10. 5 Penampang melintang dari pulau kecil koral (Falkland, 2002) Struktur pemanenan air hujan yang berada di luar lahan pertanian (off site) atau sistem makro, dan yang berada di lahan pertanian (in site) atau sistem mikro. Pemanenan air hujan secara setempat mengumpulkan air hujan dimana ia jatuh, untuk dimanfaatkan lebih efisien pada lahan yang sama. Hal ini sering mengacu pada usaha konservasi air. Pemanenan air hujan secara eksternal mengumpulkan air hujan pada suatu permukaan tanah dalam suatu daerah tangkapan, dan akan dimanfaatkan oleh daerah lain (Gambar X.6). Gambar 10. 6 Prinsip dasar pemanenan air hujan untuk meningkatkan pertanian Daerah Tangkapan Limpasan Permukaan Tampungan Daerah Pertanian Skala limpasan permukaan: • Lahan (aliran lempeng) • Sub-tangkapan (aliran alur sempit) • Daerah Tangkapan (alur, aliran sungai) Media tampungan: • Di permukaan (tangki, bendung, waduk, kolam) • Di bawah permukaan (tanah, tangki)
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 146 Tujuan dari bangunan struktur sistem makro dan mikro ini pada dasarnya untuk mengupayakan semakin panjangnya daur hidrologi, yaitu air hujan yang jatuh di daratan agar selama mungkin berada di daratan pulau. Bentuk bangunan struktur sistem makro dapat berupa jebakan air berantai pada alur drainase alam, atau embung konservasi di daerah cekungan. Bangunan ini mempunyai ciri khas dapat menahan air limpasan permukaan dan menampungnya, kemudian meresapkannya ke dalam tanah sebagai aliran air tanah. Bangunan struktur sistem mikro berupa kolam lahan, sumur resapan dan sumur gali, yang dapat menampung kebutuhan air drainase di lahan pertanian, meresapkannya, dan dapat diambil untuk mengairi tanaman di lahan pertanian. Sistem prasarana yang dipilih menentukan sistem operasi dan pemeliharaan lebih lanjut agar bangunan tetap berfungsi secara berkelanjutan. Seringkali hanya sebagian kecil dari air hujan yang mencapai dan tersimpan di dalam tanah untuk waktu yang cukup panjang, dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Hatibu et.al (2004) dalam melaporkan bahwa hampir 80 % dari air hujan yang jatuh telah hilang sebagai penguapan, limpasan permukaan yang menyebabkan erosi dan banjir di bagian hilir (Gambar X.7). Gambar 10. 7 Bagian dari air hujan yang jatuh, menghilang dan tinggal dalam tanah Tujuan pengelolaan air hujan untuk pertanian pada dasarnya merupakan unsur keluaran dari kerangka pikir pengelolaan air hujan untuk pertanian pada pulau kecil di kawasan kering. Yang menjadi tujuan pokok adalah ketersediaan air bagi kegiatan pertanian dan domestik secara berkelanjutan. Dengan adanya ketersediaan air yang mencukupi kebutuhan air, maka kegiatan pertanian akan memberikan hasil produksi yang optimal. Ini berarti pulau kecil tersebut akan mampu memenuhi ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Ketersediaan air ini juga akan memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan perkembangan ekonomi. Akhirnya, ketersediaan air berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat pada pulau kecil di kawasan kering tersebut. Penyimpanan air dapat dilakukan di permukaan ataupun di dalam tanah. Penyimpanan air di permukaan biasa dalam tangki, kolam atau embung. Sistem ini mensyaratkan suatu tangki, kolam atau embung yang kedap air, sehingga air yang disimpan tidak bocor. Faktor penting dalam sistem penyimpanan air di permukaan adalah: 1. Intensitas curah hujan (R dalam mm) 2. Luas daerah tangkapan hujan (A dalam Ha) 3. Koefisien limpasan permukaan (α) 4. Penguapan permukaan air terbuka dari tampungan (ETo dalam mm) 5. Perkolasi yang terjadi (P dalam mm)
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 147 Penyimpanan air di dalam tanah tergantung dari jumlah air yang dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai imbuhan bagi cadangan air tanah. Sistem penyimpanan air di dalam tanah tidak mensyaratkan suatu kolam tampungan yang kedap air. Faktor penting yang berpengaruh dalam penyimpanan air di dalam tanah adalah: 1. Intensitas curah hujan (R dalam mm) 2. Luas daerah tangkapan hujan (A dalam Ha) 3. Koefisien limpasan permukaan (Koef. Runoff : α ) 4. Koefisien resapan (β), yang sangat tergantung dari struktur dan tekstur tanah Pada waktu curah hujan tinggi, maka selain limpasan air permukaan yang besar, juga terjadi bahwa lengas air dalam tanah menjadi jenuh. Tanah yang jenuh ini tidak memungkinkan adanya udara dalam tanah yang sangat diperlukan oleh tanaman, sehingga tanaman akan mati, karenanya perlu dikeringkan. Kelebihan air ini diarahkan ke dalam saluran-saluran pengumpul, dialirkan ke dalam kolam-kolam air dalam lahan pertanian. Kolam-kolam air akan menampung air dari limpasan permukaan (RO) dan pengeringan kelebihan air dalam tanah (D), merupakan air yang tersedia bagi tanaman, dengan mempertimbangkan pula adanya perkolasi dan penguapan. Jumlah air hujan yang tertampung dapat diperkirakan dengan persamaan berikut: = + − − dimana: V = volume air yang tertampung E = penguapan air terbuka RO = limpasan air permukaan P = laju perkolasi D = kebutuhan drainase 10.3. Rainwater Management in Small Scale Pengelolaan air hujan dapat dilakukan dalam skala yang kecil, seperti skala rumah tangga, skala lokasi tertentu seperti taman kota, jalan raya dan sebagainya. Kolam tampung air hujan dalam suatu pekarangan rumah, merupakan bangunan skala kecil suatu bendungan besar atau waduk. Fungsinya terutama untuk memanen air hujan, demikian pula suatu bendungan besar atau waduk. Ketika saat hujan turun ke atas tanah, maka akan mengalir sebagai air limpasan permukaan, yang berpotensi untuk ditangkap, dialirkan dan ditampung untuk memenuhi kebutuhan air bersih (Migawati, H.D. et.al, 2012). Dengan topografi yang berbukit, maka limpasan air hujan akan mengalir dengan cepatnya melalui aliran air sungai menuju ke laut. Air hujan ini tidak sempat meresap ke dalam tanah, sehingga tidak terjadi imbuhan air tanah. Air limpasan permukaan ini ditahan atau ditangkap oleh suatu bangunan penangkap air limpasan permukaan, sehingga dapat dipanen dan ditampung ke dalam suatu kolam tampung. Air yang tertampung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun pertanian (Gambar X.8). Gambar 10. 8 Aliran air hujan – limpasan permukaan – kolam tampung LAU T Kolam Saluran penangkap air limpasan huja n air limpasan permukaa
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 148 Kelola air hujan skala kecil dapat dimanfaatkan untuk memenuhi air baku, yaitu kebutuhan air domestik, munisipal dan industri (D-M-I) dan kebutuhan air pertanian (Gambar X.9). Gambar 10. 9 Kelola air hujan untuk kehidupan memenuhi kebutuhan air baku Secara detail kelola air hujan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, munisipal dan industri dari kelola air hujan dalam kompleks rumah tinggal dijelaskan seperti dalam Gambar X.10. berikut ini. Gambar 10. 10 Kelola air hujan pada skala kompleks rumah tinggal
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 149 Kelola air hujan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, secara spesifik tidak hanya menyediakan air irigasi saja, tetapi juga menyediakan jaringan drainase pertanian, yang sangat penting saat hujan berlimpah yang menyebabkan kondisi jenuh air atau waterlogging (Gambar X.11). Gambar 10. 11 Kelola air hujan skala kecil untuk pertanian Infrastruktur kelola air hujan skala rumah tangga dilengkapi dengan saluran penangkap aliran air hujan baik dari atap rumah maupun permukaan lahan, dan bak tampung air hujan (Gambar X.12). Gambar 10. 12 Infrastruktur kelola air hujan skala kecil rumah tinggal Infrastruktur kelola air hujan skala daerah irigasi pertanian memerlukan kolam-kolam lahan selain saluran irigasi maupun drainase pertanian. Sebagai contoh infrastruktur kelola air hujan untuk pertanian tebu yang dilakukan oleh PT. Muria Sumba Manis di Pulau Sumba (Gambar X.13).
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 150 Gambar 10. 13 Infrastruktur kelola air hujan berupa kolam lahan Tugas 12. Berupa tugas kelompok: Buatlah artikel atau tulisan berupa inspirasi dan inovasi kelompok dalam pengelolaan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air baku, yang terdiri dari kebutuhan air rumah tangga dan pertanian berupa pemenuhan kebutuhan air irigasi kebun. Kerangka tulisan terdiri dari: 1. Abstraksi (menjawab pertanyaan mengapa (why – latar belakang), bagaimana (how - metodologi) dan untuk apa (to whom – tujuan dan manfaat, kesimpulan dan rekomendasi), maksimal 200 kata 2. Pendahuluan – latar belakang – permasalahan – tujuan/manfaat – batasan permasalahan. 3. Metodologi – diagram alir, skema kerangka pikir 4. Inovasi/inspirasi – konsep desain – desain – detail desain/gambar desain – rancangan biaya (RAB) – pelaksanaan konstruksi 5. Kesimpulan, saran dan rekomendasi Tulisan tidak lebih dari 10 halaman, dikumpulkan dalam bentuk file word (doc/docx). Perlu diperhatikan, penulisan tabel, gambar dan referensi. Diberikan template tulisan terlampir.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 151 BAB 11 – HYDROLOGICAL APPLICATION Materi aplikasi hidrologi ini dimaksudkan sebagai: 1. Pengenalan dan pemahaman model dasar hidrologi terkait dengan analisis hidrologi Model dalam SDA 2. Dalam kegiatan analisis hidrologi untuk berbagai kepentingan dalam pengembangan sumberdaya air, dalam banyak kasus diperlukan data hujan ataupun data debit dengan jangka waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan jangkauan data yang tersedia. 3. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang baik terhadap DAS tertentu sebagai sistem yang mengalihragamkan masukan menjadi keluaran debit atau hidrograf. Dooge (1973) menyebutkan bahwa model adalah struktur, alat, skema atau prosedur nyta atau MODEL abstrak, yang menghubungkan masukan, sebab atau rangsangan, tenaga atau informasi, dan keluaran, pengaruh atau tanggapan dalam referensi waktu tertentu. Ponce (1989) secara spesifik menakrifkan model (matematik) sebagai satu set pernyataanpernyataan matematik yang menyatakan hubungan antara fase-fase dari siklus hidrologi dengan tujuan mensimulasikan transformasi hujan menjadi limpasan. Clarke (1973) mendifinisikan model sebagai simplifikasi dari suatu sistem yang kompleks, baik berupa fisik, analog atau matematik. 1. Model fisik. Dibuat sebagai model dengan skala tertentu untuk menirukan prototipenya, model ini p p y mempunyai 3 bagian terpenting yaitu: rain simulator, runoff surface dan alat-alat ukurnya. 2. Model Analog. Model analog disusun dengan menggunakan rangkaian resistorkapasitor untuk memecahkan persamaan-persamaan deferensial yang mewakili proses hidrologi, dasar analognya adalah: I = O ± ΔS 3. Model Matematik. Menyajikan sistem dalam rangkaian persamaan dan kadangkadang dengan ungkapan-ungkapan yang menyajikan hubungan antarvariabel dan parameter. KOMPONEN MODEL Tiruan proses hidrologi untuk keperluan analisis jumlah tentang keberadaan air menurut aspek jumlah, waktu, tempat, probabilitas dan runtun waktu (time series). 1. merupakan integrasi dari semua proses hidrologi. 2. mensimulasikan transpormasi hujan menjadi aliran (rainfall runoff model): jumlah/waktu pada tempat tertentu. 3. diperlukan untuk analisis, perencanaan, perancangan, perkiraan jangka panjang dan peramalan, terutama bila data yang tersedia terbatas. SYARAT MODEL Syarat model antara lain: 1. Pemilihan jenis model yang tepat 2. Formulasi dan penyusunan model 3. Pengujian model, yang dilakukan dengan 2 cara yaitu kalibrasi dan verifikasi. 4. Pemakaian model setelah melalui berbagai pengujian.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 152 JENIS MODEL 1. Model Stokastik merupakan bagian dari model probabilistik yang dapat berupa model statistik dan model stokastik. Model ini lebih menekankan pada time-dependency variabel hidrologi. 2. Model Empirik adalah model yang hubungan antar parameternya diperoleh dengan cara coba-coba, tanpa memerlukan pemahaman proses yang sebenarnya terjadi. 3. Model Konseptual merupakan model yang berada antara model teoritik dan empirik, yang menyajikan proses fisik dengan penyederhanaan. 4. Model Deterministik adalah model yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmu fisika yang menunjukkan hubungan sebab akibat. 5. Model Parametrik, termasuk didalamnya model empiric misalnya model “kotak hitam” (black box model) merupakan model yang paling sederhana yang didasarkan pada pengamatan dan percobaan 6. Model yang bersifat linier dalam pengertian teori system adalah model yang didalamnya berlaku asas superposisi. 7. Lumped model adalah model yang tidak memperhitungkan variabilitas-ruang baik variabel masukan maupun parameter sistem DAS. 8. Event model adalah model yang hanya dirancang untuk perkiraan limpasan sesaat. 9. Continuous Model adalah model yang didasarkan pada proses menerus dari semua komponen proses. PERTIMBANGAN UMUM PROSEDUR ANALISIS HIDROLOGI Yang menjadi pertimbangan umum dalam prosedur analisis hidrologi antara lain: 1. Ketersediaan data 2. Kualitas data 3. Tingkat ketelitian hasil yang dikehendaki 4. Kesesuaian cara dengan DAS yang ditinjau KEBUTUHAN DAN PERKIRAAN 1. kualitas dan kuantitas data yag kurang memadai, 2. kurangcocoknya berbagai model terhadap kasus-kasus spesifik di Indonesia, 3. ketidakpuasan terhadap pemakaian cara-cara lama yang didasarkan pada cara-cara empirik atau model-model yang didasarkan hanya pada faktor geografik, karena dalam pengujian ternyata mengandung kesalahan yang cukup besar, 4. perkembangan hardware komputer dan perkembangan perangkat matematik untuk analisis data dan penyusunan model, 5. ketersediaan dana untuk penelitian dan pengembangan cara-cara baru, 6. kesenjangan antara beberapa pengertian tentang sistem hidrologi, 7. kompleksnya sistem yang dianalisis, dan 8. timbulnya kesalahan dalam peramalan dan perkiraan. Dua cara pendekatan 1. Method non optimasi (nonoptimizing method). Dalam model ini peranan data sangat menentukan, pertanyaan yang selalu terkait dengan data ini adalah: ketersediaan data dan kualitas data. Dua istilah yang sering digunakan dalam praktek adalah: data simulasi (simulated data) adalah data yang dihasilkan sebagai keluaran oleh sebuah model dan data sintetik (syntethic data) adalah data yang dihasilkan oleh analisis stokastik. 2. Method optimasi (optimizing method). Dalam model optimasi, semua aspek dalam semua bentuk dan sifatnya, baik individu maupun sifat hubungan antar variabel/parameternya dikaitkan untuk memperoleh hasil terbaik setelah memperhitungkan semua hambatan, pertimbangan, baik untung ruginya, kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kaitan ini masalahnya dapat menjadi sangat kompleks, karena bila tujuan dan hambatannya cukup banyak, maka pemilihan hasil yang ’paling
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 153 baik’ menjadi sangat sulit. Tergantung dari tingkat kebutuhan dan ketelitian yang dikehendaki, penyimpangan dalam analisis tersebut dapat diperlakukan dengan dua cara: a. membiarkan saja penyimpangan tersebut terjadi dengan menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang wajar, karena sifat alami yang tidak mungkin dapat dimodelkan secara sempurna. b. melakukan modifikasi model yang dikembangkan agar dapat memberikan unjuk raga yang lebih baik. STRUKTUR MODEL Struktur model terdiri dari: 1. Struktur Komponen Hidrometeorologi 2. Struktur Komponen Permukaan 3. Struktur Komponen Bawah permukaan 4. Struktur Komponen Sungai
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 154 KALIBRASI Kalibrasi dilakukan untuk memastikan besaran-besaran/parameter-parameter model. Kalibrasi dilakukan untuk menemukan besaran/parameter yang belum diketahui agar keluaran model ‘dekat’ dengan keluaran DAS prototipnya (observed characteristics). Kalibrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik cara manual (trial and error), otomatik (automatic calibration) atau gabungan antara keduanya. VERIFIKASI Untuk menguji ulang (menguji akhir) unjuk kerja model, diperlukan tahap verifikasi. Dalam tahap in, model dengan semua parameter yang telah diperoleh dalam tahap kalibrasi diuji dengan menggunakan data yang belum digunakan dalam kalibrasi. Misalnya tersedia data sepanjang sepuluh tahun, maka data lima tahun pertama digunakan untuk kalibrasi, sedangkan data lima tahun terakhir digunakan untuk verifikasi.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 155 MODEL HIDROLOGI SEDERHANA Model hidrologi sederhana antara lain: 1. Rainfall runoff model 2. Frequency analysis 3. Stochastic analysis Rainfall runoff model Prinsip pemodelan: tata baku dan imbangan air. Kegunaan: perkiraan ketersediaan air (continuous flow) dan debit/hidrograf aliran besar/banjir (event flow). Contoh: SSARR, SHE, MOCK, NASH, HEC-HMS, dll.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 156 Frequency analysis Prinsip pemodelan: fungsi distribusi probabilitas. Kegunaan: perkiraan besaran hidrologi sebagai nilai besaran rancangan dengan kala ulang tertentu (banjir rancangan, hujan rancangan). Contoh: distribusi Normal, Log-Normal, Gumbel, Pearson III, dll. Stochastic analysis Prinsip pemodelan: perilaku komponen perulangan (tetap), trend dan simpangan (error). Kegunaan: pembangkitan data hidrologi (hujan, debit) untuk input evaluasi unjuk kerja design capacity atau pedoman operasi bangunan air. Contoh: Thomas Fiering, Matallas, ARIMA, dll.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 157 Applications of GIS to Water Resources Engineering. Geographic Information Systems – where in the world? The Problem…no….that is Opportunity. To analyze hydrologic processes in a non-uniform landscape. Non-uniformity of the terrain involves the topography, land use and soils, and consequently affects the hydrologic properties of the flow paths.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 158 The Solutions Lumped models: Easy to implement, but do not account for terrain variability. Spatially-distributed models: Require sophisticated tools to implement, but account for terrain variability. Overview - Soil Water Balance - Flow Routing Methods - Results Soil Water Balance Model
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 159 Global Data Given: wfc : soil field capacity (mm) w pwp : soil permanent wilting point (mm) P : precipitation (mm) T : temperature (°C) Rn : net radiation (W/m2 ) fc pwp i pwp i p i n i w w w w E E (T ,R ) − − = Evaporation: i+1 = wi + Pi − Ei If w w w , E w w P and S 0 If w w w and S 0 If w w w and S w i 1 pwp i 1 pwp i i pwp i i i 1 i 1 i * pwp i 1 * i i 1 * i 1 * i 1 = = − + = = = = = − + + + + + + + + Soil moisture and surplus: Calculated: w : actual soil moisture (mm) S : water surplus (mm) E : actual evaporation (mm) E p : potential evaporation (mm) fc pwp * w = w − w Precipitation (Jan.) Temperature (Jan.) Net Radiation (Jan.) Soil Water Holding Capacity
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 160 Monthly Surplus – Niger Basin Monthly Surplus – Niger Basin Flow Routing Models Precipitation and temperature data, at 0.5° resolution, by D. Legates and C. Willmott of the University of Delaware. Net radiation data, at 2.5° resolution, by the Earth Radiation Budget Experiment (ERBR). Soil water holding capacity, at a 0.5° resolution, by Dunne and Willmott.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 161 Cell-to-Cell Model Sets a mesh of cells on the terrain and establishes their connectivity. Represents each cell as a linear reservoir (outflow proportional to storage). One parameter per cell: residence time in the cell. Flow is routed from cell-to-cell and hydrographs are calculated at each cell. Mesh of Cells Congo River basin subdivided into cells by a 2.8125° ∼ 2.8125° mesh. With this resolution, 69 cells were defined. Low Resolution River Network Low resolution river networks determined from high resolution hydrographic data.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 162 Low Resolution River Network High resolution flow directions (1-Km DEM cells) are used to define low resolution river network (0.5° cells). Cell Length The cell length is calculated as the length of the flow path that runs from the cell outlet to the receiving cell outlet. = = =
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 163 Element-to-Element Model Defines hydrologic elements (basins, reaches, junctions, reservoirs, diversions, sources and sinks) and their topology. Elements are attributed with hydrologic parameters extracted from GIS spatial data. Flow is routed from element-to-element and hydrographs are calculated at all elements. Different flow routing options are available for each hydrologic element type. Sub-Basins and Reaches Congo River basin subdivided into sub-basins and reaches. Sub-basins and reaches delineated from digital elevation models (1 Km resolution). Streams drain more than 50,000 Km2. Sub-basin were defined for each stream segment. Hydrologic System Schematic Hydrologic system schematic of the Congo River basin as displayed by HEC-HMS.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 164 Detail of the schematic of the Congo River basin. Delineated Streams
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 165 Guadalquivir Basin HMS Schematic of the Guadalquivir Basin Source-to-Sink Model Defines sources where surplus enters the surface water system, and sinks where surplus leaves the surface water system. Flow is routed from the sources directly to the sinks, and hydrographs are calculated at the sinks only. A response function is used to represent the motion of water from the sources to the sinks.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 166 Sinks Sinks are defined at the continental margin and at the pour points of the inland catchments. Using a 3°x3° mesh, 132 sinks were identified for the African continent (including inland atchments like Lake Chad). Drainage Area of the Sinks The drainage area of each sink is delineated using raster-based GIS functions applied to a 1-Km DEM (GTOPO30).
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 167 GTOPO30 has been developed by the EROS Data Center of the USGS, Sioux Falls, ND. Land Boxes Land boxes capture the geomorphology of the hydrologic system. A 0.5°x0.5° mesh is used to subdivide the terrain into land boxes. For the Congo River basin, 1379 land boxes were identified. Surplus Boxes Surplus boxes are associated to a surplus time series. Surplus data has been calculated using NCAR’s CCM3.2 GCM model over a 2.8125° x 2.8125° mesh. For the Congo River basin, 69 surplus boxes were identified.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 168 Sources Sources are obtained by intersecting: drainage area of the sinks land boxes surplus boxes Number of sources: Congo River basin: 1,954. African continent: 19,170 Response Function Global Monthly Surplus
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 169 Animation prepared by Kwabena Asante Global River Network Hydrographs - Congo River Hydrographs - Amazon River
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 170 Watershed Geomorphology Flooding t.u. Campus Animation prepared by Esteban Azagra Untuk materi ini tidak ada tugas
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 171 DAFTAR PUSTAKA Sasrodarsono, Suyono, 1987. Hidrologi Untuk Pengairan, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Soemarto, C.D., 1995. Hidrologi Teknik, Edisi ke-2, Erlangga, Jakarta. Soewarno, 1991. Hidrologi Pengukuran dan Pengolahan Data Aliran Sungai (Hidrometri), Nova, Bandung. Sosrodarsono, Suyono (Ed.), 1999. Hidrologi Untuk Pengairan, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Wilson, EM; Marjuki, Asnawi, 1993. Hidrologi Teknik, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta. Robert J. Kodoatie, 2012. Tata Ruang Air Tanah, Andi offset, Yogyakarta. Robert J. Kodoqtie & Roestom Syorief, 2010. Tata Ruang Air, Andi offset, Yogyakarta. Sentot Subagyo, 1990. Dasar-Dasar Hidrologi, Gajah Mada Pres, Yogyakarta. Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP), 2009. Pedoman Studi Kelayakan Hidrologi, Buku 2A, Dirjen ESDM. Pustaka Tambahan: Hall, M.J., 1996. Engineering Hydrology, Lecture note of IHE – Delft, The Netherlands. Mekdaschi Studer, R. and Liniger, H. 2013. Water Harvesting: Guidelines to Good Practice. Centre for Development and Environment (CDE), The International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome. McCuen, Richard H., 1998. Hydrologic Analysis and Design, Prentice Hall, New Jersey. Dawai Han, 2010. Concise Hydrology, Ventus Publishing. Chow Ven Te, 1988. Applied Hydrology, Mc. Graw Hill. Susilawati CL, 2011. FAO, 1984. INLAND AQUACULTURE ENGINEERING. FAO, 2003. OPTIMIZING SOIL MOISTURE FOR PLANT PRODUCTION Rima Mekdaschi Studer and Hanspeter Liniger, 2013. WATER HARVESTING GUIDELINES TO GOOD PRACTICE, IFAD
DAFTAR PUSTAKA BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI