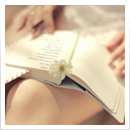HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 86 Dari tabel di atas diketahui bahwa hidrograf memiliki M = 3 dan N = 11, sehingga jumlah unit atau pulsa hidrograf satuan N-M+1 = 9. Tabel 6. 4 Hidrograf satuan yang diturunkan Dengan UH teresebut maka besarnya limpasan permukaan untuk DAS seluas 34,48 km2 akibat hujan efektif 100 mm dengan distribusi jam-jam an 30 mm, 50 mm, dan 20 mm dapat diperkirakan sebagai berikut: Tabel 6. 5 Analisis hidrograf satuan – limpasan permukaan Jumlah hujan efektif 100 mm dengan luas DAS 34,88 km2.
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 87 Volume limpasan adalah 100 x 10-3 x 34,88 x 106 m3 = 3.488.000 m3. Jumlah aliran sama dengan luas bidang di bawah hidrograf = 969 x 3.600 = 3.488.000 m3. (Gambar VI.9) Gambar 6. 9 Hidrograf limpasan permukaan dengan hujan efektif jam-jaman berturut-turut 30 mm, 50 mm, dan 20 mm 6.3. Application of Unit Hydrograph Aplikasi dari metode hidrograf satuan, seringkali digunakan dalam menganalisis banjir. Pada suatu kejadian banjir yang berlangsung akibat hujan badai dengan durasi 1 jam-jam an diperoleh hasil pencatatan hidrograf banjir sungai adalah seperti tersaji pada tabel. Jika luas DAS adalah 200 hektar dan besarnya aliran dasar/baseflow adalah konstan 1,0 m3/dt, tentukanlah hidrograf satuannya dengan durasi 1 jam-jam an.
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 88 Tabel 6. 6 Tabel debit-baseflow jam-jam an Total DRO = 40,2 m3/dt Volume DRO = 40,2 x 1 x 60 x 60 = 14,472 x 104 m3 Tinggi hujan efektif = (14,472 x 104)/(200x104) = 72 mm UH = (10/72) x DRO Tabel 6. 7 Debit-baseflow-DRO-UH Gambar 6. 10 Grafik DRO dan UH Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa untuk menurunkan hidrograf satuan diperlukan rekaman data limpasan dan data hujan. Namun, sering kali pada DAS tidak dijumpai adanya pencatatan limpasan. Untuk itu, hidrograf satuan diturunkan berdasarkan data dari DAS yang sama atau terdekat yang memiliki karakteritik yang sama → Hidrograf Satuan Sintetis. Secara umum, hidrograf satuan sintetis dibedakan menjadi: 1. UH sintetis yang mengkaitkan karakteristik hidrograf (debit puncak, waktu dasar, dsb) dengan karakteristik DAS → Snyder 1938 dan Gray 1961. 2. UH sintetis berdasarkan hidrograf satuan tidak berdimensi → SCS 1972. 3. UH sintetis berdasarkan model simpanan DAS → Clark 1943. Jam ke- Debit (m3 /dt) Baseflow (m3 /dt) 0 1.0 1.0 1 4.0 1.0 2 7.4 1.0 3 11.2 1.0 4 9.0 1.0 5 6.4 1.0 6 4.6 1.0 7 3.4 1.0 8 2.2 1.0 9 1.0 1.0 Jam ke- Debit (m3 /dt) Baseflow (m3 /dt) DRO (m3 /dt) UH (m3 /dt) 0 1.0 1.0 0.00 0.00 1 4.0 1.0 3.00 0.42 2 7.4 1.0 6.40 0.89 3 11.2 1.0 10.20 1.42 4 9.0 1.0 8.00 1.11 5 6.4 1.0 5.40 0.75 6 4.6 1.0 3.60 0.50 7 3.4 1.0 2.40 0.33 8 2.2 1.0 1.20 0.17 9 1.0 1.0 0.00 0.00 Total DRO 40.20 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Jam keQ (m3/dt) DRO UH
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 89 Dalam perencanaan drainase, UH sintetis yang sering kali digunakan untuk memperkirakan limpasan lahan adalah metode SCS 1972. Hidrograf tidak berdimensi SCS (Soil Conservation Services) adalah hidrograf satuan sintetis dimana debit dinyatakan sebagai nisbah debit q terhadap debit puncak qp dan waktu dalam nisbah waktu t terhadap waktu naik dari hidrograf satuan Tp. Jika debit puncak dan waktu keterlambatan dari suatu durasi hujan efektif (lag time) diketahui, maka hidrograf satuan dapat diestimasi dari UH sintetis SCS. T p = waktu dari awal hujan sampai punjak banjir (jam) t p = waktu dari massa hujan sampai debit puncak (jam) → lag time t b = waktu dasar hidrograf satuan tdk berdimensi (jam) untuk hidrograf satuan segitiga t b = 2,67xTp q p = debit puncak (m3/det) A = luas DAS atau lahan (km2) C = 2,08 (SI) atau 483,4 (English system) Gambar 6. 11 Metode SCS hidrograf Tabel 6. 8 SCS dimensionless unit hidrograph ordinates p Tc lagtime(t ) = 0,6 p r p t t Waktu naik T = + 2 _ ( ) p p T CA q = b Tp time _ base(t ) = 5
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 90 Jika suatu DAS seluas 5 km2 diketahui memiliki waktu konsentrasi 15 jam, hitunglah UH sintetis SCS 10 menitan untuk DAS tersebut! Durasi hujan tr = 10 menit = 0,166 jam Lag time tp = 0,6 tc = 0,6 x 15 = 0,9 jam Waktu naik Tp = 0,5 tr + tp = 0,5 x 0,166 + 0,9 = 0,983 jam Debit puncak qp = (2,08 x 5)/0,938 = 10,58 m3/dt.cm Waktu dasar tb = 5 Tp = 5 x 0,983 = 4,915 jam Ordinat hidrograf tdk berdimensi diperoleh dengan mengalikan nilai pada sumbu horisontal dengan Tp dan sumbu vertikal dengan qp. Tabel 6. 9 Perhitungan Tp dan qp Gambar VI.12. UH sintetis SCS 10 menitan untuk DAS Bila diketahui jenis tata guna lahan, panjang lahan, dan kemiringan lahan rata-rata, maka besarnya lag time dapat ditentukan sebagai berikut: = , ( − , ) , , , , Dimana: tt = catchment lag (hours) L = hydrolic length (length measured along principal watercourse) in meters CN = runoff curve number t/Tp t (jam) q/qp q (m3 /dt) t/Tp t (jam) q/qp q (m3 /dt) 0 0.000 0.0000 0.0000 2.6 2.556 0.1070 1.1321 0.2 0.197 0.1000 1.0580 2.8 2.752 0.0770 0.8147 0.4 0.393 0.3100 3.2798 3.0 2.949 0.0550 0.5819 0.6 0.590 0.6600 6.9828 3.2 3.146 0.0400 0.4232 0.8 0.786 0.9300 9.8394 3.4 3.342 0.0290 0.3068 1.0 0.983 1.0000 10.5800 3.6 3.539 0.0210 0.2222 1.2 1.180 0.9300 9.8394 3.8 3.735 0.0150 0.1587 1.4 1.376 0.7800 8.2524 4.0 3.932 0.0110 0.1164 1.6 1.573 0.5600 5.9248 4.2 4.129 0.0100 0.1058 1.8 1.769 0.3900 4.1262 4.4 4.325 0.0070 0.0741 2.0 1.966 0.2800 2.9624 4.6 4.522 0.0030 0.0317 2.2 2.163 0.2070 2.1901 4.8 4.718 0.0015 0.0159 2.4 2.359 0.1470 1.5553 5.0 4.915 0.0000 0.0000 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Jam keQ (m3/dt)
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 91 Y = average catchment land slope in meters per meter Tabel 6. 10 Runoff curve number for urban areas
HYDROGRAPH BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 92 Tugas 8: 1. Gambar dan jelaskan komponen serta langkah-langkah dalam pengembangan dan penerapan metode hidrograf! 2. Gambar dan jelaskan 3 prinsip dasar respon suatu DAS terhadap hujan 3. Jika suatu DAS seluas 5 km2 diketahui memiliki waktu konsentrasi 15 jam, hitunglah UH sintetis SCS 10 menitan untuk DAS tersebut!
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 93 BAB 7 – FLOOD DESIGN Banjir rancangan adalah besarnya debit banjir yang ditetapkan sebagai dasar penentuan kapasitas dan mendimensi bangunan-bangunan hidraulik (termasuk bangunan di sungai), sedemikian hingga kerusakan yang dapat ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung oleh banjir tidak boleh terjadi selama besaran banjir tidak terlampaui. Untuk membuat desain bangunan air seperti pelimpah, diperlukan debit banjir rencana yang realistis. Angka-angka hasil perhitungan hidrologi perlu diuji dengan menggunakan data banjir-banjir besar dari pencatatan atau pengamatan setempat. Dalam hal ini, banjir rencana dibedakan menjadi dua, yaitu: banjir rencana dengan periode ulang tertentu, misal banjir dengan periode ulang 25,100, dan 1000 tahun yang umum dikenal sebagai Q25, Q100, Q1000; dan Banjir Maksimum Boleh jadi (BMB) atau dikenal sebagai “Probable Maximum Flood” (PMF). Untuk pembuatan desain bendungan, pada umumnya diperlukan data banjir dengan kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 tahun dan BMB. Pada tabel VII.1, disajikan patokan banjir desain dan kapasitas pelimpah yang dikutip dari SNI 03,3432-1994, dan pada gambar VII.1 diperlihatkan bagan alir penentuan banjir desain dan kapasitas pelimpah bendungan. Untuk bangunan pengelak, didesain dengan banjir kala ulang 25 tahun, atau kala ulang 10 tahun per setiap tahun pelaksanaaan kontruksi tergantung pada pertimbangan risiko dan biaya pembangunan.
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 94 Tahapan analisis hidrologi untuk banjir rancangan 1. Kasus 2. Output 3. Data tersedia 4. Tahapan analisis 5. 1 6. Debit puncak 7. Debit banjir maks. tahunan 8. Analisis frekuensi data debit 9. 10. 2 11. Debit puncak 12. Hujan harian dan karakteristik daerah tangkapan hujan 13. Analisis frekuensi data hujan dan 14. pengalihragaman hujan-aliran 15. (Rational method) 16. 3 17. Debit puncak 18. Hujan jam-jaman, hidrograf banjir dan karakteristik DAS 19. 20. 21. Analisis frekuensi data hujan dan 22. pengalihragaman hujan-aliran 23. (Unit hydrograph atau Rainfall 24. -runoff model) 25. 4 26. Hidrograf 27. banjir 28. 29. Hujan jam-jaman, karakteristik DAS, tidak ada data hidrograf banjir 30. Analisis frekuensi data hujan dan 31. pengalihragaman hujan-aliran 32. (Synthetic unit hydrograph) 33. 5 34. Hidrograf 35. banjir 36. 37. Hujan jam-jaman dan hidrograf banjir 38. 39. Analisis frekuensi data hujan dan 40. pengalihragaman hujan-aliran 41. (Unit hydrograph) 42. 6 43. Hidrograf 44. banjir 45. 46. Hujan jam-jaman, hidrograf 47. banjir dan karakteristik DAS 48. 49. Analisis frekuensi data hujan dan 50. pengalihragaman hujan-aliran 51. (Unit hydrograph atau Rainfall 52. -runoff model)
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 95 7.1 Design Flood Concept Banjir rancangan umumnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan hidro-ekonomi, yaitu terkait dengan hal-hal berikut ini. a. Urgensi bangunan air terkait dengan resiko kegagalan fungsi bangunan. b. Ekonomi dengan memperhatikan kemampuan penyediaan dana untuk pembuatan bangunan air yang dirancang. Untuk membuat bangunan air dengan resiko kegagalan minimal berarti antisipasi terhadap penyebabnya (termasuk banjir) akan menunjuk pada nilai besaran rancangan yang besar. Konsekuensinya tentu saja biaya pembangunan bangunan air tersebut mahal, karena harus menyediakan fasilitas antisipasi kerusakan/kegagalan fungsi bangunan dengan dimensi atau kekuatan yang cukup besar. Akan tetapi bangunan tersebut mempunyai resiko kerugian/dampak akibat kegagalan yang kecil. Besar kecilnya nilai banjir rancangan ditunjukkan dengan nilai kala ulang (return period) dari banjir yang dipilih sebagai banjir rancangan. Dalam hal ini apabila dikehendaki resiko kegagalan bangunan yang dirancang cukup kecil akan menunjuk nilai kala ulang banjir rancangan yang besar. Apabila dikaitkan dengan faktor resiko kegagalan dan harapan kurun waktu bangunan yang akan dibangun dapat berfungsi dengan baik (umur efektif), maka dapat digunakan rumus sederhana berikut ini. dengan: R = resiko kegagalan, T = kala ulang (tahun), L = umur efektif bangunan/proyek (tahun).
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 96 Berikut disajikan tabel pedoman umum yang dapat dijadikan pertimbangan awal dalam menetapkan nilai kala ulang debit banjir rancangan untuk bangunan air yang digunakan Departeman Pekerjaan Umum untuk berbagai bangunan di sungai (Srimoerni Doelchomid, 1987). Tabel 7. 1 Kala ulang banjir rancangan untuk bangunan di sungai Jenis bangunan Kala ulang banjir rancangan (tahun) Bendung sungai besar sekali 100 Bendung sungai sedang 50 Bendung sungai kecil 25 Tanggul sungai besar/daerah penting 25 Tanggul sungai kecil/daerah kurang penting 10 Jembatan jalan penting 25 Jembatan jalan tidak penting 10 Penetapan kala ulang banjir rancangan Besarnya banjir rancangan dinyatakan dalam debit banjir sungai dengan kala ulang tertentu. Kala ulang debit adalah suatu kurun waktu berulang dimana debit yang terjadi menyamai atau melampaui besarnya debit banjir yang ditetapkan (banjir rancangan). Sebagai contoh adalah apabila ditetapkan banjir rancangan dengan kala ulang T tahun, maka dapat diartikan bahwa probabilitas kejadian debit banjir yang sama atau melampaui dari debit banjir rancangan setiap tahunnya rata-rata adalah sebesar 1/T. Pernyataan tersebut dapat pula dikatakan bahwa periode ulang rata-rata kejadian debit banjir sama atau melampaui debit banjir rancangan adalah sekali setiap T tahun. Misal diketahui debit banjir rencana di lokasi tertentu pada sungai X untuk kala ulang T tahun adalah QT m3/dt. Pernyataan ini berarti bahwa nilai rerata rentang waktu perulangan kejadian kejadian dimana debit sungai X lebih besar atau sama dengan QT m3/dt adalah T tahun. Secara grafis penjelasan tentang pengertian kala ulang tersebut dapat dilukiskan dalam Gambar VII.1. Yang perlu dipahami adalah bahwa pengertian tersebut tidak berarti debit banjir yang lebih besar atau sama dengan QT akan terjadi setiap T tahun sekali. Gambar 7. 1 Grafik ilustrasi pengertian kala ulang Gambar VII.1 menyajikan contoh grafik nilai debit banjir maksimum tahunan pada suatu lokasi tertentu sebuah sungai X selama 20 tahun. Misal akan ditinjau nilai kala ulang debit banjir sebesar 50 m3/dt, maka dapat ditarik garis mendatar pada nilai debit banjir tersebut. Selanjutnya dapat dihitung/diamati rentang waktu kejadian dimana debit banjir sama atau lebih dari 50 m3/dt. Dari gambar di atas dapat dicermati bahwa probabilitas nilai rerata rentang waktu perulangan kejadian dimana debit banjir sungai X sama atau melampaui 50 m3/dt adalah 1,73 tahun. Dengan kata lain nilai debit banjir dengan kala ulang 1,73 tahun adalah sebesar 50 m3/dt.
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 97 Pemilihan besarnya kala ulang banjir rancangan untuk setiap jenis bangunan tidak terdapat kriteria dan pedoman yang definitif. Kala ulang tersebut harus dapat menghasilkan rancangan yang memuaskan (Sri Harto, 1993), dalam arti bahwa bangunan hidraulik yang dibangun masih harus dapat berfungsi dengan baik minimal selama waktu yang ditetapkan (umur efektif), baik struktural maupun fungsional. Pengambilan keputusan dalam menetapkan kala ulang banjir rancangan paling tidak harus didasarkan pada hasil analisis ekonomi (benefit cost analysis) sebagai salah satu pertimbangan non-teknis. Untuk analisis yang lengkap dan rinci debit banjir rancangan ditetapkan berdasarkan pertimbangan beberapa hal berikut: a) ukuran dan jenis proyek, b) ketersediaan data, c) ketersediaan dana, d) kepentingan daerah yang dilindungi, e) resiko kegagalan yang dapat ditimbulkan, f) kadang bahkan juga kebijaksanaan politik. Dalam praktek perancangan bangunan air, penetapan nilai T dapat mengikuti standar perancangan yang berlaku. Apabila belum tersedia pedoman yang spesifik dan pertimbangan ekonomi dipandang lebih dominan, maka pembuat keputusan dapat menempuh pendekatan analisis ekonomi teknik dengan masukan hitungan hidrologi. Sajian grafis di bawah ini merupakan ilustrasi sedehana tentang penetapan nilai kala ulang banjir rancangan dengan pendekatan tersebut. Gambar 7. 2 Penentuan kala ulang banjir rancangan secara hidro-ekonomi Gambar diatas menunjukkan prosedur penetapan nilai kala ulang banjir rancangan (T) yang optimal, yaitu nilai kala ulang banjir yang menghasilkan jumlah biaya pembangunan minimal. Dalam hal ini jumlah biaya pembangunan yang diperhitungkan tidak hanya biaya konstruksi, tetapi juga biaya yang harus disediakan akibat kegagalan fungsi bangunan dengan memperhitungkan resiko (probabilitas) kejadian banjir yang melampaui nilai banjir rencana, dinatakan sebagai komponen risk cost. 7.2. Design Flood Analysis Dalam praktek analisis hidrologi terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menetapkan debit banjir rancangan. Masing-masing cara akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut (Sri Harto, 1993): a) ketersediaan data, b) tingkat ketelitan yang dikehendaki, c) kesesuaian cara dengan DAS yang ditinjau. Keluaran analisis hidrologi untuk penentuan banjir rancangan tergantung dari kasus yang ditinjau. Pada perancangan bendung irigasi atau sistem drainasi areal pemukiman yang tidak terlalu luas, hasil analisis yang diinginkan berupa debit banjir maksimum (peak discharge). Pada perancangan tanggul sungai atau bangunan pelimpah waduk, hasil analisis tidak cukup debit maksimum dari banjir rancangan, akan tetapi diperlukan pula hidrograf
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 98 banjir rancangan. Untuk perancangan kantong banjir (detention pond), selain hidrograf banjir juga dikehendaki nilai volume hidrograf banjir rancangan. Dapat dimengerti bahwa prosedur analisis hidrologi untuk penetapan banjir rancangan tergantung dari keluaran analisis yang diinginkan (peak discharge, flood hydrograph atau volume of flood hydrograf) dan ketersediaan data yang dapat digunakan dalam proses hitungan. Mengingat kembali pengertian konsep kala ulang, semua prosedur analisis tersebut akan selalu melalui tahap pendekatan statistik, yaitu analisis frekuensi data hujan atau data debit. Prosedur keseluruhan dalam analisis dapat dikelompokkan menjadi tiga metode pendekatan (Gupta, 1967), yaitu: a. cara empirik, b. cara statistik, c. analisis dengan model hidrologi. Cara mana yang dapat ditempuh akan tergantung dari ketersediaan data dan keluaran analisis yang dikehendaki sebagai besaran rancangan untuk pembuatan bangunan air. Yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan rumus empiris yang dikembangakn di wilayah/DAS yang kondisi klimatologi atau morfometri yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi yang kita jumpai di lokasi analisis. Untuk hal ini konversi atau penyesuaian nilai tetapan (koefisien, konstanta, parameter dll.) dalam rumus tersebut mutlak diperlukan. Secara umum, prosedur analisis hidrologi untuk masalah banjir rancangan dapat dikelompokkan berdasarkan kasus yang dijumpai seperti disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 7. 2 Tahapan analisis hidrologi untuk banjir rancangan 53. Kasus 54. Output 55. Data tersedia 56. Tahapan analisis 57. 1 58. Debit puncak 59. Debit banjir maks. tahunan 60. Analisis frekuensi data debit 61. 2 62. Debit puncak 63. Hujan harian dan karakteristik daerah tangkapan hujan 64. Analisis frekuensi data hujan dan 65. pengalihragaman hujanaliran 66. (Rational method) 67. 3 68. Debit puncak 69. Hujan jam-jaman, hidrograf banjir dan karakteristik DAS 70. 71. 72. Analisis frekuensi data hujan dan 73. pengalihragaman hujanaliran 74. (Unit hydrograph atau rainfall 75. -runoff model) 76. 4 77. Hidrograf 78. banjir 79. 80. Hujan jam-jaman, karakteristik DAS, tidak ada data hidrograf banjir 81. Analisis frekuensi data hujan dan 82. pengalihragaman hujanaliran 83. (Synthetic unit hydrograph) 84. 5 85. Hidrograf 86. banjir 87. 88. Hujan jam-jaman dan hidrograf banjir 89. 90. Analisis frekuensi data hujan dan 91. pengalihragaman hujanaliran 92. (Unit hydrograph) 93. 6 94. Hidrograf 95. banjir 96. 97. Hujan jam-jaman, hidrograf 98. banjir dan karakteristik DAS 99. 100. Analisis frekuensi data hujan dan 101. pengalihragaman hujanaliran 102. (Unit hydrograph atau rainfall
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 99 103. -runoff model) Kasus 1: Analisis frekuensi data debit banjir maksimum Pada kasus 1 prosedur analisis paling sederhana, karena langsung dengan hitungan statistik berdasarkan data debit ekstrim (maksimum) yang tercatat di lapangan. Memperhatikan syarat panjang data, cara ini akan dianggap valid apabila tersedia data minimal 20 catatan debit banjir maksimum (20 tahun). Rangkaian data ini disebut dengan annual maximum series. Namun kondisi tersebut umumnya jarang dapat dijumpai, sehingga dapat ditempuh pendekatan dengan mengumpulkan beberapa kejadian banjir ekstrim setiap tahunnya. Dengan memperhatikan distribusi nilai debit banjir, dapat pula dijumpai nilai debit banjir maksimum suatu tahun tertentu jauh di bawah nilai debit banjir maksimum kedua dari taahun yang lain. Hal ini juga dapat menimbulkan keraguan akan hasil analisis statistik. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun data partial duration series atau annual exeedence series. Partial duration series didapat dengan menetapkan batas minimum nilai debit banjir maksimum sebagai threshold. Selanjutnya debit banjir maksimum yang lebih besar dari batas tersebut digunakan sebagai masukan prosedur anaalisis frekuensi. Annual exeedence series didapat dengan cara yang sama dengan penetapan partial duration series, hanya saja nilai threshold ditetapkan sedemekian hingga data terpakai jumlahnya sama dengan jumlah tahun data. Apabila data yang digunakan untuk analisis frekuensi bukan annual maximum series, maka perlu diperhatikan bahwa sifat independency antar data sangat mungkin tidak dipenuhi. Untuk itu rumus hubungan antara nilai kala ulang untuk data annual maximum series (T) dan nilai kala ulang untuk data partial duration series atau annual exceedence series (TE) di bawah ini dapat digunakan untuk menetapkan nilai kala ulang yang seharusnya ditetapkan. Kasus 2: Analisis frekuensi data hujan dan pengalihragaman hujan-aliran metode rational Pada kasus 2 prosedur analisis melalui dua tahap, yaitu analisis frekuensi data hujan untuk mendapatkan data hujan harian maksimum dengan kala ulang sama dengan kala ulang debit banjir maksimum yang diinginkan dan selanjutnya adalah pengalihragaman hujan menjadi aliran. Prinsip mengacu pada asumsi bahwa kala ulang hujan sama dengan kala ulang debit, yang sesungguhnya sampai saat ini secara ilmiah belum dapat dibuktikan kepastian/kebenaarannya. Metode yang umum dijumpai adalah dengan rumus empiris hubungan hujan-aliran seperti rumus Rasional berikut ini. dengan: QT : debit maksimum dengan kala ulang T tahun, C : koefisien aliran permukaan, IT : intensitas hujan dengan kala ulang T tahun, A : luas daerah tangkapan hujan. Memperhatikan rumus di atas, maka diperlukan penetapan nilai intensitas hujan yang dianggap mewakili kondisi saat terjadinya debit maksimum. Untuk itu diperlukan informasi karakteristik hujan di lokasi yang ditinjau berupa kurva yang menunjukkan hubungan antara intensitas, durasi dan ala ulang hujan (IDF). Kurva ini dapat dibuat dengan beberapa rumus empiris, antara lain yang cukup dikenal terapan di Indonesia adalah rumus Mononobe sebagai berikut:
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 100 dengan: : intensitas curah hujan pada durasi t untuk kala ulang T tahun (mm/jam), t : durasi curah hujan (jam), : curah hujan harian maksimum dengan kala ulang T tahun (mm). Nilai durasi hujan (t) yang memberikan debit maksimum dianggap sama dengan nilai waktu konsentrasi (tc). Nilai tc tergantung dari karakteristik aliran permukaan dan aliran di alur/sungai, yaitu merupakan nilai maksimum dari jumlah waktu aliran air mulai dari ujung daerah tangkapan ke ujung alur dan waktu aliran sepanjang alur. Beberapa rumus empiris perkiraan nilai tc dapat digunakan sesuai dengan kondisi permukaan aliran dan topografi. Berikut disajikan contoh kurva IDF hasil pengolahan data curah hujan di stasiun Duri, propinsi Riau. Tabel 7. 3 Contoh intensitas hujan dengan kala ulang 5, 10 dan 25 tahun t (menit) I t pada beberapa kala ulang (mm/jam) 5 tahun 10 tahun 25 tahun 5 238.28 270.80 314.41 10 150.11 170.59 198.06 15 114.56 130.19 151.15 20 94.56 107.47 124.77 45 55.07 62.59 72.67 60 45.46 51.67 59.98 120 28.64 32.55 37.79 180 21.86 24.84 28.84 360 13.77 15.65 18.17 720 8.67 9.84 11.44 Gambar 7. 3 Kurva IDF di Duri dengan kala ulang 5, 10 dan 25 tahun Data hujan yang digunakan disusun dengan cara partial duration series seperti ditunjukkan pada table VII.4.
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 101 Tabel 7. 4 Data partial duration series hujan harian di Duri No. Year Recorded daily rainfall (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1992 1992 1993 1994 1995 1995 1995 1996 1996 1997 1999 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 81.0 92.0 117.0 140.5 103.2 99.7 95.4 105.1 91.5 88.0 115.2 98.6 176.7 97.0 158.0 148.5 156.7 99.0 90.0 108.2 Penggunaan rumus Rasional di atas mengandung asumsi bahwa hidrograf aliran banjir berbentuk segitiga simetri dengan waktu naik mencapai debit puncak (rising limb) dan waktu pada sisi resesi sama, yaitu sebesar waktu konsentrasi (tc) seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hujan rancangan terjadi pada intensitas tetap dengan durasi (alama kejadian) sama dengan tc. Gambar 7. 4 Tipikal bentuk hidrograf banjir cara Rasional Dalam hal tertentu, besaran rancangan yang diinginkan terkait dengan rencana pengendalian banjir bukan hanya nilai debit maksimum, akan tetapi besarnya volume tampungan aliran banjir. Sebagai contoh adalah perancangan bangunan pengendali banjir berupa tampungan daerah retensi banjir (detention storage) yang berfungsi sebagai peredam aliran banjir. Perubahan tataguna lahan suatu DAS akibat proses pembangunan yang kurang atau tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan perubahan bentuk hydrograph yang berarti juga perubahan nilai debit maksimum. Untuk melakukan antisipasi dampak negatif di areal hilir DAS akibat perubahan debit maksimum tersebut, salah satu cara yang mungkin adalah dengan membangun detention storage yang dilengkapi bangunan outlet untuk mengendalikan aliran keluar dari tampungan banjir ini. Dalam kasus ini dapat dirancang misalnya dengan ketentuan bahwa debit maksimum yang
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 102 keluar dari detention storage tidak boleh lebih besar dari nilai debit maksimum sebelum terjadinya perubahan tataguna lahan. Untuk keperluan perancangan sebuah detention storage diperlukan besaran rancangan berupa kapasitas volume tampungan yang nilainya tergantung dari hidrograf banjir pada kedua kondisi (sesudah ada perubahan tataguna lahan dan kondisi yang diinginkan dengan tingkat peredaman debit puncak tertentu). Pada prinsipnya, volume tampungan yang diperlukan merupakan selisih volume kedua hidrograf tersebut. Untuk itu perlu dihitung durasi hujan kritik, yaitu durasi hujan yang memberikan nilai volume tampungan maksimum. Nilai durasi hujan kritik dapat ditentukan dengan menggunakan modifikasi rumus Rasional. Kasus 3: Analisis frekuensi data hujan dan pengalihragaman hujan-aliran metode hidrograf satuan atau model hidrologi hujan-aliran Prosedur analisis penetapan banjir rancangan untuk kasus 3 mirip dengan kasus 2, yaitu melalui dua tahap: analisis frekuensi data hujan untuk mendapatkan data hujan harian maksimum dengan kala ulang sama dengan kala ulang debit banjir maksimum yang diinginkan dan selanjutnya adalah pengalihragaman hujan menjadi aliran. Perbedaan dengan kasus 2 adalah dalam hal ini tersedia data hujan jam-jaman dan hidrograf banjir yang akibat hujan jam-jaman tersebut, yang berarti rumusan hubungan antara hujan dan aliran dapat ditentukan dengan memanfaatkan pasangan data hidrologi ini (hujan dan hidrograf banjir). Dengan prinsip ini hasil perkiraan debit banjir akan lebih teliti dibandingkan pada kasus 2. Untuk kondisi ini, tersedia 2 macam metode pengalihragaman hujan menjadi aliran, yaitu menggunakan pendekatan teori hidrograf satuan atau model hujan aliran yang dirumuskan secara konseptual berdasarkan kaidah proses daur hidrologi dan mengikuti proses detil di dalamnya (evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, limpasan permukaan, interlow dan baseflow). Pendekatan hidrograf satuan lebih sederhana, karena tidak memerlukan data fisik DAS dan hitungan rinci pada semua proses daur hidrologi. Penggunaan model hidrologi memerlukan data yang kompleks dan prosedur kalibrasi yang seringkali menjadi rumit. Akan tetapi penggunaan model juga ada keuntungannya, yaitu apabila diinginkan perkiraan perubahan debit banjir akibat perubahan sifat fisik DAS, misal perubahan tataguna lahan. Dengan model hidrologi masukan data yang digunakan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi DAS tersebut, yang berarti keluaran model berupa debit banjir tentunya juga akan mampu menunjukkan perubahan besarnya puncak banjir. Apabila digunakan cara hidrograf satuan, maka penentuan hidrograf satuan yang dilakukan adalah cara analitis. Algoritme yang mungkin digunakan adalah cara persamaan polynomial, Collins (successive approximation) dan cara matriks. Ketiga cara tersebut menggunakan prinsip sama, yaitu mencari hidrograf aliran langsung (direct runoff) akibat hujan efektif (hujan yang telah dikurangi losses) merata di DAS dengan durasi dan tinggi/kedalaman tertentu (satu satuan, missal 1 mm/jam). Cara analitis diilustrasikan pada Gambar VII.5 dan 6. Jika digunakan metode persamaan polynomial maka hitungan hidrograf satuan cara analitis dapat ditempuh dengan urutan sebagai berikut ini. 1. Pilih data hujan jam-jaman dan hidrograf aliran terukur di sungai. 2. Pisahkan baseflow dan hidrograf limpasan langsung (HLL). 3. Tetapkan nilai losses tetap (Φindeks) dan hujan efektif jam-jaman. 4. Dengan prinsip superposisi, linear time invariant dan constant base time, dapat disusun persamaan polinomial untuk menentukan hidrograf satuan.
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 103 Gambar 7. 5 Karakter DAS dan intensitas hujan Gambar 7. 6 Skema hitungan hidrograf satuan cara analitis Dalam praktek hitungan, dengan cara persamaan polinomial sangat jarang sekali dapat diperoleh hasil yang baik dan akurat. Hal ini disebabkan ketelitian pengukuran data
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 104 terutama data debit yang mengandung banyak kesalahan (umumnya hanya konversi dari data AWLR menjadi debit menggunakan persamaan Rating Curve). Selain itu juga tidak sepenuhnya anggapan dasar teori hidrograf satuan berlaku pada kejadian proses hidrologi di alam yang sebenarnya. Alternatif lain cara yang dapat digunakan adalah metode Collins dengan prinsip successive approximation. Tahapan penentuan hidrograf satuan metode Collins adalah sebagai berikut ini. 1. Pilih data hujan jam-jaman dan hidrograf aliran terukur di sungai. 2. Pisahkan baseflow dan hidrograf limpasan langsung (HLL). 3. Tetapkan nilai losses tetap (Φindeks) dan hujan efektif jam-jaman. 4. Tetapkan sebuah hidrograf satuan perkiraan awal (UH-1). 5. Tentukan hidrograf limpasan langsung akibat hujan efektif jam-jaman kecuali untuk hujan terbesar. 6. Jumlahkan semua hidrograf limpasan langsung ini dan hasilnya kurangkan dengan hidrograf limpasan langsung terukur. Selisih hidrograf limpasan langsung yang didapatkan dibagi dengan hujan efektif jam-jaman yang maksimum. Hasilnya adalah hidrograf satuan baru (UH-2). 7. Hitung rerata UH-1 dan UH-2 sebagai UH-3, amati apakah cukup dekat dengan UH-1. 8. Apabila masih belum cukup dekat, ulangi langkah (4) sampai dengan (7) dengan mengambil UH-3 sebagai hidrograf satuan perkiraan awal yang baru. Prosedur ini diulang sampai didapatkan hasil UH-3 yang cukup dekat dengan UH-1. Kasus 4: Analisis frekuensi data hujan dan pengalihragaman hujan-aliran metode hidrograf satuan sintetik Pada ketiga kasus sebelumnya, keluaran analisis adalah debit banjir maksimum. Pada kasus ini hasil analisis banjir rancangan yang diinginkan tidak hanya nilai debit banjir maksimum, tetapi juga debit pada jam-jam yang lain yang dinyatakan dalam hidrograf banjir rancangan (design flood hydrograph). Data tersedia hanya hujan jam-jaman dan karakteristik DAS, sehingga prosedur analisis melalui dua tahap, yaitu analisis frekuensi data hujan dan pengalihragaman hujan menjadi aliran dengan mengunakan metode hidrograf satuan sintetik (synthetic unit hydrograph). Beberapa teori hidrograf satuan sintetik yang dikenal adalah cara Snyder, SCS, Nakayasu, Clark, Modified Clark dan Hidrograf Satuan Sintetik Gama I (HSS Gama I). Menegaskan kembali uraian terdahulu tentang validitas metode empiris dalam analisis banjir, maka penulis menyarankan apabila tidak ada dukungan informasi atau studi yang mendukung keyakinan pengunaan beberapa metode tersebut, sebaiknya digunakan cara HSS Gama I yang memang dikembangkan dan telah diuji keberlakuannya untuk beberapa DAS di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera oleh penemunya (Prof.Dr.Ir. Sri Harto Br., Dip.H). Perbedaan dengan kasus 3, untuk kondisi tidak ada data debit terukur adalah penentuan hidrograf satuan menggunakan pendekatan empiris dengan hidrograf satuan sintetik. Pada Gambar VII.7. disajikan bagan prosedur analisis hitungan banjir rancangan menggunakan metode hidrograf satuan. Prosedur pada tahap 2A berlaku untuk kasus 4 dimana digunakan cara hidrograf satuan sintetik. Untuk kasus 3, 5 atau 6 berlaku prosedur tahap 2B, yaitu menggunakan pasangan data hujan jam-jaman dan debit banjir jam-jaman tercatat untuk menurunkan hidroraf satuan secara analistis (cara Collins). Pada proses pengalihragaman hujan menjadi aliran diperlukan data hujan jam-jaman. Untuk hitungan banjir rancangan seharusnya distribusi hujan jam-jaman yang digunakan didasarkan pada pola distribusi hujan yang berlaku pada DAS yang ditinjau. Akan tetapi umumnya pola distribusi hujan jam-jaman ini sulit didapatkan, dimana hitungan untuk mendapatkannya memerlukan data hujan jam-jaman terukur yang cukup panjang dengan kualitas yang memadai. Untuk mengatasi persoalan tersebut dapat digunakan beberapa pendekatan empiris dalam menetapkan durasi dan distribusi hujan jam-jaman pada suatu
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 105 DAS. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain adalah cara Tadashi Tanimoto dan metode Alternating Block Method (ABM). Kedua metode tersebut memerlukan nilai durasi hujan rancangan yang dapat didekati dengan nilai waktu konsentrasi (tc). Tabel VII.5 menyajikan beberapa rumus empiris untuk perkiraan nilai tc berdasarkan karakteristik DAS dari sumber Applied Hydrology (Vent e Chow, 1992). Gambar 7. 7 Tahapan hitungan hidrograf banjir rancangan metode hidrograf satuan Tabel 7. 5 Beberapa rumus empiris hitungan waktu konsentrasi
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 106 Kasus 5: Analisis frekuensi data hujan dan pengalihragaman hujan-aliran metode hidrograf satuan Pada kasus ini prosedur analisis sama dengan pada kasus tiga, hanya saja keluaran yang diinginkan adalah hidrograf banjir rancangan bukan hanya debit banjir maksimumnya saja. Karena tidak tersedia data karakteristik DAS maka penggunaan model hidrologi hujanaliran tidak memungkinkan. Untuk itu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan cara hidrograf satuan analitis. Apabila data hujan jam-jaman tersedia cukup panjang dapat dilakukan analisis distribusi hujan jam-jaman. Hasil analisis ini adalah pola distribusi hujan jam-jaman yang berlaku pada DAS yang ditinjau, sebagai dasar penetapan distribusi hujan jam-jaman untuk input hitungan hidrograf banjir rancangan. Setelah analisis frekeunsi data hujan dilakukan akan diperoleh hujan harian maksimum dengan kala ulang sesuai dengan kala ulang banjir rancangan yang akan dicari. Hujan harian rancangan ini selanjutnya didsitribusikan kedalam hujan jam-jaman dengan pola atau prosentase ditetapkan berdasarkan pola distribusi hujan jam-jaman hasil analisis sebelumnya. Kasus 6: Analisis frekuensi data hujan dan pengalihragaman hujan-aliran metode hidrograf satuan atau model hidrologi Pada kasus ini data tersedia lebih lengkap dari pada kasus 5, yaitu juga tersedia data karakteristik DAS. Dengan demikian model hidrologi hujan-aliran dapat digunakan untuk melakukan simulasi hidrograf banjir dengan masukan hujan jam-jaman pada kala ulang banjir rancangan yang diinginkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan model hidrologi hujan-aliran adalah model mateatik yang mampu merepresentasikan proses alam yang terjadi di DAS akibat masukan berupa hujan. Model hujan-aliran selalu memerlukan data masukan. Dalam pembuatan model hujanaliran sebagian besar telah dilaksanakan dengan ujud model digital untuk kemudahan proses hitungan simulasi hujan-aliran. Beberapa model yang umum digunakan adalah: Tank Model dari Jepang, HEC-1 dari Corps of Engineers USA, TR-20 dari Soil Conservation Service USA, API dari USA, SWM-IV dari Uniersitas Standford, KWM dari USA, SSARR dari Corps of Engineers USA, HEC-HMS dan masih banyak model yang lain. Pada pelatihan ini akan diberikan uraian singkat tentang model HEC-HMS dengan contoh sederhana penggunaannya. Mengingat keterbatasan waktu yan tersedia, maka materi yang diberikan lebih bersifat untuk pengenalan model HEC-HMS.
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 107 7.2.1. Hujan Maksimum Rencana Periode hujan, intensitas, dan luas sebaran hujan mempengaruhi laju volume aliran permukaan. Jumlah aliran permukaan dari suatu hujan tergantung dari lamanya hujan pada intensitas tertentu. Hujan maksimum rencana dengan berbagai periode ulang diperoleh melalui suatu analisis data curah hujan yang akan dipergunakan untuk menentukan besaran debit banjir rencana dengan kala ulang tertentu. Untuk perhitungan hujan maksimum rencana dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut: a. Metode Gumbel b. Metode Haspers c. Metode Log Pearson Tipe III a. Metode Gumbel Hujan maksimum rencana untuk menentukan debit banjir rencana adalah curah hujan maksimum dengan periode ulang tertentu berdasarkan data hujan selama 24 jam maksimum. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: XT = X +S.K = = n i 1 Xi n 1 X n 1 X X X S n i 1 n i 1 i 2 i − − = = = n T n S Y Y K − = − = − − T T 1 YT ln ln dimana: XT = Besarnya curah hujan rencana untuk periode ulang T tahun (mm) X = Besarnya curah hujan rata-rata (mm) S = Standard deviasi K = Faktor frekwensi YT = Reduced variate, lihat Tabel VII.6 Yn = Reduce mean (fungsi dan banyaknya data, lihat Tabel VII.7) Sn = Reduce standard deviation (fungsi dan banyaknya data n, lihat Tabel VII.8) n = Jumlah data Tabel 7. 6 Reduced variate ( yt), metode Gumbel Periode Ulang (tahun) Reduced variate (YT) 2 5 10 25 50 100 0.3665 1.4999 2.2502 3.1985 3.9019 4.6001
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 108 Tabel 7. 7 Reduced mean (yn), metode Gumbel n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 0.4952 0.5236 0.4996 0.5252 0.5035 0.5268 0.5070 0.5282 0.5100 0.5296 0.5128 0.5309 0.5157 0 5320 0.5181 0.5332 0.5202 0.5343 0.5220 0.5353 30 0.5362 0.5371 0.5380 0.5388 0.5396 0.5403 0.5410 0.5418 0.5424 0.5430 40 0.5436 0.5442 0.5548 0.5453 0.5458 0 5463 0 5468 0.5473 0.5477 0.5481 50 0.5485 0.5489 0.5493 0.5497 0.5501 0.5504 0.5508 0.5511 0.5515 0.5518 60 0.5521 0.5524 0 5527 0.5530 0.5533 0.5535 0.5538 0.5540 0.5543 0.5545 70 80 0.5548 0.5569 0 5550 0.5570 0.5552 0.5572 0.5555 0.5574 0.5557 0.5576 0.5559 0.5578 0.5561 0.5580 0.5563 0.5581 0.5565 0.5583 0.5567 0.5585 90 0.5586 0 5587 0.5589 0.5591 0.5592 0.5593 0.5595 0.5596 0.5598 0.5599 100 0.5600 Tabel 7. 8 Reduced standard deviation (sn), metode Gumbel n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.9496 0.9697 0.9833 0.9971 1.0095 1.0206 1.0316 1 0411 1.0494 1 0565 20 1.0628 1.0695 1.0755 1.0812 1.0865 1.0915 1.0961 1.1004 1.1047 1.1086 30 1.1124 1.1159 1.1193 1.1226 1.1255 1.1285 1.1313 1.1339 1.1363 1.1388 40 1.1413 1.1436 1.1458 1.1480 1.1499 1.1519 1.1538 1.1557 1.1574 1.1590 50 1.1607 1.1623 1.1638 1.1653 1.1667 1.1681 1.1696 1.1708 1.1721 1.1734 60 1.1747 11759 1.1770 1.1782 1.1793 1.1803 1.1814 1.1824 1.1834 1.1844 70 1.1854 1.1863 11873 1.1881 1.1890 1.1898 1.1906 1.1915 1.1923 1.1930 80 1.1938 1.1945 1.1953 1.1960 1.1967 1.1973 1.1980 1.1987 1.1994 1.2001 90 1.2007 1.2013 1.2020 1.2026 1.2032 1.2038 1.2044 1.2049 1.2055 1 2060 100 1.2065 b. Metode Haspers Persamaan yang digunakan dalam perhitungan curah hujan maksimum dengan menggunakan metode Haspers adalah sebagai berikut: RT = Ra + S UT dimana: RT = hujan maksimum dengan periode ulang T tahun Ra = hujan maksimum rata-rata S = Standart Deviasi UT = Standart variabel untuk periode ulang T tahun. Persamaan untuk menghitung standart deviasi adalah: − + − = 2 2 a 1 1 a U R R U R R S ½ dimana : R1 = hujan absolut maksimum ke 1 R2 = hujan absolut maksimum ke 2 Um = standar variabel untuk periode ulang tm tahun tm = m n+1 n = jumlah tahun pengamatan m = rank (m = 1, 2) Standar variabel (U) untuk periode ulang T tahun yang akan dipakai dalam perhitungan, dapat dilihat dalam tabel VII.9. di bawah ini:
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 109 Tabel 7. 9 Standar variabel (u) untuk return periode (T) T U T U T U T U T U T U 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 -1.85 -1.35 -1.28 -1.23 -1.19 -1.15 -1.12 -1.07 -1.02 -0.93 -0.85 -0.79 -0.73 -0.68 -0.63 -0.54 -0.46 -0.40 -0.33 -0.28 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 6.80 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 9.00 -0.22 -0.13 -0.04 0.04 0.11 0.17 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.55 0.64 0.73 0.81 0.88 0.95 1.01 1.06 1.17 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 1.26 1.35 1.43 1.50 1.57 1.68 1.69 1.74 1.80 1.85 1.89 1.94 1.98 2.02 2.06 2.10 2.13 2.17 2.19 2.24 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.41 2.44 2.47 2.49 2.51 2.54 2.56 2.59 2.61 2.63 2.65 2.67 2.69 2.71 2.73 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 2.75 2.79 2.83 2.86 2.90 2.93 2.96 2.99 3.02 3.05 3.08 3.11 3.13 3.16 3.18 3.21 3.23 3.26 3.28 3.29 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100 110 120 130 140 3.33 3.35 3.37 3.39 3.41 3.43 3.53 3.63 3.70 3.71 c. Metode Log Pearson Tipe III Persamaan rumus yang digunakan untuk distribusi Log Pearson Tipe III adalah: 1. Harga rata-rata (Log X) n LogXi LogX n i 1 = = 2. Standart deviasi (Sx) ( ) n 1 LogXi LogX Sx n i 1 2 − − = = 3. Koefisien kemiringan sample (Cs) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 n i 1 3 n 1 n 2 Sx LogXi LogX Cs − − − = = 4. Logaritma curah hujan (Log Xt) → Log Xt = Log X + K . Sx 5. Hujan rencana (Xt). Hujan rencana dengan periode ulang (T) tahun (Xt) diperoleh dengan mencari antilog dari nilai Log Xt. Keterangan: Cs = koefisien kemiringan sample K = faktor frekuensi dimana nilai K tergantung dari nilai (Cs) yang diperoleh dari tabel 7-5 Log X = hujan rata-rata (mm) Log Xt = logaritma curah hujan (mm) Log Xi = hujan maksimum (mm) Xt = hujan rencana (mm) n = jumlah tahun pengamatan Sx = standar deviasi
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 110 Tabel 7. 10 Koefisien kemiringan sample (Cs) Koefisien Cs Waktu balik dalam tahun 2 5 10 25 50 100 Peluang (%) 50 20 10 4 2 1 3.0 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.2 -2.5 -3.0 -0.396 -0.360 -0.330 -0.307 -0.282 -0.254 -0.225 -0.195 -0.164 -0.148 -0.132 -0.116 -0.099 -0.083 -0.066 -0.050 -0.033 -0.017 0 0.017 0.033 0.050 0.066 0.083 0.099 0.116 0.132 0.148 0.164 0.195 0.225 0.254 0.282 0.307 0.330 0.360 0.396 0.420 0.518 0.574 0.609 0.643 0.675 0.705 0.732 0.758 0.769 0.780 0.790 0.800 0.808 0.816 0.824 0.830 0.836 0.842 0.836 0.850 0.853 0.855 0.856 0.857 0.857 0.856 0.854 0.852 0.844 0.832 0.817 0.799 0.777 0.752 0.711 0.636 1.180 1.250 1.284 1.302 1.318 1.329 1.337 1.340 1.340 1.339 1.336 1.333 1.328 1.323 1.317 1.309 1.301 1.292 1.282 1.270 1.258 1.245 1.231 1.216 1.200 1.183 1.166 1.147 1.128 1.086 1.041 0.994 0.945 0.895 0.844 0.771 0.660 2.278 2.262 2.240 2.219 2.193 2.163 2.128 2.087 2.043 2.018 1.998 1.967 1.939 1.910 1.880 1.849 1.818 1.785 1.751 1.716 1.680 1.643 1.606 1.567 1.528 1.488 1.448 1.407 1.366 1.282 1.198 1.116 1.035 0.959 0.888 0.793 0.666 3.152 3.048 2.970 2.912 2.848 2.780 2.706 2.626 2.542 2.498 2.453 2.407 2.359 2.311 2.261 2.211 2.159 2.107 2.054 2.000 1.945 1.890 1.834 1.777 1.720 1.663 1.606 1.549 1.492 1.379 1.270 1.166 1.069 0.980 0.900 0.798 0.666 4.051 3.845 3.705 3.605 3.499 3.388 3.271 3.149 3.022 2.957 2.891 2.824 2.755 2.686 2.615 2.544 2.472 2.400 2.326 2.252 2.178 2.104 2.029 1.955 1.880 1.806 1.733 1.660 1.588 1.449 1.318 1.197 1.087 0.990 0.905 0.799 0.667 7.2.2 Banjir Rencana Banjir rencana (design flood) adalah debit maksimum di sungai atau saluran alami dengan periode ulang tertentu. Debit banjir rencana dengan periode ulang (T) tahun dinotasikan dengan huruf "QT". Banjir rencana dengan kala ulang tahun (QT) adalah besaran banjir yang diperkirakan dapat disamai atau dilampaui sekali atau lebih dalam waktu ulang (T) tahun, berarti banjir tersebut terjadi satu kali atau lebih dalam waktu (T) tahun. Hitungan debit banjir rencana membutuhkan data masukan intensitas hujan (mm/jam), koefisien pengaliran (run off coefficien) dan luas daerah pengaliran. Analisis debit banjir dilakukan pada suatu titik tinjauan dengan berbagai periode ulang. Untuk mengetahui besarnya debit banjir rencana dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut : 1. Metode Rasional 2. Metode Weduwen 3. Metode Haspers 1. Metode Rasional
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 111 Metode ini menggambarkan hubungan antara debit limpasan dengan besar curah hujan yang terjadi pada daerah pengaliran sungai. Parameter utama yang digunakan adalah koefisien pengaliran (α), waktu konsentrasi (tc), intensitas hujan (I) dan luas daerah pengaliran sungai (A). Persamaan empiris dari metode rasional adalah : α I A 3.6 1 QT = Keterangan: QT = Debit banjir rencana (m³ /dtk) α = Koefisien pengaliran I = Intensitas hujan (mm/jam) A = Luas daerah pengaliran / tangkapan hujan (km²) a. Waktu Kosentrasi Waktu kosentrasi aliran adalah waktu yang dibutuhkan untuk hujan yang jatuh di hampir seluruh daerah tangkapan untuk dapat mengalir, sehingga seluruh aliran daerah tangkapan mengalir pada suatu titik yang ditinjau atau waktu yang dibutuhkan oleh air yang jatuh pada titik terjauh ke titik yang ditinjau. Dibawah ini adalah rumus Metode Kirpich dan Giandotti : a. Rumus Kirpich 0.385 1.156 c D 0.945 L t = b. Rumus Giandotti 0.5 0.5 c 0.8 h 4A 1.5L t + = Keterangan : tc = waktu kosentrasi (jam) L = alur terpanjang dimana permukaan mengalir (Km) D = perbedaan tinggi antara lokasi embung dan titik tertinggi pada daerah tadah hujan (m). h = perbedaan antara tingi rata-rata dari daerah tadah hujan dan ketinggian lokasi embung (m). b. Intensitas Hujan Intensitas curah hujan adalah curah hujan jangka pendek yang dinyatakan dalam intensitas perjam (mm/jam). Intensitas curah hujan digunakan untuk menghitung besarnya debit banjir rencana dalam merencanakan teknis bangunan air. Untuk menentukan intensitas curah hujan digunakan rumus Dr. Mononobe. 3 2 c T t 24 24 R I = Keterangan: I = Intensitas hujan selama waktu kosentrasi tc (mm/jam) RT = Curah hujan dengan kala ulang t tahun (mm) tc = Waktu kosentrasi (jam) c. Koefisien Pengaliran (α) Koefisien pengaliran adalah suatu faktor koreksi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi daerah tangkapan hujan seperti kemiringan kondisi vegetasi
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 112 dan lain-lain. Koefisien pengaliran dihitung dengan memperhatikan faktor iklim dan fisiografi yaitu dengan menjumlahkan beberapa koefisien sebagai berikut: C = Cp + Ct + Co + Cs + Cc Keterangan: Cp= komponen C yang disebabkan oleh intensitas hujan yang bervariasi (tabel VII.11) Ct = komponen C yang disebabkan oleh keadaan topografi (tabel VII.12) Co = Komponen C yang disebabkan oleh tampungan permukaan (tabel VII.13) Cs = kompnen C yang disebabkan oleh infiltrasi (tabel VII.14) Cc = komponen C yang disebabkan oleh penutup lahan (tabel VII.15) Tabel 7. 11 Harga komponen C oleh faktor intensitas curah hujan Cp Intensitas Hujan (mm/jam) Cp < 25 25 – 50 50 – 75 > 75 0.05 0.15 0.25 0.30 Tabel 7. 12 Harga komponen C oleh faktor topografi Ct Keadaan topografi Kemiringan (m/km) Ct Curam dan tidak rata Berbukit-bukit Landai Hampir datar 200 100 – 200 50 – 100 0 – 50 0.10 0.05 0.00 0.00 Tabel 7. 13 Harga komponen C oleh tampungan permukaan Co Tampungan permukaan Co 1. Daerah pengaliran yang curam, sedikit depresi permukaan. 2. Daerah pengaliran yang sempit dengan sistem teratur. 3. Tampungan dan aliran permukaan yanhg berarti; terdapat kolam; berkontur. 4. Sungai berkelok-kelok dengan usaha pelestarian alam. 0.10 0.05 0.05 0.00 Tabel 7. 14 Harga komponen C oleh faktor infiltrasi Cs Kemampuan infiltrasi tanah K (cm/dt) Cs Infiltrasi besar (tidak terdapat penutup lahan) Infiltrasi lambat (lempung) Infiltrasi sedang (loam) Infiltrasi cepat (pasir tebal,tanah beragregrat baik) < 10 –5 10 –5 – 10-6 10-3 – 10-4 10-3 0.25 0.20 0.10 0.05 Tabel 7. 15 Harga komponen C oleh penutup lahan Cc Penutup tumbuh-tumbuhan pada daerah pengaliran Cc 1. Tidak terdapat tanaman yang efektif. 2. Terdapat padang rumput yang baik sebesar 10 % 3. Terapat padang rumput yang baik sebesar 50 %, ditanami atau banyak pepohonan. 4. Terdapat padang rumput yang baik sebesar 90 %. hutan 0.25 0.20 0.10 0.05
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 113 2. Metode Weduwen Metode ini dimunculkan pertama kali pada tahun 1937 oleh Weduwen. Pemakaiannya hanya terbatas pada luas daerah pengaliran tidak lebih dari 100 Km2. Debit banjir rencana dengan periode ulang (T) tahun dihitung melalalui persamaan rumus sebagai berikut: QT = x x qt x A Keterangan: QT = debit dengan kemungkinan ulang T tahun (m3/dtk). = koefisien pengaliran (run off coefficien). = koefisien reduksi. qt = intensitas hujan (m3/km2/dtk). A = luas daerah pengaliran (km2). a. Koefisien reduksi () Untuk mendapatkan harga debit banjir rencana, Weduwen menentukan harga (t) dengan cara coba-coba sampai menghasilkan nilai (t=tc). Nilai (t) dimasukan dengan nilai coba-coba pada persamaan: 120 A A t 9 t 1 120 β + + + + = Keterangan: = koefisien reduksi. t = lamanya curah hujan (jam) A = luas daerah pengaliran (Km2) b. Intensitas hujan (qt) Besarnya intensitas hujan (qt) diperoleh melalui persamaan sebagai berikut : 240 Rt t 1.45 67.65 qt + = Keterangan: qt = intensitas hujan (m3/km2/dtk). t = lamanya curah hujan (jam) Rt = curah hujan dengan kemungkinan ulang T tahun (mm) c. Koefisien pengaliran () Koefisien pengaliran dihitung dengan menggunakan rumus: qt 7 4.1 1 + = − β α Keterangan: = koefisien pengaliran. = koefisien reduksi. qt = intensitas hujan (m3/km2/dtk). d. Waktu kosentrasi (tc)
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 114 Waktu kosentrasi dihitung dengan menggunakan persamaan: ( ) () 0.125 0.25 T c Q i 0.25 L t + = Keterangan: QT = debit dengan kemungkinan ulang T tahun (m3/dtk). tc = waktu kosentrasi (jam). i = kemiringan rata-rata sungai. L = panjang sungai dihitung sejarak 0.90 x L (Km). 3. Metode Haspers Metode ini pada prinsipnya mengikuti cara pendekatan rasional dengan mempertimbangkan beberapa parameter yang ada, yaitu: luas daerah pengaliran (A), panjang sungai (L), intensitas hujan (I). Besarnya debit banjir rencana (QT) dianalisis secara empiris dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: QT = x x qt x A Keterangan: QT = debit dengan kemungkinan ulang T tahun (m3/dtk). = koefisien aliran (run off coefficien). = koefisien reduksi. qt = intensitas hujan (m3/km2/dtk). A = luas daerah pengaliran (Km2). a. Koefisien pengaliran () Koefisien pengaliran dihitung dengan mengunakan persamaan sebagai berikut: 0.7 0.7 1 0.075 A 1 0.012 A α + + = Keterangan: = koefisien pengaliran. A = luas daerah pengaliran (km2). b. Waktu kosentrasi (tc) Waktu kosentrasi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 0.3 c t 0.10 L i − = Keterangan: tc = waktu kosentrasi (jam). L = panjang sungai dihitung sejarak 0.90 x L (Km). i = kemiringan sungai. c. Koefisien reduksi () Koefisein reduksi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 12 A t 15 3.7 10 1 t 1 0.75 2 c 0.4 t c c + = + − β Keterangan: = koefisen reduksi.
FLOOD DESIGN BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 115 tc = waktu kosentrasi (jam). A = luas daerah pengaliran (Km2) d. Intensitas hujan (qt) Intensitas hujan dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: c T 3.6 t r qt(jam) = c T 86.4 t r qt(hari) = Keterangan: qt = intensitas hujan (m3/km2/dtk). rT = curah hujan rencana (mm). tc = waktu kosentrasi (jam). Besarnya hujan rancangan menurut Haspers ditentukan dengan mengikuti lamanya waktu terjadi hujan dan dikategorikan sebagai berikut: 1. Untuk waktu tc < 2 jam ( ) ( ) 2 c c c T t 1 0.008 260 Rt 2 t t Rt r + − − − = 2. Untuk waktu 2 jam < tc < 19 jam t 1 t Rt r c c T + = 3. Untuk waktu 19 jam < tc < 30 hari r T = 0.707 Rt t c +1 Keterangan: rT = curah hujan rencana (mm). Rt = curah hujan dengan kemungkinan ulang T tahun (mm). tc = waktu kosentrasi (jam).
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 116 Tugas 9: 1. Jelaskan secara singkat dan sistematis konsep rancangan banjir 2. Jelaskan dalam bentuk tabulasi metode analisis desain banjir dengan ketersediaan data yang ada 3. Jelaskan dalam bentuk tabulasi analisis rancangan hujan maksimum (Gumbel-HaspersLog Pearson III) dan debit banjir maksimum (Rasional-Weduwen-Haspers)
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 117 BAB 8 – FLOOD ROUTING Menurut Soemarto (1987) penelusuran banjir merupakan peramalan hidrograf di suatu titik pada suatu aliran atau bagian sungai yang didasarkan atas pengamatan hidrograf di titik lain. Penelusuran banjir dapat diterapkan atau dilakukan melalui/lewat dua bentuk kondisi hidrologi, yaitu lewat palung sungai dan waduk. Hidrograf banjir dapat ditelusuri lewat palung sungai (cekungan yang terbentuk oleh aliran secara alamiah) atau lewat waduk. Dalam praktiknya kajian penelusuran banjir ini bertujuan untuk: 1. Peramalan banjir jangka pendek, perhitungan hidrograf satuan pada berbagai titik sepanjang sungai dari hidrograf satuan di suatu titik sungai tersebut, 2. Peramalan terhadap kelakuan sungai setelah terjadi perubahan keadaan palung sungai (misalnya karena banjir) Penelusuran lewat waduk, yang penampungannya merupakan fungsi langsung dari aliran keluar (outflow), dapat diperoleh hasil yang lebih eksak. Penelusuran banjir dapat juga di artikan sebagai penyelidikan perjalanan banjir (flood tracing). Penelusuran banjir adalah sebuah cara untuk menentukan modifikasi aliran banjir, berdasar pada konfigurasi gelombang banjir yang bergerak dari suatu tampungan. Penelusuran banjir di waduk diperlukan untuk mengetahui debit outflow maksimum dan tinggi air maksimum di atas ambang pelimpah. Secara singkat, maksud penelusuran banjir adalah untuk mengetahui pergeseran puncak debit outflow atas inflow hidrograf. Katagori penelusuran banjir meliputi: 1. Penelusuran hidrologis → menerapkan persamaan kontinuitas saja 2. Penelusuran hidraulis → menerapkan persamaan kontinuitas dan persamaan gerak aliran tidak tunak secara bersamaan Konsep Penelusuran Banjir Penelusuran banjir (flood routing) bisa ditafsirkan sebagai suatu prosedur matematika untuk menentukan/memperkirakan waktu dan besaran aliran banjir disuatu titik berdasarkan data yang diamati pada satu atau beberapa titik di bagian hulu. Dalam praktek terdapat dua macam penelusuran yaitu distribusi flood routing yang biasa dikenal sebagai hirolika routing dan lumped flood routing yang biasa dikenal sebagai hidrologi routing. Perbedaannya adalah bahwa model lumped flood routing, aliran dihitung hanya sebagai fungsi terhadap waktu saja, sedangkan model distribusi flood routing merupakan fungsi terhadap ruang dan waktu. Model distribusi flood routing memungkinkan untuk menghitung debit aliran dan kedalaman sehingga model ini lebih mendekati pada kondisi nyata aliran tidak tunak dari luapan banjir pada suatu saluran (Chow, 1988). Illustrasi penelusuran banjir pada saluan terbuka/sungai ditunjukkan seperti dalam gambar berikut ini:
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 118 Gambar 8. 1 Sketsa penelusuran banjir pada saluran terbuka (tampak penampang), Sivapalan, (1997) 8.1. Hydrology Flood Routing Pada waktu debit dalam saluran meningkat, ketinggian permukaan airnya juga meningkat dan bersamaan dengan itu meningkat pula volume air yang untuk sementara tersimpan di dalam saluran. Pada saat banjir mereda, suatu volume air yang sama harus dilepaskan dari penampungnya. Akibatnya berdasarkan waktu (time base), suatu gelombang banjir yang bergerak ke bagian hilir saluran menjadi panjang dan (bila volumenya masih tetap) puncaknya menjadi turun. Lalu gelombang banjir itu dikatakan menjadi melemah (attenuated). Pergerakan gelombang pada saluran alam dalam desain dan prediksinya secara tradisional diselesaikan dengan menggunakan penelusuran banjir secara hidrologis (hydrologic routing). Prosedur tersebut menggunakan persamaan kontinuitas (continuity equation) atau persamaan simpanan (storage equation) untuk suatu ruas sungai yang diperpanjang, yang biasanya dibatasi oleh titik tertentu yang pernah diukur. Dengan mengetahui aliran pada suatu titik di sebelah hulu, penelusuran dapat digunakan untuk menghitung aliran pada suatu titik di sebelah hilirnya. Prinsip penelusuran juga berlaku untuk perhitungan pengaruh waduk terhadap bentuk gelombang banjirnya (Linsley, Ray K., 1989). Penelusuran banjir secara hidrologi meliputi keseimbangan aliran masuk (inflow), aliran keluar (outflow) dan volume penyimpanan dengan menggunakan persamaan kontinuitas (continuity equation). Teknik penelusuran banjir secara hidrologi dapat diaplikasikan pada masalah-masalah perkiraan banjir, ukuran kendali banjir, desain pengoperasian reservoir dan simulasi pemisahan air (Bedient, Philip, B., 1987). Secara singkat, penelusuran banjir secara hidrologis dibedakan menjadi: 1. Penelusuran pada waduk (reservoir routing), dan 2. Penelusuran pada sungai (channel routing) PENELUSURAN PADA WADUK (RESERVOIR ROUTING) Persamaan dasar, yaitu persamaan kontinuitas (steady flow): − = dimana: I = inflow, Q = outflow, dS = perubahan tampungan dan dt = perubahan waktu Untuk interval waktu Δt yang pendek: ̅∆ − ̅∆ = ∆ ̅ = rerata inflow dalam waktu Δt ̅ = rerata outflow dalam waktu Δt ∆ = perubahan tampungan
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 119 ̅ = + ̅ = + ∆ = − indeks 1 menunjukkan kondisi awal ∆ Indeks 2 menunjukkan kondisi akhir ∆ + ∆ − + ∆ = − Unsteady flow (differential form) – Saint Vernant (1871) Persamaan kontinuitas: + = (T = lebar permukaan air) Persamaan momentum: + + = − dimana: v = kecepatan S0 = kemiringan dasar Sf = kemiringan muka air g = gravitasi Penyelesaian (proses) hitungan penelusuran: 1. Analitis → Newton Raphson 2. Semi analitis → modified Pul’s Method 3. Grafis → dengan bantuan kurva/grafik Penyelesaian analitis penelusuran pada waduk: a) Masukan → inflow hidrograf b) Proses → tampungan, S = S (h); pelepasan debit; Q = Q (h); perubahan tampungan, ΔS c) Keluaran → S vs t; Q vs t dan H vs t Gambar 8. 2 Konsep penelusuran pada waduk Data yang diperlukan: 1. Hubungan antara volume tampungan dengan tinggi muka air; S = S (h) 2. Hubungan antara debit outflow dengan tinggi muka air; Q = Q (h) 3. Inflow hidrograf; I = I (t) 4. Nilai awal: S; I; dan Q pada t = 0 Penyelesaian semi-analitis (modified Pul’s Method) penelusuran pada waduk: + ∆ − + ∆ = − → + ∆ + ( − ∆) = + ∆ Bila I; S (h); Q (h) diketahui, maka ruas kanan dapat ditetapkan/dihitung Kondisi awal interval Δt, indeks 1 Kondisi akhir interval Δt, indeks 2
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 120 Prosedur perhitungan: a) Dengan hubungan tampungan, keluaran (Q) dan elevasi (h) dibuat kurva: (interval Δt ditetapkan sama dengan interval inflow hidrograf) 1) + ∆ () 2) () b) Dihitung: pada kondisi awal (awal penelusuran) + ∆ + ( − ∆) + ∆ = + ∆ + ( − ∆) c) Berdasarkan nilai kondisi akhir + ∆ dibaca elevasi (h) dan outflow (Q) d) Kurangkan nilai Q2Δt terhadap nilai + ∆ untuk mendapatkan nilai ( − ∆) periode Δt berikutnya e) Urutkan 2, 3, dan 4 diulang hingga inflow hidrograf terakhir Penelusuran secara grafis Gambar 8. 3 Grafik hubungan antara outflow dan tampungan terhadap elevasi Dimulai pada I = 10 m3/detik, → Q = 10 m3/detik, → h = 100,50 m, → dibaca + ∆ → ditambah + ∆ → dibaca elevasi h → dibaca outflow Q Kondisi awal interval Δt, indeks 1 Kondisi akhir interval Δt, indeks 2
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 121 PENELUSURAN PADA SUNGAI (CHANNEL ROUTING) Pada penelusuran waduk, tampungan merupakan fungsi outflow (Q), sedangkan pada sungai, tampungan (S) merupakan fungsi inflow dan outflow secara bersamaan. Aliran sungai sesungguhnya adalah “gradually varied flow”, namun untuk analisis disederhanakan, dengan membagi tampungan menjadi: 1. Tampungan prismatik 2. Tampungan baji (segitiga) Gambar 8. 4 Tampungan prismatik dan tampungan baji (segitiga) Sp = f (Q) Sb = f (I) Dengan anggapan bahwa Sp = f (Q) dan Sb = f (I), persamaan penelusuran (tampungan): = [ + ( − ) ] Dimana: m = konstanta k = konstanta waktu penampungan x = faktor sungai (kesesuaian inflow-outflow) Nilai k dan x tergantung dari kemampuan sistem tampungan sungai akibat aliran masuk dan keluar. Nilai k dan x dihitung/ditetapkan secara grafis pada kurva tampungan (S) dengan fungsi [xI+(1-x)Q]. Nilai k adalah kemiringan grafik, sedangkan nilai x dicoba-cobakan agar grafik hampir berimpit Persamaan Muskingum Gambar 8. 5 Hubungan antara debit dan tampungan terhadap waktu
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 122 Konsep penelusuran hidrologi cara Muskingum 1. Penelusuran untuk satu pangsa sungai ( river reach ) tertentu, atau sebuah reservoir. 2. Diperlukan informasi tentang hubungan antara tinggi muka air dan tampungan ( stage storage ), atau hubungan antara debit dan tampungan (discharge storage ). Kedua hubungan tersebut dapat diperoleh dari data inflow dan outflow ke dalam pangsa sungai tersebut. 3. Tidak terdapat aliran masuk (tributaries) ke dalam pangsa sungai. Metode Muskingum menggunakan asumsi: 1. Tidak ada anak sungai yang masuk ke dalam bagian memanjang palung sungai yang ditinjau; 2. Penambahan dan kehilangan air yang berasal dari air hujan, air tanah dan evaporasi semuanya diabaikan. Untuk melakukan perhitungan dengan persamaan kontinyuitas, maka dimensi waktu (t) harus dibagi menjadi periode–periode dt yang lebih kecil, yang disebut sebagai periode penelusuran (routing period). Periode penelusuran (dt) harus dibuat lebih kecil dari tempuh dalam bagian memanjang sungai tersebut, sehingga selama periode penelusuran (dt) puncak banjirnya tidak dapat menutup bagian memanjang sungai secara menyeluruh (Soemarto, 1987). Persamaan kontinyuitas yang umum dipakai dalam penelusuran banjir adalah sebagai berikut: I – O = dS/dt (1) dimana: I = debit yang masuk ke dalam permulaan bagian memanjang palung sungai yang ditinjau (bagian hulu) (m3/det) O = debit yang keluar dari akhir bagianmemanjang palung sungai yang ditinjau (bagian hilir) (m3/det) S = besarnya tampungan (storage) dalam bagian memanjang palung sungai yang ditinjau (m3). dt = periode penelusuran (detik, jam atau hari) Untuk selang waktu t, maka persamaan di atas berubah menjadi: I = ½ (I1 + I2) O = ½ (O1 + O2)dS = S2 – S1 Sehingga persamaan (1) menjadi: ½ (I1 + I2) – ½ (O1 + O2) = S2 – S1 (2) Angka subscript 1 merupakan keadaan pada saat permulaan periode penelusuran dan subscript 2 merupakan keadaan pada akhir periode penelusuran. Persamaan (2) di atas terdapat dua komponen yang tidak diketahui nilainya, yaitu O2 dan S2. Sedangkan data yang lain seperti I1 dan I2 dapat diketahui dari hidrograf debit masuk, serta O1 dan S1 dapat diketahui dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dua nilai komponen tersebut diperlukan persamaan ketiga. Sampai tahap ini membuktikan bahwa penelusuran banjir lewat palung sungai cukup rumit dan sulit, bila dibandingkan dengan penelusuran banjir lewat waduk. Persamaan yang digunakan pada waduk lebih sederhana, yaitu: O2 = f (S2). Penelusuran banjir lewat palung sungai nilai tampungan (storage) tidak hanya merupakan fungsi dari debit keluar (outflow) saja, akan tetapi tergantung kepada debit masuk (inflow) dan debit keluar (outflow). Menurut Mc Carthy dalam Wilson (1974) yang kemudian dikenal sebagai metode Muskingum, diajukan suatu persamaan dimana storage merupakan fungsi dari inflow sebagai berikut: S = K [ x I + (1 – x) O] (3)
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 123 dimana: x = konstanta tak bersatuan dari ruas sungai K = konstanta storage yang berdimensi waktu Nilai x dan K harus dicari dari data pengamatan hidrograf I dan D yang diukur dari dua tempat lokasi pengukuran, dalam hal ini hidrograf I diperoleh dari pos pengukuran Depok dan hidrograf O diperoleh dari pos pengukuran Manggarai. Menurut Sosrodarsono dan Takeda (1980) berdasarkan praktek dan pengalaman bahwa nilai x untuk sungai-sungai alam berkisar antara 0 sampai 0.50. Akan tetapi makin curam kemiringannya, makin besar harga x itu. Biasanya harga x terletak antara 0.10 dan 0.30. Kadang-kadang harga x bernilai negatip. Untuk mendapatkan nilai konstanta x dan K harus ditempuh melalui beberapa tahapan. Secara umum urutan tahapan yang ditempuh untuk mendapatkan nilai x dan K adalah sebagai berikut (Wilson, 1974): 1. Selama I > O, air memasuki storage dalam ruas sungai tersebut dan apabila I < O, maka air meninggalkan (keluar) dari storage tersebut. Gambar VIII.6a, menunjukkan secara simultan inflow (I) dan outflow (O) dari satu ruas sungai. 2. Sedangkan Gambar VIII.6b, merupakan gambaran hubungan antara air memasuki storage dan meninggalkan storage dan menunjukkan hubungan akumulasi storage dengan waktu. (a) (b) Persamaan dasar: I – O = dS / dt Gambar 8. 6 Hubungan antara inflow dan outflow
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 124 (a) (b) (a) Translasi murni (b) Tampungan/pemipihan murni (c) Translasi dan tampungan/pemipihan (c) Gambar 8. 8 Tampungan prisma dan tampungan baji Dengan anggapan m = 1 → = [ + ( − )] Dari persamaan kontinuitas sebelumnya: Persamaan Muskingum pada interval waktu Δt: − = [( − ) + ( − )( − )] Persamaan untuk waktu ke i adalah: Si = K [ XI i + (1-X) Oi ] Sb = KX(I-O) Sp = KO S = Sb +Sp = KX(I-O)+KO = K[XI+(1-X)O] Persamaan dasar dapat diubah menjadi: 1+2 2 − 1+2 2 = 1+2 2 Penyelesian umum : O2 = C0 I 2 + C1 I 1 + C2O1 = (∆/)− (−)+(∆/) = (∆/)+ (−)+(∆/) = (−)−(∆/) (−)+(∆/) + + = dengan: S : tampungan K : koefisien tampungan X : faktor pemberat, antara 0 – 0,5 I : masukan (inflow) O : keluaran (outflow) Gambar 8. 7 Translasi tampungan yang terjadi
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 125 1) Hubungan antara S dan [ KX(I-O) + KO] adalah linear untuk nilai X tertentu. X diperoleh dengan cara coba-coba sampai hubungan keduanya sangat mendekati garis lurus. 2) Nilai X berkisar antara 0 – 0,5. X = 0 berarti routing untuk reservoir, dan X = 0,5 berarti translasi murni. 3) Cara coba-ulang sangat krusial karena keduanya berubah dengan besaran debit. Cara Muskingum-Cunge menghilangkan cara coba-coba dengan mengaitkan nilai X dengan sifat aliran dan sifat saluran. Penetapan K dengan X = 0,4 Penetapan K dengan X = 0,2 Penetapan K dengan X = 0,1 Untuk K = 2,5 jam dan X = 0,4 Untuk K = 2,5 jam dan X = 0,2 Gambar 8. 9 Penetapan nilai K dengan x = 0,4; 0,2 dan 0,1 Gambar 8. 10 Penelusuran hidrograf dengan K = 2,5 jam dan X = 0,4 atau X = 0,2
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 126 Untuk K = 5 jam dan X = 0,4 Untuk K = 5 jam dan X = 0,2 Contoh penelusuran hidrologis dengan K = 2,5 jam dan X = 0,4 dijelaskan seperti dalam Tabel VIII.1 berikut ini. Tabel 8. 1 Penelusuran hidrologis dengan K = 2,5 jam dan X = 0,4 Pada penelusuran saluran (stream routing) tampungan merupakan fungsi masukan dan keluaran, sedangkan pada penelusuran reservoir ( reservoir routing) tampungan hanya tergantung dari keluaran. S = KO Persamaan keseimbangan: I = O + S I – O = S + − + = + Gambar 8. 11 Penelusuran hidrograf dengan K = 5 jam dan X = 0,4 atau X = 0,2
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 127 Penggabungan persamaan-persamaan sebelumnya, dihasilkan: O2 = C0 I 1 + C1 I 1 + C2O1 = (∆/) +(∆/) = = −(∆/) +(∆/) + + = 8.2. Hydraulics Flood Routing Menurut Linsley JR, R.K et.al. (1982), penelusuran banjir (flood routing) secara hidrolika bersandar pada tiga asumsi yakni: 1) kerapatan airnya konstan, 2) panjang sungai yang dipengaruhi oleh gelombang banjir lebih besar daripada kedalaman airnya, 3) alirannya secara hakiki berdimensi satu. Gelombang banjir yang memenuhi asumsi ini disebut gelombang air dangkal (shallow water wave). Karena percepatan vertikal aliran diabaikan maka distribusi tekanan pada gelombang tersebut adalah hidrostatik. Melalui pendekatan secara hidrologi, analisis penelusuran banjir menggunakan metode Muskingum, dimana prinsipnya adalah kontinuitas debit masuk dengan debit keluar (Arbor Reseda,2012). Menurut Istiarto (2008), penelusuran banjir secara hidraulik adalah salah satu cara penelusuran aliran yang memperhitungkan perubahan parameter kecepatan aliran dan debit sebagai fungsi dari tempat ke waktu. Penelusuran secara hidrolika didasarkan pada persamaan energi dan persamaan momentum dapat digunakan sebagai pengganti untuk metode hidrologi (Chow,1988). Pendekatan secara hidrologis adalah yang tidak didasarkan atas hukum-hukum hidrolika, sedangkan pendekatan secara hidraulik menggunakan hukum-hukum hidrolika. Pada cara pertama, yang ditinjau hanyalah hukum kontinuitas, sedangkan persamaan keduanya didapatkan secara empirik dari pengamatan banjir. Pada cara kedua, aliran adalah tidak tetap yang berubah secara ruang (spatially varied unsteady flow), yang penelusurannya dilaksanakan secara simultan dari ekspresi-ekspresi kontinuitas dan momentum. Metode Analogi Difusi (Diffusion Analogy) Metode ini dibangun dengan menggunakan teori difusi aliran yang statistikal. Menurut teori ini, persamaan differensial untuk difusi partikel-partikel pada suatu aliran tak tunak (unsteady) adalah: di mana N = jumlah partikel, t = waktu, x = jarak, dan K = koefisien difusi Anggapan dan penjabaran: 1) Apabila partikel-partikel mengalir dalam suatu arah sepanjang sumbu x, persamaan ini memberikan distribusi partikel di dalam arah aliran sebagai fungsi jarak dan waktu. 2) Di dalam sungai alam, gangguan-gangguan aliran disebabkan oleh ketidak-teraturan saluran dan mempunyai besaran yang tetap. Gangguan-gangguan itu bercampur, dissipatif, dan berdifusi seiring pergerakan aliran sepanjang saluran. Di dalam mengaplikasikan teori difusi ke aliran air, anggapan yang dipakai difusi gangguangangguan beranalogi dengan difusi partikel-partikel. Apabila semua efek gangguan pada aliran merupakan representasi variasi kedalaman y, maka persamaan di atas dapat ditulis:
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 128 Di dalam sungai-sungai alam, ketidak-teraturan menyebabkan ketidak-teraturan pula pada simpanan, dan persamaan di atas menyatakan besarnya laju perubahan di dalam simpanan akibat ketidak-teraturan. Dengan memasukkan item ini ke dalam persamaan kontinuitas saluran prismatis, maka persamaan kontinuitas untuk saluran alam dapat ditulis: Anggapan selanjutnya ialah bahwa saluran relatif lebar sehingga aliran secara rata-rata merupakan aliran seragam dan tunak (steady). Jadi debit per satuan lebar dapat memakai rumus Chezy atau Manning. Rumus Chezy adalah: Dengan mensubtitusi persamaan q ini ke dalam persamaan kontinuitas tersebut dan menyederhanakannya, diperoleh: Persamaan ini merupakan persamaan differensial dasar untuk aliran banjir pada sungaisungai alam. Dapat dilihat bahwa koefisien dari tergantung dari tahanan saluran dan kemiringan, dan koefisien dari tergantung dari ketidak-teraturan saluran. Selanjutnya persamaan dikembangkan oleh Hayami untuk perambatan suatu gelombang banjir adalah sebagai berikut: di mana y adalah kedalaman pada suatu titik berjarak x dari hulu suatu ruas sungai, yn adalah kedalaman normal aliran pada titik yang sama sebelum banjir datang, yo adalah kedalaman di bagian hulu, t adalah waktu, K adalah koefisien difusi, Vw = 1,5V, V adalah kecepatan rata-rata, dan X adalah variabel. Metode ini sudah mempertimbangkan ketidak-teraturan saluran yang banyak dijumpai di sungai-sungai alam sehingga lebih akurat, tetapi penyelesaian metode ini merupakan persamaan differensial yang sudah mendetail seperti metode numerik. Metode ini cocok untuk sungai-sungai yang lebar, alirannya seragam dan tunak. Hal ini sesuai dengan asumsi yang diambil di dalam menerapkan rumus Chezy atau Manning. Metode Gelombang Kinematik (Kinematic Wave) Pendekatan penelusuran banjir dengan gelombang kinematik merupakan salah satu pendekatan secara hidrolis. Penelusuran banjir secara hidrolis bersandar pada 3 asumsi, yakni: 1) kerapatan airnya secara konstan 2) panjang sungai yang dipengaruhi oleh gelombang banjirnya lebih besar beberapa kali dibandingkan kedalaman alirannya 3) alirannya secara hakiki berdimensi satu. Anggapan dan Penjabaran Metode Gelombang Kinematik:
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 129 Pendekatan gelombang kinematik hanya memperhatikan gaya-gaya yang dominan mempengaruhi pergerakan aliran alami yaitu gaya berat dan gesekan. Asumsi ini diambil untuk penyederhanaan di dalam menguraikan aliran tak tunak (unsteady flow). Persamaan dasar yang dipakai adalah: di mana S0 = kemiringan dasar saluran, Sf = kemiringan gesekan (garis energi), Q = debit aliran, K = nilai pengangkutan. Metode yang menggunakan persamaan dasar dan prinsip simpanan (perubahan volume = aliran masuk – aliran keluar), atau varian dari padanya merupakan suatu metode kinematik. Masalah-masalah gelombang kinematik tertentu untuk aliran sederhana dapat diselesaikan secara eksak, misalnya untuk aliran permukaan bidang datar, tetapi untuk kasus yang lebih umum harus diselesaikan dengan metode numerik. Di dalam persamaan kinematik, aliran dipandang sebagai fungsi luas dan bukan fungsi kedalaman, atau Q = f (A). Selanjutnya ada beberapa varian penyelesaian metode ini yang menggunakan metode numerik dengan membagi-bagi ruas sungai menjadi elemen-elemen dari hulu ke hilir. Schaake misalnya menyajikan hasil penjabarannya sebagai berikut: di mana bentuk Ai,j adalah luas penampang aliran di posisi ii pada waktu tj, K = Δx/u = waktu yang dibutuhkan gelombang kinematik kecil untuk melintasi elemennya, Δx = panjang elemen, Δt = langkah waktu, dan Ij = aliran lateral yang masuk pada saat tj. Kecepatan gelombang kinematik u dihitung dengan: untuk setiap langkah waktu dan elemen. Laju aliran yang bersesuaian dengan A2,2 persamaan selanjutnya dihitung melalui persamaan: Kesalahan relatif maksimun yang diperkenankan dalam hubungan antara luas dan debit pada hasil yang diperoleh: Persamaan gelombang kinematik ini harus hati-hati digunakan pada saluran di mana terjadi penurunan yang cepat pada kemiringan atau kapasitas aliran, atau bertambahnya kekasaran. Kesulitan penyelesaian matematis akan menjadi sangat rumit jika terjadi pada perubahan yang besar pada profil aliran. HEC-RAS (Hidrologyc Engineering Center – River Analysis System) adalah pemodelan sistem sungai yang disusun untuk menangani perhitungan hidraulik satu dimensi untuk sistem saluran alam maupun saluran buatan (Istiarto, 2008). Konsep sistem peringatan dini banjir (Flood Early Warning System) Menurut Segel Ginting dan William dalam Jurnal “Sistem Peringatan Dini Banjir Jakarta”, untuk melakukan peringatan dini banjir (flood early warning) terdapat beberapa tahapan
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 130 untuk dapat tercapainya hasil secara efektif. Tahapan-tahapan tersebut menurut Werner dan Kwadjik (2005) adalah: Detection, yaitu data tepat waktu (real time) di pantau dan di proses untuk mendapatkan informasi banjir yang mungkin terjadi. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan untuk melakukan peringatan (warning) tanpa melalui proses forecasting. Pada tahapan ini diperlukan juga perlu dilakukan pemilahan dan pengolahan terhadap data karena data yang diperoleh dari lapangan belum tentu memiliki kualitas yang baik. Forecasting, tahapan ini dilakukan perkiraan terhadap curah hujan, tinggi muka air atau debit aliran banjir serta waktu datangnya banjir tersebut. Dengan diketahuinya kejadian banjir tersebut maka dapat diteruskan untuk melakukan peringatan (warning). Warning and dissemination, tahapan ini merupakan faktor kunci sukses dalam peringatan dini banjir (flood early warning). Tahapan ini menggunakan informasi yang diperoleh dari tahapan detection ataupun forecasting. Informasi tersebut dapat disebarluaskan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan ketika banjir. Response, tanggap terhadap isu peringatan banjir. Tujuan dari peringatan dini banjir adalah untuk mengurangi kerugian materil maupun non materil, sehingga dibutuhkan personil yang tanggap secara tepat dan cepat dalam melakukan evakuasi apabila banjir terjadi. Gambar 8. 12 Bagan Konsep Flood Early Warning System (FEWS) Klasifikasi perkiraan banjir berdasarkan pada waktu jeda antara kejadian hujan dengan waktu terjadinya banjir. Proses ini berkaitan dengan proses terjadinya limpasan yang terjadi akibat hujan pada lahan kemudian dilanjutkan dengan penelusuran aliran pada sungai (Segel Ginting dan William, 2014). DETECTION WARNING RESPONSE FORECASTIN G SIMULATION
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 131 Tugas 10 1. Pelajari dan tulis ulang penelusuran banjir yang diketahui bahwa hubungan antara tampungan S, outflow (Q), dengan elevasi (h) suatu waduk seperti tabel berikut ini: Tabel S vs h Tabel I vs t
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 132
FLOOD ROUTING BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 133 2. Suatu sungai mempunyai karakter konstanta waktu tampungan (k) = 12 jam dengan x = 0,20. Terjadi aliran pada titik hulu sebagai berikut: Dengan penelusuran tentukan aliran di bagian hilir.
BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 134 BAB 9 – ISLAND HYDROLOGY 9.1. Islands Hydrology Characteristics Kepulauan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan archipelago adalah sebuah sebutan untuk kumpulan pulau-pulau atau gugusan beberapa buah pulau. Sedangkan yang dimaksud dengan Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu dan lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dunia ini terdiri dari 193 Negara berdaulat yang diakui oleh Internasional yang telah menjadi anggota PBB, dan dari jumlah Negara tersebut diantaranya terdapat 45 Negara yang digolongkan sebagai Negara kepulauan. Negara Kepulauan Terbesar di Dunia adalah Negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Republik Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km2 dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Sedangkan Negara Kepulauan terbesar kedua di Dunia adalah Madagaskar yang secara geografisnya terletak di Benua Afrika dengan luas wilayah sebesar 587.041 km2. Berada di urutan ketiga adalah negara tetangga kita yaitu Papua Nugini dengan luas wilayah 462.840 km2. Sepuluh negara kepulauan terbesar di dunia menurut luas wilayahnya dan jumlah penduduknya, yaitu: Tabel 9. 1 Negara kepulauan dengan luas wilayah-jumlah penduduk-garis pantainya No. Nama negara kepulauan Luas wilayah (km2) Jumlah penduduk (jiwa) Garis pantai (m) 1 Indonesia 1.904.569 253.609.643 54.716 2 Madagaskar (Madagascar) 587.041 23.201.926 4.826 3 Papua Nugini (Papua New Guinea) 462.840 6.552.730 5.152 4 Jepang (Japan) 377.915 127.103.388 29.751 5 Filipina (Philippines) 300.000 107.668.231 36.289 6 Selandia Baru (New Zealand) 267.710 4.401.916 15.134 7 Britania Raya/Inggris (Great Britain) 246.610 63.742.977 12.429 8 Kuba (Cuba) 110.860 11.047.251 3.735 9 Islandia (Iceland) 103.000 317.351 4.970 10 Irlandia (Ireland) 70.273 4.832.765 1.448 Sumber: Dinas pariwisata NTB, 2016 JAKARTA, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Kemenkomarves) mencatat hingga Desember 2019 jumlah pulau hasil validasi dan verifikasi Indonesia mencapai 17.491 pulau. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau, yang mana 16.056 pulau telah memiliki nama baku di PBB. Provinsi yang memiliki pulau paling banyak adalah Kepulauan Riau dengan pulau sebanyak 2.408 buah (Gambar IX.1).
ISLANDS HYDROLOGY BAHAN AJAR REKAYASA HIDROLOGI 135 Gambar 9. 1 Jumlah pulau menurut propinsi di Indonesia Ciri khas pulau-pulau kecil yang dikelilingi lautan adalah keterbatasan sumber daya air berupa air tanah, dan rentan akan bencana alam. Air tanah di pulau-pulau kecil merupakan lensa yang mengapung di atas air payau atau air asin (Falkland, 2010), dengan ketebalan yang sangat tergantung pada imbuhan (recharge), dan rentan terhadap penyusupan air laut (Hehanusa, 1987). Air tanah seluruhnya berasal dari air hujan dengan siklus yang pendek untuk sampai ke laut, sehingga tidak sempat dimanfaatkan, khususnya untuk kegiatan pertanian. Gambar 9. 2 Lensa air tanah pada pulau kecil (Falkland, 2010)