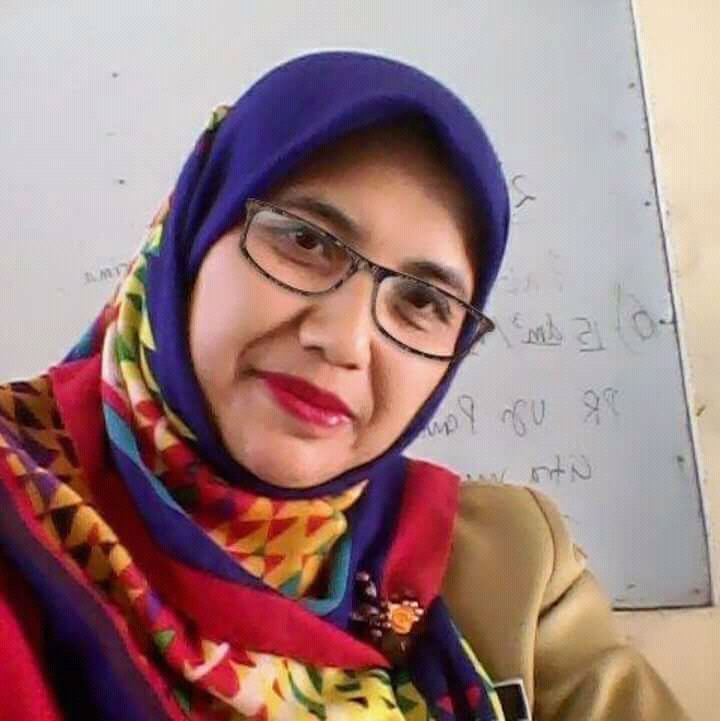Sosok Maha Patih Udara
Pada Masa Akhir Majaphit
Oleh: Agung Priyo Pidekso
Situs Kerajaan Majapahit, https://www.merdeka.com
Pada masa akhir Majapahit, konflik perebutan
kuasa di dalam istana menjadi sesuatu yang sangat panas,
sengit, dan menjadi sorotan banyak pakar para ahli
Sejarah, Arkeologi, dan pemerhati Budaya. Sejauh ini,
konflik yang selalu muncul dalam sumber tradisi lebih
mengedepankan pada proses politik yang dihimpun dan
~ Legenda Tuban ~ 151
dibungkus dalam bingkai agama. Sehingga ketika
perpolitikan yang dicampurkan dengan dalil agama, hal
itu bisa membawa pengaruh kompleks bagi suatu bangsa.
Agama dapat dengan mudah diubah dan
dihancurkan, Kebudayaan, Tradisi, Adat, serta segala
perkakas lainnya dalam suatu Bangsa, hal itu dapat
dengan sangat mudah untuk dilumpuhkan. Perpolitikan
yang dengan sangat rapi dibungkus dalam bingkai
keagamaan, hal itu juga sangat mencerminkan bagaimana
seluruh masyarakat suatu negara atau suatu bangsa sangat
memengaruhi berbagai pola, cara, dan pandangan
kehidupannya. Bahkan pun, sama seperti yang kita dapat
lihat pada masa awal Tumapel atau Singasari berdiri,
Angrok – yang mendapat banyak dukungan dari para
Brahmana Ciwa dan Pendeta Bubddhist – akhirnya karena
dukungan dari mereka-mereka semua, hal itulah yang bisa
menghancurkan dan meruntuhkan orde pemerintahan
Kediri atau Panjalu pada era kepemimpinan Sri Maharaja
Kertajaya atau Sinuwun Dhandang Gendhis.
Seperti yang sudah sering terjadi dalam tulisan
buku-buku maupun artikel sejarah mengenai Majapahit.
Majapahit didirikan pada tahun 1293 M oleh orang-orang
152 ~ Legenda Tuban ~
Sungenep (Sumenep), Tuban, dan sisa-sisa orang-orang
Tumapel pendukung Nararya Wijaya. Wijaya bersama
dengan para pendukungnya, orang-orang Tuban, dan
Sungenep pun mulai babat Alas e wang Trik (Hutannya
orang Trik). Dengan bantuan mereka, maka hutan yang
amat luas dan angker itu dapat dijadikan sebagai sebuah
desa, bernama Desa Wilwatikta atau Desa Majapahit.
Kata ini berasal dari serapan Bahasa Sanskerta
‘Wilwatikta’, ‘Wilwa’ atau ‘Bilwa’ merupakan adalah
pohon Maja, pohon kesayangan Dewa Iswara atau
Mahadewa Ciwa yang biasa dipakai sebagai bentuk
persembahan kepada Dewa Ciwa saat upacara
keagamaan. Para pemeluk agama Ciwa di India, dan
‘Tikta’yang artinya ‘Pahit’. Dalam Serat Pararaton,
dikisahkan bahwa pada bagian babat alas Tarik, para
pekerja dari Sungenep itu mengalami kelelahan dan udara
yang cukup terik saat bekerja.
Di tengah semua itu, salah seorang dari mereka
yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya memetik salah satu
buah dari pohon Wilwa tersebut. Saat dimakan mereka
memuntahkannya kembali, sebagian ada yang keracunan,
dan sebagian lainnya tidak mau memakannya. Rasanya
~ Legenda Tuban ~ 153
sungguh Pahit (Tikta), dan disamping itu dapat
mengakibatkan efek keracunan. Pengertian dari rasa pahit
buah Wilwa atau buah maja yang dimakan oleh orang-
orang pekerja asal Sungenep itu dapat dibedakan dengan
dua arti. Arti sebenarnya, maupun arti Sanepan (arti yang
bukan sesungguhnya, mengandung makna
perumpamaan).
Arti yang sesungguhnya sudah jelas dijelaskan di
atas, sedangkan makna Sanepannya ialah bahwa Wijaya,
ketika ia dinobatkan menjadi Maharaja pertama
Majapahit, Wijaya menamai nama kerajaan barunya
tersebut dengan nama ‘Wilwatikta’ atau ‘Majapahit’,
yaitu untuk mengenang perjuangan para pekerja asal
Sungenep itu, sampai di mana mereka memakan dan
memuntahkan buah maja (Buah Wilwa) yang rasanya
sangat pahit (Tikta).
Namun, ada lagi makna Sanepan yang harus
diketahui dari berdirinya Majapahit, yaitu kerajaan besar
ini dibangun di atas puing-puing Tumapel atau Singasari,
dan Pangjalu atau Kediri. Penuh dengan pemberontakan,
peperangan, maupun intrik politik di dalam istana
Majapahit sendiri. Dan hal itu dapat kita lihat pada awal
154 ~ Legenda Tuban ~
berdirinya Majapahit, serangkaian pemberontakan yang
diawali dari masa awal pemerintahan Wijaya, yaitu
Rangglawe, Lembu Sora atau Sorandaka, dan Nambi dan
para laskar Lamajang Tigang Juru yang diserang dan
dihancurkan pada masa pemerintahan Cri Jayanegara, dan
terakhir pemberontakan para Sapta Dharmaputera di
bawah pimpinan Ra Kuti pada masa pemerintahan
Jayanegara.
Semua pemberontakan itu ternyata memiliki motif
tersembunyi masing-masing, karena hal itu juga berkaitan
sejak masa pembelahan kerajaan Medang di Jawa Timur
atau Kahuripan menjadi dua: Janggala dan Pangjalu atau
Kadhiri. Janggala dan Pangjalu adalah kerajaan hasil
pecahan Medang Airlangga yang dibelah oleh Maha
Wiku ‘Pu Bharada, salah seorang Purohita (Pendeta
Tinggi di Kedhaton) dan penasihat pribadi Prabu
Airlangga sendiri.
Pembelahan kerajaan tersebut dimaksudkan untuk
mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya perang
saudara perebutan tahta dari kedua puteranya setelah
Airlangga nanti turun tahta. Airlangga memberikan
perintahnya kepada ‘Pu Bharada, lalu ‘Pu Bharada
~ Legenda Tuban ~ 155
melaksanakan sabda Sang Prabu. Batas kedua kerajaan
telah ditentukan, dan berdirilah dua kerajaan merdeka
yang merupakan hasil pembelahan kerajaan Medang di
Jawa Timur atau Kahuripan itu.
Puteranya yang sulung menerima Kerajaan yang
berada di sebelah Timur, beribukota lama di Kahuripan,
dan Kerajaan itu bernama Jenggala. Sedangkan puteranya
yang muda dan terlahir dari selir mendapatkan kerajaan di
wilayah Barat, beribukota di Dahana. Kerajaan itu disebut
sebagai Kerajaan Pangjalu, pada masa Tumapel sampai
Majapahit lebih muda disebut sebagai Kerajaan Kadhiri
atau Kediri atau Daha. Seorang raja atau ratu yang
ditempatkan memerintah di poros utama Kerajaan Kediri
atau Daha tersebut disebut sebagai ‘Bhre Daha’ (Baik
Bhatara untuk seorang laki-laki, maupun Bhatari untuk
perempuan).
Pembelahan Kerajaan yang dilakukan oleh
Airlangga lewat ‘Pu Bharada ternyata tidak membawa
hasil positif. Rupanya benar apa yang dikhawatirkan oleh
Airlangga sebelum turun takhta. Terjadilah perang
saudara antara pihak Kerajaan Barat, Pangjalu, melawan
Kerajaan Timur, Janggala. Mapanji Garasakan adalah
156 ~ Legenda Tuban ~
putera Airlangga yang terlahir dari bini aji, ia memerintah
kerajaan Timur, Janggala. Sedangkan raja di Kerajaan
Barat atau Pangjalu bukanlah Cri Samarawijaya
Dharmasuprawahana Tguh Utunggadewa, namanya
muncul dan hanya disebut sebagai Rakryan Mahamantri i
Hino dalam Prasasti Pandan dan Prasasti Pucangan Jawa
Kuna. Lalu namanya tidak disebutkan lagi setelah itu.
Menurut pendapat para pakar Sejarah, Samarawijaya
adalah putera kandung ayah mertua Airlangga, Cri
Maharaja Dharmawangsa Tguh Isyana Wikrama Dharma
Tunggadewa. Sehingga ia masih bersaudara dengan
Airlangga, sebagai adik ipar Airlangga. Samarawijaya
menggeser kedudukan kakak sepupunya, yaitu
Sanggramawijaya Dharamprasadotunggadewi, puteri
Airlangga yang terlahir dari parameswari, dan karena hal
itulah maka namanya muncul dalam Prasasti Pandan dan
Prasasti Pucangan Jawa Kuna. Namun, tiba-tiba
muncullah seorang raja dari wilayah Kerajaan Barat atau
Pangjalu, namanya ialah Cri Maharajyetendrakara
Wuryyawiryya Parakrama Cri Bhakta.
Raja ini mengeluarkan Prasasti Mataji bertarik
973 Caka/1051 M. Raja ini menurut para ahli dan pakar
~ Legenda Tuban ~ 157
Sejarah adalah putera Cri Samarawijaya
Dharmasuprawahana Tguh Utunggadewa. Ia menjadi raja
di wilayah Kerajaan Barat atau Pangjalu dan sepertinya
hendak menuntut balas kepada Airlangga karena
Ayahandanya sendiri tidak mendapatkan jatah tahta
Medang yang seharusnya diberikan oleh Dharmawangsa
Tguh kepada puteranya tersebut.
Prasasti Mātaji merupakan prasasti pertama yang
memuat informasi mengenai keberadaan Kerajaan
Pagnjalu setelah peristiwa pembagian kerajaan Medang di
Jawa Timur oleh Airlangga. Selain itu, prasasti ini juga
memuat informasi mengenai peristiwa yang kerap terjadi
di Kerajaan Barat atau Pangjalu saat itu dan nama raja
beserta gelar lengkapnya. Prabu Jyitêndra atau Cri Bhakta
memberikan anugerah sīma gaňjaran kepada penduduk
Desa Mātaji dengan perantaraan (sopana) Sang Hadyan,
dan disaksikan oleh Para Tandha Rakryan Riŋ
Pakirakiran. Kemudian anugerah ini di berikan pada
penduduk Desa Mataji, karena mereka selalu menolong
raja saat sedang menghadapi musuhnya. Sangat
disayangkan, pada prasasti ini sudah tidak ada informasi
mengenai unsur-unsur lain yang di jumpai pada prasasti
158 ~ Legenda Tuban ~
penganugerahan sima ini tidak diketahui karena aksara
pada prasasti ini sudah aus. Sedangkan berdasarkan
toponimi, Desa Mataji diduga merupakan desa yang
terletak di daerah perbatasan antara Kerajaan Janggala
dan Pangjalu, sehingga di desa ini sering terjadi
peperangan antara kedua belah pihak, kedua kerajaan
pecahan Airlangga, baik Pangjalu melawan Janggala atau
sebaliknya.
Perpecahan, pertikaian, intrik politik,
pengkhianatan, dan berbagai tipu msulihat yang
merupakan bekas-bekas dari pembelahan kerajaan oleh
Airlangga itu ternyata mengakar kuat sampai kepada
masa Majapahit. Bukan hanya pada masa Majapahit
akhir, namun pada masa transisi Tumapel ke berdirinya
Majapahit. Nararya Wijaya atau yang biasa kita sebut
sebagai Raden Wijaya, ia putera Dyah Lembu Tal atau Cri
Harsawijaya, penguasa Janggala yang disebutkan dalam
Prasasti Mula Malurung bertarik 1255 M dan Prasasti
Balawi bertarik 1305 M, dan kakek Wijaya adalah
Bhatara Narashingamurti. Wijaya, yang dipandang
sebagai tokoh besar, pahlawan, dan merupakan tokoh
Protagonis dalam Sejarah Indonesia dan Sejarah masa
~ Legenda Tuban ~ 159
awal berdirinya Majapahit, ternyata juga memicu
pertikaian dengan para sentana dan sekutu setia
Majapahit pada awal pemerintahannya. Seperti yang
terjadi pada Ranggalawe dan keluarga Ranggalawe,
mereka semua dilibas dan tidak dibiarkan sedikit pun
untuk tinggal diam dan dapat berdiri menikmati kejayaan
selama Majapahit berdiri tegak di Bhumi Jawa.
Hal ini menunjukkan, selain membawa sisa-sisa
kebudayaan yang terjadi semenjak pembelahan kerajaan
oleh Airlangga, perpecahan, peperangan, dan tipu
muslihat itu masih saja merupakan suatu budaya dan
tradisi politik turun-temurun dari era awal Majapahit
hingga era Majapahit akhir.
Hal yang sama pun juga terjadi pada era Majapahit
akhir. Majapahit, yang beribukota di Trowulan, haruslah
berakhir pada tahun 1478 M setelah digempur oleh
Demak pada masa pemerintahan Sultan Jin Bun atau Al-
Fatah, yang biasa disebut sebagai Raden Patah dalam
berita tradisi. Raden Patah atau Raden Hassan atau
Panembahan Jin Bun ialah putera selir Prabu Cri
Kertabhumi yang terlahir dari seorang selir Tionghoa asal
Tandhes (Gresik) bernama Siu Ban Chi atau Tan Eng
160 ~ Legenda Tuban ~
Kian. Siu Ban Chi adalah puteri seorang ulama dan
Saudagar kaya asal Tandhes, yaitu Babah Bantong atau
Syeikh Bentong, yang memiliki sebutan Tionghoa Siu
Tek Yo atau Tan Go Hwat. Prabu Cri Kertabhumi adalah
putera bungsu Cri Rasajawardhana Dyah Wijayakumara
‘Sang Sinagara’, raja Majapahit yang memerintah selama
3 tahun sejak tahun 1451-1453 M. Setelah
Rajasawardahana Dyah Wijayakumara ‘Sang Sinagara’,
berturut-turut yang menduduki tahta pada masa Majapahit
akhir ialah Girishawardhana Dyah Suryawikrama (1456-
1466 M), Singawikramawardhana Dyah Suraprabhawa
(1466-1468 M). Setelah tersingkir dari istana
Suraprabhawa ini kemungkinan besar bersembunyi di
wilayah pegunungan, karena pada tahun 1473 M ia
mengeluarkan Prasasti Sendang Sedati atau Prasasti
Pamintihan bertarik 1473 M yang dikeluarkan oleh putera
sulungnya sebagai raja Majapahit berikutnya, yaitu Cri
Maharaja Singawardhana Dyah Wijayakusuma, Cri
Maharaja Cri Singawardhana Dyah Wijayakusuma
(1468-1474 M).
Wijayakusuma adalah putera sulung
Surapabhawa, kakak kandung Dyah Ranawijaya. Ia
~ Legenda Tuban ~ 161
menduduki tahta Majapahit setelah ayahandanya terusir
dari kedhaton Majapahit saat kedhaton Majapahit
digempur oleh pasukan Keling pimpinan pamannya, yaitu
Bhre Kertabhumi. Namun hal itu tidaklah bertahan lama,
karena belum genap satu bulan berlalu, pasukan Kedhaton
Pandan Salas dan sisa-sisa pasukan Majapahit yang pro
mendukung pihak Surapabhawa dibawah pimpinan Dyah
Wijayakusuma menggempur Kotaraja Trowulan.
Kotaraja Majapahit di Trowulan berhasil dikuasai, berikut
seisi Kedhaton Majapahit. Pasukan Keling terpukul
mundur, banyak yang mati dibantai oleh pasukan
Majapahit dan Pandan Salas pimpinan Wijayakusuma.
Wijayakusuma pun ditobatkan menjadi Maharaja
Majapahit dan bertakhta menggantikan kekuasaan
ayahandanya, Dyah Surapabhawa.
Wijayakusuma juga turut menerbitkan Prasasti
Pamintihan atau Prasasti Sendang Sedati, yang didalam
buku-buku Sejarah dan menurut pakarnya, disebut
dikeluarkan sendiri oleh Suraprabhawa. Suraprabhawa
yang dikudeta ternyata tidaklah mati, tetapi justru
memberikan kesempatan kepada putera sulungnya untuk
menduduki takhta Majapahit sebagai raja Majapahit
162 ~ Legenda Tuban ~
berikutnya. Sesuai dengan jasa-jasa seorang tokoh yang
berasal dari Desa Pamintihan, bernama Sang Arya
Surung, berkat jasa-jasanya dan pengabdiannya kepada
Maharaja Dyah Surapabhawa yang tiada hentinya, maka
Sang Arya Surung pun mendapatkan anugerah berupa
penetapan sima oleh Prabu Cri Singakiwramawardhana
Dyah Suraprabhawa kepada Sang Arya Surung berupa
sebidang tanah di Desa Pamintihan dengan status
perdikan dan menjadi hak milik turun-temurun tanpa
batas karena kesetiaan Sang Arya Surung pada raja.
Perintah raja Cri Singawikramawardhana ini
kemudian diturunkan, dan disahkan lewat perantara
putera sulungnya yang telah menjadi raja di Majapahit,
yaitu Prabu Cri Singawardhana Dyah Wijayakusuma,
dalam bentuk Prasasti. Dyah Wijayakusuma mangkat
pada tahun 1474 M bertepatan dengan ayahandanya,
Prabu Cri Singawikramawardhana Dyah Suraparbhawa.
Tahta bergilir jatuh kepada keturunan mendiang
Rajasawardhana Dyah Wijayakumara ‘Sang Sinagara’,
yaitu Bhre Kertabhumi. Kertabhumi adalah raja
Majapahit terakhir yang memerintah selama 4 tahun
(1474-1478 M), ia disebut dalam tuturan kisah babad,
~ Legenda Tuban ~ 163
serat, kidung, dan kisah-kisah legenda sebagai ‘Prabu
Brawijaya V’ atau ‘Prabu Brawijaya Pamungkas’. Dan
pada tahun 1478 M dengan didorong oleh pergerakan
militansi para Ulama Wali Songo yang tergabung di kubu
Giri yang dipelopori oleh Sunan Giri atau Raden Paku
ditambah dengan pasukan Kesultanan Islam Demak
Bintoro yang dirajai oleh Jin Bun atau Patah, maka
terjadilah kudeta besar-besaran yang menghancurkan
sendi-sendi pemerintahan Majapahit yang beribukota di
Trowulan.
Majapahit berhasil dibobol, dijebol, dan
dihancurkan. Majapahit harus mengubur dalam-dalam
impian mereka sebagai Kemaharajaan terbesar di
Nusantara. Setelah akhirnya kerajaan sebesar Majapahit
ini dihancurkan dengan susah payah oleh Demak Bintoro
dibawah pimpinan Jin Bun. Demak pun keluar sebagai
pemenang dalam kudeta berdarah di tahun 1478 M ini.
Konflik dan kudeta berdarah tak berhenti sampai
di situ. Majapahit yang beribukota di Trowulan akhirnya
diserahkan kepada seorang penguasa berdarah Tionghoa
dan beragama Muslim. Ia tampaknya masih merupakan
kerabat Keraton Islam Demak Bintoro, namanya adalah
164 ~ Legenda Tuban ~
Nyoo Lay Wa Nyoo Lay Wa. Ia diangkat dan diberikan
kuasa atas bekas ibukota lama Majapahit di Trowulan. Ia
adalah ‘Raja Majapahit Boneka’nya Demak, dan oleh
karena pengangkatannya pula maka, dalam
pemerintahannya ia sendiri sering mengalami berbagai
tekanan dan huru-hara yang lantas merongrong tahta dan
kedudukannya. Dalam sumber sekelas naskah Kronik
Sam Poo Kong yang ditemukan dan diulas oleh Residen
Poortman dari Belanda, diketahui bahwa Nyoo Lay Wa
ini berkuasa dari tahun 1478-1486 M.
Ia memerintah selama delapan tahun, karena pada
tahun 1486 M, adik bungsu Dyah Wijayakusuma, yaitu
Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, dengan bantuan
kakak sepupunya Sang Munggwin Jinggan yaitu Bhre
Matahun Wijayaparakrama Dyah Samarawijaya, sisa-sisa
pasukan Majapahit yang loyal kepada Trah Rajasa dan
keluarga Majapahit sendiri, dan bantuan Brahmana Cri
Brahmaraja Ganggadhara, menggempur Kotara
Majapahit di Trowulan yang diperintah oleh Nyoo Lay
Wa.
~ Legenda Tuban ~ 165
Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini adalah
salah seorang menantu Prabu Cri Kertabhumi yang
dinikahkan dengan salah seorang puteri selirnya. Ketika
mendapati berita bahwa kakak tertuanya dan ayahandanya
meninggal, maka Ranawijaya segera diambil sebagai
salah seorang menantu Kertabhumi. Ia pun juga
ditabalkan menjadi Bhre Keling, menggantikan
Wijayakusuma yang mangkat dan kedudukan ayah
mertuanya, Kertabhumi, yang sebelumnya juga menjabat
sebagai Bhre Keling. Begitu ia mendapati berita
kekalahan ayah mertuanya dan kehancuran Majapahit di
Trowulan, Ranawijaya masih belum menentukan sikap
untuk dapat merebut kembali tahta ayah mertua sekaligus
tahta ayahandanya yang dulu pernah mereka duduki dari
tangan Demak.
Ranawijaya masihlah enggan, sebab dahulu tahta
ayah kandungnya juga direbut oleh ayah mertuanya
sendiri, yaitu Prabu Cri Kertabhumi atau Brawijaya V.
Namun setelah didesak oleh Brahmana Cri Brahmaraja
Ganggadhara dan dukungan dari sisa-sisa para sentana
Majapahit itu yang masih bersetia dan berpihak kepada
keluarganya, maka Ranawijaya segera mengambil
166 ~ Legenda Tuban ~
tindakan. Ia kumpulkan pasukan kedhaton Keling, sisa-
sisa sentana Majapahit, ditambah juga kakak sepupunya,
Wijayaparakrama Dyah Samarawijaya, juga ikut
membantunya menggempur Kotaraja Trowulan di
Majapahit. Selain itu, Brahmana Cri Brahmaraja
Ganggadhara, yaitu Brahmana Ciwa yang telah menjadi
pendukung setia Prabu Cri Singawikramawardhana Dyah
Suraprabhawa, juga ikut membantu Dyah Ranawijaya.
Pertempuran besar-besaran antara pasukan Keling
pimpinan Ranawijaya yang dibantu dengan sekutunya
melawan pihak Majapahit Boneka-nya Demak pun pecah.
Pertempuran besar ini benar-benar menjadi pertempuran
kedua belah pihak, antara keluarga Majapahit melawan
pihak Demak Bintoro. Dan setelah menghadapi
serangkaian peperangan yang melelahkan dan saling
bunuh, maka pemenangnya berhasil dimenangkan oleh
pihak keturunan Trah Rajasa, keturunan Majapahit.
Ranawijaya berhasil memenangkan pertempuran besar
melawan pihak Demak Bintoro yang dirajai oleh Nyoo
Lay Wa dan sekaligus memupuskan harapan Demak
untuk menguasai takhta Majapahit.
~ Legenda Tuban ~ 167
Ranawijaya beserta pasukan dan sekutunya
berhasil meraih kemenangan yang gilang-gemilang.
Namun naasnya, kakak sepupu Ranawijaya, yaitu Sang
Munggwin Jinggan, yaitu Wijayaparakrama Dyah
Samarawijaya harus meregang nyawa di palagan perang
ketika berhadapan dengan pasukan Demak. Melihat
bahwa Kotaraja Majapahit di Trowulan telah dikuasai
oleh musuh, maka seperti kepercayaan masyarakat Jawa
pada umumnya, rumah atau sebuah istana yang telah
diduduki oleh musuh sudah tidak layak lagi untuk
diduduki. Maka, Ranawijaya segera memindahkan pusat
pemerintahan Majapahit di pedalaman Daha. Ranawijaya
juga diwisuda sebagai Raja Majapahit baru, penerus Trah
Rajasa, dan juga telah membebaskan Majapahit dari
cengkeraman bayang-bayang Demak yang dikuasai oleh
orang asing. Ranawijaya menjadi Maharaja Majapahit
dengan gelar “Cri Maharaja Wilwatiktapura Janggala
Kadhiri Prabu Nata Girindrawardhana Dyah Ranawijaya’.
Setelah berhasil menjadi Maharaja Majapahit
yang baru dan kemudian melepaskan Majapahit dari
cengkeraman Demak, Ranawijaya menerbitkan Prasasti
Kembangsore atau Pethak dan Prasasti Trailokyapuri atau
168 ~ Legenda Tuban ~
Jiyu (Jiyu I-IV), kesemuanya bertarik 1408 Caka atau
1486 M. Ranawijaya, dalam Prasasti Pethak dan Jiyu,
kembali menegaskan dan mengukuhkan status perdikan
dhama ring Trailokyapuri dan Pethak agar semua wilayah
itu menjadi hak turun-temurun bagi Cri Brahmaraja
Ganggadhara dan keluarganya. Cukup lama pemerintahan
Dyah Ranawijaya, selama empat puluh satu tahun ia
memerintah, dari sejak tahun 1486 M–1527 M. Namun,
malapetaka terjadi di istana Majapahit yang beribukota di
Daha. Kala itu, pada tahun 1499 M, Mahapatih
Hamangkhubhumi Majapahit bernama Arya Udara
melakukan makar. Ia berhasil mengudeta Ranawijaya dari
atas tahta Majapahit dan memproklamirkan diri sebagai
raja baru Majapahit menggantikan Ranawijaya.
Menurut keterangan Serat Babad Tanah Jawi,
Maha Patih Arya Udara merupakan anak dari Mahapatih
Hamangkhubhumi ‘Pu Wahan,. ‘Pu Wahan adalah Maha
Patih yang sebelumnya mendampingi Girindrawardhana
Dyah Ranawijaya di awal masa pemerintahannya. Tetapi
setelah itu kedudukannya digantikan oleh puteranya, Arya
Udara, yang menjabat sebagai Maha Patih
Hamangkhubhumi di Majapahit. Udara mendampingi
~ Legenda Tuban ~ 169
Ranawijaya sebagai Mahapatih Hamangkhubhumi pada
masa akhir pemerintahannya. Udara memerintah sebagai
di Majapahit dari sejak tahun 1499-1512 M. Alasan Udara
melakukan tindakan makar ini adalah karena sebelum ia
menjadi Mahapatih Hamangkhubhumi di Majapahit,
dulunya ia sempat pergi meninggalkan kedhaton karena
pertikaiannya dengan Mahapatih Hamangkhubhumi
Majapahit pada masa Rani Dyah Suhita berkuasa, yaitu
Mahapatih Hamangkhubhumi Gajah Kanaka atau Gajah
Tanaka. Patih Gajah Kanaka atau Gajah Tanaka ini
memegang jabatan Mahapatih Amangkhubhumi
semenjak tahun 1410-1433 M. Gajah Kanaka atau Gajah
Tanaka atau Tuan Tanaka ini sendiri dalam kisah Serat
Damarwulan disebut sebagai ‘Mahapatih Loh Gender’.
Cerita rakyat di sebuah Desa di Jember juga
menyangkut-pautkan tentang kisah masa lalu Udara.
Cerita rakyat ini tepatnya berasal dari Dusun Paloombo
(Palu Ombo/Paluhombo/Paluhomba) adalah salah satu
Dusun yang tertelak di Desa Sumber Salak, Kecamatan
Ledok Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pertikaian
antara Arya Udara dengan Gajah Kanaka atau Patih Loh
Gender ini bermula ketika Udara muda memiliki seorang
170 ~ Legenda Tuban ~
isteri yang sangat cantik. Ketika isterinya mengandung
dan sedang hamil tua, Udara muda tiba-tiba diusir keluar
dari kedhaton tanpa alasan dan sangat tiba-tiba. Padahal
kala itu isterinya sedang hamil tua, dan ia harus
meninggalkan istana Majapahit.
Menurut penuturan seorang bapak yang biasanya
disebut sebagai Cak Fakhtur, seorang keturunan Madura
yang tinggal di Dusun Paloombo tersebut, ia menuturkan
bahwa sebelum kepergiannya, Patih Maudoro atau Arya
Udara berpesan kepada istrinya tersebut, agar menyusul
ke Gunung Argo Giri jika isterinya diganggu oleh Patih
Loh Gender. Mengapa harus pergi ke Argo Giri? Karena
di situlah dia akan bertemu dengan ayahnya Patih
Maudoro atau Arya Udara, yang berjuluk Resi Paluombo
(Paluhombo/Paluhomba). Pashraman Paloombo atau
Paluhombo atau Pashraman Paluhomba didirikan oleh
seorang Begawan bernama Begawan Musthikamaya.
Begawan Mustikhamaya sendiri sebenarnya
adalah Bhre Paguhan Kapisan, yaitu Raden Sumana, ayah
Raden Damar Wulan atau Raden Aji Ratnapangkaja.
Sedangkan tokoh Resi Paloombo sebagai sosok Ayah
Arya Udara yang dituturkan oleh Cak Fakhtur sendiri
~ Legenda Tuban ~ 171
tidak lain dan tidak bukan ialah ‘Pu Wahan. ‘Pu Wahan
sering bertapa menyepi di Pashraman Paluhomba atau
Paluhombo atau Paloombo itu. Dan jika ia bergi bertapa
dan menyepi lebih jauh, maka ia akan bertapa di atas
puncak Pegunungan Argo Giri tersebut.
Arya Udara atau Mahodara atau Maudoro atau
Pate Amdura akhirnya harus berpisah dengan isteri dan
calon jabang bayinya tersebut untuk waktu yang lama. Ia
menyadari, bahwa Patih Loh Gender sendiri adalah orang
besar, memiliki wibawa dan pengaruh besar, tetapi sayang
kelemahannya adalah sifatnya yang berangasan dan
sering menggoda perempuan-perempuan cantik. Pada
masa pemerintahan Bhatara Prabu Aji Wikramawardhana
sampai pada masa pemerintahan Aji Ratnapangkaja atau
yang disebut sebagai Raden Damar Wulan.
Udara muda yang terusir dari kedhaton akhirnya
menjalani kehidupannya selama bertahun-tahun dengan
bertapa, puasa, semadhi, dan berbagai lelaku lainnya yang
dilakukan oleh keturunan Resi maupun Brahmana. Udara
merasa sakit hati atas penghinaan dan pengusirannya ke
luar kedhaton karena ulah Patih Loh Gender atau Gakah
Kanaka. Untuk itu, Udara berniat membalas dendam
172 ~ Legenda Tuban ~
kepada keturunan Trah Rajasa yang menjadi Raja
Majapahit pamungkas. Siapa pun dia. Tidak peduli laki-
laki ataupun perempuan, pihak kedhaton harus membayar
atas semua penghinaan yang tak tertanggungkan ini
kepadanya. Ia bersumpah untuk menjadi raja Majapahit
dan merebut tahta Majapahit dari tangan keturunan Trah
Rajasa Majapahit.
Saat-saat yang ditunggu oleh Udara pun akhirnya
datang. Ia terpilih oleh Dewan Bhatara Sapta Prabu
untuk menggantikan kedudukan ayahandanya, ‘Pu
Wahan dan Udara menjadi Mahapatih Hamangkhubhumi
mendampingi Ranawijaya pada masa akhir
pemerintahannya saat usia Ranawijaya sudah uzur. Udara
menjadi Mahapatih Hamangkhubhumi pada awal tahun
1499 M, dan pertengahan tahun 1499 M ia berhasil
mengkudeta dan mengusir Ranawijaya keluar dari
kedhaton. Keluarga Majapahit akhirnya harus
bersembunyi di sebuah tempat perlindungan yang aman,
agar jangan sampai pasukan Majapahit yang diperintah
oleh Udara menemukannya. Maka dilarikannya
Ranawijaya beserta keluarga Majapahit lainnya menuju
ke Blambangan. Di situ, Ranawijaya menceritakan semua
~ Legenda Tuban ~ 173
permasalahan yang menimpanya kepada penguasa
Blambangan dan ia memohon bantuan dengan sangat agar
dapat merebut kembali takhta Majapahit. Persetujuan
kedua belah pihak pun akhirnya berhasil dicapai. Kedua
belah pihak memutuskan bekerjasama.
Pengelana asal Portugis, Tom Pires, dalam catatan
perjalanannya selama di Jawa – yaitu Suma Oriental –
menuliskan mengenai sosok Prabu Cri Udara atau Arya
Udara ini. Dalam catatan Tom Pires, Suma Oriental, Tom
Pires menyebut Udara sebagai Pate Udra (atau Pate
Amdura). Pires menyatakan dalam Suma Oriental, bahwa
Guste Pate (Gusti Patih atau Mahapatih, yang dimaksud
disini ialah Udara) memiliki kekuasaan yang cukup besar.
Meskipun hanya sebagai Patih (viso rey) dan panglima
perang (capitam moor), ia sangat disegani sehingga
dianggap hampir setara seperti raja.
Demikianlah tuturan Tom Pires dalam Suma
Oriental mengenai sosok Patih Udara dalam Suma
Oriental:
“Para bangsawan Jawa dimuliakan dan dipatuhi
seperti Dewa. Negeri Jawa di bagian pedalaman
berpenduduk padat, memiliki banyak kota besar, di
174 ~ Legenda Tuban ~
antaranya adalah Kota Dayo (Daha), di mana Raja Jawa
tinggal. Sang Raja jarang menampakkan diri di depan
umum, hanya sekali-dua kali saja dalam setahun. Raja
Jawa lebih suka berdiam di istana bersama para istri dan
selir. Mereka hidup dalam pesta dan kesenangan.
Kabarnya, Raja Jawa (Bahatara Prabu) memiliki seribu
kasim untuk menjaga para wanita itu.
Rakyat Jawa tidak percaya lagi kepada perintah
Raja karena mereka kecewa telah kehilangan sebagian
besar tanahnya. Sebenarnya orang yang berkuasa atas
Jawa saat ini adalah Guste Pate (Gusti Patih, Mahapatih
Hamangkhubhumi, yaitu Udara). Semua pemimpin di
Jawa tunduk kepadanya. Ia menguasai segala aspek,
menggenggam Raja di tangannya (Seperti Raja Boneka).
Dialah orang yang berhak memberikan perintah agar Raja
diberi makan. Sang Raja tidak lagi dianggap penting.
Guste Pate adalah penguasa yang sebenarnya di
Negeri Jawa. Sebelumnya, ia dikenal dengan nama Pate
Amdura (Pate Udra, Mahodara, Amdura, atau Mahapatih
Udara). Ia juga mertua Sang Raja. Guste Pate (Amdura
atau Patih Udara) ini adalah seorang kesatria, selalu maju
dalam peperangan. Ia selalu berperang melawan orang
~ Legenda Tuban ~ 175
Moor (kaum Muslim) di pesisir Pantai (Pantai Utara),
terutama melawan penguasa Demak. Pada saat maju
berperang, Guste Pate selalu membawa 200.000 prajurit,
yang mana dua ribu di antaranya adalah prajurit berkuda,
serta empat ribu prajurit bersenapan.”
Dari penuturan Tom Pires dalam cuplikan Suma
Oriental di atas, jelaslah bahwa Arya Udara, selain terlahir
sebagai seorang Brahmana, ia pun juga menguasai ilmu
kanuragan sehingga dapat dengan mudah menggerakan
pasukan dan melawan pasukan musuh yang menyerang.
Brahmana-Ksatriya, seperti layaknya tokoh Brahmana
Dronacharyya atau Mahaguru Drona. Oleh karena itulah,
maka rakyat Majapahit lebih menghormat dan segan
terhadap seorang tokoh Arya Udara, baik sebagai
Brahmana, Mahapatih, maupun seorang Ksatria
sekaligus. Dengan kemampuan yang ia dapat sebagai
seorang Brahmana-Ksatriya seperti layaknya Mahaguru
Drona, maka pantaslah sosok seorang Udara lebih pantas
menjadi raja di Majapahit daripada Ranawijaya sendiri.
Oleh karena didorong keinginan dendamnya terhadap
Majapahit yang telah tega mengusirnya dari istana pada
masa mudahnya, maka hal itulah yang semakin
176 ~ Legenda Tuban ~
menegaskan kedudukan Udara sebagai Mahapatih
Hamangkhubhumi sekaligus penguasa di Majapahit.
Pada akhirnya, Udara berhasil disingkirkan oleh
Ranawijaya melalui bantuan penguasa Blambangan kala
itu, Prabu Menak Pintor, yang disebut dalam Suma
Oriental sebagai Pate Pimtor dalam pengucapan Portugis.
Mengenai sosok Prabu Menak Pintor atau Pate Pimtor
sebagai penguasa Blambangan yang ikut membantu
Ranawijaya mengkudeta Udara, Tom pires menuliskan
sebagai berikut:
“Penguasa Blambangan (Balumbuam) bernama
Pate Pimtor (masyarakat Blambangan atau Banyuwangi
di kemudian hari menyebut tokoh ini sebagai Prabu
Menak Pintor), seorang Pagan yang agung dan dihormati
di Jawa. Ia menahan kaum Moor (Muslim) sehingga tidak
dapat bertindak lebih jauh lagi. Negerinya memiliki
penduduk yang besar. Rakyatnya sederhana dan patuh
kepada Guste Pate. Pate Pimtor merupakan putra dari
saudara perempuan Guste Pate (Mahapatih Udara atau
Pate Amdura). Ia hidup dari hasil panennya. Ia juga
memiliki banyak kuda, dan lebih banyak dibanding para
Pate lainnya di Jawa. Budak-budaknya juga banyak
~ Legenda Tuban ~ 177
sekali. Konon budak-budak yang dijual di seluruh penjuru
Jawa berasal dari negeri ini.”
Meskipun Ranawijaya berhasil meyingkirkan
Udara dan mengukuhi kembali tahta Majapahit, tetapi –
seperti yang disebutkan dalam catatan Suma Oriental
Tom Pires mengenai sosok patih Udara ini – Udara tidak
lantas mati setelah Ranawijaya menyingkirkannya. Ia
justru menyingkir melarikan diri dari kejaran pasukan
musuh pimpinan Ranawijaya. Udara lantas mencari
perlindungan. Salah seorang Tumenggung yang sekaligus
menjabat sebagai Adipati di Tuban, yaitu Arya
Wilwatikta atau Pangeran Shantibadra, ayahanda Sunan
Kalijaga atau Pangeran Shantikusuma atau Raden Sahid
(Syeikh Malayakusuma) ternyata bersahabat baik dengan
Udara. Tentu saja Udara sangat senang karena ia dapat
memilih Tuban sebagai tempat persembunyiannya yang
tidak mungkin diketahui oleh Ranawijaya maupun pihak-
pihak Majapahit lain sekalipun.
Pangeran Shantibhadra atau Arya Wilwatikta
sebenarnya adalah seorang beragama Muslim, tetapi dari
catatan Tome Pires dalam Suma Oriental menerangkan
bahwa Shantibhadra atau Arya Wilwatika ini – dalam
178 ~ Legenda Tuban ~
ejaan Portugis ia disebut sebagai pate Vira – ia adalah
seorang Muslim yang tidak taat. Ketidaktaatan
Shantibhadra ini dikarenakan, selain memeluk Islam,
Shantibhadra atau Arya Wilwatikta ini jugalah menjadi
Samanera Buddha yang dikenal sebagai ‘Mpu Shanti
Bhadra’ dalam tuturan kisah Sejarah Carita Lasem (CSL).
Ia memiliki sejumlah besar selir. Pires mencatat bahwa
jumlah selir Wilwatikta sebanyak 200 orang wanita.
Ditambah lagi, di dalam istana Kadipaten Tuban sendiri,
Pate Vira atau Arya Wilwatikta memelihara anjing.
Anjing, oleh sebagian besar kaum Muslim kala itu,
dipandang sebagai binatang yang menajiskan. Yang
menajiskan dari seekor anjing adalah air liurnya, karena
dengan terkena sedikit saja air liur seekor anjing, maka
seorang pemeluk agama Muhammad atau Muslim akan
dikatakan najis. Tome Pires menyebutkan persekutuan
dan persahabatan Udara dengan Arya Wilwatikta sebagai
berikut:
“Antara Guste Pate (Mahapatih Udara) dan Tuban
ada kesepakatan untuk saling membantu. Itu karena para
Pate Moor (Muslim) membenci Pate Vira (Adipati Arya
Wilwatikta) yang akrab dengan para Pate Pagan. Pate
~ Legenda Tuban ~ 179
Vira tidak takut pada siapa pun dan penduduk Tuban juga
adalah kaum pemberani yang melebihi penduduk Jawa
lainnya. Pertemanan dengan Guste Pate membuat Pate
Vira kaya raya. Ia memiliki banyak keris, tombak, trisula
berburu, seribu anjing pemburu dan jenis lain, serta 200
selir, juga rumah-rumah besar dan indah. Setiap pagi ia
mengendarai kereta berukir indah, namun tidak
memunculkan diri di pedesaan. Ia cenderung menutup diri
dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk berburu
daripada di dalam kota.”
Mahapatih Udara atau Prabu Udara menyingkir
dari Kotaraja Majapahit di Daha setelah ia disingkirkan
oleh Ranawijaya, kemudian ia menyingkir ke Tuban. Di
Tuban, ia bertemu dengan Arya Wilwatikta. Sebagai
seorang sahabat dari Patih Udara, maka atas perkenanan
Adipati Tuban Arya Wilwatikta, Udara mendapatkan
perlindungan di Tuban. Sebagai sosok sahabat dan segan
terhadap sahabatnya yang sedang dikejar-kejar oleh
gabungan pasukan Majapahit dan Blambangan, maka
Udara diungsikan oleh Wilwatikta atau Shantibhadra
menuju ke daerah pegunungan yang penuh perbukitan. Di
sana lantas Udara juga dibuatkan sebuah kedhaton
180 ~ Legenda Tuban ~
sebagai perlindungan oleh pihak Kadipaten Tuban atas
perintah Adipati Tuban Arya Wilwatikta.
Kedhaton itu disebut sebagai Kedhaton Maja
Agung (Mojoagung). Lama-kelamaan bekas benteng dan
istana kedhaton milik Udara disebut sebagai Bejagung
oleh masyarakat Tuban. Di Tuban sendiri, keberadaan
benteng dan istana kedhaton Maja Agung milik Udara ini
dikaitkan dengan makam sosok penyebar ajaran Islam di
Tuban, seorang Waliyullah, bernama Syeh abdul asy'ari
atau yang biasa disebut sebagai Sunan Bejagung oleh
masyarakat Tuban pada umumnya. Tumpukan dan
timbunan batu bata kuno pada abad XV di lokasi makam
Waliyullah Syeh abdul asy'ari, baik Sunan Bejagung Lor
maupun Sunan Bejagung Kidul, sudah sangat
membuktikan keberadaan letak posisi benteng dan istana
kedhaton Mahapatih Udara yang menyingkir ke Tuban
dan dilindungi oleh pihak Tuban.
Selain itu, ada lagi sebuah Gang di Kabupaten
Tuban yang dinamai dengan nama ‘Gang Atas Angin –
Brawijaya, Gang Dondong, Kelurahan Gedongombo,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Disini, ada sebuah makam keramat yang disebut-sebut
~ Legenda Tuban ~ 181
oleh masyarakat sekitar dipercayai sebagai makam Prabu
Brawijaya VII atau Prabu Brawijaya Pamungkas.
Barangkali yang dimaksud sebagai Brawijaya Pamungkas
ini adalah sosok Udara sendiri. Karena terdapat dua
makam kuno keramat di wilayah Atas Angin, Tuban, yang
dimana makam keramat yang satu disebut sebagai Makam
Keramat Prabu Atas Angin atau Makam Atas Angin
(Ngatas Angin), dan makam keramat satunya lagi ialah
Makam Keramat Prabu Brawijaya VII atau Prabu
Brawijaya Pamungkas. Semenjak masa Majapahit, orang-
orang asing yang datang dari Negara Tetangga Majapahit
(atau bahkan sebelum Majapahit sendiri berdiri), bangsa-
bangsa yang datang ke Nusantara disebut sebagai ‘Orang-
orang Atas Angin’ atau ‘Ngatas Angin’. Ngatas Angin
atau Atas Angin, sebutan ini begitu mencolok ketika pada
masa abad ke-15, yaitu semenjak Majapahit telah
mengalami masa kemundurannya dan masa redupnya.
Untuk pengertian Atas Angin sendiri ada dua hal yang bisa
kita simpulkan sebagai berikut:
1) Mereka adalah orang-orang asing yang berasal dari
Negara Tetangga Majapahit (atau sebelum Majapahit
182 ~ Legenda Tuban ~
ada), dan mereka sebagai pemeluk agama Muhammad
(Muslim).
2) Sebuah wilayah yang berada di atas gunung dan
dipenuhi perbukitan, sehingga wilayah atau daerah
tersebut yang berapa pada dataran tinggi itulah yang
oleh orang-orang masyarakat sekitar disebut dengan
sebutan ‘Negara Atas Angin’ (Negeri Ngatas Angina
tau Negeri Di Atas Angin).
Hal ini didasarkan atas cerita rakyat di Jawa Timur
mengenai kisah sosok seorang Raja yang memerintah di
sebuah kerajaan yang letak kerajaannya sendiri hampir
menyentuh langit. Karena itulah disebut dengan sebutan
‘Prabu Ngatas Angin’. Sebetulnya hal ini merupakan
sebuah sanepan belaka, karena arti sesungguhnya dari
Kerajaan Atas Angin dan sosok Prabu Atas Angin sendiri
sebenarnya ialah kiasan atau sanepan seorang raja yang
tinggal di wilayah pegunungan atau wilayah perbukitan,
mendirikan istana di sana, dan karena wilayah
pegunungan atau perbukitan tersebut jauh dan sulit untuk
dijangkau oleh musuh, maka karena itulah raja tersebut
berkuasa penuh atas wilayah sekitar pegunungan dan
perbukitan tersebut. Dan karena hal tersebut, sang raja
~ Legenda Tuban ~ 183
lantas digelari dengan sebutan: Prabu Ngatas Angin
(Prabu Atas Angin). Dan sosok orang yang tepat digelari
sebagai Prabu Atas Angin ini, tidak lain dan tidak bukan
adalah Prabu Cri Udara atau Mahapatih
Hamangkhubhumi Arya Udara.
Kedhaton Maja Agung (Mojo Agung) Udara –
yang oleh tutur masyarakat sekitar Tuban disebut
‘Kerajaan Atas Angin’- itu tidak bertahan lama pada
akhirnya. Pada tahun 1527 M, aliansi pasukan Demak
Bintoro dibawah pimpinan Sultan Trenggana atau
Sinuwun Trenggana melakukan ekspansi dan
penyerangan terhadap Majapahit yang beribukota di
Daha. Langkah pertama Demak adalah dengan
menghancurkan Kedhaton Maja Agung beserta benteng
pertahanannya sebagai pertahanan terakhir Udara. Udara
melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan Demak
Bintoro yang merangsek, namun sayang mereka sudah
berhasil menghancurkan benteng kedhaton dan dengan
cepat segera memasuki kedhaton. Kedhaton Udara,
Kedhaton Maja Agung (Mojo Agung atau Bejagung)
akhirnya dapat dihancurkan dan Udara sendiri mati
terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah berhasil
184 ~ Legenda Tuban ~
menghcurkan Kedhaton Maja Agung atau Bejagung milik
Udara, Trenggana mengalihkan pasukannya menuju ke
Daha, Ibukota Kerajaan Majapahit pimpinan Ranawijaya.
Ranawijaya dan seluruh pasukannya melawan dengan
sengit, namun tetap saja mereka semua tidak bisa
membendung kekuatan pasukan Demak pimpinan
Trenggana tersebut. Nasib serupa juga dialami oleh
Ranawijaya, sama seperti Udara. Dan berakhirlah
kekuasaan Kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara
dan Asia Tenggara, Majapahit hancur, musnah, ‘Sirna
Illang Kerthaning Bhumi’ (Sirna Hilanglah Kemuliaan
Bumi).
~ Legenda Tuban ~ 185
Daftar Acuan:
Damar Shasangkha, Sabda Palon 3 “Geger Majapahit”,
Cetakan-1: Februari 2016, Tanggerang Selatan:
Penerbit Dlphin.
Damar Shasangkha, Sabda Palon 4 “Pudarnya Surya
Majapahit”, Cetakan-1: Februari 2016, Tanggerang
Selatan: Penerbit Dolphin.
Makkinudin Samin, Ranggalawe, Sang Penakluk
Mongol, Cetakan-1: Februari 2018, Tanggerang
Selatan: Javanica (PT. Kaurama Buana Antara).
Tom Pires, Suma Oriental: Perjalanan Dari Laut Merah
Ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues, 2017,
Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Makkinudin Samin, Ahangkara: Sengketa Agama dan
Kekuasaan, Cetakan-1: 2017, Tanggerang Selatan:
Javanica (PT. Kaurama Buana Antara).
Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik: Sebuah Epos Pasca
kejayaan Nusantara di awal abad ke-16, Cetakan-1:
2002, Hasta Mitra.
Cerita Tutur Masyarakat Tuban sekitar Makam Sunan
Bejagung Lor dan Sunan Bejagung Kidul.
186 ~ Legenda Tuban ~
Cerita Tutur Masyarakat Tuban sekitar Makam Ngatas
Angin dan Makam Prabu Brawijaya Pamungkas.
Cerita Sejarah Lasem, digubah pada tahun 1858 oleh
Raden Panji Hamza, tanpa penerbit.
W.L. Olthof, Babad Tanah Djawi, 1941, teks Bahasa
Jawa, hlm. 17-18, Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Prof. Dr. Slamet Muljana, ‘Runtuhnya Kerajaan Hindu
Jawa dan Berdirinya Negara-negara Islam di
Nusantara’, Cetakan-3: 2005, Yogyakarta: LKiS.
Hadi Sidomulyo, ‘Napak Tilas Perjalanan Mpu
Prapanca’, Cetakan-1: 2007, Jurusan Pendidikan
Sejarah FIS Unesa: Wedatama Widyasastra dan
Yayasan Nandiswara.
Prof. Dr. Slamet Muljana, ‘Negarakrtagama dan Tafsir
Sejarahnya’, Cetakan-1: 2006, Yogyakarta: LKiS.
Prof. Dr. Slamet Muljana, ‘Menuju Puncak Kemegahan:
Sejarah Kerajaan Majapahit’, Cetakan-1: 2005,
Yogyakarta: LKiS.
Serat Babad Tuban, dicetak oleh Penerbit Tan Khoen
Swie (TKS), tanpa tahun.
Serat Babad Majapahit dan Para Wali.
Serat Babad Tanah Jawi Pasisiran (Demakan).
~ Legenda Tuban ~ 187
Asal Usul Desa Sekardadi
Oleh: Nur Hidayah
Keindahan Pantai Di Jenu Tuban,
https://www.pantainesia.com
***
Sekardadi adalah nama Desa yang merupakan
bagian dari kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jawa
Timur, dengan letak wilayah sebelah barat berbatasan
dengan Desa Jenggolo, bagian timur berbatasan dengan
desa Jenu, dan bagian selatan berbatasan dengan
kecamatan Merakurak. Desa Sekardadi adalah daerah
188 ~ Legenda Tuban ~
pedesaan yang dikelilingi persawahan yang subur dan
makmur, dengan ditanami pohon-pohon rindang di
sepanjang jalan yang berada di tepi sawah membuat
suasana desa menjadi asri dan menyejukkan mata saat
melintasinya. Kantor kepala Desa tepat berada di jalan
utama Desa, tertata rapi dengan dihiasi berbagai tanaman
khas pohon tanjung dan pohon sawo kecik.
Berdasarkan versi cerita atau sejarah yang
bersumber dari sesepuh Desa Sekardadi, , Nama desa
Sekardadi mulai disebutkan pada Masa penjajahan
Belanda sekitar tahun 1940an. Sekardadi diambil dari
gabungan nama-nama dukuh yang ada di desa tersebut,
diantaranya Sekaning, Kandangan dan Kedinding. Dalam
versi lain disebutkan bahwa nama Sekardadi mempunyai
makna sebagai berikut, Sekar adalah Bunga, sedangkan
Dadi dalam bahasa Indonesia berarti Menjadi. Dari
pendapat-pendapat tersebut bisa diartikan “Bunga Yang
Menjadi Harum dan Indah” . Ibarat sebuah pohon akan
semakin indah jika dihiasi dengan adanya bunga, dengan
harapan segala sesuatu kebaikan yang bersumber dari
daerah itu mampu membawa harum nama Desa tersebut.
***
~ Legenda Tuban ~ 189
Tradisi atau warisan leluhur yang masih lestari
sampai saat ini adalah adanya acara Manganan atau biasa
disebut dengan sedekah bumi yang dilaksanakan setiap
tahunnya pada hari kamis wage, bulan Juni di makam
mbah Ndukoh. Menurut cerita Mbah Ndukoh adalah salah
satu santri dari Sunan Kalijaga yang ditelusuri melalui
masjid Astana yang ada di desa Sekardadi. Sebuah masjid
yang merupakan tempat petilasan Sunan Kalijaga pada
masa itu. Di depan masjid tersebut terdapat sungai yang
menghubungkan wilayah Kecamatan Merakurak
melewati desa Sekardadi dan bermuara di laut utara Jawa.
Secara geografis sungai tersebut sangat strategis sebagai
sarana transportasi karena pada zaman dahulu angkutan
darat belum seperti saat ini untuk membawa glondongan
kayu-kayu yang besar lebih praktis dilewatkan sungai,
Yang konon ceritanya banyak santri yang saat itu
mengambil kayu jati dari Desa Koro Kecamatan
Merakurak untuk dipergunakan membangun masjid
Demak Bintoro, didirikan oleh Raden Patah bersama Wali
songo. Adapun 4 tiang/soko Masjid menjadi tanggung
jawab 4 Wali yaitu, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan
Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Masjid Demak Bintoro
190 ~ Legenda Tuban ~
merupakan Masjid tertua di Indonesia berdiri sejak 1479
Masehi di daerah Kauman Demak Jawa Tengah, masjid
ini, situs masjid Demak sebelumnya pernah digunakan
sebagai pusat belajar dan tempat para Wali songo dalam
syiar agama Islam di Pulau Jawa Pada abad ke 15.Desain
dari bangunan Masjid Agung Demak sangat kental akan
ornamen budaya Jawa yang syarat akan makna filosofinya
menggunakan material kayu jati pilihan diantaranya yang
diangkut melalui sungai dengan melewati desa Sekardadi.
Cerita ini dikuatkan oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh
spiritual di Kabupaten Tuban.
Di masjid Astana juga terdapat sebuah makam
yang diduga adalah makam salah satu santri Sunan
Kalijaga yang meninggal sewaktu membawa kayu-kayu
tersebut, kemudian dimakamkan di dekat Masjid Astana
dan tempat tersebut terkenal dengan nama makam mbah
Soko Dedes.
Adanya kegiatan tahlil bersama yang
dilaksanakan setiap malam jum’at di makam Mbah Soko
Dedes dihadiri oleh banyak jama’ah baik dari para tokoh
Agama, tokoh spiritual, masyarakat sekitar maupun dari
desa sekitar. Dengan adanya kegiatan ini menjadikan
~ Legenda Tuban ~ 191
tempat tersebut sebagai salah satu wisata religi yang ada
di desa Sekardadi.
Di sebelah timur Makam mbah Suko Dedes ada
juga tempat yang sering diadakan acara Manganan atau
Sedekad bumi yaitu Makam bayi dan Ndok Semar. Yang
tak kalah menarik ada makam Tua Mbah Kyai
Argonegoro bin Kyai Ronggonegoro/ Syeikh Nur Sholeh,
masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan makam
Mbah Pethak (yang berarti Putih dalam bahasa Jawa)
berada di makam Waru dusun Sekaning Desa Sekardadi,
Kecamatan Jenu. Sesuai dengan Buku Tarikh silsilah para
wali yang tercatat di kabupaten Tuban beliau termasuk
urutan yang ke-65, menilik dari usia beliau hidup di masa
dakwah Sunan Bonang pada abad ke-15.
Banyak orang dari desa sekitar yang sering
melaksanakan ritual berwasilah mencari berkah dengan
berziarah di makam tersebut. Sampai sekarang makam itu
tidak pernah sepi dari pengunjung khususnya pada malam
jum’at. Menurut sejarah Mbah Ronggo Negoro yang pada
masa itu beliau telah melaksanakan syiar agama di daerah
Sekardadi.
***
192 ~ Legenda Tuban ~
Pada masa sekarang desa Sekardadi sudah
mengalami kemajuan yang besar terutama pada sektor
pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang masih
sangat muda, bersemangat, rendah hati dan dikenal ramah
terhadap semua warganya yang bernama Bapak Ahmad
Zaki, ST. Memancing adalah salah satu hobby yang
masih digemari beliau, disamping melaksanakan kegiatan
sehari-hari sebagai petani di area sawah merupakan
bentuk sarana komunikasi dengan para petani yang ada
di Desanya, walaupun demikian kegiatan yang ada di
Pemerintahan Desa selalu diutamakan demi kesejahteraan
dan kemajuan Desa dengan didukung Tiga Pilar Desa
yang selalu siap bersinergi dalam mengawal
pembangunan di desa Sekardadi Kecamatan Jenu.
Masyarakat Desa Sekardadi dalam melaksanakan
aktivitas sehari-hari adalah sebagai petani yang dalam
keseharian terjadi interaksi satu sama lain sehingga dapat
mempererat tali silaturrahim pada setiap masyarakat Desa
Sekardadi.
Pertanian di Desa Sekardadi cukup luas sehingga
masyarakar Desa Sekardadi lebih banyak berpotensi
sebagai petani sawah, lahan pertanian yang banyak
~ Legenda Tuban ~ 193
dijumpai di Desa Sekardadi adalah lahan persawahan,
dengan adanya pertanian tersebut menyebabkan
perkembangan perekonomian di Desa Sekardadi cukup
bagus sekaligus menjadi mata pencaharian bagi
masyarakat , dan sebagian kecil penduduknya bermata
pencaharian sebagai nelayan karena Desa Sekardadi juga
dekat dengan pesisir pantai.
Saat ini di Desa Sekardadi terdapat empat
Kelompok Tani yang semakin berkembang yaitu: Sekar
Maju, Dadi Makmur, Margomulyo dan Margodadi.
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing
kelompok tani diantaranya, pembersihan saluran irigasi
yang diadakan setiap 6 bulan sekali terutama pada masa
berkembangnya tanaman Eceng gondok karena tanaman
ini dapat menghambat saluran irigasi yang ada di sungai
area persawahan. Selain itu saling membantu antar warga
saat musim tanam maupun musim panen tiba.
Adapun kegiatan yang melibatkan ibi-ibu PKK
untuk mendukung ekonomi pemerinta Desa dengan
program Bumdesnya yang bergerak di bidang Catering,
dengan dikelola secara bersama, kegiatan Catering ini
dimanfaatkan dalam berbagai acara khususnya oleh warga
194 ~ Legenda Tuban ~
Desa Sekardadi sendiri, contohnya untuk memenuhi acara
pesta pernikahan, khitanan, tasyakuran dan lain-lain, hal
ini dapat menambah pemasukan pendapatan warga dan
juga sebagai nilai positif dalam mengembangkan
pengetahuan memasak, mengelola keuangan dan
berorganisasi.
Demikian sejarah singkat tentang asal usul Desa
Sekardadi, jika ada kekurangan dalam hal ini, kami
mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mohon pendapat atau
saran dalam penulisan untuk menambah wawasan yang
ada di Desa Sekardadi, atas berkenannya kami ucapkan
terima kasih.
Sumber referensi dari:
• Buku Tuban Bumi Wali Pemda Kabupaten Tuban
• Tarikh Wali Tuban
~ Legenda Tuban ~ 195
Lima Jam Menyusuri Goa Ngerong
Oleh: Mardiyanto
Goa Ngerong Rengel,
https://www.gapuranews.com
Tertarik untuk mengikuti proyek menulis bersama
IGPT mengenai Legenda di Kabupaten Tuban, saya jadi
teringat dan tergerak untuk mengingat kembali dan
menuliskan pengalaman pribadi saya sekitar 15 tahun
yang lalu. Kebetulan saya mempunyai salah seorang
teman yang rumahnya persis di pinggir sungai, di depan
196 ~ Legenda Tuban ~
Goa Ngerong. Karena kami begitu akrab, jadi saya juga
sering bertandang kerumahnya dan menginap di situ.
Saya begitu senang dan kagum setiap kali melihat
air Sungai Ngerong yang mengalir tepat di depan rumah
temanku itu. Berhulu dari dalam Goa Ngerong, airnya
begitu jernih dengan pamandangan yang menakjubkan,
karena banyak sekali ikan yang begitu bebas berenang dan
tidak ada yang berani mengambilnya. Karena menurut
cerita yang berkembang, orang yang berani mengambil
ikan di situ akan terkena musibah. Wallahu a’lam. Saking
jernihnya air di situ banyak sekali orang-orang, baik
pendatang maupun penduduk sekitar yang mandi dan
berenang. Mereka tampak sangat gembira menikmati
sejuk dan jernihnya air Sungai Ngerong dan berenang
bersama ikan-ikan yang begitu banyak.
Singkat cerita, pada suatu saat saya ditantang oleh
kawan saya, apakah saya berani memasuki dan menyusuri
Goa Ngerong ? Selama ini saya hanya menyaksikan goa
tersebut hanya dari depannya saja. Mulut goa menganga
begitu lebar, ditumbuhi pepohonan dan semak-semak.
Dalam goa tampak begitu gelap, dan kondisi itu menjadi
tempat yang nyaman untuk jutaan kelelawar bersarang di
~ Legenda Tuban ~ 197
dalamnya. Jalan masuk satu-satunya hanya melalui sungai
itu, yang kita juga tidak tahu persis seberapa dalam dan
panjang Sungai Ngerong yang ada di dalam goa.
Terdorong rasa penasaran dan rasa keingintahuan yang
begitu besar terhadap semua rahasia yang ada di dalam
Goa Ngerong, kupenuhi tantangan temanku untuk
bersama-sama memasuki dan menyusuri goa tersebut.
Untuk membuat situasi agak rame dan tidak
terlalu mencekam, maka kita juga mengajak kawan-
kawan lain yang mau dan tertantang untuk bersama-sama
menyusuri kedalaman Goa Ngerong. Terkumpullah 8
orang, yang sebagian besar masih berusia muda, siap
bersama-sama kita memasuki gelapnya Goa Ngerong.
Setelah disepakati dan ditentukan waktunya, dipilih hari
Sabtu malam Minggu agar kita memiliki waktu istiarahat
yang cukup. Dipilih waktu malam dengan alasan bahwa
keadaan dalam goa kosong dari Kelelawar. Kalau siang
hari jutaan kelelawar ada di dalam goa sehingga
dikhawatirkan kita bisa kekurangan oksigen.
Setelah tiba hari yang disepakati, sehabis salat
Isya kita berkumpul di rumah temanku untuk melakukan
prepare dan cek peralatan seadanya. Karena kita bukan
198 ~ Legenda Tuban ~
petualang profesional, kita hanya menyiapkan beberapa
peralatan sederhana. Setiap orang membawa satu lampu
senter yang dibungkus dengan plastik supaya kedap air
dan satu ban dalam mobil untuk membantu mengapung
dan berenang jika diperlukan. Setelah semua persiapan
dirasa cukup, kamipun terlebih dulu berdoa bersama
untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari
Allah.
Waktu itu sekitar pukul 20.00 malam kamipun
bersama-sama turun ke Sungai Ngerong berjalan menuju
ke mulut goa. Semua bercelana pendek, memegang satu
senter dan membawa ban. Ada sebagian teman yang
bersepatu untuk melindungi kakinya. Tetapi saya tidak
memakai sepatu, karena menurut saya itu justru akan
sangat mengganggu karena kita akan berjalan dan
berenang di air dan mungkin tanah berlumpur. Kami
berhenti sejenak di depan mulut goa yang tampak
menganga dan hitam, seolah-olah siap menelan kami
semuanya. Saya sempat termangu sejenak, berbagai
perasaan berkecamuk melihat gelapnya dalam goa. Kami
nyalakan lampu senter melihat keadaan dalam goa, yang
tampak hanya hamparan air.
~ Legenda Tuban ~ 199
“Ayo, jalan….!” Teriak salah seorang dari kami.
Kami serentak berjalan perlahan-lahan didalam air,
masuk ke dalam mulut goa. Begitu masuk ke dalam goa,
sangat terasa bau menyengat kotoran kelelawar
menyeruak. Napas kami sedikit sesak dan terasa pengap,
tetapi itu tidak berlangsung lama. Kami mencoba
beradaptasi dengan cara menarik napas panjang, dan
keluarkan pelan-pelan beberapa kali. Akhirnya kami
merasa mulai terbiasa dengan suasana udara di dalam goa.
Kami nyalakan senter melihat suasana dalam goa.
Ternyata dalam goa begitu luas, tampak masih banyak
juga kelelawar yang menempel di dinding goa.
Kami terus berjalan menyusuri sungai dalam goa.
Kami berjalan beriringan, dan tidak mau ada yang berada
di posisi paling belakang. Sepertinya ada rasa takut dan
khawatir, sesuatu terjadi jika berada di paling belakang.
Dasar sungai berlumpur, bercampur dengan kotoran
kelelawar. Hal itu membuat kami harus berjalan perlahan-
lahan, sambil terus waspada mengamati situasi di
sekeliling kami.
Ketika air masih memungkinkan kami untuk
berjalan, maka kamipun terus berjalan. Namun ada
200 ~ Legenda Tuban ~
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Layout Legenda Tuban
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search