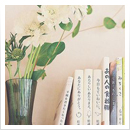SPIRIT ACLAK, BINGKAK DAN LADAK:
INTERAKSI SIMBOLIK UPACARA ADAT
BARONG IDER BUMI
Menguak Sisi Dalam Masyarakat dan
Budaya Using Kontemporer
ROCHSUN
SPIRIT ACLAK, BINGKAK DAN LADAK:
INTERAKSI SIMBOLIK UPACARA ADAT
BARONG IDER BUMI
Menguak Sisi Dalam Masyarakat dan
Budaya Using Kontemporer
Copy right ©2020, Rochsun
All rights reserved
SPIRIT ACLAK, BINGKAK DAN LADAK: INTERAKSI SIMBOLIK UPACARA ADAT
BARONG IDER BUMI
Menguak Sisi Dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer
Rochsun
Kata Pengantar: Dr. Achmad Habib, MA
Editor: Dewi Kusumaningsih dan Akhsanul In'am
Desain Sampul: Daniswara Helga Pradana
Lay out/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong
Ider Bumi, Menguak Sisi Dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontempore/
Rochsun/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020
xviii + 118 halaman; 15 x 23 cm
ISBN: 978-623-7148-63-0
Cetakan Pertama: 2020
Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)
Email: [email protected]
Website: www.penerbitbildung.com
Anggota IKAPI
Bekerja sama dengan AMCA (Associa on of Muslim Community in Asean)
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengu p atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari
Penerbit.
iv
KATA PENGANTAR
Dr. Achmad Habib, MA
Sosiolog Universitas Muhammdiyah Malang
WILAYAH INDONESIA terdiri dari 13.466 pulau dan
pendudukanya terdiri dari berbagai macam ras dan suku
bangsa yang memiliki budaya, adat istiadat, bahasa dan
agama yang berbeda-beda. Menurut data BPS, sesuai dengn
Sensus Penduduk tahun 2010 terdapat 1.340 suku bangsa
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tetapi faktanya
dalam suatu suku bangsa tertentu bisa dibagi lagi menjadi
sub sub suku bangsa, sehingga jumlah suku bangsa menjadi
lebih banyak dari hasil sensus tersebut. Sebagaimana
diketahui bahwa pembagian kelompok suku di Indonesia
tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk,
percampuran budaya, dan saling mempengaruhi; sebagai
contoh sebagian pihak berpendapat bahwa orang Cirebon
adalah suku tersendiri dengan dialek yang khusus pula,
sedangkan sementara pihak lainnya berpendapat bahwa
mereka hanyalah subetnik dari suku Jawa secara keseluruhan.
Demikian pula suku Baduy dan suku Banten yang sementara
pihak menganggap mereka sebagai bagian dari keseluruhan
suku Sunda. Contoh lain percampuran suku bangsa adalah
suku Betawi yang merupakan suku bangsa hasil percampuran
berbagai suku bangsa pendatang baik dari Nusantara maupun
Tionghoa dan Arab yang datang dan tinggal di Batavia pada
era kolonial.
v
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Demikian juga keunikan bermacam macam sub suku
itu terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai provinsi
yang paling luas dibandingkan 6 provinsi lainnya di Pulau
Jawa, provinsi yang wilayah seluas 47.922 km², terdiri dari
29 kabupaten dan 9 kota, mayoritas penduduk di Jawa Timur
merupakan suku Jawa dan sama-sama berbahasa Jawa dan
beberapa menggunakan bahasa Madura. Namun kalau
ditelisik lebih dalam sebenarnya sangatlah majemuk dalam
hal kebudayaannya. Budayawan Universitas Jember, Ayu
Sutarto (2004) mengatakan, wilayah Jatim ini terbagi ke dalam
sepuluh tlatah atau kawasan kebudayaan. Tlatah kebudayaan
besar ada empat, yakni Mataraman, Arek, Madura Pulau,
dan Pandalungan. Sedangkan tlatah yang lebih kecil terdiri
atas Jawa Panoragan, Using, Tengger, Madura Bawean,
Madura Kangean, dan Samin (Sedulur Sikep). Tlatah ini yang
kemudian membedakan karakteristik masyarakat di Jawa
Timur berdasarkan wilayahnya. Konon tlatah ini bukanlah
untuk membeda-bedakan masyarakat Jawa Timur melainkan
untuk menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur
merupakan masyarakat yang unik dan kaya akan budaya dan
kearifan lokal. Pun perbedaan ini tidak membuat Jawa Timur
saling memisahkan diri, tetap menyatu sebagai satu kawasan
provinsi.
Varian kebudayaan yang sangat unik tersebut
menyebabkan daerah Jawa Timur merupakan sorga bagi para
peneliti Ilmu Sosial dan Budaya. Telah banyak para ilmuwan
sosial yang meneliti dan menyebut bahwa komunitas yang
memiliki tlatah kebudayaan tersebut merupakan suku
tersendiri (bukan sub suku), seperti : Komunitas Using,
Tengger, Samin, dan Madura Pendalungan. Suku Using
yang merupakan suku mayotitas yang tinggal di desa-desa,
Kecamatan Kota, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi.
Blimbingsari, Singojuruh, Songgon dan Srono, sebagain
besar masih memiliki budaya dan bahasa yang sama, yaitu
budaya dan bahasa Using. Walaupun beberapa unsur budaya
vi
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
masyarakat suku Using sebagian sudah mulai punah, karena
terpengaruh oleh budaya luar maupun budaya modern,
namun masyarakat Using yang masih asli dapat dilihat di
desa Kemiren dan sekitarnya. Masyarakat Osing di desa
Kamiren memiliki tradisi khas yang dijalankan turun-
temurun yang kesemuanya masih asli. Memasuki desa
Kamiren ada atmosfer yang berbeda dari pada seluruh desa
yang ada di Banyuwangi. Salah satunya, dalam hal bercocok
tanam, masyarakat Kemiren menggelar tradisi selamatan
sejak menanam benih, saat padi mulai berisi, hingga panen.
Saat masa panen tiba, petani menggunakan ani-ani diiringi
tabuhan angklung dan gendang yang dimainkan di pematang-
pematang sawah. Saat menumbuk padi, para perempuan
memainkan tradisi gedhogan, yakni memukul-mukul lesung
dan alu sehingga menimbulkan bunyi yang enak didengar.
Musik lesung ini menjadi kesenian yang masuk dalam
warisan budaya asli suku Using. Disamping itu setiap Hari
Raya Idhul Fitri masyarakat di desa itu melaksanakan upcara
“Barong Ider Bumi”. Setelah ditetapkan menjadi Desa Wisata
Using, tahun 1995 oleh Bupati Purnomo Sidik, dibangunlah
bangun anjungan wisata yang terletak di utara desa.
Anjungan ini dikonsep menyajikan miniatur rumah-rumah
khas Using, mempertontonkan kesenian warga setempat, dan
memamerkan hasil kebudayaannya
Sudah banyak para pakar yang meneliti budaya Using,
khususnya di desa Kemiren, namun baru penelitian Dr.
Rochsun, M.Kes yang mampu mengungkap spirit budaya
aclak, bingkak dan ladak dalam upacara adat Barong Ider Bumi di
desa Kemiren. Dengan menggunakan teori Sosisologi Interaksi
Simbolik, karya Margaret Mead, peneliti berhasil mengungkap
dengan tuntas spirit ketiga unsur budaya masyarakat Using,
yang sampai sekarang masih tetap terjaga kelestariannya,
bukan hanya di desa Kemiren, tetapi di semua komunitas suku
Using di Kabupaten Banyuwangi. Nilai positif dari ketiga
unsur budaya tersebut sangat relevan sebagai representasi
vii
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
sifat dan sikap suku Using, yang percaya diri dan sangat
membanggakan nilai nilai luhur kebudayaannya. Nilai – nilai
luhur kebudayaan itu terus dilestarikan dibudayakan kepada
anak keturunan mereka, dibalik derasnya terpaan budaya
modern. Bukan hanya di komunitas mereka masih tinggal di
sebagian wilayah daerah Banyuwangi, bahkan ketika mereka
merantau di daerah daerah lain di seluruh Indonesia, mereka
tetap membagakan kebudayaan dan keseniannya dan selalu
berusaha melestarikan kebudayaan tradisional tersebut. Hal
ini tercermin dengan dibentuknya organisasi daerah yang
disebut IKAWANGI (Ikatan Keluarga dan Mahasiswa asal
Banyuwangi), yang masih sangat “guyub”dengan berbagai
kegiatan, misalnya: arisan, perayaan Maulud Nabi, Malam
Kesenian dan kegiatan lain dalam rangka melestarikan
kebudayan asli itu.
Sebagai Sosisolog, saya percaya bahwa hasil karya
Dr. Rochsun, M.Kes ini merupakan karya ilmiah luar biasa
yang perlu dibaca, bukan hanya oleh para ilmuwan Ilmu
Sosial, tetapi juga wajib dibaca oleh masyarakat Banyuwangi,
baik yang masih berdomisili di Banyuwangi, maupun yang
tinggal di perantaun, agar mereka lebih bersemangat dalam
usaha melestarikan budaya aseli Using, suatu budaya yang
sangat mereka banggakan. Pemerintah Daerah telah berusaha
maksimal melestarikan unsur unsur budaya “adi luhung” itu,
dengan kemasan yan berupa festifal-festifal sepanjang tahun,
guna menarik kunjungan wisatawan. Tanpa usaha yang lebih
seirus dari komunitas Using, budaya yang sangat luhur,
makin lama makin hilang dan sebagai akibatnya akan punah,
karena terpaan budaya modern.
Malang, April 2020
viii
PENGANTAR PENULIS
BERMULA DARI ketidaksengajaan menyaksikan fenomena
budaya di desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi, berupa upacara adat Barong Ider Bumi.. Yaitu
upacara adat tahunan diselenggarakan oleh masyarakat desa
Kemiren setiap tanggal dua bulan Syawal dalam kalender
Islam. Suatu kalender biasa digunakan oleh masyarakat desa
Kemiren yang mayoritas pendudknya beragama Islam dan
berbasis etnis Using.
Etnis Using, berdasarkan para ahli sejarah lokal
merupakan penduduk asli Banyuwangi. Mereka merupakan
keturunan sisa-sisa penduduk Blambangan yang masih
selamat dan bertahan hidup pada masa hegemoni Blambangan
kisaran tahun 1763-1813. Sampai suatu ketika terbentuk
peradaban dan kebudayaan baru, kemudian saat ini dikenal
sebagai masyarakat etnis dan berbudaya Using.
Naluri akademik muncul, berhasrat untuk meneliti,
dipicu oleh pertanyaan, bagaimana masyarakat agamis taat
menjalankan syariat agama Islam sebagai agama mayoritas
masyarakat desa Kemiren, mampu hidup berdampingan
dengan masyarakat yang teguh memegang weluri untuk
meng uri-uri budaya tua dan cenderung sinkritis. Secara syar’i
tentu bertentangan dengan pemahaman agamanya, namun
ix
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
fenomena budaya tua itu tetap eksis dan bertahan sampai
sekarang.
Namun kemampuan disiplin ilmu untuk mengkaji
fenomena budaya tersebut secara akademik tidak cukup
memadahi, bahkan cenderung “awam”, bahkan paradok
dengan disiplin ilmu sebagai seorang dosen pendidikan
Matematika. Keputusan untuk menyeberang ke disiplin ilmu
sosial adalah keniscayaan. Belajar ilmu sosial tidak seperti
yang dibayangkan apalagi sosiologi politik, merupakan
“istri baru” sama sekali harus belajar menyesuaikan diri, dari
habitat berbeda.
Beberapa kawan prihatin dengan latar belakang
akademik saya untuk belajar ilmu baru dalam kurun
waktu singkat. Mereka peduli dan berhasrat membantu,
mempermudah bagaimana belajar sosiologi. Kepedulian tidak
saja datang dari kolega, juga para dosen pengajar, mereka
memberi kemudahan untuk mengakses hal-hal baru bahkan
tidak jarang meminjami litaratur serta menjelaskan secara
private tentang banyak hal, dan semua gratis. Ketulusan
mereka memotivasi saya untuk belajar lebih maksimal.
Bermodal semangat, berani tampil dan tidak takut salah,
meskipun tertatih-tatih semua proses dilalui dengan wajar.
Dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat, kolega
dan dosen menambah energi tersendiri untuk terus berusaha
sampai suatu titik finish.
Hasrat untuk meneliti itu pun terlaksana, ketika
pada tahun 2012, hasil penelitian saya berjudul Tanggapan
masyarakat terhadap upacara adat Barong Ider Bumi desa Kemiren
Banyuwangi dimuat oleh jurnal nasioal Humaniora terbitan
kopertis wilayah VII Jawa Timur. Hal menjadi pengalaman
menarik dalam kehidupan akademik saya, ketika jurnal
itu disitasi oleh beberapa peneliti termasuk disitasi oleh
calon doktor universitas terkemuka di Jogjakarta dalam
sebuah disertasinya. Juga, dalam jurnal yang sama volume
x
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
11, nomor 2, Desember 2014 berjudul Spirit Budaya Using:
Studi Fenomenologi Upacara Adat Ider Bumi, telah disitasi oleh
beberapa peneliti kemudian.
Hal itu memotivasi untuk segera menyelesaikan
program doktor. Dengan ijin Allah S.W.T, akhirnya disertasi
saya berjudul Spirit Barong Ider Bumi Desa Kemiren Banyuwangi
selesai dan dipertahankan di hadapan penguji pada 15 Januari
2018. Untuk kepentingan publikasi, beberapa perubahan dan
tambahan telah dilakukan, di antaranya seperti judul. Pada
monograf ini berjudul Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak; Interaksi
simbolik Barong Ider Bumi, Menguak Sisi Dalam Masyarakat dan
Budaya Using.
Fokus kajian referensi ini adalah upacara adat Barong
Ider Bumi sebagai salah satu budaya Using, melewati
berbagai masa bahkan di jaman melenial budaya ini mampu
bertahan. Sementara tidak jarang beberapa budaya dan
etnis hampir punah, bahkan beberapa Bahasa daerah di
Indonesia bagian timur menurut beberapa sumber
terpercaya sudah mulai musnah. Padahal, heroisme
Banyuwangi sebagai tempat terbentuk dan domisili etnis
dan budaya Using juga berpotensi musnah. Berbagai faktor
penyebab, bertahun-tahun menurut Margana sejak
1763-1813 terjadi berbagai isu penting, seperti
penyelundupan, resistensi, sentimen etnik dan agama. Hal
itu, berlajut hingga melampaui beberapa masa, sampai masa
sekarang. Ketika seorang bupati keturunan etnis Using
dipilih dan ditetapkan sebagai bupati periode
2000-2005, menjalankan kebijakan di antaranya melalui
slogan Jenggirat Tangi, Periode ini disebut era kebangkitan.
Slogan Jenggirat Tangi, secara luas dimaknai seperti
pengertian Spirit dalam konsep Weber tentang Protestant
Ethic and the Spirit of Capitalism (Weber, 2015). Semangat
untuk mencapai tujuan tertentu kemudian mempertahankan
tanpa harus meninggalkan koridor etika budaya, yaitu etika
dan semangat memelihara dan mempertahankan tradisi
xi
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
tua. Begitu juga slogan Jenggirat Tangi, adalah semangat
memelihara dan mempertahankan dengan istilah uri-
uri budaya Using. makna yang terkandung di dalamnya
sebagaimana Spirit konsep Weber. Makna Spirit dalam
slogan Jenggirat Tangi diterjemahkan melalui studi-studi
para pemerhati Banyuwangi pada era tahun 2000-2005 ketika
rezim kebangkitan berkuasa. Seperti ketika seni budaya
tertua etnis Using Gandrung dikonservasi, bahkan pada
masa itu menjadi maskot dalam bentuk patung dan gambar
Gandrung terpasang di tempat-tempat strategis. Ditetapkan
Gandrung sebagai tarian resmi penyambutan tamu. Sepekan
(tanggal 18 sampai 25 Desember) berbusana dan berbahasa
Osing kepada seluruh pegawai negri dan swasta di setiap hari
ulang tahun kabupaten Banyuwangi. Bahasa Using dijadikan
bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah.
Desa Kemiren suatu desa mayoritas etnis Using, dijadikan
cagar budaya Using, dan upacara adat Barong Ider Bumi
diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Semua dimaknai
sebagai wujud emplementasi dari slogan Jenggirat Tangi,
yaitu semangat memelihara dan mempertahankan budaya
tua. Cara pikir dan perilaku demikian dalam konsep budaya
Using dinamakan Aclak, Bingkak dan Ladak.
Ironisnya, upaya meng-uri-uri budaya Using di era
kebangkitan oleh beberapa kalangan mengalami penolakan.
Dimulai dari kontraversi kebijakan oleh kalangan elit politik
di badan legislatif setempat, sampai pada penolakan oleh
para tokoh organisasi masa Islam Banyuwangi. Demonstrasi,
penyebaran suara penolakan melalui berbagai media
sebagai langkah tekanan yang dilakukan oleh kelompok
yang bersebrangan. Mereka beranggapan kebijakan rezim
ini hanyalah kepentingan etnik tertentu dan menyalahi
kebutuhan masyarakat Banyuwangi yang majemuk dan
plural, serta menyimpang dari ajaran Islam sebagai pemeluk
mayoritas.
xii
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Berakhirnya era kebangkitan digantikan oleh suatu
era baru, dalam tulisan ini disebut sebagai era multikultur.
Hadirnya era multikultur membawa Banyuwangi dipimpin
oleh seorang bupati wanita. Bagi kabupaten Banyuwangi
hal ini merupakan kebaruan, karena sepanjang sejarahnya,
Banyuwangi pertama kali dipimpin oleh seorang bupati
wanita. Sebagai rezim multikultur pada periode 2005-2010,
seakan mengobati keinginan masyarakat yang majemuk,
sebagaimana tuntutan kelompok masyarakat yang
dialamatkan pada masa rezim kebangkitan, pemerintahan
sebelumnya. Kehadiran rezim multikultur, tampil sebagai
nuansa baru di tampuk pemerintahan Banyuwangi. Ambisi
mengangkat kemajemukan dan plurarisme wong cilik sebagai
ikon kinerjanya merupakan obat mujarab dalam mengambil
hati masyarakat Banyuwangi, ketika kelompok masyarakat
membutuhkan figur yang sejalan dengan keinginannya dan
kecewa atas pemerintahan sebelumnya. Rezim multikultur
menyadari akan kebutuhan masyarakat Banyuwangi yang
heterogen, perlakuan yang sama terhadap semua etnis menjadi
jargon utamanya. Karena berbagai etnis menjadi penduduk
tetap tinggal dan berdomisili di kabupaten Banyuwangi,
seperti etnik Jawa Mataraman, etnik Madura Pandalugan,
etnik Using, etnis Bali, etnis Bugis, etnis Arab, etnis mandar
hinga etnis Cina dan lain sebagainya.
Namun belum lama menjabat, rezim ini menghadapi
berbagai protes, hujatan dan makian menjadi tidak terkendali.
Tidak jelas persoalannya, namun dimulai dari ,komflik
interes dalam intern pemerintahannya sampai dianggap
membawa Banyuwangi ke nuansa Bali. Wajar, karena bupati
era multikultur ini adalah istri seorang bupati yang sedang
menjabat di kabupaten Jembrana Bali. Gelombang protes
berjalan terus datang dari kelompok masyarakat yang
tidak puas terhadap cara kepemimpinannya, termasuk dari
kelompok yang menamakan diri budayawan etnik Using dan
xiii
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
kelompok masyarakat yang menamakan diri Kompak, yaitu
kelompok pemekaran wilayah Banyuwangi.
Konsistensi dalam mengangkat dan menjaga
multikulturalisme Banyuwangi, membawa kesan bahwa
kinerja bupati rezim ini tidak tampak keberpihakannya dalam
mengangkat citra Banyuwangi melalui etnis dan budaya,
apalagi mengangkat citra etnis dan budaya Using. Fokus
kinerja rezim lebih kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat
secara umum dalam hal pendidikan dan kesehatan serta
pembangunan fisik pedesaan. Namun, polemik antara sang
bupati dengan sekelompok masyarakat pun terus berlanjut,
sampai merambah pada persoalan politik dan hukum,
hingga berakhir masa kepemimpinan sebagai seorang bupati
Banyuwangi. Situasi hampir sama dengan kondisi bupati
sebelumnya penguasa rezim era kebangkitan. Penguasa rezim
multi kultur ini pada akhirnya membawa pada persoalan
yang lebih rumit dari sisi kehidupan pribadinya.
Berakhirnya era multikultur digantikan era baru masa
bakti 2010-2015, kemudian dalam tulisan ini disebut era
kebaruan atau era melenial. Kepiawaian mengambil pelajaran
dari para pendahulunya, bupati era melenial ini memperoleh
dukungan luas, baik dari masyarakat Banyuwangi maupun
simpati dari pemerintah pusat. Kemampuannya dalam
menggandeng semua pihak merupakan strategi jitu dan
kemahirannya menjalin kerja sama pada level lokal, regional,
nasional sampai level internasional, sehingga membawanya
dikenal semua kalangan. Prestasi itu berbuah simpati dari
masyarakat, akhirnya dipercaya untuk memimpin kembali
kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Jawa ini dalam
dua periode, yaitu periode 2010-2015, dan berlanjut pada
periode kedua, masa bakti 2015-2020.
Kecerdasan seorang bupati pilihan rakyat berasal
dari kalangan santri terpelajar etnis Jawa Mataraman,
xiv
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
adalah mampu mengambil pelajaran dan peran dalam
menjalankan roda pemerintahan. Melalui modal gagasan
bupati-bupati pendahulunya, mempermudah langkah dalam
membangun Banyuwangi. Berbagai terobosan spektakuler
mengawali kinerjanya untuk memperkenalkan Banyuwangi
dalam skala lebih luas seraya membuka Banyuwangi dari
keterkungkungan persoalan internal. Selain membangun
sarana dan prasarana fisik, rezim ini mengangkat budaya
etnik rintisan pendahulunya dengan gaya melenial. Semangat
untuk meng uri-uri budaya Using dengan gaya kebaruan,
kemudian disebut sebagai gaya melenial ketika mengemas
budaya Using yang klasik menjadi lebih kontemporer.
Berharap budaya Using tidak saja menjadi konsumsi etnik
tertentu, tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat Banyuwangi
pada umumnya, bahkan dapat diakses oleh masyarakat dunia.
Seperti, Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) pertama pada
bulan oktober 2011, dan BEC kedua pada bulan Nopember
2012, dalam rangka memperkenalkan Banyuwangi dengan
menggunakan kemasan budaya etnik Using dalam skala yang
lebih luas dan menginternasional.
Terlepas dari berbagai kepentingan, rezim melenial ini
telah melakukan hal terbaik untuk Banyuwangi hingga dikenal
luas oleh masyarakat global melalui budaya dan kekayaan
alamnya. Dibukanya destinasi-destinasi wisata dan kemasan
budaya etnik Using adalah langkah jitu untuk mengundang
investor menanamkan modalnya di Banyuwangi. Hadirnya
wisatawan menumbuhkan efek domino bagi industry
pariwisata Banyuwangi, dan berdampak pada pendapatan
asli daerah. Seperti mengemas Gandrung yang klasik dan
mungkin membosankan menjadi Gandrung Sewu yang
spektakuler dan melenial, mengemas Barong Ider Bumi
kedalam even Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), adalah
strategi kreatif mencari perhatian dunia. Semangat demikain
dalam konsep budaya Using dinamakan Aclak, Ladak dan
Bingkak.
xv
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Namun, ikhtiar yang telah dilakukan oleh rezim
dalam meng-internasionalisasi-kan budaya Using pada
akhirnya menuai protes. Bebarapa kelompok masyarakat
yang mengatasnamakan seniman Banyuwangi melakukan
penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Perdebatan pun
terjadi di berbagai forum oleh berbagai pihak, protes-protes
melalui jejaring sosial dan komentar-komentar di media
sosial termasuk yang dimuat oleh majalah khusus BEC (2012)
itu sendiri adalah wujud penolakan. Mereka mengkritisi,
bahwa BEC itu akan menghilangkan nilai tradisi etnik hingga
orsinilitas budaya menjadi hilang. Meskipun gelombang
protes masih mewarnai upaya sang rezim dalam mengangkat
citra Banyuwangi, kenyataanya semangat uri-uri budaya
Using itu masih tetap berjalan.
Kajian yang disajikan dalam bentuk referensi ini
masih sangat jauh dari kesempurnaan, bahkan jauh dari
harapan pembaca. Namun setidaknya, mampu memberikan
pengayaan terutama terhadap data-data dan informasi penting
terkait dengan etnis dan budaya Using. Seperti bagaimana
karaktristik masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan
budaya Using. Apakah karakteristik etnis terimplentasi
melalui budaya Using, sehingga untuk mengetahui seperti
apa karakteristik etnis dan budaya dapat dilihat dari budaya-
budaya yang diciptakan, dan lain sebagainya. Tentu hal ini
mengundang para peneliti-peneliti selanjutnya.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi banyak orang
khususnya penggiat etnis dan budaya Using atau pada
umumnya pemerhati Banyuwangi.
Malang, 10 Maret 2020
Penulis
xvi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar oleh: Dr. Achmad Habib, MA v
Pengantar Penulis ix
Daftar Isi xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Realitas dan Permasalahan Budaya Using 1
B. Dasar Teori dan Konsep yang Digunakan 6
C. Penelitian Terdahulu dan Alur Pikir dan Metode
14
Penelitian
BAB II MASYARAKAT USING BUKAN SUKU 21
TERASING 21
A. Kata Pengantar 22
B. Wilayah Tinggal Masyarakat Using Banyuwangi
C. Hubungan Sosial Budaya dan Agama Masyarakat 26
Using 33
D. Partisipasi Politi dan Perokonomian Masyarakat
Using
BAB III BUDAYA USING DALAM PERSILANGAN 37
DUA KEBUDAYAAN 37
A. Kata Pengantar
xvii
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak 40
B.Budaya Using dalam Wujud Budaya Material 45
(Tangibles) 48
C. Budaya Using dalam Wujud Budaya Non-Material
(Intangibles)
D. Budaya Using dalam Wujud Budaya Kontemporer
BAB IV NILAI-NILAI SPIRIT PADA BUDAYA 51
USING 51
A. Kata Pengantar 53
B. Nilai Spirit pada Budaya Tangibles 57
C. Nilai Spirit pada Budaya Intangibles
BAB V ACLAK BINGKAK dan LADAK SEBAGAI 63
NILAI SPIRIT BUDAYA USING 63
A. Kata Pengantar 65
B. Nilai Spirit Aclak Pada Budaya Using 68
C. Nilai Spirit Bingkak Pada Budaya Using 73
D. Nilai Spirit Ladak Pada Budaya Using
BAB VI PENUTUP 83
Daftar Pustaka 87
Glosarium 97
Indeks 113
115
Biodata Penulis
xviii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Realitas dan Permasalahan Budaya Using
MEMINJAM ISTILAH Jenggirat untuk mengatakan Jenggirat
Budaya Using di era kebaruan bukan merupakan ungkapan
berlebihan, karena memang demikian realitasnya. Ketika
budaya Using mampu mengimbangi rongrongan budaya
luar, karena setiap saat bisa saja luntur. Mengingat secara
geografis letak pemangku kebudayaan itu tidak saja tepat
pada persilangan dua budaya besar yaitu budaya Jawa dan
Bali, juga pengaruh budaya global yang semakin susah
dibendung. Apalagi di era kebaruan atau sering disebut
sebagai era melenial, di mana teknologi komunikasi dan
teknlogi informasi semakin canggih dalam mempercepat
akses, memfasilitasi komunikasi antar budaya di dunia hampir
tidak ada pembatas. Kecepatan dan ketepatan pertukaran
pesan bebas melintasi ruang dan waktu, memungkinkan
suatu budaya luntur oleh budaya global, sebagaimana kata
Huntington (2003) terjadi benturan antar budaya bahkan
benturan antar peradaban, sehingga tidak mustahil dalam
pandangan Mc Luhan, bahwa dunia hanya dengan satu
budaya (Liliweri, 2002).
1
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Realitasnya, budaya Using eksis dan tampil memukau di
antara budaya lainnya, bahkan tidak sedikit para pendukung
budaya ini mengelu-elukan kiprahnya dalam kancah
yang lebih luas dan modern dengan tetap memelihara dan
mempertahankan budaya warisan leluhur dengan semangat
menggelora. Semangat menggelora dalam bahasa Using
kurang lebih seperti kata Jenggirat Tangi. Istilah Jenggirat
Tangi, meminjam dari slogan yang sangat populer dan viral
di era tahun 2000-2005, saat kabupaten Banyuwangi dipimpin
oleh seorang putra daerah etnis Using, suatu etnis dalam
sejarahnya merupakan etnis asli penduduk Banyuwangi
(dulu bernama Blambangan). Slogan Jenggirat Tangi itu
terpampang gagah hampir di semua sudut kota dan desa
kabupaten Banyuwangi, seakan ingin menyampaikan pesan
kepada masyarakat untuk turut serta berperan aktif, giat,
bergegas, dan semangat secara menggelora dan bersungguh-
sungguh membangun Banyuwangi.
Kiranya asumsi pesan pada slogan itu cukup memadai
untuk digunakan memahami maksud dari kata Jenggirat.
Namun, Jenggirat yang dimaksud dalam tulisan ini, seperti
pengertian Spirit yang dikemukakan Weber dalam Protestant
Ethic and the Spirit of Capitalism (Weber, 2015). Semangat untuk
mencapai tujuan tertentu kemudian mempertahankan tanpa
harus meninggalkan koridor etika budaya. Yaitu, semangat
memelihara dan mempertahankan tradisi tua. Semangat
memelihara dan mempertahankan tradisi tua sebagaimana
konsep Weber, sesungguhnya merupakan etika budaya yang
telah diimplementasikan bertahun-tahun oleh aktor budaya
Using dengan menggunakan istilah uri-uri, seperti halnya
pemeliharaan dan pemertahanan budaya tua di New York
dalam konsep Weber. Implementasi uri-uri terlihat ketika para
aktor budaya Using melakukan diplomasi budaya, presentasi
dan publikasi pada setiap kesempatan. Melalui dialog-dialog,
pertunjukan-pertunjukan dan terkadang menegosiasikannya
tanpa beban, dengan semangat percaya diri.
2
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Seperti halnya budaya Using dalam wujud seni budaya
Gandrung, ia dipresentasikan sebagai milik dan simbol
ketertindasan di satu sisi, dan sekaligus kegigihan di sisi
lainnya, oleh karenanya ia dikonservasi (Anoegrajekti, 2007).
Kegigihan para aktor dalam menegosiasikan budaya itu
terlihat ketika terbit surat keputusan (SK) Bupati nomor 173
tertanggal 31 Desember 2002 tentang penetapan tari Gandrung
sebagai maskot pariwisata kabupaten Banyuwangi, dan
ditetapkannya Gandrung sebagai tari resmi penyambutan
tamu. Anjuran atau perintah sepekan berbusana dan
berbahasa Using kepada seluruh pegawai negri dan swasta
pada tanggal 18 sampai 25 Desember setiap tahunnya. Ketika
bahasa Using dijadikan bahasa daerah sebagai muatan
lokal di sekolah dasar (SD dan sekolah menengah pertama
(SMP) melalui Perda no. 5 tahun 2007 (Saputra, 2007), dan
ketika desa Kemiren dijadikan desa wisata adat Using (WU)
sebagai sebuah cagar budaya (Muarief, 2002 : Sunarlan, 2008),
Juga, ketika upacara adat Barong Ider Bumi sebagai budaya
turun temurun diselenggarakan secara rutin setiap tahun
(Sulistiyani, 2007) adalah merupakan wujud uri-uri oleh para
aktor budaya Using dalam bingkai Jenggirat Budaya Using
atau Spirit budaya Using.
Namun, spirit para aktor budaya Using dalam
meng-uri-uri budaya tua bukan tanpa kendala, upaya
itu menuai kontraversi di antara kalangan elit politik di
badan legislatif setempat dan para tokoh organisasi masa
Islam Banyuwangi. Mereka beranggapan uri-uri budaya
Using hanyalah kepentingan etnis tertentu dan menyalahi
kebutuhan masyarakat Banyuwangi yang majemuk dan
plural, serta menyimpang dari ajaran Islam sebagai pemeluk
mayoritas (Anoegrajekti, 2007: Sunarlan, 2008: Rochsun,
2012). Perselisihan itu cukup lama hingga habis masa
pemerintahan periode itu, pada akhirnya sampai tergantikan
tapuk pimpinan pemerintahan baru pada periode berikutnya
ditahun 2005-2010.
3
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Silang pendapat dikalangan elit partai dan kelompok
masyarakat terkait kiprah budaya Using, oleh bupati peganti
dimaksudkan untuk mengambil jalan tengah sebagai
alternatif yang bijaksana. Yaitu, ketika budaya Using dikemas
lebih multikultural dengan harapan dapat mengakomodasi
seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi yang plural dan
majemuk. Namun, rekontruksi kebudayaan tersebut justru
menyebabkan timbulnya resisten pemerintahannya. Sejak
pelantikannya pada tahun 2005, eksistensi sebagai bupati
telah menuai protes dan memuncak ketika kebijakan politik
kebudayaan itu dihenduskan. Sejak itu menuai perlawanan
yang datangnya dari elit partai politik, tokoh oraganisasi
masa Islam, sampai komunitas etnik Using. Mereka
menganggap bahwa rezim ini telah melakukan Balinisasi
dan Hindunisasi (Anoegrajekti, 2007: 41-44). Bahkan, pada
masa kepemimpinannya menyisakan persoalan politik, yaitu
muncul adanya gagasan pemekaran wilayah kabupaten
Banyuwangi oleh Komite Masyarakat Pemekaran Kompak
(Sunarlan, 2008: 148).
Budaya Using eksis kembali ketika rezim lama digantikan
oleh bupati baru pilihan rakyat dari kalangan santri terpelajar
ber etnis Jawa Mataraman. Sejak pelantikannya pada tahun
2010 berupaya meneruskan gagasan bupati sebelumnya dan
mengembangakan Banyuwangi disemua sektor, termasuk
turut serta meng uri-uri budaya Using. Ide kebaruan tampak
dipermukaan ketika mengemas kebudayaan tradisonal Using
menjadi lebih kontemporer sebagai bentuk tranformasi
budaya. Bahwa, kebudayaan Using tidak saja menjadi
konsumsi etnis tertentu, tetapi dapat dinikmati oleh semua
etnis di Banyuwangi, bahkan sampai level Internasional.
Melalui Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) pertama pada
bulan oktober 2011 dan BEC kedua pada bulan nopember
2012, sepertinya ingin mengangkat nilai tradisi etnis yang
menurut beberapa kalangan cenderung stagnan dan hanya
dinikmati oleh etnis tertentu saja, yaitu komunitas etnis Using
4
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
itu sendiri. Sehingga menjadi sebuah tontonan yang lebih
menarik dan marketable dan pada akhirnya menimbulkan
efek domino bagi industri kepariwisataan di Banyuwangi.
Seperti, mengemas Gandrung yang klasik dan mungkin
membosankan menjadi Gandrung Sewu (Gandrung milinial),
mengemas Barong Ider Bumi kedalam even Banyuwangi Ethno
Carnival (BEC yang menginternasional).
Upaya menginternasionalkan budaya Using bukan
jalan yang mulus. Justru menumbuhkan gelombang protes,
menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan
seniman dan budayawan Banyuwangi. Perdebatan terjadi di
berbagai forum oleh berbagai pihak, khususnya pendukung
etnis Using, di antaranya melalui jejaring sosial di facebook
dan komentar-komentar di media sosial lainnya. Mereka
mengkritisi, bahwa BEC itu akan menghilangkan nilai
tradisional etnis hingga orsinilitas budaya menjadi hilang
(Majalah Khusus BEC, 2012).
Pasang surut dukungan dan penolakan terhadap
eksistensi budaya Using sepertinya menjadi irama
indah tersendiri bagi aktor dan masyarakat Using pada
umumnya. Melalui cara pandang, cara memahami dan cara
mengemplementasi eksistensi budaya Using, realitasnya
budaya ini tampil memukau dengan semangat patriotik,
bahkan menjadi even tahunan. Salah satu budaya khas
masyarakat Using desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten
banyuwangi yang menjadi even tahuanan adalah Upacara
Adat Barong Ider Bumi. Budaya ini, eksis dan bertahan sejak
tahuan 1800-an, dan mampu diekspresikan secara apik oleh
masyarakat Using desa Kemiren, hingga menjadi even dan
agenda tahunanan bagi pemerintah daerah Banyuwangi
sebagai pariwisata budaya.
Upacara adat Barong Ider Bumi, sama seperti halnya
upacara-upacara adat lainnya di belahan nusantara, bahkan
5
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
upacara ini lebih kepada bentuk penghormatan kepada
leluhur yang bernama buyut Cili, Seorang yang dituakan
dan telah meninggal dunia dimakamkan di desa Kemiren,
kemudian diyakini sebagai danyang desa. Prinsipnya tidak
jauh berbeda dengan acara selamatan adat Islam Jawa bila
ada kerabatnya yang meninggal dunia, yaitu, selamatan tiga
hari, tujuh hari, dan seterusnya. Tidak ada yang istimewa,
bahkan cenderung bertentangan dengan syariat agama yang
dianut oleh kebanyakan masyarakat Using desa Kemiren itu
sendiri. Sehingga tidak mustahil ada diskusi-diskusi kecil
untuk menolak ketika fenomena budaya Barong Ider Bumi
itu dilaksanakan.
Ketika secara realita bahwa spirit budaya Using dalam
hal ini adalah wujud budaya intangibles masyarakat Using
berupa upacara adat Barong Ider Bumi tetap eksis dan
bertahan. Maka, pertanyaan yang muncul adalah spirit apa
saja yang terkandung dalam upacara adat Barong Ider Bumi
sehingga budaya itu tetap eksis dan bertahan?.
B. Dasar Teori dan Konsep yang Digunakan
Para peneliti budaya terdahulu menggunakan teori
Interaksionis simbolik sebagai pisau analisis. Seperti Andung
(2010) tentang upacara adat Natoni masyarakat Boti di
Nusa Tenggara Timur; Lestari, dkk (2015) tentang upacara
adat Kebo-Keboan di Desa Aliyan Banyuwangi Jawa Timur;
Wanulu, Rukyah (2016) tentang upacara adat Cumpe dan
Sampua masyarakat Buton Samarinda. Mereka menggunakan
teori interaksionis simbolik Mead sebagai pisau analisis dalam
memganalisis fenomena budaya. Hanya saja lebih kepada
konsep dasar teori itu, yaitu manusia merupakan individu
aktif dan kreatif. Mereka belum menyentuh bagaimana suatu
budaya itu eksis dan bertahan.
Pada tulisan ini, peneliti mengkaji pandangan individu
masyarakat Using (dimensi mikro), tentang beragam simbol
6
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
yang dia ciptakan dan dia tangkap dari hasil proses interaksi
sosial pada fenomena upacara adat Barong Ider Bumi,
lebih kepada menampilkan aktualisasi diri yaitu dorongan
dari kapasitas berpikir (aktif), berkreasi (kreatif) dalam
menangkap simbol-simbol fenomena sosial selama proses
sosial berlangsung. Maka penggunaan teori intraksionis
simbolik Mead khususnya konsep Mind, Self dan Society lebih
diperlukan. Penggunaan teori interaksionis simbolik Mead
itu difungsikan untuk mengungkap spirit yang terkandung
dalam fenomena Barong Ider Bumi, juga difungsikan untuk
mengungkap pemahaman individu masyarakat Using sebagai
aktor dalam memahami spirit yang terkandung dalam Barong
Ider Bumi.
Sebagaimana konsep dasar teori interaksionis simbolik
bahwa, manusia dibekali kemampuan berpikir, dan
kemampuan berpikir manusia itu dibentuk oleh interaksi
sosialnya. Melalui interaksi sosial itu, manusia mempelajari
arti dan simbol yang memungkinkan untuk melakukan
tindakan yang penuh arti. Dengan kata lain, teori ini ingin
mengatakan bahwa manusia itu merupakan individu yang
aktif dan kreatif. (Ritzer & Goodman, 2010). Jika prinsip
dasar teori interaksionis simbolik tersebut dikaitkan dengan
pengertian budaya yang dikemukan oleh Sutrisno (2008),
bahwa kebudayaan merupakan aktivitas manusia dalam
berpikir, berkomunikasi dan bekerja. Maka dalam konteks
penelitian ini, budaya Using dalam hal ini Barong Ider
Bumi dipahami merupakan hasil aktivitas dan kreativitas
masyarakat Using yang penuh arti dan makna, baik dalam
wujud bendanya (tangibles) mapun dalam wujud upacara adat
(intangibles). Ketika prinsip dasar teori itu dikaitkan dengan
pengertian budaya atau kebudayaan, bahwa Barong Ider
Bumi merupakan hasil buah pikir atau buah budi idividu–
individu yang dibangun oleh interaksi sosial di antara
masyarakat Using itu sendiri.
7
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Berdasar pada uraian di atas, penggunaan teori
interaksionisme simbolik pada kajian budaya Using ini
merupakan suatu hal yang diperlukan, khususnya tentang
mind, self dan society. Terkait dengan itu teori interaksionis
simbolik Mead, mendeskripsikan dialektika antara individu
dan orang lain. Bahwa, diri sebagai bagian dari internalisasi
orang lain, merupakan subjek yang bertujuan sebagai kendali
dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Artinya ide-ide
dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran
manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di
tengah interaksi sosial, kemudian menginterpretasi makna
itu di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut
menetap.
Persoalannya adalah, apakah teori interaksionis
simbolik Mead khususnya terkait dengan konsep Mind, Self
dan Society memiliki ketajaman dalam memotret individu
masyarakat Using sebagai pemangku kepentingan juga selaku
aktor pada fenomena Barong Ider Bumi, mengingat lahirnya
teori tersebut berasal dari latar belakang individu masyarakat
yang berbeda. Meskipun terdapat celah kesamaan, yaitu
sama-sama masyarakat organisasi.
Pada tradisi teori interaksionis simbolik, dan teori-teori
lainnya dalam lingkup paradigma definisi sosial menyatakan
bahwa, selain manusia merupakan individu aktif dan kreatif,
juga menyatakan idividu selaku aktor, dan aktor dipandang
sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal mencapai
tujuan, aktor mempunyai alternatif cara atau alat serta teknik
meskipun terdapat sejumlah kondisi yang dapat membatasi
tindakannya dalam mencapai tujuan (Ritzer, 2010). Artinya
aktor melakukan segala upaya untuk mewujudkan tujuan yang
hendak dicapai meskipun berbagai kendala menghalangi.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa beberapa
peneliti terdahulu telah menggunakan teori interaksionis
8
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
simbolik sebagai pisau analisis. Namun, penelitian-penelitian
itu belum menyentuh dalam konteks yang lebih luas, seperti
bagaimana budaya itu dapat eksis dan bertahan, spirit apa
yang muncul pada diri individu masyarakat sebagai aktor
sehingga budaya tersebut dapat eksis dan bertahan, serta
bagaimana aktor memahami nilai-nilai spirit tersebut dalam
perspektif teori interaksionis simbolik Mead pada konsep
Mind, Self dan Society. Kiranya diperlukan sedikit penjelasan
tentang teori intraksionis simbolik Mead itu.
Secara umum, teori interaksionis simbolik Mead
dipahami sebagai sebuah teori yang memiliki asumsi bahwa
manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori
ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang
dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain.
Oleh karena itu, teori interaksinis simbolik Mead merupakan
salah satu theoitical orientation pada penelitian ini, dipandang
memiliki kedekatan secara karakteristik untuk mengungkap
hal-hal tersebut di atas sebagai sebuah fenomena sosial.
Fenomena sosial yang dimaksud, ialah suatu aktivitas atau
tindakan sosial masyarakat Using dalam budaya berinteraksi,
budaya berkomunikasi atau pertukaran simbol yang
diberi makna. Di samping itu, teori ini dipandang mampu
memotret fenomena sosial dimaksud, mengingkat teori
ini memfokuskan diri pada hakekat interaksi pada pola-
pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Di
antaranya menekankan pentingnya proses mental, yaitu
suatu proses berpikir bagi manusia sebelum mereka bertindak
(Mead, 1934 : Ritzer, 2010)
Penggunaan teori interaksionis simbolik Mead ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami perilaku dan
tindakan manusia dari sudut pandang orang yang mengalami,
yaitu dari sudut pandang subjek, dengan menunjukkannya
bahwa perilaku dan tindakan manusia harus dilihat sebagai
proses yang memungkinkan manusia membentuk dan
9
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan
ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka
(Mead, 1934 : Ritzer & Goodman, 2010).
Menurut Mead (1934) perspektif teori interaksionisme
simbolik itu adalah individu. Ia merupakan hal yang paling
penting dalam konsep sosiologi, karena individu menurutnya
merupakan obyek yang dapat secara langsung ditelaah dan
dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain.
Secara pragmatis, terdapat tiga hal penting dalam teori
interaksionis simbolik terkait dengan dunia nyata, yaitu:
pertama, memusatkan perhatian pada interaksi antara aktor
dengan dunia nyata; kedua, memandang baik aktor maupun
dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai
struktur yang statis; ketiga, arti penting yang dihubungkan
kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan
sosial (Ritzer & Goodman, 2010). Artinya, teori interasionis
simbolik menekankan pada pengertian, bahwa manusia
bertindak berdasarkan atas makna – makna, di mana makna
tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta
makna – makna itu terus berkembang dan disempurnakan
ketika interaksi itu berlangsung (Ritzer, 2010).
Oleh karena itu, proses interaksi dan komunikasi di
antara mereka dengan menggunakan teknik dan cara tertentu,
dapat dipahami maknanya melalui simbol-simbol yang
mereka gunakan. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyana
(2006), bahwa teori interaksionis simbolik dalam memandang
kehidupan sosial pada dasarnya adalah “interasksi manusia
dengan menggunakan simbol-simbol. Esensi interaksi
simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas
manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang
diberi makna.
Gambaran singkat tentang inti perspektif teori
interaksionis simbolik di atas, kiranya dapat membantu
10
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
dalam menemukan nilai spirit dan memaknai nilai spirit yang
terkandung dalam upacara adat Barong Ider Bumi. Namun,
untuk melengkapi pemahaman teori ini dalam memotret
fenomena sosial lebih lanjut dikemukakan beberapa hal yang
diadaptasi dari Mead (1934); Poloma (1979); Soeprapto (2002);
Ritzer & Goodman (2010); Rusdi (2011). Bahwa terdapat lima
hal penting perspektif teori ini dalam memahami fenomena
sosial atau tindakan individu masyarakat selaku aktor yang
dapat dirangkum sebagai berikut:
Pertama, terkait dengan realitas sosial, teori ini
memandang bahwa, realitas sosial yang sejati itu tidak
pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan
ketika manusia bertindak “di dan terhadap” dunia. Apa
yang nyata bagi manusia tergantung pada definisi atau
interpretasi atau pandangan individu itu sendiri. Bahwa
manusia melandaskan pengetahuan mereka tentang dunia
pada apa yang terbukti dan berguna bagi hidupnya. Manusia
mendefinisikan obyek fisik dan non fisik adalah berdasarkan
kegunaan dan tujuannya. Manusia selalu berubah-ubah
dari waktu kewaktu, baik menyangkut pandangan tentang
diri dan lingkungannya, tujuannya, orientasi hidupnya,
simbol-simbol yang digunakan, aturan-aturan, peralatan
dan sebagainya. Oleh karena itu memahami manusia harus
dengan pendekatan dinamik dan kontekstual.
Kedua, tentang individu, bahwa individu merespon
suatu situasi simbolik. Individu merespon lingkungan,
termasuk obyek fisik (benda) dan obyek sosial (tindakan sosial)
berdasarkan makna yang terkandung dalam obyek tersebut.
Artinya, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu
makna tidak melekat pada obyek, melainkan “dinegosiasikan”
melalui penggunaan bahasa. Makna yang diinterpretasikan
individu dapat berubah dari waktu kewaktu, sejalan dengan
perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.
11
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Ketiga, tentang pikiran (Mind) adalah kemampuan
manusia dalam menggunakan simbol untuk menunjukkan
obyek disekitarnya. Pikiran itu merupakan “proses” dari
pada “struktur” (sebagaimana pandangan fungsional
struktural). Pikiran adalah kemampuan memahami simbol.
Sedangkan Diri (self) pada dasarnya adalah kemampuan
untuk menempatkan seseorang sebagai subyek sekaligus
obyek. Diri (self) tidak mungkin ada tanpa adanya pengalaman
sosial. Setiap diri itu berkembang ketika orang itu belajar
‘mengambil peranan orang lain” dalam proses interaksi sosial.
Tindakan manusia dalam proses interaksi tidak ditentukan
oleh faktor eksternal, melainkan manusia sendiri dengan
kemampuan pikiran membentuk obyek, menilai berdasarkan
makna dan memutuskan untuk berbuat berdasarkan makna
itu. Mead mengidentifikasi fase diri, dalam dua fase, yaitu “I”
dan “me”. Keduanya adalah proses yang terjadi dalam proses
diri yang lenih luas. Self memiliki peran ganda, suatu ketika
sebagai subyek (I), independen, bebas, tak terkendali. Suatu
ketika berperan sebagai obyek (Me), dependen, tak bebas,
terkendali.
Keempat, pandangan tentang masyarakat. Menurut
interaksionalis simbolik, bahwa masyarakat sebagai suatu
organisasi interaksi, tergantung pada pikirin invidu.
Masyarakat juga tergantung pada kapasitas diri individu.
Dengan demikian masyarakat secara terus menerus akan
terjadi perubahan, karena pikiran individu terus berubah
melalui interaksi. Masyarakat sebagai penyaji sistem
sosialisasi yang dinamik, dan sosial itu sendiri dirumuskan
individu-individu dari proses interaksi dan sosialisasi melalui
sejumlah tingkat yang berbeda,
Kelima, asumsi Mead, individu adalah rasional dan
produk dari hubungan sosial (interaksi sosial); masyarakat
adalah dinamis dan berevolusi, menyediakan perubahan
dan sosialisasi yang baru dari individu; realitas sosial adalah
12
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
bersifat individu dan sosial yang dinamik; Interaksi sosial
meliputi pikiran, bahasa dan kesadaran akan diri sendiri.
Lima hal penting di atas, kiranya mampu memotret
fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Using Desa
Kemiren, khususnya pada fenomena upacara adat Barong
Ider Bumi. Inti teorinya adalah ingin mengatakan bahwa,
manusia merupakan individu yang aktif dan kreatif.
Di samping itu Mead (1934) menyatakan bahwa, melalui
bahasa menjadikan makhluk sadar-diri (self-conscious), yaitu
sadar akan individualitas yang prosesnya memerlukan
simbol. Artinya, semua interaksi antar individu manusia
melibatkan suatu pertukaran simbol, yang dipergunakan
untuk mengerti apa yang dikatakan dan lakukan orang lain
kepada kita sebagai individu, dengan menggunakan simbol-
simbol signifikan. Pendapat Mead tentang simbol signifikan
itu, meskipun isyarat fisik kurang ideal tetapi menjadi simbol
signifikan, kareana tidak dapat dengan mudah melihat
atau mendengarkan isyarat fisiknya sendiri. Mead juga
menyatakan bahwa, ungkapan suaralah yang paling mungkin
menjadi simbol yang signifikan, meskipun tidak semua
ucapan dapat menjadi simbol signifikan, tetapi kumpulan
isyarat suara yang paling mungkin menjadi simbol signifikan
adalah bahasa (Ritzer, 2010).
Fungsi bahasa atau simbol yang signifikan menurut
Mead pada umumnya adalah menggerakkan tanggapan
yang sama dipihak individu yang berbicara dan juga di
pihak lainnya. Pengaruh lain dari bahasa adalah merangsang
orang yang berbicara dan orang yang mendengarnya. Mead
mencontohkan seperti orang meneriakkan “kebakaran” di
dalam bioskup yang padat penonton setidaknya akan bergegas
keluar sebagaimana halnya orang yang mendengarkan
teriakannya itu. Artinya, simbol signifikan semacam menjadi
stimulator tindakan mereka sendiri (Ritzer & Goodman, 2010).
13
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Mencermati pendapat dan pandangan di atas, dapat
dipahami bahwa teori interasionisme simbolik adalah sebuah
teori yang mempunyai inti bahwa manusia merupakan invidu
yang aktif dan kreatif. Aktualisasi aktivitas dan kreativitas
diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol budaya yang
diciptakan. Simbol-simbol demikian penuh dengan makna.
Makna-makna tersebut didapatkan dari hasil interaksi sosial,
yaitu interaksi dengan dirinya dan atau dengan orang lain.
Makna–makna itu terus berkembang dan disempurnakan
pada saat interaksi itu berlangsung (Ritzer, 2010).
C. Penelitian Terdahulu, Alur Pikir dan Metode Penelitian
Posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitan
terdahulu. Seperti, penelitian yang telah dilakukan oleh
Paul Arthur Wolbers (1985), dengan judul ”Maintaining
Using Identity Through Musical Perormance Seblang and
Gandrung Of Banyuwangi, East Java, Indonesia”. Penelitian
ini membicarakan tentang dua tradisi, yaitu Seblang dan
Gandrung sebagai bentuk protes politik disatu sisi, dan
disisi lainnya sebagai ungkapan rasa syukur atas panen
yang melimpah dan penduduk terhindar dari berbagai
penyakit (pageblug). Suparman Herusantoso (1987), dengan
judul “Bahasa Using Di Kabupaten Banyuwangi”. Hasl
penelitian memberikan informasi tentang indikasi asal-usul
pemberian nama Using terhadap sekelompok masyarakat
terpencil, bahasa komunikasi yang digunakan, serta wilayah
sebarannya. Woro Sri Soeprihati & R.M. Soedarsono
(2000), judul penelitiannya “Drama Tari Rengganis di desa
Cluring Banyuwangi Jawa Timur”, Hasil peneliannya
menginformasikan bahawa Drama tari rengganis merupakan
hasil kolaborasi, asimilasi, dan akulturasi berbagai budaya,
yaitu budaya hindu Jawa dan Islam, Jawa Tengah (wayang
orang dan ketoprak), budaya Using, dan budaya modern
(barat). Made Sudjana (2001), judulnya “ Negari Tawon
Madu”. Menggambarkan bahwa Belambangan diibaratkan
14
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
sebagai sebuah nagari Tawon Madu, karena ibukota
Belambangan menjadi simbol kekuasaan yang menentukan
pasang surutnya eksistensi Belambangan. Penelitian ini
mengiformasikan bahwa Kerajaan Belambangan dapat
bertahan selama lebih kurang 500 tahun karena ditunjang
oleh satu faktor utama, yakni keberhasilan para pewaris tahta
Belambangan dalam mempertahankan negeri seperti konsep
tawon Madu, dimana semua, lapisan masyarakat, tentara,
tunduk pada ratu Tawon. Hanya ada satu penguasa tunggal
dalam satu kerajaan (PATRONS CLIENT). Penelitian yang
telah dilakukan Andrew Beatty (2001), dengan judul “ Variasi
Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi ”. Dalam
konteks Using, hasil penelitian Beatty memberikan informasi
bahwa budaya etnik Using merupakan budaya sinkritik.
Nilai rukun di Jawa khususnya etnik Using di Banyuwangi
terwujud dalam budaya Slametan, budaya ini dikatakannya
sebagai pemersatu kerukunan antar agama.
Juga Novi Anoegrajekti (Jurnal Bahasa dan Seni, tahun
31, Nomor 2, Agustus 2003). Judulnya adalah “Seblang
Using: Studi Tentang Ritus dan Identitas Komunitas Using”.
Isi penelitiannya menyampaikan informasi, bahwa etnik
Using memiliki keteguhan dalam memegang nilai tradisi
dan kesakralan, sebagai wujud rukun dalam konteks
sosial kemasyarakatan, dan wujud syukur dalam konteks
Ketuhanan melalui simbol upacara seblang sebagai identitas
etnik Using. Penelitian I Nyoman Cau Arsana & I Made
Bandem (Humanika, 18(1), Januari, 2005). Judulnya adalah
“Gamelan Janger: Hibidra Musik Banyuwangi dan Bali
Sebuah Akulturasi Budaya”. Melaporakan bahwa Gamelan
Janger sebagai pengiring drama tari Damar wulan merupakan
asemble Banyuwangi yang mendapat pengaruh Gong Kebyar
Bali. Dimana Gong Kebyar Bali ini mengalami perkembangan
sangat pesat di Bali hingga keluar pulau Bali sampai ke
Banyuwangi, dibawa oleh penduduk Bali yang migrasi ke
Banyuwangi sekitar abad ke-20. Penelitian Heru S. P. Saputra
15
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
(2007). Judulnya adalah: “Memuja Mantra: Sabuk Mangir
dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi”.
Inti dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan karakter
etnik Using, yang Aclak, Bingkak dan Ladak. Penelitian Sunu
Catur Budiono (2009). Disertasi dengan judul “Konstruksi
Identitas Etnik dalam Masyarakat Multietnik di Banyuwangi”.
Temuannya merekonstruksi Teori Dramaturgi, bahwa dalam
panggung terbuka (masyarakat) dan sekaligus melibatkan
berbagai elemen, aktor, peran, kepentingan, dan kekuasaan.
Menurutnya yang terjadi tidak sepenuhnya sebagaimana
yang dibayangkan Goffman. Panggung depan front stage
adalah ruang presentasi identitas dan ruang negosiasi.
Sebaliknya panggung belakang back stage bukan merupakan
atau semata-mata ruang privat untuk kerja diri sendiri tetapi
sekaligus merupakan panggung publik untuk berinteraksi dan
bernegosiasi dalam persoalan privat dan publik. Penelitian
Novi Anoegrajekti (2010), pada penelitainnya yang berjudul
“Etnografi Sastra Using: Ruang Negosiasi dan Pertarungan
Identitas”, memberikan informasi bahwa bagaimana politik
identitas dibangun dan diartikulasikan di ruang publik
yang kompleks (multi kutur). Sulistiyani (Jurnal Mudra; 22
:28-38). Dengan judul “Upacara Ider Bumi Di Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian
ini memberikan informasi tentang mengapa upacara ider
bumi diselenggarakan dan bagaimana tata cara atau urutan
penyelenggaraannya. Pada penelitian ini juga ditunjukkan
akan adanya singkritisme kebudayaan.
Di samping itu, penelitian dari Irawan Setyabudi (Lokal
Wisdom, Volume III, Nomor 1, Halaman 01 – 06, Februari,
2011). Judulnya adalah “Nilai Guna Ruang Rumah Tinggal
Suku Using Banyuwangi Dalam Kegiatan Sosial, Budaya dan
Agama”. Penelitian ini mengangkat peran rumah etnik Using
dapat mengakomudasi kebutuhan sosial, budaya dan agama
sebagai wujud nilai lokal yang selayaknya dipertahankan,
seiring mulai terkikisnya budaya lokal yang tergerus oleh
16
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
berkembangnya budaya global melalui berbagai sarana, baik
melalui media, pariwisata maupun melalui pendidikan. Novi
Anoegrajekti (Humaniora, volume 23, nomer. 1 februari 2011).
Judul penelitiaannya “Gandrung Banyuwangi: Kontestasi
dan Representasi Identitas Using”. Isinya menegaskan bahwa,
sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 Seni budaya
Gandrung diperebutkan dalam ruang identitas yang berbeda.
Dengan menggunakan perspektif Hegemoni terkait dengan
kontestasi antara budaya residual, dominan, dan emergent.
Representasi identitas Using merupakan medan pertarungan
pemaknaan dalam proyek politik kebudayaan. Penelitian
Ahmad Kholil (Jurnal El-Harakah Vol. 13, No 2 page. 2011)
berjudul: Kebo-keboan dan Ider Bumi Suku Using: Potret
Inklusivisme Isalam di Masyarakat Using Banyuwangi.
Menyimpulkan: a) kearifan itu menjelma dalam nilai dasar
rukun yang menjadi falsafah hidup masyarakat, yang datang
dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut dan dari
sistem etika sosial yang diwarisi secara turun temurun, b)
Keyakinan keagamaan, bagi masyarakat Using terdapat pada
ruang personal di wilayah yang sangat private, sedangkan
dari sisi sosial, mereka mampu beradaptasi melalui ruang
dialogis yang penuh toleransi sebagai milik bersama, yaitu
ruang kehidupan sosial kemanusian. Penelitian oleh Nurhadi,
(2012). Dalam disertasinya tentang Transformasi Budaya
Lokal pada Sekolah Unggul. Temuan hasil penelitian adalah:
(1) budaya Using mempunyai karakteristik dan nilai-nilai
budaya yang tetap eksis dan dijunjung tinggi hingga saat
ini, diantaranya : (a) sikap egaliter, (b) sikap religius yang
tinggi, (c) naluri seni yang tinggi, (d) terbuka/transparan,
(e) gotong royong/solidaritas sosial, (f) kerja keras, (g)
kompetitif dan kreatif.(2) Unsur-unsur budaya Using yang
masih eksis sampai saat ini adalah: (a) Bahasa Using, (b)
kesenian daerah, (c) Sistim mata pencaharian, (d) Sistim religi
dan upacara keagamaan. Serta penelitian oleh Sri Margana,
(2012). Judul penelitiaannya: “Ujung Timur Jawa, 1763-1813:
17
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Perebutan Hegemoni Blambangan”. isi dari hasil peneitian
ini menggambarkan bahwa Blambangan pada periode
1763-1813 merupakan wilayah yang menjadi the contested
frontier, dimana berbagai bangsa-bangsa memperebutkan
hegemoni Blambangan. Berbagai isu penting telah muncul
selama periode itu. Mulai dari konflik dan perang, resistensi
dan kolaborasi, perdagangan dan penyelundupan, hingga
sentiment etnis dan agama. Penelitian oleh Frederica K,
dkk (Jurnal DKV Adiwarna Vol 2 .2014, page 12) berjudul :
Perancangan Buku Essay Mengenai Barong Ider Bumi sebagai
Wisata Upacara Adat Kemiren. Menyimpulkan: upacara Ider
Bumi merupakan fenomena budaya masyarakat Using yang
patut di dokumentasikan sebagai kearifan lokal mualai dari
awal prosesi hingga akhir upacara adat Ider Bumi dalam
sebuah buku essay sebagai inventarisasi suku Using. Terakhir
penelitian yang telah dilakukan oleh Ketut Darmana, (2015)
tentang: Upacara Barong Ider Bumi Masyarakat Using Desa
Kemiren Banyuwangi-Jawa Timur. Hasil temuannya tentang
revitalisasi fungsi dan makna Upacara Barong Ider Bumi.
Bahwa eksistensi sebuah kebuadayaan Using dalam hal ini
adalah barong Ider Bum dikarnakan faktor revitalisasi fungsi
dan makna Barong Ider Bumi.
Semua penelitian-penelitian itu belum menyentuh
substansi seperti yang diungkap oleh penelitian ini. Oleh
karena itu, hasil penelitian yang dituangkan dalam monograf
ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya diyakini
memiliki tingkat orsinilitas. Adapun alur pikir dalam
penelitian ini dapat diskemakan sebagai berikut:
18
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Alur Pikir Penelitian
Budaya Hindu Budaya Islam
Barong Ider Bumi
?
Spirit Barong Ider Bumi Spirit Barong Ider Bumi
Proses interaksi sosial masyarakat Using masa lalu
mampu membentuk kemampuan berpikir (Ritzer, 2010),
sehingga menghasilkan sifat dan karakter khas masyarakat
Using, di antaranya bersifat akomodatif. Sifat akomodatif
masyarakat Using, membantu mempermudah ruang
negosiasi dua budaya besar yang secara bersama-sama
dalam mempengaruhinya, yaitu budaya Hindu dan Islam.
Akulturasi dua budaya besar ini mengkonstruksi secara
aktif dan kreatif kebudayaan Using dengan ciri sinkritis.
Proses interaksi sosial menghasilkan budaya yang bersifat
sinkritis, salah satunya adalah upacara adat Barong Ider
Bumi. Penyelenggaraan Barong Ider Bumi memicu tindakan
sosial yang syarat dengan makna. Baik bermakna bagi
19
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
individu masyarakat Using selaku aktor maupun ditujukan
pada orang lain (Weber dalam Ritzer, 2010). Juga, dipahami
melalui interasi dan presentasi itu terdapat spirit dan makna
yang terkandung dalam Barong Ider Bumi. Hal tersebut
merupakan “thing” yang akan diungkap dalam penelitian ini.
Metode penelitian pada tulisan ini diawali dengan
meninjau paradigma yang digunakan, yaitu definisi sosial.
Tujuannya, mengungkap pemahaman individu selaku aktor
masyarakat Using terkait upacara adat Barong Ider Bumi
dari sudut pandang aktor itu sendiri, dengan cara menyelami
pemikiran aktor lalu merenungkannya. Pendekatan kualitatif
dipilih untuk mengungkap makna nilai-nilai spirit budaya
Using melalui data deskriptif berupa ucapan lisan, tulisan
dan perilaku yang dapat diobservasi dari subyek. Melalui
pertanyaan “pancingan”, dan membiarkannya bercerita
tentang pengalamannya dengan panduan pertanyaan yang
sudah disiapkan terlebih dahulu.
Data dikumpulkan melalui langkah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi dengan
menggunakan dua teknik. Teknik non-partisipan melalui tiga
waktu, yaitu dua hari sebelum pelaksanaan upacara (H-2),
pada saat hari pelaksanaan (hari H), dan dua hari setelahnya
(H+2). Teknik partisipan, yaitu peneliti ikut terlibat langsung
dalam upacara adat Barong Ider Bumi sebagai peserta kirab.
Analisis data menggunakan langkah-langkah: deskripsi,
reduksi, esensi dan intensionalitas dari hasil pertanyaan
pancingan, seperti: Apa pengalaman bapak tentang
tradisi upacara adat ritual Barong Ider Bumi? Bagaimana
perasaannya bapak tentang pengalaman tradisi upacara adat
ritual Barong Ider Bumi tersebut? Apa makna yang diperoleh
bapak atas tradisi upacara adat ritual Barong Ider Bumi.
Adapun keabsahan data dilakukan dengan cara trianggulasi.
20
BAB II
MASYARAKAT USING BUKAN SUKU TERASING
A. Pengantar
SEBUAH ARTIKEL dimuat dalam iddaily.net pada tahun 2006
berjudul “Osing, Suku Yang Terasing di Tengah Modernisasi”,
oleh Iman D Nugroho seorang jurnalis sekaligus sebagai
anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Artikel itu seakan
memberikan pesan informasi kepada pembaca, bahwa ada
suatu suku atau etnis di Banyuwangi memiliki potensi secara
etnis maupun budaya, namun kurang memperoleh perhatian
dari pemangku kepentingan. Keramahan etnis dan keindahan
budaya digambarkan secara apik, seperti ingin menunjukkan
bahwa etnis dan budaya Using layak untuk diangkat sebagai
kekayaan budaya nusantara.
Gambaran sebagai suku atau etnis termarjinalkan
menjadi fokus tulisannya, ketika didapati berbagai sentimen
yang diarahkan kepada etnis Using. Seperti isu PKI dengan
genjer-genjernya, isu santet, isu abangan, dan sebaginya,
menambah beban psikologis teramat mendalam bagi
kehidupan sosial mereka. Horoisme perebutan kewilayahan,
sentiment etnis, sentimen agama, perekonomian, budaya,
sosial kemasyarakatan, dan politik dipaparkan sedemikian
rupa sehingga membawa kesan bahwa masyarakat Using
21
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
merupakan suku atau etnis tertindas dan terasing dari hiruk
pikuk modernitas.
Pengalaman pahit itu seakan tak kunjung usai, sejak
abad ke-18 rentetan peristiwa sejarah kelam telah dialami
oleh para leluhur mereka, ketika berbagai bangsa-bangsa
memperebutkan hegemoni Blambangan dalam konplik
politik, resistensi, penyelundupan, hingga sentimen etnis
dan agama, menjadi irama sumbang yang masih terkadang
diperdengarkan kepada anak cucu sebagai pewaris peradaban
dan budaya Using. Bukan prustasi terhadap suatu keadaan,
justru hal itu dijadikan pelajaran sebagai pewaris suku atau
etnis yang digdaya, patriotik dan pantang menyerah.
Spirit pantang menyerah terhadap suatu keadaan dan
mencoba bangkit dari keterpurukan, sampai suatu ketika
di era tahun 2000-2005 mengalami kebangkitan melalui
slogan Jenggirat Tangi. Etnis dan budaya Using mendapati
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa,
melalui kebudayaan khas yang mereka miliki, untuk
mengangkat citra Banyuwangi dan nasional dalam percaturan
global. Eronisnya, kebangkitan itu kemudian dikatakan
sebagai kebangkitan yang terseok.
Gambaran Iman D Nugroho tentang masyarakat dan
budaya Using di atas memotivasi hasrat untuk mengetahui
lebih jauh seperti apa sesungguhnya wilayah tinggal
masyarakat Using Banyuwangi, bagaimana hubungan
sosial budaya dan agama masyarakat Using dan bagaimana
partisipasi politik serta perokonomian masyarakat Using,
B. Wilayah Tinggal Masyarakat Using Banyuwangi
Berdasarkan para ahli sejarah lokal dan buku-buku
tentang sejarah Blambangan cetakan tahun 2012 meyakini
bahwa, masyarakat Using merupakan penduduk asli
Banyuwangi yang tersisa akibat perang melawan penjajah
22
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Belanda. Sebagian besar di antara mereka adalah prajurit
yang gagah berani memiliki kedigdayaan dan keahlian
lebih. Kekalahan perang fisik membawa mereka mengungsi
di wilayah pedesaan, hutan-hutan dan gunung dalam
kurun waktu yang sangat lama. Akhirnya membentuk
perkampungan baru, peradaban baru, kebudayaan baru,
terutama pertanian dan perkebunan yang mereka buka dari
hutan-hutan dan pegunungan disekitar tempat tinggal mereka
mengungsi. Kemahiran dan keahlian dibidang pertanian
dan perkebunan serta seni budaya diwariskan kepada anak
keturunannya hingga saat ini. Oleh karena itu masyarakat
Using Banyuwangi yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut
dikenali sebagai etnis Using atau suku Using yang pandai
bercocok tanam dan mahir dibidang pertanian dan seni
budaya.
Banyuwangi secara kewilayahan dan etnis dibagi dalam
empat wilayah besar, tentu ada komunikas-komunitas etnis
yang jumlahnya tidak signifikan tersebar dibeberapa tempat
tinggal di mana mereka berdomisili. Seperti kampung Bali,
kampung Arab, Bugisan atau kampung Bugis, Pecinan atau
kampung Cina, kampung Melayu, kampung Mandar dan
lain sebagainya. Enis dengan jumlah penduduknya kecil ini
kebanyakan tinggal di wilayah kota kabupaten Banyuwangi.
Sedangkan etnis dengan jumlah penduduk cukup besar
terbagi dalam tiga wilayah. Seperti etnis Jawa Mataraman
berdomisili di wilayah Banyuwangi selatan, etnis Madura
Pandalungan berdomisili di wilayah pesisir dan sebagian di
wilayah perkebunan karet, sedangkan etnis Using berdomisili
di daerah pertanian subur atau diwilayah tengah dan utara,
sebagian tinggal di tengah kota kabupaten Banyuwangi.
Contoh masyarakat etnis Using kemudian dalam
monograf ini disebut sebagai masyarakat Using desa
Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi. Desa ini
merupakan wilayah penduduk berbasis etnis Using, seperti
23
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
desa-desa lainnya dalam wilayah kecamatan Glagah. Seperti
desa Kampung Anyar, Kenjo, Olehsari, Paspan, Rejosari,
Taman Suruh, dan kelurahan Bakungan, serta kelurahan
Banjasari. Desa-desa dan kelurahan ini jaraknya kurang
lebih lima sampai delapan kilo meter arah barat dari pusat
kota kabupaten Banyuwangi, tepatnya di lereng gunung Ijen.
Merupakan gunung aktif yang terkenal di dunia karena Blue
fire.
Masyarakat Using desa Kemiren, selain memiliki
kemiripan secara karakteristik dalam satuan wilayah
kecamatan sebagaimana disebutkan di atas. Juga, memiliki
kemiripan dengan masyarakat Using pada umumnya di
Banyuwangi, terutama terkait dengan karakteristik tempat
tinggal dan adat kebiasaannya atau budayanya. Mereka rata-
rata bermukim di wilayah pertanian dan perkebunan subur,
seperti di kecamatan Giri, Licin, Singojuruh, Rogojampi,
Blimbingsari, Songgon, Kabat, Cluring, Banyuwangi Kota,
sebagian kecamatan Genteng. tersebar di 10 kecamatan saling
berdekatan dari 24 kecamatan di Banyuwangi.
Posisi desa Kemiren itu sendiri, jika ditempuh dengan
kendaraan bermotor, dari pusat kota Banyuwangi menuju
desa tersebut, kurang lebih membutuhkan waktu 10 sampai
15 menit atau sekitar lima sampai delapan kilo meter menuju
arah barat, searah jika hendak menuju gunung Ijen. Wilayah
desa ini merupakan dataran tinggi dengan curah hujan cukup
tinggi sehingga banyak sumber-sumber mata air sering disebut
belik. Memiliki kontur tanah bergelombang, disepanjang garis
melintang membujur dari timur ke barat terbentang tanah
pertanian, serta disebelah selatan dan utara desa ini dibatasi
dua buah aliran sungai, suatu kondisi wilayah pedesaan yang
subur dan ramah lingkungan.
Berdasarkan data statistik desa pada tahun 2012, bahwa
luas wilayah desa Kemiren sekitar 177,052 km2, ketinggian
24
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
wilayah 144 m dpl. Jumlah penduduk 2600 jiwa, terdiri 1025
KK. Mayoritas atau sekitar 99% masyarakatnya beragama
Islam. Penduduknya mayoritas berbasis masyarakat Using,
terlihat nuansa khas masyarakatnya dalam mempertahankan
kebudayaan peninggalan leluhur khususnya dalam wujud
budaya tangibles dan intangible seperti beragam seni budaya
dan tradisi upacara, di antaranya upacara adat Barong Ider
Bumi.
Asal usul masyarakat Using desa Kemiren oleh beberapa
sumber mengatakan sebagai masyarakat pendatang berasal
dari penduduk desa Cungking. Rata-rata mereka adalah para
pejuang tangguh yang mengungsi untuk mengatur strategi
ketika melawan penjajah Belanda. Desa Kemiren awalnya
merupakan hutan dan bukit-bukit yang penuh dengan
tanaman pohon kemiri, durian dan aren. Tanaman-tanaman
itu tumbuh subur di wilayah ini, sehingga diberi nama desa
Kemiren. Suatu ketika terjadi heroisme wilayah timur dan
selatan Banyuwangi akibat perlawanan masyarakat Using
terhadap penjajah Belanda, maka beberapa penduduk
masyarakat Cungking lebih memilih tinggal di pegunungan
atau hutan dan perkebunan untuk mengungsi. Dalam waktu
cukup lama mereka tinggal di hutan dan pegunungan, dan
mereka lebih nyaman dan aman tinggal di perkampungan
yang dibuat dengan cara membabat hutan untuk dijadikan
perkampungan baru, bernama Kemiren. Menurut beberapa
sumber, awalnya desa Kemiren merupakan bagian dari desa
cungking, sebagai pedukuhan, yaitu dukuh Kemiren. Seiring
berjalannya waktu, perkampungan baru itu menjadi desa
mandiri, dukuh Kemiren akhirnya menjadi desa Kemiren.
Dalam perkembangannya desa Kemiren memiliki
dua wilayah perdusunan, yaitu dusun Kedaleman yang
terdiri dari 11 RT dan dusun Krajan yang terdiri dari 13 RT.
Masing-masing dusun berbatasan dengan desa tetangga,
yaitu untuk batas wilayah desa sebelah barat dengan desa
25
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
Taman Suruh; sebelah utara dengan desa Jambesari; di
sebelah timur dengan kelurahan Banjarsari; dan di sebelah
selatan dengan desa Olehsari. Desa Kemiren ini diapit oleh
dua sungai di sebelah utara dan selatan membujur dari barat
ke timur. Kiri kanannya di penuhi hamparan sawah dan
ladang subur. Di sanalah suku atau etnis Using desa Kemiren
tinggal dan berdomisili, tidak terlalu jauh dari kota, akses
mudah dan cepat melewati jalan lurus dan bagus. Meskipun
secara tempat domisili berpotensi terpengaruh budaya global
dan cenderung mengalami pergeseran nilai budaya, tetapi
semangat kegigihan memelihara dan mempertahankan
budaya tua lebih diutamakan sebagai kepatuhannya terhadap
uri-uri leluhur.
C. Hubungan Sosial Budaya dan Agama Masyarakat Using
Kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat
Using desa Kemiren tergambarkan ketika kepala desa Kemiren
yang sedang menjabat saat itu, menjelaskan dengan penuh
semangat seraya mempersilakan untuk menikmati hidangan
jajanan khas Using yang tertata rapi di atas meja. Berada dalam
nuansa rumah adat Using yang unik. Seraya mempromosikan
kebiasaan masyarakatnya perihal kerukunan, persaudaraan,
kebersamaan, lemesan, gotong royong atau kemroyok.
Misalkan ada salah satu warga masyarakat yang mengalami
situasi tertentu atau mempunyai hajat tertentu, mendirikan
rumah atau selamatan, maka warga lainnya berduyun-
duyun mendatanginya dan turut serta membantu. Tidak
hanya tenaga, juga biaya atau keperluan lain sebagaimana
kebiasaan mereka yang telah dilakukan sejak lama. Bahkan
tidak jarang, demi kerukunan dan kebersamaan tidak segan-
segan merepoti diri sendiri, dengan mengada-adakan sesuatu
yang sesungguhnya mereka sendiri tidak punya, dengan
berbagai cara mereka upayakan demi menjaga kebersamaan,
kerukunan dan gotong royong.
26
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Ketika salah satu warga, ada yang sekedar memperbaiki
atap rumah yang bocor, atau sedang membetulkan atap
rumah terbuat dari genting, sejumlah warga berdatangan
membantu. Tidak hanya tenaga yang disumbangkan, juga
dengan membawa gula, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.
Begitu seterusnya, bahkan jika ada yang tidak ikut serta
dalam kegiatan itu atau tidak berpartisipasi, mereka merasa
kikuh atau risih, merasa tersisihkan, merasa kurang nyaman
atau gengsi. Fenomena itu menurut kepala desa merupakan
kebiasaan adat istiadat masyarakat Using, sehingga jika ada
anggota masyarakat yang tidak menyadari dengan kondisi
demikian kecenderungan tidak kerasan (tidak jenak tinggal di
desa itu), dan cenderung pindah. Kebiasaan masyarakat Using
demikian oleh kepala desa dikatakan dengan peribahasa
“besar pasak dari pada tiang”, artinya antara pendapatan
dan pengeluaran tidak seimbang. Perilaku masyarakat Using
demikian kemudian diistilahkan sebagai sikap dan perilaku
Aclak.
Gambaran sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi
semangat kolektivitas, tercermin dari semangat kebersamaan
dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari. Konsep rahab
atau rukun dan gotong royong tertanam dalam perilaku
kehidupan mereka. Perbedaan dalam keyakinan beragama
bukan merupakan penghalang dalam menjaga nilai-nilai
kebersamaan di antara mereka, mereka tidak segan-segan
berkorban untuk membantu meskipun dirinya sendiri sedang
membutuhkan, artinya mereka tidak segan-segan merepoti
dirinya sendiri, dalam konsep bahasa Using hal itu disebut
Aclak (Sunarlan, 2008 : 137).
Konsep rahab atau rukun yang melekat dalam
diri masyarakat Using menjadi dasar kuat dalam
mempertahankan nilai persaudaraan. Aktualisasi nilai-nilai
persaudaraan terlihat ketika cara mereka menghormati tamu
yang berkunjung ke rumah atau wilayahnya, atau ketika
27
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
mereka menghadiri undangan-undangan atau slamatan.
Perilaku grapyak diperlihatkan dengan siapa saja berinteraksi,
terlepas dikenal atau tidak dikenal, perlakukan mereka
begitu nyedulur. Karakter egaliter membuat mereka mudah
beradaptasi karena bagi mereka semua orang setara, tidak
membedakan tingkatan, baik cara berkomunikasi lisan
ataupun cara berinteraksi sosial. Sifat dan sikap demikian
merupakan karakter dalam istilah budaya Using disebut
Bingkak.
Hubungan sosial mereka tidak sebagaimana masyarakat
Jawa pada umumnya, yang memiliki herarki dalam menjalin
hubungan sosial di antara mereka. Masyarakat Using desa
Kemiren lebih egaliter dalam memahami realitas sosial. Bagi
masyarakat Using desa Kemiren status sosial atau atribut
sosial yang melekat pada diri seseorang tidak mempola
hubungan sosialnya. Mereka memiliki prinsip, bahwa
hormat lebih hanya kepada yang bersifat penghargaan dalam
kesataraan (horisontal). Sehingga bukan menjadi suatu hal
yang berlebihan jika sikap, sifat dan perilaku kebanyakan
masyarakat Using adalah Bingkak.
Sikap dan sikap itu tercermin dari penggunaan bahasa
komunikasi dalam interaksi sosialnya, mereka menggunakan
bahasa khas, disebut Bahasa Using. Bahasa yang mereka
gunakan bukan seperti bahasa Jawa, terdapat istilah bahasa
ngoko, bahasa kromo dan bahasa kromo inggil. Sehingga
cap atau identitas egaliter melekat pada masyarakat Using,
seperti hormat ketika hanya kepada mertua dan orang yang
telah menunaikan ibadah Haji. Interaksi sosialnya seperti itu
kemudian disebut bisiki.
Sebagian besar (99%) masyarakat Using desa Kemiren
pemeluk agama Islam. Namun, mereka masih terlihat secara
sadar tetap menjalankan tradisi yang sudah mengakar sebagai
warisan para leluhurnya. Karena secara historis masyarakat
28
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Using sebagaimana yang digambarkan oleh Cliford Geertz
dan Beatty (2001) sebagai masyarakat abangan. Kehadiran
Islam dalam artian syariat Islam bukan sebagai ancaman
dalam memaknai keyakinan beragama dan keyakinan
sebelumnya, bahkan telah terjadi akulturasi budaya. Oleh
karena itu sebagaimana dalam kajian Andrew Beatty
terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat Using
dengan didukung oleh sikap yang terbuka dan tentu sepakat
untuk berbeda tanpa mempertentangkan adanya perbedaan
pendapat secara tajam, namun lebih mementingkan nilai-
nilai semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam suatu
keluarga, kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari adalah
keniscayaan. Sikap dan sifat demikian dalam konsep budaya
Using disebut dengan istilah Ladak.
Keluarga, kekerabatan dan kehidupan sehari-hari
masyarakat Using desa Kemiren, menjunjung tinggi nilai-nilai
persaudaraan dan semangat kolektivitas. Bagi masyarakat
Using kerukunan lebih utama, karena ancaman yang
sebenarnya bukan terletak pada kepentingan-kepentingan
obyektif, paradoks itu menurut Sunarlan (2008) dapat
dikompromikan secara memuaskan, tetapi menjadi lebih sulit
dalam emosi-emosi yang melekat padanya terkait hubungan
pernikahan. Sehingga menjadi tabu bagi masyarakat using
jika dalam sebauah mahligai keluarga terjadi perceraian.
Kebudayaan bertani dan berkebun adalah kebudayaan
yang diwarisi oleh leluhurnya. Di bidang pertanian,
mereka sangat mahir ketika mengelola sawah, sehingga
tidak jarang produk dan hasil budaya yang dihasilkan oleh
masyarakat Using selalu terkait dengan hasil pertanian dan
perkebunan serta menghasilkan nilai ekonomi yang baik.
Ketekunan dalam bidang pertanian, tergambarkan dalam
kemampuannya secara inovatif untuk meningkatkan hasil
produksi padi, melalui kemampuannya membuat Angklung
Paglak dan Kiling. Kedua hasil inovasi itu merupakan alat
29
Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak
yang digunakan untuk mengusir hama burung yang akan
menyerang sawah mereka. Dalam perkembangannya, kedua
alat pengusir hama padi itu menjadi membudaya, dan masuk
dalam budaya secara bendawi (tangible) sekali gus dalam
aktualisasinya menjadi budaya non bendawi (in-tangible).
Perilaku inovasi demikian dalam khasanah budaya Using
disebut dengan istilah Ladak.
Di samping itu, terkait dengan kesejateraan dan
kedamaian kehidupan masyarakat Using desa Kemiren
terjadi perilaku budaya seperti Upacara Barong Ider Bumi dan
Tumpeng sewu serta kegiatan upacara-upacara adat lainnya
yang rutin dilaksanakan setiap tahun, pada akhirnya menjadi
suatu tindakan sosial sebagaimana konsep Weber. Bahwa
suatu tindakan sosial terjadi bilamana tindakan individu itu
yaitu masyarakat Using selaku aktor sepanjang tidakannya
mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan
diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2010).
Seperti Barong, sebenarnya Barong merupakan budaya
tangibles atau budaya bendawi, yaitu sebuah budaya material
khas masyarakat Using desa Kemiren. Sebagian sumber
mengatakan Barong sengaja dibuat pada awalnya sebagai
sarana bermain anak-anak kecil diwaktu sore hari, namun,
kemudian menjadi intangibles ketika budaya bendawi itu
berubah peran menjadi Barong Ider Bumi dijadikan media
upacara adat oleh masyarakat Using desa Kemiren. Tentu
dalam kontek interasionis simbolik Mead, hal ini merupakan
kemajuan dalam cara berpikir yang menghasilkan budaya khas.
Kemajuan peradaban yang mereka bangun memunculkan
aktivitas, kreativitas serta inovatif dalam peran terkendali.
Sementara itu juga memunculkan karakteristik dalam sikap
dan sikap yang konotasi negatif dengan menggunakan istilah
Aclak Bingkak dan Ladak sebagaimana konsep diri (self) dalam
teori interaksionis simbolik Mead, tentang I dan me yang
memiliki peran ganda.
30
Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi
Berbeda dengan upacara adat Ider Bumi di tempat
lain, seperti desa Alasmalang Singojuruh dan desa Aliyan
Rogojampi. Upacara adat Ider Bumi di desa Kemiren terkait
dengan sosok danyang desa bernama buyut Cili. Buyut Cili,
dalam kepercayaan masyarakat setempat sebagai sosok
yang melindungi, sosok yang selalu hadir dalam kehidupan
mereka. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh masyarakat desa Kemiren selalu menyertakan buyut Cili
dalam kehidupannya dengan melakukan persembahan sesaji
di makan buyut Cili, sebagai tanda permohoanan ijin kepada
danyang desa tersebut.
Cara pifikir dan cara pandang masyarakat Using desa
Kemiren sampai kepada suatu perilaku dan tindakan sosial
bermakna atau berarti subyektif bagi masyarakat Using
itu sendiri dan diarahkan kepada tindakan orang lain.
Artinya, segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan upacara adat Barong Ider Bumi itu mampu
membawa kepada suatu ketentraman dan kesejahteraan
bagi individu masyarakat Using desa Kemiren, dan melalui
tindakannya itu berpengaruh dalam beberapa aspek
kehidupan orang lain. Seperti, keamanan desa Kemiren dan
kesejahteraan masyarakatnya difahami merupakan akibat
dari tindakan individu masyarakat Using selaku aktor.
Diselenggarakannya upacara adat Barong Ider Bumi
berawal dari adanya sosok yang selalu hadir dalam kehidupan
masyarakat Using merupakan mitos tentang buyut Cili, dan
terkait dengan wabah penyakit diberi nama Pageblug. Mitos
diartikan sebagai cerita suci yang bersifat sakral, terkait
dengan tokoh yang sering dipuja. Oleh karena itu cerita-
cerita masyarakat Using desa Kemiren tentang sosok buyut
Cili dipahami sebagai suatu keyakinan terhadap mitos. Bagi
masyarakat Using desa Kemiren, meskipun hal itu merupakan
cerita yang bersifat mitos, namun dipercaya memiliki fungsi.
Kehadirannya dianggap mampu memberikan pedoman serta
31
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
SPIRIT ACLAK, BINGKAK DAN LADAK INTERAKSI SIMBOLIK UPACARA ADAT BARONG IDER BUMI by Rochsun (z-lib.org)
View in Fullscreen
SPIRIT ACLAK, BINGKAK DAN LADAK INTERAKSI SIMBOLIK UPACARA ADAT BARONG IDER BUMI by Rochsun (z-lib.org)
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search