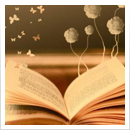DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:
SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS & UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
BIODIVERSITAS EKOLOGI
BIOTA PERAIRAN
Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
BIODIVERSITAS EKOLOGI
BIOTA PERAIRAN
Gazali Salim, dkk.
DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:
SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS & UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
JBuIOdDulIVBEuRkSu:ITAS EKOLOGI BIOTA PERAIRAN
Penulis:
Gazali Salim, Sutrisno Anggoro, Adri Patton, Agus Indarjo, Sitti Hartinah,
Julian Ransangan, Lukman Yudho Prakoso, Rukisah Saleh, Ratno Achyani,
Azis, Muhammad Firdaus, Meiryani, Nabila Meiliyani, Abdul Rahim
ESdafirtiodra:
PMeunhaatmamLaedtaIkrf:an
IPqebraalnRciadnhga Sampul:
ISBN:
SPYraIAceHtaKkUdAaLnAPUrNodIVuEkRsiS: ITY PRESS
SPyeinaehrbKiut:ala University Press
Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111,
Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh
Telp: 0651-8012221
Eupmt.apiel:[email protected]
[email protected]
Whttepbss:/i/tues:kpress.usk.ac.id/
UJanlaivneArsmitaalsLBamoranNeoomTaorra1k,aTnarakan
Telp. 08115307023
Fax. 08115307023
Email: [email protected]
Cetakan Pertama, 2021
Tahun Digital, 2021
vii + 119 Halaman (15,5 cm x 23 cm)
Anggota IKAPI 018/DIA/2014
Anggota APPTI 005.101.1.09.2019
Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku
ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.............................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................. iv
DAFTAR TABEL....................................................................................... v
PRAKATA................................................................................................. vii
BAB I KEANEKARAGAMAN HAYATI.......................................................1
A. Keanekaragaman Hayati..................................................................1
B. Keanekaragaman Hayati Laut..........................................................2
C. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati............................................3
D. Manfaat dan Ancaman Keanekaragaman Hayati.............................4
BAB II KEANEKARAGAMAN MANGROVE DI KALIMANTAN UTARA �����7
A. Ekosistem Mangrove Di Kalimantan Utara.......................................8
B. Ekosistem Mangrove Di Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan
(Kkmb)............................................................................................ 11
BAB III KEANEKARAGAMAN BIVALVIA DI KALIMANTAN UTARA....19
A. Keanekaragaman Jenis Kerang di Kalimantan Utara.................... 20
BAB IV KEANEKARAGAMAN GASTROPODA DI KALIMANTAN UTARA ����31
A. Gastopoda..................................................................................... 31
B. Jenis-Jenis Gastropoda di Kalimantan Utara................................. 32
BAB V KEANEKARAGAMAN CRUSTACEA DI KALIMANTAN UTARA ��� 41
A. Jenis Crustacea Di Kalimantan Utara............................................ 41
BAB VI KENAKERAGAMAN PISCES DI KALIMANTAN UTARA..........51
A. Klasifikasi Pisces........................................................................... 51
B. Morfologi Ikan................................................................................ 52
C. Jenis Ikan Yang Berada Di Kalimantan.......................................... 54
BAB VII METODE KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI-
SUMBERDAYA PERAIRAN.....................................................................59
A. Pengertian Dasar...........................................................................59
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................95
TENTANG PENULIS..............................................................................103
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Rhizophora apiculata ..........................................................10
Gambar 2.2 Rizhophora mucronata.........................................................12
Gambar 2.3 Sonneratia alba....................................................................13
Gambar 2.4 Nypa fruticans......................................................................14
Gambar 3.1 Fitur Utama dari Bivalvia......................................................17
Gambar 3.2 Anatomi Umum Bivalvia.......................................................17
Gambar 3.3 Kerang Kapah (Meretrix meretrix)........................................19
Gambar 3.4 Kerang Kapah (Geloina coaxans)........................................21
Gambar 3.5 Penyebaran Kerang Kapah (Geloina coaxcans)..................21
Gambar 3.6 Kerang Kapah (Meretrix lyrata)............................................22
Gambar 3.7 Penyebaran Kerang Kapah jenis Meretrix lyrata.................23
Gambar 3.8 Kerang Pahut-Pahut (Phaarella acutidens).........................24
Gambar 3.9 Kerang Darah (Anadara granosa)........................................25
Gambar 3.10 Anadara inaequivalvis..........................................................27
Gambar 4.1 Morfologi Umun Gastopoda.................................................29
Gambar 4.2 Temberungun (Telescopium telescopium)...........................31
Gambar 4.3 Cassidula aurisfelis..............................................................32
Gambar 4.4 Littoraria scabra...................................................................33
Gambar 4.5 Nerita articulata....................................................................34
Gambar 4.6 Cerithidea obtuse.................................................................35
Gambar 4.7 Cerithidea cingulata.............................................................36
Gambar 4.8 Chicoreus capucinus............................................................37
Gambar 5.1 Udang Windu yang Ditangkap Di Perairan Juata
Kota Tarakan........................................................................39
Gambar 5.2 Udang Nenek yang Ditangkap Di Perairan Juata Kota Tarakan �44
Gambar 5.3 Perbedaan morfologi kepiting jantan dan betina..................48
Gambar 5.4 Spesies Uca Rosea.............................................................49
Gambar 5.5 Spesies Uca Arcuata............................................................49
Gambar 5.6 Spesies Uca Crassipes........................................................49
Gambar 5.7 Spesies Uca Dussumieri......................................................50
Gambar 5.8 Spesies Uca Tetragonon......................................................50
Gambar 5.9 Spesies Uca Vocans............................................................50
Gambar 6.1 Skema Ikan Untuk Menunjukkan Ciri-Ciri Morfologi Utama
dan Ukuran-Ukuran yang Digunakan dalam Identifikasi......48
iv
Gambar 7.1 Pembagian Kategori, Jenis dan Zona Kawasan Konservasi
Kehati Perairan....................................................................61
Gambar 7.2 Integrasi Perencanaan WP3K dengan Zonasi Kawasan
Konservasi........................................................................... 62
Gambar 7.3 Gambaran Kawasan Konservasi Kehati Multifungsi yang
dikelola dengan Sistem Zonasi............................................62
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia................................. 3
Tabel 2.1 Jenis mangrove di daerah pantai wilayah Kecamatan
Tarakan Utara............................................................................8
Tabel 2.2 Jenis mangrove di daerah pantai wilayah Kecamatan
Tarakan Timur...........................................................................9
Tabel 2.3 Jenis mangrove di daerah pantai wilayah Kecamatan
Tarakan Barat..........................................................................10
Tabel 2.4 Jenis mangrove yang terdapat di Pulau Sadau...................... 11
Tabel 3.1 Jenis-Jenis Bivalvia yang ditemukan di Kalimantan Utara..... 21
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Gastopoda yang ditemukan di Kalimantan Utara..... 33
Tabel 5.1 Jenis Crustacea yang Ditemukan Di Kalimantan Utara......... 41
Tabel 6.1 Komposisi Jenis Ikan yang Ditemukan Perairan Dekat
Vegetasi Mangrove................................................................ 55
Tabel 6.2 Komposisi Jenis Ikan yang Ditemukan di Tambak-Tambak
Kalimantan Utara................................................................... 56
Tabel 7.1 Kategori dan Jenis Kawasan Konservasi................................59
Tabel 7.3 ................................................................................................64
Tabel 7.2 Sistem Zonasi Kawasan Konservasi KEHATI Perairan..........63
Tabel 7.2 Sistem Zonasi Kawasan Konservasi KEHATI Perairan..........63
Tabel 7.4 Kriteria Kesesuaian Zonasi Konservasi Kehati.......................68
Tabel 7.5 Kriteria untuk Pencadangan Kawasan Konservasi
Keanekaragaman Hayati Perairan..........................................72
Tabel 7.6 Penggolongan Skor untuk Penilaian Kesesuaian Zona pada
Kawasan Konservasi di WP3K................................................81
Tabel 7.7 Sistem Penilaian Kesesuaian Kawasan Konservasi
Keanekaragaman Hayati.........................................................82
Tabel 7.8 Contoh Hasil Penilaian Kesesuaian Kawasan Konservasi
Kehati alternatif 1....................................................................83
Tabel 7.9 Contoh Hasil Penilaian Kesesuaian Zona Konservasi Kehati
Alternatif 2...............................................................................84
Tabel 7.10 Pengaturan Kegiatan di Kawasan Konservasi Kehati............87
Tabel 7.11 Contoh Pengaturan Kegiatan di Zona Kawasan Konservasi.......89
PRAKATA
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan
rahmatNya, buku Referensi Biodiversitas Ekologi Biota Perairan ini dapat
menyelesaikan buku ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan
kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menyampaikan petunjuk
pada kita, agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Smeoga kita
mendapatkan syafa’atnya kelak di akhirat nanti.
Sebelumnya kami ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, dari awal
penyusunan hingga akhir. Buku ini memiliki tema biodiversitas atau
keanekaragaman biota perairan, khususnya yang berada di Kalimantan
Utara. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi sumber ilmu,
menjadi buku referensi yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan,
dan dapat menambah ilmu mengenai keanekaragaman hayati, khususnya
keanekaragaman hayati biota perairan.
Kami selaku penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu kami ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan
yang ditemukan pada buku ini. Dan kami selaku penulis mengharapkan
kritik dan saran agar kami dapat menjadi lebih baik ladi kedepannya nanti.
Terimakasih.
Penulis
vii
BAB I
KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
A. KEANEKARAGAMAN HAYATI
Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman atau variasi
dari berbagai hewan, tumbuhan, mikroorganisme, materi genetik atau
bentuk ekosistem yang memiliki berbagai macam perbedaan didalamnya
(Ridhwan, 2012). Indonesia yang merupakan negara kepulauan, terdapat
berbagai macam mahkluk hidup. Mereka berada di setiap pulau, laut,
maupun daratan yang kelilingi oleh gunung-gunung, rawa, sungai atau
ekosistem lainnya. Dengan presentase luas daratan yaitu 1,3% dari jumlah
luas daratan yang berada di dunia, Indonesia tetap memiliki berbagai
macam keanekaragaman hayati dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan,
fungi, serta dari mikroorganisme (Gautam dkk, 2000). Pada data IBSAP
tahun 2003, Indonesia memiliki 38.000 dari jenis tumbuhan. 55% dari
jumlah ini adalah tumbuhan khas endemik Indonesia.
Selain memilki keanekaragaman tumbuhan, Indonesia juga memiliki
keanekaragaman hewan. Dari jenis hewan bertulang belakang atau
vertebrata, terdapat 515 jenis, 39% dari jumlahnya merupakan hewan
khas Indonesia; 511 jenis reptilia, 30% dari jumlahnya juga merupakan
hewan khas Indonesia; 1531 jenis burung, 20% dari jumlahnya merupakan
hewan khas Indonesia; dan terdapat 270 jenis amphibi, 40% dari jumlahnya
merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia. keanekaragam ini
menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam, yang didalamnya
terdapat berbagai jenis hewan serta tumbuhan (Walujo, 2011).
Kondisi letak geografisnya yang berada di daerah tropis, menyebabkan
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Berbeda dari negara-
negara yang daerahnya memiliki kondisi geografis seperti sub-tropik yang
beriklim sedang, atau daerah kutub. Tingginya suatu keanekaragaman
hayati yang dimiliki dapat dilihat dari berbagai macamnya jenis ekosistem
dimiliki, yaitu ekosistem hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem
pantai, ekosistem air laut, ekosistem air tawar, ekosistem terumbu karang,
ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem estuaria, ekosistem savanna
dan lainnya. Setiap ekosistem-ekosistem ini memiliki keanekaragaman
hayatinya sendiri (Ridhwan, 2012).
1
Keanekaragaman hayati dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu
Genetic diversity serta Species diversty (Keanekaragaman genetik dan
keanekaragaman spesies). Keanekaragam bisa bersumber dari berbagai
aspek, seperti tumbuhan yang berkembang di daratan, tumbuhan yang
berkembang di laut, atau ekosistem lainnya.
Keanekaragaman jenis merujuk pada jumlah jenis serta jumlah
individu pada setiap jenisnya. Keanekaragaman jenis juga biasanya
dijadikan sebagai karakteristik dari tingkatan komunitas, berdasarkan
organisasi biologisnya. Keanekaragaman jenis mempunyai komponen
yang dapat memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap faktor
geografi, perkembangan atau fisiknya. Setiap satu komponen utamanya
disebut sebagai kekayaan varietas atau kekayaan jenis.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya
keanekaragaman jenis. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Ketersediaan Jumlah Energi
Faktor pendunkung terjadinya keanekaragaman jenis yang terjadi ini
dikarenakan adanya peningkatan radiasi matahari pada daerah tropis
sehingga aktivitas fotosintesis pun meningkat. Hal ini menyebabkan
meningkatnya sumberdaya untuk organisme.
b. Heterogenitas Habitat (Keberagaman Habitat)
Daerah tropis merupakan daerah yang biasanya mengalami
gangguan serta memiliki ketidakseragaman lingkungan yang lebih
besar daripada daerah yang lain. Karena hal ini, keanekaragaman
memiliki jumlah variasi yang lebih besar.
B. KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki “Mega
Biodiversitas”, dan terkenal sebagai pusat konsentrasi keanekaragaman
hayati dunia. Terlebih keanekaragaman hayati yang berasal dari lautan,
Indonesia sendiri juga termasuk yang memilki keanekaragaman hayati
yang tinggi. Terdapat berbagai jenis mahkluk hidup yang tersebar di wilayah
laut Indonesia. Wilayah laut Indonesia sendiri terbagi menjadi dua wilayah,
yaitu willayah paparan dan wilayah laut dalam. Dua paparan wilayah laut
ini membagi Indonesia menjadi bagian Barat dan bagian Timur Indonesia
yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis mahkluk hidup. Hal ini
dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menyajikan keanekaragaman hayati di
laut Indonesia (Yusron, 2005).
2
Tabel 1.1 Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia
(MOOSA, 1999 dalam Yusron, 2005)
Kelompok Kelompok Jumlah Sumber
Taksa Utama Jenis
196 Van Boose, 1928
Tumbuhan Alga Hijau 134 Van Boose, 1928
Alga Coklat 425 Van Boose, 1928
Alga Merah Den Hartog, 1970
13 Soegiarto & Polunin, 1981
Lamun 38 Tomascik dkk, 1997
Mangrove 461 Hermanlimianto, T.H
210 Hermanlimianto, T.H
Karang Scleractinia 350 Van Soest
Karang Lunak 850 Kastoro, W.
1500 Valentine, 1971
Gorgonia 1000 Moosa, M.K
112 Moosa, M.K
Spons Desmospongia 1400 Clark & Rowe, 1971
91 Clark & Rowe, 1971
Moluska Gastropoda 87 Clark & Rowe, 1971
Bivalvia 142 Clark & Rowe, 1971
284 Clark & Rowe, 1971
Krustasea Stomatopoda 141 Fishbase, 1996
Brachyura 2140 Rene Marquez, 1990
6 Suwelo, 1988
Ekhinodermata Crinoidea 1 Tomascik dkk, 1997
Asteroidea 31 Van Balen
Ophiuroidea 148 Suwelo, 1998
Echinoidea 29 Soegiarto & Polunin, 1981
Holothuroidea 1
Ikan Ikan Laut
Reptilia Penyu
Buaya
Ular Laut
Burung Burung Laut
Mamalia Paus & Lumba-Lumba
Duyung
Sumber: Yusron, 2005
C. PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Kawasan pesisir merupakan kawasan yang memilki keanekaragam
sumber daya hayati yaitu ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove
dan biota-biota yang lainnya. Daerah pesisir mempunyai letak yang strategis
karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem
laut, dan memiliki potensi sumber daya alam yang kaya. Kekayaan sumber
daya alam yang banyak dapat menjadi daya tarik abgi beberapa pihak untuk
memanfaatkannya. Terdapat beberapa kekayaan sumber daya alam seperti
pulau-pulau, mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya hayati
maupun non-hayati yang terdapat didalamnya.
3
Selain kekayaan sumberdaya hayati, daerah kawasan pesisir
biasanya juga memilki keanekaragaman non-hayati seperti mineral-
mineral yang terkandung didalamnya. Semua yang dimiliki oleh kawasan
pesisir ini menjadi daya tarik tersediri untuk dikembangkan menjadi salah
satu objek wisata kawasan pesisir.
Hal yang bisa kita lihat sebagai contoh adalah pemanfaatan
keanekaragaman hayati sebagai pariwisata bahari. Di Indonesia terdapat
berbagai daerah yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam bahari
untuk dijadikan sebagai tempat wisata yang dapat menarik para wisatawan
dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah kegiatan penyelaman
untuk melihat keanekaragaman terumbu karang yang hidup di dasar laut.
Sebagai contoh salah satu daerah di Kalimantan, yaitu Pulau Derawan. Di
pulau ini terkenal dengan keindahan bawah airnya yaitu terumbu karang,
sehingga banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang datang
untuk melihat keindahannya. Selain di Pulau Derawan, kegiatan seperti ini
juga terdapat di daerah-daerah lain seperti Jogja dan Bali.
Selain sebagai kegiatan pariwisata, keanekaragaman hayati juga
bermanfaat di bidang obat-obatan. Dengan tingkat keanekaragaman
hayati yang tinggi, Indonesia memiliki potensi tanaman obat yang tinggi
pula. Saat ini terdapat 9600 spesies tumbuhan yang dikonfirmasi bisa
digunakan sebagai bahan baku untuk membuat obat-obatan tradisional
(Herdiani, 2012). Di pedalaman Kalimantan Tengah, terdapat tanaman
obat yang biasanya di manfaatkan oleh masyarakat lokal, yaitu bawang
hantu. Bawang hantu ini memilki kandungan yaitu glikosida, flavonoid,
tannin, fitokimia alkaloid, dan fenolik (Galingging, 2007). Selain itu,
pada penelitian Zuhud (2009) didapatkan bahwa terdapar 2000 spesies
tumbuhan di hutan Indonesia, dan dari jumlah ini terdapat 772 spesies
merupakan tanaman obat yang berasal dari hutan hujan tropis. Biasanya
tumbuhan obat ini bagian yang dimanfaatkan untuk dijadikan obat ialah
akar, daun, batang, biji, buah, serta air batang (Nugroho, 2017).
D. MANFAAT DAN ANCAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Keanekaragaman dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan dari
ekosistem. Contoh keanekaragaman laut menjadi salah satu indikator
kesehatan bumi serta penentu keberlangsungan hidup manusia. Contoh
yang dapat dikita lihat adalah laut sebagai penghasil oksigen. Tanaman-
tanaman yang berada di laut menghasilkan 50% kebutuhan oksigen di
alam. Selain itu, terumbu karang juga dapat menghasilkan 37 milliar dollar
4
pada setiap tahunnya. Dari sisi perikanan, perikanan tangkap maupun
perikanan budidaya memberikan kontribusi pendapatan lebih dari 10%
dari seluruh populasi dunia. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan
sumber daya ikan memiliki manfaat sebagai sumber protein dan nutrisi
bagi manusia.
Ekosistem seperti ekosistem terumbu karang, mangrove juga
memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Sebagai
salah satu contoh, mangrove dapat memberikan manfaat sebagai
pelindung dari terjangan badai dan cuaca ekstrim. Karena banyaknya
manfaat yang diberikan inilah kita perlu menjaga kelestarian lingkungan
laut agar terhindar dari pencemaran. Selain itu diperlukannya pengelolaan
manusia yang tepat agar sumber daya alam selalu lestari, dan terhindar
dari kerusakan atau kepunahan (Lendi, 2019).
Selain pemanfaatan keanekaragaman hayati, hal yang perlu
dilakukan juga adalah menjaga kelestariannya.The United Nations
Environmental Programme atau biasa disebut UNEP (2000) menyatakan
jika kepunahan keanekaragaman hayati terjadi di sekitar kita, maka timbul
berbagai macam masalah seperti menurunnya suplai makanan, kehilangan
panorama pemandangan yang indah yang menyebabkan turunnya tingkat
pariwisata, kehilangan sumber-sumber seperti kayu dan obat-obatan serta
hilangnya sumber energi (Samshitawrati, 2017).
Keberadaan keanekaragaman hayati laut saat ini menjadi terancam
karena telah terjadi eksploitasi secara besar-besaran serta tidak
bertanggung jawab dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan itu. Hal
ini pun dikritisi oleh dari kalangan peneliti maupun pemerhati lingkungan.
Craig (2005) dalam Samshitawrati (2017) menyatakan bahwa kegiatan
eksploitasi terjadi dikarenakan meningkatkan populasi manusia, sehingga
kegiatan eksploitasi pun gencar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Karena hal ini, kehidupan biota laut, yang menjadi rantai utama
untuk keberlangsungan hidup kita pun terganggu. Dari hasil studinya, Craig
(2005) menunjukan di tahun 1995, perikanan laut yang telah di eksplotasi
sebesar 22%. Selain kegiatan perikanan. Kegiatan-kegiatan lain yang
mengancam sumber daya alam hayati laut ialah kegiatan pembangunan
yang dilakukan di daerah pesisir pantai, yang menyebabkan kerusakan
habitat laut, dan penangkapan ikan secara berlebihan atau Over Fishing
(Samshitawrati, 2017). Dahuri (2003) menyatakan bahwa terdapat
beberapa faktor yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam,
yaitu:
5
1. Pemanfaatan sumber daya yang berlebihan atau (Over Exploitation)
2. Penggunaan peralatan yang merusak lingkungan
3. Terjadinya degradasi fisik habitat
4. Pencemaran lingkungan
5. Introsuksi spesies asing
6. Merubah kawasan lindung
Keanekaragaman hayati sumber daya alam dapat diperbaharui.
Hal ini dapat terjadi jika kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut
dengan cara yang baik, serta rama lingkungan. Pengelolaan sumberdaya
hayati yang benar dan tepat dapat menjadikan Indonesia sebagai negara
yang akan selalu kaya akan keanekaragaman hayatinya.
6
BAB II
KEANEKARAGAMAN MANGROVE DI
KALIMANTAN UTARA
Mangrove menjadi komponen alam yang berperan penting. Mangrove
dapat menjadi penghasil produktivitas perairan yang dapat menunjang
kehidupan disekitarnya, baik untuk biota maupun untuk penduduk yang berada
di sekitarnya. Bagi wilayah pesisir, mangrove merupakan jalur hijau yang
berada di sepanjang pantai atau sungai yang sangat penting untuk biota yang
memanfaatkan mangrove sebagai tempat untuk memijiah. Selain itu, mangrove
juga menjadi pelindung dari abrasi, intrusi dan angin laut yang kencang.
Ekosistem mangrove merupakan daerah yang kaya akan unsur hara
yang dibutuhkan bagi lingkungan, sehingga perairan memiliki produktivitas
yang tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya tingkatan trofik makanan,
karena ketersediaan plankton dan bentos yang menjadi makanan bagi biota
yang ada di sekitar ekosistem ini. Karena itu, biota seperti ikan dan udang
memanfaatkan mangrove sebagai tempat untuk mencari makan, memijah,
dan pembesaran. Hal ini yang menjadikan mangrove sebagai daerah yang
memiliki nilai ekologis yang tinggi karena memiliki peran untuk menunjang
kehidupan biota yang berada di kawasan mangrove.
Bengen (2000) menyatakan bahwa mangrove memiliki berapa fungsi
sebagai berikut:
1. Pelindung pantai dari ombak, arus, maupun angin;
2. Menjadi tempat untuk berlindung, berpijah atau berkembang biak, dan
daerah asuhan biota perairan;
3. Penghasil bahan organic yang tinggi
4. Menjadi sumber bahan baku industri bahan bakar;
5. Pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya; serta
6. Tempat pariwisata.
Sedangkan menurut Baran dan Hambrey (1999), ekosistem
mangrove memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Tempat hidup serta mencari makan dan bereproduksi berbagai jenis
ikan, kepiting, dan udang
2. Sumber bahan makanan bagi biota estuari yang hidup disekitarnya
karena mangrove menghasilkan bahan organik;
7
3. Pelindung lingkungan dari erosi pantai, tsunami, gelombang, arus laut,
dan angin topan;
4. Penghasil biomas organik dan mampu menyerap polutan di sekitarnya;
5. Tempat rekreasi karena memiliki pemandangan kehidupan burung dan
satwa liar lainnya;
6. Sumber bahan kayu
7. Dapat dimanfaatkan sebagai sebuah tempat untuk melakukan
penangkaran dan penghasil bibit ikan;
8. Bahan obat-obatan.
A. EKOSISTEM MANGROVE DI KOTA TARAKAN
Kota Tarakan meliputi 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Sadau.
Kota Tarakan memiliki ciri pantai dengan vegetasi khas yaitu hutan mangrove
yang tersebar hampir di seluruh wilayah pantainya. Sebaran mangrove ini
terbentuk secara tidak merata tergantung dengan kondisi lingkungan di
sekitarnya. Hasil identifikasi BPLH Kota Tarakan tahun 2014 diketahui ±
17 Jenis mangrove yang ada di Kota Tarakan yang tersebar di sepanjang
pantai wilayah Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Timur, Tarakan Barat dan
Pulau Sadau. Berikut hasil identifikasi di masing-masing wilayah:
Jenis mangrove yang ditemukan di sepanjang pantai wilayah
Kecamatan Tarakan Utara beragam. Dari hasil observasi yang telah
dilakukan ditemukan berkisar 15 jenis mangrove (Tabel 2.1). Mangrove
di daerah pantai pada kecamatan Tarakan Utara yang menghadap ke
arah laut didominasi oleh 2 (dua) jenis yaitu avicenia alba (api-api) dan
Sonneratia alba (prepat). Sedangkan ke arah bagian belakang pantai jenis
yang ditemukan lebih bervariasi dengan jenis yang lebih banyak ditemukan
dari jenis Rhizophora apiculata dan Rhizophora mucronata.
Tabel 2.1. Jenis mangrove di daerah pantai wilayah Kecamatan Tarakan Utara.
No Jenis Sebaran
1 Sonneratia alba Pantai ke arah laut
2 Avicennia alba Pantai ke arah laut
3 Rhizophora apiculata Pantai ke arah darat
4 Rhizophora mucronata Pantai ke arah darat
5 Bruguiera gymnorhiza Pantai ke arah darat
6 Bruguiera plavifora Pantai ke arah darat
7 Ceriops tagal Pantai ke arah darat
8
No Jenis Sebaran
8 Shcyphiphora sp Pantai ke arah darat
9 Lumnitzhera racemosa Pantai ke arah darat
10 Xylocarpus granatum Pantai ke arah darat
11 Hereteria sp Pantai ke arah darat
12 terompet Pantai ke arah darat
13 Buta-buta Pantai ke arah darat
14 Aegiceras sp Pantai ke arah darat
15 Nypa fruticans Pantai ke arah darat
Sumber: BPLH Kota Tarakan (2014)
Jenis mangrove yang ditemukan di sepanjang pantai wilayah
Kecamatan Tarakan Timur cukup beragam. Dari hasil observasi yang
telah dilakukan ditemukan berkisar 13 jenis mangrove. Pada pantai yang
terdapat di wilayah Kecamatan Tarakan Timur secara umum terletak
terbuka dan menghadap kearah Laut Sulawesi dengan kondisi arus lebih
kuat sehingga substrat lumpur akan mudah teraduk dan terangkat bahkan
pada daerah tertentu mengakibatkan abrasi pantai yang mengancam
keberadaan hutan mangrove di daerah ini. Berikut ini Tabel 2.2 gambaran
jenis-jenis mangrove yang ditemukan.
Tabel 2.2 Jenis mangrove di daerah pantai wilayah Kecamatan Tarakan Timur.
No Jenis Sebaran
1 Sonneratia alba Pantai ke arah laut
2 Avicennia alba Pantai ke arah laut
3 Sonneratia casiolaris Pantai ke arah darat
4 Rhizophora apiculata Pantai ke arah darat
5 Rhizophora mucronata Pantai ke arah darat
6 Bruguiera gymnorhiza Pantai ke arah darat
7 Ceriops tagal Pantai ke arah darat
8 Shcyphiphora sp Pantai ke arah darat
9 Lumnitzhera racemosa Pantai ke arah darat
10 Lumnitzhera littorea Pantai ke arah darat
11 Xylocarpus granatum Pantai ke arah darat
12 Kacangan Pantai ke arah darat
13 Nypa fruticans Pantai ke arah darat
Sumber: BPLH Kota Tarakan (2014)
9
Jenis mangrove yang ditemukan di sepanjang kawasan pantai
wilayah Kecamatan Tarakan Barat lebih beragam, yaitu ditemukan 17
jenis mangrove yang berasosiasi (Tabel 2.3). Jumlah jenis mangrove di
kawasan pantai Kecamatan Tarakan Barat lebih banyak dibandingkan
dengan di kawasan pantai kecamatan lainnya di Kota Tarakan. Faktor yang
berpengaruh terhadap mangrove di lokasi ini adalah kondisi lingkungan
dimana letak geografis kawasan relative lebih terlindung dari arus dan
gelombang laut yang kuat. Kondisi ini menyebabkan proses pengendapan
lumpur sering terjadi sehingga membentuk substrat mangrove berlumpur.
Substrat dominan lumpur merupakan wadah yang sesuai dan mudah bagi
mangrove untuk berkembang dan tumbuh.
Tabel 2.3 Jenis mangrove di daerah pantai wilayah Kecamatan Tarakan Barat.
No Jenis Sebaran
1 Sonneratia alba Pantai ke arah laut
2 Avicennia alba Pantai ke arah laut
3 Avicennia marina Pantai ke arah darat
4 Rhizophora apiculata Pantai ke arah darat
5 Rhizophora mucronata Pantai ke arah darat
6 Bruguiera gymnorhiza Pantai ke arah darat
7 Bruguiera plavifora Pantai ke arah darat
8 Bruguiera sexangula Pantai ke arah darat
9 Ceriops tagal Pantai ke arah darat
10 Shcyphiphora sp Pantai ke arah darat
11 Lumnitzhera racemosa Pantai ke arah darat
12 Xylocarpus granatum Pantai ke arah darat
13 Xylocarpus sp Pantai ke arah darat
14 terompet Pantai ke arah darat
15 Buta-buta Pantai ke arah darat
16 Kacangan Pantai ke arah darat
17 Nypa fruticans Pantai ke arah darat
Sumber: BPLH Kota Tarakan (2014)
Ekosistem hutan mangrove di Pulau Sadau terkonsentrasi di dua
tempat pada bagian Pulau Sadau. Ekosistem mangrove terkonsentrasi di
bagian sebelah utara ke arah timur Pulau Sadau dan dari timur ke arah
Selatan Pulau Sadau, Sedangkan dari arah utara menuju arah barat
dan sampai ke utara sangat sedikit dan sebagian besar tidak dijumpai
10
ekosistem mangrove. Dari hasil observasi dan proses identifikasi vegetasi
mangrove di Pulau Sadau ditemukan 7 famili mangrove dengan 11 jenis
(Tabel 2.4). Pada bagian utara Pulau Sadau, mangrove yang menghadap
ke arah laut lebih banyak dijumpai jenis Sonneratia alba. Sedangkan pada
bagian belakang pantai ditemukan lebih bervariasi.
Tabel 2.4. Jenis mangrove yang terdapat di Pulau Sadau
No Famili Species Nama Lokal
1 Rhizophoraceae Rhizophora apiculata Bakau
Bakau merah
Rhizophora mucronata Tomo
Tengar
Bruguiera gymnorhiza Api-api putih
Api-api
2 Avicenniaceae Ceriops tagal Prepat
Avicennia marina Inggili
Teruntum
Avicennia alba Cingam
Nipa
3 Sonnneratiaceae Sonneratia alba
4 Meliaceae Xylocarpus granatum
5 Combretaceae Lumnitzera littorea
6 Rubiaceae Scyphiphora hydrophyllacea
7 Arecaceae Nypa fruticans
Sumber: BPLH Kota Tarakan (2014)
B. EKOSISTEM MANGROVE DI KAWASAN KONSERVASI MANGROVE
BEKANTAN (KKMB)
Kota Tarakan adalah kota yang dikelilingi oleh laut, sehingga kota Tarakan
memiliki daerah pesisir yang di tumbuhi oleh tanaman mangrove. Daerah
ini ada yang dijadikan sebagai daerah konservasi, seperti yang ada di Kota
Tarakan yaitu Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan (KKMB). Kawasan
ini ditetapkan oleh pemerintah kota pada tahun 2001. Kawasan ini berapa
pada pada koordinat 3o18’10”–3o18’22” LU dan 117o34’30”–117o34’43” BT,
dengan luas kawasan adalah ± 9 ha. KKMB merupakan tempat ini ekowisata
yang terletak di tengah-tengah Kota Tarakan. Hingga tahun 2006, luas KKMB
berubah menjadi 22 ha. Kawasan ini berdampingan dengan pemukiman
penduduk. Penetapan kawasan KKMB ini memiliki tujuan untuk melindungi
ekosistem mangrove dari kerusakan, sehingga pemerintah pun melakukan
berbagai upaya untuk menjaga kawasan mangrove agar tetap lestari.
Pada tahun 2007, KKMB direhabilitasi dengan melakukan penanaman
tumbuhan mangrove kembali oleh beberapa perusahaan, guna untuk
melestarikan ekosistem mangrove serta satwa liar yang hidup didalamnya,
11
dan dapat mejadi daerah tujuan ekowisata alternatif (Dinas Lingkungan
Hidup dan SDA Kota Tarakan, 2007; Yusuf, 2008).
Terdapat beberapa jenis mangrove yang ditemukan di KKMB ini,
diantaranya Rhizophora sp, Avicennia sp, Sonneratia alba dan Nypa Fruticans.
1. Rhizophora apiculata
Klasifikasi dari Rhizophora apiculata Blume adalah sebagai berikut:
Kerajaan : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Bangsa : Myrtales
Suku : Rhizophoraceae
Marga : Rhizophora
Jenis : Rhizophora apiculata
Gambar 2.1 Rhizophora apiculata (Wetlands, 2021)
12
Mangrove jenis ini merupakan mangrove yang tumbuh di substrat
berlumpur. Mangrove ini memiliki nama yang berbeda-beda disetiap daerahnya,
yaitu bakau minyak, bakau tandok, bakau akik, atau bakau jangkar (Pratiwi,
2005). Rhizophora apiculata adalah mangrove dengan ciri-ciri pohon tinggi
hingga 30m. pohon ini memiliki diameter batang >50cm, dengan perakaran
tunjang yang panjangnya 5m dari permukaan tanah. (Noor et al., 1999).
Ciri khas dari mangrove jenis Rhizphora apiculata adalah memiliki
daun muda yang terlindung oleh selaput bumbung (ocrea) berwarna merah.
Rhizophora apiculata memiliki bunga tumbuh dari ketiak daun. Buah jenis
mangrove ini berbentuk bulat serta memanjang dan berwarna coklat.
Permukaan buah kasar dan buah dapat memilli panjang sekitar 2–5cm.
Rhizophora apiculata biasanya memiliki tingkat dominasi yang tinggi saat
berada di suatu vegetasi (Noor dkk., 1999; Kusmana dkk., 2003).
2. Rhizophora mucronata
Klasifikasi tumbuhan bakau (Rhizophora mucronata) adalah sebagai
berikut (Duke, 2006):
Kingdom : Plantae
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Mytales
Famili : Rhizophoraceae
Genus : Rizhophora
Spesies : Rizhophora mucronata
Jenis ini biasanya disebut dengan bakau oleh masyarajat sekitar.
Jenis mangrove ini banyak ditemukan di sekitar pesisir pantai, dengan
pasang surut air laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 35–40 meter.
Batang yang dimiliki oleh tanaman ini berbentuk silinder, berwarna coklat
hingga keabu-abuan, dan bagian luar kulit terlihat retak. Jenis akar yang
dimiliki adalah akar tunjang, yang digunakan sebagai alat pernapasan
karena memiliki lentisel dipermukaannya.
Akar tanaman ini menggantung dari batang dan cabang yang rendah,
dan dilapisi oleh lilin yang dapat dilewati oleh oksigen dan tidak tembus
air. Daunnya memiliki bentuk lonjong dan mengkilap, dan memiliki ukuran
panjang 17–35 mm. pohon ini memiliki bunga yang berwarna kuning
dengan kelopak kecoklatan hingga kemerahan. Pada bulan April hingga
Oktober, penyerbukan yang dibantu oleh serangga pun terjadi untuk
menyerbuki pohon jenis ini, sehingga menghasilkan buah berwarna hijau
dengan panjang 36–70 cm (Kusmana dkk, 2003).
13
Gambar 2.2 Rizhophora mucronata (Wetlands, 2021)
3. Sonneratia alba
Klasifikasi tanaman mangrove Sonneratia alba adalah sebagai berikut
(Safnowandi, 2015):
Kingdom : Plantae
Kelas : Mangnoliophyta
Ordo : Myrtales
Family : Sonneratiaceae
Genus : Sonneratia
Spesies : Sonneratia alba
14
Gambar 2.3 Sonneratia alba (Wetlands, 2021)
Pohon jenis ini memiliki tinggi sekitar 15 meter dengan kayu berwarna
putih tua hingga berwarna coklat. Akar yang dimiliki berjenis akar nafas,
dengan tinggi 225 cm berbentuk lancip, dengan warna coklat muda hingga
coklat tua. Pohon jenis ini biasanya banyak tumbuh di sekitar pesisir
pantai. Daunnya memiliki bentuk yang bulat telur, dengan panjang 6–15
mm, dan dikelilingi oleh mahkota berwarna putih dan mudah sekali rontok.
Bunganya memiliki 6–8 kelopaj, dengan warna pada bagian luarnya
adalah hijau dan bagian dalamnya agak kemerahan. Buah yang dimiliki
oleh pohon ini adalah berbentuk bola, dan pada bagian dasarnya terdapat
kelopak bunga. Buah ini tidak akan terbuka saat buah masuk kedalam fase
matang. Buahnya biasanya berukuran 3,5–4,5 cm berwarna hijau, dengan
kelopak berbantuk seperti cawan. Didalam buah ini, terdapat sekitar 200
biji (Safnowandi, 2015).
15
4. Nypa fruticans
Klasifikasi tanaman Nypa fruticans adalah sebagai berikut:
Kingdom : Plantae
Kelas : Liliopsida
Ordo : Arecales
Famili : Arecaceae
Genus : Nypa
Species : Nypa fruticans
Gambar 2.4 Nypa fruticans (Wetlands, 2021)
16
Nipah termasuk kedalam tumbuhan palpa yang tidak memiliki batang
pada daerah permukaan, dan membentuk rumpun dengan batang yang
berada di bawah tanah. Daun nya hampir menyerupai daun kelapa,
dengan warna hijau mengkilat di bagian permukaan dan terdapat serbuk
di bagian permukaan bawah daunnya. Bentuk yang dimiliki oleh daun
adalah lanser, dengan bagian ujung meruncing. Biasanya nipah tumbuh
pada daerah substrat berlumpur, dan biasanya tumbuh dekat dengan
jalan. Sistem perakaran yang dimiliki adalah akar rapat serta kuat yang
telah disesuaikan dengan jumlah air yang masuk. Hal ini menjadikan nipah
memiliki perakaran yang baik dibandingkan tumbuhan mangrove yang
lainnya (Admin, 2009).
Nipah menjadi sumber pakan dan energy, tetapi penelitian mengenai
potensi ini masih belum banyak di publikasikan. Di daerah Batu Ampar,
Pontianak, nipah dimanfaatkan sebagai penghasil gula serta garam. Gula
nipah diperoleh dengan mengelola nira atau cairan manis yang keluar
dari tandan bunga yang belum mekar, dan garam nipah didapatkan dari
pelepah yang telah tua (Santoso dkk, 2005).
17
BAB III
KEANEKARAGAMAN BIVALVIA DI
KALIMANTAN UTARA
Bivalvia atau kerang adalah hewan invertebrate dari kelompok
moluska, yang memiliki 2 cangkang keras untuk melindungi tubuhnya.
Kerang hidup di perarian pantai dengan susbtrat pasri berlumpur,
pada kedalaman ± 4–6 meter, dengan perairan yang tenang. Selain di
pantai, kerang juga dapat di temukan di muara, ekosistem manggrove,
dan padang lamun. Umumnya kerang hidup berkelompok dan mereka
membenamkan diri di dalam pasir berlumpur. Kerang memiliki manfaat,
mulai dari dagingnya yang enak untuk dikonsumsi dan menjadi sumber
protein dan sumber mineral, cangkangnya digunakan sebagai perhiasan
atau bahan kerajinan tangan, ada kerang yang menghasilkan mutirara,
dan pemanfaatan kerang sebagai biofilter polutan. Manfaat lain yang
dapat dirasakan adalah kerang adalah sumber minera yaitu antioksidan
Kerang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena memiliki rasa
daging yang enak dan memiliki kandungan protein dan mineral yang
tinggi. Karena itu kerang banyak diminati oleh masyarakat umum. Sulistijo
dkk (1980) dalam Supratman dkk (2019) menyebutkan bahwa dari 20
jenis moluska yang ada, kerang merupakan salah satu jenis moluska yang
memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena itu sering terjadi eksploitasi secara
berlebihan, yang berdampak pada kelimpahan dan keanekaragamannya.
Kelimpahan kerang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya
ketersediaan makanan, kondisi lingkungan, predator, dan perubahan
lingkungan perairan yang disebabkan oleh manusia (Susiana, 2011; Budi
dkk, 2013).
Kerang memiliki alat gerak berupa kaki diantara valves yang akan
melebar dan mengait dasar material dengan suatu mekanisme tarik ulur
dan adanya kontraksi otot (Nyabakken dkk, 1992). Beberapa jenis kerang
mampu menempelkan diri ke substrat keras dengan byssus, seperti serat
yang keluar dari dalam tubuhnya (Kastro dan Sudjoko, 1988). Kerang
tidak memiliki kepala serta mata didalam tubuhnya, dan kerang hanya
terdiri dari tiga bagian utama yaitu kaki, mantel serta organ dalam. Kaki
yang dimilikinya dapat di keluarkan melalui dua cangkang tertutup, yang
19
berfungsi sebagai alat geraknya (Robet dkk (1982) dalam Syafikri, 2008).
Umumnya kerang merupakan filter feeder, yang menyaring makanan
menggunakan insang. Makanan utama dari kerang adalah plankton,
terutama fitoplankton (Suwignyo, 2005).
Gambar 3.1 Fitur Utama dari Bivalvia (FAO, 1998)
Gambar 3.2. Anatomi Umum Bivalvia (FAO, 1998)
A. KEANEKARAGAMAN JENIS KERANG DI KALIMANTAN UTARA
Keanekaragaman suatu biota pada perairan sangat dipengaruhi oleh
banyaknya spesies pada suatu komunitas. Jika jumlah jenis yang ditemukan
banyak, besar pula keanekaragaman yang dimiliki, walaupun setiap jenis
20
memilki nilainya masing-masing (Wihm & Doris, 1986). Kerbs, 1997 dalam
Melati, 2007 juga menyatakan bahwa semakin banyak anggota individu dan
tersebar merata, maka keanekaragaman juga menjadi lebih besar.
Di Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan terdapat beberapa
jenis bivalvia yang ditemukan. Berikut adalah jenis-jenis kerang yang
ditemukan, disajikan dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Jenis-Jenis Bivalvia yang ditemukan di Kalimantan Utara
No. Nama Lokal Nama Ilmiah
1. Kerang Kapah Meretrix meretrix
2. Kerang Kapah Gelonia coaxans
3. Kerang Kapah Meretrix lyrata
4. Kerang Pahut-Pahut Pharella acutidens
5. Kerang darah/Tudai Anadara granosa
6 Kerang darah/Tudai Anadara inaequivalvis
Sumber: Salim dkk, 2021
a. Kerang Kapah (Meretrix meretrix)
Kerang kapah atau Meretrix meretrix adalah kerang kelas Bivalvia atau
Pelecypoda, yang memiliki kaki tunggal dengan bentuk yang mirip dengan
kapak, dan keluar dari kedua cangkang yang dimilikinya. Kerang kapah
menjadi salah satu produk yang berada di Kota Tarakan. Kerang kapah
menjadi salah satu produk yang digemari di Kota Tarakan karena memiliki
citarasa yang enak, sehingga nilai dari kerang kapah pun tinggi. Diketahui
setelah mewawancari warga sekitar yang menjual kerang kapah, harga yang
ditaksir untuk satu kilogram kerang kapah adalah Rp45.000 (Harga tahun
2015). Kerang jenis ini hidup pada habitat pantai berpasir, dengan cangkang
yang memiliki corak berwarna coklat keemasan, dengan garis sebagai motif
pada cangkangnya. Cangkang yang dimiliki oleh kerang kapah ini halus dan
lembut, sehingga cangkakngnya sering di manfaatkan sebagai hiasan atau
bahan kerajinan tangan.
Kerang kapah memiliki klassifikasi sebagai berikut (FAO 2011):
Kingdom : Animalia
Filum : Mollusca
Kelas : Bivalvia
Ordo : Veneroida
Family : Venereidae
Genus : Meretrix
Spesies : Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758).
21
Gambar 3.3 Kerang Kapah (Meretrix meretrix) (Achyani dan Salim, 2011)
Kerang kapah memiliki penyebaran Indo-Pasifik barat dari Afrika Timut
hingga ke Filipina, dari utara hingga ke selatan Jepang, dan terebar di Indonesia
(FAO, 2011). Untuk jenis kapah yang berada di Kota Tarakan, kerang kapah
tersebar di bagian selatan pada pesisir Pulau Tarakan (FAO, 2011 dalam Salim
dan Firdaus, 2012). Sebaran populasi dapat terjadi karena seleksi dari habitat,
predasi atau komperisi yang dilakukan antar spesies lain, dan juga karena
faktor lingkungan baik secara fisik maupun kimia (Krebs, 1985).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pantai Amal
Lama di Kota Tarakan, kerang kapah memiliki kandungan protein sebesar
15,22% dan kandungan lemak sebesar 0,79%. Nilai ini didapatkan dengan
melakukan uji potein dan uji lemak dengan daging seberat 100 gram.
Sehingga dalam 100 gram kerang kapah, kandungan protein yang dimiliki
sebesar 15,22 gram, dan kandungan lemak sebesar 0,79 gram (Salim
dan Firdaus, 2012). Kerang kapah memiliki tiga jenis pertumbuhan yaitu
pertumbuhan antara panjang cangkang dan berat daging; pertumbuhan
antara tinggi cangkang dengan berat daging; dan pertumbuhan tebal
cangkang dengan berat daging (Firman dan Salim, 2016). Kerang kapah
yang ditemukan di Kota Tarakan memiliki panjang maksimal sebesar
9–12 cm, dengan rata-rata pertumbuhan adalah 0,051 cm setiap 3 bulan
(Wiharyanto dkk, 2013).
b. Kerang kapah (Geloina coaxans)
Kerang kapah jenis Geloina coaxans merupakan salah satu jenis dari
kerang kapah lain yang ditemukan di Kota Tarakan. Kerang ini ditemukan
di KKMB atau di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Kota
22
Tarakan. Jenis ini berbeda dari jenis kapah Meretrix yang di temukan
di Pantai Kota Tarakan. Jenis kerang kapah Geloina coaxans memiliki
warna coklat keemasan yang mencolok dan memiliki motif garis-garis
pada cangkangnya. Warna yang dimiliki oleh kapah ini berbeda dengan
jenis kapah yang ditemukan di Pantai, dimana warna kerang kapah yang
ditemukan di pantai lebih putih. Warna cangkang gelap yang dimiliki
oleh jenis kerang kapah Geloina coaxans ini disebabkan karena habitat
tempat ia tinggal, yang merupakan substrat lumpur, dan cangkangnya
memiliki tekstur yang agak kasar, tidak seperti jenis Meretrix yang halus
(Wiharyanto dkk, 2012).
Klasfikasi kerang kapah (Geloina coaxans) menurut FAO (2011) dalam
Wiharyanto dkk (2012) adalah sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Filum : Mollusca
Kelas : Bivalvia
Ordo : Veneroida
Family : Corbiculoidae
Genus : Geloina
Spesies : Geloina coaxans (Gmelin, 1791)
Gambar 3.4 Kerang Kapah (Geloina coaxans) (Salim, 2012)
Menurut FAO (2011) dalam Wiharyanto dkk (2012), kerang kapah
Geloina coaxans tersebar di Indo-Pasifi Barat, dari India hingga Vanuatu;
Dari utara hingga selata pulau Jepang; bagian selatan Queensland hingga
ke New Caledonia. Di Kota Tarakan, kerang ini tersebar di pesisir bagian
barat kota Tarakan.
23
Gambar 3.5 Penyebaran Kerang Kapah (Geloina coaxcans)
(FAO, 2011 dalam Wiharyanto dkk, 2012)
Kerang ini memiliki ukuran paling panjnag adalah 8,842 cm, dan
ukuran terkecil adalah 3.06 cm. Tetapi pada umumnya kerang memiliki
ukuran tubuh 4–6 cm dan untuk ukuran besar berkisaran 10 cm. kerang
ini hidup pada daerah pasang surut, hingga perairan sublitoral dengan
kedalaman 20 meter (FAO, 2011 dalam Wiharyanto dkk, 2012). Kerang
kapah Geloina coaxcans dapat hidup dengan faktor pendukung seperti
kandungan DO, suhu, TDS, pH air dan salinitas. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, kerang ini dapat dihidup dengan kandungan DO
sebesar 1.40–5.21 ppm, suhu sebesar 27–29oC, TDS sebesar 10.38–
79.15 ppt. pH air sebesar 6.34–7.35, dan salinitas sebesar 4–30 ppt
(Wiharyanto dkk, 2012).
c. Kerang Kapah (Meretrix lyrata)
Klasifikasi kerang kapan Meretrix lyrata (G. B. Sowerby II, 1851) adalah
sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Bivalvia
Ordo : Venerida
Family : Veneridae
Subfamily : Meretricinae
Genus : Meretrix
Spesies : Meretrix lyrata
24
Gambar 3.6 Kerang Kapah (Meretrix lyrata)
(Salim dan Firdaus, 2012)
Kerang kapah jenis Meretrix lyrata juga merupakan salah satu produk
yang berpotensi, tetapi belum dikelola atau dikembangkan dengan baik,
baik dari kualitan maupun kuantitasnya. Untuk secara kuantitas, kapah
jenis ini telah mengalami penurunan jumlah, ukuran dan bentuk. Hasil
kapah yang ditemukan oleh para masyarakat yang berada di pesisir kota
Tarakan hanya dikonsumsi sendiri, dan beberapa dijual ke luar daerah
karena nilai jual yang tinggi (Suhelm dkk, 2012). Kerang kapah ini memiliki
habitat dengan substrat pasir dan lumpur. Kerang ini hidup di kedalaman
20 cm. Selain ditemukan di Indonesia, kapah ini juga di temukan dan di
konsumsi di Vietnam, Thailand, dan Filipina. Penyebaran kerang ini adalah
pasifik barat tropis, dari Indonesia bagian barat hingga Filipinna, Laut cina
utara hingga timur, Taiwan hingga ke bagian selatan Indonesia (FAO,
1998).
Gambar 3.7 Penyebaran Kerang Kapah jenis Meretrix lyrata (FAO, 1998)
25
Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Kerang kapah Meretrix
lyrata di Kota Tarakan, kerang kapah yang ditemukan di beberapa daerah
pesisir Kota Tarakan seperti daerah Pantai Amal Lama, daerah Binalatung,
dan daerah Pantai Amal Baru memiliki ukuran yang berbeda-beda, yang
termasuk kedalam kategori kurus, sedang, dan gemuk (Suhelmi dkk,
2012).
d. Kerang Pahut-Pahut (Pharella acutidens)
Berikut adalah klasifikasi dari Kerang Pahut-Pahut (Broderip & Sowerby,
1829):
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Bivalvia
Ordo : Adapedonta
Family : Pharidae
Subfamily : Pharellinae
Genus : Pharella
Spesies : Pharella acutidens
Gambar 3.8 Kerang Pahut-Pahut (Phaarella acutidens) (FAO,1998)
Kerang pahut-pahut merupakan jenis kerang yang berasal dari
p=filum molusca. Bentuk kerang ini sangat tipis dan memanjang, dengan
bagian anterior serta posterior yang memiliki bagian pinggir membulat.
Warna dari kerang ini biasanya putih, coklat atau hijau periostracum pada
cangkannya. Untuk bagian dalamnya berwarna cream muda hingga putih
agak kebiruan. Biasanya kerang ini memiliki panjang maksimum 8 cm,
tetapi juga ada yang ditemukan dengan ukuran berbeda yaitu 6 cm. kerang
ini biasanya ditemukan pada habitat ekosistem mangrove, dengan substrat
pasir dan lumput seperti yang biasanya berada di kawasan mangrove.
Kerang pahut-pahut jenis ini biasanya hidup berkumpul dengan jenis yang
26
lain, biasanya adalah jenis pharella javanica (Carpenter dan Niem, 1998
dalam Syam dkk, 2013). Kerang dapat hidup hingga kedalam 10 m, dan
penyebarannya adalah pasifik barat tropis, laut cina selatan, Indonesia dan
Filipina (FAO, 1998). Kerang ini memiliki kandungan protein cukup tinggi,
sebesar 13,08%. Kerang ini memiliki kekurangan yaitu cangkang yang
memiliki pertahanan atau perlindungan yang rendah (Syam dkk, 2013).
Diperkirakan pada tahun 1980, kerang ini ditemukan cukup melimpah
di Kota Tarakan, karena habitatnya belum terpengarh oleh kegiatan
pembangunan. Tetapi pada tahun 1990, populasi kerang ini mulai menurun
karena eksploitas secara besar tanpa adanya rencana pengelolaan yang
berkelanjutan, dan karena adanya penyempitan habitiat, yaitu perubahan
kawasan mangrove menjadi tambak. karena itu, kerang ini sudah jarang
ditemukan, dan hanya tempat tertentu yang masih terdapat kerang
ini seperti di kawasan KKMB Kota Tarakan, tetapi ukuran yang ditemui
terkategori kecil. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syam dkk
(2013), kerang ini memiliki habitat dengan kualitas perairan yaitu salinitas
sebesar 26,955 ± 0,285 ppt; kandungan oksigen sebesar 4,49 ± 0,21 ppm;
pH sebesar 7,51 ± 0,29; suhu sebesar 27,84 ± 0,72 oC; TDS sebesar 21,09
± 0,27 ppm (Syam dkk, 2013).
e. Kerang Darah (Anadara granosa)
Gambar 3.9 Kerang Darah (Anadara granosa) (Ginting Dkk, 2017)
27
Kerang darah termasuk kedalam golongan hewan lunak yang hidup
di habitat perairan dengan substrat berlumpur. Taksonomi dari kerang
darah adalah sebagai berikut (Ginting dkk, 2017):
Kingdom : Animalia
Phylum : Moluska
Kelas : Bivalva
Ordo : Arcoida
Famili : Arcidae
Subfamili : Anadarinae
Genus : Anadara
Spesies : Anadara granosa
Kerang darah dengan nama latin Anadara granosa adalah salah satu
jenis kerang yang memiliki potensi dan bernilai ekonomi tinggi, dan bermanfaat
sebagai sumber protein dan mineral yang dibutuhkan oleh masyarakat pada
umumnya. Kerang darah ini juga dimintai oleh masyarakat Kota Tarakan, dan
daerah lain yang berada di Kalimantan Utara. Kerang darah biasanya hidup
pada daerah dengan substrat lumpur, dan hidup dengan cara infauna atau
membenamkan diri pada lumpur. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kerang ini
adalah memiliki dua cangkang yang tebal, berbentuk elips, dengan ukuran
cangkang yang sama besarnya dan permukaan yang kasar. Cangkangnya
memiliki warna putih yang tertutup oleh periokstrakum berwarna kuning
kecoklatan dan ada pula yang berwarna coklat kehitaman. Ukuran kerang
dewasa biasanya mencapai 6 hingga 9 cm (Latifah, 2011).
Kerang darah biasanya dijumpai didaerah yang jauh dari muara
sungai. Ini dikarenakan biasanya muara sungai menjadi daerah yang sering
terkena dampak dari pencemaran, serta daerah yang paling banyak kegiatan
penangkapan secara berlebihan (Dahuri dkk, 1996). Kerang darah adalah
organisme bentos yang hidup di wilayah pasang surut, dengan rata-rata pasang
surut tinggi dan daerah pertengahan pasang tinggi dan surut (Intan dkk, 2012).
f. Anadara inaequivalvis
Klasifikasi dari kerang Anadara inaequivalvis adalah sebagai berikut
(Gingting dkk, 2017):
Kingdom : Animalia
Phylum : Moluska
Kelas : Bivalvia
Ordo : Arcoida
Famili : Arcidae
Genus : Anadara
Spesies : Anadara inaequivalvis
28
Gambar 3.10 Anadara inaequivalvis (Ginting dkk, 2017)
Kerang jenis ini memiliki ukuran cangkang dari yang sedang hingga
besar dengan umbo. Cangkang yang dimiliki tidak terlalu tipis, tetapi tidak
juga terlalu tebal. Hanya bagian ventar yang lebih tebal ukurannya. Warna
kerang ini adalah kecoklatan yang ditutupi dengan bulu kecil berwarna
coklat kehitaman, dan memiliki warna putih didalamnya. Kerang ini memiliki
ukuran antara 40–75 mm, hingga 90 mm. Dharma (2011) menyebutkan
bahwa kerang ini memiliki ukuran yang tidak simetris. Pada bagian
posteriornnya sedikit miring atau melengkung keluar, dan agak metuncing
pada bagian ujung bawahnya. Jenis kerang ini memiliki sifat cosmopolitan,
yaitu tersebar pada perairan tropis maupun subtropis, dan hidup pada
substrat lumpur berpasir dengan membenamkan dirinnya (Riniatsih dan
Widianingsih, 2007).
29
BAB IV
KEANEKARAGAMAN GASTROPODA DI
KALIMANTAN UTARA
A. GASTROPODA
Gastropoda adalah salah satu kelas terbesar dari Molusca, karena
terdapat 75.000 spesies yang telah diidentifikasi. Dari jumlah ini, 15.000
diantaranya adalah fosil. Gastropoda menjadi kelas yang paling sukses,
karena ditemukan di berbagai habitat diantara kelas yang lainnya (Barnes,
1987). Morofolgi gastopoda dapat dilihat dari cangkang yang dimilikinya.
Cangkang gastropoda terbagi menjadi dua jenis, yaitu dekstral dimana
cangkang berputar searah jarum jam, dan jenis kedua adalah sinistral
dimana cangkang berputar berlawanan arah jarum jam. Di laut, gastopoda
yang ditemukan biasanya memiliki cangkang dekstral dibandingkan dengan
bentuk sinistral (Dharma, 1988). Cangkang dapat tumbuh denganmelilin
spiral disebabkan oleh pengendapan bahan cangkang yang berada di luar
lebih cepat dibandingkan cangkang bagian dalam (Nontji, 1987).
Beberapa gastropoda bernilai ekonomis karena dapat digunakan
sebagai perhiasan mahal. Contoh gastopoda yang dijadikan perhiasan
adalah jenis Murex dan Trochus. Selain itu, beberapa gastropoda juga
dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperi dari jenis Cymbiola yang
dagingnya dikonsumi, dan dari segi ekologi terdapat gastopoda yang
berperan sebagai konsumen yaitu Cellana radiata (Dharma, 2005).
Gastropoda mampu beradaptasi baik dengan mangrove. Karena itu
keberadaannya menjadi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan
suatu ekosistem. Jika terjadi penurunan jumlah gastropoda di lingkungan,
maka akan berdampak pada proses dekomposisi, sehingga berkurangnya
sedimentasi yang didapatkan dari hasil konsumsi yang dilakukan oleh
gastropoda. Gastopoda dapat menjadi suatu bioindikator jika terjadi
sebuah kerusakan ekosistem mangrove. Jika jumlah gastropoda melimpah
dan keanekaragmannya tinggi, maka ekosistem mangrove bisa dikatakan
memiliki kondisi yang baik (Rosario dkk, 2019).
31
Gambar 4.1 Morfologi Umun Gastopoda (FAO, 1998)
B. JENIS- JENIS GASTROPODA DI KALIMANTAN UTARA
Kalimantan Utara memiliki berbagai macam ekosistem, salah satunya
adalah ekosistem mangrove, yang tersebar di pesisir pulau atau sungai.
Ekosistem mangrove menjadi kawasan yang memiliki keanekaragaman
hayati, termasuk keanekaragam gastropoda. Gastopoda sendiri
merupakan sumber daya hayati yang memiliki keanekaragaman yang
tinggi, dan menempati mangrove sebagai habitatnya (Irawan, 2008).
Di Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan terdapat beberapa
jenis gastopoda yang ditemukan. Berikut adalah jenis-jenis gastopoda
yang ditemukan, disajikan dalam tabel 4.1.
32
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Gastopoda yang ditemukan di Kalimantan Utara
No. Nama Lokal Nama Ilmiah
1. Temberungun Telescopium telescopium
2. - Cassidula aurisfelis
3. - Littoraria scabra
4. - Nerita articulata
5. Keong Matah Merah Cerithidea obtusa
6. - Chicoreus capucinus
7. - Cerithidea cingulata
Sumber: Salim dkk, 2021
a. Temberungun (Telescopium telescopium)
Beikut adalah klasifikasi dari temberungun atau Telescopium Telescopium
(Linnaeus, 1758) (Eisenberg, 1981):
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Caenogastropoda
Family : Potamididae
Genus : Telescopium
Spesies : Telescopium telescopium
Temberungun adalah salah satu biota yang memiliki peran peting
pada proses dekomposisi serah serta proses mineralisasi bahan organik
yang bersifat detritivor dan herbivor guna memperbaiki kualitas perairan.
Hamsiah (2000) menyebutkan bahwa keong bakau memiliki kemampuan
menjadi biofilter untuk menurunkan kadar tersuspensi, menurunkan
populasi bakteri, dan menurunkan suspensi dari air limbah atau buangan
budidaya udang dan pencemaran air. Apabila populasi temberungun
menurun, maka telah terjadi kerusakan lingkungan hutan mangrove.
Penyebab kerusakan hutan mangrove bisa disebabkan oleh berbagai hal,
seperti berkurangnya kerapan hutan mangrove, pencemaran lingkungan,
atau terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap temberungun. Karena
itu, temberungun menjadi salah satu bioindikator kerusakan lingkungan.
Radjasa dkk (2011) menyebutkan bahwa temberungun hidup pada habitat
air payau dengan substrat lumpur, dan masih dipengaruhi oleh pasang
surut air laut.
33
Gambar 4.2 Temberungun (Telescopium telescopium) (Salim dkk, 2017)
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salim dkk (2017),
temberungun memiliki kelimpahan yang lebih rendah di KKMB,
Kota Tarakan. Hal ini disebabkan oleh kerapatan mangrove yang
tinggi. Budiman (1991) dalam Salim dkk (2017) menyebutkan bahwa
temberungun menyukai tempat tinggal dengan lahan mangrove yang
terbuka yang disebabkan karena pohon tumbang. Hal ini menyebabkan
munculnya genangan air yang luas dan lebih banyak cahaya matahari
yang masuk kedalam daerah mangrove. Selain itu, Rahmawati (2011) juga
mengatakan bahwa kelimpahan temberungun dilahan luas lebih banyak,
karena temberungun tidak memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi
terhadap predator.
b. Cassidula aurisfelis
Klasifikasi Cassidula aurisfelis adalah sebagai berikut (Eisenberg, 1981):
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Pulmonata
Family : Ellobiidae
Genus : Cassidula
Spesies : Cassidula aurisfelis
34
Gambar 4.3 Cassidula aurisfelis (Wahyuni dkk, 2016)
Jenis keong ini memiliki ciri morfologi yaitu cangkang yang tebal,
dengan bentuk oval. Cangkangnya termasuk jenis cangkang dekstral.
Bentuk apex yang dimiliki tumpul, dan memiliki permukaan cangkang yang
halus berwarna coklat. Panjang cangkang yang dimiliki berkisar 2,7–3 cm,
dengan lebar cangkang 1,5–2 cm. kerang ini juga memiliki permukaan
cangkang yang halus. Kerang ini dapat ditemukan di bagian bawah pohon
mangrove, di dekat batang dan akar pohonnya (Nurrudin dkk, 2015), dan
memiliki habitat di hutan bakau dan didaerah tepi pantai di daerah atas
pasang surut.
c. Littoraria scabra
Klasifikasi Littoraria scabra adalah sebagai berikut (Eisenberg, 1981):
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Littorinimorpha
Family : Littorinidae
Genus : Littoraria
Spesies : Littoraria scabra
35
Gambar 4.4 Littoraria scabra (Wahyuni dkk, 2016)
Littoraria scabra memiliki cangkang dengan jenis dekstral, dan
memiliki permukaan yang tipis dan halus, dengan apex runcing. Jenis
ini memiliki warna cangkang yaitu kuning kecoklatan dengan garis-garis
berwarna coklat gelap. Panjang cangkangnya adalah 1,5–2,5 cm dan lebar
cangkangnya adalah 1,1–1,6 cm. kerang ini dapat ditemukan menempel
di batang, daun, maupun akar pohon mangrove (Nurrudin dkk, 2015).
Habitat hewan ini dapat ditemukan melimpah di hutan nipah, rawa-rawa
atau di daerah tepi arah laut dekat hutan mangrove.
d. Nerita articulata
Klasifikasi Nerita articulata adalah sebagai berikut (Eisenberg, 1981):
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Cycloneritida
Family : Neritidae
Genus : Nerita
Spesies : Nerita articulata
36
Gambar 4.5 Nerita articulata (Wahyuni dkk, 2016)
Keong ini memiliki cangkang kecil, garis pada cangkangnya atau
spire berjumlah banyak. Arah putaran cangkangnya berjenis dekstral.
Cangkangnya memiliki warna coklat kehitaman, dengan bentuk oval.
Keong ini memiliki panjang cangkang 3,88–1,51 cm dengan lebar
cangkang 2,97–1,31 cm. Hewan ini bisa ditemukan di batang atau bagian
akar pohon mangrove (Wahyuni dkk, 2016). Untuk habitatnya hewan ini
hidup di daerah dengan substrat berlumpur atau daerah berbatu, dan
hidup di sekiar tepi laut ekosistem mangrove (Tan dan Clements, 2008).
e. Cerithidea obtusa
Keong matah merah adalah salah satu spesies filum moluska, yang
mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral dengan cangkang berbentuk
kerucut serta melingkar. Klasifikasi keong matah merah (Cerithidea
obtusa) adalah sebagai berikut (Abbot dan Boss, 1989):
Kindom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Caenogastropoda
Famili : Potamididae
Genus : Cerithidea
Spesies : Cerithidea obtuse
37
Gambar 4.6 Cerithidea obtuse (Wahyuni dkk, 2016)
Keong ini memiliki cangkang berwarna coklat, berbentuk kerucut
dan tebal. Apex yang dimiliki tumpul dan memiliki jenis cangkang dekstral.
Ukuran panjang cangkang bisa mencapai 3–4,4 cm dengan lebar 2–2,3 cm
(Nurrudin dkk, 2015). Keong matah merah hidup pada akar, batang, dan
ranting mangrove. Pada umumnya, keong mangrove ini banyak dijumpai
di kawasan Asia Tenggara (Coremap, 2010 dalam Akbar, 2018). Keong
mata merah memiliki kandungan gizi yaitu air 80,30%, abu 4,50%, lemak
2,80% dan protein sebesar 11,80% (Purwaningsih, 2008).
f. Cerithidea cingulate
Klasifikasi Cerithidea cingulata adalah sebagai berikut (Eisenberg, 1981):
Kingdom: Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Caenogastropoda
Family : Potamididae
Genus : Cerithidea
Spesies : Cerithidea cingulata
38
Gambar 4.7 Cerithidea cingulata (Agustina dkk, 2019)
Kerang ini memiliki warna cangkang coklat kehitaman, dengan
apex meruncing berbentuk kerucut. Cangkangnya memiliki arah putaran
dekstral. Ukuran cangkang yang dimiliki adalah 2,5–3,1 cm dengan lebar
cangkang 1–1,5 cm. Jenis kerang ini dapat ditemukan di akar mangrove
atau di permukaan substrat mangrove (Nurrudin dkk, 2015).
g. Chicoreus capucinus
Klasifikasi Cerithidea cingulata adalah sebagai berikut (Eisenberg, 1981):
Kingdom : Animalia
Filum : Molusca
Kelas : Gastropoda
Ordo : Neogastropoda
Family : Muricidae
Genus : Chicoreus
Spesies : Chicoreus capucinus
Chicoreus capucinus memiliki cangkang bergerigi, dengan putaran
cangkang berjenis dekstral. Cangkangnya berwarna coklat, dengan
panjang 3–5 cm dan lebar 1,8–2,5 cm. Jenis ini dapat ditemukan di akar
dan substrat mangrove (Nurrudin dkk, 2015). Habitat hewan ini adalah
daerah dengan substrat lumpur yang berada di sekitar pohon mangrove.
39
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search