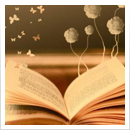Gambar 4.8 Chicoreus capucinus (Wahyuni dkk, 2016)
40
BAB V
KEANEKARAGAMAN CRUSTACEA DI
KALIMANTAN UTARA
Crustacea adalah invertebrate yang terdiri dari 6 kelas, yaitu
Branchiopoda, Remipedia, Cephalocarida, Maxillopoda, Ostracoda dan
Malacostraca. Hewan yang termasuk jenis crustacea ini dapat di hidup
berbagai perairan seperti sungai, laut, perairan estuari, atau perairan yang
berada di dekat daerah mangrove, dan ada juga jenis crustacea yang
hidup pada perairan jenis tertentu. Jumlah jenis krustacea terbesar berasal
dari dua suku, yaitu suku Ocypodidae yang daerah tempat tinggalnya di
daerah pantai dan didekat muara sungai, dan suku Sesarmidae yang
daerah tempat tinggalnya adalah daerah kering, suka memanjat akar atau
batang pohon mangrove. Crustacea memiliki kemampuan bertahan hidup
serta berkembang biak jika daerah tempat tinggalnya memiliki kondisi pH,
suhu, dan salinitas yang dapat di terima oleh biota tersebut. Crustacea
juga merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kedalam benthos,
seperti moluksa yang termasuk filter feeder. Biasanya hewan yang
termasuk crustacea ini pada umunnya hidup pada daerah dengan substrat
pasir atau substrat berlumpur. Jenis yang dapat ditemukan adalah udang
dan kepiting yang hidup di daerah pasang surut, dan merupakan pemakan
serasah mangrove dan daun (Rahayu dan Setyadi, 2009).
A. JENIS CRUSTACEA DI KALIMANTAN UTARA
Di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terdapat berbagai macam jenis
crustacea yang ditemukan. Berikut adalah jenis-jenis crustacea yang
ditemukan, disajikan dalam tabel 5.1 berikut:
Tabel 5.1 Jenis Crustacea yang Ditemukan Di Kalimantan Utara
No. Nama Lokal Nama Ilmiah
1. Udang Windu Penaeus monodon
2. Udang Galah Macrobrachium rosenbergii
3. Udang Putih Litopenaeus vannamei
4. Udang Nenek Harpiosquilla raphidea
5. Kepiting Bakau Scylla serata
6. Kepiting Fiddler Uca sp.
Sumber: Salim dkk, 2021
41
1. Udang windu (Penaeus Monodon)
Udang windu dengan nama latin Penaeus Monodon adalah salah
satu jenis yang menjadi komoditi unggulan sektor perikanan budidaya.
Udang windu memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan devisa
Indonesia (Lante dkk, 2018). hal ini telah berkembang pesat pada dari awal
era tahun 1980, hingga tahun 1990. Lalu produksi udang sempt mengalami
penurunan karena penyakit yang menyeran oudang windu berupa virus,
bakteri, parasite serta jamur (Suwoyo dan Sahabuddin, 2017). Walau
begitu, udang windu masih tetap diminati hingga saat ini, dan udang windu
juga menjadi salah satu bahan yang diekspor ke berbagai negara.
Gambar 5.1 Udang Windu yang Ditangkap Di Perairan Juata Kota Tarakan
(Verastiawan, 2021)
Kegiatan penangkapan yang dilakukan di daerah Kota Tarakan
terbilang cukup tinggi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap
udang windu biasanya adalah pukat hela atau Trawl. Selain penangkapan,
udang windu juga di kembangbiakkan di di tambak-tambak tradisional di
sekitar Kota Tarakan. Karena udang dikembang secara tambak tradisional,
udang windu yang berkembang di tambak masih dipengaruhi oleh alam,
khususnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di
Kalimantan Utara, udang windu yang berada di Kota Tarakan memiliki
berat maksimum yaitu 261 gram. Berdasarkan penelitan lain, udang
windu memiliki kandungan protein sebanyak 149 mg. Semakin besar
berat udang windu, maka semakin banyak pula kandungan protein yang
dimilikinya. Karena hal ini, permintaan udang windu di pasar pun tinggi
dan meningkat seiring waktu, baik dari pasar dalam negeri maupun pasar
luar negeri. Di Kota Tarakan Sendiri, Udang windu biasanya diekspor
42
dari perusahaan-perusahaan cold storage. Karena banyaknya tambak
yang berada di Kalimantan Utara, perusahaan-perusahaan cold storage
pun banyak bermunculan, khususnya di Kota Tarakan. Berdasarkan hasil
penelitian mengenai udang windu yang lain, udang windu yang berada di
tambak memiliki berbagai varian ukuran. Dari yang berukuran kecil, hingga
yang berukuran sedang dan besar. Dari segi populasi, udang windu yang
dikembangkan di tambak lebih banyak dibandingkan udang windu yang
berada di lautan.
Penelitian lain yang dilakukan adalah perhitungan sex rasio udang
windu yang berada di Perairan Juata dan Tambak tradisional. Pada
perairan Juata laut ditemukan perbandingan sex ratio untuk jantan dan
betina adalah 2:1, dengan presentase jantan adalah 66,7% dan betina
adalah 33,3%. Pertumbuhan alometrik pada udang jantan adalah positif,
dan hal pertumbuhan alometrik udang betina adalah negatif. Sedangkan
udang windu yang berada di tambak memiliki sex rasio untuk jantan dan
betina adalah 1:1,57, dengan presentase 39,6% untuk udang windu jantan
dan 60,4% untuk udang windu betina. Pertumbuhan alometrik panjang
total dan berat total untuk udang jantan adalah negatif, dan untuk udang
betina adalah positif. Untuk lemak, udang windu yang berada di tambak
memilliki nilai yang lebih besar, yaitu sebanyak 57,1%, dan udang windu
yang berada di perairan memilki tubuh dengan lemak 56,3% (Salim dkk,
2020).
2. Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii)
Udang galah atau Macrobrachium rosenbergii adalah komunitas air
tawar dengan nilai ekonomis tinggi. Peluang pasar udang galah terbuka dari
pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Permintaan udang galah yang
beru terpenuhi di Indonesia dalah 40%, dari seluruh permintaan yang ada. Hal
ini dapat terjadi karena masih rendahnya produksi udang galah, dibandingkan
jenis udang yang lainnya. Biasanya udang galah hidup di sungai, dan di
beberada daerah tertentu udang galah di budidayakan di kolam-kolam air
tawar. (Ali dan Waluyo, 2015)
Udang galah atau Macrobrachium rosenbergii merupakan salah satu
species udang tawar yang berasal dari Indonesia. Udang galah digemari
oleh masyaraka karena udang ini memiliki ukuran tubuh yang besar, dan
memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dipasaran. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan Indarjo dkk (2020) bahwa udang galah yang dijual di daerah
Nunukan mencapi harga yang cukup tinggi. Dari harga Rp.80.000 hingga
43
Rp100.000/kg. pada daerah salimbatu, udang galah dijual dengan harga
Rp40.000 hingga Rp65.000/kg. sedangkan di buong baru, desa sesayap
di kabupatan tana tidung. Udang galah dijual dengan harga yang sama
dengan harga yang berada di nunukan, yaitu dari harga Rp80.000 hingga
Rp100.000/kg. di provinsi Kalimantan sendiri, udang galah menjadi sangat
penting untuk meningkatkan pedapatan bagi masyarakat pesisir (Samuel
dan Aida, 2008). Untuk harga udang galah di provinsi Kalimantan sendri
dapat mencapai Rp140.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya, sesuai
dengan ukuran udang galah (Sukarli, 2017). Indarjo dkk (2020) menyatakan
bahwa udang galah yang ditangkap masyarakat memiliki potensial yang
sangat besar bagi perikanan tangkap, tetapi jika penangkapan dilakukan
terus menerus, maka akan terjadi degradasi populasi dari udang galah
dan akan berdampak pada populasi natural dari udang galah itu sendiri.
Karena meningkatnya permintaan pasar, penangkapan udang galah
secara besar-besaran pun terjadi.
Hossain dkk (2012) menyatakan bahwa udang galah merupakan
jenis udang yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Dilaporkan bahwa
udang galah dapat tumbuh hingga 250 mm untuk jenis udang galah betina,
dan 320 mm unutk jenis udang galah jantan. Dan udang galah pun memilki
berat hingga 300 gram (Wowor dan Ng, 2007, 2010). Sofian dan Sari (2018)
juga melaporkan bahwa udang galah dapat tumbuh dari 7.6 cm–27 cm
dengan berat 3 hingga 297 gram. Karena itu dapat di diduga bahwa udang
galah memiliki ukuran yang bervariasi. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan Indarjo dkk (2020), udang galah jantan dan betina dapat tumbuh
hingga 14.55 ± 6.55 cm dan 12.4 ± 4.6 cm. udang galah juga merupakan
mahkluk hidup yang dapat hidup di daerah dengan salinitas yang berbeda-
beda (Ali dan Waluyo, 2015). Indrajo dkk (2020) menyebutkan bahwa
udang galah dapat hidup pada salinitas 6 hingga 7 ppt. pada penelitian
lainnya udang galah dapat hidup pada salinitas 15 hingga 20 ppt.
Udang galah memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga banyak
nelayan yang melakukan penangkapan udang galah. Di porvinsi
Kalimantan utara, kabupaten yang melakukan penangkapan udang galah
adalah kabupaten bulungan, kabupaten Tana Tidung, dan kabupaten
Nunukan. Terdapat berbagai jenis alat yang melakukan penangkapan
udang galah, yaitu:
- Tugu
- Jala
- Empang Lulung
44
- Bengkirai Bilah
- Pancing
- Rawai Udang
- Rompong
- Pukat Rantau.
3. Udang Putih (Litopenaeus vannamei)
Udang putih atau Litopenaeus vannamei adalah udang yang biasanya
dibudidayakan Kalimantan Utara, selain dari udang windu. Udang putih
atau vanname adalah spesies udang yang berasal dari Amerika Tengah
dan Selatan. Udang ini dapat hidup pada salinitas hingga 35 ppt dan
biasanya berada pada bagian muara perairan, karena memiliki makan
yang melimpah, karena itu udang dapat bertumbuh dengan sangat pesat.
Selain hidup di muara, udang ini juga dikembangkan di kolam-kolam
budidaya (Salim dkk, 2020).
Beberapa tahun terakhir, udang putih menjadi salah satu komoditas
yang berkontribusi pada sektor budidaya perikanan di Indonesia. udang
putih memiliki peran yang dapat menggantikan budidaya udang windu.
Undang putih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak digemari
oleh masyarkat umum. Darmono (1991) dalam Maharani dkk (2009)
menyebutkan bahwa udang putih adalah salah satu dari sekian jenis
udang yang menjadi sumber protein hewani yang memiliki mutu tinggi.
Ikan jenis ini bukanhanya digemari oleh masyarakat dalam negeri, tetapi
juga digemari oleh konsumen luar negeri karena memiliki rasa gurih dan
rendah kolesterol. Karena itu banyak yang membudidayakan udang
jenis ini, dan berkembang pesat di Indonesia. Briggs dkk (2004) juga
menyatakan bahwa udang jenis ini dapat tumbuh dengan sangat cepat,
seperti udang windu yang bisanya tumbuh 3 gram per minggunya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Salim dkk
(2020), ditemukan bahwa udang putih yang ditemukan di perairan Juata
Tarakan memiliki sex rasio untuk udang jantan dan betina adalah 1,68:1
dengan presentase 62,71% dan 37.29%. sedangkan udang putih yang
ditemukan di tambak memilki sex rasio untuk udang jantan dan betina
adalah 1: 3 dengan presentase 25% hingga 75%.
4. Udang Nenek (Harpiosquilla raphidea)
Beikut adalah klasifikasi udang nenek yang ditemukan di Kota
Tarakan (Marinespecies, 2014 dalam Salim dan Wiharyanto, 2015).
45
Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Kelas : Malacostraca
Ordo : Stomatopoda
Family : Squillidea
Genus : Harpiosquilla
Spesies : Harpiosquilla raphidea
Udang nenek (Harpiosquilla raphidea) merupakan sejenis udang
mantis, yang hidup di perairan intertidal. Udang ini biasanya memiliki
ukuran panjang 33 cm untuk udang jantan. Karapaks udang ini hanya
menutupi sebagian dari kepalanya dan tiga segmen pertama dari toraks.
Udang jenis ini memiliki aneka ragam warna, mulai dari warna gelap,
coklat dan berwarna terang. Udang ini biasanya bersembunyi di balik
baatu karang atau bebatuan untuk menunggu mangsanya (FAO, 2014).
Udang nenek memiliki habitat di daerah demersal, dengan kedalaman
berkisar 2–45 meter.
Gambar 5.2 Udang Nenek yang Ditangkap Di Perairan Juata Kota Tarakan
(Verastiawan, 2021)
Pulau Tarakan yang berada di Kalimantan Utara memiliki potensi
perikanan yang tinggi, serta memiliki keanakeragaman hayati yang bernilai
ekonomis tinggi. Salah satu potensi perikanan yang memiliki potensi yang
cukup tinggi untuk dikelola adalah udang Harpiosquilla raphidea. Udang
jenis ini biasanya disebut oleh warga sekitar dengan sebutan udang nenek.
46
Udang ini memiliki kandungan protein sebesar 16,49% (Salim dan Firdaus,
2013). Tetapi dari sekian banyak jenis udang yang memiliki potensi nilai
ekonomis yang tinggi, udang nenek menjadi hasil tangkapan buangan
nelayan. Hal ini dikarenakan udang ini tidak memiliki nilai ekonomis yang
tinggi, padahal kandungan proteinnya terbilang cukup tinggi. Udang ini
hidup dengan kualitas lingkungan pH 8,12; DO 7,46 mg/l; suhu 2,4 OC;
salinitas 20 ppt; dan kecerahan 113,5 cm (Chandra dkk, 2015).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salim dan
Wiharyanto (2015), udang nenek jantan memiliki kisaran berat rata-rata
120, 68 ± 119,32 gram, sedangkan udang nenek betina memiliki kisaran
berat rata-rata 117,6 ± 114,9 gram.
5. Kepiting Bakau (Scylla serata)
Pulau Tarakan memiliki berbagai macam ekosistem, salah satunya
adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove sendiri menjadi tempat
tinggal bagi berbagai macam biota perairan, salah satunya dalah kepiting
bakau atau Scylla serata. Kepiting bakau memiliki potensi yang sangat
tinggi. Kepiting ini meiliki kandungan protein sebesar 13,6 gram per 100
gram daging kepiting (Afrianto dan Liviawaty, 1993). Kepiting bakau juga
memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terbukti dari besarnya permintaan dari
pasar dalam neger dan luar negeri. Beberapa negara meminta ekspor
kepiting kering untuk dijadikan sebagai bahan kitosan untuk sumber bahan
baku obat. Selain obat-obatan, kepiting ini juga digunakan sebagai bahan
kosmetik, pangan, antibakteri dan antivirus (Aulia, 2010).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Salim dkk
(2018), kepiting bakau memiliki model jenis pertumbuhan antara dimensi
karapaks yaitu panjang, lebar dan tebal karapaks, dengan berat total.
Untuk hasil allometrik, didapatkan bahwa kepiting jantan dan betina
memiliki pertumbuhan yang bersifat allometrik negatif. Untuk indeks
kondisi berdasarkan panjang karapaks dan berat total, kepiting jantan
dan betina yang ditemukan di Kota Tarakan memiliki bentuk tubuh yang
gemuk, sedangkan indeks kondisi berdasarkan cangkang dan berat
total, kepiting jantan dominasi oleh ukuran tubuh yang kurus, sedangkan
kepiting betina dominansi oleh ukuran tubuh yang gemuk. Untuk jumlah
populasinya, kepiting bakau jantan lebih banyak ditemukan, karena
kepiting jantan tidak melakukan ruaya kelaut, seperti yang dilakukan oleh
kepiting betina. Menurut Hill (1975) dalam Agus (2011) kepiting betina akan
melakukan ruaya saat ingin melakukan pemijahan, sedangkan kepiting
47
bakau jantan akan tetap berada di perairan sekitar hutan bakau atau di
muara sungai. Pendapat lain dari Wijaya dkk (2010) kepiting jantan lebih
banyak tertangkap oleh nelayan karena memiliki sifat agresif saat mencari
makanan. Oleh sebab itu, populasi kepiting jantan lebih banyak ditemukan
di sekitar hutan mangrove dibandingkan kepiting betina (Salim dkk, 2018).
6. Kepiting Fiddler (Uca Sp)
Kepiting fiddler adalah kepiting yang memiliki salah satu capit
yang besar, yang berada di sebelah kanan atau kiri kepalanya. Kepiting
fiddler memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem mangrove
(Rosenberg, 2000). Kepiting fidller banyak dijumpai hidup di tepi pantai
yang tanahnya agak berlumpur, dimana daerah ini merupakan daerah
pasang surut. Tempat yang paling disenangi oleh kepiting ini adalah pantai
dangkal yang memiliki tumbuh-tumbuhan mangrove seperti hutan bakau
dan nipah Kepiting fidller tersebar luas di bagian barat Indo-Pasifik yakni
dari daerah Pakistan ke Malaysia dan Filipina, serta sangat berlimpah
mengelilingi bagian selatan Laut Cina Selatan (Afrianto, 1992 dan Keenan,
1998 dalam Rosberg, 2001).
Kepiting bakau ukurannya bisa mencapai lebih dari 20 cm. Sapit
pada jantan dewasa lebih panjang dari pada sapit betina. Kepiting yang
bisa berenang ini terdapat hampir di seluruh perairan pantai Indonesia,
terutama di daerah mangrove, di daerah tambak air payau, muara
sungai, tetapi jarang ditemukan di pulau-pulau karang (Nontji, 2002).
Disamping morfologi sapit, kepiting jantan dan betina dapat dibedakan
juga berdasarkan ukuran abdomen, dimana abdomen jantan lebih sempit
dari pada abdomen betina (Gambar 5.3).
Gambar 5.3 Perbedaan morfologi kepiting jantan dan betina
(Sumber: www.environment.gov.au, 2007).
48
kepiting Fiddler (Uca Sp) yang ditemukan di daerah kawasan
konservasi mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan, adalah
sebanyak 7 Spesies dari genus kepiting Fiddler (Uca Sp) yaitu:
Gambar 5.4 Spesies Uca Rosea
(https://www.fiddlercrab.info/u_rosea.html)
Gambar 5.5 Spesies Uca Arcuata
https://www.fiddlercrab.info/u_arcuata.html
Gambar 5.6 Spesies Uca Crassipes
(https://www.fiddlercrab.info/u_crassipes.html)
49
Gambar 5.7 Spesies Uca Dussumieri
(http://courses.washington.edu/larescue/projects/mangrove/mangrove.htm)
Gambar 5.8 Spesies Uca Tetragonon
(https://www.fiddlercrab.info/u_tetragonon.html)
Gambar 5.9 Spesies Uca Vocans
(https://www.fiddlercrab.info/u_vocans.html)
50
BAB VI
KEANEKARAGAMAN PISCES DI
KALIMANTAN UTARA
Ikan merupakan mahkluk hidup bertulang belakang serta berdarah
dingin, yang hidup di dalam perairan dan menggunakan insang untuk
bernafas. Selain itu, ikan merupakan organisme yang mampu berenang
dan pindah secara aktif (Odum, 1991). Ikan merupakan kelompok
vertebrata dimana terdapat keanekaragaman yang tinggi, yaitu sekitar
27.000 di dunia. Terdapat 4 kelas dan vertebarata sejenis ikan, yaitu:
a. KelasAgnatha, vertebrata tidak berahang. Contohnya adalah Ostrachodermi
yang telah punah, dan Cyclostomata (Lamprey dan Hagfishes).
b. Ikan purba yang memiliki rahang keras yaitu kelas Placodermi yang
telah punah.
c. Kelas Chondrichtyes, ikan dengan tulang rawan yaitu hiu dan pari.
d. Kelas Osteichthyes atau ikan yang memiliki tulang sejati.
Kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes merupakan kelompok yang
termasuk superkelas Pisces. Cohen (1970) menyebutkan bahwa terdapat
515–555 yang termasuk jenis Chondrichthyes dan terdapat 19.135–20.980
yang termasuk kedalam jenis Osteichthyes. Jumlah ini ternyata lebih banyak
dibandingkan dari seluruh vertebrata yang ada. Hal ini tidak menjadi hal asing,
karena sebanyak 80% bumi tertutup oleh air (Sukiya, 2005).
A. KLASIFIKASI PISCES
Klasidikasi ikan dapat dilihat pada bagian di bawah ini.
1. Superkelas: PISCES
a. Kelas Chondrichthyes, ikan bertulang rawan
b. Kelas Osteichthyes, ikan bertulang keras
c. Kelas Chondrichthyes. Ikan yang termasukk kelas ini memiliki skeleton
atau rangka tubuh yang hampir seluruhnya tersusun dari tulang rawan.
Ikan yang dianggap termasuk kelas ini adalah ikan hiu dan dan ikan pari
yang hidup di laut. Beberapa jenis ikan pari memiliki duri yang beracun
pada bagian ekornya. jika terkena sengatannya, akan terkena suatu
penyakit. Selain memiliki racun pada ekornya, terdapat beberapa jenis Ikan
pari lain yang dapat memberikan kejutan-kejutan listrik yang kuat (Sumadji
Sastrosuparno, 1978).
51
d. Kelas Osteichthyes. Ikan yang termasuk kedalam kelas ini memiliki
skeleton yang sebagian besarnya tersusun dari tulang keras. Pada
umumnya ikan yang termasuk kelas ini memiliki sisik. Dari 23.000
spesies ikan, sebanyak 20.000 spesies merupakan anggota dari kelas
ini. Ikan-ikannya memiliki variasi yang beragam pada bagian ukuran,
warna, bentuk, dan cara menyesuaikan diri pada lingkungannya.
(Sumadji Sastrosuparno, 1978)
B. MORFOLOGI IKAN
Ikan menjadi anggota terbesar dari 4 anggota vertebrata yang lain.
Ikan dikatakan sebagai jenis yang menempati 43,1% jumlahnya dari seluruh
spesies yang ada, yaitu 41.600. Di Indonesia sendiri, terdapati 4000 jenis lebih,
dengan 800 jenisnya hidup di perairan tawar atau di perairan payau. Ikan
memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu Caput atau kepala, Truncus, serta Caudal
atau ekor. Bagian ini memiliki batas- batas, tetapi batas antara Caput dengan
Truncus tidak jelas dapat terlihat. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa
batas antara caput dan truncus adalah tepi ujung dari Operkulum. Batas lain
yaitu Truncus dan Caudal. Sebagian orang juga berpendapat bahwa anus
adalah batas antara truncus dan caudal. Kottelat dkk (1993) telah membagi
ikan secara morfologis seperti sebagai berikut:
Gambar 6.1 Skema Ikan Untuk Menunjukkan Ciri-Ciri Morfologi Utama dan Ukuran-Ukuran
yang Digunakan dalam Identifikasi (Kottelat dkk, 1993)
Keterangan:
(A) sirip punggung; (B) sirip ekor; (C) gurat sisi; (D) lubang hidung; (E) sungut; (F) sirip
dada;(G) sirip perut; (H) sirip dubur; (a) panjang total; (b) panjang standar;
(c) panjang kepala; (d) panjang batang ekor; (e) panjang moncong; (f) tinggi sirip punggung;
(g) panjang pangkal sirip punggung; (h) diameter mata; (i) tinggi batang ekor; (j) tinggi badan;
(k) panjang sirip dada; (l) panjang sirip perut.
52
1. Sisik
Sisik merupakan bagian tubuh luar, yang dapat menjadi pelindung
serta penutup tubuh bagi ikan bertulang keras maupun ikan bertulang
rawan. Sisik memiliki fungsi penting dalam menentukan klasifikasi ikan.
Sisik tersusun dari beberapa lempengan tulang. Terdapat berbagai jenis
sisik. Ikan hiu serta ikan pari memiliki bentuk sisik yaitu plakoid, lalu ikan
gars memiliki bentuk sisik yang bertipe ganoid yang berbentuk seperti
belah ketupat tersusun dengan sangat rapat antar sisik satu dengan sisik
yang lain. Untuk tipe sisik sikloid, biasanya di miliki oleh ikan bertulang
keras. Sisik ini akan tertanam pada bagian depannya, dicelah-celah kulit.
Tidak seperti jenis sisik yang lain, sisik ini memiliki susunan seperti kulit
yang dimana sisiknya tidak dilindungi oleh epidermis, metrial seperti email,
ataupun ganoin. Sisik tipe sikloig biasanya melingkar dan akan bertambah
ukurannya seiring dengan pertumbuhan ikan. karena itu, pertumbuhan
sisik akan terlihat seperti lingkaran tahun pada pohon, yang memiliki
tanda cincin pertumbuhan. Cincin ini dapat terlihat jelas pada sisik. Tetapi
pertumbuhan sisik dapat melambat jika masuk pada musim dingin, karena
menurunnya suhu serta pasokan makanan. Untuk jenis sisik ctenoid, ia
memiliki struktur dan susunan yang hampir sama dengan tipe sisik sikloid.
Tetapi pada bagian belakangnya akan berbentuk seperti sisir. Sisik ctenoid
ini bisa ditemukan pada ikan pari, dan menjadi duri pada sirip dorsalnya.
2. Warna Tubuh
Hewan vertebrata memiliki warna tubuh yang indah. Pada ikan,
warna tubuh yang dimiliki lebih kompleks. Hal ini dikarenakan terdapatnya
kromatofora yang berada pada lapisan dermis. Ikan memiliki pigmen
utama yaitu melanin dan karotenoid yang berada didalam kromatofora.
Melanin mampu memberikan warna pada ikan, dan memproduksi warna
tubuh ikan seperti warna coklat, hitam atau ungu. Sedangkan karotenoid
responsive terhadap warna kuning, merah dan orange. Kromatofa yang
didalamnya mengandung melakin disebut dengan melanofora, sedangkan
yang menandung karotenoid disebut denga lipofora. Perubuhan warna
tubuh ikan dapat dilihat pada beberapa jenis ikan, ketika masa kawin
tiba. Perubahan warna ini juga dapat dijadikan sebagai pengenalan jenis
kelamin. Selain itu, warna tubuh ikan dapat berubah, tergantung lingkungan
tempat tinggal, dan ini juga menjadi salah satu cara ikan beradaptasi pada
lingkungan yang akan berguna untuk melindungi dirinya dari predator.
53
Sebagai contoh, ikan yang hidup pada daerah karang akan memiliki warna
tubuh yang cerah. Lalu ikan yang hidup pada dasar pada daerah yang
memiliki kecerahan yang berubah-ubah akan memiliki tubuh yang terdapat
garis gelap terangnya. Dan biasanya permukaan bagian atas tubuh ikan
akan menyerupai sesuai dengan warna susbtrat tempat dia tinggal.
3. Alat Gerak
Pada umumnya, ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor.
Ikan dengan tulang rawan maupun ikan dengan tulang keras dasarnya
memiliki sirip pektoral, dan sirip pelvic yang berpasang, ditambah sirip
medial dan kaudal. Sirip ikan terbungkus oleh kulit tebal, oleh karena itu
bagian penyusunnya tidak akan nampak terlihat. Sebagai contoh ikan
hiu mempunyai dua sirip dorsal, tetapi pada spesies yang lain hanya
memiliki satu sirip dorsal, dan satu sirip anal. Untuk kelompok jenis
ikan pari memiliki sirip pectoral yang membesar dan menempel pada
tubuhnya hingga sampai ke depan sirip pelvic. Pada umumnya ikan
pari memiliki dua sirip median dorsal yang posisinya jauh dari ekor. Sirip
selain sebagai alat gerak, ada beberapa jenis ikan yang menggunakan
sirip untuk memindahkan spermanya kepada hewan betina. Jenis ikan
yang melakukan hal ini adalah ikan hiu jantan dan ikan pari jantan, yang
menggunakan bagian dalam sirip pelvicnya.
C. JENIS IKAN YANG BERADA DI KALIMANTAN UTARA
Keanekararagaman hayati yang berada di perairan menjadi sangat
penting, dikarenakan organisme biologi memiliki keanekaragaman
genetic, spesies atau ekosistem guna mempertahankan kehidupan
yang berkelanjutan. Selain sebagai faktor untuk keberlangsungan hidup,
keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu hal yang penting untuk
meningkatkan nilai ekonomi perikanan, dan menjadi pemenuh kebutuhan
protein, dimana masyarakat memanfaatkan kelimpahan ikan untuk
dikonsumsi. Jika terjadi kepunahan akibat eksploitasi yang berlebihan,
maka muncul berbagai kerugian, dari sisi keanekaragaman hayati maupun
sisi ekonomi. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan sumberdaya yang
baik agar keanekaragaman hayati terus terjaga.
Kalimantan Utara memiliki berbagai daerah perairan, seperti sungai,
danau, rawa, maupun laut yang menjadi tempat tinggal para ikan. Karena
hal inilah, Kalimantan utara memiliki berbagi aneka jenis ikan didalamnya.
Sebagai contoh, muara sungai merupakan wilayah air yang menjadi titik
54
pertemuan antara satu atau sungai yang berada di wilayah pesisir dan
laut. Kondisi muara sangat dipengaruhi oleh kondisi air yang berasal
dari daratan yang didapatkan dari aliran sungai, dan air laut yang masuk
melalui proses pasang surut, dan gelombang sehingga air asin pun masuk
kedaerah muara. Karena itu, muara memiliki banyak kekayaan biologis
yang didapatkan dari perairan daratan dan laut. Kondisi ini menyebabkan
tingginya keanekaragam hayati yang berada di Kalimantan Utara. sebagai
contoh daerah yang berada di Kalimantan Utara, yaitu Perairan Juata, pada
bagian utara dari Pulau Tarakan. Perairan Juata merupakan sebagaian
kecil dari perairan muara yang berada di Kalimantan Utara. perairan ini
menghubungkan sungai Sesayap, yang menjadi salah satu sungai besar
yang berada di Kalimantan Utara. hampir sama seperti perairan yang
lain, perairan Juata memiliki substrat lumpur, dan terdapt vegetasi hutan
mangrove yang tumbuh dengan sangat baik di sekitar pulau-pulau yang
berada di dekat perairan ini.
Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh beberapa
peneliti di Kalimantan Utara, didapatkan berbagai jenis ikan yang berada
di Perairan Juata. Variasi jenis ikan yang ditemukan dapat dilihat pada
tabel 6.1 berikut.
Tabel 6.1 Komposisi Jenis Ikan yang Ditemukan Perairan Dekat Vegetasi Mangrove
NO. Ikan Spesies
1 Nomei Harpadon nehereus (F. Hamilton, 1822)
2 Merah Lunitanus erythropterus
3 Gulama Pseudocienna amovensis
4 Bawal Parastromateus niger
5 Belanak Mugil sp
6 Layur Trichiurus savala
7 Lidah Cynoglossus spp
8 Kakap Lutjanus rivulatus
9 Bandeng Chanos-Chanos
10 Belut Monopterus albus
11 Tempakul/Glodok Periopthalmodon sp.
12 Selar Kuning Selaroides leptolepis
13 Timoka/pepetek Leiognathus equhus
14 Otak Arius thalassinus
15 Puput Ilisha sp
16 Sembilang Euristhmus microceps
55
NO. Ikan Spesies
17 Bulu Ayam Thryssa setirostris
18 Selangat Anodontostoma selangkat
19 Kaca Chandara boervensis
20 Julung-Julung Dermogenys sp
21 Kerong-Kerong Therapon jarbua
22 Ketang –ketang Scatophagus sp
23 Buntal Porcupinesfish
Sumber: Hasil Penelitian Wiharyanto dan Salim, 2014
Selain ikan pada yang berada di ekosistem mangrove, terdapat
juga jenis-jenis ikan dikambangbiakkan di tambak-tambak yang berada
di provinsi Kalimantan Utara. Untuk daftar nama ikan dapat dilihat pada
Tabel 6.2 berikut ini.
Tabel 6.2 Komposisi Jenis Ikan yang Ditemukan di Tambak-Tambak Kalimantan Utara
No. Nama Ikan Nama Latin
1 Ikan Sumpit Toxotes chatereus
2 Ikan Dato Synancea verrucasa
3 Ikan Kapasan Silver biddies
4 Ikan Sardine Escualosa thoracata
5 Ikan Petek Leiognathus eguulus
6 Ikan Ceri todong Apogon harzfeldi
7 Ikan Puput Ilisha sp
8 Ikan Kaca Ambassis sp
9 Ikan Pari Putih Stolephorus
10 Ikan Julung-Julung Dermogenys sp
11 Ikan Buntal Pufferfish
12 Ikan Sembilang Plotosus canius
13 Ikan Kerondong Gymnothorax unduculatus
14 Ikan Therapon Therapon jarbua
15 Ikan Ketang-ketang Scatophagus sp
16 Ikan Bandeng Laki Elops hawaiensis Regan
17 Ikan Belosoh Saurida tumbil
18 Ikan Belanak Valamugil speigleri
19 Ikan Tempakul Periopthalmus sp
Sumber: Hasil Penelitian Wiharyanto dan Salim, 2014
56
Jenis-jenis ikan yang ditemukan di perairan Juata Laut yang
berdekatan dengan vegetasi mangrove lebih banyak yaitu 23 jenis,
sedangkan di perairan tambak jenis ikan yang ditemukan sebanyak 19
jenis. Tingkat keanekaragaman ikan yang ditemukan di perairan mangrove
yang dapat dilihat pada tabel 6.1 lebih tinggi, dibandingkan dengan jenis
ikan yang ditemukan di tambak (Tabel 6.2). Hal ini bisa disebabkan oleh
sifat dari setiap perairan. Dapat diketahui bahwa perairan tambak memiliki
daerah yang tertutup, dan secara umum ikan yang berada di perairan
tambak adalah ikan yang berasal dari perairan mangrove, yang masuk
saat proses pengisian tambak. Menurut Iromo dkk (2010), tambak yang
berada di sekitar Kalimantan Utara ini masih dijalankan secara tradisional.
Pada proses pengisian air , para petambak memanfaatkan air pasang laut,
sehingga benih-benih ikan dapat ikut masuk kedalam tambak.
Adanya ekosistem, serta peran manusia menjadi sangat penting
untuk keberadaan ikan yang berada di perairan daratan maupun di
perarairan laut. Ekosistem dapat menjadi sumber keanekaragaman hayati
karena menjadi daerah asuhan, tempat tinggal dan mencari makan bagi
para biota yang berada di perairan. Sedangkan peran manusia adalah
dengan menjaga kebersihan laut, tidak menggunakan bahan bebahaya
ketika melakukan penangkapan, dan pengelolaan sumber daya yang
baik akan menjadi keanekaragaman hayati laut tetap terjaga. Karena itu,
pentingnya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ini agar
kita dapat terus merasakan manfaatnya, terhindar dari kepunahan, dan
menjadi sumber yang dapat terus mendukung kehidupan manusia hingga
waktu yang lama nanti.
57
BAB VII
METODE KONSERVASI KEANEKARAGAMAN
HAYATI SUMBERDAYA PERAIRAN
PENGERTIAN DASAR
Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) perairan dapat
didefinisikan sebagai upaya atau proses pemeliharaan dan pengelolaan
keanekaragaman hayati sumberdaya perairan secara sistematis dan
terencana untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara
perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Konservasi juga dapat
dinyatakan sebagai proses pengelolaan yang rasional terhadap suatu
sumberdaya atau keanekaragaman hayati perairan dengan mengatur
proporsi perlindungan dan pemanfaatannya agar sumberdaya serta
habitatnya tetap lestari. Kawasan konservasi di perairan adalah bagian
dari wilayah perairan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu
kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
secara berkelanjutan, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya
perairan secara berkelanjutan (Permen KP No. 17 Tahun 2008 tentang
Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
Kategori Kawasan Konservasi KEHATI di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (WP3K)
Kawasan konservasi KEHATI di WP3K dapat dikelompokkan menjadi
beberapa kategori. Adapun kategori kawasan konservasi Kehati di WP3K
adalah sebagai berikut:
Tabel 7.1 Kategori dan Jenis Kawasan Konservasi
Kawasan, kategori dan jenis kawasan konservasi
Menurut UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Klasifikasi Kategori Jenis
Kawasan
Kawasan Kawasan Konservasi a. Suaka pesisir;
Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau b. Suaka pulau kecil;
Kecil (KKP3K c. Taman pesisir; dan
d. Taman pulau kecil.
59
Klasifikasi Kategori Jenis
Kawasan a. Daerah perlindungan adat maritim;
b. Daerah perlindungan budaya
Kawasan Konservasi
Maritim (KKM) maritim.
a. Taman Nasional Perairan
Kawasan Konservasi b. Suaka Alam Perairan
Perairan (KKP c. Taman Wisata Perairan
Kawasan Lindung d. Suaka Perikanan
Sempadan Pantai
(KLSP) Akan diatur lebih lanjut melalui Perpres
Sumber: PP No. 60/2007, PermenKP No. 17/2008 dan PermenKP No. 31/2020
Sistem Zonasi Kawasan Konservasi Kehati
Zona atau mintakat adalah ruang yang penggunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dan telah
ditetapkan status hukumnya dengan Peraturan Menteri atau Peraturan
Daerah (Sumber: Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
Pengelolaan Kawasan konservasi dilakukan dengan sistem zonasi.
Sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, zonasi merupakan suatu bentuk rekayasa Teknik pemanfaatan
ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi
dan kerawanan sumberdaya dan daya dukung serta proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
Pencadangan Kawasan konservasi pada hakekatnya bertujuan
untuk melindungi spesies dan habitat keanekaragaman hayati dan
mempertahankan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.
Pembagian kategori, jenis serta mintakat (zona) di dalam kawasan
konservasi kehati dapat dilihat pada Gambar 7.1.
60
Gambar 7.1 Pembagian Kategori, Jenis dan Zona Kawasan Konservasi Kehati Perairan
Pertanyaan yang sering timbul, bagaimanakah mekanisme
pengintegrasian perencanaan zonasi WP3K di dalam kawasan konservasi
kehati perairan? Untuk jelasnya kita dapat lihat pada Gambar 3. Dari
gambar tersebut maka jelas diketahui bahwa kawasan konservasi kehati
memiliki banyak fungsi, bukan hanya berfungsi melindungi, yang tercermin
dari adanya zona inti (zona preservasi) yang tidak dapat dimanfaatkan
oleh kegiatan apapun (no take zone), namun juga terdiri atas zona
pemanfaatan terbatas dan zona perikanan berkelanjutan. Pada zona
pemanfaatan terbatas dan zona perikanan berkelanjutan, kegiatan-
kegiatan pemanfaatan yang terkendali dan tidak merusak lingkungan
serta tidak mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan masih
dibolehkan.
61
Gambar 7.2 Integrasi Perencanaan WP3K dengan Zonasi Kawasan Konservasi
(Sumber: Permen KP No. 17/2008 dan PermenKP No. 30/2010
Gambar 7.3 Gambaran Kawasan Konservasi Kehati Multifungsi yang dikelola dengan
Sistem Zonasi
62
Pengelolaan kawasan konservasi Kehati perlu dilakukan melalui
perencanaan alokasi ruang (pencadangan kawasan), pola pengelolaan
dan tata cara pengelolaan yang rasional. Perencanaan pemintakatan
kawasan konservasi kehati terdiri dari rencana jangka panjang, rencana
jangka menengah dan rencana jangka pendek tahunan, sedangkan pola
pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui sistem pemintakatan.
Di dalam kawasan konservasi kehati yang rasional diperlukan
adanya sistem pemintakatan atau zonasi. Adapun sistem zonasi dari
setiap kategori kawasan konservasi dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini:
Tabel 7.2 Sistem Zonasi Kawasan Konservasi KEHATI Perairan
Kawasan, kategori dan jenis kawasan konservasi
Menurut UU No. 27 Tahun 2007 & PP 19 Tahun 2019
Klasifikasi Kategori Sistem Zonasi
Kawasan
Kawasan Konservasi a. zona inti;
Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau b. zona pemanfaatan terbatas; dan/
Konservasi Kecil atau
Kawasan Konservasi c. zona lainnya sesuai dengan
Maritim peruntukan kawasan
Kawasan Konservasi a. zona inti;
Perairan b. zona perikanan berkelanjutan;
c. zona pemanfaatan; dan/atau
d. zona lainnya sesuai dengan
peruntukan kawasan
Sempadan Pantai Akan diatur lebih lanjut melalui Perpres
Sumber: PP No. 60/2007, PermenKP No. 17/2008, PermenKP No. 30/2010, PermenKP No
31/2020
63
64 Penilaian Zona untuk Pencadangan Kawasan Konservasi Kehati
Tahap penilaian suatu wilayah untuk dicadangkan sebagai kawasan konservasi WP3K, melalui berbagai tahapan, yaitu:
JENIS DATA/PETA SKALA KEDETILAN DATA KEMUTAKHIRAN DATA KELENGKAPAN SUMBER DATA/
Klasifikasi Peta Topografi Data terakhir yang
Dasar Laut Skala 1 : dikeluarkan oleh instansi ATRIBUT INSTANSI
250.000 dan 1 : 50.000 yang berwenang
Topografi Dasar 1 : 250.000 ID ESDM
Laut 1 : 50.000 Peta Kontur Kedalaman Perimeter Instansi terkait
Laut Skala 1:250.000 Jenis relief dasar
dengan interval laut
5,10,20,50,100,500,1000; Kemiringan dasar
dan skala 1 : 50.000 laut
dengan interval Luas
2,8,10,20,50,
Kedalaman/ 1 : 250.000 100,500,1000. Data terakhir yang ID Peta Laut
Bathimetri 1 : 50.000 Peta pola arah dan dikeluarkan oleh instansi Koordinat (Dishidros)
Data spasial kecepatan arus skala 1 : yang berwenang Perimeter Peta LPI (BIG)
kedalaman perairan 250.000 dan 1 : 50.000 Nilai Kedalaman Survey lapangan
laut (meter) Luas
Arus 1 : 250.000 Data 5 tahun terakhir dan ID Survey lapangan
1 : 50.000 atau data terakhir yang Arah arus
dikeluarkan oleh instansi Kecepatan arus
yang berwenang Waktu survey
Kelas arus
Luas
JENIS DATA/PETA SKALA KEDETILAN DATA KEMUTAKHIRAN DATA KELENGKAPAN SUMBER DATA/
ATRIBUT INSTANSI
Gelombang 1 : 250.000 Peta pola arah penjalaran Data 5 tahun terakhir dan
1 : 50.000 dan besar gelombang atau data terakhir yang ID Survey lapangan
dikeluarkan oleh instansi Tinggi
yang berwenang gelombang
Waktu survey
Kelas gelombang
Luas
Kecerahan 1 : 250.000 Peta kecerahan Data 5 tahun terakhir dan ID Survey lapangan
1 : 50.000 permukaan laut skala atau data terakhir yang Nilai
1:250.000 dan 1: 50.000 dikeluarkan oleh instansi Luas area Survey lapangan
yang berwenang Waktu survey Kementerian
Kondisi Kehutanan
Mangrove 1 : 250.000 Peta Sebaran dan Data 5 tahun terakhir dan oseanografi Survey lapangan
1 : 50.000 Kondisi mangrove Skala atau data terakhir yang Musim
1 : 250.000 dan skala 1: dikeluarkan oleh instansi
50.000 yang berwenang ID
Tipe penutupan
Terumbu Karang, 1 : 250.000 Peta Sebaran Terumbu Data 5 tahun terakhir dan Luas
Padang Lamun dan 1 : 50.000 Karang, lamun dan atau data terakhir yang Waktu survei
Substrat Dasar substrat dasar perairan dikeluarkan oleh instansi Musim
Skala 1 : 250.000 dan yang berwenang Kondisi
skala 1: 50.000 Oseanografi
ID
65 Tipe penutupan
Luas
Waktu survei
Musim
Kondisi
Oseanografi
66 JENIS DATA/PETA SKALA KEDETILAN DATA KEMUTAKHIRAN DATA KELENGKAPAN SUMBER DATA/
ATRIBUT INSTANSI
Keanekaragaman/ 1 : 250.000 Data spasial sebaran jenis Data 5 tahun terakhir dan
kekayaan dan 1 : 50.000 dan Kelimpahan Ikan atau data terakhir yang ID Survey lapangan
kelimpahan ikan: Skala 1 : 250.000 dan 1 : dikeluarkan oleh instansi Koordinat
- Endemik 50.000 untuk musim barat yang berwenang Jenis ikan
- Langka dan musim timur Kelimpahan
- Dilindungi UU Waktu survei
- Fekunditas Musim
Kondisi
Rendah Oseanografi
- Sedentary
(Menetap)
- Migratory
(Berpindah-
pindah tempat:
beruaya)
Risiko Bencana 1 : 250.000 Peta Kerawanan dan Data 5 tahun terakhir dan ID Survey lapangan
1 : 50.000 Risiko Bencana Skala atau data terakhir yang Koordinat
1:250.000 dan 1:50.000 dikeluarkan oleh instansi Jenis bencana
yang berwenang Luas area
bencana
Waktu terjadi
bencana
Keterangan
JENIS DATA/PETA SKALA KEDETILAN DATA KEMUTAKHIRAN DATA KELENGKAPAN SUMBER DATA/
Data Sosial Budaya 1 : 250.000 Peta Ancaman Aktivitas ATRIBUT INSTANSI
Manusia Data hasil survei
1 : 50.000 mengenai kegiatan ID Survei lapangan
Peta Tingkat Kepentingan perikanan yang tidak Koordinat
Ekonomi ramah lingkungan, Jenis aktivitas
pencemaran dan Luas area
kerusakan lingkungan, ancaman oleh
baik bersumber dari aktivitas manusia
aktivitas di darat maupun (kerusakan dan
di laut, misal penggunaan pencemaran)
alat tangkap yang tidak Waktu kejadian
ramah lingkungan, seperti Keterangan
potassium, trawl dan
Data Ekonomi 1 : 250.000 bahan peledak ID Survei lapangan
1 : 50.000 Data tingkat kepentingan Koordinat
masyarakat terhadap Jenis aktivitas/
sumberdaya dalam kepentingan
memenuhi kebutuhan Luas area
ekonomi (tinggi, sedang, aktivitas/
rendah) kepentingan
Keterangan
67
Pertama, tahap sebelum penilaian perlindungan dan pemanfaatan
Keanekaragaman Hayati, mencakup kegiatan: (1) pengumpulan data
dan informasi, dan (2) penyusunan kriteria dan parameter (variabel);
Kedua, tahap penilaian, mencakup kegiatan: (1) penyiapan peta
identifikasi, (2) penilaian kesesuaian lokasi untuk zona konservasi
keanekaragaman hayati, (3) penilaian lanjut bagi lokasi yang sesuai untuk
dicadangkan sebagai kawasan konservasi kehati.
Ketiga, tahap setelah penilaian, mencakup kegiatan: (1)
pertimbangan dan penentuan zona lindung dan kawasan konservasi
kehati, (2) pengaturan zona lindung dan Kawasan konservasi kehati.
Kebutuhan Data dan Informasi untuk Perencanaan Kawasan
Konservasi Kehati
Setelah pengertian kawasan konservasi dipahami, maka pada tahap
awal perlu dicari dan/atau dikumpulkan data dan informasi yang relevan dan
mutakhir, agar proses penentuan dan pengaturan kawasan konservasi kehati
di suatu wilayah dapat dilakukan. Melalui data dan informasi yang dikumpulkan
(Tabel 7.3), maka kondisi kondisi fisik dan kondisi sumberdaya alam dan
ekosistem yang ada di wilayah tersebut dapat dideskripsikan dan diketahui
dengan baik, sebagai masukan untuk tahap berikutnya.
Kriteria Kawasan Konservasi Kehati
Untuk mengetahui apakah suatu wilayah di perairan darat atau
perairan pesisir dan laut itu sesuai/cocok atau tidak untuk dicadangkan
sebagai kawasan konservasi kehati, maka dapat diacu Permen-KP No. 30
Tahun 2010, yang disajikan pada Tabel 7.4 di bawah ini.
Tabel 7.4 Kriteria Kesesuaian Zonasi Konservasi Kehati
No Parameter Kriteria
1. Zona Inti (zona a) merupakan daerah pemijahan (spawning ground,
preservasi atau atau nesting area), pengasuhan (nursery ground)
zona lindung dan/atau alur ruaya (migrasi) biota;
penuh kehati) b) merupakan habitat biota perairan tertentu yang
prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau
kharismatik;
c) mempunyai keistimewaan keanekaragaman jenis
biota perairan beserta ekosistemnya;
d) mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili
keberadaan biota tertentu yang masih asli;
e) mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli
dan tidak atau belum diganggu manusia;
68
No Parameter Kriteria
f) mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin
kelangsungan hidup jenis-jenis biota tertentu untuk
menunjang pengelolaan perikanan atau eksploitasi
sumberdaya yang efektif dan menjamin berlangsungnya
proses bio-ekologis secara alami; dan
g) mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah
bagi Kawasan Konservasi Kehati Perairan.
2. Zona a) mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota
Pemanfaatan perairan, bentang alam beserta ekosistem perairan
berkelanjutan yang indah dan unik;
b) mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin
kelestarian potensial dan daya tarik untuk
dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
c) mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan
yang mendukung kepentingan konservasi; dan
d) mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik
untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak
merusak ekosistem aslinya.
3. Zona Lainnya a) fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona
tertentu di luar zona inti dan zona pemanfaatan;
b) dapat berupa antara lain zona perlindungan dan
zona rehabilitasi.
Sumber: Permen-KP No 30/2010
Kriteria Penetapan Zona Preservasi dan Kawasan Konservasi Kehati Perairan
Kriteria spasial yang digunakan untuk peta Rencana Tata Ruang, baik
RTRW maupun RZWP3K, adalah pada tingkat kawasan. Berdasar alokasi ruang
pada RTRW dan RZWP3K, jenis kawasan konservasi, informasi yang dimuat
meliputi berbagai tipe kawasan konservasi, yaitu Kawasan Konservasi Pulau-
Pulau Kecil (KP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi
Perairan (KKP), dan Kawasan Konservasi Sempadan Pantai (KKSP).
Selain perlu menetapkan kriteria penentuan suatu wilayah menjadi
kawasan konservasi, juga perlu diketahui kriteria penetapan zona pada
Kawasan konservasi di wilayah pesisir yang dituangkan dalam peta RZBWP-
3-K (Rencana Zonasi Bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
Setelah data dan informasi terkumpul, maka tahap selanjutnya
adalah menentukan apakah wilayah yang dikaji tersebut, memang sesuai
untuk dicadangkan alokasi ruangnya sebagai kawasan konservasi kehati
di WP3K atau tidak. Untuk penentuan alokasi ruang bagi Kawasan
konservasi kehati tersebut, maka perlu disusun kriteria kesesuaian, yang
akan dipakai sebagai acuan.
69
Penilaian suatu wilayah untuk dijadikan calon kawasan konservasi kehati
perairan di wilayah pesisir dan laut, dapat mengacu kepada kriteria penetapan
Kawasan Konservasi Perairan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah
No.60 Tahun 2007 tentang KSDI (konservasi sumberdaya ikan). Kriteria untuk
pencadangan kawasan konservasi tersebut adalah sebagai berikut:
Kriteria Ekologi, mencakup:
• Konservasi keanekaragaman hayati; kriteria ini digunakan untuk
menilai apakah suatu kawasan:
- Berperan dalam memelihara proses ekologi atau menjadi sistem
penyangga kehidupan.
- Merupakan habitat bagi satwa langka atau satwa yang terancam punah.
- Melindungi keanekaragaman genetik.
• Kealamiahan; kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu
kawasan masih memiliki kondisi biofisik yang belum mengalami
kerusakan dan belum mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas.
• Keterkaitan ekologis; kriteria ini digunakan untuk melihat adakah
hubungan fungsional antar ekosistem di suatu kawasan (misalnya
ekosistem estuaria dengan ekosistem mangrove dengan ekosistem
terumbu karang dan ekosistem padang lamun);.
• Keterwakilan; kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu
kawasan memiliki keanekaragaman hayati yang bersumber dari
ekosistem laut.
• Keunikan; kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kawasan
memiliki keunikan spesies, ekosistem, biodiversitas, atau bentang alam
• Produktivitas; kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu
kawasan memiliki produktivitas yang tinggi/optimal (terutama dari
aspek perikanan).
• Daerah Ruaya; kriteria ini di gunakan untuk melihat apakah suatu
kawasan merupakan daerah ruaya atau migrasi (untuk tujuan kawin
atau pemijahan) bagi suatu jenis ikan atau mamalia tertentu.
• Habitat Ikan Langka; kriteria ini digunakan untuk melihat apakah suatu
kawasan memiliki habitat yang sesuai dan dihuni oleh ikan langka/unik/
endemik/khas/dilindungi.
• Daerah Pemijahan Ikan (Spawning Ground); kriteria ini digunakan
untuk melihat apakah suatu kawasan merupakan habitat yang cocok
dan optimal bagi ikan untuk memijah.
70
• Daerah Asuhan (Nursery Ground); kriteria ini digunakan untuk melihat
apakah suatu kawasan memiliki kondisi ekosistem yang optimal bagi
pertumbuhan stadia awal kehidupan biota air (Anakan atau larva ikan
serta biota air lainnya).
Kriteria sosial dan Budaya
Kriteria sosial mencakup beberapa parameter, yaitu:
• Dukungan masyarakat; kriteria ini digunakan untuk menilai dukungan
masyarakat terhadap kegiatan konservasi keanekaragaman hayati perairan
• Potensi konflik kepentingan; kriteria ini untuk menilai kecil atau besarnya
potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam hayati serta ekosistemnya.
• Potensi ancaman; kriteria ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang
mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati perairan
pesisir.
• Potensi Sejarah Maritim; kriteria ini ini digunakan untuk melihat apakah
ada sejarah yang berlatar belakang kemaritiman yang perlu dilestarikan.
• Kearifan lokal; kriteria ini digunakan untuk melihat adakah pengetahuan
lokal/pengetahuan tradisional yang dapat membantu kelestarian
sumberdaya alam dan ekosistemnya.
• Adat istiadat; kriteria ini digunakan untuk menilai ada atau tidaknya adat
dan kebiasaan masyarakat yang dapat mendukung kegiatan konservasi
keanekaragaman hayati.
Kriteria Ekonomi
Kriteria ini mencakup beberapa parameter, yaitu:
• Nilai penting perikanan; kriteria ini digunakan untuk melihat nilai
penting sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan
budidaya serta kegiatan iringannya dalam suatu wilayah;
• Potensi rekreasi dan pariwisata; kriteria ini digunakan untuk melihat
apakah suatu kawasan memiliki potensi dalam rekreasi dan pariwisata
yang menunjang kegiatan konservasi (ekowisata atau eduekowisata);
• Estetika; kriteria ini digunakan untuk menilai keindahan alam dari suatu
perairan dan/atau biota yang memiliki daya tarik tertentu sehingga perlu
dilestarikan;
• Kemudahan mencapai lokasi; kriteria ini memperhatikan ketersediaan
akses dan kemudahan dalam mencapai lokasi kawasan yang dicadangkan
untuk keperluan konservasi keanekaragaman hayati dari berbagai daerah.
71
Selanjutnya kriteria yang tercantum di Tabel 7.5 dapat dijadikan
acuan untuk melihat syarat yang harus dipenuhi suatu wilayah untuk
dapat dijadikan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Kawasan
KEHATI), baik Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KKP3K),
Kawasan Konservasi Maritim (KKM) maupun Kawasan Konservasi
Perairan (KKP).
Tabel 7.5 Kriteria untuk Pencadangan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan
Kriteria Penetapan Kawasan Konservasi Kategori Kawasan Konservasi
Ekologi KKP3K KKM KKP
- Keanekaragaman Hayati
- Kealamiahan 3 13
- Keterkaitan Ekologis 3 v3
- Keterwakilan 3 v2
- Keunikan 3 v2
- Produktifitas 3 31
- Daerah Ruaya 2 v1
- Habitat Ikan (Biota): 2 11
- Khas/Unik/Langka/Endemik
- Dilindungi 2 v3
2 v3
• Daerah Pemijahan Ikan 3 v2
• Daerah Asuhan 2 v2
Sosial 1 31
- Dukungan Masyarakat 1 31
- Potensi Konflik Kepentingan 1 23
- Potensi Ancaman v 3v
- Potensi Sejarah Maritim v 1v
- Kearifan Lokal v 3v
- Adat-Istiadat
v 21
Ekonomi v 3v
- Nilai Penting Perikanan 1 31
- Potensi Rekreasi dan Pariwisata 1 31
- Estetika
- Kemudahan Mencapai Lokasi
72
Keterangan :
Angka 3 = Mutlak (harus dipenuhi dengan skor minimal 2)
Angka 2 = Utama (menjadi pertimbangan utama setelah syarat mutlak)
Angka 1 = Tambahan (syarat tambahan yang masuk dalam hitungan)
V = prasyarat (syarat yang tidak wajib dipenuhi dan tidak masuk
dalam hitungan)
Analisis Penilaian Parameter untuk Pencadangan Kawasan Konservasi Kehati
Setelah data dan informasi terkumpul, serta kriteria didapatkan, maka
Langkah berikutnya dilakukan analisis parameter (variabel) untuk menilai
apakah wilayah atau kawasan yang dikaji itu sesuai untuk dicadangkan
sebagai zona konservasi kehati atau tidak.
Apa sajakah parameter atau variable yang harus diperhitungkan
ke dalam penilaian ini? Serta, bagaimana menghitung skor dari setiap
parameter atau variabel tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu,
maka di bawah ini dijelaskan seluruh parameter atau variabel yang perlu
diperhitungkan, beserta rumus perhitungan skor dari setiap parameter.
1. Keanekaragaman hayati
Parameter ini hanya untuk tiga ekosistem utama di pesisir perairan
yaitu ekosistem terumbu karang (coral reefs ecosystem), padang lamun
(seagrass beds ecosystem) dan bakau (mangrove ecosystem), yaitu
dengan menghitung indek keanekaragaman jenis (species).
Indek keanekaragaman dapat dihitung dengan menggunakan
rumus indeks Shannon-Wiener yaitu:
Keterangan:
H’ = Indeks Keanekaragaman jenis
N = Jumlah total individu
Ni = Jumlah individu dalam genus ke-i
Hasil perhitungan di atas kemudian dapat dikelompokkan menjadi tiga
kriteria, yaitu:
• H < 1 = nilai indeks keanekaragaman Rendah (skor 1)
• H > 1 – 3 = nilai indeks keanekaragaman Sedang (skor 2)
• H > 3 = nilai indeks keanekaragaman Tinggi (skor 3)
73
2. Kealamiahan
Perhitungan kealamiahan ekosistem (habitat) dapat dilakukan
dengan menggunakan rumus yang mengacu kepada Yunia, C. (1996),
yaitu:
Or = (1-(Am/An))*100%
Keterangan:
Or = kealamiahan (%)
Am = luas ekosistem yang telah mengalami campur tangan manusia
An = luas ekosistem yang dinilai
Tingkat kealamiahan dapat dikelompokkan menjadi tiga kriteria, yaitu:
• > 75% = alami (skor 3)
• 50 ≤ Pr ≤ 75% = cukup alami (skor 2)
• < 50% = tidak alami (skor 1)
3. Keterkaitan Ekologis
Parameter ini ditujukan untuk melihat hubungan atau keterkaitan
antar ekosistem (mangrove, terumbu karang, padang lamun, lainnya)
yang ada di suatu wilayah perairan, dengan kriteria sebagai berikut:
• ≥75-100% = komponen ekosistem terkait sangat erat secara ekologis(skor
3)
• ≥50- <75% = komponen ekosistem terkait erat secara ekologis (skor 2)
•< 50% = komponen ekosistem terkait kurang erat secara ekologis
(skor 1)
4. Keterwakilan
Parameter ini mempertimbangkan keterwakilan ekosistem/habitat
yang bersangkutan terhadap kawasan yang dilindungi (konservasi)
di suatu wilayah biogeografi atau pulau tertentu yang dikaji, dengan
perhitungan sebagai berikut:
Pr = (E Ec/EEs)*100%c
Keterangan:
Pr = Keterwakilan (%)
EEc = Jumlah tipe ekosistem di kawasan yang dinilai
EEs = Jumlah ideal tipe ekosistem yang ada di suatu wilayah
(biogeografi atau pulau).
74
Tingkat keterwakilan dapat dikelompokkan menjadi tiga kriteria
sebagai berikut:
• Pr ³ 75% = terwakili (skor 3)
• 40 £ Pr < 75% = cukup terwakili (skor 2)
• Pr < 40% = tidak terwakili (skor 1)
5. Keunikan
Nilai keunikan ini memperhitungkan apakah jenis flora/fauna
ataupun ekosistem tersebut hanya ada di wilayah yang dikaji, atau
banyak ditemukan di tempat lain.
Tingkat keunikan dapat digolongkan ke dalam tiga kriteria sebagai
berikut:
• Unik = hanya terdapat di satu daerah di Indonesia (skor 3)
• Cukup unik = terdapat di beberapa daerah dalam satu wilayah
biogeografi yang sama (skor 2)
• Tidak unik = banyak terdapat di wilayah Indonesia (skor 1)
6. Produktivitas
Produktivitas dapat diperoleh melalui perhitungan biomassa ikan
atau biota perairan lainnya, dan tingkatannya dapat digolongkan
menjadi tiga kriteria sebagai berikut:
• Produktivitas tinggi (> 1200 kg/Ha/satuan waktu) = skor 3
• Produktivitas sedang (600–1200 Kg/Ha/satuan waktu) = skor 2
• Produktivitas rendah (< 600 Kg/Ha/satuan waktu) = skor 1
7. Daerah Ruaya (Migrasi pemijahan)
Parameter ini untuk mengetahui apakah suatu wilayah menjadi
jalur migrasi bagi suatu jenis ikan, atau mamalia laut tertentu yang
dilindungi, langka, atau terancam punah, contohnya: Paus, Paus Hiu,
Lumba lumba, Pesut, Penyu, Sidat. Wilayah perairan yang merupakan
jalur migrasi biota kategori tersebut akan mendapatkan nilai yang tinggi.
Kategori untuk parameter (variabel) ini adalah sebagai berikut:
• Banyak (>1) jenis ikan yang beruaya = skor 3
• Sedikit (1) jenis ikan yang beruaya = skor 2
• Tidak ada ikan yang beruaya = skor 1
75
8. Habitat Ikan Khas/Langka/Unik/Endemik dan Dilindungi
Penilaian dibuat terpisah antara ikan langka/unik/endemik/khas dan
ikan yang dilindungi. Hal ini untuk menentukan apakah lokasi tersebut
akan dijadikan Suaka Perikanan (fisheries sanctuary) atau lebih cocok
untuk Taman Perairan (Aquatic Park)
Kriteria penilaian ikan yang khas/langka/unik/endemik adalah
sebagai berikut:
• Ada >2 jenis ikan khas/langka/unik/endemik = skor 3
• Hanya satu atau dua jenis ikan khas/langka/unik/endemik = skor 2
• Tidak ada ikan langka khas/langka/unik/endemik = skor 1
Kategori penilaian ikan yang dilindungi adalah sebagai berikut:
• Ada >2 jenis ikan dilindungi = skor 3
• Ada dua jenis ikan dilindungi = skor 2
• Ada satu jenis ikan dilindungi = skor 1
9. Daerah Pemijahan (spawning ground atau nesting area) Ikan
Parameter ini untuk menetapkan apakah suatu wilayah perairan itu
harus dilindungi karena menjadi tempat pemijahan dari beberapa jenis
ikan penting.
Penilaian dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:
• Terdapat >2 lokasi pemijahan ikan = skor 3
• Terdapat 2 lokasi pemijahan ikan = skor 2
• Terdapat 1 lokasi pemijahan ikan = skor 1
10. Daerah Pengasuhan (nursery ground)
Khusus parameter ini, yang dilihat adalah keberadaan ekosistem lamun,
terumbu karang dan mangrove, sebagai daerah pengasuhan ikan.
Kriteria penilaian terhadap daerah pengasuhan adalah sebagai berikut:
• Terdapat ekosistem lamun dan mangrove, atau terumbu karang = skor 3
• Terdapat salah satu ekosistem lamun, terumbu karang atau mangrove =
skor 2
• Tidak terdapat ekosistem yang berfungsi untuk nursery ground = skor 1
11. Dukungan Masyarakat
Untuk mendapatkan informasi mengenai dukungan masyarakat
sekitar, maka dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner.
Tingkat dukungan masyarakat yang tinggi sangat bergantung pada
jumlah responden (masyarakat sekitar) yang menyetujui keberadaan
Kawasan konservasi kehati sesuai usulan.
76
Am = (Eps/Epo)x100%
Keterangan:
Am = Aspirasi masyarakat
Eps = Jumlah penduduk yang setuju
Epo = Jumlah responden
Tingkat dukungan masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga
kriteria, yaitu:
• ≥ 75% = mendukung (skor 3)
• ≥ 40 - <75% = cukup mendukung (skor 2)
• < 40% = tidak mendukung (skor 1)
12. Potensi Konflik Kepentingan (conflict stakeholder analysis)
Potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam penting untuk dinilai, karena suatu kawasan tidak
dapat dikelola dengan baik, dengan adanya konflik.
Potensi konflik dapat dikaji melalui wawancara dengan setiap
perwakilan masyarakat, menelaah rencana tata ruang pemanfaatan
kawasan, dan juga mencermati potensi konflik yang berasal dari faktor
politik dan kepentingan ekonomi daerah.
Penilaian potensi konflik dapat dikelompokkan sebagai berikut:
• Berpotensi konflik tinggi = skor 1
• Berpotensi konflik sedang = skor 2
• Kurang berpotensi konflik = skor 3
13. Potensi Ancaman
Potensi ancaman bagi kelestarian keanekaragaman hayati pada
sumberdaya pesisir dan laut antara lain adalah pemanfaatan berlebih,
penangkapan ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi
fisik habitat, pencemaran, perubahan iklim, bencana alam, dan kegiatan
antropogenik lainnya yang merusak.
Penilaian potensi ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga
kriteria sebagai berikut:
• Berpotensi ancaman tinggi (terdapat > 5 faktor ancaman) = skor 1
• Berpotensi ancaman sedang (terdapat ≥2 hingga 5 faktor ancaman)
= skor 2
• Kurang berpotensi ancaman (terdapat < 2 faktor ancaman) = skor 3
77
14. Potensi Sejarah Maritim
Parameter ini diperoleh dari kajian keberadaan sejarah maritim
yang dimiliki yang dapat menunjang pengelolaan zona konservasi
keanekaragaman hayati.
Penilaian potensi sejarah maritim dapat dikelompokkan sebagai berikut:
• Memiliki sejarah maritim yang menunjang konservasi = skor 3
• Memiliki sejarah maritim tetapi tidak efektif = skor 2
• Tidak memiliki sejarah maritim = skor 1
15. Kearifan Lokal
Kearifan lokal masyarakat akan sangat mendukung pengelolaan
kawasan konservasi keanekaragaman hayati.
Penggolongan ada/tidaknya kearifan lokal dapat dinyatakan sebagai
berikut:
• Memiliki kearifan lokal yang menunjang konservasi = skor 3
• Memiliki kearifan lokal tetapi tidak efektif = skor 2
• Tidak memiliki kearifan lokal = skor 1
16. Adat Istiadat
Adat Istiadat masyarakat sangat menunjang dalam menjaga
kawasan konservasi.
Penilaian terhadap parameter ini adalah sebagai berikut:
• Memiliki adat istiadat yang menunjang konservasi = skor 3
• Memiliki adat istiadat tetapi tidak efektif = skor 2
• Tidak memiliki adat istiadat = skor 1
17. Nilai Penting Perikanan
Nilai penting perikanan dapat diperoleh dengan menganalisis
ekonomi wilayah. Analisis ekonomi wilayah dilakukan dengan
menghitung LQ (Location Quotient). Analisis dengan model LQ ini
digunakan untuk melihat sektor basis atau non basis dari suatu wilayah
perencanaan, serta dapat mengidentifikasi adanya sektor unggulan
atau keunggulan komparatif suatu wilayah.
Pendekatan dengan menggunakan metoda LQ ini adalah dengan
menganalisis nilai PDRB sub sektor i di suatu provinsi, dengan rumus
sebagai berikut:
78
LQij = Xij / Xi.
Xj / X ..
Keterangan:
Lqij = indeks kuosien lokasi
Xij = jumlah PDRB Provinsi yang dinilai pada sub sektor Perikanan
Xi. = jumlah PDRB Nasional yang dinilai pada sub sektor Perikanan
X.J = jumlah PDRB total di Propinsi yang dinilai
X.. = jumlah PDRB total di Nasional yang dinilai
Penilaian dari hasil perhitungan LQ dapat dikelompokkan dalam tiga
kriteria sebagai sebagai berikut:
• LQ > 1 = skor 3
• LQ = 1 = skor 2
• LQ < 1 = skor 1
18. Potensi Rekreasi dan Pariwisata
Adanya potensi pariwisata di suatu daerah yang akan menjadi
kawasan konservasi juga penting untuk diperhatikan. Potensi pariwisata
ini dapat diketahui dengan menelaah informasi tentang ada/tidaknya
potensi aktivitas pariwisata bahari yang ramah lingkungan seperti
menyelam, snorkeling, memancing, pantai pasir putih, dan surfing.
Informasi tersebut dapat kita peroleh dari cluster yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pariwisata and Ekonomi Kreatif.
Penilaian untuk potensi rekreasi dan pariwisata dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
• Berpotensi tinggi (apabila terdapat > 3 jenis wisata) = skor 3
• Cukup berpotensi (apabila terdapat 1–3 jenis wisata) = skor 2
• Kurang berpotensi (apabila tidak ada potensi) = skor 1
19. Estetika
Parameter ini merupakan parameter keindahan alam, kebersihan
lingkungan dan kenyamanan.
Tingkat estetika suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai berikut:
• Memiliki estetika tinggi = skor 3
• Memiliki estetika cukup = skor 2
• Estetika rendah = skor 1
79
20. Kemudahan Pencapaian Lokasi (Akses)
Aksesibilitas dapat dinilai dengan memperhatikan ketersediaan jalan
masuk (akses) atau jalan, atau transportasi air yang menghubungkan
kota-kota terdekat ke obyek-obyek menarik di dalam kawasan.
Penilaian aksesibilitas dilakukan melalui perhitungan frekuensi
kendaraan yang menuju kawasan sesuai dengan rumus di bawah ini:
Kp = EOc *100%
EOs
Keterangan:
Kp = Aksesibilitas (%)
Eoc = Frekuensi kendaraan yang menuju obyek menarik
Eos = Frekuensi kendaraan yang optimum menuju obyek menarik
Tingkat kemudahan pencapaian lokasi digolongkan menjadi tiga
kriteria sebagai berikut:
• Kp > 75% = mudah dicapai (skor 3)
• 40 £ Kp £ 75% = dapat dicapai (skor 2)
• Kp < 40% = sulit dicapai (skor 1)
Setelah diketahui cara menghitung skor dari setiap parameter,
selanjutnya perlu disusun matriks yang berisi penggolongan skor ke
dalam skala/skor 1-3, dengan penjelasan sebagai berikut:
• Skor 1 =tidak sesuai untuk dicadangkan sebagai kawasan konservasi
• Skor 2 = sesuai untuk dicadangkan sebagai kawasan konservasi
• Skor 3 = sangat sesuai untuk dicadangkan sebagai kawasan konservasi
Dengan adanya matriks penggolongan tersebut, maka dapat
dilakukan penilaian kesesuaian untuk zona preservasi dari suatu
Kawasan konservasi atau wilayah yang telah dianalisis setiap
parameternya. Contoh matriks penggolongan skor tersebut dapat
dilihat pada Tabel 7.6 berikut.
80
Tabel 7.6 Penggolongan Skor untuk Penilaian Kesesuaian Zona pada Kawasan Konservasi
di WP3K
Kriteria Penetapan Kawasan Konservasi 3 = Sangat Skor 1 = Tidak
Sesuai 2 = Sesuai sesuai
Ekologi
- Keanekaragaman Hayati (H’) Tinggi Sedang Rendah
- Kealamiahan (Or) >75% 50%≤ Or ≤ 75% ≤50%
- Keterkaitan Ekologis ≥75% - 100% 50% - <75% ≤50%
- Keterwakilan (Pr) ≥75% - 100% 40%≤ Pr ≤ 75% ≤40%
- Keunikan (sebaran flora, fauna, ekosistem) Unik Cukup unik Tidak unik
- Produktifitas (biomassa kg/Ha) >1.200 >600 - ≤1.200 ≤600
- Daerah Ruaya (Jenis Ikan) >1 1 0
- Habitat Ikan:
Khas/Unik/Langka/Endemik (Jenis Ikan) >2 21
Dilindungi (Jenis Ikan) >2 21
- Daerah Pemijahan Ikan (lokasi) >2 21
- Daerah Asuhan (ekosistem) 2 10
Sosial ≥75% >40% - <75% ≤40%
- Dukungan Masyarakat (Dukungan) Kurang Sedang Tinggi
- Potensi Konflik Kepentingan >5 >2 - ≤5 ≤2
- Potensi Ancaman (Faktor Ancaman) efektif Kurang efektif Tidak ada
- Potensi Sejarah Maritim (Mendukung) efektif Kurang efektif Tidak ada
- Kearifan Lokal (Ada dan Mendukung) efektif Kurang efektif Tidak ada
- Adat-Istiadat (Ada dan Mendukung)
Ekonomi >1 =1 <1
- Nilai Penting Perikanan (LQ) >3 1-≤3 Tidak ada
- Potensi Rekreasi dan Pariwisata (jenis) Tinggi Cukup Tidak memadai
- Estetika (kesehatan dan kebersihan) ≥75% >40% - <75% ≤40%
- Kemudahan Mencapai Lokasi
Penilaian Pencadangan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan
Penilaian kesesuai untuk pencadangan Kawasan konservasi
keanekaragaman hayati perairan mencakup tahapan sebagai berikut:
1. Menyusun peta identifikasi (Peta Paket Sumberdaya)
2. Penilaian kesesuaian lokasi untuk zona konservasi WP3K
3. Penilaian lanjut bagi lokasi yang sesuai untuk zona konservasi WP3K,
untuk mengetahui apakah sesuai untuk dijadikan zona konservasi
KKP3K, KKM atau KKP
Yang perlu dilakukan pertama kali ialah menyusun peta identifikasi
untuk pencadangan kawasan konservasi kehati. Peta identifikasi untuk
kawasan konservasi kehati dapat disusun melalui proses identifikasi, yang
81
dapat dilakukan dengan cara: Interpretasi citra digital, Interpretasi peta
dasar, dan Inferensi data sekunder yang tervalidasi atau diverivikasi.
Setelah diperoleh peta hasil identifikasi, maka setiap lokasi di dalam
suatu wilayah yang dicadangkan untuk kawasan konservasi (misalnya:
A, B, C, D, F, G, H, I) kemudian dinilai dengan sistem penilaian yang
tercantum pada Tabel 7.7.
Tabel 7.7 Sistem Penilaian Kesesuaian Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati
No Parameter ABCDE FGH I
EKOLOGI 333322322
1 Keanekaragaman Hayati 233311112
2 Kealamiahan 323221311
3 Keterkaitan Ekologis 212211111
4 Keterwakilan 112211113
5 Keunikan 131311122
6 Produktivitas 111211113
7 Daerah Ruaya 111111313
8 Habitat Ikan Langka 232222231
9 Daerah Pemijahan Ikan 333312221
10 Daerah Pengasuhan
SOSIAL DAN BUDAYA 323312122
1 Dukungan Masyarakat 222322222
2 Potensi Konflik kepentingan 313322222
3 Potensi Ancaman 211111111
4 Potensi Sejarah Maritim 111111112
5 Kearifan Lokal 212211112
6 Adat Istiadat
EKONOMI
1 Nilai Penting Perikanan 233322222
2 Potensi Rekreasi dan Pariwisata 3 3 3 3 2 2 2 2 3
3 Estetika 232211112
4 Kemudahan Mencapai Kawasan 3 3 3 2 3 3 3 2 3
Nilai Keseluruhan 42 41 44 46 29 30 34 31 40
Dari hasil penilaian tersebut, maka lokasi yang memperoleh nilai
keseluruhan ≥ 40 akan terpilih untuk dicadangkan sebagai kawasan
konservasi keanekaragaman hayati.
82
Selanjutnya diperlukan penilaian lanjut terhadap lokasi-lokasi yang
memiliki skor ≥ 40, yang sesuai untuk dijadikan kawasan konservasi kehati.
Penilaian lanjut dilakukan kemudian untuk menilai kessuaian dari setiap
lokasi untuk dijadikan kawasan konservasi kehati, antara lain: KKP3K,
KKM, atau KKP. Contoh cara penilaian lanjut tersebut dapat dilihat pada
tabel 7.8 berikut ini:
Tabel 7.8 Contoh Hasil Penilaian Kesesuaian Kawasan Konservasi Kehati alternatif 1
Skoring KKP3K KKM KKP
(S)
No Kriteria Penetapan Kawasan A Bobot BxS Bobot BxS Bobot BxS
(B) (B) (B)
EKOLOGI
1 Keanekaragaman Hayati 34 12 2 64 12
2 Kealamiahan 24 81 24 8
3 Keterkaitan Ekologis 34 12 1 33 9
4 Keterwakilan 24 81 23 6
5 Keunikan 14 41 42 2
6 Produktivitas 13 31 12 2
7 Daerah Ruaya 13 32 22 2
8 Habitat Ikan Langka 13 31 14 4
9 Daerah Pemijahan Ikan 24 81 23 6
10 Daerah Pengasuhan 33 91 33 9
SOSIAL DAN BUDAYA 3 1 34 12 2 6
1 Dukungan Masyarakat 2 1 24 82 4
2 Potensi Konflik kepentingan 3 1 33 94 12
3 Potensi Ancaman 2 1 24 81 2
4 Potensi Sejarah Maritim 1 1 12 21 1
5 Kearifan Lokal 2 1 24 81 2
6 Adat Istiadat
EKONOMI
1 Nilai Penting Perikanan 2 2 43 62 4
2 64 12 1 3
2 Potensi Rekreasi dan Pariwisata 3 2 44 82 4
2 64 12 2 6
3 Estetika 2 48 103 48 111 48 104
0,94 1,01 0,95
4 Kemudahan Mencapai Kawasan 3
Total Nilai 42
Nilai Scoring
Rumus untuk mendapatkan nilai scoring adalah sebagai berikut:
Nilai Scoring = Total Nilai (Bobot x Scoring)
Jumlah (Bobot + Scoring + Parameter)
83
84 Berdasarkan Tabel 8, maka diketahui bahwa nilai scoring tertinggi jatuh pada kategori KKM, yaitu sebesar 1,01,
oleh karena itu maka lokasi yang dinilai melalui Tabel 8 (zona konservasi alternatif-1), lebih cocok untuk dijadikan zona
konservasi KKM, dibandingkan untuk dijadikan zona konservasi KKP3K ataupun KKP.
Di bawah ini diberikan satu contoh penilaian lagi, yakni pada Tabel 9.
Tabel 7.9 Contoh Hasil Penilaian Kesesuaian Zona Konservasi Kehati Alternatif 2
Skoring KKP3K KKM KKP
(S)
No Kriteria Penetapan Kawasan B Bobot BxS Bobot BxS Bobot BxS
(B) (B) (B)
EKOLOGI
1 Keanekaragaman Hayati 3 4 12 2 64 12
2 Kealamiahan
3 Keterkaitan Ekologis 3 4 12 1 34 12
4 Keterwakilan
5 Keunikan 2 4 81 23 6
6 Produktivitas
7 Daerah Ruaya 1 4 41 23 3
8 Habitat Ikan Langka
9 Daerah Pemijahan Ikan 1 4 41 42 2
10 Daerah Pengasuhan
3 3 91 32 6
1 3 32 22 2
1 3 31 14 4
3 4 12 1 33 9
3 3 91 33 9
Skoring KKP3K KKM KKP
(S)
No Kriteria Penetapan Kawasan B Bobot BxS Bobot BxS Bobot BxS
(B) (B) (B)
SOSIAL DAN BUDAYA
1 Dukungan Masyarakat 2 1 24 82 4
2 Potensi Konflik kepentingan
3 Potensi Ancaman 2 1 24 82 4
4 Potensi Sejarah Maritim
4 Kearifan Lokal 1 1 13 34 4
5 Adat Istiadat
1 1 14 41 1
1 1 12 21 1
1 1 14 41 1
EKONOMI 3 2 63 92 6
1 Nilai Penting Perikanan
2 Potensi Rekreasi dan Pariwisata 3 2 64 12 1 3
3 Estetika 3 2 64 12 2 6
4 Kemudahan Mencapai Kawasan 3 2 64 12 2 6
Total Nilai 41 48 108 48 103 48 93
Nilai Skoring 0,99 0,94 0,85
85 Pada contoh penilaian pada Tabel 9, diperoleh scoring tertinggi jatuh pada kategori KKP3K, yaitu sebesar 99,0,
sehingga zona konservasialternatif 2 tersebut lebih cocok untuk dijadikan kawasan konservasi KKP3K.
Pengaturan kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Setelah menyelesaikan tahap pertimbangan dan penentuan
Kawasan konservasi kehati, maka tahap akhir yang perlu dilakukan adalah
penetapan batas-batas (delineasi) dan mintakat di kawasan konservasi.
Mengapa pengaturan zona konservasi kehati itu penting dilakukan?
Jika tidak dilakukan pengaturan, maka terjadi tumpeng tindih kegiatan atau
jenis pemanfaatan lainnya yang dapat merugikan aktivitas konservasi,
dapat menjadi satu di dalam zona konservasi tersebut. Dua jenis
pemanfaatan yang berbeda dapat saja disatukan di dalam suatu wilayah,
dengan syarat harus terjadi sinergi dan harmoni, tidak saling bertentangan
atau merugikan. Untuk itu maka diperlukan pengaturan kegiatan dari
berbagai jenis pemanfaatan di suatu wilayah.
Pengaturan kegiatan atau pemanfaatan tersebut dilakukan melalui
penyusunan matriks zona/subzona konservasi dengan zona/sub zona
lainnya. Setiap jenis pemanfaatan lainnya kemudian dihubungkan
dengan subzona-subzona konservasi, untuk mengetahui apakah jenis
pemanfaatan tersebut mengganggu atau tidak terhadap kepentingan
konservasi.
Terkait hubungannya dengan kawasan konservasi, maka setiap jenis
pemanfaatan lain harus diidentifikasi dan ditelaah, agar dapat dimasukkan
ke dalam salah satu di antara empat kategori di bawah ini:
1) Pemanfaatan yang dibolehkan, diizinkan, atau direkomendasikan (I)
2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)
3) Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)
4) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X)
Jenis kegiatan apa sajakah yang masih diperbolehkan di zona/
subzona konservasi? Pada Tabel 10 dapat diketahui jenis kegiatan apa
saja yang masuk kategori: (1) Boleh (direkomendasikan, Kategori I), (2)
Tidak Boleh atau Dilarang (Kategori X), (3) Boleh Bersyarat (diperbolehkan
setelah mendapat ijin: Kategori T dan B) di dalam setiap subzona kawasan
konservasi. Dengan mengacu ketentuan pada Tabel 10 tersebut, maka
dapat dibuat matrik pengaturan kegiatan dari setiap jenis pemanfaatan
di setiap subzona di Kawasan konservasi kehati, sebagaimana yang
tercantum pada Tabel 10.
86
Tabel 7.10 Pengaturan Kegiatan di Kawasan Konservasi Kehati
Zona pada Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan
Konservasi Deskripsi Ketentuan Umum Keterangan
Kegiatan a) perlindungan proses ekologis yang menunjang
Zona Inti zona inti yang dimanfaatkan
antara lain: Perlindungan mutlak kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya
Zona perlindungan mutlak habitat habitat dan populasi ikan; ikan dan ekosistemnya;
Pemanfaatan b) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat
dan populasi ikan serta alur mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan
Terbatas migrasi biota laut; dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau;
perlindungan ekosistem c) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
pesisir unik dan/atau rentan
terhadap perubahan; Penelitian; a) penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk
pengumpulan data dasar;
perlindungan situs budaya
atau adat tradisional; b) Penelitian terapan menggunakan metode survei untuk
penelitian; dan/ tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi; dan/atau
ataupendidikan.
c) Pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.
Pendidikan. diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan
material langsung dari alam.
zona pemanfaatan terbatas, perlindungan dan a) perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang
yang dijabarkan dalam sub pelestarian habitat dan kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya
zona antara lain: populasi ikan;
perlindungan habitat dan alam hayati dan ekosistemnya;
populasi ikan; b) penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang
pariwisata dan rekreasi;
penelitian dan pengembang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi
an; dan /atau pendidikan. kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
c) pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya
87 untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara
populasi dengan daya dukung habitatnya;
d) perlindungan alur migrasi biota perairan; dan
e) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
88 Zona pada Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan
Konservasi Deskripsi Ketentuan Umum Keterangan
Kegiatan
pariwisata dan rekreasi; a) berenang;
b) menyelam;
c) pariwisata tontonan;
d) pariwisata minat khusus;
e) perahu pariwisata;
f) olahraga permukaan air; dan
g) pembuatan foto, video dan film.
penelitian dan a) penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan
pengembangan; dan konservasi;
b) penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan
konservasi; dan
c) pengembangan untuk kepentingan konservasi.
pendidikan. a) pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati;
b) perlindungan sumber daya masyarakat lokal;
c) pembangunan perekonomian berbasis ekowisata
bahari;
d) pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung
kehidupan;
e) promosipemanfaatansumberdayasecaraberkelanjutan;
dan
f) promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan
kawasan konservasi perairan.
Zona Lainnya zona lain sesuai dengan Rehabilitasi
peruntukan Kawasan,
yang dimanfaatkan untuk
rehabilitasi.
Sumber: Permen-KP No 30/2010 yang diperbarui dengan Permen-KP No 31/2020
Tabel 7.11 Contoh Pengaturan Kegiatan di Zona Kawasan
No Kegiatan Zona Kawasan Konservasi
Zona Inti Zona Pemanfaatan Terbatas Zona Lainnya
Kawasan Pemanfaatan Umum
1 Perikanan tangkap XX I
XX I
Penangkapan ikan demersal
Penangkapan ikan pelagis
2 Perikanan Budidaya XX I
Budidaya kerapu XX I
Budidaya udang XX I
Budidaya rumput laut XX I
Budidaya kerang XX I
Budidaya mutiara
3 Pariwisata XI I
Wisata selam XI I
Wisata rekreasi pantai dan air XI I
Wisata olahraga air
4 Permukiman X- -
Permukiman nelayan X- -
Permukiman non nelayan
89 5 Pelabuhan X X
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan X
Kepentingan (DLKP)
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search