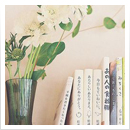menggunakan garis sebagai media komunikasi, seperti huruf paku peninggalan
bangsa Phoenicia (abad 12-10 Sm) yang berupa goresan-goresan. Disamping
potensi garis sebagai pembentuk kontur, garis merupakan elemen untuk
mengungkapkan gerak dan bentuk. Baik bentuk dua dimensi maupun tiga
dimensi. Suasana garis dalam hubungannya sebagai elemen seni rupa, garis
memiliki kemampuan untuk mengungkapkan suasana. Suasana yang tercipta
dari sebuah garis terjadi karena proses stimulasi dari bentuk-bentuk sederhana
yang sering kita lihat di sekitar kita, yang terwakili dari bentuk garis tersebut.
Sebagai contoh adalah bila kita melihat garis ‘S’, atau yang sering disebut ‘Line of
beauty’ maka kita akan merasakan sesuatu yang lembut, halus dan gemulai.
Perasaan ini terjadi karena ingatan kita mengasosiasikannya dengan bentuk-
bentuk yang dominan dengan bentuk lengkung seperti penari atau gerak ombak di
laut, (Anonim :2012).
Karakter garis merupakan bahasa rupa dari unsur garis, baik untuk garis
nyata maupun garis semu. Bahasa garis ini sangat penting dalam penciptaan
karya seni untuk menciptakan karakter yang diinginkan. Bentuk tugu misalnya
dapat diterjemahkan ke dalam bentuk garis vertikal, bangunan rumah yang
mendatar dapat diterjemahkan kedalam bentuk garis mendaftar. Brikut ini
beberapa karakter garis tersebut, (Sadjiman 2005:80).
a. Garis horisontal
Garis horisontal atau garis mendatar air mengasosiasikan cakrawala laut
mendatar, pohon tumbang orang/mati dan lain-lain benda yang panjang
mendatar. Garis horisontal memberi karakter terkenal, damai, pasif dan kaku.
Melambangkan ketenangan, kedamaian dan kemantaban, (Sadjiman 2005:80).
b. Garis vertikal
Garis vertikal atau garis tegak ke atas mengasosiasikan benda- benda yang
berdiri tegak lurus seperti batang pohon, orang beridri, tugu dan lain-lain,
mengesankan keadaan tak bergerak, suatu yang meleset menusuk langit
mengesankan agung, jujur, tegas, cerah, cita-cita/pengharapan. Garis vertikal
memberikan karakter keseimbangan, megah, kuat, tetapi statis, kaku.
Melambangkan kestabilan/ keseimbangan, kemegahan, kekuatan, kekokohan,
kejujuran dan kemashuran, (Sadjiman 2005:80).
c. Garis diagonal
Garis diagonal atau garis miring kekanan atau kekiri mengasosiasikan
orang lari, kuda meloncat, pohon doyong dan obyek yang mengesankan keadaan
yang tak seimbang dan menimbulkkan gerakan akan jatuh. Garis diagonal
memberikan karakter gerakan (movement), gerak lari/meluncur, dinamik, tak
seimbang, gerak gesit, lincah, kenes, menggetarkan. Melambangkan
kedinamisan, kegesitan, kelincahan dan kekenesan, (Sadjiman 2005:80).
Kajian Seni SD 45
d. Garis zig-zag
Garis zig-zag merupakan garis lurus patah-patah bersudut runcing yang
dibuat dengan gerakan naik turun secara cepat spontan merupakan gabungan dari
garis-garis vertikal dan diagonal memberi sugesti semangat dan gairah.
Karenanya diasosiasikan sebagai petir/kilat, letusan, retak-retak tembok dan
semacamnya, sehingga mengesankan bahaya. Garis zig-zag memberi karakter
gairah, semangat, bahaya, mengerikan. Karena dibuat dengan tikungan-tikungan
tajam dan mendadak maka mengesankan, kilau irama musik seperti rolling stone,
rock, mental, dan semacamnya. Melambangkan gerak semangat, kegairahan dan
bahaya, (Sadjiman 2005:80).
e. Garis lengkung
Garis lengkung meliputi lengkung mengapung, lengkung kubah,
lengkung busur, memberi kualitas mengapung seperti pelampung
mengasosiasikan gumpalan asap, buih sabun, balon dan semacamnya,
mengesankan gaya mengapung, ringan dan dinamik. Garis ini memberi karakter
ringan, dinamis, kuat serta melambangkan kemegahan, kekuatan dan
kedinamikaan, (Sadjiman 2005:80).
f. Garis lengkung S
Garis lengkung S atau atau garis lemah gemulai merupakan garis
lengkung majemuk atau lengkung ganda. Garis ini dibuat dengan gerakan
melengkung ke atas bersambung melengkung kebawah atau melengkung ke
kanan bersambung melengkung ke kiri, yang merupakan gerakan indah. Garis
indah ini merupakan garis terindah dari semua garis, yang memberikan asosiasi
gerakan ombak, padi/rumput tertiup angin, pohon tertiup angin, gerakan lincah
bocah/ anak binatang, dan semacamnya. Garis lengkung S memberi karakter
indah, dinamis, luwes. Melambangkan keindahan, kedinamisan dan keluwesan,
(Sadjiman 2005:80).
46 Pengantar
Gambar 1. Contoh garis (Sadjiman 2005:74)
3. Bidang
Unsur seni rupa yang berikut adalah bidang. Bidang menurut Sadjiman,
(2009:117) adalah suatu bentuk raut pipih, datar sejajar dengan dimensi panjang
dan lebar serta menutup permukaan. Bentuk-bentuk yang pipih/ gepeng seperti
tripleks, kertas, karton, seng, papan tulis dan bidang latar yang lainnya.
Bidang juga dapat diartikan sebagai bentuk yang menempati ruang dan
bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra. Bidang yang
menempati ruang dapat membentuk datar sejajar tafril yang memiliki panjang
dan lebar, atau dapat berbentuk maya yaitu bidang yang seolah-olah membuat
sudut dengan tafril sehingga seperti memiliki kedalaman tetapi semu. Bidang
sebagai ruang merupakan ruang dwimatra dan merupakan tempat dimana objek-
obyek berada yang dapat berwujud triplek, kertas, karton, seng, papan tulis,
kanvas dan lain-lain semacamnya, yang walaupun memiliki ketebalan, sehingga
hanya berdimensi panjang dan lebar, (Sadjiman 2005:83).
Macam-macam bentuk bidang meliputi bidang geometri dan bidang non
geometri. Bidang geometri adalah bidang teratur yang dibuat secara matematika,
seperti segi tiga, segi empat, segi lima, segi enam, segi delapan, lingkaran dan
bidang yang mempunyai bentuk yang teratur. Sedangkan bidang non geometri
adalah bidang yang dibuat secara bebas, atau bisa juga dikatakan bidang organik,
bidang bersudut bebas, bidang gabungan, dan bidang maya. Bidang organik yaitu
bidang-bidang yang dibatasi garis lengkung-lengkung bebas, bidang bersudut
bebas yaitu bidang-bidang yang dibatasi garis patah-patah bebas, bidang
gabungan yaitu bidang gabungan antara lengkung dan bersudut, (Sadjiman
2005:84).
Selain bentuk bidang yang rata sejajar tafril, terdapat bidang yang bersifat
maya, yaitu bentuk bidang yang seolah meliuk, bentuk bidang yang seolah miring
membentuk sudut dengan tafril/membentuk perspektif, bentuk bidang yang
seolah bersudut-sudut, bentuk bidang yang seolah muntir. Bentuk apa saja di
Kajian Seni SD 47
alam ini dapat disederhanakan menjadi bentuk bidang dengan geometri, non
geometri, atau bidang gabungan seperti pohon, rumah, kuda, gitar dan lain-lain
yang bersifat datar/dekoratif sebagai ciri khasnya, (Sadjiman 2005:84).
Bidang geometri
Bidang non geometri
Bidang bersudut-sudut bebas
Bidang gabungan
Bidang maya
Gambar 2. Macam-macam bidang (Sadjiman, 2005:85).
4. Bentuk
Bentuk merupakan sebuah istilah yang memiliki beberapa pengertian,
dalam seni dan perancangan, istilah bentuk seringkali dipergunakan untuk
menggambarkan struktur formal sebuah pekerjaan yaitu cara dalam menyusun
dan mengkoordinasi unsur-unsur dan bagian-bagian dari suatu komposisi untuk
menghasilkan suatu gambaran nyata.
Bentuk dikemukakan Kartika, (2009:30) sebagai totalitas dari pada karya
seni. Bentuk merupakan organisasi atau satu kesatuan atau komposisi dari unsur-
unsur pendukung karya. Menurut Sadjiman, (2009:93) Bentuk adalah wujud,
rupa, bangun atau gambaran tentang apa saja yang ada di alam termasuk karya
seni atau desain yang dapat disederhanakan menjadi, titik, garis danbidang.
48 Pengantar
Sementara itu Usman (2010:17) mengungkapkan bahwa bentuk adalah
pengorganisasian unsur-unsur dasar dari semua perwujudan dalam seni rupa
yang meliputi titik, garis, cahaya, tekstur, massa, ruang dan isi. Elemen-elemen
formal ini diorganisir sehingga menjadi prinsip-prinsip desain yang
mengorganisir elemen-elemen visual sehingga menjadi sebuah motif dalam suatu
karya.
Pada umunya bentuk dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu :
1) Bentuk beraturan (Geometris) yaitu obyek-obyek yang mempunyai bentuk
beraturan seperti : a) Bentuk Kubistik; Obyek yang mempunyai bentuk dasar
piramida, kubus, balok, prisma dan limas. b) Bentuk Silindris; Obyek yang
mempunyai bentuk dasar tabung, kerucut. c) Bentuk Bola; Obyek yang
mempunyai bentuk dasar bulat seperti bola, (Anonim:2012).
Gambar 3. Macam-macam bentuk geometris
Sumber:http://www.google.com.bentuk+geometris.bentuk.htm&docid
2) Bentuk tak beraturan (Non Geometris), yaitu obyek-obyek yang bentuknya
tidak beraturan (bukan kubistik, silindris dan bola). Maka dapat disimpulkan
bentuk adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wujud yang dapat
dilihat dan dapat dirasakan.
Kajian Seni SD 49
5. Ruang
Setiap bentuk pasti menempati ruang oleh karena itu ruang merupakan
unsur rupa yang mesti ada, karena ruang merupakan bentuk-bentuk berada.
Dengan kata lain bahwa setiap bentuk pasti menempati ruang. Dikarenakan
bentuk dapat dua dimensi, tiga dimensi, maka ruangpun meliputi ruang dua
dimensi/dwimatra dan tiga dimensi/trimatra, (Sadjiman 2005:97).
a. Ruang dwimatra
Ruang dwimatra adalah merupakan ruang datar. Ruang ini banyak
dimanfaatkan oleh para desainer/perancang untuk menempatkan bentuk raut
yang sifatnya cukup datar/terlihat datar saja, seperti gambar-gambar proyeksi
dengan potongan-potongan dan pandangan-pandangan tertentu, bentuk tulisan,
bentuk-bentuk kode, rancangan tekstil, dan gambar-gambar dekoratif, (Sadjiman
2005:97).
Ruang dwimatra hanya mengenal dua dimensi, yaitu panjang dan lebar,
ruang dwimatra juga hanya mengenal arah horisontal, diagonal, dan vertikal
yang rata dengan tafril, dan hanya mengenal kedudukan di kiri-tengah-kanan,
atas-tengah-bawah, yang menempati/ terletak pada tafril. Ruang dwimatra yang
terisi obyek pada umumnya disebut ruang positif, dan ruang yang tidak terisi
obyek disebut ruang negatif, (Sadjiman 2005:98).
b. Ruang trimatra
Ruang trimatra merupakan jenis ruang yang benar-benar diartikan
sebagai ruangan yang berongga atau yang sempurna, yang memiliki tiga dimensi
penuh, panjang, lebar, dalam/ tebal. Semua bentuk yang ada di alam termasuk
karya seni yang bersifat tiga dimensi seperti berbagai bentuk bangunan/
arsitektur, taman, patung, interior, kerajinan, hasil-hasil, industri, yang dapat
dijamah/diraba adalah menempati ruang trimatra, (Sadjiman 2005:98).
Tata rupa trimatra pada prinsipnya sama dengan dwimatra, yang berbeda
hanya unsur-unsurnya dimana jika garis untuk dwimatra merupakan hasil
goresan, sedangkan untuk trimatra wujud garis berupa, kawat, tali, galah, tiang
dan apa saja yang berbentuk kecil memanjang, bidang trimatra, dapat berwujud
triplek, seng, kertas, karton, dinding, papan tulis, dan apa saja yang memiliki
dimensi panjang dan lebar, dengan ketebalan yang tidak diperhitungkan sebagai
tebal. Prinsip dasar tata rupa trimatra sama dengan dwimatra, dimana dikatakan
memiliki nilai seni apabila di dalamnya terdapat kesatuan, memiliki irama,
memiliki dominasi, ada keseimbangan, memiliki proporsi yang baik, (Sadjiman
2005:98).
c. Ruang maya
Ruang maya adalah ruang tiga dimensi semu, adalah ruang datar dua
dimensi namun bentuk raut yang menempati ruang tersebut direka sedemikian
rupa sehingga mengecoh si penglihat secara imajinasi terlihat adanya ruang tiga
dimensi, seperti misalnya gambar pemandangan, (Sadjiman 2005:99).
50 Pengantar
Ruang tiga dimensi semu merupakan jenis ruang yang paling banyak digunakan
oleh para perupa /desainer untuk menuangkan ekspresi, karena jenis ruang ini
paling banyak dapat melahirkan ide-ide yang imajinatif dan emosional. Secara
nyata ruang dua dimensi adalah datar berdimensi panjang dan lebar, namun
secara maya dapat diciptakan dimensi ke dalam, sehingga membentuk ilusi ke
ruangan, dimana kedudukan bentuk tidak hanya menempati ruang di kiri ke
kanan atau di atas ke bawah sejajar tafril, akan tetapi juga menempati ruang di
depan dan di belakang tafril, (Sadjiman 2005:99).
Unsur Ruang (dictio.id)
(Sumber: https://moondoggiesmusic.com/seni-rupa/)
6. Warna
Bentuk/benda apa saja di alam ini tentu memiliki warna, manakala
terdapat cahaya. Tenpa cahaya warna tidak akan ada. Warna seperti halnya
suara, merupakan fenomena getaran/ gelombang cahaya. Warna merupakan
getaran/ gelombang yang diterima indra penglihatan warna-warni adalah sama
dengan not-not musik atau tangga nada suara. Warna-warna adalah ungu, biru,
hijau, kuning, jingga, merah, sama dengan not musik do, re, mi, fa, sol, la, si,
merupakan tangga nada warna/ tingkatan/gradasi warna, (Sadjiman 2005:9).
Warna termasuk salah satu unsur keindahan dalam seni dan desain selain
unsur–unsur visual yang lain (Prawira, 1989:4). Lebih lanjut, Sanyoto (2005:9)
mendefinisikan warna secara fisik dan psikologis. Warna secara fisik adalah sifat
cahaya yang dipancarkan, sedangkan secara psikologis sebagai bagian dari
pengalaman indera penglihatan. Nugraha (2008:34) mengatakan bahwa warna
adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda–
benda yang dikenai cahaya tersebut.
Selanjutnya, Laksono (1998:42) mengemukakan bahwa warna
merupakan bagian dari cahaya yang diteruskan atau dipantulkan. Terdapat tiga
unsur yang penting dari pengertian warna, yaitu benda, mata dan unsur cahaya.
Secara umum, warna didefinisikan sebagai unsur cahaya yang dipantulkan oleh
sebuah benda dan selanjutnya diintrepetasikan oleh mata berdasarkan cahaya
yang mengenai benda tersebut.
Warna dapat didefinisikan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang
Kajian Seni SD 51
dipancarkan, atau secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman
indara penglihatan. Secara objektif/fisik warna dapat diberikan oleh panjang
gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah bentuk pancaran
energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik,
(Sadjiman 2009:13).
Proses terlihatnya warna adalah dikarenakan adanya cahaya yang
menimpa suatu benda, dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata (retina)
terlihatlah warna, manakala orang tersebut tidak buta warna. benda berwarna
merah karena bersifat pigmen benda tersebut memantulkan warna merah dan
menserap warna pelangi lainnya. Benda berwarna hitam karena sifat pigmen
benda tersebut menserap semua warna pelangi. Sebaliknya suatu benda berwarna
putih karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan semua warna pelangi atau
semua panjang gelombang. Sebagai bagian dari pengalaman indra penglihatan,
warna adalah merupakan pantulan cahaya dari sesuatu yang nampak, yang
diterima mata berupa: cat, tekstil, batu, tanah, daun, kulit, rambut, dan lain-lain
disebut pigmen atau warna bahan, (Sadjiman 2005:10).
Menurut kejadiannya warna dibagi menjadi dua yaitu warna additive dan
subractive. Additive adalah warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut
spektrum. Sedangkan warna subtractive adalah warna yang berasal dari pigmen.
Kejadian warna ini diperkuat dengan hasil temuan Newton (Prawira, 1989:26)
yang mengungkapkan bahwa warna adalah fenomena alam berupa cahaya yang
mengandung warna spektrum atau pelangi dan pigmen. Menurut Prawira
(1989:31), pigmen adalah pewarna yang larut dalam cairan pelarut. Warna pokok
additive ialah merah, hijau, dan biru. Dalam komputer disebut warna model RGB.
Warna pokok subractive menurut teori adalah sian (cyan), magenta,dan kuning.
Dalam komputer disebut warna model CMY. Dalam teori, warna-warna pokok
additive dan subractive disusun ke dalam sebuah lingkaran, di dalam lingkaran itu
warna pokok additive dan warna pokok subjective saling berhadapan atau saling
berkomplemen, (Sadjiman 2005:11).
Gambar 4. Lingkaran warna additive dan subraktive
(Sadjiman 2005:14)
52 Pengantar
Pada tahun 1831, Brewster (Ali Nugraha, 2008: 35) mengemukakan teori
tentang pengelompokan warna. Teori Brewster membagi warna–warna yang ada
di alam menjadi empat kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier,
dan netral. Kelompok warna mengacu pada lingkaran warna teori Brewster
dipaparkan sebagai berikut:
a. Warna Primer
Warna primer adalah warna dasar yang tidak berasal dari campuran dari
warna–warna lain. Menurut teori warna pigmen dari Brewster, warna primer
adalah warna–warna dasar (Nugraha, 2008:37). Warna–warna lain terbentuk
dari kombinasi warna–warna primer. Menurut Prang, warna primer tersusun atas
warna merah, kuning, dan hijau (Nugraha, 2008:37). Akan tetapi, penelitian lebih
lanjut menyatakan tiga warna primer yang masih dipakai sampai saat ini, yaitu
merah seperti darah, biru seperti langit/laut, dan kuning seperti kuning telur.
Ketiga warna tersebut dikenal sebagai warna pigmen primer yang dipakai dalam
seni rupa.
Secara teknis, warna merah, kuning, dan biru bukan warna pigmen
primer. Tiga warna pigmen primer adalah magenta, kuning, dan cyan. Oleh karena
itu, apabila menyebut merah, kuning, biru sebagai warna pigmen primer, maka
merah adalah cara yang kurang akurat untuk menyebutkan magenta, sedangkan
biru adalah cara yang kurang akurat untuk menyebutkan cyan.
Warna Primer
(Sumber: http://materi4belajar.blogspot.com/2019/01/)
b. Warna Sekunder
Warna sekunder merupakan hasil campuran dua warna primer dengan
proporsi 1:1. Teori Blon (Prawira, 1989:18) membuktikan bahwa campuran
warna–warna primer menghasilkan warna–warna sekunder. Warna jingga
merupakan hasil campuran warna merah dengan kuning. Warna hijau adalah
campuran biru dan kuning. Warna ungu adalah campuran merah dan biru.
Kajian Seni SD 53
Warna Sekunder
(Sumber: http://materi4belajar.blogspot.com/2019/01/)
c. Warna Tersier
Warna tersier merupakan campuran satu warna primer dengan satu
warna sekunder. Contoh, warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran
warna primer kuning dan warna sekunder jingga. Istilah warna tersier awalnya
merujuk pada warna–warna netral yang dibuat dengan mencampur tiga warna
primer dalam sebuah ruang warna. Pengertian tersebut masih umum dalam
tulisan–tulisan teknis.
Warna Tersier
(Sumber: http://materi4belajar.blogspot.com/2019/01/)
d. Warna Netral
Warna netral adalah hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi
1:1:1. Campuran menghasilkan warna putih atau kelabu dalam sistem warna
cahaya aditif, sedangkan dalam sistem warna subtraktif pada pigmen atau cat
akan menghasilkan coklat, kelabu, atau hitam. Warna netral sering muncul
sebagai penyeimbang warna–warna kontras di alam. Munsell (Prawira, 1989:70)
54 Pengantar
mengemukakan teori yang mendukung teori Brewster. Munsell mengatakan
bahwa: Tiga warna utama sebagai dasar dan disebut warna primer, yaitu merah
(M), kuning (K), dan biru (B). Apabila warna dua warna primer masing–masing
dicampur, maka akan menghasilkan warna kedua atau warna sekunder. Bila
warna primer dicampur dengan warna sekunder akan dihasilkan warna ketiga
atau warna tersier. Bila antara warna tersier dicampur lagi dengan warna primer
dan sekunder akan dihasilkan warna netral.
Rumus teori Munsell dapat digambarkan sebagai berikut:
Warna primer : Merah, Kuning, Biru
Warna Sekunder : Merah + Kuning = Jingga
Merah + Biru = Ungu
Kuning + Biru = Hijau
Warna Tersier : Jingga + Merah = Jingga kemerahan
Jingga + Kuning = Jingga kekuningan
Ungu + Merah = Ungu kemerahan
Ungu + Biru = Ungu kebiruan
Hijau + Kuning = Hijau kekuningan
Hijau + Biru = Hijau kebiruan
Karakter dan simbulisasi warna (bahasa rupa warna)
Karakter warna adalah untuk warna-warna murni (warna pelangi),
sedangkan jika warna berubah muda atau tua atau menjadi redup karakternya
akan berubah.
a. Kuning adalah warna emosional yang menggerakan energi dan kecerian,
kejayaan, dan keindahan. Kuning emas melambangkan, keagungan,
kemewahan, kejayaan, kemagahan, kemulyaan, kekuatan. Kuning sutera
adalah warna marah, sehingga tidak populer. Kuning tua dan kuning
kehijau-hijauan mengasosiasikan sakit, penakut, iri, cemburu, bohong, luka,
(Sadjiman, 2005:38).
b. Jingga, asosiasi pada awan jingga. Awan jingga terlihat pada pagi hari
sebelum matahari terbit, menggambarkan gelap malam menuju terbit
matahari, sehingga melambangkan kemerdekaan, anugerah, kehangatan.
Karakter warna jingga memberi dorongan, merdeka, anugerah, bahaya.
Lambang kemerdekaan, penganugrahan, kehangatan, bahaya, (Sadjiman,
2005:38).
c. Merah, asosiasi pada darah dan juga api. Karakter warna merah yaitu kuat,
enerjik, marah, berani, bahaya, positif, agresif, merangsang, panas. Simbul
umum dari sifat nafsu primitif, marah, berani, perselisihan, bahaya, perang,
seks, kekejaman, bahaya, kesadisan. Dibanding dengan warna lain, merah
adalah warna paling kuat dan enerjik. Warna pertama digunakan pada seni
primitif maupun klasik. Warna ini paling populer pada wanita, (Sadjiman,
2005:39).
Kajian Seni SD 55
d. Ungu, sering juga disamakan dengan violet, tetapi ungu lebih tepat dengan
purpel, yaitu warna tersebut cenderung kemerahan. Sedangkan violet
cenderung kebiruan. Ungu memiliki watak keangkuhan, kebesaran,
kekayaan. Ungu merupakan percampuran antara merah dan dan biru
sehingga juga membawa atribut dari kedua warna tersebut, (Sadjiman,
2005:39).
Biru, asosiasi pada air, laut, langit, di barat pada es. Watak dari biru adalah
dingin, pasif, melankoli, sayu, sedu, sedih, tenang, berkesan jauh, tetapi cerah.
Lambang dari biru yaitu dihubungkan dengan langit tempat tinggal para
Dewa/yang maha tinggi, sehingga biru lambang keagunan, keyakinan, keteguhan
iman, kesetiaan, kebenaran, kemurahan hati, kecerdasan dan perdamaian,
(Sadjiman, 2005:39).
e. Hijau, asosiasi : pada hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang hidup
dan berkembang. Karakternya: segar, muda, hidup, tumbuh dan beberapa
hampir sama dengan warna biru. Dibanding dengan warna lain, warna hijau
relatif lebih netral pengaruh emosinya, sehingga cocok untuk istirahat. Hijau
melambangkan kesuburan, kesetiaan, keabadian, kebangkitan, kesegaran,
kemudahan, keremajaan, keyakinan, kepercayaan, keimanan, pengharapan,
dan kesanggupan, (Sadjiman, 2005:40).
f. Putih, asosiasi : di barat pada salju, di Indonesia pada sinar putih berkilauan,
pada kain kafan, sehingga dapat menakutkan pada anak-anak. Watak dari
warna ini adalah positif, cerah, tegas dan mengalah. Sedangkan lambang
dari warna ini adalah sinar kesucian, kemurnian, kekanak-kanakan,
kejujuran, ketulusan, kedamaian, ketentraman, kebenaran, kesopanan,
keadaan tak bersalah kelembutan dan kewanitaan, (Sadjiman, 2005:41).
g. Hitam, asosiasi : kegelapan, kesengsaraan, bencana, perkabungan,
kebodohan, misteri, ketiadaan dan keputusan. Lambang dari warna ini
adalah kesedihan, malapetaka, kesuraman, kemurungan, bahkan kematian,
teror, kejahatan, keburukan ilmu sihir, kedurjanaan, kesalahan, kekejaman,
kebusukan, dan rahasia, Hitam memang misterius, karena hitam yang
berdiri sendiri memiliki watak-watak buruk, tetapi jika dikombinasi dengan
warna-warna lain hitam akan merubah total wataknya. Sebagai latar
belakang warna, hitam mengasosiasikan kuat, tajam, formal, bijaksana.
Hitam dipergunakan bersama-sama putih mempunyai makna kemanusiaan,
resolusi, tenang, sopan, keadaan mendalam, kebijaksanaan. Terdapat istilah
hitam manis karena hitam selalu dikombinasi dengan warna lain menjadi
manis, (Sadjiman. 2005:41).
h. Abu-abu, asosiasi suasana suram, mendung, kelabu tidak ada cahaya
bersinar. Wataknya antara hitam dan putih. Pengaruh emosinya berkurang
dari putih, tetapi terbebas dari tekanan berat warna hitam, sehingga
wataknya lebih menyenangkan, walau masih membawa watak-watak warna
56 Pengantar
putih dan hitam. Cocok untuk latar belakang semua warna, terutama untuk
warna-warna pokok merah, biru dan kuning. Lambang : ketenangan,
kebijaksanaan, mengalah, kerendahan hati, tetapi simbul turun tahta, juga
suasana kelabu dan ragu-ragu.
i. Coklat, Asosiasi : pada tanah, warna tanah, atau warna natural. Karakter :
kedekatan hati, sopan, arif, bijaksana, hemat, hormat, tetapi sedikit terasa
kurang bersih atau tidak cemerlang karena warna ini berasal dari
percampuran beberapa warna seperti halnya warna tersier. Lambang :
kesopanan, kearifan, kebijaksanaan dan kehormatan, (Sadjiman ,2005: 38-
41).
Maka warna dapat disimpulkan adalah suatu gelombang yang dapat dinikmati
oleh panca indra kita seperti mata, tanpa mata dan cahaya kita tidak bisa melihat
keindahan warna yang ada di alam dan yang ada di bumi, hanya mata dan
bantuan cahaya yang bisa membedakan warna-warna yang ada di sekitar kita,
tanpa keduaanya hanya kegelapan yang bisa dilihat.
7. Tekstur
Pada umumnya orang menyebut tekstur itu dihubungkan dengan sifat
permukaan yang kasar. Pada hal sesunggunhnya permukaan yang haluspun
merupakan tekstur pula, dimana nilai, sifat, atau ciri khas permukaannya atau
teksturnya halus. Dengan demikian sifat-sifat permukaan kasar-halus, kasab-
licin, keras-lunak, bermotif-polos, cemerlang suram dan lainnya, semuanya
adalah tekstur, (Sadjiman, 2005:62).
Dengan demikian secara sederhana tekstur dapat dikelompokkan ke
dalam tekstur kasar nyata, tekstur kasar semu dan tekstur halus.
a. Tekstur nyata, pada umunya lebih berfokus pada tekstur kasar nyata,
karena tekstur ini memiliki peran amat penting dalam seni rupa. Adapun
peran penting tekstur kasar nyata dalam seni rupa antara lain:
1) Tekstur kasar nyata amat berguna untuk membantu memperoleh
keindahan karena dengan permukaan yang kasar akan lebih mudah untuk
memperoleh keselarasan/ harmoni. Permukaan yang kasar memiliki
bukit-bukit atau relief, sehingga karena adanya sinar maka menimbulkan
bayangan gelap terang atau value yang kemudian menetralisir warna-
warna yang ada, dan secara otomatis susunan menjadi harmonis.
2) Tekstur kasar nyata juga dapat difungsikan sebagai dominasi atau daya
tarik, manakala sebagian besar susunan menggunakan tekstur halus.
Dominasi merupakan dalah satu prinsip dasar tata rupa untuk
memperoleh keindahan.
3) Tekstur kasar nyata amat berguna untuk membantu memperoleh
keindahan berpadu dengan kekuatan. Jika suatu permukaan dengan
tekstur halus dapat mudah digulung atau dilipat maka permukaan
Kajian Seni SD 57
tersebut kemudian dilukai atau diberi lipatan-lipatan sehingga memiliki
tekstur kasar maka akan sulit digulung atau dilipat.
4) Tekstur kasar nyata juga amat berguna untuk tujuan keindahan yang
mengikuti fungsi. Ini dapat kita jumpai pada desain-desain produk,
misalnya kisi-kisi lubang kipas, lubang pengeras suara, pegangan kunci,
tutup botol, jendela dan pentilasi. Dimana memberi keindahan juga
memiliki fungsi, (Sadjiman, 2005: 62-63).
b. Tekstur kasar semu, adalah tekstur yang kekerasan rautnya bersifat semu,
artinya terlihat kasar tetapi jika diraba akan terasa halus, tekstur ini terbagi
atas tiga macam :
1) Tekstur hias manual, yaitu yang menghiasi permukaan yang dibuat secara
manual. Tekstur ini hanya sekedar menghias permukaan saja, jika
teksturnya dihilangkan tidak dapat mempengaruhi bidangnya.
2) Tekstur mekanik, yang dibuat dengan alat mekanik seperti mistar, jangka,
alat foto, tipografi, raster cetak dan cetak komputer.
3) Tekstur ekspresi, yaitu merupakan bagian dari proses penciptaan rupa, di
mana tekstur merupakan kesatuan tak dapat dipisahkan. Tekstur jenis ini
banyak dilakukan pada seni lukis, seni grafis, desain komunikasi visual
dan lain-lain, dapat merupakan hasil goresan tangan atau hasil mekanik,
(Sadjiman, 2005: 64).
c. Tekstur halus, adalah tekstur yang dilihat halus diraba pun halus. Tekstur bisa
licin, kusam atau mengkilat. Tekstur halus tidak banyak dibicarakan orang,
bahkan tidak dianggap sebagai tekstur karena pada umunya dikatakan tekstur
selalu dihubungkan dengan sifat permukaan kasar. Disamping itu tekstur
halus merupakaan permukaan yang bisa terlihat sehari-hari pada berbagai
obyek, sehingga kurang diperhitungkan nilai keindahannya. Namun pada
tekstur halus mengkilat memiliki kekhususan tersendiri yaitu apabila kita
menyusun warna pada pemukaan halus licin mengkilat sangat sulit untuk
memperoleh keharmonisan karena pemantulan-pemantulan permukaan
mengkilat tersebut, (Sadjiman, 2005: 65).
Tekstur merupakan nilai atau ciri khas suatu permukaan tersebut dapat
kasar, halus, polos, bermotif/bercorak, mengkilat, buram, licin, keras, dan lunak.
Dari berbagai tekstur tersebut ada yang bersifat teraba, dan bersifat visual.
Dari beberapa pengertian tentang tekstur di atas maka dapat disimpulkan
tekstur adalah suatu permukaan yang keindahannya bisa dinikmati oleh panca
indra yang memiliki sifat kasar, halus, lembut serta semu.
58 Pengantar
Unsur Tekstur (pixabay.com)
(Sumber: https://moondoggiesmusic.com/seni-rupa/)
F. Periodisasi Perkembangan Seni Rupa Anak SD
Hasil suatu karya seni sesungguhnya sangat dipengaruhi dan bahkan
ditentukan oleh pelaku seni itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa
karya seni anak bersifat ekspresif karena karya rupa mereka umumnya
merupakan suatu ungkapan yang kuat, jujur, langsung berangkat dari hati dan
dari dalam dirinya. Bersifat dinamis yaitu artinya karya mereka umumnya
mengesankan sesuatu yang bergerak terus. Pada pemilihan warna misalnya anak
lebuh suka pada warna kontras, tajam atau mencolok.
1. Tipologi
Tipologi seni rupa anak terdiri atas 3 tipe. Yakni tipe visual, tipe haptik
dan tipe campuran (visual–haptik). Sebenarnya pada kenyataannya jarang tipe-
tipe ini muncul secara murni, umumnya tipe-tipe tersebut bergerak dan
cenderung bercampur.
a. Tipe visual
- Lebih menonjol daya tangkap indrawinya
- Mengutamakan kesamaan hasil rekaman objek nyata
- Memperhatikan proporsi dan perbandingan rekaman objek nyata
- Menonjolkan sentuhan perspektif
b. Tipe haptik
- Tidak berorientasi pada kenyataan
- Lebih mengutamakan suasana hati atau emosi
- Bersifat sangat individual
2. Karakteristik Gambar Anak
a. Gambar X-Ray :
Anak mewujudkan dan menggambarkan benda-benda yang dipikirkan
tampak tembus pandang.
Kajian Seni SD 59
b. Gambar rebahan :
Karya seni yang sejalan dengan analisis anak terhadap benda-benda
disekitarnya. Ia berpandapat bahwa semua benda teletak tegak lurus pada
latarnya.
c. Perspektif burung :
Anak berkarya seni dengan menunjukan seluruh objek terkait dengan
objek yang menjadi sasaran pandang, tetapi dalam bentuk kecil-kecil. Jadi
seperti kita melihat sesuatu dari ketinggian (burung terbang)
d. Gambar realistis :
Anak tahu dan mengerti kenyataan dia tidak lagi bersifat naif tidak hanya
berpanut pada emosinya tetapi juga dasar rasionya
e. Gambar tumpang tindih :
Anak menggambar objek dengan cara tumpang tindih antara objek yang
satu dengan objek yang lain, yakni mulai timbul kesadaran ruang.
Perkembangan anak melalui pikiran dan perasaan menentukan sifat dan
bentuk pada lukisan anak. Dimulai dalam mengenal bentuk dan mengungkapkan
oyek dalam gambarnya sampai dapat memahami arti gambar itu sendiri. Setiap
guru SD perlu mengenal latar belakang anak didiknya, khususnya landasan teori
tentang dunia kesenirupaan anak yang telah dikembangkan oleh para ahli, agar
ia dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Anak
Sekolah Dasar (SD) berusia sekitar 6 - 12 tahun.
Berdasarkan teori tahap-tahap perkembangan menggambar/seni rupa
secara garis besar dapat dibedakan dua tahap karakteristik, yaitu kelas I sampai
dengan kelas III ditandai dengan kuatnya daya fantasi-imajinasi, sedangkan
kelas IV sampai dengan kelas VI ditandai dengan mulai berfungsinya kekuatan
rasio. Perbedaan kedua karakteristik ini tampak pada gambar-gambar (karya dua
dimensi) atau model, patung dan perwujudan karya tiga dimensi lainnya.
Ada beberapa tokoh yang telah melakukan kajian tentang periodisasi
karya seni rupa anak, di antaranya Corrado rinci dari Italia (1887), kemudian
dilanjudkan oleh Sully, Kerchensteiner, William Stern, Cyrul Burt, Margaret
Meat, Victor Lowefeld dan Brittain, Rhoda Kellog, Scot, Langsing, dan lain-lain.
1. Periodisasi perkembangan seni rupa anak menurut Victor Lowenfeld dan
Lambert Brittain adalah:
Penyelidikan yang dilakukan terhadap anak-anak usia 2 sampai 17 tahun
menghasilkan periodisasi sebagai berikut:
a. Masa mencoreng (scribbling) : 2 - 4 tahun
b. Masa prabagan (preschematic) : 4 - 7 tahun
c. Masa bagan (schematic period) : 7 - 9 tahun
d. Masa realism awal (Dawning realism) : 9 - 12 tahun
e. Masa naturalism semu (Pseudo naturalistic) : 12 - 14 tahun
f. Masa penentuan (period of Decision) : 14 - 17 tahun
60 Pengantar
2. Tahapan perkembangan menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain
sebagai berikut:
a. Masa mencoreng-moreng (scribbling)
Goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-3 tahun belum menggambarkan
suatu bentuk obyek. Biasanya tahap pertama hanya mampu
menghasilkan goresan terbatas dengan arah vertical dan horizontal.
Periode ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : corengan tidak beraturan,
corengan terkendali dan corengan bernama. Ciri gambar yang dihasilkan
pada corengan tidak beraturan adalah bentuk gambar yang sembarang,
mencoreng tanpa melihat kertas, belum dapat membuat corengan berupa
lingkaran dan memilki semangat yang tinggi. Corengan terkendali
ditandai dengan kemampuan anak menemukan kendali visualnya
terhadap coretan yang dibuatnya. Corengan bernama dapat diamati
ketika anak dapat membuat goresan yang terkontrol bahkanmemberinya
nama.
b. Masa pra bagan (Pre Schemic Period)
Ciri-ciri anak pada masa ini adalah anak telah menggunakan bentuk-
bentuk dasar geometris untuk member kesan objek dari dunia sekitar.
Aspek warna belum ada hubungan tertentu dengan objek, orang bisa saja
berwarna biru, merah, coklat atau warna lain yang disenanginya.
Penempatan objek bersifat subjektif, didasarkan pada kepentingannya.
c. Masa realism awal (Early Realism)
Pada periode ini karya anan lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran
perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan sendiri.
Pemahaman warna sudah mulai disadari, penguasaan konsep ruang
mulai dikenalnya sehingga letak objek tidak lagi bertumpu pada garis
dasar melainkan pada bidang dasar sehingga mulai ditemukan garis
horizontal.
d. Masa naturalisme semu
Pada masa ini kemampuan-kemampuan berfikir abstrak serta kesadaran
sosialnya makin berkembang. Penguasaan rasa perbandingan (proporsi)
serta gerak tubuh objek lebih meningkat. Tipe haptic memperlihatkan
tanggapan keruang dan objek secara subjektif, lebih banyak menggunakan
perasaan.
e. Periode Penentuan
Karya yang dibuat pada anak usia ini sudah menunjukkan penguasaan
teknik menggambar dengan baik. Penguasaan ruang diwujudkan dengan
penguasaan perspektif dengan baik. Begitu pula warna yang digunakan
sudah mendekati naturalis.
Karakter Gambar Anak Berkembang Seiring Pertambahan Usia.
Menggambar merupakan kegiatan ekspresi kreatif yang populer di kalangan
Kajian Seni SD 61
anak-anak. Pengalaman batin yang sederhana pada anak-anak merupakan
kenangan indah dan hangat yang sewaktu-waktu bisa diungkapkan dengan
berekspresi dan juga merupakan pendorong baginya. Sebagian besar kehidupan
anak-anak dipenuhi dengan permainan, permainan sebagai bagian yang
menyeluruh dalam kehidupan anak. Dalam permainnya anak senantiasa meniru-
niru orang dewasa, mereka membuat rumah-rumahan, kemudian membersih-
kannya, mengecatnya, serta menatanya layaknya orang dewasa.
Sebagaimana kemampuan lain pada umumnya, kemampuan meng-
gambar anak sudah berkembang bahkan sejak periode batita. Lebih dari itu
gambar yang dihasilkan oleh seorang anak di setiap periode memiliki arti dan
karakteristik yang berbeda-beda. Viktor Lowenfeld dalam bukunya Creative and
Mental Growth (1982) meneliti tingkat perkembangan menggambar anak
berdasarkan usia, menganalisis tentang periodisasi yang menjadi ciri umum
lukisan anak-anak sesuai waktu (usia) dan tahap perkembangan sosial intelektual
mereka, sebagai berikut:
1. Periode Coreng-moreng (Scribbling Stage)
Periode ini berlaku bagi anak berusia 2 sampai 4 tahun (masa prasekolah).
Gambar yang dibuat tanpa makna, hanya perbuatan meniru orang lain, tetapi
merupakan latihan gerak motorik dari koordinsai gerakan tangan dan mata,
gambar berupa goresan tipis tebal dengan arah yang belum terkendali. Periode ini
terdiri dari 3 fase, hanya setiap fase jaraknya sangat singkat sekali, sehingga
dianggap satu fase.
a. Goresan tak Beraturan
Gambar tanpa makna, karena anak melakukannya hanyalah meniru
orang lain, belum dapat membuat coretan berupa lingkaran, karena hanya
merupakan latihan gerak motorik antara mata dengan gerak tangan, bentuk garis
sembarangan, bersemangat tanpa melihat ke kertas, merupakan fase yang paling
awal dalam tahap perkembangan menggambar anak.
b. Goresan Terkendali
Berupa goresan-goresan tegak, mendatar, lengkung bahkan lingkaran,
coretan dilakukan berulang-ulang. Nampak anak mulai memerlukan kendali
visual terhadap coretan yang dibuatnya, disini koordinasi antara perkembangan
visual (gerak mata) dengan gerak motorik (tangan) semakin lengkap. Goresan
dibuat dengan penuh semangat.
c. Goresan Bermakna
Pengalaman anak dalam membuat goresan semakin lengkap, gambar
anak mulai terwujud menjadi satu kesatuan, bentuk yang semakin bervariasi,
anak mulai memberi nama pada hasil coretannya dan mulai menggunakan
warna. Dalam menggambar, anak belum mempunyai tujuan untuk menggambar
sesuatu, karena fase ini lebih didasari oleh perkembangan fisik dan jiwa anak.
62 Pengantar
Anak yang normal pasti suka meggambar.
2. Periode Pra Bagan (Pre Schematic Stage)
Periode ini berlaku bagi anak berusia 4-7 tahun (taman kanak-kanak).
Sejalan dengan meningkatnya perkembangan anak, pengalaman anakpun makin
bertambah, lingkup sosial makin luas, anak berkesempatan mencipta,
bereksperimen, menjelajah, dan berbagai hal baru yang erat dengan per-
kembangan jiwa, rasa maupun emosinya. Anak mulai mengenal dunia baru,
mengenal sekolah, teman sebaya, guru, dan lingkungan baru. Sehingga gambar
yang dibuat oleh anak mulai menggambar bentuk-bentuk yang berhubungan
dengan dunia sekitar mereka. Rumah, manusia pohon dan lingkungan sekitarnya
menjadi obyek yang menarik perhatian anak. Unsur warna kurang diperhatikan,
anak lebih tertuju pada hubungan antara gambar dan obyek gambar. Warna
menjadi subyektif karena tidak mempunyai hubungan dengan obyek.
3. Periode Bagan (Schematic Stage)
Periode ini berlaku bagi anak berusia 7 sampai 9 tahun. Sejalan dengan
tahap perkembangan anak, pada akhir tahap ini perkembangan akal sudah mulai
mempengaruhi gambar anak. Anak sudah mulai menggambar obyek dalam suatu
hubungan yang logis dengan gambar lain. Konsep ruang mulai nampak dengan
adanya pengaturan antara hubungan obyek dengan ruang, gambar mulai realistis,
mulai mengarah ke bentuk-bentuk yang mendekati kenyataan. Ciri utama
gambar anak pada fase ini adalah adanya garis dasar yang merupakan tempat
obyek atau benda-benda berdiri, merupakan suatu perkembangan yang wajar.
Muncul gejala yang disebut “folding over”, yakni cara menggambar obyek tegak
lurus pada garis dasar, meskipun obyek akan nampak terbalik. Ciri lainnya,
adanya gambar yang disebut “sinar X” (X-ray), yakni gambar yang berisi benda
atau obyek lain dalam suatu ruang yang sebenarnya tidak kelihatan. Gambar
dibuat berdasarkan ide anak itu sendiri, misalnya gambar rumah yang kelihatan
bagian dalamnya seolah-olah rumah tersebut terbuat dari kaca bening. Warna
mulai obyektif, artinya anak menyadari adanya hubungan antara warna dengan
obyek. Ciri lain yang kurang menguntungkan, gambar nampak lebih kaku. Anak
cenderung mencontoh gambar orang lain, hal ini karena berkembangnya sifat
kooperatif di antara mereka.
4. Periode Awal Realisme (Early Realism Stage)
Periode ini berlaku bagi anak berusia 9 sampai 12 tahun (kelas IV SD-VI
SD) disebut pula “usia pembentuk kelompok”. Masa ini ditandai oleh besarnya
perhatian anak terhadap obyek gambar yang dibuatnya. Bentuk-bentk gambar
mulai mengarah ke bentuk realistis, tetapi nampak lebih kaku, hal ini sebagai
akibat perkembangan sosial yang meningkat, mereka lebih memikirkan bentuk
Kajian Seni SD 63
gambar yang dapat diterima oleh lingkungannya, akibatnya spontanitas
berkurang. Anak mulai mengekspresikan obyek gambar dengan karakter tertentu,
lelaki atau wanita secara jelas. Karakteristik warna mulai mendapat perhatian,
walaupun belun adanya penampilan dalam hal perubahan efek warna dalam
terang dan bayang-bayang. Dalam gambar adanya penemuan penggambaran
bidang dasar sebagi tempat pijakan (ground) benda dan obyek gambar. Adanya
garis horizon, walaupun fungsinya belum dimengerti, sehingga kesan perspektif
akan kelihatan janggal. Terlihat adanya menghias (mendekorasi) obyek gambar.
5. Periode Naturalistik Semu (Pseudo Naturalistic Stage)
Periode ini berlaku bagi anak berusia 12 sampai 14 tahun. Masa pra
puber. Gambar yang dibuat sesuai dengan obyek yang dilihatnya, sehingga
timbul minat terhadap naturalisme, terutama pada anak yang bertipe visual.
Anak menjadi kritis terhadap karyanya sendiri. Ia mulai memperhitungkan
kualitas tiga dimensi (perspektif). Mereka mampu menyerap apa yang mereka
lihat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dari buku-buku komik,
kalender, bahkan dari media visual lainnya (televisi, majalah, Koran dan lain-
lain).
Selain pembahasan tahapan atau periodisasi perkembangan seni rupa
anak di atas, akan dibahas lagi perkembangan seni rupa anak berikut contohnya.
Seperti diketahui anak Sekolah Dasar (SD) berusia sekitar 6 - 12 tahun.
Berdasarkan teori tahap-tahap perkembangan menggambar/seni rupa secara
garis besar dapat dibedakan dua tahap karakteristik, yaitu kelas I sampai dengan
kelas III ditandai dengan kuatnya daya fantasi-imajinasi, sedangkan kelas IV
sampai dengan kelas VI ditandai dengan mulai berfungsinya kekuatan rasio.
Perbedaan kedua karakteristik ini tampak pada gambar-gambar (karya dua
dimensi) atau model, patung dan perwujudan karya tiga dimensi lainnya.
k. Perodisasi menurut Kerchensteiner (Muharam dan Sundaryati, 1991:34)
Kerchensteiner mengadakan penyelidikan pada anak-anak dari masa bayi
sampai empat belas tahun. Dari 100.000 buah gambar ia menggolongkannya
dalam beberapa periode, masa, yaitu:
1) Masa Mencoreng : 0 – 3 tahun
2) Masa bagan : 3 – 7 tahun
3) Masa bentuk dan garis : 7 – 9 tahun
4) Masa bayang-bayang : 9 – 10 tahun
5) Masa persfektif : 10 – 14 tahun
l. Periodisai menurut Lowenfeld, (1975:118-119) Membagi periodisasi gambar
menjadi tujuh tingkatan, yaitu:
1) Masa mencoreng : 2 – 3 tahun
2) Masa garis : 4 tahun
3) Masa simbolisme deskriptif : 5 – 6 tahun
64 Pengantar
4) Masa realisme deskriftif : 7 – 8 tahun
5) Masa realisme visual : 9 – 10 tahun
6) Masa represi : 10 – 14 tahun
7) Masa pemunculan artistik : masa adolesen
m. Periodisasi masa perkembangan seni rupa anak menurut Viktor Lowenfeld
dan Lambert Brittain. Penyelidikan yang dilakukan terhadap anak-anak usia
2 sampai 17 tahun menghasilkan periodisasi sebagai berikut:
1) Masa mencoreng (scribbling) : 2-4 tahun
Goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-4 tahun belum
menggambarkan suatu bentuk objek. Pada awalnya, coretan hanya
mengikuti perkembangan gerak motorik. Biasanya, tahap pertama hanya
mampu menghasilkan goresan terbatas, dengan arah vertikal atau
horizontal. Ciri gambar yang dihasilkan anak pada tahap corengan tak
beraturan adalah bentuk gembar yang sembarang, mencoreng tanpa
melihat ke kertas, belum dapat membuat corengan berupa lingkaran dan
memiliki semangat yang tinggi
Pada masa mencoreng, bila anak difasilitasi oleh orang tua maka
akan memiliki peluang untuk melakukan kreasi dalam hal garis dan
bentuk, mengembangkan koordinasi gerak, dan mulai menyadari ada
hubungan gambar dengan lingkungannnya.
Gambar 3. 1 Goresannya tak beraturan
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
Setiap anak (usia 2-4 tahun) pada umumnya senang menggoreskan
sesuatu (pensil, pena dan sejenisnya).
2) Masa Prabagan (preschematic) : 4-7tahun
Ciri-ciri yang menarik lainnya pada tahap ini yaitu telah
Kajian Seni SD 65
menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan
objek dari dunia sekitarnya. Koordinasi tangan lebih berkembang. Aspek
warna belum ada hubungan tertentu dengan objek, orang bisa saja
berwarna biru, merah, coklat atau warna lain yang disenangi.
Gambar 3. 2
Kepala berkaki, ciri umum gambar anak usia 2-4 tahun
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
Penempatan dan ukuran objek bersifat subjektif, didasarkan kepada
kepentingannya. Jika objek gambar lebih dikenalinya seperti ayah dan
ibu, maka gambar dibuat lebih besar dari yang lainnya. Ini dinamakan
dengan “perspektif batin”. Penempatan objek dan penguasan ruang
belum dikuasai anak pada usia ini.
Gambar 3.3
Objek yang penting, “Bapak” dan “Ibu” dibuat lebih besar
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
3) Masa Bagan (schematic period) : 7-9 tahun
Konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang
bentuk. Gambar masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah
(tampak pada penggambaran pohon di kiri kanan jalan yang dibuat tegak
lurus dengan badan jalan, bagian kiri rebah ke kiri, bagian kanan rebah
ke kanan). Pada perkembangan selanjutnya kesadaran ruang muncul
66 Pengantar
dengan dibuatnya garis pijak (base line).
Gambar 3.4
Penempatan objek gambar terletak pada garis dasar gambar (base line)
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
Penafsiran ruang bersifat subjektif, tampak pada gambar “tembus
pandang” (contoh: digambarkan orang makan di ruangan, seakan-
akan dinding terbuat dari kaca). Gejala ini disebut dengan idioplastis
(gambar terawang, tembus pandang). Misalnya gambar sebuah rumah
yang seolah-olah terbuat dari kaca bening, hingga seluruh isi di dalam
rumah kelihatan dengan jelas.
Gambar 3.5
Idioplastis, objek yang digambar tampak tembus pandang
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
Pada masa ini juga, kadang-kadang dalam satu bidang gambar dilukiskan
berbagai peristiwa yang berlainan waktu. Hal ini dalam tinjauan budaya
dinamakan continous narrative, anak sudah bisa memahami ruang dan
waktu. Objek gambar yang dilukiskan banyak dan berulang
menggambarkan sedang dilakukan.
4) Masa Realisme Awal (Dawning Realism) : 9-12tahun
Pada periode Realisme Awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan.
Kajian Seni SD 67
Kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan
sendiri. Mereka menyatukan objek dalam lingkungan. Selain itu
kesadaran untuk berkelompok dengan teman sebaya dialami pada masa
ini. Perhatian kepada objek sudah mulai rinci. Namun demikian, dalam
menggambarkan objek, proporsi (perbandingan ukuran) belum dikuasai
sepenuhnya.
Pemahaman warna sudah mulai disadari. Warna biru langit berbeda
dengan biru air laut. Penguasan konsep ruang mulai dikenalnya
sehingga letak objek tidak lagi bertumpu pada garis dasar, melainkan pada
bidang dasar sehingga mulai ditemukan garis horizon. Selain dikenalnya
warna dan ruang, penguasaan unsur desain seperti keseimbangan dan
irama mulai dikenal pada periode ini.
Ada perbedaan kesenangan umum, misalnya: anak laki-laki lebih senang
kepada menggambarkan kendaraan, anak perempuan kepada boneka atau
bunga.
Gambar 3.6
Bunga sering digambar oleh anak perempuan
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
Gambar 3.7
Gambar pemandangan, upaya anak dalam meniru bentuk alam, tampak sudah
mendekati kenyataan (realitas)
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
68 Pengantar
5) Masa Naturalisme Semu (Pseudo Naturalistic) : 12-14 tahun
Pada masa naturalisme semu, kemampuan berfikir abstrak serta
kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai
kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek
lebih rinci. Tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe haptic dengan
tipe visual. Tipe visual memperlihatkan kesadaran rasa ruang, rasa
jarak dan lingkungan, dengan fokus pada hal-hal yang menarik
perhatiannya.
Penguasaan rasa perbandingan (proporsi) serta gerak tubuh objek lebih
meningkat. Tipe haptic memperlihatkan tanggapan keruangan dan objek
secara subjektif, lebih banyak menggunakan perasaannya. Gambar-
gambar gaya kartun banyak digemari.
Gambar 3.8
Tokoh kartun banyak digemari anak-anak
Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/
Ada sesuatu yang unik pada masa ini, di mana pada satu sisi anak
ekspresi kreatifnya sedang muncul sementara kemampuan intelektual-
nya berkembang dengan sangat pesatnya. Sebagai akibatnya, rasio
anak seakan-akan menjadi penghambat dalam proses berkarya.
Apakah gambar ini seperti kucing? Sementara kemampuan menggambar
kucing kurang misalnya. Sebagai akibatnya mereka malu kalau
memperlihatkan karyanya kepada sesamanya.
6) Masa Penentuan (Period of Decision) : 14-17 tahun.
Pada periode ini tumbuh kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan
tipe individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan
melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa
tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, apalagi tanpa
bimbingan. Dalam hal ini peranan guru banyak menentukan, terutama
dalam meyakinkan bahwa keterlibatan manusia dengan seni akan
berlangsung terus dalam kehidupan.
Kajian Seni SD 69
2. Periodisasi masa perkembangan seni rupa anak menurut Lansing dalam
Kamaril (1999:2.38)
a. Masa coreng-moreng : 2-4 tahun
b. Masa/tahap figurative : 3-12 tahun
Perkembangan gambar anak pada dasarnya dapat disederhanakan
menjadi tiga tahap pokok: (1) tahap coreng-moreng (umur 2 – 4 tahun),
(2) tahap figuratif (umur 3 – 12 tahun), dan (3) tahap keputusan artistik
(umur 12 tahun ke atas). Pada tahap coreng-moreng anak membuat
simbol-simbol visual sesuai dengan rangsangan gerakan otot, yang
kemudian terkontrol dan akhirnya terstruktur sehingga mengesankan
“sesuatu benda”.
c. Subtahap figuratif awal : 3 -7 tahun
Pada tahap perkembangan simbolik ini gambar anak menunjukkan
hubungan dengan kenyataan atau bersifat naturalistik. Pada umumnya
anak pertama kali menggambarkan figur manusia. Peralihan dari tahap
coreng-moreng ke subtahap figuratif awal ini berkembang hampir tidak
tampak, karena penggambaran figur manusia didasarkan pada
kombinasi dari bentuk coreng-moreng. Ketika pertama kali berusaha
menggambarkan manusia, anak membuat lingkaran sebagai kepala atau
badan dangaris-garis lengkung sebagai kaki dan rambut. Anak mungkin
memahami bahwa terdapat bagian-bagian tubuh manusia yang lain,
tetapi ia belum mampu menggambar-kannya. Jadi, gambar anak
merupakan petunjuk kematangan intelektualnya sampai umur sepuluh
tahun. Pada masa perkembangan ini objek-objek baru disusun sesuai
dengan perasaan atau intuisi anak, dan anak belum memiliki kesadaran
untuk berpikir tentang keindahan. Pada masa perkembangan ini
umumnya anak begitu suka menggambar dan bertahan dalam
gayanya hingga waktu yang lama.
d. Subtahap figuratif tengah : 9-10tahun
Ciri pokok gambar anak tahap figuratif tengah. Garis dasar ini dapat
berupa garis yang digambar anak atau garis tepi kertas gambar. Jadi,
jelas bahwa gambar anak sekarang telah menunjukkan orientasi
bawah dan atas, sehingga objek yang terletak di bagian atas bidang
gambar mengarah ke langit dan sebaliknya, objek yang terletak di bagian
bawah bidang gambar mengarah ke tanah. Ciri yang lain gambar anak
pada tahap perkembangan ini adalah gambar tembus pandang (x-ray
drawing). Sebagai contoh, gambar bus penuh dengan para penumpang-
nya atau ibu dan dua anak di dalam badannya. Gambar ini merupakan
penggabungan penampakan suatu objek dari dalam dan dari luar
sekaligus. Cara penggambaran ini terutama ditemukan pada subtahap
70 Pengantar
figuratif tengah, tetapi dapat ditemukan juga pada semua tahap
perkembangan, kecuali tahap coreng-moreng.
e. Subtahap figuratif akhir : 9-12 tahun
Pada subtahap figuratif akhir ini anak menggambarkan orang dengan ciri-
ciri jenis kelaminnya dengan lebih jelas. Jika sebelumnya anak
sudah menggambarkan orang perempuan dengan rok dan orang laki-
laki dengan celana panjang, pada tahap perkembangan ini anak
menggambarkan orang perempuan dengan rambut yang panjang dan
berombak, dengan dada dan bibir yang mencolok. Orang laki-laki
digambarkan dengan rambut pendek, pundak lebar, dan otot-otot yang
menonjol.
f. Tahap artistik : 12 tahun ke atas
Ada dua cara untuk memahami perkembangan seni rupa anak-anak.
Pertama, mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan senirupa
anak menurut para ahli. Kedua, mengamati dan mengkaji karya anak secara
langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan karya anak
berdasarkan rentang usia yang relevan dengan teori yang telah kita pelajari.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kita bisa memahami perkembangan seni rupa
anak secara komprehensif. Dalam psikologi perkembangan dinyatakan baha
pada rentang kehidupan manusia khususnya anak ada yang disebut masa
keemasan yang dikenal dengan masa peka. Hal ini dipertegas oleh Duquet
(1953:41) bahwa: “A children who does not draw is an anomaly, and particulary so in
the years between 6 an 10, which is outstandingly the golden age of creative expression”.
Pada masa peka atau keemasan ini anak harus diberi kesempatan agar
potensi yang dimilikinya berfungsi secara maksimal. Masa peka tiap orang
berbeda-beda. Secara umum, masa peka menggambar ada pada masa lima
tahun, sedangkan masa peka perkembangan ingatan logis pada umur 12 dan 13
tahun (Muharam dan Sundaryati, 1991:33).
Selanjutnya, untuk terciptanya kesempatan bagi siswa agar dapat
melakukan ekspresi kreatif, maka guru perlu melakukan kegiatan berupa: 1)
memberi perangsang (stimulasi) kepada siswa, 2) guru dapat mempertajam
imajinasi dan memperkuat emosi siswa dengan menggunakan metode
pertanyaan yang dikembangkan Sokrates.
Oleh karenanya, alangkah lebih baiknya apabila sebagai orang dewasa
kita mau mengambil langkah pertama, membuat suatu perubahan dalam
membebaskan kreativitas anak “Membebaskan” anak menggambar sama dengan
membebaskan anak dalam menuangkan imajinasi dan mengungkapkan dirinya
melalui gambar. Melalui menggambar, secara tanpa disadari anak dapat belajar
memecahkan persoalan yang dihadapi. Dengan menggambar anak dapat
bermain dan berekspresi dengan sepuas-puasnya. Jadi, tugas guru dan orang tua
Kajian Seni SD 71
sebaiknya tidak mengajarkan konsep pendidikan seperti di masa lalu, dimana
anak dianggap sebagai mahluk yang lemah, serba tidak tahu. Tugas orang dewasa
hanyalah mengembangkannya secara alami.
G. Menggambar, Kolase, Montase, dan Mozaik
Menggambar tidak hanya merupakan aktivitas yang menghasilkan
kegembiraan dan memuaskan perasaan dengan menorehkan pensil di atas kertas
saja. Akan tetapi gambar juga merupakan proses yang terintegratif dari melihat,
memvisualisasikan, dan mengekspresikan image. Untuk mampu menyajikan
kemiripan terhadap suatu objek ketiga aktivitas tersebut harus terkoordinasi
secara baik dan saling mendukung. Image yang dilihat memperkaya penemuan
baru tentang dunia, image yang divisualisasikan memungkinkan untuk berfikir
dalam terminologi dan untuk memahami apa yang dilihat. Image yang digambar
memungkinkan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan pemikiran dan
persepsi manusia (Mujiono dan Muharrar,2007:7)
Dalam menggambar ada dua cara yakni dengan melihat objek benda atau
sesuatu yang akan digambar secara langsung dan tanpa melihat objek. Meng-
gambar dengan melihat objek secara langsung dibutuhkan kemampuan indra
penglihatan yang baik. Dengan cara ini ketepatan dan kemiripan bentuk sangat
diutamakan. Hal yang harus diperhatikan dalam menggambar dengan melihat
objek gambar secara langsung adalah bentuk benda, ukuran benda, proporsi,
perspektif benda, gelap terang benda, sudut pandang dan jarak antara benda
dengan penggambar.
Sementara itu untuk bisa menggambar tanpa melihat objek langsung
diperlukan suatu imajinasi dan kreativitas yang baik. Karena dalam menggambar
tanpa melihat objek secara langsung, diperlukan ide dan gagasan. Tanpa adanya
imajinasi maka ide tidak akan muncul dan tanpa adanya kreativitas akan sulit
untuk memvisualisasikan objek yang telah dipikirkan.
Dengan demikian untuk dapat menghasilkan gambar yang baik tanpa
harus melihat objek secara langsung dituntut untuk memiliki imajinasi yang baik.
Untuk bisa menumbuhkan imajinasi yang baik, maka diperlukan latihan dan
memperbanyak referensi bentuk benda yang ada di alam. Kreativitas juga
diperlukan untuk menghasilkan visualisasi gambar yang menarik. Dengan
imajinasi yang baik tapi tanpa kreativitas maka visualisasi gambar yang
dihasilkan akan tidak sesuai harapan.
1. Kolase
Kolase berasal dari Bahasa Perancis (collage) yang berarti merekat. Kolase
adalah aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis (lukisan
tangan) dengan menempelkan bahan-bahan tertentu (Sumanto, 2005:93).
72 Pengantar
Menurut Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi (2010: 5.4) kolase merupakan karya
seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam selama
bahan dasar tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain yang akhirnya
dapat menyatu menjadi karya yang utuh dan dapat mewakili ungkapan perasaan
estetis orang yang membuatnya. Siswa latihan membuat kolase bisa
menggunakan bahan sobekan kertas, sobekan majalah, koran, ketas lipat dan
bahan bahan yang ada dilingkungan sekitar. Ini adalah alasan untuk para guru
untuk tidak membuang barang bekas disekitar mereka. Barang-barang bekas
dapat digunakan untuk media anak didik untuk mengembangkan kreativitasnya.
Berkarya kreatif sebagai upaya pengembangan kemampuan dasar bagi
siswa berkarya melalui melalui kegiatan kolase dengan mengenali sifat
bahan/alat tersebut dapat melatih keterampilan kreatif anak dalam berekspresi
membuat bentuk karya kolase secara bebas. Kegiatan kolase dalam penelitianini
adalah kegiatan berolah seni rupa yang menggabungkan teknik melukis (lukisan
tangan) dengan keterampilan menyusun dan merekatkan bahan-bahan pada
kertas gambar/bidang dasaran yang digunakan, sampai dihasilkan tatanan yang
unik, menarik dan berbeda menggunakan bahan kertas, bahan alam dan bahan
buatan.
Contoh Kolase Karya Rava Azzahra Putri Kolase Karya Muhammad Yazid
(Sumber: https://www.dasarguru.com/perbedaan-kolase-montase-mozaik/)
2. Montase
Teknik montase merupakan teknik yang cukup menarik dan mudah
untuk dikerjakan oleh siswa setingkat sekolah dasar. Karya montase sangat
identik dengan guntingan gambar atau biasa juga disebut sebagai karya gunting
tempel (cut and paste). Montase merupakan sebuah karya yang dibuat dengan cara
memotong objek-objek gambar dari berbagai sumber kemudian ditempelkan pada
suatu bidang sehingga menjadi satu kesatuan karya dan tema (Susanto,2012).
Guntingan gambar artinya gambar yang sudah ada atau sudah tercetak pada
media cetak seperti foto, koran, majalah, buku dan sebagainya digunting hingga
terlepas dari lembaran-lembaran aslinya. Gambar-gambar yang banyak tersedia
dari berbagai sumber tersebut dipilih dan hanya digunting yang sesuai dengan
Kajian Seni SD 73
objek yang dikehendaki, menurut tema yang dibuat (Muharrar, 2013:44).
Menurut Sunaryo (2010:59) montase merupakan karya lukisan rekatan
yang dibuat dengan cara menyusun guntingan-guntingan gambar sehingga
menciptakan kesatuan bentuk yang baru. Dengan demikian untuk membuat
montase dibutuhkan sejumlah gambar dari media cetak yang dapat digunting dan
ditempel. Adapun media cetak yang dapat digunakan untuk membuat montase
antara lain : koran, majalah, buku, tabloid, kalender, dan lain sebagainya. Pada
dasarnya dalam pembuatan montase ada dua cara, yakni rekatan di atas dan
rekatan di bawah. Pada cara rekatan di atas, rekatan pada bidang tempel dimulai
dari memilih bidang-bidang warna yang luas dan polos, atau jika bergambar
dipilih yang sederhana dan tidak rumit. Bidang-bidang tempelan yang luas atau
bergambar sederhana ini diperlukan sebagai dasar atau latar belakang lukisan.
Selanjutnya di atas latar ini dapat disusun dan direkatkan guntingan-
guntingan gambar yang lebih kecil untuk mewujudkan kesatuan bentuk dan tema.
Pada rekatan bawah, disusun terlebih dahulu guntingan-guntingan gambar yang
dipilih dan kemudian direkatkan pada bidang tempel. Setelah itu susunan
ditindih dan ditempeli guntingan gambar yang luas, yang pada beberapa
bagiannya telah dilubangi (Sunaryo, 2010:59).
Montase karya Athiya Nuhaashofa Montase karya Fina Nailatul Izzah
(Sumber: https://www.dasarguru.com/perbedaan-kolase-montase-mozaik/)
3. Mozaik
Beberapa ahli seni berpendapat mengenai pengertian mozaik. Pengertian
mozaik dijelaskan oleh Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi (2008, 5.6) bahwa
mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa dua atau tiga dimensi yang
menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat
dengan cara dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan kemudian disusun
dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-
benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas,
dan potongan kayu. Tetapi untuk satu potongan gambar menggunakan satu jenis
potongan material. Soemardji (1992: 207) berpendapat bahwa, “mozaik adalah
elemen-elemen yang disusun dan direkatkan di atas sebuah permukaan bidang.”
74 Pengantar
Elemen-elemen mozaik berupa benda padat dalam bentul lempengan-
lempengan, kubus-kubus kecil, potongan-potongan, kepingan-kepingan, atau
bentuk lainnya. Ukuran elemen-elemen mozaik pada dasarnya hampir sama
namun bentuk potongannya dapat bervariasi. Mozaik adalah sebuah karya seni
yang terbuat dari elemen-elemen yang tersusun sedemikian rupa sehingga
membentuk gambar atau desain.
Pengertian lain mengenai mozaik diutarakan oleh Sumanto (2005: 87),
“mozaik adalah suatu cara membuat kreasi gambar, lukisan, hiasan yang
dilakukan dengan cara menempelkan atau merekatkan potongan-potongan
bahan tertentu yang ukurannya kecil-kecil.”
Berdasarkan keterangan di atas dapat dirangkum pengertian mozaik adalah
kegiatan yang dilakukan dengan cara menempelkan potongan-potongan benda
pada bidang yang bergambar atau belum bergambar dan potongan-potongan
tersebut sudah dalam bentuk geometri, seperti lingkaran, segitiga, setengah
lingkar, dan persegi.
Bermacam-macam bahan dapat digunakan untuk membuat mozaik,
yakni potongan kertas, potongan kain, biji-bijian, daun kering, potongan kayu,
potongan tripleks yang kecil-kecil, biji korek api dan lain sebagainya (Hajar
Pamadhi dan Evan Sukardi, 2008: 5.2)
Mozaik untuk anak-anak memiliki teknik tertentu dalam membuatnya.
Menurut Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi (2008: 5.27) menjelaskan bahwa,
teknik mozaik anak yang berbentuk dua atau tiga dimensi adalah sebagai berikut:
potongan-potongan kertas atau bahan lain ditempel dengan menggunakan lem
pada pola atau bidang gambar yang telah disediakan.
Dalam membuat mozaik membutuhkan langkah yang terencana
sehingga menghasilkan suatu karya dan peningkatan dari latihan tersebut.
Langkah-langkah membuat mozaik antara lain menggenggam, menjimpit,
mengelem dan menempel.
Mozaik karya Indratno Prakasa Mozaik karya Fina Nailatul Izzah
(Sumber: https://www.dasarguru.com/perbedaan-kolase-montase-mozaik/)
Perbedaan kolase montase dan mozaik adalah dari bahan atau material yang
ditempelkan. Kolase dari bahan yang berbeda jenis, montase dengan bahan dari
Kajian Seni SD 75
gambar yang sudah jadi, sedangkan mozaik berupa susunan kepingan dengan
jenis bahan yang sama.
H. Referensi
Bandi, dkk. 2009. Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta: Direktorat
Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
Budi, S. Catur. 2012. Pendidikan Seni Rupa. Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Duquet, Pierre. 1953. Creative Communication: Education and Art. A Symposium.
Paris: UNESCO.
Eka. 2012. Seni Kontemporer. [Online]. Tersedia: http://eka.web.id/pengertian-
seni-kontemporer.html [13 Mei 2017]
Gareth, Lilian. 2011. Art. NewYork: Publisher.
Gie, The Liang. 1976. Garis Besar Estetika (Filsafat Keindahan). Yogyakarta:
Super Sukses.
Kamaril, C. Dkk. 1999. Pendidikan Seni Rupa / Kerajinan Tangan. Jakarta:
Universitas Terbuka.
Kartika, Dharsono Sony. 2007. Kritik Seni. Bandung: Rekayasa Sains.
Laksono, Endang Widjajanti. 1998. Meramalkan Zat Pewarna dengan Pendekatan
Partikel dalam Kotak I–Dimensi. Dalam jurnal Cakrawala Pendidikan. 1
(17).
Lowenfeld, Victor. 1982. Creative and Mental Growth, Eisi V, New York:
McMillan.
Muharam dan Sundaryati, Warti. 1991. Pendidikan Kesenian II Seni Rupa. Jakarta:
Departeman Pendidikan dan Kebudyaaan Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan. .
Nugraha, Ali. 2008. Pengembangan Pembelajaran Sains pada Anak Usia Dini.
Bandung: JILSI Foundation.
Nurfatoni, Septian. 2013. Kajian Gambar Ekspresi Karya Siswa Tingkat Sekolah
Dasar. Bandung: UPI Press.
Nurhadiat, Dedi. 2004. Pendidikan Seni : Seni Rupa 2. Jakarta : PT. Grasindo.
Pekerti, Widia, dkk. 2012. Metode Pengembangan seni, Bandung: Universitas
Terbuka.
Prawira, Sulasmi Darma. 1989. Warna Sebagai Salah Satu Unsur Seni dan Desain.
Jakarta : Depdikbud.
Retnowati, Hartiti Tri, Prihandi Bambang. 2010. Pembelajaran Seni Rupa.
Yogyakarta: UNY.
76 Pengantar
Rondhi, M. 1989. Nilai Seni Patung. Hand Out. Jurusan Seni Rupa FBS
UNNES. tidak dipublikasikan
Sachari, Agus. 2007. Budaya Visual Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Sanyoto, Sadjiman Ebdi. 2004. Dasar-dasar Tata Rupa dan Desain. Yogyakarta:
Arti Bumi Intaran.
-------. 2005. Dasar-dasar Tata Rupa dan Desain. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
Cetakan ke-2.
-------. 2009. Nirmana (Dasar-Dasar Seni dan Desain). Yogyakarta : Jalasutra.
Soelarko, R. M. 1990. Komposisi Fotografi. Jakarta: Balai Pustaka.
Sukaryono. 1994. Kajian Seni Rupa. Yogyakarta Yayasan Kanisius.
Sunaryo, A. 2002. Nirmana I. Hand Out. Jurusan Seni Rupa FBS UNNES tidak
dipublikasikan.
Susanto, Mikke. 2002. Diksi Rupa Kumpulan Istilah Seni Rupa. Yogyakarta:
Kanisius.
Tocharman, Maman. 2006. Pendidikan Seni Rupa. Bandung: UPI Press.
Usman, Yusradi. 2010. Penyusutan Tutur dalam Masyarakat Gayo: Pendekatan
Ekolinguistik. [Tesis]. Medan: : Universitas Sumatera Utara.
Kajian Seni SD 77
BAB III
SENI MUSIK
A. Pengertian
Sejarah perkembangan musik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
budaya manusia. Hal ini disebabkan karena musik merupakan salah satu hasil
dari budaya manusia di samping ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa, sastra,
dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:602), musik
diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dan hubungan
temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai keseimbangan
dan kesatuan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga
mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Istilah seni musik berasal dari dua
kata yaitu “seni” dan “musik”. Seni artinya suatu hasil cipta, karsa maupun rasa
manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana. Sedangkan musik merupakan
kata yang berasal dari bahasa Yunani “mousikos”, melambangkan dewa
keindahan yang menguasai bidang keilmuan dan seni. Secara harfiah seni musik
dapat diartikan sebagai suatu karya sastra seniman yang diekspresikan
sedemikian rupa baik menggunakan alat musik dan vokal suara.
Pendapat Banoe (2003:288), mengemukakan bahwa musik yang berasal
dari kata muse (bahasa Yunani) merupakan cabang seni yang membahas dan
menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan
dipahami oleh manusia.
Pendapat lain tentang pengertian musik dikemukakan oleh Jamalus
(1988:1) bahwa musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk
lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya
melalui unsur-unsur pokok musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau
struktur lagu, serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.
Menurut Djohan (2006:36) kata musik berasal dari kata Yunani muse.
Dalam mitologi Yunani dikenal bahwa Sembilan muse, dewi-dewi bersaudara
yang menguasai nyanyian, puisi, kesenian, dan ilmu pengetahuan, merupakan
anak Zeus (Raja Para Dewa) dengan Mnemosyne (Dewi Ingatan). Dengan
demikian, musik merupakan anak cinta ilahiah yang keanggunan, keindahan,
dan kekuatan penyembuhannya yang misterius itu sangat erat hubungannya
dengan tatanan maupun ingatan surgawi tentang asal-usul dan takdir kita.
Sedangkan menurut Bernstein & Picker dalam Djohan, (2006:24) musik
adalah suara yang diorganisir ke dalam waktu. Musik juga bentuk seni tingkat
tinggi yang dapat mengakomodir interpretasi dan kreativitas individu.
Sekelompok orang dalam kegiatan musik tidak pernah menunjukkan adanya 2
orang yang mengekspresikan musik dengan cara yang mutlak sama.
78 Pengantar
Lebih jelas lagi Campbell (2002) mendefinisikan musik sebagai bahasa
yang mengandung unsur universal, bahasa yang melintasi batas usia, jenis
kelamin, ras, agama, dan kebangsaan. Musik muncul di semua tingkat
pendapatan, kelas sosial, dan pendidikan. Musik berbicara kepada setiap orang
dan kepada setiap spesies.
Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa musik
merupakan seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai
pengungkapan ekspresi diri yang diolah dalam suatu nada atau suara-suara yang
harmonis. Sebagai salah satu bagian dari seni, pengertian seni musik secara
umum merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada yang
mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu
(Rusyanti, 2013).
Seni musik (instrument art) adalah bidang seni yang berhubungan dengan
alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini
membahas cara menggunakan instrument musik. Masing-masing alat musik
mempunyai nada tertentu, di samping itu seni musik juga membahas cara
membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik
instrument. Seni musik dapat disatukan dengan seni vokal. Seni instrument
adalah seni suara yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik, sedangkan
seni vokal adalah melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantara
suara saja tanpa iringan instrument musik. Pada tingkat peradaban manusia yang
masih rendah, seni musik telah diinterpretasikan sedemikian rupa pada hampir
seluruh aspek kehidupan. Masyarakat primitif memanfaatkan musik tidak hanya
sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai alat untuk upacara ritual
keagamaan, adat kebiasaan, bahkan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan
sosial. Kesadaran dan penilaian mereka menunjukkan bahwa musik mempunyai
peran yang cukup penting dalam kehidupan manusia.
Salah satu peran yang cukup menonjol pada seni musik yaitu sebagai
mediator. Pada konteks ini seni musik merupakan bahasa umum yang
diekspresikan lewat simbol-simbol estetis. Sebagai alat komunikasi, musik
menjelma secara substansial menjadi sarana aktivitas interaktif antara musisi dan
pendengarnya. Pada tingkat inilah seni musik menunjukkan peran yang cukup
luas yang mencakup kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kehidupan
religius (keagamaan).
Musik pertama-tama akan diproses oleh auditory cortex dalam bentuk
suara agar dapat dinikmati oleh otak kanan. Otak kiri akan memproses lirik
dalam musik tersebut. Efek selanjutnya adalah pada sistem limbic (otak mamalia)
yang menangani memori jangka panjang. Sistem limbic ini menangani respon
terhadap musik dan emosi (Simatupang & Anggi, 2007:79). Sama halnya dengan
Rina dalam Muttaqin & Kustap, (2008:3) yang berpendapat bahwa musik
Kajian Seni SD 79
merupakan salah satu cabang kesenian yang pengungkapannya dilakukan
melalui suara atau bunyi-bunyian.
Musik merupakan salah satu bagian pokok dalam kehidupan manusia.
Hampir semua peradaban masyarakat di dunia ini memiliki musik sebagai hasil
budaya mereka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa musik berhubungan erat
dengan kehidupan sosilal masyarakat. Musik merupakan karya seni yang berupa
bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan
perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni,
bentuk dan struktur lagu (Jamalus,1988:1). Jadi musik memiliki hubungan erat
dengan bunyi. Menurut Ronald (1985:26) ” Without time and sound music can not
exist”, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tanpa bunyi dan waktu musik
tidak dapat terwujud. Menurut Hardjana (1983:56) ”bunyi sebagai isi didalam
musik menampilkan dirinya dalam bentuk ritme, melodi, harmoni, dan vitalis
musik lainnya”. Lebih jauh Hardjana menjelaskan kedudukan Bunyi di dalam
musik adalah sebagai isi dan bentuk sebagai kerangka. Jadi betapa pokoknya
bunyi didalam musik. Menurut Syafiq (2003:203) dalam bukunya yang berjudul
Ensiklopedia Musik Klasik, ”musik adalah seni pengungkapan gagasan melalui
bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni dengan unsur
pendukung berupa bentuk gagasan, sifat dan warna bunyi”.
Bunyi pada dasarnya adalah hasil dari getaran, namun tidak setiap
getaran yang menghasilkan bunyi itu musik. Bunyi yang bisa dikatakan musik
adalah bunyi yang berasal dari getaran yang teratur. Misalnya nada A harus
memiliki frekuensi getaran 440 hz .Jika lebih atau kurang dari 440 Hz/ second
maka bunyi dikatakan fals atau tidak sempurna. Seperti yang dikatakan Djohan
(2009:32)” bunyi (elemen vibrasi) dalam bentuk frekuensi, amplitudo, dan durasi
belum menjadi musik bagi manusia sampai semua di transformasikan secara
neurologis dan diinterpretasikan melalui otak menjadi : pitch (nada-harmoni),
timbre (warna suara), dinamika (keras lembut), dan tempo (cepat lambat)”. Jadi
setiap bunyi tidaklah selalu sebagai musik karena harus memiliki beberapa
elemen-elemen pokok pembentuk musik. Dalam Ronald (1985:26) elemen musik
dibagi menjadi tiga yaitu ;
1. Pitch
”A given sound is perceived as relatively high or low because of pitch”. Maksudnya
suara dapat dilihat dari tinggi dan rendahnya karena pitch. Selanjutnya lebih jelas
diterangkan bahwa, “Every definite pitch vibrates with specific frequency – it vibrates a
certain number of times per second. The higher the frequency, the higher the pitch”. Dari
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pitch diatentukan dengan frekuensi
yaitu banyaknya getaran dalam satu detik. Semakin tinggi frekuensinya maka
semakin tinggi pula nadanya.
80 Pengantar
2. Timbre
“Timbre is quality of and peculiar to a given instrument. A flute playing a given pitch
sounds distinctly different from a trumpet playing the same pitch.” Artinya timbre adalah
kualitas dari kekhasan yang diberikan oleh suara instrumen. Sebuah flute
yang dimainkan akan memberikan bunyi yang nyaring yang berbeda dengan
trumpet yang dimainkan dalam nada yang sama.
3. Volume
”Volume or amplitudo is the degree of loudnees dan softness.” Artinya volume atau
amplitude adalah tingkat keras atau lembut suara. Dalam musik lebih dikenal
juga dengan nama dinamik.
Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa musik
adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang
mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik
yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu
kesatuan.
B. Karakteristik Seni Musik untuk SD
Musik anak harus sesuai dengan perkembangan fisik yang mampu
menjadikan dirinya sebagai media pengungkapan perasaan, pikiran, isi hati anak.
Karakter musik anak seyogyanya dapat ditemukan tidak hanya pada semua aspek
musik tetapi juga seperti; aspek bunyi, nada, ritme, tempo dan dinamik serta
ekspresi dan bentuk musik. Selain itu seyogyanya musik anak seyogyanya
mampu memberikan kesempatan bagi perkembangan kreativitas berfikir dan seni
(rasa keindahan) anak serta dunia anak. Berikut ini karakteristik yang sebaiknya
muncul dalam musik anak adalah:
1. Musik sesuai dengan minat dan menyatukan dengan kehidupan anak sehari-
hari.
2. Ritme musik dan pola melodinya pendek sehingga mudah diingat
3. Nyanyian atau lagu tersebut juga harus mengandung unsur musik lainnya.
4. Melalui musik anak diberi kesempatan pula untuk bergerak melalui musik.
C. Fungsi Seni Musik
Seni musik sebagai seni yang berhubungan dengan bunyi/irama dan juga
syair memiliki fungsi yang berhubungan dengan kreativitas individu. Hal ini
diungkapkan oleh Rien (1999:1) yang mengemukakan tentang pendapat para
pakar pendidikan menyatakan bahwa seni musik mempunyai peranan yang
penting dalam kehidupan seorang siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam
kegiatan seni musik, selain dapat mengembangkan kreativitas, musik juga dapat
80 Pengantar
membantu perkembangan individu, mengembangkan sensitivitas, membangun
rasa keindahan, mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan, melatih
disiplin dan mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa mereka.
Seni musik juga berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi, keseriusan,
kepekaan terhadap lingkungan. Untuk menyanyikan atau memainkan musik
yang indah, diperlukan konsentrasi penuh, keseriusan dan kepekaan rasa mereka
terhadap tema lagu atau musik yang dimainkan. Sehingga pesan yang terdapat
pada lagu atau musik bisa tersampaikan dan diterima oleh pendengar.
Berdasarkan beberapa pandangan tentang fungsi pendidikan seni musik
bagi siswa yang sejalan dengan pendekatan “Belajar dengan Seni, Belajar Melalui
Seni, dan Belajar tentang Seni”, berikut ini dikemukakan secara urut fungsi
pendidikan seni musik sebagai sarana atau media ekspresi, komunikasi, bermain,
pengembangan bakat, dan kreativitas.
Dalam perkembangan ditengah pesatnya kemajuan di berbagai aspek
kehidupan, keindahan tidak lagi menjadi tujuan yang paling penting dalam
berkesenian. Sedangkan The Liang Gie berpendapat bahwa jenis nilai yang
melekat pada seni mencakup: 1) nilai keindahan, 2) nilai pengetahuan, 3) nilai
kehidupan. Fungsi musik dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yakni
sebagai berikut :
1. Seni musik sebagai sarana ekspresi diri; Ekspresi merupakan ungkapan atau
pernyataan seseorang. Perasaan dapat berupa sedih, gembira, risau, marah,
menyeramkan atau sesuai dengan masalah yang dihadapi. Fungsi ini
memungkinkan untuk mengeksplorasi ekspresi seseorang dalam memuncul-
kan karya-karya baru.
2. Seorang musisi akan lebih mudah meluapkan atau meluapkan perasaannya
lewat musik. Di samping untuk mengisyaratkan bakatnya, ekspresi perasaan
melalui musik akan lebih mudah dirasakan. Apalagi semisal musik tersebut
berupa vokal yang berisi lirik yang tersusun elok dan mudah dipahami,
disertai dengan iringan nada yang mewakili pengungkapan yang akan
dikeluarkan.
3. Seni musik sebagai media komunikasi; Ekspresi yang dieksplorasikan akan
dikomunikasikan kepada orang lain. Artinya karya-karya seni musik yang
dialami seseorang dikomunikasikan sehingga pesan yang terdapat dalam
karya tersebut bisa tersampaikan pada orang lain.
4. Di beberapa daerah di Indonesia, nada instrumen tertentu yang memiliki arti
tertentu juga untuk anggota golongan masyarakatnya. Bunyi-bunyian itu
mengandung pola ritme tertentu yang menandakan bahwa ada suatu
kejadian atau kegiatan yang ingin dibagikan kepada penduduk. Instrumen
yang sering dipakai dalam penduduk Indonesia adalah seperti kentongan,
bedug di surau, dan lonceng di gereja.
Kajian Seni SD 81
5. Seni musik sebagai sarana bermain dan hiburan ; Bermain merupakan dunia
anak-anak. Anak-anak memerlukan kegiatan yang bersifat rekreatif yang
menyenangkan bagi pertumbuhan jiwanya. Bermain sekaligus memberikan
kegiatan penyeimbang dan penyelaras atas perkembangan individu anak
secara fisik dan psikis.
6. Seni musik sebagai media pengembang bakat ; Setiap manusia memiliki
potensi di bidang seni musik yang luar biasa. Pendidikan seni musik
ditekankan untuk memberikan pemupukan yang terus menerus sehungga
diperlukan upaya efektif untuk menumbuhkan bakat seseorang.
7. Seni musik sebagai sarana terapi ; Musik sebagai terapi awal mulanya
diperkenalkan pada perang dunia ke-II untuk memulihkan korban perang.
Kini musik banyak digunakan untuk terapi penyakit mental atau
kelumpuhan organ tubuh. Musik juga dapat berguna untuk menyegarkan
sejenak sistem pola otak setelah lama dimanfaatkan saat bekerja.
8. Seni musik sebagai sarana upacara ; Musik di Indonesia, pasti akan selalu
berkaitan erat dengan upacara-upacara tertentu seperti perkawinan,
kelahiran, kematian, serta upacara spiritual dan kenegaraan. Di beberapa
daerah, bunyi dari suatu alat musik diyakini memiliki unsur magis.
9. Seni musik sebagai sarana komersial ; Bagi para seniman, musik merupakan
salah satu pundi-pundi penghasilan. Mereka merekam hasil karya mereka
dalam bentuk pita kaset atau CD.
10. Kemudian, karya mereka akan dijual ke pasaran. Dari hasil penjualannya ini
mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak
hanya dalam media kaset dan CD. Para seniman juga melakukan
pementasan yang dipungut biaya.
11. Musik juga sering dikontrak sebagai soundtrack sebuah film atau biasa
disebut OST (Original Soundtrack). Biasanya musik yang dijadikan sebagai
OST mempunyai keterkaitan terhadap film berupa keterkaitan kisah yang
dapat meluapkan isi dari film tersebut. Bahkan musik juga sering
dimanfaatkan sebagai OST dari sebuah Iklan, baik itu di televisi maupun
radio.
12. Musik sebagai sarana tari ; Musik sering kali dikaitkan dengan tarian.
Keduanya saling berkaitan dengan adanya kesamaan struktur dan ritme satu
diantara keduanya, suatu tarian tanpa disertai irama musik akan terasa
hampa (kosong) dan menyulitkan bagi sang penari.
13. Tatkala penari mendemokan gerak tarinya dibutuhkan tempo dan ritme agar
gerakannya elok. Di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik dibuat oleh
penduduk untuk mengisi tarian-tarian lokal.
82 Pengantar
14. Oleh karena itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya dapat diisi
oleh musik daerah nya sendiri. Barangkali di luar negeri juga seperti itu.
Seperti dansa, ballet dan lain sebagainya.
15. Seni musik sebagai sarana pendidikan ; Sebagai media pendidikan, musik
digunakan dalam proses belajar di sekolah. Musik dimanfaatkan untuk
meningkatkan rasa cinta tanah air kepada para siswa melalui lagu-lagu
perjuangan. Tak hanya itu itu, lagu daerah juga bisa digunakan untuk
pendidikan siswa dalam hal meningkatkan sikap tenggang rasa terhadap
perbedaan suku, ras dan agama.
16. Dalam pendidikan, musik juga dapat dimanfaatkan sebagai media
peningkatan diri siswa. Musik juga bisa mencetak kepribadian yang baik
untuk seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwasanya
musik dapat menanamkan perasaan halus dan budi yang halus dalam jiwa
manusia. Dengan musik, jiwa lebih mempunyai rasa akan harmoni dan
irama. Diantara keduanya ialah landasan yang bagus untuk menanamkan
rasa keadilan. Namun dalam pendidikan musik, mesti dijauhkan lagu-lagu
yang bersifat melemahkan jiwa serta mudah menanamkan nafsu buruk.
17. Seni musik sebagai sarana kreativitas ; Kreatif ialah sifat yang murni ada
pada diri manusia yang dikaitkan terhadap skill atau kekuatan untuk
menciptakan. Sifat kreatifitas ini selalu diperlukan untuk mengiringi
kepribadian manusia dalam rangka memenuhi keperluannya.
18. Seni musik sebagai sarana hiburan ; Musik sangat efisien dalam menghibur.
Selama suatu musik tersebut dianggap elok, sudah pasti musik tersebut dapat
menghibur. Seseorang bahkan memerlukan musik untuk menghibur diri jika
sedang bosan ataupun sedih. Lebih dari menghibur, musik juga dapat
melalaikan manusia dari kehidupan sehari-harinya.
D. Manfaat dan Tujuan Seni Musik
1. Manfaat Seni Musik
a. Meningkatkan suasana hati (mood)
Reaksi masing-masing individu kala mendengarkan musik memang berbeda.
Tetapi, apapun jenis musik yang kita pilih, sebuah penilitian 2011 di Kanada,
yang diterbitkan jurnal Nature Neuroscience menunjukkan bahwa mendengar
musik kesukaan kita akan merubah suasana hati dan membuat kita lebih
relax.
Sementara itu penelitian lain di McGill University Montreal:
“mendengarkan musik dapat memicu pelepasan hormon dopamin pada
tubuh”. “Otak sangat rumit, ada banyak unsur yang terlibat dalam
menciptakan perasaan senang, tidak mengherankan jika ada penilitian yang
Kajian Seni SD 83
menunjukkan bahwa pelepasan dopamin berhubungan dengan perasaan
senang,” kata Bridget O’Connell, kepala informasi dari Mental Health Charity
Mind.
b. Membantu agar fokus
Bukti menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat membantu kita
untuk berkonsentrasi. Sebuah alat digital tonic yang biasa disebut Ubrain,
mengklaim dapat membantu pikiran fokus serta rileks. Aplikasi ini
didasarkan pada binaural beats (yang dapat merangsang aktivitas tertentu di
otak) sehingga membantu kita untuk meningkatkan energi, pikiran dan
meningkatkan mood saat mendengarkan musik favorit.
“Dengan mem bantu korteks otak menghasilkan gelombang tertentu, kita
dapat menginduksi beberapa bagian pada otak tetap terjaga, tergantung yang
ingin kita lakukan,” jelas Paris psikolog klinis dari Brigitte Forgeot.
c. Meningkatkan daya tahan tubuh
Mendengarkan musik tertentu sebenarnya bisa membantu kita berlari lebih
cepat. Sebuah studi di Brunei University, London Barat telah menunjukkan
bahwa musik dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sebesar 15
persen, meningkatkan semangat dan efisiensi energi 1-2 persen.
Sebaiknya lagu yang dipilih harus sesuai dengan tempo olahraga kita.
Mendengarkan musik sambil olahraga akan memberikan efek metronomik
pada tubuh, sehingga memungkinkan kita untuk berolahraga lebih lama.
d. Kesehatan mental lebih baik
Musik juga sangat membantu bagi mereka yang bermasalah dengan kondisi
yang kurang stabil.
“Dua cara musik dijadikan sebagai media terapi, baik sebagai sarana
komunikasi dan ekspresi diri atau untuk kualitas ingeren restoratif atau
penyembuhan,” kata Bridget O’Connell.
e. Redakan stres
Riset tahun 2011 dari lembaga sosial kesehatan mental menunjukkan,
hampir sepertiga orang mendengarkan musik untuk memberikan semangat
ketika sedang bekerja. Dan satu dari empat oranng mengaku bahwa mereka
mendengarkan musik saat perjalanan ke tempat kerja untuk membantu
mengatasi stres.
f. Perawatan pasien
Musik ternyata juga sangat memberikan dampak besar positif untuk
membantu pengobatan penyakit jangka panjang, seperti penyakit jantung,
kanker dan kondisi pernapasan. Banyak percobaan telah menunjukkan
bahwa musik dapat membantu meredakan rasa sakit, kecemasan dan
meningkatkan kualitas hidup pasien.
84 Pengantar
“Musik dapat sangat berguna bagi seseorang yang berada dalam situasi di
mana mereka telah kehilangan kontrol dari lingkungan eksternal mereka,”
kata dr Williamson.
“Dengan musik mereka bisa mendapatkan kembali rasa kontrol itu dan
menciptakan ketenangan pada diri sendiri serta mencegah beberapa
gangguan yang ada di sekitar pasien,” tambahnya.
2. Tujuan Seni Musik
Setiap karya manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Termasuk karya
yang berupa musik, beberapa tujuan diciptakannya musik adalah sebagai
berikut ;
a. Tujuan Magis ; Musik pada tujuan ini, musik dianggap properti yang mampu
memperkuat suasana magis dalam ritual-ritual tertentu.
b. Tujuan Religius ; Musik dapat diciptakan sebagai pengakuan akan
keagungan Tuhan, sebagai sarana mendekatkan diri dengan Tuhan.
c. Tujuan Simbolis ; Karya musik yang diciptakan pada konteks ini memiliki
tujuan simbolis yang dapat menimbulkan kebanggaan terhadap sesuatu.
Seperti lagu kepahlawanan, atau lagu kebangsaan.
d. Tujuan Komersial ; Di sini sudah jelas, musik dijadikan barang yang dapat
membuahkan penghasilan bagi senimannya.
e. Tujuan Kreatif ; Tujuan penciptaannya semata-mata hanya untuk kepuasan
dirinya sendiri dan biasanya bersifat eksperimental.
f. Tujuan Rekreatif ; Musik diciptakan untuk hiburan semata.
E. Unsur-Unsur Seni Musik
Pada saat mempelajari musik, maka dasar pertama yang harus diketahui
adalah unsur unsur seni musik itu sendiri. Unsur-unsur seni musik adalah sebagai
berikut :
1. Melodi
Melodi yaitu suatu kesatuan frase yang terdiri dari bunyi-bunyi dengan
urutan, interval, dan tinggi rendah yang tersruktur. Diantara unsur-unsur seni
musik yang lain, melodi dinilai sebagai unsur yang menjadi daya tarik musik itu
sendiri. Melodi yang baik adalah melodi yang memiliki intervalnya dapat
terjangkau setiap alat musik ataupun suara manusia, artinya tidak terlalu tinggi
atau rendah. Melodi terdiri dari pitch, durasi, dan tone. Adapun untuk
menciptakan melodi, para musisi biasanya menggunakan perkusi atau media
musik melodis lainnya seperti piano, gitar, atau bonang.
Kajian Seni SD 85
2. Irama
Irama (ritme) ialah pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras
lembut nada atau suara dalam suatu gugusan musik. Secara sederhana, irama
dapat dapat diartikan sebagai penentu ketukan dalam musik. Irama akan
menentukan ketukan dalam musik. Ritme dapat dirasakan dengan
mendengarkan sebuah lagu secara berulang-ulang yang dapat melahirkan pola
irama. Pola irama ini akan memberikan perasaan ritmis pada seseorang. Adapun
munculnya unsur seni musik yang satu ini biasanya dikarenakan oleh
pengulangan suara, panjang pendek kata dalam lagu, atau karena pergantian
tekanan-tekanan kata.
3. Birama
Birama merupakan unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan
berulang-ulang yang datang dengan teratur pada waktu yang sama. Penulisan
birama acap kali ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan
seterusnya. Angka di atas tanda “/” (pembilang) menyiratkan jumlah ketukan,
sedangkan angka di atas tanda “/” (penyebut) menyiratkan nilai nada dalam satu
ketukan. Birama yang nilai penyebutnya genap disebut birama bainar, sedangkan
birama yang penyebutnya ganjil dinamakan birama ternair.
4. Harmoni
Harmoni ialah sekumpulan nada yang bila dimainkan bersama-sama
menjadi suara yang enak di dengar. Harmoni juga bisa didefinisikan sebagai suatu
deretan akord-akord yang disusun senada dan dimainkan sebagai iringan musik.
Harmoni memiliki elemen interval dan akor. Interval merupakan susunan nada
yang bila dibunyikan serentak akan terdengar harmonis, sedangkan akor akan
mengiringi melodi. Harmoni memberi nilai, bobot, dan bentuk tabuh dalam
jalinan sebuah melodi sehingga harmoni yang baik akan menjadikan sebuah lagu
menjadi indah.
5. Tangga Nada
Tangga nada ialah deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan
sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Tangga nada terdiri dari
do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis
dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diantonis adalah tangga nada yang
tercipta dari 7 buah nada dengan 2 jenis jarak (1/2 dan 1), sedangkan tangga nada
diatonis ialah tangga nada yang tercipta dari 5 buah nada dengan jarak tertentu.
6. Tempo
Tempo merupakan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Semakin cepat
suatu lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut.
Ukuran untuk menentukan tempo ialah beat, yaitu ketukan dasar yang digunakan
untuk menghitung banyaknya ketukan dalam satu menit. Satuan dari beat ialah
MM atau Metronome Mazel, yaitu alat pengukur tempo yang dibagi menjadi tiga
86 Pengantar
kriteria, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Unsur-unsur seni musik yang
satu ini digolongkan menjadi 8, yaitu Largo (Lambat Sekali), Lento (Lebih
Lambat), Adagio (Lambat), Andante (Sedang), Moderato (Sedang Agak Cepat),
Allegro (Cepat), Vivace (Lebih Cepat), dan Presto (Cepat Sekali).
7. Dinamik
Dinamik merupakan tanda untuk memainkan nada dengan volume
nyaring atau lembut. Di antara unsur-unsur seni musik yang lain, dinamika
menjadi unsur yang paling kuat menunjukkan perasaan yang terkandung dalam
suatu komposisi musik.Untuk menciptakan suatu musik tidak terdengar monoton
dan datar, maka suatu musik harus memiliki tingkatan keras dan lembutnya suatu
nada. Hal ini tercipta dari bagaimana pemusik memainkan alat musiknya.
Tingkatan nyaring dan lembut dalam memainkan sebuah nada disebut sebagai
unsur dinamis. Unsur ini menjadi unsur terkuat yang menggambarkan emosi dan
perasaan yang terkandung dalam sebuah karya seni musik, baik nuansa sedih,
agresif, riang, ataupun datar. Dinamika dinotasikan dalam singkatan sebagai
berikut f (forte), ff (fortissimo), fff (forte fortissimo), mf (mezzo forte), p (piano), pp
(pianissimo), ppp (piano pianissimo), mp (mezzo piano), > (crescendo), dan <
(decrescendo).
8. Timbre
Timbre adalah kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Unsur seni
musik satu ini keberadaannya sangat dipengaruhi sumber suara dan cara
bergetarnya. Timbre yang dihasilkan alat musik tiup pasti akan berbeda dengan
timbre yang dihasilkan dari alat musik petik, kendatipun keduanya dimainkan
dalam nada yang sama.
9. Ekspresi
Ekspresi merupakan ungkapan perasaan hati yang dituangkan melalui
mimik wajah, baik itu rasa sedih, kecewa, gembira, cinta, dan lainnya. Agar
penikmat hanyut dalam musik yang dibawakan, penyanyi harus mampu
berekspresi sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan melalui lagunya.
Pendidikan seni musik lebih menekankan pada pemberian pengalaman
seni musik, yang nantinya akan melahirkan kemampuan untuk memanfaatkan
seni musik pada kehidupan sehari-hari. Pendidikan seni musik diberikan di
sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap
kebutuhan perkembangan siswa, yang terletak pada pemberian pengalaman
estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi.
Pembelajaran seni musik dilaksanakan melalui pendekatan: “belajar dengan
seni”, “belajar melalui seni”, dan “belajar tentang seni” (BSNP, 2006). Peran ini
tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain.
1. Pendekatan “Belajar dengan Seni” Pendekatan ini menekankan pada proses
pemerolehan dan pemahaman pengetahuan yang didapatkan dengan
Kajian Seni SD 87
kegiatan seni musik misalnya siswa belajar menyanyikan lagu Indonesia
Raya, maka dengan mempelajari lagu tersebut siswa dapat mengetahui dan
memahami sikap apa yang terdapat pada lagu. Siswa seharusnya tahu
tentang apa yang diceritakan lagu dan dari pengetahuan tersebut mereka bisa
mengambil suatu simpulan bahwa lagu Indonesia Raya menginginkan
terwujudnya sikap cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotis.
2. Pendekatan “Belajar melalui Seni” Pendekatan ini menekankan pada
pemahaman emosional yang tercermin ke dalam penanaman nilai-nilai atau
sikap yang terbentuk melalui kegiatan berkesenian. Seperti dalam
menyanyikan atau memainkan sebuah lagu, siswa dituntut untuk membuat
keteraturan tempo/ketukan. Apabila siswa tidak bisa mengikuti tempo
tersebut maka lagu yang dibawakan menjadi kacau atau tidak teratur. Jadi
melalui bernyanyi atau bermain alat musik akan tertanam sikap disiplin yang
tinggi untuk membuat keteraturan.
3. Pendekatan “Belajar tentang Seni” Pendekatan ini lebih menekankan pada
pembelajaran tentang penguasaan materi seni musik yang tergambar pada
unsur-unsurnya seperti irama, melodi, dan harmoni.
Mahmud (1995) dalam Rachmawati (2005:16), menyatakan bahwa,
“unsur pokok musik adalah irama, melodi, dan harmoni”. Dalam sebuah lagu,
semua unsur musik itu muncul sebagai satu kesatuan. Berikut ini penjelasan
unsur-unsur musik.
1. Irama
Penggunaan istilah yang berhubungan dengan irama ini bermacam-
macam, dan berasal dari istilah-istilah asing, seperti ritme, ritem, ritmik.
Perbedaan istilah ini terjadi karena belum adanya pembakuan istilah bidang
musik. Mahmud (1995) menyatakan irama adalah denyut jantung musik yang
memberi rasa hidup (Rachmawati, 2005:16). Sejalan dengan pendapat Mahmud,
Sukarya, dkk. (2008:2.2.7) menjelaskan bahwa,“Ritme adalah pengaturan bunyi
dalam waktu”. Lebih lanjut Safrina (2002:63) menjelaskan bahwa irama ialah
rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. Irama dalam
musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam
lama waktu atau panjang-pendeknya sehingga membentuk pola irama, bergerak
menurut pulsa dalam ayunan birama. Irama dapat dirasakan, kadang-kadang
dirasakan dan didengar, atau dirasakan dan dilihat, ataupun dirasakan dan
didengar serta dilihat.
Jadi irama adalah pengaturan bunyi dalam waktu yang dapat dirasakan,
didengar, atau bahkan dilihat sehingga memberi rasa hidup. Alat musik pembawa
irama yang dipelajari di SD masih sederhana, seperti maracas, kendang,
tamborin, dan sebagainya. Pembelajaran irama diajarkan sebelum pembelajaran
melodi karena berkaitan dengan unsur waktu dan keteraturan pembunyian.
88 Pengantar
2. Melodi
Alat musik pembawa melodi yang dipejari di SD contohnya rekorder dan
pianika. Pembelajaran melodi di SD berkaitan dengan penguasaan tinggi
rendahnya nada, berbeda dengan irama yang tanpa menggunakan ketinggian
nada. Sukarya, dkk. (2008:2.2.7) menjelaskan bahwa,“Melodi adalah serangkai-
an nada dalam waktu”. Lebih lanjut, Safrina (2002:124) menjelasakan melodi
ialah susunan rangkaian nada yang terdengar berurutan serta berirama, dan
mengungkapkan suatu gagasan, pikiran, dan perasaan. Rangkaian tersebut dapat
dibunyikan sendirian, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari
rangkaian akord dalam waktu (biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi
dalam akord-akord tersebut). Sejalan dengan hal tersebut, Mahfud (1995)
menyatakan bahwa, “melodi adalah jiwa musik yang menyimpan daya kekuatan
serta dapat menggerakkan pikiran dan perasaan” (Rachmawati, 2005:16).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bawa melodi
adalah serangkaian nada dalam waktu yang berurutan dan berirama serta
menggerakan pikiran dan perasaan. Rachmawati (2005:17) menjelaskan bahwa
di dalam melodi terkandung (1) jangkauan atau pola yang pasti akan tinggi
rendah nada, (2) selingan tinggi nada yang disimak melalui sedikit atau
banyaknya interval, dan (3) pengaturan nada.
Melodi dituliskan dalam berbagai lambang atau notasi, Notasi
merupakan bagian terpenting dari musik, yang menurut Martinus (2001:404)not
adalah tanda tertulis yang memiliki titi nada. Martinus juga mengartikan notasi
sebagai proses membuat tanda nada. Sedangkan menurut Banoe (2003:299)
notasi adalah lambang atau tulisan musik. Notasi musik yaitu notasi huruf,
notasi angka, dan notasi balok. Notasi huruf adalah melodi yang dituliskan atau
dilambangkan dengan huruf. Notasi huruf merupakan notasi paling mudah yang
didasarkan pada bunyi nadanya. Kita membaca notasi melodi dengan do re mi fa
sol la si do. Tangga nada do re mi fa sol la si do apabila ditulis dengan notasi huruf
menjadi d r m f s l t d’. Agar tidak ada keraguan untuk membaca atau menyanyikan
nada sol dan si maka si diganti dengan ti sehingga notasinya menjadi t. Notasi
angka adalah melodi yang dituliskan atau dilambangkan dengan angka. Angka-
angka yang digunakan adalah angka:
1 2 3 4 5 6 7i
Do Re Mi Fa Sol La Si do
Notasi angka juga menggunakan tanda titik (·) untuk memperjelas
penulisan notasi. Tanda titik (·) digunakan dalam dua macam fungsi, yaitu
sebagai tanda tinggi rendah nada dan sebagau tanda jumlah/panjang ketukan.
Untuk nada rendah, titik diletakkan di bawah nada yang dimaksud, sedangkan
untuk nada tinggi diletakkan di atas nada yang dimaksud. Berikut ini contoh
penggunaan tanda titik (·) yang berfungsi sebagai tanda tinggi rendah nada.
Kajian Seni SD 89
Nada Rendah Nada Tinggi · ·
· 6 7
5675
···
Tanda titik digunakan untuk tanda penambahan jumlah atau panjang
ketukan suatu nada. Titik diletakkan setelah nada yang dimaksud.
Contoh:
1. Penambahan 2 ketukan │3 · · 4│
2. Penambahan 1 ketukan │2 · 3 4│
Notasi balok adalah melodi yang dituliskan atau dilambangkan dengan
gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam
not balok sesuai dengan tinggi-rendah dan sifat bunyi yang dilambangkan. Pada
pembelajaran di SD notasi balok jarang digunakan karena memiliki tingkat
kesulitan yang lebih tinggi daripada notasi lainnya.
3. Harmoni
Harmoni disebut juga dengan paduan nada. Sukarya, dkk. (2008:2.2.7)
menyatakan bahwa harmoni adalah kejadian dua nada atau lebih dengan tinggi
nada yang berbeda dan dibunyikan bersamaan. Sejalan dengan pendapat
tersebut, Safrina (2002:156) menjelaskan bahwa harmoni adalah susunan
gabungan dua nada atau lebih dengan tinggi nada yang berbeda yang kita dengar
serentak.
Musik dikatakan harmoni jika ia berhasil memadukan dua jenis bunyi-
bunyian atau lebih menjadi bunyi yang indah dan enak didengar. Mahfud(1995)
mengungkapkan bahwa,“harmoni adalah bingkai komposisi yang menopang
melodi serta memberi sifat dan warna tertentu pada musik” (Rachmawati,
2005:16). Jadi harmoni adalah dua nada atau lebih yang dibunyikan secara
serentak serta memberi sifat dan warna tertentu pada musik. Harmoni yang terdiri
dari tiga nada atau lebih yang dibunyikan bersamaan biasanya disebutakord.
Karakter musik untuk siswa SD adalah musik anak yang seyogyanya
tepat dengan hakikat perkembangan anak ditinjau dari segi biologis, jiwa,
maupun kemampuan berpikir serta minat anak (Sukarya, 2008:4.3.5). Karakter
musik anak harus dibuat atau dipilih yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan anak. Musik tersebut harus memberikan
kesempatan seluas-luasnya yang mendorong perkembangan kreativitas berpikir
serta kreativitas seni anak.
Pemilihan musik atau lagu untuk siswa harus memperhatikan
perkembangan gerak psikomotorik. Misalnya bila musik tersebut untuk musik
instrumentalia maka pemilihan alat-alat musik yang digunakan disesuaikan
dengan kemampuan gerak siswa. Tidak mungkin siswa usia 10 tahun harus
90 Pengantar
memainkan cello atau saxophon. Ukuran alat musik harus disesuaikan dengan
pertumbuhan tubuh anak. Aspek perkembangan berpikir siswa SD adalah hal lain
yang perlu menjadi pertimbangan guru yang ingin mengajarkan nyanyian. Salah
satu daya tarik siswa SD mau berlatih menyanyi atau memainkan alat musik
adalah karena siswa berminat pada hal-hal yang menarik perhatian mereka. Guru
perlu memilih tema lagu yang menjadi minat siswa. Lagu yang dipilih sebaiknya
lagu yang memiliki nilai pendidikan yang baik.
Pada awal usia sekolah, anak sudah mampu menghasilkan pitch secara
tepat. Anak lebih mudah memahami perubahan serangkaian nada yang teratur
daripada yang acak. Hal tersebut merujuk pada pendapat Djohan (2009:45-46)
yang menyatakan: Anak-anak sudah mampu mereproduksi sebuah frase pendek
dalam berbagai variasi dengan pitch yang tepat. Oleh sebab itu, kemampuan
untuk menghasilkan pitch secara akurat dan apresiatif terhadap tangga nada serta
kunci nada dasar telah berkembang ketika awal usia sekolah. Perubahan yang
terjadi dalam serangkaian tangga nada yang teratur lebih mudah dideteksi
daripada rangkaian nada yang acak. Dan, pilihan yang timbul untuk mengakhiri
sebuah kalimat melodi lebih pada nada yang stabil dari kunci yang didengar.
Selain harus sesuai dengan perkembangan fisik, daya pikir, dan minat siswa,
musik siswa juga harus musik yang mampu menjadikan dirinya sebagai media
pengungkapan perasaan, pikiran, dan isi hati anak. Musik siswa seharusnya
mampu memberikan kesempatan bagi perkembangan kreativitas berpikir dan
kreativitas seni (rasa keindahan) siswa, serta dunia siswa. Menurut Pamadhi, dkk.
(2011:3.25-3.26) beberapa karakteristik yang sebaiknya muncul dalam musik
siswa adalah:
1. Musik sesuai dengan minat dan kehidupan siswa sehari-hari. Musik harus
mengandung hal-hal yang menarik perhatian anak, seperti lagu yang
menggambarkan tentang khayalan anak dan cerita peristiwa tingkah laku
binatang yang jenaka.
2. Ritme musik dan pola melodinya pendek agar mudah diingat sehingga guru
dapat meminta siswa untuk berimprovisasi, mengubah melodi, atau teks lagu
sesuai dengan kemampuan dan kreativitas siswa.
3. Nyanyian harus mengandung unsur musik lainnya, seperti tempo, dinamik,
bunyi, dan ekspresi musik yang dapat diolah dan diganti serta diekspresikan
siswa sehingga siswa berkesempatan memperloleh pengalaman mengolah
bunyi melalui musik. Misalnya siswa diberi kesempatan untuk memainkan
musik dengan tempo yang berbeda-beda, menambahkan suara lain dalam
karya tersebut.
4. Siswa diberi kesempatan untuk bergerak melalui musik. Siswa dapat
menghasilkan bunyi melalui gerak tubuhnya dengan cara memukulkan
tongkat, bertepuk tangan, menghentakkan kaki, dan sebagainya.
Kajian Seni SD 91
F. Jenis-jenis Aliran dalam Seni Musik
Banyak cara yang dapat digunakan oleh musisi untuk mengungkapkan
ekspresinya lewat musik. Terlebih lagi dengan kebebasan seni musik dan
perkembangan teknologi di zaman modern ini. Hal ini menciptakan aliran/genre
dalam seni musik. Masing-masing genre terbagi lagi menjadi beberapa sub-genre.
Pengkategorian musik seperti ini, meskipun terkadang merupakan hal yang
subjektif, namun merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dan ditetapkan oleh
para ahli musik dunia, antara lain adalah:
1. Blues
Blues adalah nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan genre
musik yang diciptakan terutama dalam Masyarakat Afrika-Amerika di Deep
South Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dari lagu rohani, lagu kerja, hollers
lapangan, teriakan, dan narasi sederhana berirama balada . The blues di mana-
mana... dalam bentuk jazz, R&B, dan rock n roll dicirikan oleh kord progresif
tertentu dengan dua belas bar akord miring progresi yang paling umum dengan
nada miring, mencatat bahwa untuk tujuan ekspresif yang dinyanyikan atau
dimainkan secara bertahap rata atau menekuk (minor 3 untuk 3 major)
sehubungan dengan lapangan dari major scale.
2. Pop
Musik pop (istilah yang awalnya berasal dari singkatan dari "populer")
adalah sebuah genre musik dari musik populer yang berasal dalam bentuk
modern pada 1950-an, yang berasal dari rock and roll. Istilah musik populer dan
musik pop sering digunakan secara bergantian, meskipun yang pertama adalah
deskripsi musik yang populer (dan dapat termasuk gaya apapun), sedangkan yang
terakhir adalah genre tertentu yang mengandung kualitas daya tarik massa.
Sebagai genre, musik pop sangat eklektik, sering meminjam elemen dari gaya-
gaya lain termasuk urban, dance, rock, latin dan country. Musik pop umumnya
dianggap sebagai sebuah genre yang komersial dicatat dan keinginan untuk
memiliki daya tarik audiens massa.
3. Dangdut
Dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik yang berkembang
di Indonesia. Bentuk musik ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an.
Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-
unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan
harmonisasi). Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka
masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar
listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh
dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik
populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari
keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan house music.
92 Pengantar
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Pengantar kajian seni merupakan buku yang berisikan empat cabang seni yang terdiri seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni drama.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search