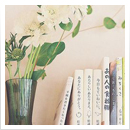Penyebutan nama “dangdut” merupakan onomatope dari suara permainan tabla
(dalam dunia dangdut disebut gendang saja) yang khas dan didominasi oleh
bunyi dang dan ndut. Nama ini sebetulnya adalah sebutan sinis dalam sebuah
artikel majalah awal 1970-an bagi bentuk musik melayu yang sangat populer di
kalangan masyarakat kelas pekerja saat itu.
4. Jazz
Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan blues, ragtime,
dan musik Eropa, terutama musik band. Beberapa subgenre jazz adalah dixieland,
swing, bebop, hard bop, cool jazz, free jazz, jazz fusion, smooth jazz, danCafJazz.
5. R&B
R&B adalah genre musik populer yang menggabungkan jazz, gospel, dan
blues, yang pertama kali diperkenalkan oleh pemusik Afrika-Amerika. Pada
tahun 1948, perusahaan rekaman RCA Victor memasarkan musik kaum kulit
hitam yang disebut Blues and Rhythm. Pada tahun yang sama, Louis Jordan
mendominasi lima besar tangga lagu R&B dengan tiga lagu, dan dua dari lagunya
berdasar pada ritme boogie-woogie yang terkenal pada tahun 1940-an. Band
Jordan, Tympany Five (1938) terdiri dari dirinya sebagai vokal dan pemain
saksofon beserta musisi-musisi lain sebagai pemain trompet, saksofon tenor,
piano, bas, dan drum.Istilah ini pertama kali dipakai sebagai istilah pemasaran
dalam musik di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh Jerry Wexler yang bekerja
pada majalah Billboard. Istilah ini menggantikan istilah musik ras dan kategori
Billboard Harlem Hit Parade pada Juni 1949. Tahun 1948, RCA Victor
memasarkan musik kulit hitam dengan nama Blues and Rhythm. Frasa tersebut
dibalik oleh Wexler di Atlantic Records, yang menjadi perusahaan rekaman yang
memimpin bidang R&B pada tahun-tahun awal.
6. Death Metal
Death metal adalah sebuah sub-genre dari musik heavy metal yang
berkembang dari thrash metal pada awal 1980-an. Beberapa ciri khasnya adalah
lirik lagu yang bertemakan kekerasan atau kematian, ritme gitar rendah
(downtuned rhythm guitars), perkusi yang cepat, dan intensitas dinamis. Vokal
biasanya dinyanyikan dengan gerutuan (death grunt) atau geraman maut (death
growl). Teknik menyanyi seperti ini juga sering disebut “Cookie Monster vocals”.
7. Rock
Genre Rock adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara
umum pada pertengahan tahun 50an. Akarnya berasal dari rhythm and blues,
musik country dari tahun 40 dan 50-an serta berbagai pengaruh lainnya.
Selanjutnya, musik rock juga mengambil gaya dari berbagai musik lainnya,
termasuk musik rakyat (folk music), jazz dan musik klasik. Bunyi khas dari musik
rock sering berkisar sekitar gitar listrik atau gitar akustik, dan penggunaan back
beat yang sangat kentara pada rhythm section dengan gitar bass dan drum, dan
Kajian Seni SD 93
kibor seperti organ, piano atau sejak 70-an, synthesizer. Disamping gitar atau
keyboard, saksofon dan harmonika bergaya blues kadang digunakan sebagai
instrumen musik solo. Dalam bentuk murninya, musik rock “mempunyai tiga
chords, bakcbeat yang konsisten dan mencolok dan melody yang menarik”. Pada
akhir tahun 60-an dan awal 70-an, musk rock berkembang menjadi beberapa
jenis. Yang bercampur dengan musik folk (musik daerah di Amerika) menjadi folk
rock, dengan blues menjadi blues-rock dan dengan jazz, menjadi jazz-rock fusion.
Pada tahun 70an, rock menggabungkan pengaruh dari soul, funk, dan musik latin.
Juga pada tahun 70an, rock berkembang menjadi berbagai subgenre (sub-
kategori) seperti soft rock, glam rock, heavy metal, hard rock, progressive rock, dan
punk rock. Sub kategori rock yang mencuat pada tahun 80an termasuk New Wave,
hardcore punk dan alternative rock. Pada tahun 90an terdapat grunge, Britpop,
indie rock dan nu metal. Contoh Band yang menggunakan Genre Rock : My
Chemical Romance.
8. Reggae
Reggae merupakan irama musik yang berkembang di Jamaika. Reggae
mungkin jadi bekas di perasaan lebar ke menunjuk ke sebagian terbesar musik
Jamaika, termasuk Ska, rocksteady, dub, dancehall, dan ragga. Barangkali istilah
pula berada dalam membeda-bedakan gaya teliti begitu berasal dari akhir 1960-
an. Reggae berdiri di bawah gaya irama yang berkarakter mulut prajurit tunggakan
pukulan, dikenal sebagai “skank”, bermain oleh irama gitar, dan pemukul drum
bass di atas tiga pukulan masing-masing ukuran, dikenal dengan sebutan “sekali
mengeluarkan”. Karakteristik, ini memukul lambat dari reggae pendahuluan, ska
dan rocksteady. Contoh Band yang menggunakan genre Reggae : Steven And
Coconut Treez.
9. Lagu Anak-Anak
Lagu anak-anak adalah lagu yang dirancang sedemikian rupa, baik lirik
maupun melodinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Melodi lagu
anak umumnya bertempo sedang dan kaya pengulangan. Sementara liriknya
disusun dengan bahasa yang sederhana, mudah diucapkan, dan kaya
pengulangan. Sesuai kebutuhan anak untuk bermain, lagu untuk anak harus
dapat digunakan untuk mengiringi anak bermain.
10. Lagu Daerah
Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan, adalah lagu atau
musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan
baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya
pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias noname. Lagu kedaerahan
mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja.
Lagu kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya
94 Pengantar
masing-masing seperti tondok kadadingku dari Jawa Barat dan Rasa Sayange dari
Maluku.
Lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan
atau dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu pada masing-masing daerah, misal
pada saat menina-bobok-kan anak, permainan anak-anak, hiburan rakyat, pesta
rakyat, perjuangan rakyat, dan lain sebagainya.
11. Lagu Kebangsaan
Lagu kebangsaan adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi
dan menjadi simbol suatu negara atau daerah. Lagu kebangsaan dapat
membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi
dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme.
G. Referensi
Banoe, Pono. 2003. Kamus Musik. Yogyakarta: Kanisius.
Campbell. 2002. Introduction to Remote Sensing: Third Edition. New York: The
Guilford Press.
Djohan. 2009. Psikologi Musik. Yogyakarta: Buku Baik.
-------. 2006. Terapi Musik Teori dan Aplikasi.Yogyakarta. Galangpress
Jamalus. 1988. Panduan Pengajaran buku Pengajaran musik melalui pengalaman
musik. Jakarta: Proyek pengembangan Lembaga Pendidikan.
KBBI. Alwi Hasan. 2005. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai
Pustaka
Hardjana, Suka. 1983. Estetika Musik. Jakarta:Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Mahmud, A.T. 1995. Musik dan Anak. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Mustaqin & Kustap. 2006. Musik Klasik: Pengantar Musikologi Untuk SMK.
Departemen Pendidikan Nasional
Pamadhi, Hajar & Evan Sukardi. 2011. Seni Keterampilan Anak. Jakarta:
Universitas Terbuka.
Rachmawati, Yeni & Euis Kurniati. 2005. Strategi Pengembangan Kreativitas
Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak. Jakarta : Depdikbud.
Rien, Safarina. 1999. Pendidikan Seni Musik. Bandung: Maulana.
Ronald, L. Byrnside. 1985. Musik Sound and Sense. United State of America :
Wm.C. Brown Publishers.
Rusyanti, hetty. 2013. Pengertian Musik Menurut para Ahli.
http://www.kajianteori.com/2013/02/pengertian-musik-definisi-
musik-menurut.html. (Diakses pada tanggal 29 Mei 2017).
Safrina, Rien. 2002. Seni Musik. Bandung: Alfabeta.
Simatupang dan Anggi. 2007. Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Musik.
Medan: UNM
Sukarya, Mahmud. 2008. Pustaka Nada 230 Lagu Anak-Anak. Jakarta: PT.
Grasindo.
Syafiq. 2003. Ensiklopedia Musik Klasik. Yogyakarta:Adicita Karya Nusa.
Kajian Seni SD 95
BAB IV
SENI TARI
A. Pengertian
Pada bab IV ini akan dibahas cabang seni yang berhubungan dengan
gerakan. Cabang seni tersebut adalah seni tari. Tari dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1991: 1011) didefinisikan sebagai gerakan badan (tangan dan
sebagainya) yang berirama dan biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan,
dan sebagainya). Dan penari diartikan sebagai orang yang pekerjaannya menari.
Menurut Rohkyatmo (1986: 74) tentang pengertian tari, yaitu beberapa orang ahli
tari telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi tari, dimana
kesemuanya selalu berkisar pada materi pokok yang sama, yaitu gerak ritmis yang
indah sebagai ekspresi jiwa manusia, dengan memperhatikan unsur ruang dan
waktu.
Tari sebagai hasil kebudayaan yang sarat makna dan nilai, dapat disebut
sebagai sistem simbol. Sistem simbol adalah sesuatu yang diciptakan oleh
manusia dan secara konvensional digunakan bersama, teratur, dan benar-benar
dipelajari, sehingga memberi pengertian hakikat manusia, yaitu suatu kerangka
yang penuh dengan arti untuk mengorientasikan dirinya kepada yang lain;
kepada lingkungannya, dan pada dirinya sendiri, sekaligus sebagai produk dan
ketergantungannya dalam interaksi sosial (Hadi, 2005:22).
Tari sebagai bagian dari seni menggunakan tubuh manusia sebagai
media. Dalam bentuk penyajiannya tari ditopang oleh berbagai elemen yaitu:
gerak tari, pola lantai, iringan, tata rias dan busana, properti serta tempat
pementasan” (Hermin, 1980:9).
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tari merupakan
sebuah seni atau kesenian yang berupa gerakan badan yang ritmis sebagai
ekspresi jiwa yang menimbulkan keindahan. Indonesia memiliki aneka ragam
tari, hal ini dipengaruhi oleh keragaman budaya dan suku bangsa yang dimiliki.
Tari sebagai sebuah kesenian tumbuh mengikuti perkembangan zaman yang
selalu dipengaruhi kebutuhan hidup yang beranekaragam dan kemudian
menuntut terjadinya perubahan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai pelaku
seni tersebut. Tari juga hadir dan berfungsi dan berperan pada lingkungan tertentu
yang memiliki adat istiadat dan tata masyarakat. Menurut Nursantara (2007:35-
36) tari dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya tari tradisional,
tari nusantara, tari kreasi dan tari kontemporer. Diantara kesemua jenis tari yang
ada, tari tradisional merupakan jenis tari yang perjalanan perkembangannya
paling lama karena dilakukan dengan berpegang pada pola tertentu yang sudah
mentradisi.
96 Pengantar
B. Karakteristik Tari Anak
Sebelum membahas tentang karakteristik tari anak akan diuraikan
mengenai karakteristik gerak pada anak. Karakteristik gerak pada
anak umumnya, yaitu mereka dapat melakukan dengan berbagai kegiatan-
kegiatan pergerakan menirukan Apabila seorang guru dapat menunjukkan
kepada anak didik suatu action yang dapat diamati (observable), maka anak akan
mulai membuat tiruan action tersebut sampai pada tingkat otot-ototnya dan
dituntut oleh dorongan kata hati untuk menirukannya. Bahwa dalam
perkembangan umumnya anak dapat melakukan kegiatan-kegiatan bergerak
sebagai berikut :
1. Menirukan, seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya dalam upaya
pengembangan kreativitas tari bahwa dalam bermain anak senang
menirukan sesuatu yang dilihat. Anak dapat menirukan gerakan-gerakan
yang dilihat baik dari televisi ataupun gerakangerakan yang secara langsung
dilakukan oleh orang lain, berdasarkan tema maupun gerakan-gerakan
binatang yang diamati.
2. Manipulasi, dalam kegiatan ini anak-anak secara spontan menampilkan
berbagai gerak-gerak dari obyek yang diamatinya. Namun dalam
pengamatan dari obyek tersebut anak akan menampilkan sebuah gerakan
yang hanya disukainya.
3. Keseksamaan (precision). Ini meliputi kemampuan anak didik dalam
penampilan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi dan
memproduksi suatu kegiatan tertentu.
4. Artikulasi, yang utama disini anak didik telah dapat mengkoordinasikan
serentetan action dengan menetapkan urutan/sikuen tepat diantara pada
action yang berbeda-beda.
5. Naturalisasi, tingkat terakhir dari kemampuan psikomotorik adalah apabila
anak telah dapat melakukan secara alami satu action atau sejumlah action
yang urut. Keterampilan penampilan ini telah sampai pada kemapuan yang
paling tinggi dan action tersebut ditampilkan dengan pengeluaran energi yang
minimum (Sunaryo,1984).
Gerak fisik menurut Kamtini dan Tanjung (2005:23) bahwa secara
keseluruhan dapat dikatakan bahwa karakteristik gerak fisik anak adalah:
1. Sederhana,
2. Bersifat maknawi dan bertema, artinya tiap gerak mengandung tema
tertentu,
3. Gerak anak menirukan gerak keseharian orang tua dan juga orang-orang
yang berada di sekitarnya,
4. Anak juga menirukan gerak-gerak binatang.
Kajian Seni SD 97
Seorang guru dalam menata sebuah tari-tarian bagi anak harus
memperhatikan dua hal yaitu, harus memperhatikan bagian-bagian tubuh yang
dapat dilatih dari karakteristik atau ciri-ciri gerak anak. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan untuk dapat memberikan tari yang sesuai dengan karakteristik
anak yaitu ada beberapa butir yang harus diketahui antara lain:
1. Tema
Bahwa pada umumnya anak-anak selalu menyenangi apa yang pernah dia
lihat. Dari apa yang dilihatnya secara tidak disadari atau disadari dengan
spontan. Anak akan menirukan gerak-gerak yang sesuai dengan apa yang pernah
dilihatnya.
Dari gerak-gerak yang pernah dilihat dan diamati oleh anak maka dapat
dijadikan suatu tema. Tema-tema yang pada umumnya disenangi oleh anak-anak
diantaranya adalah tingkah laku binatang seperti : kucing, anjing, burung, kupu-
kupu, bebek dan lain-lain. Anak juga menirukan tingkah laku manusia seperti :
ayah, ibu, dokter, insinyur dan lain-lain. Contohnya tingkah laku binatang seperti
: kucing, anjing, burung, dan lain-lain serta tingkah laku manusia seperti : ayah,
ibu, dokter, dan lain-lain.
2. Bentuk Gerak
Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik tari anak-anak, pada
umumnya gerak-gerak yang dilakukannya tidaklah terlalu sulit dan sangat
sederhana sekali. Mengingat pada dasarnya imajinasi anak tinggi dan
mempunyai daya kreativitas yang tinggi pula. Dan bentuk-bentuk gerak yang
biasa dilakukan adalah bentuk gerak-gerak yang lincah, cepat dan seakan
menggambarkan kegembiraannya. Misalkan : bentuk gerak jalan ditempat
dengan tepuk-teuk tangan.
3. Bentuk Iringan
Dilihat dari karakteristik anak yang senang bergerak dengan gembira, anak
biasanya menyenangi musik iringan yang menggambarkan kesenangan dan
kegembiraan. Terutama lagu-lagu anak yang mudah diingat, misalnya : lagu
kelinciku, kebunku, kupu-kupuku dan lain-lain. Misalnya : lagu keleinciku,
kebunku, kupu-kupu, dan lain-lain.
4. Jenis Tari
Apabila suatu karya cipta gerak tari sudah tersusun dan menjadi satu
kesatuan tari anak, maka dibentuklah menjadi satu bentuk tari dan sebuah jenis
tari yang sesuai dengan karakteristik dan sifat anak yang memiliki sifat
kegembiraan atau kesenangan, geraknya yang lincah dan sederhana, dan iringan
musiknya pun mudah dipahami oleh anak. Misalkan tari gembira, tari kupu-
kupu, tari kelinci, dan lain-lain.
98 Pengantar
C. Unsur-Unsur Seni Tari
Agar tercipta gerakan ritmis yang estetis, unsur unsur seni tari harus
diperhatikan untuk membangun dan menciptakan gerakan tubuh tersebut.
Seperti layaknya sebuah organisasi yang punya ketua, sekretaris, bendahara, dan
anggota, begitupula tari. Ada dua unsur unsur seni tari yang membangunnya
yaitu unsur utama dan unsur tambahan.
1. Unsur Utama
`Unsur utama seni tari adalah unsur esensial dan pokok yang harus melekat
dalam sebuah tarian. Apabila salah satu dari unsur ini hilang atau tidak
diperhatikan, maka suatu pertunjukkan sendratari tidak akan harmonis. Rasanya
ada yang kurang, bahkan bisa jadi penonton tidak lagi dapat mengerti maksud
dari tarian tersebut.
Maka dari itu, unsur utama ini menjadi poin penting keberhasilan suatu tari
yang dibawakan. Juga, menjadi penilaian penting apabila tari ini menjadi
pertunjukkan yang dinilai oleh ahli seni. Berikut tiga unsur utama dalam seni tari:
a. Wiraga (raga)
Wiraga dalam bahasa Jawa berarti raga, yang dalam konteks seni tari biasa
dikenal dengan gerakan. Tarian harus menonjolkan gerakan tubuh yang dinamis,
ritmis, dan estetis. Meskipun, memang tidak semua gerakan dalam suatu seni tari
memiliki maksud tertentu. Gerak biasa atau gerak murni adalah gerakan dalam
sebuah tarian yang tidak memilki maksud tertentu, sedangkan gerak maknawi
adalah gerakan dalam sebuah tarian yang memiliki makna mendalam dan
memiliki maksud tertentu.
Secara umum, melalui gerakan penari, penonton bisa menebak karakter yang
dimainkan. Misalnya gerak memutar pergelangan tangan pada tari yang
dibawakan oleh wanita memiliki arti keluwesan atau kelembutan. Begitu pula
gerakan berdecak pinggang pada tari yang dibawakan oleh pria bisa memiliki arti
wibawa dan kekuasaan.
Tanpa gerakan, sebuah seni tari tidak memiliki makna dan menjadi hampa
karena memang yang namanya tari harus ada unsur gerakan. Maka dari itu,
wiraga termasuk ke dalam unsur utama sebuah seni tari.
b. Wirama (irama)
Tidak mungkin sebuah seni tari hanya melulu penari bergerak kesana kemari
tanpa adanya musik yang mengiringi. Musik berfungsi untuk mengiringi gerakan
penari. Dengan adanya musik, suatu gerakan akan lebih memiliki makna karena
tercipta suasana tertentu.
Seorang penari harus bisa menari sesuai dengan irama, ketukan, dan tempo
pengiringnya sehingga bisa harmonis dan estetis di mata penonton. Selain itu,
irama juga bisa sebagai isyarat bagi penari kapan harus memulai atau mengganti
sebuah gerakan. Hal ini sangat berguna ketika sebuah tarian dibawakan oleh
100 Pengantar
banyak penari sehingga setiap penari tidak tergantung gerakannnya pada penari
lain tetapi bisa menyamakan sendiri dengan irama pengiring.
Irama yang digunakan bisa berupa rekaman (biasa digunakan untuk
kepentingan pendidikan) ataupun iringan langsung dari instrumen musik (seperti
gamelan, kecapi, atau alat musik tradisional lain). Namun, tidak menutup
kemungkinan irama yang mengiringi tarian berupa tepukan tangan, hentakan
kaki, maupun nyanyian. Apapun bentuknya, irama digunakan sebagai pelengkap
sebuah gerakan tari. Meskipun berfungsi sebagai pengiring, irama juga termasuk
ke dalam unsur utama.
c. Wirasa (rasa)
Seni tari harus bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada
penonton melalui gerakan dan ekspresi penari. Oleh karena itu, seorang penari
harus bisa menjiwai dan mengeskpresikan tarian tersebut melalui mimik wajah
dan pendalaman karakter. Sebagai contoh, apabila karakter yang dimainkan
adalah gadis desa yang lembut maka selain gerakan yang lemah gemulai, penari
juga harus menampilkan mimik wajah yang mendukung.
Unsur ini akan makin menguatkan suasana, karakter, dan estetika sebuah
seni tari bila dikombinasikan dengan irama dan gerakan yang mendukung.
Dengan adanya rasa dalam sebuah tari, penonton bisa makin mudah menangkap
maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh penari. Maka, unsur rasa ini tidak
dapat terlepas dari unsur esensial seni tari. Tanpa adanya rasa, makna tarian tidak
akan dapat tersampaikan kepada penonton
Setelah mengetahui unsur utama yang harus ada dalam sebuah tarian, alangkah
baiknya bila kita juga mengetahui unsur tambahannya. Memang, unsur ini
adalah pelengkap dari ketiga unsur unsur seni tari di atas tapi tidak serta merta
dapat diabaikan begitu saja karena unsur ini sangat mendukung sebuah tarian.
Bisa jadi, apabila beberapa unsur tambahan ini tidak diperhatikan juga dapat
mempengaruhi keberhasilan sebuah pertunjukkan sendaratari.
2. Unsur Pendukung
a. Tata Rias dan Kostum
Tidak mungkin sebuah pertunjukkan tarian menampilkan penari dengan
kostum dan riasan seadanya. Pasti ada riasan khusus dan kostum yang
sesuai dengan tarian dan karakter yang dibawakan oleh penari. Unsur ini
mendukung terciptanya suasana tarian dan menyampaikan karakter serta
pesan secara tersirat.
b. Pola Lantai
Tarian akan indah apabila penari bisa menguasai pola lantai. Tidak hanya
melulu berada di tengah panggung tapi juga bergerak kesana kemari
sehingga tidak membuat penonton bosan karena monoton. Hal ini juga
Kajian Seni SD 101
sangat penting untuk tarian yang dibawakan oleh banyak penari supaya
antar penari tidak saling bertabrakan sehingga gerakan yang ditampilakan
dapat selaras, kompak, dan teratur.
c. Setting Panggung
Seni pertunjukkan tari yang baik akan memperhatikan pengaturan
panggungnya. Hal ini penting karena dengan adanya panggung yang
sesuai tarian, tidak terlalu sempit, dan tertata rapi akan menimbulkan
kesan pada penonton. Setting panggung yang dimaksud juga termasuk
pencahayaan. Sekiranya, panggung sendratari tidak terlalu terang tetapi
juga tidak terlalu gelap. Intinya, penata ruangan harus bisa menyesuaikan
dengan tari yang akan dibawakan.
d. Properti
Dalam tarian tertentu, penari akan membawa properti. Properti ini
merupakan alat pendukung seperti selendang, piring, payung, lilin.
Meskipun memang tidak semua tarian menggunakan properti, unsur ini
juga perlu diperhatikan untuk mendukung visualisasi tarian.
Dengan adanya aksesoris penunjang, penonton makin yakin bahwa tarian
yang dibawakan telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Selain itu, juga ada
aksesoris penunjang yang memudahkan penonton untuk mengetahui
karakter tarian yang dibawakan.
Kedua unsur tersebut baik unsur utama maupun pendukung saling
melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila unsur-unsur
tersebut diperhatikan dan dipadukan dengan harmonis maka pesan yang ingin
disampaikan kepada penonton dapat tersampaikan dengan baik.
D. Fungsi Tari
Sebagai suatu karya seni, tari memiliki fungsi dalam pelaksanaannya.
Fungsi seni tari tidak statis namun ada yang bergeser meskipun bentuknya tidak
berubah, atau ada yang fungsinya bergeser serta bentuknya berubah, atau fungsi
dan bentuknya saling tumpang tindih. Kurath dalam Soedarsono (1995:17-18)
menjelaskan ada 14 macam fungsi seni (tari), yaitu: 1) Upacara pubertas; 2)
Upacara inisiasi; 3) Percintaan; 4) Persahabatan; 5) Upacara perkawinan; 6)
Pekerjaan; 7) Upacara kesuburan; 8) Perbintangan; 9) Upacara perburuan; 10)
Lawakan; 11) Perang; 12) Pengobatan; 13) Upacara kematian; 14) Tontonan.
Penyusunan gerak dalam seni tari, gerak dari masing-masing penari
maupun dari kelompok penari bersama, ditambah dengan penyesuaiannya
dengan ruang, sinar, warna, dan seni sastranya, kesemuanya merupakan suatu
pengorganisasian seni tari yang disebut koreografi (Djelantik, 1990:23).
102 Pengantar
Secara umum, fungsi seni tari adalah sebagai hiburan, media pergaulan,
media pendidikan dan pertunjukan. Seni tari mempunyai fungsi yang berbeda-
beda tergantung jenisnya. Seni tari terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari upacara, tari
hiburan dan tari pertunjukan. Berikut adalah jenis-jenis seni tari berdasarkan
fungsinya
1. Sarana upacara
Tari jenis ini sebagai sarana upacara banyak macamnya, seperti untuk
upacara keagamaan atau upacara penting lainya. contohnya adalah tari pendet
dari Bali yang digunakan saat upacara keagamaan, para penari membawa bokor
yang berisi bunga sebagai sesaji untuk persembahan. Selain itu ada tari Gantar
dari Kalimantan, disajikan saat upacara adat selamatan untuk Dewi Sri.
2. Sarana Hiburan
Tari jenis ini tujuannya untuk menghibur penonton, biasanya penonton
yang ikut terhibur juga ikut menari karena lagunya enak dan mengasyikkan.
Contoh tari hiburan adalah tari Tayub dari Jawa Tengah, ini adalah tari hiburan
yang dipertunjukkan sehabis panen. Contoh lainnya ada juga tari Giring-Giring
dari Kalimantan, tari Serampang Duabelas dari Sumatera dan tari Maengket.
3. Sarana Penyaluran Terapi
Tari jenis ini ditunjukkan untuk yang berkebutuhan khusus seperti
penyandang cacat fisik. Penyalurannya dilakukan secara langsung dan tidak
langsung.
4. Sarana Pendidikan
Tari jenis ini mempunyai tujuan untuk mendidik anak agar bersikap
dewasa dan terjaga dari pergaulan yang melanggar norma-norma.
5. Sarana Pergaulan
Tari jenis ini merupakan tari yang melibatkan beberapa orang. maka dari
itu kegiatan itu bisa berfungsi sebagai sarana pergaulan.
6. Sarana Pertunjukkan
Tari jenis ini dipentaskan atau dipertunjukkan dengan persiapan yang
matang dari segi artistik, koreografi, interpretasi, konsepsional dan tema yang
menarik. Tari pertunjukkan juga mempunyai peran untuk mengembangkan
pariwisata daerah. Salah satu contohnya adalah Sendratari Ramayana yang
dipertunjukkan untuk menarik para wisatawan yang datang ke Yogyakarta.
7. Sarana Katarsis
Katarsis artinya pembersihan jiwa. Seni tari ini sebagai sarana katarsis
yang mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai penghayatan seni
mendalam seperti para seniman.
Kajian Seni SD 103
E. Jenis-Jenis Tari
Jenis-jenis tari yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok, seperti bahasan berikut.
1. Tari tradisional
Tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada.
Tarian ini diwariskan secara turun temurun. Sebuah tarian tradisional biasanya
mengandung nilai filosofis, simbolis dan relegius. Semua aturan ragam gerak tari
tradisional, formasi, busana, dan riasnya hingga kini tidak banyak berubah.
2. Tari tradisional klasik
Tari tradisional klasik dikembangkan oleh para penari kalangan
bangsawan istana. Aturan tarian biasanya baku atau tidak boleh diubah lagi.
Gerakannya anggun dan busananya cenderung mewah. Fungsi : sebagai sarana
upacara adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh : Tari Topeng Kelana
(Jawa Barat), Bedhaya Srimpi (Jawa Tengah), Sang Hyang (Bali), Pakarena dan
pajaga (Sulawesi Selatan)
3. Tari tradisional kerakyatan
Berkembang di kalangan rakyat biasa. Gerakannya cenderung mudah
Ditarikan bersama juga iringan musik. Busananya relatif sederhana. Sering
ditarikan pada saat perayaan sebagai tari pergaulan. Contoh: Jaipongan (Jawa
Barat), payung (Melayu), Lilin (Sumatera Barat)
4. Tari kreasi baru
Merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Dirancang
menurut kreasi penata tari sesuai dengan situasi kondisi dengan tetap memelihara
nilai artistiknya. Tari kreasi baik sebagai penampilan utama maupun sebagai
tarian latar hingga kini terus berkembang dengan iringan musik yang bervariasi,
sehingga muncul istilah tari modern. Pada garis besarnya tari kreasi dibedakan
menjadi dua golongan yaitu:
a. Tari Kreasi Baru Berpolakan Tradisi ; yaitu tari kreasi yang garapannya
dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi,
musik/karawitan, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya.
Walaupun ada pengembangan tidak menghilangkanesensiketradisiannya.
b. Tari Kreasi Baru Tidak Berpolakan Tradisi (Non Tradisi) ; Tari Kreasi yang
garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam hal koreografi,
musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun tarian ini
tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama sekali tidak
menggunakan unsur-unsur tari tradisi, mungkin saja masih
menggunakannya tergantung pada konsep gagasan penggarapnya. Tarian ini
104 Pengantar
disebut juga tari modern, yang istilahnya berasal dari kata Latin “modo”
yang berarti baru saja.
5. Tari kontemporer
Gerakan tari kontemporer simbolik terkait dengan koreografi bercerita
dengan gaya unik dan penuh penafsiran. Seringkali diperlukan wawasan khusus
untuk menikmatinya. iringan yang dipakai juga banyak yang tidak lazim sebagai
lagu dari yang sederhana hingga menggunakan program musik komputer seperti
Flutyloops.
F. Gerak Dasar Tari
Elemen penting dalam tari adalah gerak, yaitu gerak-gerak yang memiliki
nilai ritmis tertentu dan erat hubungannya dengan tempo dan dinamika gerak.
Gerak yang ada dalam kegiatan dan kehidupan kita sangat banyak macamnya,
antara lain :
1. Gerak dasar kepala
a. Kedet, yaitu gerakan kepala seolah menarik dagu
b. Gedug, yaitu kepala tegak di gerakan kesamping kanan dan kiri. Gedug
angka delapan, yaitu gerak kepala dengan memfokuskan putaran dagu
seolah menulis angka angka delapan dengan diakhiri gerak hedot
c. Gilek, yaitu gerak kepala membuat lengkungan kebawah kiri dan kanan
d. Godegreud, yaitu gerak gilek diakhiri gerak kedet
e. Galieur, yaitu gerak halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu,
kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah diakhiri dengan
kedet
2. Gerak dasar tangan
a. Meber, yaitu kedua tangan kesamping, telapak tangan menghadap ke
belakang
b. Nangreu, yaitu kedua tangan kedepan, empat jari lurus keatas ibujari
ditekuk
c. Nyampurit, yaitu kedua tangan kedepan, telapak tangan kedalam ibu
jari dan jari telunjuk membuat lingkaran
d. Mereket, yaitu telapak tangan dikepalkan
e. Rumbe, yaitu kedua tangan kesamping, telapak tangan keluar lima jari
lurus kebawah
f. Ngaplek, yaitu kedua tangan kesamping, telapak tangan keluar lima jari
lurus kebawah tali, yaitu kedua tangan nangreu lalu disilangkan
g. Mungkur, yaitu kedua tangan kedepan ditekuk kedua telapak tangan
menghadap keluar punggung tangan disatukan
Kajian Seni SD 105
h. Nyawang, yaitu tangan ditekuk tepat dimuka kepala (seperti hormat)
i. Sembah, yaitu telapak tangan dirapatkan tepat didepan hidung
j. Capit soder, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari keatas, jari manis
dan jari kelingking disatukan
k. Jiwir soder, yaitu ibu jari dan jari tengah membuat lingkaran lalu
disatukan
l. Kepret soder, yaitu kedua tangan sikap mungkur didepan perut lalu
kesampingkan dengan cara menggerakan kelima jari
m. Ukel, yaitu gabungan dari gerak mungkur, ngaplek, rumbe, dan nangreu
dengan cara diputarkan
n. Lontang, yaitu tangan kanan kedepan dengan posisi nangreu tangan kiri
kedepan dengan posisi nyampurit
o. Capang, yaitu tangan kanan kedepan nangreu dan tangan kiri ditekuk
nangreu
p. Selut, yaitu tangan kanan nangreu dan tangan kiri rumbe dengancara
tangan kiri yang rumbe ditarik keatas
q. Baplang, yaitu tangn kanan serong nangreu dan tangan kiri kesamping
rumbe
3. Gerak dasar kaki
a. Adeg-adeg masekon, yaitu kaki kanan dilangkahkan, serong kanan
serong kiri kaki tetap diam
b. Adeg-adeg serong, yaitu sikap kaki sama adeg-adeg masekon hanya
badan menjadi serong kanan
c. Adeg-adeg kembar, yaitu sikap tumit kaki merapat telapak kaki dibuka
d. Tengkoh, yaitu gerak kaki dengan kedua lutut ditekuk sikap badan
merendah
e. Jangreng, sikap kaki lurus / tegak
f. Sasag, yaitu gerak sikap posisi tumit sejajar dengan mata kaki
4. Gerak dasar calik
a. Sila mando, yaitu kedua kaki disilangkan dengan sikap cantik
b. Calik deku, yaitu kedua lutut untuk menyentuh lantai badan tegak
c. Calik jengkong, yaitu sikap badan tegap duduk diatas tumitkiri/kanan
d. Calik ningkat, yaitu lutut kiri dan kanan diangkat duduk di atastumit
kaki
106 Pengantar
Berikut Gambar Gerak Dasar Tari:
1. Ragam Gerak Kepala
2. Ragam Gerak Badan
3. Ragam Gerak Tangan 107
Kajian Seni SD
4. Ragam Gerak kaki
contoh lain teknik tari
108 r:
Pengantar
Sumber: https://tetisecret.blogspot.com/2019/01/
G. Referensi
Djelantik, M.A.A. 1990. Pengantar Dasar Ilmu Estetika. Denpasar: STSI.
Hadi, Y. Sumandiyo. 2005. Sosiologi Tari. Yogyakarta: Pustaka.
Kamtini, dan Tanjung, Husni Wardhi. 2005. Bermain Melalui Gerak dan Lagu di
Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Kajian Seni SD 109
Laelasari, Elly dan Sabaria, Ria. 2010. Praktik Seni Tari. Jakarta: Pusat Perbukuan
Kementian Pendidikan Nasional.
Nalan, Arthur S. 1996. Kapita Selekta Tari. Bandung: STSI Press Bandung.
Narawati, Tati dan Masunah, Juju. 2012. Seni dan Pendidikan Seni. Bandung :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Seni Tradisional
(P4ST) UPI.
Nugrahaningsih, RHD dan Heniwati, Yusnizar. 2012. Tari. Identitas dan
Resistensi. Medan: Unimed Perss.
Nursantara, Yayat. 2007. Seni budaya untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.
Nurwani. 2007. Pengetahuan Tari. Diktat Jurusan Sendratasik, FBS Universitas
Negeri Medan.
Rohkyatmo, Amir. 1986. Pengetahuan Tari Sebuah Pengantar. Jakarta : Direktorat
Kesenian Proyek Pengembangan Kesenian Jakarta Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Rosala, Dkk. 1999. Bunga Rampai Tarian khas Jawa Barat. Bandung: Humaniora
Utama Press
Sudarsono. 1995. Tari-Tarian Indonesia I. Jakarta: Proyek Pengembangan Media
Kebudayaan Departement Pendidikan dan Kebudayaan.
Sunaryo. 1984. Evaluasi Hasil Belajar. Jakarta: P2LPTK.Dikti. Depdikbud.
110 Pengantar
BAB V
SENI TEATER/DRAMA
A. Pengertian
Kata drama berasal dari bahasa Greek; tegasnya dari kata kerja dran yang
berarti “berbuat, to act atau to do”. Drama berarti perbuatan, tindakan, atau
beraksi (action). Drama cenderung memiliki pengertian ke seni sastra. Di dalam
seni sastra, drama setaraf dengan jenis puisi, prosa/esai. Drama juga berarti suatu
kejadian atau peristiwa tentang manusia. Cerita konflik manusia dalam bentuk
dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan
aktion dihadapan penonton (audience) (Depdiknas, 2011:5)
Sementara Bethaazar Verhagen yang dikutip oleh Slamet Mulyana dalam
Depdiknas, 2011:6) mengatakan bahwa drama adalah kesenian melukiskan sifat
dan sifat manusia dengan gerak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa drama pada dasarnya adalah salah satu cabang seni sastra
yang mementingkan dialog, gerak, dan perbuatan menjadi suatu lakon yang
dipentaskan di atas panggung. Drama juga adalah seni yang menggarap lakon-
lakon mulai sejak penulisannya hinggga pementasannya yang membutuhkan
ruang, waktu, dan khalayak atau hidup yang disajikan dalam gerak yang memuat
sejumlah kejadian yang memikat dan manarik hati.
Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah “sandiwara”. Istilah ini diambil
dari bahasa Jawa “sandi” dan “warah”, yang berarti pelajaran yang diberikan
secara diam-diam atau rahasia (sandi artinya rahasia, dan warah artinya
pelajaran). Istilah sandiwara seperti yang dipakai pada sandiwara radio atau
sandiwara pentas menunjukkan bahwa kata sandiwara dapat menggantikan kata
drama. Selain kedua istilah di atas, kita juga mengenal istilah teater. Teater dan
drama pada dasarnya memiliki arti yang sama, tetapi berbeda uangkapannya.
Teater berasal dari kata yunani kuno "theatron" yang secara harfiah berarti
gedung/tempat pertunjukan. Dengan demikian maka kata teater selalu
mengandung arti pertunjukan/tontonan. Jika peristiwa atau cerita tentang
manusia kemudian diangkat ke suatu pentas sebagai suatu bentuk pertunjukan,
maka menjadi suatu peristiwa Teater. Kesimpulannya teater tercipta karena
adanya drama.
Hal senada diungkapkan oleh Tarigan dalam Depdiknas, (2011:7) bahwa
dalam sastra Indonesia drama dipisahkan atas dua pengertian. Pertama, drama
sebagai text play atau naskah karya sastra milik pribadi, yaitu naskah bacaan milik
penulis drama yang masih membutuhkan pembaca soliter dan perlu digarap yang
baik dan teliti jika ingin dipentaskan. Kedua, drama sebagai teater atau
Kajian Seni SD 109
pementasan adalah seni kolektif atau pertunjukan yang siap dipentaskan sehingga
berfungsi sebagai tontonan pertunjukan.
Istilah drama datang dari khazanah kebudayaan Barat. Istilah drama
berasal dari kebudayaan atau tradisi bersastra di Yunani. Hal ini sesuai dengan
yang dinyatakan Krauss (1999:249) dalam bukunya Verstehen und Gestalten,
“Gesang und Tanz des altgriechischen Kultus stammende künstlerische Darstellungsform,
in der auf der Bühne im Klar gegliederten dramatischen Dialog ein Konflikt und seine
Lӧsung dargestellt wird”. (drama adalah suatu bentuk gambaran seni yang datang
dari nyanyian dan tarian ibadat Yunani kuno, yang di dalamnya dengan jelas
terorganisasi dialog dramatis, sebuah konflik dan penyelesaiannya digambarkan
di atas panggung).
Secara ringkas tentang seni drama (teater) dapat dikemukakan sebagai
berikut. Drama pada hakekatnya adalah life presented in action (Moulton melalui
Harymawan, 1993: 1). Dasar drama adalah konflik kemanusiaan yang selalu
menguasai perhatian dan minat umum. Dasar itulah yang selanjutnya disebut
the law of drama (Ferdinand Brunetiere melalui Harymawan, 1993:9) yang
berpokok bahwa lakon harus menghidupkan pernyataan kehendak manusia
menghadapi dua kekuatan yang saling beroposisi, yang secara teknis disebut
‘kisah dari protagonis’ (yang menginginkan sesuatu) dan ‘antagonis’ (yang
menentang dipenuhinya keinginan tersebut).
Seni drama bisa ditarik masuk ke dua dunia, yakni ke dunia sastra
(literature) dan ke dunia seni pertunjukan (performance art). Drama bisa ditarik
masuk ke dunia sastra, mengingat bahwa sebelum ada peristiwa teater (teatrikal),
drama berbentuk lakon atau tertulis (sering disebut naskah drama). Drama tertulis
(lakon) adalah salah satu bentuk sastra yang sengaja ditulis atau dibuat khusus
untuk dipanggungkan (Oemarjati, 1971:12). Setiap lakon merupakan cerita yang
dikarang dan disusun untuk dipertunjukkan oleh para pelakunya di atas
panggung di depan publik (Brahim, 1968:52). Elemen-elemen sastra dalam drama
harus dipandang pada tiga sendi, yakni isi, bentuk, dan kerangka (Tambajong,
1981:24-37). Dari sendi isinya, drama harus mengandung persoalan-persoalan
inti kehidupan. Ungkapan ini akan menentukan kuat tidaknya pengarang
terhadap masalah yang diusungnya. Dari sendi bentuknya, setiap drama dari
kurun ke kurun setidaknya mengandung gaya dan cara menyajikan cerita yang
berbeda-beda dan cenderung mandiri. Dari berbagai bentuk yang ada, dikenal
tiga modus yang penting, yaitu modus bahasa (gaya yang dipakai dalam
penulisan, terikat atau tidak pada kaidah-kaidah bahasa), modus aliran (gaya
yang ditentukan oleh sikap yang tumbuh pada kurun-kurun tertentu yang
kemudian menjadi pola), dan modus sajian (bentuk dramatiknya, apa yang
terkandung dalam jalinan perasaan yang menunjang cerita).
110 Pengantar
Drama bisa ditarik masuk ke dunia seni pertunjukan, mengingat bahwa
drama memang pertunjukan kisah hidup dari kehidupan manusia yang
diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak, dengan media
percakapan, gerak dan laku, dengan atau tanpa dekor, didasarkan pada naskah
tertulis (hasil seni sastra) dengan atau tanpa nyanyian, musik, tarian (Ramelan,
1980:10). Drama adalah cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang
diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action di
hadapan penonton (audience) (Harymawan, 1993:2).
Sebagai seni pertunjukan, drama berhasil dijelmakan oleh sebuah kerja
kolektif. Kerabat kerja (crew) yang terlibat di dalamnya adalah: produser (jika
diperlukan) adalah orang yang bertugas mendanai segala biaya produksi),
sutradara adalah pimpinan artistik tertinggi yang menafsirkan lakon untuk
diterjemahkan menjadi pertunjukan, pengarang adalah orang yang bertugas
menulis naskah/sastra lakon/repertoar, pemain yaitu orang yang bermain di
dalam drama/aktor/aktris, penata pakaian (orang yang bertugas
mendesain/menata kostum yang akan dikenakan oleh pemain), penata dekor
(orang yang bertugas menterjemahkan kemudian mewujudkan keinginan
sutradara mengenai setting panggung/pentas dari drama yang akan digelar),
penata rias (orang yang bertugas mewujudkan riasan wajah pemain sesuai dengan
karakter masing-masing yang diinginkan dalam naskah), penata lampu (orang
yang bertugas mendesain dan bertanggung jawab urusan penyinaran dan
pencahayaan di pentas), penata musik (orang yang bertanggung jawab memberi
iringan musik untuk setiap adegan),
stage manager (orang yang pada saat pertunjukan berlangsung bertanggung jawab
atas kelancaran pertunjukan, yakni memimpin
crew teknik), dan petugas publikasi, penjual karcis, pengatur penonton (jika
dikehendaki/diperlukan) (Ramelan, 1980:25-37).
Drama hadir dengan mengusung berbagai unsur di dalamnya, di
antaranya theme, plot/dramatic conflict, setting, dan style. Pertama, theme (tema)
artinya dasar (Lubis, t.t.), gagasan yang akan dikemukakan (Caraka, 1976),
merupakan the controlling idea in a literary work; the insight or concept to be revealed by
it (Lisle, t.t.), atau the subject of discourse; the underlying action or movement; or general
topic, of which the particular story is an illustration (Shipley, 1971). Kedua, plot,
dramatic conflict, alur cerita, adalah struktur penyusunan kejadian dalam cerita
yang disusun secara logis dalam hubungan kausalitas (Oemarjati, 1971). Plot is
that framework of incidents, however simple or complex, upon which the narrative or drama
is constructed; the events of the depicted struggle, as organized into an artistic unit (Shipley,
1971), merupakan the series of action or episodes which are arranged by the author to lead
to a climax and denouement in a dramatic or narrative work (Lisle, t.t.). Adapun
bangunan plot terdiri atas lima bagian, yakni situation, generating circum stances,
Kajian Seni SD 111
rising action, climax, dan denouement (Lubis, t.t.). Ketiga, setting adalah latar
belakang tempat dan waktu, merupakan salah satu unsur drama yang
menyatakan waktu dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam lakon
(Sumaryadi, 1979). Maka, setting umumnya mencerminkan keadaan yang wajar
atau sewajarnya. Sebagai ilustrasi, salah satu ciri drama konvensional adalah
selalu memberikan tekanan pada adanya ‘persoalan ruang’, yakni orang-orang
atau tokoh-tokoh di dalamnya hanya bergerak di antara ruang-ruang yang sempit.
Keempat, style, gaya (bahasa) adalah pancaran jiwa pengarang (Adinegoro,
1966). Style is a term of literary criticism, viewed as specific by some and as generic by
oyhers, use to name or describe the manner or quality of an expression (Shipley,1971).
Drama dikelompokkan sebagai karya sastra karena media yang
dipergunakan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pengarangnya adalah
bahasa (Budianta, dkk, 2002:112). Pendapat lain yang memperkuat kedudukan
drama sebagai karya sastra adalah bahwa drama termasuk ke dalam ragam sastra
karena ceritanya bersifat imajinatif dalam bentuk naskah drama (Zulfahnur. dkk,
1996:23). Marquaβ (1998:6) pun menyatakan, “Das Lesedrama ist ein spezielle Form
des Dramas, die nicht in erster Linie aufgeführt, sondern wie ein Roman gelesen werden
soll“ (naskah drama adalah sebuah bentuk khusus dari drama yang tidak untuk
dipentaskan, melainkan untuk dibaca selayaknya roman).
Ditilik dari segi bentuk, penulisan naskah drama sangat berbeda dengan
jenis karya sastra lain. Drama menurut Budianta (2002:95) adalah sebuah genre
karya sastra yang penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya
dialog atau cakapan di antara tokoh-tokoh yang ada. Bentuk verbal ini
ditunjukkan oleh Marquaβ (1998:9) dalam bukunya yang berjudul Dramentexte
Analysieren, yakni sebagai berikut. Hierbei muss der Dramentext zunächst einmal in
den Hauptext und den Nebentext untergliedert werden. Unter dem Haupttext versteht man
die Figurenrede, also den Text, den die Schauspieler während der Aufführung aufder Bühne
sprechen sollen. Dieser besteht überwiegend aus Dialogen (Gesprächen von zwei oder mehr
Figuren) und seltener aus Monologen (Selbstgespräch).
Oleh karena itu, teks drama dibagi menjadi Haupttext (teks utama) dan
Nebentext (teks pendamping). Haupttext adalah pembicaraan para tokoh, yakni
teks yang semestinya dikatakan para pemain selama pertunjukan di atas
panggung. Hal ini terdiri dari dialog (percakapan antara dua atau lebih tokoh)
dan terkadang monolog (berbicara dengan diri sendiri).
Menurut Kabisch (1985:43), dialog adalah “Wechselrede zwischen zwei oder
mehr Personen. Kuzmittel zur Entfallung von Handlung und Charakter (pergantian
percakapan antara dua orang atau lebih. Pendeknya untuk mengembangkanalur
dan karakter). Dengan keahlian pengarang dalam menentukan kata, melakukan
diksi, pada dialog-dialog para tokohnya sehingga tercerminlah siapa tokoh dan
bagaimana karakter-karakternya. Di samping dialog, terdapat pula monolog,
112 Pengantar
yang diartikan Kabisch (1985: 43) sebagai Selbstgespräch. Als epischer Monolog,
Beschreibung nicht darzustellender Situationen als betrachtender Monolog deutender
Kommentar (in der Funktion ähnlich dem griechischen Choir) als Konflikt-Monolog, um
Entscheindung ringendes Selbstgespräch auf dem hӧhen Punkt der Handlung.
Monolog adalah percakapan dengan diri sendiri. Sebagai monolog epik,
penggambaran bukan menggambarkan situasi sebagai monolog pengamat,
memperjelas komentar (fungsinya hampir sama dengan koor yunani), sebagai
monolog konflik, untuk membuat suatu keputusan dalam puncak alur.
Berdasarkan pengertian di atas, adanya dialog dan monolog adalah
bagian dari Haupttext (teks utama) yang merupakan salah satu unsur drama.
Marquaβ menjelaskan bahwa dialog dan monolog adalah bentuk dari
komunikasi dalam drama. Jika drama tidak komunikatif, maksud pengarang,
pembangun respon emosional tidak akan sampai. Selanjutnya keberadaan
Nebentext juga sangat penting dalam membangun keutuhan suatu drama, karena
melalui Nebentext-lah latar waktu, tempat, dan suasana drama dapat diketahui.
Hal ini dinyatakan Marquaβ (1998:9) Unter dem Nebentext versteht man zusätzliche
Angaben des Authors zur Ausstattung der Bühne, zum Äuβeren und zum Verhalten der
Schauspieler (Regieanweisungen). Hier zu gehӧren auch die Kennzeichnung oder
Nummerierung der Handlungsteile, gegebenenfals ein Personenverzeichnis und anderes.
Artinya, pada Nebentext orang akan mengerti keterangan pelengkap dari
pengarang tentang dekorasi panggung, penampilan dan tingkah laku aktor
(petunjuk instruksi). Di sini juga termasuk penandaan atau penomoran bagian-
bagian cerita, jika perlu daftar personil dan lain-lainnya.
Kesatuan peranan fungsi dialog dan monolog inilah yang menjadikan
drama istimewa. Hasanudin, (1996:2) mengungkapkan bahwa, tanpa
dipentaskan sekalipun, karya drama tetap dapat dipahami, dimengerti dan
dinikmati. Segers (2000:25) menyampaikan sebuah definisi kerja teks sastra
adalah seperangkat tanda-tanda verbal yang eksplisit, terbatas, dan terstruktur,
serta fungsi estetisnya dirasakan dominan oleh pembaca. Jadi, berdasarkan
pengertian-pengertian di atas, jelas bahwa drama memenuhi hakikatnya sebagai
karya sastra.
Drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di
atas pentas dengan media percakapan (dialog), gerak dan tingkah laku. Naskah
merupakan hal utama dalam bermain drama (modern) karena ia merupakan
panduan bagi para pemeran (aktor) di atas pentas. Selain naskah, ada unsur-unsur
lain yang sangat menentukan yaitu dekorasi (setting), musik, lighting, make up,
kostum, nyanyian, tarian, dan unsur penunjang lainnya. Menurut Aminuddin
dan Roekhan (2003:84) unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah drama adalah:
Kajian Seni SD 113
1. Penokohan dan Perwatakan
Unsur utama dalam karya drama adalah pelaku. Dalam cerita pelaku
berfungsi untuk (1) menggambarkan peristiwa melalui lakuan, dialog, dan
monolog, (2) menampilkan gagasan penulis naskah secara tidak langsung, (3)
membentuk rangkaian cerita sejalan dengan peristiwa yang ditampilkan, dan (4)
menggambarkan tema atau ide dasar yang ingin dipaparkan penulis naskah
melalui cerita yang ditampilkan. Fungsi tersebut dapat memberikan gambaran
bahwa untuk memahami peristiwa, gagasan pengarang, rangkaian cerita, dan
tema dalam suatu naskah drama, maupun karya pementas drama terlebih dahulu
memahami lakuan, dialog, monolog, pikiran, suasana batin, dan hal lain yang
berhubungan dengan pelaku.
Berdasarkan fungsi di atas pelaku dapat dibedakan antara pelaku utama
dan pelaku tambahan. Pelaku yang menjadi sumber dan berperan uatama dalam
setiap peristiwa, berperan utama dalam membentuk cerita, mempunyai peranan
penting dalan mewujudkan tema disebut pelaku utama. Sebaliknya pelaku yang
hanya berfungsi sebagai pembantu atau pendukung kehadiran pelaku utama
disebut pelaku tambahan. Agar pelaku yang ditampilkan dapat memberikan efek
yang nyata atau hidup dan menarik perlu diadakan karakterisasi.
Salah satu bentuk karakterisasi yang dilakukan adalah dengan
memberikan gambaran penampilan dan gambaran perwatakan kepada para
pelaku yang ditampilkannya. Penggambaran pelaku tersebut dapat dilakukan
melalui penggambaran pikiran, sikap, suasana batin, perilaku, cara berhubungan
dengan orang lain, dialog, monolog komentar atau penjelasan langsung. Selain
itu pelaku juga dapat digambarkan melalui pembicaraan, sikap, maupun
pandangan pelaku lain terhadap yang dijadikan sebagai sasaran pemahaman.
Dari sinilah para pembaca dapat merasakan adanya pelaku yang memberi kesan
menyenangkan dan tidak menyenangkan.
2. Latar Cerita
Termasuk dalam latar cerita adalah latar berupa peristiwa, benda, objek,
suasana, maupun situasi tertentu. Latar dalam drama selain berfungsi untuk
membuat cerita menjadi lebih tampak hidup juga dapat dimanfaatkan untuk
menggambarkan gagasan tertentu secara tidak langsung Latar cerita juga bisa
berupa lingkungan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sosial budaya.
Dalam hal demikian bisa juga latar tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan
gambaran secara fisik tetapi mesti ditafsirkan oleh pembaca atau penonton.
3. Tema Cerita
Tema merupakan ide dasar yang melandasi pemaparan suatu cerita.
Tema mesti dibedakan dengan nilai moral atau amanat. Misal, ketika membuat
naskah drama yang berjudul “Sampuraga” penyusun naskah bertolak dari tema
114 Pengantar
“Anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapat hukuman yang setimpal”.
Tema demikian dapat saja terwujudkan dalam gambaran peristiwa maupun
rangkaian cerita yang berbeda-beda sebagai lay down atau landas tumpu
penceritaan sehingga pengembangan cerita mestilah menunjukkan keselarasan
dengan tema ataupun berbagai pokok permasalahan yang digarap melalui
pengembangan ceritanya.
4. Penggunaan Gaya Bahasa
Sebagaimana dalam puisi, karya drama juga menggunakan gaya bahasa
dalam penerapannya. Penggunaan gaya bahasa tersebut antara lain difungsikan
untuk (1) memaparkan gagasan secara lebih hidup dan menarik, (2)
menggambarkan suasana lebih hidup dan menarik, (3) untuk menekankan suatu
gagasan, (4) untuk menyampaikan gagasan secara tidak langsung.
Meskipun ada beberapa kesamaan dengan penggunaan gaya bahasa
dalam puisi maupun karya drama pada umumnya, dalam drama terdapat
penggunaan gaya bahasa yang sulit digunakan dalam puisi karena penggunaan
gaya bahasa tersebut berkaitan dengan penggambaran suatu cerita keseluruhan.
Gaya bahasa yang dimaksud adalah gaya bahasa ironi, yaitu penggunaan gaya
bahasa untuk menyampaikan gagasan secara tidak langsung melalui pemaduan
antara penggunaan bahasa, penggambaran peristiwa, dan penyampaian cerita.
5. Rangkaian Cerita
Penentuan rangkaian cerita dalam drama berbagai macam. Apabila
ditentukan berdasarkan cerita berbentuk roman misalnya, rangkaian cerita
tersebut dapat digambarkan melalui tahap-tahap; perkenalan, komplikasi,
konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Unsur-unsur dan rangkaian
cerita tersebut tidak selalu berlaku dalam setiap cerita drama. untuk
menyusunnya pun pembaca harus menggambarkan ulang berbagai peristiwa
yang termuat dalam cerita yang dibacanya. Untuk menyusun gambaran peristiwa
tersebut sehingga membentuk sebuah plot, pembaca mungkin menggarapnya
berdasarkan urutan waktu maupun urutan sebab akibat.
Dalam memerankan drama seorang pemain harus dapat membayangkan
latar dan tindakan pelaku dan dapat menggunakan suara sesuai dengan
pemahamannya terhadap perasaan dan pikiran pelaku. Bermain drama yang
merupakan pengembangan keterampilan berbicara harus dapat dilatihkan dengan
sungguh-sungguh kepada siswa sekolah dasar melalui kegiatan pembelajaran.
Untuk mengembangkan keterampilan bermain drama seseorang siswa, tentunya
guru harus memiliki dan memahami berbagai metode, teknik, dan model
pembelajaran sehingga pembelajaran bermain drama dapat dipahami oleh siswa,
dan menumbuhkan rasa antusias siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang
dilakukan. (Lisa Rindani, 2012; 6).
Kajian Seni SD 115
Dalam drama yang dibagi menjadi sejumlah babak biasanya kita
menemukan detail tahapan cerita dalam setiap babaknya yang dapat kita rinci ke
dalam tahap-tahap tertentu. Bahkan tidak terutup kemungkinan dalam setiap
babak tersebut seakan-akan kita sudah bisa membentuk sebuah kesatuan cerita
yang belum menggambarkan adanya klimaks dan penyelesaian.
Sebelum bermain drama, Dewojati (2012:266) mengemukakan beberapa
dasar-dasar pementasan yang perlu dikuasai dengan baik supaya pemntasan
dapat menarik simpati penonton. Dasar-dasar tersebut sebagai berikut:
1. Penguasaan Lafal
Seorang calon pemain drama harus menguasai pelafalan bunyi konsonan
dan vokal sesuai dengan artikulasinya secara tepat dan sempurna. Disertai suara
yang jelas dan keras. Penguasaan lafal ini biasanya di tempat terbuka untuk
mengulang-ulang suatu pelafalan/vokal tertentu sampai sempurna pengucapan-
nya.
2. Penguasaan Intonasi
Di samping lafal, mimik dan gerak tubuh, pemain drama harus pula
menguasai intonasi dasar sedih (tempo lambat-nada rendah-tekanan lembut)
intonasi marah (tempo cepat, nada tinggi, tekanan keras) dan intonasi gembira
(tempo-nada-tekanan bersifat sedang). Suatu peran menjadi hidup bila aktornya
memiliki penguasaan pemahaman dan penghayatan watak peran yang tepat.
Ketika dialog pemain belum bisa menguasai intonasi, maka dialog yang
diucapkan oleh pemain akan sulit dimengerti.
3. Penguasan Kelenturan Tubuh/Gesture
Dalam penguasaan kelenturan tubuh atau gesture ini penting dalam
sebuah pementasan drama.Tubuh seorang pemain drama harus lentur atau elastis
sehingga dalam memainkan peran tertentu tidak kelihatan kaku.Untuk mencapai
penguasaan tubuh yang elastik tersebut, perlu melakukan serangkaian gerakan
seperti berlari cepat dalam jarak dekat, bolak balik ke utara, selatan, timur, barat,
ke segala penjuru. Berjalan dengan menggambarkan perasaan sedih, jalan
kepayahan membayangkan berjalan di padang pasir hingga jatuh bergulingan,
dan seterusnya.
4. Penguasaan Mimik dan Ekspresi
Seorang calon pemain harus menguasai mimik dasar seperti mimik sedih,
gembira, marah dan lainlain. Mimik marah biasa ditandai dengan mata melotot,
muka kemerah-merahan, kening berkerut, mimik sedih ditandai dengan wajah
muram, pandangan mata sayu, dan mulut tertutup, sedang mimik gembira
ditandai muka yang bercahaya, mata bersinar, dan mulut tersenyum.
Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang
membutuhkan suatu pemahaman dan kompetensi kebahasaan. Keterampilan
116 Pengantar
berbicara pada dasarnya harus dimiliki oleh semua orang yang di dalam
kegiatannya membutuhkan komunikasi, baik bersifat satu arah maupun timbal
balik ataupun keduanya. Namun, keterampilan berbicara tidaklah dimiliki oleh
seseorang secara otomatis. Keterampilan berbicara yang baik dapat dimiliki
dengan cara mengolah maupun melatih seluruh potensi yang ada.
Keterampilan berbicara harus dikembangkan melalui latihan. Salah satu
latihan pengembangan keterampilan berbicara adalah bermain drama. Bermain
drama merupakan suatu kegiatan memerankan tokoh yang ada dalam naskah
melalui alat utama yakni percakapan (dialog), gerakan dan tingkah laku yang di
pentaskan. Herman J. Waluyo menyebutkan bahwa banyak manfaat yang dapat
diambil dari drama diantaranya adalah dapat membantu siswa dalam
pemahaman dan penggunaan bahasa (untuk berkomunikasi), melatih
keterampilan membaca (teks drama), melatih keterampilan menyimak atau
mendengarkan (dialog pertunjukan drama, mendengarkan drama radio, televisi
dan sebagainya), melatih keterampilan menulis (teks drama sederhana, resensi
drama, resensi pementasan), melatih wicara (melakukan pementasan drama)
(Waluyo, 2001:158).
Dalam memerankan drama, seorang pemain (aktor) harus mampu
membawakan dialog sesuai dengan karakter tokoh yang diperankannya,
menghayati sesuai dengan tuntutan peran yang ditentukan dalam naskah,
mampu membawakan dialog tersebut dengan gerak yang pas (tidak berlebihan
atau dibuat-buat), mampu membayangkan latar dan tindakannya serta mampu
mengolah suara sesuai dengan pemahamannya terhadap perasaan dan pikiran
pelaku.
Upaya untuk meningkatkan keterampilan bermain drama, perlu
menggunakan suatu metode yang mampu menggugah minat siswa dalam
bermain drama. Salah satunya dengan menghadirkan suatu pembelajaran yang
mampu meningkatkan keterampilan bermain drama. Pembelajaran tersebut
diharapkan dapat meningkatkan proses belajar yang nantinya dapat
meningkatkan hasil belajar yang akan dicapai.
Selama pembelajaran drama guru hanya memberikan materi,
memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari naskah drama kemudian
mempraktikkannya di depan kelas. Hal tersebut membuat peserta didik pasif dan
tidak kreatif karena mereka hanya menuruti apa yang diperintah oleh guru.
Pembelajaran drama seperti itu hanya akan membatasi ruang gerak
peserta didik sehingga kreativitas mereka kurang berkembang. Pembelajaran
drama di sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu (1)
pembelajaran teks sastra, dan (2) pementasan drama yang termasuk bidang teater
(Waluyo, 2001:156). Dalam pembelajaran drama (dan sastra), kiranya memang
tidak cukup diberikan pengetahuan tentang drama. Mereka harus mampu
Kajian Seni SD 117
mengapresiasi (unsur yang termasuk afektif) dan mementaskan (psikomotorik)
(Waluyo, 2001:161).
Pembelajaran drama di sekolah dapat ditafsirkan dua macam, yaitu:
pengajaran teori drama, atau pengajaran apresiasi drama. Masing-masing juga
terdiri atas dua jenis, yaitu: pengajaran teori tentang teks (naskah) drama, dan
pengajaran tentang teori pementasan drama. Pengajaran apresiasi dibahas naskah
drama dan apresiasi pementasan drama (Waluyo, 2001:153).
Pementasan drama dibahas di sekolah (untuk demonstrasi) dan
pementasan untuk sekolah yang ditonton oleh seluruh siswa di sekolah itu.
Pementasan pertama dilakukan oleh guru bahasa Indonesia, sedangkan
pementasan jenis kedua biasanya dilakukan oleh teater sekolah atau atas
kerjasama guru bahasa Indonesia, teater sekolah, dan OSIS (Waluyo, 2001:156).
Dalam pembelajaran drama (dan sastra), kiranya memang tidak cukup diberikan
pengetahuan tentang drama. Mereka harus mampu mengapresiasi (unsur yang
termasuk afektif) dan mementaskan (psikomotorik) (Waluyo, 2001:161).
B. Manfaat Drama
Banyak hal yang dapat kita raih dalam bermain drama, baik fisik maupun
psikis. Pembicaraan ini tidak akan memisahkan secara rinci antara bermain
drama dan teater, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Di
bawah ini akan diuraikan manfaat bermain drama atau teater.
1. Meningkatkan pemahaman
Meningkatkan pemahaman kita terhadap fenomena dan kejadian-
kejadian yang sering kita saksikan dan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Kita menyadari bahwa memahami orang lain merupakan pekerjaan yang paling
sulit dan membutuhkan waktu. Untuk itu drama/teater merupakan salah satu
cara untuk memecahkannya. Dengan bermain drama atau berteater kita selalu
berkumpul dengan orang-orang yang sama sekali berbeda dengan diri kita. Dari
segi individual differences inilah kita dituntut untuk memahami orang lain.
Pemahaman kita kepada orang lain tidak hanya dilihat dari orangnya, melainkan
keseluruhan orang tersebut. Meliputi sifat, watak, cara berbicara, cara bertindak
(tingkah laku), cara merespon suatu masalah, merupakan keadaan yang harus
kita pahami dari orang tersebut.
2. Mempertajam kepekaan emosi
Drama melatih kita untuk menahan rasa, melatih kepekaan rasa,
menumbuhkan kepekaan, dan mempertajam emosi kita. Rasa kadang kala tidak
perlu dirasakan, karena sudah ada dalam diri kita. Perlu diingat bahwa rasa,
sebagai sesuatu yang khas, perlu dipupuk agar semakin tajam. Apa yang ada
118 Pengantar
dihadapan kita perlu adanya rasa. Kalau tidak, maka segala sesuatu yang ada
akan kita anggap wajar saja. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita semakin
peka terhadap sesuatu tentu saja melalui latihan yang lebih. Rasa indah,
seimbang, tidak cocok, tidak asyik, tidak mesra adalah bagian dari emosi. Oleh
karena itu, perasaan perlu ditingkatkan untuk mencapai kepuasan batin.
Drama menyajikan semua itu. Peka panggung, peka kesalahan, peka
keindahan, peka suara atau musik, peka lakuan yang tidak enak dan enak, semua
berasal dari rasa. Semakin kita perasa semakin halus pula tanggapan kita terhadap
sesuatu yang kita hadapi.
3. Pengembangan ujar
Naskah drama sebagai genre sastra, hampir seluruhnya berisi cakapan.
Cakapan secara tepat, intonasi, maka ujar kita semakin jelas dan mudah
dipahami oleh lawan bicara. Kejelasan tersebut dapat membantu pendengar
untuk mencerna makna yang ada. Harus ada kata yang ditekankan supaya
memudahkan pemaknaan. Dimana kita memberi koma (,) dan titik (.). hampir
keseluruhan konjungsi harus diperhatikan selam kita berlatih membaca dalam
bermain drama. Suara yang tidak jelas dapat berpengaruh pada pendengar dan
lebih-lebih pemaknaan pendengar atau penonton. Di sini perlu adanya kekuatan
vokal dan warna vokal yang berbeda dalam setiap situasi. Tidak semua situasi
memerlukan vokal yang sama. Tidak semua kalimat harus ditekan melainkan
pasti ada yang dipentingkan. Drama memberi semua kemungkinan ini. Sebagai
salah satu karya sastra yang harus dipentaskan dan berisi lakuan serta ucapan.
4. Apresiasi dramatik.
Apresiasi dramatik dikatakan sebagai pemahaman drama. Realisasi
pemahaman ini adalah dengan pernyataan baik dan tidak baik. Kita bisa memberi
pernyataan tersebut jika kita tidak pernah mengenal drama. Semakin sering kita
menonton pementasan drama semakin luas pula pemahaman kita terhadap
drama atau teater. Karena itulah, kita dituntut untuk lebih meningkatkan
kecintaan kita terhadap drama. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh
wawasan dramatik yang lebih baik.
5. Pembentukan Postur Tubuh
Postur berkaitan erat dengan latihan bermain drama, latihan ini dibagi
menjadi dua golongan besar, yaitu dasar dan lanjut. Yang termasuk latihan dasar
ini adalah latihan vokal dan latihan olah tubuh. Yang terkait dengan postur
adalah olah tubuh. Kelenturan tubuh diperlukan dalam bermain drama, sebab
bermain drama memerlukan gerak-gerik. Gerak-gerik inilah yang nantinya dapat
membentuk postur tubuh kita sedemikian rupa.
Kajian Seni SD 119
6. Berkelompok (Bersosialisasi)
Bermain drama tidak mungkin dilaksanakan sendirian, kecuali monoplay.
Bermain drama, secara umum, dilakukan secara berkelompok atau group. Betapa
sulitnya mengatur kelompok sudah kita pahami bersama, bagaimana kita bisa
hidup secara berkelompok adalah bergantung pada diri kita sendiri. Masing-
masing orang dalam kelompok drama memiliki tugas dan tanggung jawab yang
sama. Tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang, semuanya sama rendah dan
sama tinggi, sama-sama penting. Untuk itu, drama selalu menekankan pada sikap
pemahaman kepada orang lain dan lingkungannya.
Kelompok drama harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua
unsur dalam drama tidak ada yang tidak penting, melainkan semuanya penting.
Rasa kebersamaan, memiliki, dan menjaga keharmonisan kelompok merupakan
tanggung jawab dan tugas semua anggota kelompok itu. Bukan hanya tugas dan
tanggung jawab ketua kelompok. Baik buruknya pementasan drama tidak akan
dinilai dari salah seorang anggota kelompok tetapi semua orang yang terlibat
dalam pementasan. Oleh karena itu, perlu adanya kekompakan, kebersamaan,
dan kesatuan serta keutuhan.
7. Menyalurkan hobi
Bermain drama dapat juga dikatakan sebagai penyalur hobi. Hobi yang
berkaitan dengan sastra secara umum dan drama khususnya. Dalam drama
terdapat unsur-unsur sastra. Drama sebagai seni campuran (sastra, tari,
arsitektur).
Menurut Moody dalam Depdiknas, (2011:70) manfaat drama sebagai
berikut;
a. Informasi, agar siswa mengenal informasi yang memadai tentang apa itu
drama, apa saja unsur yang membangun drama, siapa pengarang drama,
kapan drama dikarang, termasuk pengarang angkatan mana, dan
sebagainya.
b. Konsep, konsep adalah pengertian-pengertian pokok tentang suatu hal.
Terminologi dari setiap aspek dikenal oleh siswa. Tidak hanya sekadar tahu
konsep tetapi dapat menerapkan konsep tertentu dalam suatu pembahasan
karya sastra drama. Misalnya saja konsep-konsep tentang aliran drama,
macam-macam drama, apa yang disebut komedi, tragedi, dagelan, dan
sebagainya.
c. Perspektif, perspektif yaitu kemampuan untuk memandang bagaimana
drama itu menurut perspektif pikiran siswa. Tepatkah jalan keluar yang
diambil dalam lakon? Bagaimanakah sikapnya sekiranya dia menjadi
pengarang? Bagaimana dikapnya jika ia menjadi tokoh sentral dalamdrama
itu?.
120 Pengantar
d. Apresiasi, pengertiannya sudah masuk ke dalam ranah afektif, yaitu
pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan penghargaan kepada drama.
Disamping itu tujuan drama menurut Sitti (2012:11) adalah;
1. Untuk membahagiakan sekaligus instruksi.
2. Memperoleh suatu pengetahuan, kesenangan, pengalaman, dan
pengetahuan seni keindahan.
3. Untuk hiburan santai dan pengalaman mengenai estetika.
C. Macam-Macam Drama
Drama adalah suatu aksi atau perbuatan (bahasa yunani). Sedangkan
dramatik adalah jenis karangan yang dipertunjukkan dalan suatu tingkah laku,
mimik dan perbuatan. Sandiwara adalah sebutan lain dari drama di mana sandi
adalah rahasia dan wara adalah pelajaran. Orang yang memainkan drama disebut
aktor, pelaku atau lakon.
Drama menurut masanya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu drama baru dan
drama lama.
1. Drama Baru / Drama Modern
Drama baru adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan
pendidikan kepada mesyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia
sehari-hari.
2. Drama Lama / Drama Klasik
Drama lama adalah drama khayalan yang umumnya menceritakan
tentang kesaktian, kehidupan istanan atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi,
kejadian luar biasa, dan lain sebagainya.
Macam-Macam drama berdasarkan isi kandungan cerita:
1. Drama Komedi ; Drama komedi adalah drama yang lucu dan menggelitik
penuh keceriaan.
2. Drama Tragedi ; Drama tragedi adalah drama yang ceritanya sedih penuh
kemalangan.
3. Drama Tragedi Komedi ; Drama tragedi-komedi adalah drama yang ada
sedih dan ada lucunya.
4. Opera ; Opera adalah drama yang mengandung musik dan nyanyian.
5. Lelucon / Dagelan ; Lelucon adalah drama yang lakonnya selalu bertingkah
pola jenaka merangsang gelak tawa penonton.
6. Operet / Operette ; Operet adalah opera yang ceritanya lebih pendek.
7. Pantomim ; Pantomim adalah drama yang ditampilkan dalam bentuk
gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan.
Kajian Seni SD 121
8. Tablau ; Tablau adalah drama yang mirip pantomim yang dibarengi oleh
gerak-gerik anggota tubuh dan mimik wajah pelakunya.
9. Passie ; Passie adalah drama yang mengandung unsur agama /relijius.
10. Wayang ; Wayang adalah drama yang pemain dramanya adalah boneka
wayang. Dan lain sebagainya.
Kalasifikasi drama didasarkan atas jenis stereotip manusia dan tanggapan
manusia terhadap hidup dan kehidupan atau dilihat dari modus perasaan yang
dimasukan dalam drama itu. Seorang pengarang drama dapat menghadapi
kehidupan ini dari sisi kegembiraan dan kesedihan, bisa juga memberikan variasi
keduanya. Tambajong dalam Depdiknas (2011:30) mengklasifikasikan drama ke
dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:
1. Tragedi (Drama Duka)
Tragedi atau drama duka adalah drama yang melukiskan kisah sedih
yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar.
Drama ini biasanya berakhir dengan suasana menyedihkan, bahkan seringkali
maut menjemput tokoh utama pada penghujung cerita. Tokoh dalam drama ini
adalah pahlawan yang mengalami nasib tragis atau tragic hero.
Drama Yunani karya Sophocles, Oidipus Sang Raja, Hamlet dan Romeo-
Juliet karya Shakespare merupan contoh jenis drama ini. Contoh lain Kapai-
kapai karya Arifin C. Noer, Ken Arok dan Ken Dedes karya Moh. Yamin, dan
Aduh karya Putu Wijaya.
2. Komedi (Drama Ria)
Komedi adalah drama ringan yang sifatnya menghibur dan di dalamnya
terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan
kebahagiaan. Dalam komedi ditampilkan tokoh tolol, konyol atau tokoh
bijaksana yang lucu, seperti Pak Pandir, Pak Belalang, Kabayan, dan Abu Nawas.
Beberapa contoh drama komedi di antaranya Akal Bulus Scapin dan Dokter
Gadungan karya Molierre (seorang tokoh pencipta drama komedi terkenal asal
Perancis), Kebun Ceri karya A.P. Cekhov, Si Bakhil karya Nur Sutan Iskandar,
Si Kabayan karya Utuy Tatang Sontani, dan Tuan Amin karya AmalHamzah.
3. Tragikomedi
Tragikomedi merupakan jenis drama yang memadukan dua perasaan
sekaligus. Di dalam drama seperti ini dijumpai bagian-bagian yang menyedihkan
dan bagian-bagian yang menggembirakan. Yang tergolong dalam drama ini
adalah Jas Panjang Pesanan karya Wolf Mankowitz, Malam Jahanam karya
Motinggo Boesye, Api karya Usmar Ismail, dan Awal dan Mira karya Utuy
Tatang Sontani.
122 Pengantar
4. Melodrama
Melodrama adalah lakon yang sangat sentimental, dengan tokoh dan
cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. Drama ini sangat menonjolkan
perasaan. Kadang-kadang drama seperti ini tidak bicara apa-apa, emosi disajikan
dengan bantuan alunan musik. Tokoh dalam melodrama adalah tokoh yang tidak
ternama, hitam-putih, dan storeotip. Tokohnya juga dilukiskan dengan menerima
nasib seperti apa yang terjadi. Dua Orang Algojo karya Fernando Arrabal yang
diterjemahkan Sori Siregar adalah salah satu contoh drama jenis ini.
5. Dagelan (Farce)
Dagelan disebut juga banyolan atau seringkali disebut komedi murahan,
picisan, dan ketengan. Dagelan adalah drama kocak dan ringan, alurnya tersusun
berdasarkan arus situasi dan tidak berdasarkan perkembangan struktur dramatik
dan perkembangan cerita sang tokoh. Isinya cenderung kasar, lentur, dan fulgar.
Drama ini menonjolkan gerak-gerik karikatural, sehingga kadang-kadang terlihat
tidak logis, terlihat dibuat-buat. Sebagai contoh adalah Si Bedul karya Elwy
Mitchel dan seperti lakon pada “Srimulat”
D. Karakteristik Drama SD
Dalam kaitan dengan pendidikan drama, pembelajaran drama, atau
pergelaran drama di lingkungan sekolah atau siswa, diperlukan dua syarat utama,
yakni syarat seni dramanya dan syarat pedagogisnya, yang kedua bersifat
komplementer. Untuk itu, diperlukan lakon atau cerita yang sesuai dengan
kebutuhan pendidikan dan sesuai dengan alam kejiwaan anak. Lakon mesti yang
dapat ‘dimainkan’ oleh anak-anak dan pengemasannya (dekor, properti, dan lain-
lain) tidak terlampau sulit. Demikian halnya laku dalam lakon pun mesti yang
dapat dilakukan oleh anak-anak dengan perlengkapan dan kelengkapan yang ada
atau yang mungkin diadakan. Dialog-dialog diusahakan bisa hidup, ‘cair’, dan
relatif mudah diucapkan oleh anak dengan tetap memperhatikan syarat-syarat
etika.
Anak-anak mesti memiliki kesanggupan untuk bermain drama, baik
ketika menghadapi naskah maupun ketika harus bermain di atas panggung yang
sebenarnya. Mereka mesti mampu membawakan dialog dengan tepat dengan
diikuti perasaan atau penghayatan. Mereka mesti memiliki persiapan batin dan
mengenal dengan baik watak-watak atau karakter tokoh-tokoh yang akan
diperankannya. Pengoptimalan penggunaan artikulator dan titik artikulasi mesti
dilakukan.
Memerankan tokoh sama dengan memberikan bentuk lahir pada watak
dan emosi dengan laku dan ucapan. Watak yang harus diperankan menurut
Richard Boleslavsky (melalui Harymawan, 1988:30-41) mempunyai tiga bagian
Kajian Seni SD 123
yang harus tampak, yakni watak tubuh, watak pikiran, dan watak emosi. Anak
bisa menciptakan sebuah peran berarti anak itu sudah menciptakan keseluruhan
hidup sukma manusia di atas panggung, baik secara fisik, mental, dan emosional,
dan itu harus unik. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan oleh anak-anak
adalah bangunan suasana drama. Betapa pun bagusnya lakon dan penyuguhan
yang tepat, jika kurang didukung oleh suasana, tentu saja drama itu kurang
berhasil. Unsur dukungan dari penonton cukup dibutuhkan dalam membangun
suasana. Untuk itu, diperlukan lakon yang tepat, penyajian yang bagus, penataan
artistik (busana, rias, lampu, suara, panggung, properti) yang tepat, dan penonton
dibina untuk mampu menjadi penonton yang apresiatif.
Kegiatan drama atau teater bisa membantu anak ke arah pembentukan
pribadinya yang erat hubungannya dengan pembentukan sikap sosial anak. Anak
semakin menyadari bahwa masing-masing individu terjadi atas tiga dimensi,
yakni sebagai makluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai
makhluk sosial. Anak-anak tidak hanya terbentuk menjadi manusia-manusia
materialistis semata-mata, melainkan menjadi manusia-manusia yang mampu
menghargai dan mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan
sehari-hari.
Bimbingan dan pendidikan estetika (drama) cukup signifikan untuk
menyalurkan emosi anak-anak ke arah yang menguntungkan pembentukan
pribadi yang baik. Pendidikan estetika menjadikan anak-anak mampu
menghargai keindahan, kehalusan, dan ketertiban/kedisiplinan. Sudah dipahami
bersama bahwa esensi drama adalah konflik manusia. Perhatian terhadap konflik
kemanusiaan itulah yang menjadi dasar dari drama. Maka, siswa yang bergaul
secara akrab dengan seni drama, di samping merasakan dan menghayati
keselarasan dan keindahan drama itu, anak-anak memiliki pengalaman jiwa ikut
merasakan dan menghayati pergolakan batin atau konflik-konflik yang terjadi di
kalangan manusia, entah itu konflik manusia yang satu dengan manusia yang
lain, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan alam, bahkan mungkin
manusia dengan penguasa, bahkan mungkin dengan Tuhan. Anak-anak memiliki
pandangan yang relatif mendalam tentang sifat-sifat watak manusia serta hidup
dan kehidupannya. Melalui lakon atau pergelaran drama, anak-anak
mendapatkan pemahaman tentang psikologi watak-watak manusia. Berangkat
dari itu, anak-anak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendasar tentang
sifat-sifat manusia lain (pada umumnya) dan tentang dirinya sendiri.
Drama atau teater menyediakan kesempatan kepada anak-anak untuk
mempelajari psikologi manusia dengan berbagai perilakunya, dengan pelbagai
tingkah lakunya. Anak-anak mempunyai kesempatan memerankan tokoh. Peran
tokoh itu tentu saja dihayatinya dengan baik, sehingga tanpa sadar prosesi itu
akan sangat membantu anak-anak dalam proses pendewasaan diri. Anak-anak
124 Pengantar
mengidentifikasikan diri mereka dengan tokoh-tokoh yang dibawakannya, pun
mengenal secara baik problem-problem tokoh tersebut. Demikian pula, anak-
anak tahu secara persis nilai-nilai (moral) yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh,
sehingga anak-anak cukup terlatih dalam upaya memecahkan problemnya sendiri
dalam kehidupan sehari-hari.
Drama memberikan peluang secara strategis kepada anak-anak untuk
berkenalan dan mengenal manusia yang sangat boleh jadi perwatakannya jauh
lebih hebat dibanding dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, anak-anak
menemukan ‘hero’ di dalam drama yang digaulinya secara intensif, yang mau
tidak mau, itu akan berpengaruh dalam pembinaan dan pengembangan pribadi
dan pematangan jiwa anak. Berkegiatan drama/teater yang dilakukan secara
rutin atau berkesinambungan bisa berdampak positif bagi anak-anak karena
mereka cenderung menjadi betah bergaul dengan orang lain tanpa memandang
status sosial. Mereka bisa saling menghormati pendapat orang lain, sabar
mendengarkan pembicaraan orang lain. Anak-anak menjadi terbiasa dengan
‘pertentangan pendapat’ di antara mereka, berjiwa toleran, berani menentang hal-
hal yang tidak baik, demikian seterusnya. Anak-anak dengan sering bergaul
dengan cerita atau lakon-lakon drama akan banyak mengambil keuntungan
karena anak-anak banyak melihat dan menyaksikan betapa seorang tokoh
menyusun pikiran dan perasaan dengan sebaik mungkin untuk disampaikan
kepada orang (tokoh) lain. Dengan itu, anak-anak akan terbiasa dan secara
mudah dan lancar untuk mengemukakan pikiran dan perasaan secara logis dan
sistematis di depan orang banyak secara lisan. Di samping itu, anak-anak akan
memperoleh kekayaan kosakata yang luar biasa yang mungkin tidak akan mereka
dapatkan dalam bahasa yang dipergunakan sehari-hari. Kita juga tahu bahwa
kegiatan drama (teater) adalah kegiatan kolektif yang memerlukan kesetiaan,
kedisiplinan yang tinggi, rasa tanggung jawab, dan kerjasama yang baik. Maka,
tidak mustahil pada diri anak-anak akan tertanam dalam-dalam sikap atau
perilaku gotong-royong dan bekerjasama dalam rangka menggapai tujuan
bersama. Casting pun cukup bermanfaat untuk anak-anak, yakni menumbuh-
kembangkan kesadaran berkompetisi secara sehat, yang berbuah pada dorongan
untuk selalu mau dan mampu berusaha secara optimal.
Dalam kegiatan drama (teater), ternyata baik pemain (aktor/aktris)
maupun penonton (pemirsa, audience) sama-sama mendapatkan keuntungan.
Pemain atau aktor/aktris yang bermain drama adalah orang-orang yang
memperoleh kesempatan besar untuk menemukan dirinya (Saleh, 1967: 213).
Sementara itu, penonton atau pemirsa/audience dari waktu ke waktu mesti belajar
menjadi penonton yang baik, santun, dan bermartabat. Kedua keuntungan
tersebut merupakan faktor penting untuk perkembangan kemanusiaan dari
individu yang mengalaminya. Pernah dibuktikan di Amerika Serikat bahwa
Kajian Seni SD 125
educational theatre teramat bermanfaat sebagai salah satu cara untuk
mengendorkan ketegangan emosi siswa dan memberikan kontribusi yang berarti
untuk kesehatan mental anak-anak (Sihombing, 1974:459). Maka tak ayal kalau
ada juga pernyataan yang menegaskan bahwa ‘... It is also a literary form which is
capable of adaptation for students of all ages. Being closely linked with the fundamental
instinct of imitation–which obviously implies a close degree of observation–its value in
education is becoming widely appreciated. Educationists see drama as a means where by
the young can progress towards maturity by trying out and experimenting with various roles
which they need to have some appreciation of in order to obtain a full grasp of the world
they are entering: ...‟ (Moody, 1972:62).
Pembelajaran drama juga cukup memberikan kontribusi kepada proses
pembelajaran yang lain dalam pengetahuan dan kepandaian, misalnya dalam
kaitannya dengan pembelajaran bahasa, kesusasteraan, bercakap dengan irama,
menghilangkan tabiat malu, menggembirakan karena drama (sandiwara) bersifat
permainan, memberikan beberapa pengertian baru, berlatih gerak irama,
menyanyi, menyesuaikan kata dengan pikiran, rasa, kemauan, dan tenaga,
mengajarkan adat sopan santun, dan seterusnya (Dewantara, 1962:310).
Drama (sandiwara) sebagai media pembelajaran pun teramat strategis
dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan mengingat drama (sandiwara)
bersifat sangat menarik minat dan mengikat perhatian (Saleh, 1967:213). Hal itu
berkaitan dengan tuntutan eksistensi drama yang to act a story dan bukan hanya
to tell a story sebagai berikut: “Drama does not tell, it shows. And the word drama in its
literary usage means simply that: showing instead of telling, or perhaps better, telling by
showing” (Lisle at al, t.t.:255).
Sandiwara (istilah yang bersinonim dengan drama) dalam kebudayaan
Indonesia diakui sebagai kesenian yang diperuntukkan penyiaran pendidikan dan
pembelajaran. Hal itu bersesuaian dengan istilah ‘sandiwara’ yang berasal dari
kata ‘sandi’ (tertutup, rahasia) dan kata ‘wara’ (pembelajaran), sehingga secara
keseluruhan bermakna pembelajaran yang diberikan secara perlambang
(Dewantara, 1962:350), secara tidak terang-terangan, secara tidak vulgar. Maka,
dengan menggauli drama (sandiwara) secara intensif, baik memainkan maupun
menonton, anak-anak tanpa dipaksakan, tanpa terasa dimasuki pesan-pesan atau
amanat-amanat yang terkandung dalam drama (sandiwara).
E. Referensi
Adinegoro. 1966. Publisistik & Djurnalistik. Jakarta : Pt Gunung Agung.
Aminuddin dan Roekhan. 2003. Apresiasi Drama. Jakarta. Angkasa.
Asmara, Adhy. 1983. Apresiasi Drama. Yogyakarta: Nur Cahaya.
Brahim. 1968. Drama dalam Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung.
Budianta, Melani, dkk. 2002. Membaca Sastra (Pengantar Memahami Sastra untuk
126 Pengantar
Perguruan Tinggi). Magelang: Indonesia Tera.
Dewantara, Ki Hadjar. 1962. Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama:
Pendidikan. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.
Hamzah, Adjib A. 1985. Pengantar Bermain Drama. Bandung: CV. Rosda.
Harymawan, R.M. 1988. Dramaturgi. Bandung: CV. Rosda.
-------. 1993. Dramaturgi. Bandung: Djatnika..
Hasanudin. 1996. Drama Karya Dalam Dua Dimensi Kajian Teori, Sejarah dan
Analis. Bandung: Angkasa.
Kabisch, Eva Maria. 1985. Literaturgeschichte Kurzgefaßt. Stuttgart: Ernst Klett
Verlag.
Krauss, Hedwig. 1999. Verstehen und Gestalten. München: Franzis Print and
Media GmbH.
Leslie L. Lewis.1966. A Handbook for the Study of Fiction. New York: The
Macmillan Company.
Lubis. 2015. Pemikiran Kritis Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
Moody, H.L.B. 1972. The Teaching of Literature. London: Longman.
Oemarjati, B.S. 1971. Bentuk Lakon dalam sastra Indonesia. Jakarta: Gunung
Agung.
Ramelan. 1980. Morfologi. Suatu Tinjauan Deskriptif. Yogyakarta: Karyono.
Segers, Rien T. 2000. Evaluasi Teks Sastra, Sebuah Penelitian Eksperimental
berdasarkan Teori Semiotik dan Estetika Resepsi. Yogyakarta: Adicita.
Shipley. 1971. Dictionary of World Literary Terms. London: George Allen&Unwin
Ltd.
Siti, dkk. 2012. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia
Dini. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Sumardjo, Jakob. 1992. Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tambayong, Japy. 1981. Dasar-dasar Dramaturgi. Bandung: Pustaka Prima.
Waluyo, Herman J. 2008. Drama Teori dan Pengajarannya. Yogyakarta: PT.
Hanindita.
Zulfahnur, dkk. 1996. 1996. Teori Sastra. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Kajian Seni SD 127
128 Pengantar
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Pengantar kajian seni merupakan buku yang berisikan empat cabang seni yang terdiri seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni drama.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search