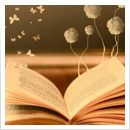BAB 1
BILANGAN BERPANGKAT, BENTUK AKAR, DAN LOGARITMA
Kompetensi Dasar :
3.1 Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam
menyelesaikan masalah.
4.1 Menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma
Pendahuluan
Tahukah kalian bagaimana cara menghitung massa-massa benda luar angkasa? Misalkan massa
matahari?Untuk menghitung permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan kemampuan
mengoperasikan bilangan berpangkat, bentuk akar dan konsep matematika
A. Bilangan Berpangkat
PANGKAT
Bilangan bulat positif
Pangkat normal adalah pangkat dengan bilangan bulat positif, yaitu perkalian berulang sebanyak
dengan pangkat tersebut.
Contoh:
42 = 4.4 = 16
43 = 4.4.4 = 64
44 = 4.4.4.4 = 256
Pangkat nol dan negatif
Pangkat tipe kedua adalah bilangan bulat kurang dari sama dengan nol.
Sifat-sifat:
a0 = 1
NB: maaf, kesalahan menulis, seharusnya a-n bukan an.
Pangkat dalam bentuk akar
Pangkat juga bisa diubah kedalam bentuk akar seperti berikut:
Sifat-sifat bilangan berpangkat
B. Bentuk Akar
Hubungan akar dengan pangkat
Akar sebenarnya adalah bentuk lain dari pangkat pecahan, lihat persamaan berikut.
Aljabar dalam bentuk akar
Berikut ini adalah sifat sifat akar dalam operasi aljabar.
Penyebut Irasional
Maksudnya adalah penyebut yang berbentuk akar, bilangan tersebet disebut juga dengan bilangan yang
tidak rasional, karena sulit untuk di pecahkan. Oleh karena itu penyebut harus diubah menjadi bilangan
bulat atau bilangan yang rasional, dengan cara-cara berikut:
C. Logaritma
Hubungan akar, pangkat dan logaritma
Jika akar adalah bentuk lain dari pangkat, maka logaritma adalah lawan dari pangkat. Jika dalam pangkat
yang kita cari adalah hasil dari perkalian berulang tersebut maka logaritma adalah mencari berapa
banyak perkalian yang terjadi alias mencari pangkat itu sendiri, perhatikan contoh berikut.
Sifat-sifat logaritma
Zona Aktivitas
A. Uji Pengetahuan
1. Hitunglah ilai x yang memenuhi persamaan 273x – 4 =39x + 1
2. Persamaan kuadrat x2 + 2x – 3 = 0 mempunyai akar x1 dan x2. Persamaan
yang akar-akarnya x1 dan x2 adalah …
x2 x1
3. Hitunglah nilai dari 162log 3−0,5
B. Praktikum
Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian
kerjakan soal berikut :
Carilah informasi mengenai taraf intensitas rata-rata dari sebuah sirene pemadam
kebakaran. Gunakan pengetahuan kalian tentang materi yang telah dipelajari,
yaitu logaritma, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Setelah menghitung buatlah prtesentasinya dalam bentuk power point dan
presentasikan di depan kelas
C. Tugas Mandiri Terstruktur
Persamaan kuadrat x2 + 2x – 3 = 0 mempunyai akar x1 dan x2.Buat Persamaan
baruyang akar-akarnya x1 dan x2
x2 x1
Rangkuman
Sifat-sifat bilangan berpangkat
Berikut ini adalah sifat sifat akar dalam operasi aljabar.
Sifat-sifat logaritma
Ulangan Akhir
1. Tulis bentuk sederhana dari (5p2)3
2. Hitung hasil dari (24)3 x (2-5)3
3. Tulis bentuk sederhana dari 36 2 2 5 ( )2
15 24 2 2
4. Tulis bentuk sederhana dari ( 23 23)3
5. Jika log 3 = 0,477 dan log 5 = 0,699 maka hitunglah log 45
6. Carilah akar-akar dari persamaan 5x2 + 4x -12 = 0
7. Buatlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan -5
2
8. Akar-akar persamaan kuadrat x2 + 3x – p = 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 + 3x2 = 5
maka nilai carilah p
9. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan 3x2 + 4x – 1 = 0 maka
hitunglah nilai 1 + 1
x1 x2
10. Hitung jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan 3x2 – 6x = -15 adalah
A dan B. nilai dari 2A2B
BAB 2
Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel yang Memuat Nilai Mutlak
Kompetensi Dasar
3.2 Menerapkan persamaan da pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel
4.2 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan
nilai mutlak bentuk linear satu variable
Pendahuluan
Kalian pernah menjumpai botol berisi air mineral? Ada yang berukuran 600 ml maupun ada yang
berukuran 240 ml. Jika kalian ingin botol yang berukuran 240 ml, tidak lebih berat dari yang
berisi 600 ml, berapa banyak air mineral berukuran 240 ml yang harus dimasukkan ke dalam
botol 240 ml? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep persamaan
dan pertidaksamaan linear.
A. Dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari x ditulis | x |, adalah jarak dari x ke 0 pada
garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau nol maka nilai mutlak x juga selalu
bernilai positif atau nol untuk setiap x bilangan real.
Secara formal, nilai mutlak x didefinisikan
dengan|x|={−xjikax≥0−xjikax<0|x|={−xjikax≥0−xjikax<0atau dapat pula ditulis
| x | = -x jika x ≥ 0
| x | = -x jika x < 0
Definisi diatas dapat kita maknai sebagai berikut :
Nilai mutlak bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri dan nilai mutlak bilangan negatif
adalah lawan dari bilangan tersebut.
Sebagai contoh,
| 7 | = 7 | 0 | = 0 | -4 | = -(-4) = 4
Jadi, jelas bahwa nilai mutlak setiap bilangan real akan selalu bernilai positif atau nol.
Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak
| x | = a dengan a > 0
Persamaan | x | = a artinya jarak dari x ke 0 sama dengan a. Perhatikan gambar berikut.
Jarak -a ke 0 sama dengan jarak a ke 0, yaitu a. Pertanyaannya adalah dimana x agar
jaraknya ke 0 juga sama dengan a.
Posisi x ditunjukkan oleh titik merah pada gambar diatas, yaitu x = -a atau x = a. Jelas
terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan a. Jadi, agar jarak x ke nol sama
dengan a, haruslah x = -a atau x = a.
| x | < a untuk a > 0
Pertaksamaan | x | < a, artinya jarak dari x ke 0 kurang dari a. Perhatikan gambar berikut.
Posisi x ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah, yaitu himpunan titik-titik diantara -a
dan a yang biasa kita tulis -a < x < a. Jika kita ambil sebarang titik pada interval tersebut,
sudah dipastikan jaraknya ke 0 kurang dari a. Jadi, agar jarak x ke 0 kurang dari a,
haruslah -a < x < a.
| x | > a untuk a > 0
Pertaksamaan | x | > a artinya jarak dari x ke 0 lebih dari a. Perhatikan gambar berikut.
Posisi x ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah yaitu x < -a atau x > a. Jika kita ambil
sebarang titik pada interval tersebut, sudah dipastikan jaraknya ke 0 lebih dari a. Jadi, agar
jarak x ke nol lebih dari a, haruslah x < -a atau x > a.
Contoh
Tentukan himpunan penyelesaian dari |2x - 7| = 3
Jawab :
Berdasarkan sifat a :
|2x - 7| = 3 ⇔ 2x - 7 = 3 atau 2x - 7 = -3
|2x - 7| = 3 ⇔ 2x = 10 atau 2x = 4
|2x - 7| = 3 ⇔ x = 5 atau x = 2
Jadi, HP = {2, 5}.
Menggunakan Definisi untuk Menyelesaikan Persamaan dan
Pertidaksamaan Nilai Mutlak
Dalam menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan nilai mutlak bentuk linier dengan
menggunakan definisi, akan sangat membantu jika bentuk |ax + b| kita jabarkan menjadi
|ax + b| = ax + b jika x ≥ -b/a
|ax + b| = -(ax + b) jika x < -b/a
Untuk langkah-langkah penyelesaiannya dapat disimak pada contoh-contoh berikut.
Contoh
Jabarkan bentuk nilai mutlak berikut :
a. |4x - 3|
b. |2x + 8|
Jawab :
a. Untuk |4x - 3|
|4x - 3| = 4x - 3 jika x ≥ 3/4
|4x - 3| = -(4x - 3) jika x < 3/4
b. Untuk |2x + 8|
|2x + 8| = 2x + 8 jika x ≥ -4
|2x + 8| = -(2x + 8) jika x < -4
Zona Aktivitas
A. Uji Pengetahuan
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari │3x + 2│> 5
2. Tentukan nilai variable dari persamaan : 5x – 4 = x + 16
B. Praktikum
Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian
kerjakan soal berikut :
Carilah informasi mengenai taraf intensitas rata-rata dari sebuah sirene pemadam
kebakaran. Gunakan pengetahuan kalian tentang materi yang telah dipelajari,
yaitu logaritma, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Setelah menghitung buatlah prtesentasinya dalam bentuk power point dan
presentasikan di depan kelas
C. Tugas Mandiri Terstruktur
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari |2x - 1| < 7
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari |4x + 2| ≥ 6
Rangkuman
Ulangan Akhir BAB 2
2. Tentukan nilai variable dari persamaan : 5 ( a + 1 ) = 10
3. Tentukan nilai variable dari persamaan : 7x – 4 = 2x + 16
4. Tentukan variable dari persamaan 4 ( x + 1 ) – 2x = 12
5. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan : 3x – 4 ≥ 16 + 8x
6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan : 5b – 3 < 7b + 11
7. Tentukan penyelesaian dari persamaan │4x – 16│= 4
8. . Carilah nilai x yang memenuhi pertidaksamaan │x – 3│> 4
8. Tentukan himpunan penyelesaian dari │x + 3│≤│2x – 3
9. Ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok, waktu
hidup seseorang akan berkurang 5,5 menit. Berapa rokok yang dihisap Fahri
setiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun dan waktu hidupnya berkurang
selama 275 hari?
10. Agar tumbuh sehat, tanaman palawija harus diberi tiga jenis pupuk, yaitu pupuk
A, B, C. Perbandingan ketiga pupuk tersebut berturut-turut adalah 5 : 3 : 1. Massa
total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200gram. Jika pupuk A dan
pupuk C yang diberikan berturut-turut 20 gram dan 40 gram, berapa jumlah
maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija dapat tumbuh
subur?
BAB 3
SISTEM PERSAMAAN LINIER
Kompetensi Dasar :
3.3 Menentukan nilai variable pada system persamaan linier dua variable dalam masalah
konstektual
4.3 Menyajikan penyelesaian masalah system persamaan linier dua variabel
Pendahuluan
Anda akan belajar persamaan bentuk linier satu variable dengan persamaan linier aljabar.
Pernahkah anda memperhatikan bentuk-bentuk persamaan linier ? Coba kita akan pelajari bersama
A. Pengertian Persamaan Linear Satu Variabel
Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan
(=) dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu
variabel adalah ax + b = 0. Contohnya :
1. x + 3 = 7
2. 3a + 4 = 1
3. r2– 6 = 10
Untuk memahami persamaan linear satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu kita
pahami yaitu tentang pernyataan, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Kalimat
terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya, variabel
(peubah) adalah lambang (simbol) pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang
anggota himpunan yang telah ditentukan. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu
bilangan tertentu, dan himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-
variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Contohnya :
1. x + 13 = 17
2. 7 – y = 12
3. 4z – 1 = 11
Pada bagian 1. (x + 13 = 17) disebut kalimat terbuka, nilai x disebut variabel, sedangkan 13
dan 17 disebut dengan konstanta). Himpunan penyelesaiannya adalah x = 4
Pada bagian 2. (7 – y = 12) disebut dengan kalimat terbuka, nilai y disebut dengan variabel,
sedangkan 7 dan 12 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah y = -5
Pada bagian 3. (4z – 1 = 11) disebut dengan kalimat terbuka, nilai z disebut dengan variabel,
sedangkan – 1 dan 11 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah z = 3.
B. Kesetaraan Bentuk PLSV
Dua persamaan atau lebih dikatakan setara (Equivalen) jika mempunyai himpunan penyelesaian
yang sama dan dinotasikan dengan simbol “ ↔ “. Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke
dalam suatu persamaan yang setara adalah dengan cara :
1. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
2. Mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Contoh soal :
1. Tentukan nilai x – 3 = 5
Penyelesaian :
Jika x diganti 8 maka nilai 8-3 = 5 {benar} (syarat ke-1)
Jadi penyelesaian persamaan x-3 = 5 adalah x = 8
2. Tentukan nilai 2x – 6 = 10
Penyelesaian :
2x-6 = 10 → 2x = 16 (syarat ke-1)
Nilai x diganti dengan 8 agar kedua persamaan setara
2(8) = 16 → 16 = 16 .
Jadi penyelesaian persamaan 2x – 6 = 10 adalah x = 8
3. Tentukan nilai x + 4 = 12
Penyelesaian :
x + 4 = 12 → x = 12-4 { syarat ke-1}
Maka nilai x = 8
Jadi penyelesaiannya adalah x = 8
C. Penyelesaian Soal PLSV
Cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel adalah dengan cara substitusi. Metode
substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut
menjadi kalimat yang benar.
Contoh :
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan y + 2 = 5, jika nilai y merupakan variabel dan
bilangan asli.
Pembahasan :
Kita ganti variabel y dengan nilai y = 3 (substitusi), ternyata persamaan y + 2= 5 menjadi
kalimat terbuka yang benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari y + 2 = 5 adalah {3}.
Adapun langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut :
1. Kelompokkan suku yang sejenis.
2. Jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas.
3. Jika pindah ruas maka tanda berubah (positif (+) menjadi negatif (-) dan sebaliknya).
4. Cari variabel hingga = konstanta yang merupakan penyelesaian.
Contoh :
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4x – 3 = 3x + 5. Jika nilai x variabel pada
himpunan bilangan bulat.
Pembahasan :
4x – 3 = 3x + 5
4x- 3 + 3 = 3x +5 + 3 (kedua ruas ditambah 3)
4x = 3x + 8 (langkah 1 (kelompokkan suku sejenis))
4x – 3x = 8
x = 8 (himpunan penyelesaiannya adalah x = 8)
Model Matematika PLSV
Aplikasi PLSV banyak digunakan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari
contohnya menentukan bilangan yang tidak diketahui, menentukan luas dan keliling tanah,
penentuan jumlah hasil panen, harga jual suatu kendaraan, jumlah paket pengiriman jasa,
dll. Biasanya dalam penyelesaian soal aplikasi PLSV adalah dengan membuat model
matematika. mobel matematika ini digunakan dengan cara memisalkan informasi yang tidak
diketahui yaitu dengan memisalkan dengan variabel tertentu pada informasi yang tidak
diketahui. Contoh soal Aplikasi SPLV adalah sebagai berikut :
1. Selisih dua bilangan adalah 7 dan jumlah keduanya adalah 31. Buatlah model matematikanya
dan tentukan kedua bilangan tersebut.
Pembahasan :
Model Matematikanya : Bilangan I = x
Bilangan II = x =7
Dan penyelesaian dari model matematika di atas adalah :
x + (x + 7) = 31
2x +7 = 31
2x = 12
Jadi, Bilangan I = 12
Bilangan II = x+7
= 19
Soal dan Pembahasan
Soal :
Penyelesaian :
Dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian linear satu variabel, diperoleh :
2. Soal : Aplikasi PLSV dalam menentukan jumlah hasil panen
Jika jumlah hasil panen jeruk di suatu perkebunan pada bulan ke-t dengan B(t) = 80t + 75 kg,
maka jumlah hasil panen jeruk sebesar 1,275 ton akan terjadi pada bulan ke……..
Penyelesaian :
Diketahui :
B (t) = 80 t + 75 kg
B (t) = 1,275 ton = 1275 kg
Oleh karena B (t) = 80t + 75 kg dan t = 1275 kg , maka diperoleh :
Jadi, jumlah hasil panen jeruk sebesar 1,275 ton akan terjadi pada bulan ke-15.
Zona Aktivitas
A. Uji Pengetahuan
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4x – 3 = 3x + 5. Jika nilai x variabel pada himpunan
bilangan bulat.
B. Praktikum
Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian kerjakan soal
berikut :
Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut
6 m lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling tanah 60 m, buatlah model matematika
dan tentukan luas tanah petani.
Setelah menghitung buatlah prtesentasinya dalam bentuk power point dan presentasikan di
depan kelas
C. Tugas Mandiri Terstruktur
Selisih dua bilangan adalah 7 dan jumlah keduanya adalah 31. Buatlah model matematikanya dan
tentukan kedua bilangan tersebut.
Rangkuman
Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan yang setara adalah
dengan cara :
1. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
2. Mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel adalah dengan cara substitusi. Metode
substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut
menjadi kalimat yang benar.
Adapun langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut :
1. Kelompokkan suku yang sejenis.
2. Jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas.
3. Jika pindah ruas maka tanda berubah (positif (+) menjadi negatif (-) dan sebaliknya).
Cari variabel hingga = konstanta yang merupakan penyelesaian
Ulangan Akhir BAB 3
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x – y = -1 dan x + 2y =
12
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear y = 2x − 3
3x + 2y = 8
3. Penyelesaian dari sistem persamaan 2ax + by = 10 dan 10x – 2ay = -b adalah x = 1
dan y = 2. Carilah nilai a dan b !
4. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan x+y=5
x2 + y2 = 17
5. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 273x – 4 =39x + 1
6. Jika {(x, y)} merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
x = 2y + 9 dan x + 5y = -5, maka berapakah nilai x – y
7. Diketahui keliling suatu persegi panjang adalah 10 cm. Berapa luas maksimum
dari persegi panjang tersebut ?
8. Tentukan himpunan penyelesaian dari a – 3b + c = -2, 2a – b + c = 6, dan a + 2b –
c=3
9. Penyelesaian dari sistem persamaan linier + 2 = 4 adalah x1 dan y1.
− = 1
Hitung nilai x1 + y1
10. Pak Didik bekerja dengan perhitungan 4 hari lembur dan 2 hari tidak lembur serta
mendapat gaji Rp 740.000,00, sedangkan Pak Topo bekerja 2 hari lembur dan 3
hari tidak lembur dengan gaji Rp 550.000,00. Jika pak Lilik bekerja dengan
perhitungan lembur selama lima hari maka berapa gaji yang diterima Pak Lilik ?
BAB 4
Program Linear
Kompetensi Dasar :
3.4 Menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan konstektual yang berkaitan dengan
program linear dua variable
4.4 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan program linear dua variable
Pendahuluan
Dunia industri yang memanfaatkan pemrograman linear diantaranya adalah industri transportasi,
energi, telekomunikasi dan manufaktur. Pemrograman linear juga dimanfaatkan dalam
pembuatan model berbagai jenis masalah dalam perencanaan, perancangan rute, penjadwalan,
pemberian tugas dan desain. Secara lengkap materi tentang program linear akan dipelajari pada
bab berikut.
Program linear ialah suatu program yang digunakan sebagai metode yang umumnya digunakan untuk
memecahkan suatu masalah seperti pengalokasian sumber daya dengan tujuan akhir yaitu
menentukan nilai minimum atau maksimum. Lebih lengkapnya yuk kita simak pembahasannya berikut:
program linier
A. Pengertian Program Linear
Program linear merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum
dari suatu persoalan linear. Nilai optimum (maksimal atau minimum) dapat diperoleh dari nilai dalam
suatu himpunan penyelesaiaan persoalan linear.
Di dalam persoalan linear tersebut terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif.
Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear adalah merupakan sistem pertidaksamaan
linear.
Perhatikan tabel persoalan maksimum dan minimum dibawah berikut:
Model Matematika Program Linear
Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum,
kemudian diubah kedalam sebuah model matematika.
Model matematika adalah pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika.
Sebagai gambaran:
Sebuah produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Komposisi
model yang pertama terdiri dari 200 gr bahan pertama dan bahan kedua 150 gr. Sedangkan komposisi
model kedua tersebut terdiri dari 180 gr bahan pertama dan 170 gr bahan kedua. Persediaan di gudang
bahan pertama 76 kg dan persediaan digudang untuk bahan kedua 64 kg. Harga model pertama ialah
Rp. 500.000,00 dan untuk model kedua harganya Rp. 400.000,00.
Apabila disimpulkan atau disederhanakan ke dalam bentuk tabel akan menjadi sebagai berikut:
Dengan peubah dari jumlah optimal model 1 ialah x dan model 2 ialah y, serta hasil penjualan optimal
ialah f(x, y) = 500.000x + 400.000y. Dengan beberapa syarat:
Apabila jumlah maksimal bahan 1 yaitu 72.000 gr, maka 200x + 150y ≤ 72.000.
Apabila jumlah maksimal bahan 2 yaitu 64.000 gr, maka 180x + 170y ≤ 64.000
Masing-masing dari setiap model harus terbuat.
Model matematika untuk mendapatkan jumlah penjualan yang maksimum yaitu:
B. Nilai Optimum Fungsi Objektif
Fungsi objektif yaitu fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah
himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada ialah berupa titik-titik dalam diagram
cartesius yang apabila koordinatnya disubstitusikan kedalam fungsi linear maka dapat memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear bisa ditentukan dengan menggunakan metode
grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, maka kita bisa tentukan letak
titik yang menjadi nilai optimum.
Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :
Menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada pada cartesius.
Menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan pada garis batasan dengan garis
batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut adalah himpunan penyelesaian dari batasannya
dan memiliki suatu kemungkinaan besar akan membuat fungsi menjadi optimum.
Meneliti nilai optimum fungsi objektif dengan dua acara, yaitu :
o Menggunakan garis selidik, dan
o Membandingkan nilai fungsi objektif pada tiap titik ekstrim.
1. Menggunakan Garis Selidik
Garis selidik dapat diperoleh dari fungsi objektif f(x, y) = ax + by yang mana garis selidiknya ialah:
ax + by = Z
Nilai Z diberikan sembarang nilai.
Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaannya juga dibuat.
Garis selidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal. Lalu kemudian dibuat garis-garis yang
sejajar dengan garis selidik awal.
Berikut adalah pedoman untuk mempermudah penyelidikian nilai fungsi optimum:
Cara 1 (syarat a > 0), yaitu:
Apabila maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat
himpunan penyelesaian berada di kiri garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik
maksimum.
Apabila minimum, maka dibuatlah garis yang sejajar garis selidik awal sehingga akan membuat suatu
himpunan penyelesaian berada di kanan garis tersebut.
Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik minimum.
Perhatikan grafik dibawah:
Cara ke- 2 (syarat b > 0), yaitu:
Apabila maksimum: maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat
himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah
titik maksimum.
Apabila minimum: maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat
himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik
minimum.
Perhatikanlah grafik dibawah berikut:
Bagi nilai a < 0 dan b < 0 maka berlaku sebuah kebalikan dari kedua cara yang dijelaskan di atas.
C. Membandingkan Nilai Fungsi Tiap Titik Ekstrim
Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu
menentukan titik-titik potong dari suatu garis-garis batas yang ada. Titik-titik potong tersebut
merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum pada salah satu titiknya.
Berdasarkan titik-titik tersebut, maka dapat ditentukan nilai masing-masing fungsinya, yakni kemudian
dibandingkan.
Nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil adalah merupakan nilai minimum.
Zona Aktivitas
A. Uji Pengetahuan
Tentukanlah sebuah nilai minimum dari: f(x, y) = 9x + y pada daerah yang telah dibatasi oleh 2 ≤
x ≤ 6, dan 0 ≤ y ≤ 8 serta x + y
B. Praktik
Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian kerjakan soal
berikut :
1. Seorang agen sepeda ingin membeli dua jenis sepeda untuk persediaan. Setiap
sepeda jenis biasa harganya Rp 150.000,00 dan jenis sepeda balap harganya Rp
200.000,00. Sepeda yang dibeli paling banyak 25 buah dan modal yang tersedia
Rp 4.200.000,00. Laba yang diperoleh tiap sepeda biasa Rp 68.000,00 dan sepeda
balap Rp 70.000,00 Tentukan :
a. Model matematikanya
b. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem
pertidaksamaan.
c. Fungsi tujuan atau sasaran serta nilai optimumnya.
d. Nilai keuntungan maksimum
Setelah selesai buatlah prtesentasinya dalam bentuk power point dan presentasikan di
depan kelas
C. Tugas Mandiri Terstruktur
Seorang pemborong pengecatan rumah mempunyai perse3diaan 50 kaleng cat
warna biru. Pemborong mendapat tawaran untuk mengecat ruang tamu dan
ruang tidur. 1 ruang tamu menghabiskan 3 kaleng cat putih dan 1 kaleng cat
biru. Jika banyaknya ruang tamu dinyatakan dengan x dan banyaknya ruang
tidur dengan y, maka buat model matematika beserta penyelesaiannya dari
masalah tersebut!
Rangkuman
Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear bisa ditentukan dengan menggunakan
metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, maka kita
bisa tentukan letak titik yang menjadi nilai optimum.
Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :
Menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada pada
cartesius.
Menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan pada garis batasan dengan
garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut adalah himpunan penyelesaian dari
batasannya dan memiliki suatu kemungkinaan besar akan membuat fungsi menjadi optimum.
Meneliti nilai optimum fungsi objektif dengan dua acara, yaitu :
o Menggunakan garis selidik, dan
o Membandingkan nilai fungsi objektif pada tiap titik ekstrim.
Ulangan Akhir
1. Cari nilai minimum dari bentuk obyektif : 5 + 4 pada gambar daerah
penyelesaian system pertidaksamaan 3 + 6 ≥ 18; + ≥ 4; ≥ 0; ≥ 0
2. Suatu tempat parkir luasnya 200 m2. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata
diperlukan tempat seluas 10m2 dan bus 20m2 .Tempat parker itu tidak dapat
menampung lebih dari 12 kendaraan. Jika di tempat parkir itu x mobil dan y
bus maka berapa x dan y harus memenuhi …
3. Suatu lahan parkir dapat menampung paling banyak 200 mobil dan sepeda
motor, jika setiap sepeda motor memerlukan lahan 1,5 m2 dan setiap mobil
memerlukan lahan 3m2.Sementara luas lahan parkir 450m2. Jika banyaknya
sepeda motor x dan banyaknya mobil y maka model matematika untuk
masalah tersebut …
4. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240
kaleng cat putih.Pemborongtersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan
kamar tidur di suatu perumahan. Stelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1
kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2
kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong
untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp 300.000,00 dan untuk setiap kamar tidur
Rp 250.000,00 buat model matematika daripersoalan tersebut.
5. Seorang petani memetik buah cokelat setiap hari dan mencatatnya. Ternyata
banyaknya buah cokelat yang dipetik pada hari ke-n tersebut memenuhi
persamaanUn=40+5n. Tentukan jumlah buah cokelat yang dipetik selama 30
hari pertama!.
6. Tulis persamaan garis k di bawah ini adalah…
y
5
0 3x
k
7. Tulis sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada
gambar dibawah ini!
x (3, 3)
3
4y
8. Tentukan nilai x dan y dari system persamaan linier 2 + − 5 = 0 +
− 3 = 0 dengan menggunakan determinan
9. Tentukan nilai maksimum fungsi tujuan = 5 + 6 dari system pertidaksamaan :
2 + ≤ 30, + 2 ≤ 24, ≥ 0, ≥ 0
10. Tentukan nilai minimum (, ) = 400 + 300 yang memenuhi daerah
penyelesaian system pertidaksamaa n: 3 + 2 ≤ 12, + 3 ≤ 6, ≥ 0, ≥
BAB 5
Barisan dan Deret
Kompetensi Dasar :
3.5 Menganalisis barisan dan deret aritmetika
3.6 Menganalisis barisan dan deret geometri
3.7 Menganalisis pertumbuhan , peluruhan, bunga dan anuitas
4.5 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan barisan dan deret
geometri
4.6 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan barisan dan deret
geometri
4.7 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan barisan dan deret
geometri
Pendahuluan
Banyak sekali penggunaan konsep barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari, maka simak
materi berikut untuk menambah kompetensi kalian dalam menyelesaikan permasalahan
mengenai barisan dan deret.
A. Barisan dan Deret Aritmatika
1. Pengertian Barisan Aritmatika
Sebelum memahami pengertian barisan aritmatika kita harus mengetahui terlebih dahulu
mengenai pengertian basiran bilangan. Barisan bilangan merupakan sebuah urutan dari bilangan
yang dibentuk dengan berdasarkan kepada aturan-aturan tertentu. Sedangkan barisan aritmetika
dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan
mengandung nilai selisih yang sama persis, contohnya adalah barisan bilangan: 2, 4 , 6, 8, 10, 12,
14, …
Barisan bilangan tersebut dapat disebut sebagai barisana aritmatika karena masing-masing suku
memiliki selisih yang sama yaitu 2. Nilai selisih yang muncul pada barisan aritmatika biasa
dilambangkan dengan menggunakan huruf b. Setiap bilangan yang membentuk urutan suatu
barisan aritmatika disebut dengan suku. Suku ke n dari sebuah barisan aritmatika dapat
disimbolkan dengan lambang Un jadi untuk menuliskan suku ke 3 dari sebuah barisan kita dapat
menulis U3. Namun, ada pengecualian khusus untuk suku pertama di dalam sebuah barisan
bilangan, suku pertama disimbolkan dengan menggunakan huruf a.
Maka, secara umum suatu barian aritmatika memiliki bentuk :
U1,U2,U3,U4,U5,…Un-1
a, atb, a+2b, a+3b, a+4b,…a+(n-1)b
Cara Menentukan Rumus suku ke-n dari Sebuah Barisan
Pada barisan aritmatika, mencaru rumus suku ke-n menjadi lebih mudah karena memiliki nilai
selisih yang sama, sehingga rumusnya adalah:
U2 = a + b
U3 = u2 + b = (a + b) + b = a + 2b
U4 = u3 + b = (a + 2b) + b = a + 3b
U5 = u4 + b = (a + 3b) + b = a + 4b
U6 = u5 + b = (a + 4b) + b = a + 5b
U7 = u6 + b = (a + 5b) + b = a + 6b
.
.
.
U68 = u67+b = (a + 66b) + b = a + 67b
U87 = u86+b = (a + 85b) + b = a + 86b
Berdasarkan kepada pola urutan diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa rumus ke-n dari
sebuah barisan aritmatika adalah:
Un = a + (n – 1)b dimana n merupakan bilangan asli
Beda di rumuskan dengan : B = Un – Un-1
Suku ke-n dari barisan Aritmatika dirumuskan :
Un = a + (n – 1)b Dimana : a = suku pertama
B = beda
Jika n ganjil , maka suku tengahnya dirumuskan :
Ut = ½(a + Un) dimana t = ½(n + 1)
Jika diantara 2 suku disisipkan K buah suku maka barisan tersebut memiliki beda baru (b’) yang
dirumuskan :
B = b/k+1
Contoh soal Barisan Aritmatika.
Tentukan suku ke-25 dari barisan deret aritmatika : 1, 3, 5, 7, … ?
Jawab :
Dik :
deret : 1. 3, 5, 7, …
a=1
b = 3-1 = 5-3 = 7-5 = 2
Un = a + (n-1) b
= 1 + (25-1)2
= 1 + (24).2
= 1 + 48
= 49
Jadi nilai dari suku ke-25 (U25) adalah 49
2. Pengertian Deret Aritmatika
Deret aritmatika dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika
yang dihitung secara berurutan. Sebagai contoh kita ambil sebuah barisan aritmatika
8,12,16,20,24 maka deret aritmatikanya adalah 8+12+16+20+24
Untuk menghitung deret aritmatika tersebut masih terbilang mudah kaerna jumlah sukunya
masih sedikit:
8+12+16+20+24 = 80
Namun, bayangkan jika deret aritmatika tersebut terdiri dari ratusan suku, tentu akan sulit untuk
menghitungnya, bukan? Oleh karenanya, kita harus mengetahui rumus untuk menghitung jumlah
deret aritmatika. Rumus yang biasa digunakan adalah:
Sn = 1/2 n (2a+(n-1)b)
Contoh soal Deret Aritmatika.
Hitunglah jumlah 20 suku pertama dari deret arimetika 3 + 5 + 7 + …..
Jawab :
A = 3, b = 5 – 3 = 2, dan n = 20, maka :
S20 = 10( 6 + 19.2)
= 10 ( 6 + 38)
= 10 ( 44 }
= 440
Barisan dan deret geometri adalah salah satu materi yang dipelajari dalam Matematika
SMA. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku
sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai
suku-suku yang berdekatan selalu sama yaitu r. Nilai suku pertama dilambangkan dengan a.
Untuk mengetahui nilai suku ke-n dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus
berikut.
Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri.
Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke-n barisan geometri dapat dihitung dengan
rumus berikut.
dengan syarat r < 1
atau
dengan syarat r > 1
Contoh Soal : Soal khusus
Selembar kertas dipotong menjadi dua bagian. Setiap bagian dipotong menjadi dua dan
seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan …
Pembahasan:
Diketahui: a = 1
r=2
Ditanya:
Jawab:
=32
Jadi, jumlah potongan kertas setelah potongan kelima adalah 32
Zona Aktivitas
A. Uji Pengetahuan
1. Jika diketahui nilai dari suku ke-15 dari suatu deret arimatika adalah 32 dan beda deret
adalah 2, maka cari nilai dari suku pertamanya ?
2. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-7 adalah 33 dan suku ke-12 adalah
58.
Tentukan : a). Suku pertama (a) dan beda (b)
b). Besarnya suku ke-10
B. Praktikum
Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian kerjakan soal
berikut :
1. Dari suatu deret aritmatika dengan suku ke-n adalah U . diketahui U3 + U6 + U9 +
U12 = 72. Hitung jumlah 14 suku pertama deret ini
2. Diketahui suku ke-5 dari barisan geometri adalah 243, hasil bagi suku ke-9 dengan suku
ke-6 adalah 27. Suku ke-2 dari barisan tersebut adalah …
Setelah menghitung buatlah prtesentasinya dalam bentuk power point dan presentasikan
di depan kelas
C. Tugas Mandiri Terstruktur
1. Suatu deret aritmatika mempunyai beda 2 dan jumlah 20 suku pertamanya adalah
240,
jumlah 7 suku pertamanya adalah ?
2. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9
adalah 768. Suku ke-7 deret tersebut adalah …
Rangkuman
Kita harus mengetahui rumus untuk menghitung jumlah deret aritmatika. Rumus yang
biasa digunakan adalah:
Sn = 1/2 n (2a+(n-1)b)
Suku ke-n dari barisan aritmatika dirumuskan : Un = a + (n – 1)b
Untuk mengetahui nilai suku ke-n dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus
berikut.
Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri.
Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke-n barisan geometri dapat dihitung dengan
rumus berikut.
dengan syarat r < 1
atau
dengan syarat r > 1
Ulangan Akhir BAB 5
1. Jika diketahui nilai dari suku ke-15 dari suatu deret arimatika adalah 32 dan beda
deret adalah 2, maka cari nilai dari suku pertamanya ?
2. Dalam suatu barisan aritmatika, jika U3 + U7 = 56 dan U6 + U10 = 86 , carilah
suku ke-2 deret tersebut !
3. Diketahui barisan aritmatika dengan Un adalah suku ke-n. jika U2 + U15 + U40 =
16 5, maka berapakah U19 ?
4. Tentukan suku ke-10 dan rumus suku ke-n barisan tersebut!
5. Suku keberapakah yang nilainya 198 ?
6. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9
adalah 768. Berapakah suku ke-7 deret tersebut
7. Diketahui suku ke-5 dari barisan geometri adalah 243, hasil bagi suku ke-9 dengan
suku ke-6 adalah 27. Cari suku ke-2 dari barisan tersebut
8. Berapakah jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 + 6 + 18 + …
BAB 6
Trigonometri
Kompetensi Dasar :
3.8 Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku
3.9 Menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran
3.10 Menentukan koordinat Cartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya
3.11 Menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri
3.12 Menerapkan aturan sinus dan cosinus
3.13 Menentukan luas segitiga pada trigonometri
3.14 Menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut
4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada
segitiga siku-siku
4.9 Menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran
4.10 Menyelesaikan masalah perubahan koordinat Cartesius menjadi koordinat kutub
dan sebaliknya
4.11 Menyajikan grafik fungsi trigonometri
4.12 Menyelesaikan permasalahan konstektual dengan aturan sinus dan cosinus
4.13 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan luas seegitiga pada
trigonometri
4.14 Menyelesaikan nilai-nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut
Pendahuluan
Untuk mengetahui ketinggian semburan awan panas yang disebabkan oleh letusan
Gunung Merapi yang terletak di daerah sekitar Yogyakarta, kalian dapat
menggunakan teropong. Kita yang berada pada jarak dan ketinggian tertentu
mengarahkan teropongnya sampai ujung ketinggian dari awan panas tersebutdapat
terlihat. Penggunaan rumus-2 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku akan
kita pelajari pada bab ini.
A. Ukuran Sudut
1. Ukuran Derajat
Besar sudut dalam satu putaran adalah 360°. Berarti 1°= 1/360 putaran. Ukuran sudut
yang lebih kecil dari derajat adalah menit ( ‘ ) dan detik ( “ ).
Hubungan ukuran sudut menit, detik, dan derajat adalah:
2. Ukuran Radian
Satu radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-
jari.
3. Hubungan Derajat dengan Radian
Untuk mengubah sudut sebesar �� ke dalam satuan radian, menggunakan rumus:
Dan untuk mengubah sudut sebesar X radian ke dalam satuan derajat, menggunakan rumus:
Contoh Soal
1. Nyatakan sudut 0,65 radian dalam satuan derajat!
Jawab :
2. Suatu lingkaran memiliki panjang busur 15 cm dan dengan sudut pusat 45°, carilah jari-jari
lingkaran tersebut!
Jawab:
Kita harus merubah ��= 45° ke dalam bentuk radian.
B. Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku
Perhatikanlah gambar berikut!
Jika dipandang dari sudut ��, maka sisi BC disebut sisi depan, sisi AB disebut sisi samping, dan sisi AC
disebut sisi miring.
Jika sisi AB = x, sisi BC = y, dan sisi AC = r, maka
Contoh soal
Perhatikan gambar berikut!
Diketahui panjang AC = 9 cm, dan panjang AB = 12 cm, dengan sudut b = ��. Tentukan nilai
dari sin ��, cos ��, dan tan ��!
Pemecahan:
C. Perbandingan Trigonometri Sudut Berelasi
Dalam satu putaran, yaitu 360°, sudut dibagi menjadi empat relasi, yaitu:
1. Kuadran I : 0°≤ α ≤ 90°
2. Kuadran II : 90° < α ≤ 180°
3. Kuanran III : 180° < α ≤ 270°
4. Kuadran IV : 270° < α ≤ 360°
Perhatikan gambar berikut!
1. Perbandingan Trigonometri Sudut di Kuadran I
Pada ∆ AOC, berlaku:
Pada ∆ BOC, berlaku:
2. Perbandingan Trigonometri Pada Sudut Kuadran II
Pada ∆ AOC, berlaku: ∠α = 180°- ��
3. Perbandingan Trigonometri Pada Sudut Kuadran III
Pada ∆ AOC berlaku: ∠ AOP = α
4. Perbandingan Trigonometri Pada Sudut Kadran IV
sin (360° - ��) = - sin ��
cos (360° - ��) = cos ��
tan (360° - ��) = - tan ��
cosec (360° - ��) = - cosec ��
sec (360° - ��) = sec ��
cotan (360° - ��) = - cotan ��
5. Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut Diatas 360° atau Sudut Negatip
a. Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut Diatas 360°
Sin (k × 360° + ��) = sin ��
Cos (k × 360° + ��) = cos ��
tan (k × 360° + ��) = tan ��
cosec (k × 360° + ��) = cosec ��
sec (k × 360° + ��) = sec ��
cotan (k × 360° + ��) = cotan ��
Keterangan:
k = banyaknya putaran, dengan nilai k adalah bilangan bulat positif.
b. Perbandingan Trigonometri Sudut Negatif
Sin (- ��) = -sin ��
Cos (-��) = cos ��
tan (-��) = -tan ��
cosec (-��) = -cosec ��
sec (-��) = sec ��
cotan (-��) = -cotan ��
Contoh Soal
1. Nyatakan sudut berikut kedalam perbandingan trigonometri sudut lancip positif!
a. Sin 175°
b. Cos 325°
c. Sec (-225°)
d. Tan 780°
e. Sin 3500°
Pemecahan:
Persamaan Trigonometri sin x = sin α, cos x = cos α, dan tan x = tan α
1. Jika sin x = sin α, maka x = α + k . 360° atau x = (180° - α) + k . 360°
2. Jika cos x = sin α, maka x = α + k . 360° atau x = (360° - α) + k . 360° = -α + k . 360°
3. Jika tan x = tan α, maka x = α + k . 180°
Contoh Soal
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut!
a. Sin x = sin ⅚ ��, 0 ≤ x ≤ 2��
b. Tan x = tan ⅓��, 0 ≤ x ≤ 2��
c. Cos x = cos 150°, 0° ≤ x ≤ 360°
Pemecahan:
a. Sin x = sin ⅚ ��, 0 ≤ x ≤ 2��
Himpunan penyelesaian = {⅚ ,⅙��}
b. Tan x = tan ⅓��, 0 ≤ x ≤ 2��
Himpunan penyelesaian={⅓�� ,4/3 ��}
c. Cos x = cos 150°, 0° ≤ x ≤ 360°
Himpunan penyelesaian= {150°,210°}
E. Identitas Trigonometri
1. Rumus Dasar
2. Menentukan Identitas Trigonometri
a. Ubah bentuk ruas kiri hingga sama dengan bentuk ruas kanan.
b. Ubah bentuk ruas kanan hingga sama dengan bentuk tuas kiri.
c. Kedua ruas diubah hingga didapat bentuk baru yang sama.
Contoh Soal
1. Buktikan bahwa sec2 �� + tan2 �� = 2tan2��+1
2. Buktikan bahwa sec Y – cos Y = sin Y . tan Y
Penyelesaian:
1. sec2 �� + tan2 �� = 2tan2��+1
Ruas kiri
= tan2 �� + 1 + tan2 ��
= 2 tan2 ��+1
2. sec Y – cos Y = sin Y . tan Y
bukti dengan mengubah ruas kiri
F. Trigonometri Pada Segitiga Sembarang
1. Aturan Sinus
Rumus:
Contoh soal
1) Perhatikan gambar berikut!
Tentukan panjang x dalam cm!
Penyelesaian:
2. Aturan Cosinus
Rumus:
a2 = b2+c2 - 2bc cos ��
b2 = a2+c2 - 2ac cos ��
c2 = a2+b2 - 2ab cos ��
Contoh soal
1) Perhatikan gambar berikut!
Tentukan panjang PR!
Pemecahan:
PR2 = RQ2 + PQ2 – 2RQPQ cos ∠ Q
PR2 = 172 + 302 – 2 . 17 . 30 cos 53°
PR2 = 289 + 900 – 1020 . ⅗
PR2 = 1189 – 612
PR2 = 577
PR = √577 = 24,02 cm
3. Luas Segitiga
Rumus:
L = ½ ab sin ��
L = ½ bc sin ��
L = ½ ac sin ��
Contoh Soal
Hitunglah luas ABCD berikut!
Pemecahan:
a. Untuk ∆ BCD
Luas ∆ BCD = ½ BD.CD. sin ∠ D
Luas ∆ BCD = ½ . 18√2 . 12√6 . sin 30°
Luas ∆ BCD = ½ . 18√2 . 12√6 . ½ = ¼ . 216√12 = 108√3 cm2
b. Untuk ∆ ABD
Luas ∆ ABD = ½ AD.BD. sin ∠D
Luas ∆ ABD = ½ . 18. 18√2 . sin 105°
c. Luas ABCD
Luas ABCD = Luas ∆ BCD + Luas ∆ ABD
Luas ABCD = 108√3 cm2 + 81√3 + 81 cm2
Luas ABCD = 189√3 cm2 + 81 cm2
Luas ABCD = 327,35 + 81
Zona Aktivitas
D. Uji Pengetahuan
1. Nyatakan sudut 154° ke satuan radian!
2. Tentukan nilai dari
E. Praktikum
Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian kerjakan soal
berikut :
Jika sin 15°= y. Tentukan nilai trigonometri berikut dalam y!
a. Cos 15°
b. Tan 15°
c. Sin 75°
d. Cos 75°
e. Tan 75°
f. Cosec 15°
g. Cotan 75°
h. Sec 75°
Setelah menghitung buatlah prtesentasinya dalam bentuk power point dan presentasikan
di depan kelas
F. Tugas Mandiri Terstruktur
Diketahui sin 35° = 2k, nyatakan trigonometri sudut berikut dalam k!
a. Sin 55°
b. Cos (-215°)
c. Tan 125°
d. Cosec 935°
e. Sin 665°
Rangkuman
Ukuran Derajat
Ukuran Radian
Untuk mengubah sudut sebesar �� ke dalam satuan radian, menggunakan rumus:
Dan untuk mengubah sudut sebesar X radian ke dalam satuan derajat, menggunakan rumus:
Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku
Jika sisi AB = x, sisi BC = y, dan sisi AC = r, maka
Persamaan Trigonometri sin x = sin α, cos x = cos α, dan tan x = tan α
1. Jika sin x = sin α, maka x = α + k . 360° atau x = (180° - α) + k . 360°
2. Jika cos x = sin α, maka x = α + k . 360° atau x = (360° - α) + k . 360° = -α + k . 360°
3. Jika tan x = tan α, maka x = α + k . 180°
Ujian Akhir BAB 6
1. Diketahui , tentukanlah nilai dari sin α, tan α, dan cosec α!
2. Tentukan nilai dari
3. Nyatakan sudut berikut kedalam perbandingan trigonometri sudut lancip positif!
a. Sin 175°
b. Cos 325°
c. Sec (-225°)
d. Tan 780°
e. Sin 3500°
4. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut!
a. Sin x = cos 300°, 15°≤ x ≤ 360°
b. Cos x = cotan 135°, 0°≤ x ≤ 360°
c. Tan x = sin 0°, 180°≤ x ≤ 360°
d. Cos 3x = cos 180°, 0° ≤ x ≤ 360°
e. Sin (30°+x) = sin 75°, 0°≤ x ≤ 270°
f. Sin (4x+38°) = sin 173°, 0° ≤ x ≤ 360°
5. Hitung nilai cos 75˚ cos 15˚ − sin 75˚ 15 ˚
6. Diketahui sin = 3 cos = 5 . Jika A dan B merupakan sudut lancip maka
5 13
hitunglah nilai tan( − )
7. Bentuk sederhana dari sin 5 +sin 3 = ⋯
cos 5 +cos 3
8. Diketahui sebuah Δ ABC, AB = 6cm, BC = 5cm dan AC = 4. Berapakah nilai cos ∠ ?
9. Jika 0° < a < 90° dan tan a = 5 , hitunglah nilai sin a?
√11
10. Jika sin A = − 5 dan A di kuadran III, berapakah nilai cotan A?
13
BAB 7
Matriks
Kompetensi Dasar :
3.15 Menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Matriks
3.16 Menentukan nilai determinan, invers, dan transpos pada ordo 2x2 dan 3x3
4.15 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks
4.16 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, invers, dan transpos
pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpos pada 3x3
Pendahuluan
Ada banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan matriks. Misalnya
mengirim pesan rahasia, membuat analisis ekonomi, menyederhanakan proses
pengolahan data, membantu menyelesaikan masalah transformasi transformasi
geometri dll. Oleh karena itu kita akan pelajari materi matriks beserta operasinya
supaya mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya.
A. Pengertian Matriks
Matriks adalah suatu susunan elemen-elemen atau entri-entri yang berbentuk persegi panjang yang
diatur dalam baris dan kolom. Susunan elemen ini diletakkan dalam tanda kurung biasa ( ), atau kurung
siku [ ]. Elemen-elemen atau entri-entri tersebut dapat berupa bilangan atau berupa huruf.
Matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C dan seterusnya. Sedangkan elemennya jika
berupa huruf maka ditulis dengan huruf kecil.
Dalam matriks dengan i dan j merupakan bilangan bulat yang menunjukkan baris ke-i dan
kolom ke-j. Misalnya artinya elemen baris ke-1 dan kolom ke-2.
Contoh :
Dari matriks A diatas :
a. Banyaknya baris adalah 4.
b. Banyaknya kolom adalah 5.
c. Elemen-elemen baris ke-3 adalah 0, 5, 1,7, -1.
d. Elemen-elemen baris ke-4 adalah 9, 2, 6, 1, 0.
e. Elemen-elemen kolom ke-1 adalah -1, 4, 0, 9.
f. Elemen-elemen kolom ke-4 adalah 7, -3, 7, 1.
g. Elemen baris ke-2 dan kolom ke-3 atau adalah 9.
h. Elemen baris ke-3 dan kolom ke-5 atau adalah -1.
B. Ordo Matriks
Ordo (ukuran) dari matriks adalah banyaknya elemen baris diikuti banyaknya kolom. berarti
matriks A berordo m x n, artinya matriks tersebut mempunyai m buah baris dan n buah kolom.
Contoh :
Tentukan ordo dari matriks dibawah ini !
a. b.
Jawab :
a. Matriks G terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, maka matriks G berordo 2 x 3, atau ditulis G2X3.
b. Matriks H terdiri dari 1 baris dan 4 kolom, maka matriks H berordo 1 x 4, atau ditulis H1X4.
C. Jenis - Jenis Matriks
1. Matriks Nol
Matriks nol adalah matriks yang seluruh elemennya nol.
Contoh :
2. Matriks Kolom
Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom.
Contoh :
3. Matriks Baris
Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris
Contoh :
4. Matriks Persegi atau Bujur Sangkar
Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom.
Contoh :
5. Matriks Diagonal
Matriks diagonal adalah matriks yang seluruh elemennya nol kecuali pada diagonal utamanya tidak
semuanya nol.
Contoh :
6. Matriks Segitiga
Matriks segitiga terdiri atas dua macam yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah.
Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen dibawah diagonal utama seluruhnya nol.
Contoh :
Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen diatas diagonal utama seluruhnya nol.
Contoh :
7. Matriks Identitas
Matriks identitas adalah matriks yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah satu dan elemen
lainnya adalah nol.
Contoh :
D. Transpose Matriks
Transpose matriks A = (aij) dengan ordo m x n ditulis AT = (aij) dan mempunyai ordo n x m. Elemen-
elemen baris matriks AT diperoleh dari elemen-elemen kolom matriks A dan sebaliknya.
Contoh : maka
E. Kesamaan Dua Matriks
Dua matriks dikatakan sama, apabila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang seletak
(bersesuaian) dari kedua matriks tersebut sama.
Contoh :
Matriks A = B karena ordo dan elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut sama.
Sedangkan walaupun elemennya sama tetapi tidak seletak.
Contoh :
Tentukanlah nilai x, y, z, a, b dan c dari kesamaan dua matriks dibawah ini :
Jawab :
· Elemen baris 1 kolom 1 (a11) : 2x = 4
x=2
· Elemen baris 1 kolom 3 (a13) : 2 + x = y
y=2+2=4
· Elemen baris 2 kolom 1 (a21) : z = 3y
z = 3.4 = 12
· Elemen baris 2 kolom 2 (a22) : a + 1 = 4z
a + 1 = 4.12 a = 48 – 1 = 47
· Elemen baris 3 kolom 1 (a31) : b = a + 5
b = 47 + 5 b = 52
· Elemen baris 3 kolom 2 (a32) :
Jadi, nilai x = 2, y = 4, z = 12, a = 47, b = 52 dan c = 100.
F. Operasi Matriks
Penjumlahan dan Pengurangan Matriks
Dua matriks A dan B dapat dijumlahkan atau digunakan operasi pengurangan bila ordo (baris x kolom)
kedua matriks tersebut sama. Hasil jumlah (selisih) didapat dengan cara menjumlahkan (mengurangkan)
elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut.
Contoh :
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Bilangan berpangkat, akar dan logaritma
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search