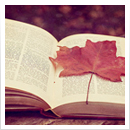Universitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin
2022
E - MODUL
TEKNIK PEMESINAN BUBUT
Untuk Siswa SMK
Kelas X
Disusun Oleh: Aldi Setiawan I 1750324403
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan modul elektronik ini untuk peserta didik kelas X SMK kompetensi
keahlian Teknik Pemesinan. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari
kegelapan menuju jalan yang lebih terang.
Penulis ucapkan juga rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya
modul elektronik ini, yaitu orang tua penulis, rekan-rekan penulis, dan masih banyak lagi yang tidak
bisa penulis sebutkan satu per satu. Adapun, modul elektronik yang berujudul “Pengembangan Modul
Pembelajaran Teori Pemesinan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta” ini telah selesai penulis buat
secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi peserta didik yang membutuhkan
informasi, pengetahuan, dan media belajar bagi peserta didik untuk belajar mengenai dasar
menggunakan mesin bubut dan menjelaskan secara terperinci. Modul praktik mesin bubut ini
menitikberatkan pada bagaimana mengoperasikan bagian-bagian mesin bubut dengan benar.
Modul elektronik praktik mesin bubut ini dilengkapi dengan gambar-gambar, keterangan, dan
langkah-langkah menggunakan mesin bubut. Media berbentuk modul elektronik yang diberikan kepada
peserta didik bertujuan agar dapat menumbuhkan rasa kemandirian dalam belajar. Peserta didik akan
mempelajari atau memahami bagaimana melakukan praktik mesin bubut dengan baik dan benar.
Dengan adanya pembelajaran menggunakan modul elektronik ini diharapkan kemandirian belajar
peserta didik akan tumbuh. Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari
sempurna tentang modul elektronik ini. Oleh sebab itu, penulis mohon agar pembaca memberi kritik
dan juga saran yang membangun untuk kesempurnaan modul ini sangat diharapkan.
Demikian modul elektronik ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami
informasi dasar menggunakan mesin bubut serta dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam arti luar.
Terima kasih.
Yogyakarta, 07 Oktober 2022
Penulis
ii
DAFTAR ISI ii
iii
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. vii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….... viii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………… xi
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………... xii
PETA KEDUDUKAN E-MODULE …………………………………………………………... 1
PERISTILAHAN/GLOSARY …………………………………………………………………. 1
BAB I ………………………………………………………………………………………….... 1
PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………... 1
1
A. DESKRIPSI E-MODULE ……………………………………………………………... 2
B. PRASYARAT MEMPELAJARI E-MODULE ………………………………………. 2
C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ……………………………………………... 2
D. TUJUAN AKHIR ……………………………………………………………………… 2
3
1. Kinerja yang diharapkan ………………………………………………………… 5
2. Kriteria keberhasilan ……………………………………………………………... 5
3. Variabel dan kriteria keberhasilan ………………………………………………. 5
E. KOMPETENSI ………………………………………………………………………... 5
BAB II ………………………………………………………………………………………….. 5
PEMBELAJARAN ……………………………………………………………………………. 5
Kegiatan Belajar 1: Memahami Aspek Keselamatan Kerja ………………………………… 5
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran ………………………………………………………. 9
2. Uraian Materi ………………………………………………………………………….. 9
a. Keselamatan kerja yang harus dipenuhi saat melakukan praktik mesin bubut 9
b. Aspek yang harus diperhatikan untuk melakukan praktik mesin bubut ……… 10
3. Rangkuman 1 …………………………………………………………………………... 11
4. Tugas 1 …………………………………………………………………………………. 12
5. Tes Formatif ……………………………………………………………………………. 12
Lembar Jawaban 1 …………………………………………………………………………….. 12
Petunjuk ………………………………………………………………………………………... 12
Kegiatan Belajar 2: Memahami Gambar Kerja dan Tanda-tanda Pengerjaan …………… 12
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran ………………………………………………………. 13
2. Uraian Materi ………………………………………………………………………….. 13
a. Macam-macam Proyeksi …………………………………………………………. 14
14
1) Proyeksi Piktorial …………………………………………………………… 15
a) Proyeksi Isometri ………………………………………………………... 15
b) Proyeksi Dimetri ………………………………………………………… 16
c) Proyeksi Miring …………………………………………………………. 18
d) Proyeksi Perspektif ……………………………………………………… 19
20
2) Proyeksi Orthogonal ………………………………………………………... 20
a) Proyeksi orthogonal berdasarkan benda yang diproyeksikan ……………. 20
b) Proyeksi orthogonal berdasarkan pandangan atau proyektornya ………… 21
b. Pemotongan Gambar Benda Kerja ……………………………………………….
c. Kekasaran Permukaan ……………………………………………………………
d. Penunjukkan Nilai Kekasaran dan Arah Bekas Pengerjaan ……………………
1) Simbol Dasar Penunjukkan …………………………………………………
2) Simbol dengan Tambahan Nilai Kekasaran dan Perintah Pengerjaan …..
3) Simbol Arah Bekas Pengerjaan (Tanda Pengerjaan) ……………………...
iii
3. Rangkuman 2 …………………………………………………………………………... 23
4. Tugas 2 …………………………………………………………………………………. 23
5. Tes Formatif ……………………………………………………………………………. 23
Lembar Jawaban 2 …………………………………………………………………………….. 24
Petunjuk ………………………………………………………………………………………... 25
Kegiatan Belajar 3: Memahami Gambar Kerja dan Tanda-tanda Pengerjaan …………… 26
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran ………………………………………………………. 26
2. Uraian Materi ………………………………………………………………………….. 26
26
a. Persyaratan Kerja ………………………………………………………………… 26
1) Kondisi Mesin ……………………………………………………………….. 26
2) Benda Kerja …………………………………………………………………. 26
27
b. Persiapan Praktik di Mesin Bubut ……………………………………………….. 27
c. Peralatan Proses Membubut ……………………………………………………... 27
28
1) Kelompok Alat Potong ……………………………………………………… 28
a) Geometri Pahat Bubut …………………………………………………… 29
29
2) Kelompok Alat Ukur ………………………………………………………... 30
a) Jangka Sorong …………………………………………………………... 30
b) Micrometer ……………………………………………………………… 31
32
d. Perencanaan dan Perhitungan Mesin Bubut ……………………………………. 33
3. Rangkuman 3 …………………………………………………………………………... 34
4. Tugas 3 …………………………………………………………………………………. 34
5. Tes Formatif ……………………………………………………………………………. 34
Lembar Jawaban 3 …………………………………………………………………………….. 34
Petunjuk ………………………………………………………………………………………... 35
Kegiatan Belajar 4: Mengoperasikan Mesin Bubut ………………………………………….. 35
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran ………………………………………………………. 35
2. Uraian Materi ………………………………………………………………………….. 36
36
a. Pengertian Mesin Bubut ………………………………………………………….. 36
b. Bagian-bagian Utama Mesin Bubut ……………………………………………… 37
37
1) Sumbu utama (main spindle) ………………………………………………... 37
2) Meja mesin (bed) .……………………………………………………………. 39
3) Eretan (carriage) ……….……………………………………………………. 41
4) Kepala lepas (tail stock) …………………………………………………….. 43
5) Penjepit pahat ……………………………………………………………….. 45
6) Tuas pengatur kecepatan sumbu utama dan plat penunjuk kecepatan …. 46
7) Transporter dan sumbu pembawa …………………………………………. 47
8) Chuck (cekam) ………………………………………………………………. 48
9) Cekam kolet (collet chuck) ………………………………………………….. 48
10) Alat Pembawa ……………………………………………………………….. 49
11) Alat Penyangga/Penahan Benda Kerja …………………………………….. 50
12) Senter Mesin Bubut ………………………………………………………….
13) Cekam Bor (drill chuck) ……………………………………………………..
c. Gerakan-gerakan dalam membubut ……………………………………………...
d. Jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan pada mesin bubut ………………...
1) Pembubutan permukaan (surface turning) ………………………………...
2) Pembubutan rata (pembubutan silindris) ………………………………….
3) Pembubutan ulir (threading) …….………………………………………….
iv
4) Pembubutan tirus (tapper) ………………………………………………….. 58
5) Pembubutan drilling ………………………………………………………… 62
6) Perluasan lubang (boring) …………………………………………………... 62
7) Pembubutan radius …………………………………………………………. 62
e. Parameter yang dapat diatur pada mesin bubut ………………………………… 63
f. Pahat ……………………………………………………………………………….. 66
g. Kekasaran Permukaan ...………………………………………………………….. 68
1) Permukaan …….…………………………………………………………….. 68
2) Permukaan dan profil ……...……………………………………………….. 69
h. Penyimpangan Selama Proses Pembuatan ………………………………………. 69
i. Toleransi …………………………………………………………………………… 70
j. Suaian (fit) ………..………………………………………………………………... 71
k. Cara Penulisan Toleransi Ukuran/Dimensi ……………………………………… 71
l. Pembuatan Work Preparation …………………………………………………….. 73
3. Rangkuman 4 …………………………………………………………………………... 73
4. Tugas 4 …………………………………………………………………………………. 74
5. Tes Formatif ……………………………………………………………………………. 75
6. Kunci Jawaban ………………………………………………………………………… 78
7. Langkah Kerja …………………………………………………………………………. 78
Lembar Penilaian Jawaban 4 (Bubut 01) …………………………………………………….. 79
Lembar Penilaian Jawaban 4 (Bubut 02) …………………………………………………….. 80
Lembar Penilaian Jawaban 4 (Bubut 03) …………………………………………………….. 81
Petunjuk ………………………………………………………………………………………... 82
Kegiatan Belajar 5: Memeriksa Komponen dan Dimensi Benda Kerja secara Visual …….. 83
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran ………………………………………………………. 83
2. Uraian Materi ………………………………………………………………………….. 83
a. Memahami Skala Alat Ukur ……………………………………………………… 83
1) Jangka Sorong (vernier caliper) …………………………………………….. 83
85
a) Mengukur Dimensi Luar ………………………………………………… 86
b) Mengukur Dimensi Dalam ………………………………………………. 86
c) Mengukur Kedalaman …………………………………………………… 86
2) Micrometer ………………………………………………………………….. 88
b. Cara Menggunakan Alat Ukur …………………………………………………... 88
1) Jangka Sorong ………………………………………………………………. 89
2) Micrometer ………………………………………………………………….. 90
3. Rangkuman 5 …………………………………………………………………………... 91
4. Tugas 5 …………………………………………………………………………………. 91
5. Tes Formatif ……………………………………………………………………………. 92
Lembar Jawaban 5 …………………………………………………………………………….. 93
Petunjuk ………………………………………………………………………………………... 94
BAB III …………………………………………………………………………………………. 94
EVALUASI …………………………………………………………………………………….. 94
A. Pertanyaan ……………………………………………………………………………... 95
B. Lembar Jawaban ………………………………………………………………………. 96
Petunjuk ………………………………………………………………………………………... 97
BAB IV …………………………………………………………………………………………. 97
PENUTUP ………………………………………………………………………………………
v
KUNCI JAWABAN …………………………………………………………………………… 98
1. Kunci Jawaban Tes Formatif 1 ………………………………………………………... 98
2. Kunci Jawaban Tes Formatif 2 ………………………………………………………... 98
3. Kunci Jawaban Tes Formatif 3 ………………………………………………………... 98
4. Kunci Jawaban Tes Formatif 4 ………………………………………………………... 99
5. Kunci Jawaban Tes Formatif 5 ………………………………………………………... 99
101
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………..
vi
Tabel 1. DAFTAR TABEL 3
Tabel 2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Teori Pemesinan ……………………... 3
Tabel 3. Penjabaran Standar Kompetensi ……………………………………………………. 19
Tabel 4. Nilai Kekasaran dan Tingkat Kekasaran …………….……………………………... 20
Tabel 5. Simbol dengan Tambahan Kekasaran ……………………………………………… 21
Tabel 6. Simbol dengan Tambahan Perintah Pengerjaan …………………..………………... 21
Tabel 7. Simbol Arah Bekas Pengerjaan ……………...……………………………………... 52
Tabel 8. Dimensi Ulir Metris ………………………………………………………………... 52
Tabel 9. Dimensi Ulir Withworth ……………………………………………………………. 53
Tabel 10. Kecepatan potong pembubutan rata dan pembubutan ulir dengan pahat …………… 62
Tabel 11. Ukuran Tapper Morse ………………...…………………………………………..... 66
Tabel 12. Cara Penentuan Jenis Pahat, Geometri Pahat, Harga V, dan Harga f (EMC) ………. 79
Tabel 13. Penilaian tugas praktik peserta didik 01 …………………………………………..... 80
Tabel 14. Penilaian tugas praktik peserta didik 02 ……………………………………………. 81
Tabel 15. Penilaian tugas praktik peserta didik 03 ……………………………………………. 95
Penilaian tugas praktik peserta didik evaluasi ………………………………………
vii
Gambar 1. DAFTAR GAMBAR 5
Gambar 2. 6
Gambar 3. Pahat setinggi senter …………………………………………………………... 7
Gambar 4. Kacamata Safety ……………………………………………………………… 7
Gambar 5. Sarung tangan kulit …………………………………………………………… 8
Gambar 6. Sepatu safety …………………………………………………………………... 8
Gambar 7. Wearpack ……………………………………………………………………... 12
Gambar 8. Kondisi mesin …………………………………………………………………. 13
Gambar 9. Jenis proyeksi piktorial ……………………………………………………….. 13
Gambar 10. Proyeksi isometri ……………………………………………………………… 14
Gambar 11. Proyeksi dimetri …………………………...………………………………….. 14
Gambar 12. Proyeksi miring ……………………………………………………………….. 15
Gambar 13. Proyeksi perspektif ……………………….…………………………………… 15
Gambar 14. Proyeksi orthogonal sebuah titik ..……………………………………………... 16
Gambar 15. Proyeksi orthogonal sebuah garis ……………………………………………... 16
Gambar 16. Proyeksi orthogonal sebuah bidang …………………………………………… 17
Gambar 17. Proyeksi orthogonal sebuah bangun ruang ..…………………………………... 18
Gambar 18. Proyeksi eropa atau proyeksi kwadran I …..…………………………………... 19
Gambar 19. Proyeksi amerika atau proyeksi kwadran III ………………………………….. 20
Gambar 20. Potongan sebagian ………….…………………………………………………. 21
Gambar 21. Simbol kekasaran permukaan ……………...………………………………….. 22
Gambar 22. Letak simbol-simbol ………………………………………………………….. 22
Gambar 23. Contoh penunjukkan simbol dan huruf pada gambar …………………………. 23
Gambar 24. Contoh penunjukkan simbol dan huruf dengan beberapa variasi …………….. 27
Gambar 25. Bagian dongkrak ulir yang dilengkapi tanda kekasaran ………………………. 27
Gambar 26. Geometri pahat bubut …...…………………………………………………….. 27
Gambar 27. Geometri sudut pahat bubut …….…………………………………………….. 28
Gambar 28. Pahat kanan dan pahat kiri ……………………….……………………………. 28
Gambar 29. Penggunaan sensor jangka sorong …………………………………………….. 29
Gambar 30. Bentuk penunjukkan nonius, jam ukur, dan digital …………………………… 29
Gambar 31. Bentuk micrometer luar dan micrometer dalam ………………………………. 34
Gambar 32. Perencanaan proses bubut …………………………………………………….. 35
Gambar 33. Mesin bubut …………………………………………………………………… 35
Gambar 34. Sumbu utama (main spindle) …………………………………………………. 36
Gambar 35. Meja mesin ……………………………………………………………………. 36
Gambar 36. Eretan (carriage) ………………………………………………………………. 36
Gambar 37. Kepala lepas …………………………………………………………………... 37
Gambar 38. Penjepit pahat …………………………………………………………………. 37
Gambar 39. Tuas pengatur kecepatan sumbu utama dan plat penunjuk kecepatan …………. 38
Gambar 40. Transporter dan sumbu pembawa ……………………………………………... 38
Gambar 41. Cekam rahang tiga, empat, dan enam sepusat …….…………………………… 38
Gambar 42. Beberapa contoh cekam rahang empat tidak sepusat (independent chuck) …… 39
Cekam dengan rahang dapat dibalik posisi rahangnya …………………………
Gambar 43. Cekam dengan rahang bentuk khusus ………………………………………… 39
Gambar 44. 39
Gambar 45. Dudukan spindel mesin bubut bentuk ulir dan tirus …………………………… 40
Gambar 46. Contoh cekam sepusat dan tidak sepusat terpasang pada spindel mesin ……… 40
Beberapa contoh cekam kolet dengan batang penarik …………………………
Beberapa contoh bentuk kolet ……………………………………..…………..
viii
Gambar 47. Pemasangan kolet pada spindel mesin bubut ………………………………….. 40
Gambar 48. Pemasangan benda kerja pada kolet …………………………………………… 41
Gambar 49. Plat pembawa permukaan bertangkai dan plat pembawa permukaan rata ……. 41
Gambar 50. Contoh penggunaan plat pembawa bertangkai dan permukaan rata ………….. 41
Gambar 51. Contoh pengikatan benda kerja pada plat pembawa ………………………….. 42
Gambar 52. Contoh beberapa macam pembawa berekor lurus …………………………….. 42
Gambar 53. Contoh beberapa macam pembawa berekor bengkok ………………………… 42
Gambar 54. Penggunaan pembawa berekor lurus ………………………………………….. 43
Gambar 55. Penggunaan pembawa berekor bengkok ….…………………………………… 43
Gambar 56. Beberapa macam bentuk penyangga/penahan tetap …………………………… 44
Gambar 57. Contoh penggunaan penyangga tetap …………………………………………. 44
Gambar 58. Beberapa macam bentuk penyangga jalan ……………………………………. 44
Gambar 59. Contoh penggunaan penyangga jalan …………………………………………. 45
Gambar 60. Contoh beberapa jenis senter tetap ……………………………………………. 45
Gambar 61. Contoh beberapa jenis senter putar (rotary center) ……………………………. 45
Gambar 62. Pemasangan senter tetap dan senter putar pada kepala lepas ………………….. 46
Gambar 63. Contoh penggunaan senter putar pada mesin bubut …………………………… 46
Gambar 64. Cekam bor dengan pengunci ……………………..……………………………. 46
Gambar 65. Cekam bor tanpa pengunci (keyless chuck drill) …………………………….. 47
Gambar 66. Pemasangan cekam bor pada kepala lepas ……………………………………. 47
Gambar 67. Contoh pengeboran pada mesin bubut ………………………………………… 47
Gambar 68. Gerakan pahat tegak lurus terhadap benda kerja ………………………………. 48
Gambar 69. Gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja …………………………… 49
Gambar 70. Bagian-bagian ulir …………………………………………………………….. 51
Gambar 71. Ulir sekrup standard british withworth ………………………………………... 51
Gambar 72. Ulir sekrup british association ………………………………………………… 51
Gambar 73. Tuas pengatur roda gigi sesuai kisar ulir ………………………………………. 54
Gambar 74. Roda-roda gigi pengganti untuk membubut ulir ………………………………. 55
Gambar 75. Ulir segiempat ………………………………………………………………… 55
Gambar 76. Ulir trapesium …………………………………………………………………. 55
Gambar 77. Ulir trapesium siku-siku (buttress threads) ……………………………………. 56
Gambar 78. Ulir radius (knuckle threads) ………………………………………………….. 56
Gambar 79. Ulir ISO metrik pada baut …………………………………………………….. 56
Gambar 80. Ulir trapesium pada mesin bubut ……………………………………………… 57
Gambar 81. Ulir radius untuk gelas atau botol minum …………………………………….. 57
Gambar 82. Ulir withworth pada sambungan pipa …………………………………………. 58
Gambar 83. Ulir radius pada lampu ………………………………………………………… 58
Gambar 84. Ulir segiempat pada ulir penggerak …………………………………………… 58
Gambar 85. Pembubutan tirus dengan menggeser kepala lepas ……………………………. 59
Gambar 86. Pembubutan tirus dengan menggeser eretan atas ……………………………… 60
Gambar 87. Pembubutan tirus dengan perkakas pembentuk ……………………………….. 61
Gambar 88. Dimensi tirus morse …………………………………………………………… 62
Gambar 89. Panjang permukaan benda kerja ………………………………………………. 64
Gambar 90. Gerak makan (f) dan kedalaman pemotongan (h) …………………………….. 65
Gambar 91. Proses-proses pembubutan ……………………………………………………. 65
Gambar 92. Geometri pahat bubut …………………………………………………………. 67
Gambar 93. Geometri pahat bubut …………………………………………………………. 67
ix
Gambar 94. Pahat kanan dan pahat kiri …………………………………………………….. 68
Gambar 95. Pasangan poros dan lubang, ukuran dasar, daerah toleransi …………………… 70
Gambar 96. Sistem suaian berbasis poros dan suaian berbasis lubang ……………………... 71
Gambar 97. Cara penulisan harga toleransi ukuran ………………………………………… 72
Gambar 98. Jangka sorong manual ………………………………………………………… 83
Gambar 99. Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 …………………………………………. 84
Gambar 100. Penunjukkan skala ukur ……………………………………………………….. 84
Gambar 101. Penunjukkan skala ukur ……………………………………………………….. 85
Gambar 102. Bagian utama jangka sorong digital …………………………………………… 85
Gambar 103. Mengukur dimensi luar ………………………………………………………... 85
Gambar 104. Mengukur dimensi dalam ……………………………………………………... 86
Gambar 105. Mengukur kedalaman …………………………………………………………. 86
Gambar 106. Micrometer luar (outside micrometer) ………………………………………… 87
Gambar 107. Bagian-bagian micrometer luar ……………………………………………….. 87
Gambar 108. Skala ukur micrometer ………………………………………………………… 88
Gambar 109. Bagian-bagian skala ukur micrometer ………………………………………… 88
x
PETA KEDUDUKAN E-MODULE
Keterangan: : Melaksanakan penangan material secara manual
: Menjelaskan dasar kekuatan bahan dan komponen mesin
014.DKK.01 : Menjelaskan proses dasar perlakuan logam
014.DKK.02 : Menjelaskan proses dasar teknik mesin
014.DKK.03 : Menerapkan K3
014.DKK.04 : Menggunakan peralatan pembanding dan/atau alat ukur dasar
014.DKK.05 : Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi
014.KK.01 : Menggunakan perkakas tangan
014.KK.02 : Mengintreprestasikan sketsa
014.KK.03 : Membaca gambar teknik
014.KK.04 : Menggunakan mesin untuk operasi dasar
014.KK.05 : Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut
014.KK.06 : Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda
014.KK.07 : Menggunakan mesin bubut kompleks
014.KK.08 : Menggunakan mesin frais kompleks
014.KK.09 : Menggerinda pahat dengan alat potong
014.KK.10 : Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar)
014.KK.11 : Pemograman mesin NC/CNC dasar
014.KK.12 : Menggambar dengan program autocad
014.KK.13 : Menggambar dengan menggunakan program inventor
014.KK.14 : Melaksanakan penanganan material secara manual
014.KK.15 : Menggunakan peralatan pembanding dan/atau alat ukur dasar
014.KK.16 : Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi
014.MLK.02
014.MLK.03
xi
Kepala Lepas PERISTILAHAN/GLOSARY
Digital : Bagian penahanan benda kerja yang dapat digeser sepanjang meja
Parameter mesin.
Mesin Bubut : Berhubungan dengan angka-angka untuk system perhitungan tertentu.
: Suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur terhadap nilai
Ulir
Kartel atau kondisi yang lainnya.
: Salah satu mesin perkakas yang dipergunakan untuk membentuk benda-
Proyeksi
benda silindris yang dikerjakan dengan menggunakan pahat di mesin
Isometri bubut.
: Suatu profil atau alur yang melilit pada tabung atau lubang yang bulat
Champer : Adalah suatu alat yang dipergunakan untuk membuat alur-alur kecil
Spindel pada benda kerja.
Eretan : Wujud suatu benda dalam bentuk gambar diperlukan suatu cara yang
Pahat disebut.
Jangka Sorong : Panjang garis pada sumbu-sumbunya menggambarkan panjang
sebenarnya.
Micrometer : Perintah untuk membuat sudut.
: Bagian untuk mengatur putaran (rpm).
HSS : Bagian yang menggerakan pahat dan kedudukan.
: Bahan yang digunakan untuk menyayat atau memotong benda kerja.
: Alat ukur presisi yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi benda
bagian dalam dan luar.
: Alat ukur linier langsung yang presisi dengan ketelitian yang akurat dan
berfungsi untuk mengukur ketebalan, lubang, kedalaman, atau mengukur
celah dari suatu lubang benda kerja.
: High Speed Steel. Mempunyai tingkat kekerasan lebih tinggi
dibandingkan dengan tool steel.
xii
BAB I
PENDAHULUAN
A. DESKRIPSI E-MODULE
Ruang lingkup materi praktik mesin bubut yang akan dibahas dalam e-module pembelajaran
ini diantaranya, adalah:
1. Kegiatan belajar 1, menguraikan tentang “Memperhatikan Aspek Keselamatan Kerja”.
2. Kegiatan belajar 2, menguraikan tentang “Menentukan Persyaratan Kerja”.
3. Kegiatan belajar 3, menguraikan tentang “Mempersiapkan Pekerjaan”.
4. Kegiatan belajar 4, menguraikan tentang “Mengoperasikan Mesin Bubut”, terdiri atas
membubut rata bertingkat, membubut ulir, membubut dalam, dan mengkartel.
5. Kegiatan belajar 5, menguraikan tentang “Memeriksa Kesesuaian Komponen dengan
Spesifikasi”.
B. PRASYARAT MEMPELAJARI E-MODULE
Sebagaimana dalam menggunakan system moduler, adanya hubungan keterkaitan antara satu
standar kompetensi dan standar kompetensi yang lain merupakan ciri pembelajaran yang
berkesinambungan. Standar kompetensi menggunakan mesin bubut, kompetensi dasar tersebut
membahas tentang:
1. Memperhatikan aspek keselamatan kerja,
2. Menentukan persyaratan kerja,
3. Mempersiapkan pekerjaan,
4. Mengoperasikan mesin bubut, dan
5. Memeriksa kesesuaian komponen dengan spesifikasi.
C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Sebelum mempelajari modul ini perhatikan dan ikutilah petunjuk-petunjuk serta cara-cara
mempelajarinya, baik oleh peserta didik maupun oleh guru atau fasilitator agar pembelajaran dapat
berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan e-module ini.
1. Penjelasan bagi peserta didik penggunaan e-module praktik mesin bubut
1
2. Peran guru
a. Membantu peserta didik dalam merencanakan proses pembelajaran.
b. Membimbing peserta didik dalam melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan ke dalam
tahapan belajar.
c. Membantu peserta didik memahami konsep-konsep dan praktik baru menjawab pertanyaan
mengenai proses pembelajaran.
d. Membantu peserta didik untuk menentukan dan mengakses sumber tahapan lain yang
diperlukan untuk belajar.
e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok bila diperlukan.
f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika
diperlukan.
g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya.
h. Melakukan penilaian.
i. Menjelaskan kepada peserta didik tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari suatu
kompetensi yang perlu untuk dibenahi serta dirundingkan pencapaian kemajuan peserta
didik.
j. Mencatat pencapaian kemajuan peserta didik.
k. Mengadakan remidi bagi peserta didik yang belum kompeten.
D. TUJUAN AKHIR
Tujuan akhir dari mempelajari e-module praktik mesin bubut ini adalah pencapaian peserta
didik dalam menggunakan mesin bubut sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1. Kinerja yang diharapkan
Kinerja yang diharapkan setelah mempelajari standar kompetensi ini adalah
terbentuknya kompetensi peserta didik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam
menggunakan mesin bubut dengan baik dan benar. Diantaranya adalah peserta didik mampu
membubut lurus, membubut tirus, membubut ulir segitiga, dan membubut dalam.
2. Kriteria keberhasilan
Kriteria keberhasilan dalam penguasaan standar kompetensi ini diukur dari segi kuantitas
dan dari segi kuantitas, yaitu hasil bubutan yang dihasilkan sesuai dengan dimensi yang
dipersyaratkan.
3. Variabel dan kriteria keberhasilan
Peserta didik dinyatakan kompeten apabila telah memperoleh batas minimal KKM, misalnya
7,50. Apabila belum mencapai batas minimal tersebut maka peserta didik harus mengulang
kembali. Kriteria dan variabel keberhasilan adalah sebagai berikut:
2
9,00 – 10,00 = A (Kompeten Istimewa)
8,00 – 8,99 = B (Kompeten Amat Baik)
7,50 – 7,99 = C (Kompeten Baik)
0,00 – 7,49 = D (Belum Kompeten)
E. KOMPETENSI
Modul ini dibuat berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD).
Kompetensi tersebut memiliki sub kompetensi menggunakan bermacam-macam. Berikut ini
penjelasan SKKD dan sub konpetensi pada mata diklat praktik pemesinan.
Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Teori Pemesinan
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
Melakukan pekerjaan dengan mesin 1. Memperhatikan aspek keselamatan kerja.
bubut 2. Menentukan persyaratan kerja.
3. Mempersiapkan pekerjaan kerja.
4. Mengoperasikan mesin bubut.
5. Periksa kesesuaian komponen dengan spesifikasi.
Tabel 2. Penjabaran Standar Kompetensi
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI
PEMBELAJARAN
1. Memperhatikan aspek Prosedur keselamatan kerja 1. Pemakaian kacamata,
keselamatan kerja. dan penggunaan baju baju pelindung, dan akat.
pelindung dan kacamata 2. Identifikasi alat dan
pengaman yang dipakai dapat prosedur keselamatan
diamati. kerja.
2. Menentukan persyaratan Gambar teknik, urutan Memahami gambar kerja dan
kerja. operasi ditentukan dan tanda-tanda pengerjaan.
memilih perkakas untuk
menghasilkan sesuai
spesifikasi dapat dipahami.
3. Mempersiapkan Pekerjaan disiapkan dengan 1. Menyiapkan peralatan.
pekerjaan. menggunakan alat pendukung 2. Menyetel peralatan.
yang diperlukan pada 3. Menggunakan alat sesuai
pekerjaan tersebut. prosedur.
3
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI
4. Mengoperasikan mesin PEMBELAJARAN
1. Menentukan kecepatan 1. Memahami kecepatan
bubut. putar dan kecepatan putar mesin.
potong dihitung secara 2. Penyetelan kecepatan
5. Periksa kesesuaian matematis dan sesuai putar, potong, dan
komponen dengan dengan bahan baku yang kecepatan pemakanan
spesifikasi. dipergunakan. pada mesin bubut.
3. Memahami,
2. Menggunakan semua alat mengidentifikasi
bantu yang ada pada peralatan cekam dan alat
mesin bubut, seperti bantu pembubutan.
cekam rahang tiga, 4. Penggunaan alat cekam
cekam rahang empat, dan alat bantu
senter plat pembawa, pembubutan yang sesuai
penyangga, eretan prosedur.
lintang, dan kepala lepas. 5. Memahami cara
mengebor senter.
3. Proses mempebesar 6. Memperbesar lubang,
lubang, meremer, meremer, membubut ulir,
membuat ulir tunggal, dan memotong sesuai
memotong dilakukan prosedur.
proses spesifikasi. 7. Praktik mengebor senter,
mengebor lubang,
Komponen diperiksa untuk memperbesar lubang,
kesesuaian dengan spesifikasi meremer, dan membubut
menggunakan teknik alat dan ulir tunggal, dan
peralatan yang standar. memotong.
1. Memeriksa komponen
dan dimensi benda kerja
secara visual.
2. Menggunakan alat ukur
untuk memeriksa
komponen/benda kerja.
4
BAB II
PEMBELAJARAN
Kegiatan Belajar 1: Memperhatikan Aspek Keselamatan Kerja.
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
Setelah melaksanakan kegiatan belajar 1, diharapkan peserta didik mampu:
a. Mengidentifikasi keselamatan kerja praktik mesin bubut.
b. Memahami pentingnya keselamatan kerja praktik mesin bubut.
2. Uraian Materi
Kesehatan dan keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat,
alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-
cara melakukan pekerjaan.
a. Keselamatan kerja yang harus dipenuhi saat melakukan praktik mesin bubut
1) Pakailah alat pelindung diri kerja sesuai dnegan syarat keselamatan kerja di bengkel bubut.
2) Alat pelindung pada mesin terpasang dan berfungsi.
3) Ikuti petunjuk yang sudah dijelaskan oleh instruktur atau guru.
4) Menguasai mesin dan peralatannya dengan baik dan benar.
5) Menguasai teknik pengerjaan pembubutan sesuai standar.
6) Menguasai tindakan pencegahan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
7) Pinjam dan kembalikan peralatan sesuai daftar.
b. Aspek yang harus diperhatikan untuk melakukan praktik mesin bubut
1) Memasang pahat setinggi senter dan panjang pahat sependek mungkin.
Gambar 1. Pahat setinggi senter
(sumber: M. Reza Furqoni, 6 September 2022 pada teknikkece.com)
Pemasangan pahat setinggi senter untuk menghindari dari terangkatnya bemda kerja
maupun kerusakan pada pahat dan adapun cara memasang pahat bubut yang baik dan benar
adalah sebagai berikut:
5
a) Letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada toolpost.
b) Atur tinggi pahat sehingga mendekati titik senter untuk memudahkan penyetelan.
Contohnya menggunakan ganjal.
c) Putar tiga baut toolpost yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga
menyentuh/mendekati pahat.
d) Kencangkan sedikit demi sedikit 3 baut tersebut secara bergantian.
e) Pastikan mata sayat pada pahat dalam posisi setinggi senter.
Berikut terlampir untuk link video untuk melihat cara memasang pahat pada mesin
bubut dengan baik dan benar https://www.youtube.com/watch?v=YPithh8kCJY.
2) Menggunakan kacamata safety.
Gambar 2. Kacamata Safety
(sumber: M. Jafar Shiddiq, 29 Juni 2019 pada siddix.blogspot.com)
Tujuan menggunakan kacamata akan terhindar dari segala potensi bahaya sebagai
berikut:
a) Bagian wajah dan mata operator mesin bubut akan terhindar dari potensi bahaya
percikan serbuk logam dari benda kerja yang dihasilkan dari proses pembubutan.
b) Muka dan mata operator mesin bubut terhindar dari potensi terkena pecahan atau
patahan mata pahat mesin bubut pada proses pembubutan.
c) Muka dan mata operator mesin bubut akan terhindar dari potensi bahaya terkena
benturan benda kerja pada saat operator melakukan setting benda kerja pada chuck
mesin bubut.
d) Menghindarkan potensi bahaya muka dan mata operator mesin bubut dari potensi
bahaya tersemprot air cooling mesin bubut pada saat mengoperasikan mesin bubut.
e) Menghindarkan muka dan mata operator mesin bubut dari potensi bahaya terkena
percikan air cooling yang terbawa oleh putaran mesin bubut.
6
3) Menggunakan sarung tangan kulit.
Gambar 3. Sarung tangan kulit
(sumber: Samidi, 13 Maret 2020 pada samiinstansi.com)
Hal ini dimaksudkan dengan alas an sebagai berikut:
a) Sarung tangan berbahan kulit bersifat tidak mudah menempel pada permukaan benda
kerja sehingga untuk mengantisipasi agar tangan operator tidak tergulung oleh putaran
mesin bubut pada saat handling benda kerja.
b) Sarung tangan berbahan kulit tidak mudah berserabut sehingga hal ini bermaksud untuk
menghindari potensi menempelnya kotoran pada benda kerja dari serabut sarung
tangan.
c) Sarung tangan berbahan kulit tahan terhadap panas dari percikan benda kerja dampak
proses pembubutan sehingga kondisi tangan operator terlindung dari percikan benda
logam panas.
d) Sarung tangan berbahan kulit terhadap panas benda logam sehingga sarung tangan
berbahan kulit tidak mudah berlubang karena percikan logam dari benda kerja.
4) Menggunakan sepatu safety.
Gambar 4. Sepatu safety
(sumber: Samidi, 13 Maret 2020 pada samiinstansi.com)
Sepatu safety digunakan oleh operator mesin bubut pada saat mengoperasikan mesin
bubut karena untuk melindungi anggota tubuh bagian kaki dari potensi bahaya seperti
berikut:
a) Potensi bahaya kaki tertimpa benda kerja pada saat melakukan setting benda kerja di
chuck mesin bubut.
7
b) Potensi bahaya kaki terkena percikan logam panas dari benda kerja karena proses
pembubutan.
c) Potensi bahaya kaki terjepit benda kerja pada saat handling benda kerja yang berat atau
besar.
d) Potensi bahaya kaki menginjak benda kerja yang tajam di area mesin bubut.
e) Potensi bahaya kaki kejatuhan benda kerja yang berat dan besar pada saat handling
benda kerja dengan menggunakan hoist.
5) Menggunakan wearpack.
Gambar 5. Wearpack
(sumber: M. Reza Furqoni, 7 September 2022 pada teknikkece.com)
Tujuannya untuk melindungi anggota tubuh bagian dada, perut, dan paha operator
dari percikan serbuk logam pada saat proses pembubutan. Wearpack digunakan untuk
menutupi bagian-bagian tubuh tersebut agar percikan serbuk logam tidak melukai bagian
tubuh tersebut.
6) Kondisi mesin yang baik dan aman.
Gambar 6. Kondisi mesin
(sumber: Samidi, 29 Mei 2019 pada samiinstansi.com)
8
3. Rangkuman 1
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja,
bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara
melakukan pekerjaan. Aspek yang diperhatikan untuk melakukan praktik mesin bubut:
a. Memasang pahat setinggi senter dan panjang pahat sependek mungkin.
b. Menggunakan kacamata safety.
c. Menggunakan sarung tangan kulit.
d. Menggunakan sepatu safety.
e. Menggunakan wearpack.
f. Kondisi mesin yang baik dan aman.
4. Tugas 1
Amati bahaya seorang praktikum dari bahaya percikan tatal saat melakukan praktik di mesin
bubut tanpa menggunakan kacamata pelindung.
5. Tes Formatif
a. Mengapa praktikum wajib memakai alat pelindung diri yang lengkap?
b. Apa saja yang harus dipenuhi untuk keselamatan kerja pada praktik mesin bubut?
9
Lembar Jawaban 1
10
Petunjuk
Cocokan kunci jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif, hitunglah hasil jawaban anda
yang benar dan pergunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui kompetensi dasar “Memperhatikan
Aspek Keselamatan Kerja”. ℎ 100%
ℎ
Kriteria ketercapaian:
90% - 100% = A (Kompeten Istimewa)
80% - 89% = B (Kompeten Amat Baik)
75% - 79% = C (Kompeten Baik)
0% - 74% = D (Belum Kompeten)
Jika tingkat ketercapaian minimal 75%, maka berhak mengikuti kompetensi dasar selanjutnya.
Namun, apabila ketercapaian masih di bawah minimal maka harus mengulangi kembali kompetensi
dasar ini.
11
Kegiatan Belajar 2: Memahami Gambar Kerja dan Tanda-tanda Pengerjaan.
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik mampu memahami gambar kerja untuk melakukan proses praktikum dimensi bubut.
2. Uraian Materi
Gambar teknik adalah alat untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik, maka gambar
teknik sering disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa bagi kalangan ahli-ahli teknik. Sebagai
suatu bahasa, gambar teknik harus dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan
obyektif. Gambar teknik sebagai suatu bahasa teknik mempunyai tiga fungsi penting, yaitu untuk
menyampaikan informasi, sebagai bahan dokumentasi,dan menuangkan gagasan untuk
pengembangan.
a. Macam-macam Proyeksi
Wujud suatu benda dalam bentuk gambar diperlukan suatu cara yang disebut proyeksi,
gambar proyeksi yaitu gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukis menurut garis-
garis pandangan pengamat pada suatu bidang gambar. Cara menggambar proyeksi dapat
dibedakan atas proyeksi piktorial dan proyeksi orthogonal. Proyeksi piktorial terdiri dari
proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Proyeksi aksonometri terdiri
dari proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi trimetri. Sementara itu, proyeksi
orthogonal terdiri dari proyeksi kwadran I (Proyeksi Eropa) dan proyeksi kwadran III (Proyeksi
Amerika).
1) Proyeksi Piktorial
Proyeksi piktorial adalah cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk
dan ukuran sebenarnya secara tiga dimensi, dengan pandangan tunggal. Gambar piktorial
disebut juga gambar ilustrasi, tetapi tidak semua gambar ilustrasi termasuk gambar
piktorial. Fungsi proyeksi piktorial adalah untuk menggambar benda tiga dimensi pada
sebuah bidang dua dimensi. Hal ini diperlukan agar gambar dapat dengan mudah dibaca
dan diintepretasikan oleh pelaksana sehingga benda yang dibuat sesuai dengan rencana.
Proyeksi piktorial terdapat beberapa jenis tergantung darimana memproyeksikan bendanya.
Berikut merupakan jenis proyeksi piktorial:
Gambar 7. Jenis Proyeksi Piktorial
(sumber: sekolahkami.com)
12
a) Proyeksi Isometri, merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang
menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu x dan y sebesar 30
derajat. Ciri-ciri proyeksi isometri sebagai berikut:
(1) Sudut yang dibentuk dari sumbu x dan sumbu y berdasarkan dengan garis lurus
sebesar 30 derajat.
(2) Sudut yang dibentuk antara sumbu x dan sumbu y sebesar 120 derajat.
(3) Panjang sumbu masing-masing baik x, y, dan z memiliki panjang atau skala 1:1
dengan benda yang digambar.
Untuk cara membuat gambar proyeksi isometri perhatikan gambar berikut ini
dan untuk melihat cara membuat gambar tersebut bisa dilihat pada link video berikut
ini https://www.youtube.com/watch?v=ozfyr5tw3wc.
Gambar 8. Proyeksi Isometri
(sumber: sekolahkami.com)
b) Proyeksi Dimetri, merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan
benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu x dan y sebesar 7 dan 40 derajat. Ciri-
ciri proyeksi dimetri sebagai berikut:
(1) Sudut dibentuk sumbu x dan sumbu y berdasarkan garis sumbu sebesar 7 dan 40
derajat.
(2) Sudut yang dibentuk antara sumbu x dan sumbu y sebesar 133 derajat.
(3) Panjang sumbu masing-masing baik x mempunyai skala 1:1, sumbu y 1:2, dan
sumbu z 1:1.
Untuk cara membuat gambar proyeksi dimetri perhatikan gambar berikut ini dan
untuk melihat cara membuat gambar tersebut bisa dilihat pada link video berikut ini
https://www.youtube.com/watch?v=CkRzC6tiBBc.
Gambar 9. Proyeksi Dimetri
(sumber: sekolahkami.com)
13
c) Proyeksi Miring, merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan
benda nyata atau benda tiga dimensi dengan proyeksi pada garis sumbu x dan y sebesar
0 dan 45 derajat. Ciri-ciri proyeksi miring atau proyeksi oblique sebagai berikut:
(1) Sudut yang dibentuk sumbu x dan sumbu y berdasarkan garis sumbu sebesar 0 dan
45 derajat.
(2) Sudut yang dibentuk antara sumbu x dan sumbu y sebesar 135 derajat.
(3) Panjang sumbu masing-masing baik sumbu x mempunyai skala 1:1, sumbu y 1:2,
dan sumbu z 1:1. Perbandingan dengan ukuran benda yang asli.
Untuk cara membuat gambar proyeksi miring atau oblique perhatikan gambar
berikut ini dan untuk melihat cara membuat gambar tersebut bisa dilihat pada link video
berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=oZ3Rz3of2PU.
Gambar 10. Proyeksi Miring
(sumber: sekolahkami.com)
d) Proyeksi Perspektif, merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang
menggambarkan benda nyata atau benda tiga dimensi dengan menggunakan garis-garis
yang dipusatkan pada suatu titik sehingga didapatkan visual yang sangat baik. Namun
untuk gambar teknik, proyeksi perspektif jarang digunakan. Proyeksi perspektif terdiri
dari beberapa jenis, berikut merupakan jenis proyeksi perspektif:
(1) Proyeksi perspektif satu titik hilang.
(2) Proyeksi perspektif dua titik hilang.
(3) Proyeksi perspektif tiga titik hilang.
Untuk cara membuat gambar proyeksi perspektif perhatikan gambar berikut ini
dan untuk melihat cara membuat gambar tersebut bisa dilihat pada link video berikut
ini https://www.youtube.com/watch?v=o8pul_nwteg.
Gambar 11. Proyeksi Perspektif
(sumber: sekolahkami.com)
14
2) Proyeksi Orthogonal
Proyeksi orthogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai
sudut tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Fungsi proyeksi orthogonal adalah gambar
proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya
atau garis-garis yang memproyeksikan benda-benda terhadap bidang proyeksi. Hal ini
sebenarnya sama seperti proyeksi piktorial, proyeksi orthogonal memiliki fungsi untuk
memperjelas informasi gambar sehingga gambar benar-benar seperti benda nyata. Proyeksi
orthogonal tidak menggambarkan benda tiga dimensi secara nyata apabila hanya satu
proyeksi saja. Oleh karena itu untuk bisa menggambarkan benda secara utuh maka
diperlukan beberapa proyeksi dan penambahan bidang proyeksi apabila diperlukan.
Proyeksi orthogonal terdapat beberapa jenis tergantung penggolongannya. Berikut
merupakan jenis proyeksi orthogonal:
a) Proyeksi orthogonal berdasarkan benda yang diproyeksikan
Berdasarkan benda yang diproyeksikan, proyeksi orthogonal dibagi menjadi
beberapa jenis. Berikut merupakan proyeksi orthogonal berdasarkan benda yang akan
diproyeksikan.
(1) Proyeksi orthogonal sebuah titik
Gambar 12. Proyeksi orthogonal sebuah titik
(sumber: sekolahkami.com)
(2) Proyeksi orthogonal sebuah garis
Gambar 13. Proyeksi orthogonal sebuah garis
(sumber: sekolahkami.com)
15
(3) Proyeksi orthogonal sebuah bidang
Gambar 14. Proyeksi orthogonal sebuah bidang
(sumber: sekolahkami.com)
(4) Proyeksi orthogonal sebuah bangun ruang
Gambar 15. Proyeksi orthogonal sebuah bangun ruang
(sumber: sekolahkami.com)
b) Proyeksi orthogonal berdasarkan pandangan atau proyektornya
Berdasarkan proyektornya atau pandangannya, proyeksi orthogonal terbagi
menjadi beberapa jenis. Berikut merupakan proyeksi orthogonal berdasarkan
proyektornya atau pandangannya:
(1) Proyeksi Eropa atau Proyeksi Kwadran I
Proyeksi eropa merupakan salah satu jenis proyeksi orthogonal, atau yang
lebih dikenal dengan proyeksi kwadran I. Pada proyeksi eropa, letak proyeksi
terbalik dengan arah atau posisi pandangannya. Untuk mempemudah ingatan
tentang proyeksi eropa, kuncinya adalah bahwa objek atau benda terletak antara
orang yang melihat dengan bidang proyeksi. Dalam proses memproyeksikan suatu
benda, benda seolah-olah didorong menuju bidang proyeksi. Suatu balok yang
dipotong tidak beraturan terletak diantara pengamat dan bidang proyeksi. Dalam
proyeksi eropa maka balok mempunyai bidang segiempat sama sisi. Hal ini
didapatkan dengan cara menarik garis-garis ke bidang proyeksi.
Untuk mendapatkan pandangan yang benar-benar mewakili benda aslinya
maka dapat menggunakan tiga posisi proyeksi sekaligus yaitu bidang depan, atas,
dan samping. Namun pada proyeksi eropa secara lebih lengkap yaitu pandangan
depan tetap, pandangan kiri merupakan bagian kanan, pandangan kanan
16
merupakan bagian kiri, pandangan atas merupakan bagian bawah. Berikut
merupakan cara membuat proyeksi eropa atau proyeksi kwadran I perhatikan
gambar berikut ini dan berikut link video untuk membuat proyeksi eropa atau
proyeksi kwadran I https://www.youtube.com/watch?v=Tvxg9VIi7aM.
Gambar 16. Proyeksi Eropa atau Proyeksi Kwadran I
(sumber: sekolahkami.com)
(2) Proyeksi Amerika atau Proyeksi Kwadran III
Proyeksi amerika atau yang lebih dikenal dengan proyeksi kwadran III
merupakan salah satu jenis proyeksi orthogonal. Pada proyeksi amerika, letak
proyeksi sesuai dengan arah atau posisi pandangannya. Pada proyeksi amerika
sendiri penggunaannya lebih rasional serta mudah dipahami, atas dasar inilah
proyeksi amerika lebih banyak digunakan pada negara pantai laut pasifik seperti
Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia.
Untuk lebih mudahnya, proyeksi amerika seperti bayangannya yang
menembus suatu bidang. Oleh karena itu, pada proyeksi amerika tidak terjadi
pembalikan atau penukaran pandangan. Pandangan atas merupakan bagian atas,
pandangan bawah merupakan bagian bawah, pandangan samping kiri merupakan
bagian kiri, serta pandangan samping kanan merupakan bagian kanan. Berikut
merupakan cara membuat proyeksi amerika atau proyeksi kwadran III perhatikan
gambar berikut ini dan berikut link video untuk membuat proyeksi amerika atau
proyeksi kwadran III https://www.youtube.com/watch?v=Lu7BgIuS3Ms.
17
Gambar 17. Proyeksi Amerika atau Proyeksi Kwadran III
(sumber: sekolahkami.com)
(3) Perbedaan Proyeksi Eropa dan Proyeksi Amerika
Pada penggunaan proyeksi orthogonal pada gambar teknik yang paling banyak
digunakan yaitu Proyeksi Amerika. Hal ini terjadi karena proyeksi amerika
memiliki beberapa kelebihan. Berikut merupakan perbedaan proyeksi eropa dan
proyeksi amerika:
(a) Bentuk benda dapat dibayangkan secara langsung dengan melihat posisi depan
sebagai patokan
(b) Gambar mudah dibaca dan tidak terjadi perselisihan.
(c) Memudahkan dalam membaca ukuran-ukuran benda asli.
(d) Memudahkan dalam membuat proyeksi tambahan.
b. Pemotongan Gambar Benda Kerja
Pada gambar teknik sering ditemui beberapa objek tertentu seringkali terdapat rongga
atau bagian yang tertutup sehingga tidak dapat melihat pada bagian tersebut. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut guna menampilkan gambar pada bagian tertutup atau tersembunyi, maka
pada bagian objek yang menutupi dapat dilakukan potong atau juga dapat disebut dengan irisan
jika diperlukan yang berfungsi untuk mengetahui objek tertutup secara lebih jelas. Potongan
semacam ini dilakukan hanya memotong Sebagian dari (ujung) benda tersebut. Disini
dimaksudkan untuk melihat bagian dalam dari salah satu ujung yang diperlukan, bentuk benda
semacam ini tidak boleh dipotong memanjang secara penuh. Berikut gambar potongan
sebagian.
18
Gambar 18. Potongan Sebagian
(sumber: sii-tannarelli.com)
c. Kekasaran Permukaan
Konfigurasi permukaan yang mencakup antara lain kekasaran permukaan dan arah bekas
pengerjaan (tekstur), memegang peranan penting dalam perencanaan suatu elemen mesin, yaitu
yang berhubungan dengan gesekan, keausan, pelumasan, tahanan kelelahan, kerekatan suaian,
dan sebagainya. Konfigurasi permukaan yang diminta perencana harus dinyatakan dalam
gambar, menurut cara-cara sesuai dengan standar.
Kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata-rata profil,
yang selanjutnya disebut nilai kekasaran (Ra). Nilai kekasaran rata-rata aritmetik telah
diklasifikasikan oleh ISO menjadi 12 tingkat kekasaran, dari mulai N1 sampai N12. Untuk
penunjukkan pada gambar mengenai spesifikasi kekasaran ini dapat dituliskan langsung nilai
Ra-nya, atau tingkat kekasarannya.
Tabel 3. Nilai Kekasaran dan Tingkat Kekasaran
Kekasaran Ra (µm) Tingkat Kekasaran Panjang Sampel (mm)
50 N12 8
25 N11
12,5 N10 2,5
6,3 N9
3,2 N8 0,8
1,6 N7
0,8 N6
0,4 N5
0,2 N4 0,25
0,1 N3
0,05 N2
0,025 N1 0,08
Nilai kekasaran permukaan suatu elemen ditentukan menruut fungsinya, sedangkan
untuk mencapainya bergantung pada kemampuan proses pengerjaan manual atau pemesinan di
tempat produksi. Pilihlah nilai kekasaran sekasar mungkin, sehalus yang diperlukan. Makin
halus permukaan yang diminta, semakin mahal biaya pengerjaannya.
19
d. Penunjukkan Nilai Kekasaran dan Arah Bekas Pengerjaan
1) Simbol Dasar Penunjukkan
Simbol dasar (Gambar 19a) terdiri atas dua garis yang membentuk sudut 60º dengan
garis yang tidak sama panjang. Garis sisi kiri minimal 4 mm dan garis sisi kanan dua kali
garis sisi kiri. Ketebalan garis disesuaikan dengan besarnya gambar, biasanya diambil tebal
garis 0,35 mm.
Gambar 19. Simbol kekasaran permukaan
(sumber: Wisnu Suryaputra, suryaputra2009.wordpress.com)
Apabila pengerjaan pada permukaan menggunakan mesin, simbol dasarnya
ditambah garis sehingga membentuk segitiga sama sisi (Gambar 19b). Sementara itu,
simbol menurut Gambar 19c digunakan untuk menujukkan bahwa kekasaran permukaan
dicapai tanpa membuang bahan.
2) Simbol dengan Tambahan Nilai Kekasaran dan Perintah Pengerjaan
Pengertian simbol yang disertai nilai kekasaran ditunjukkan pada Tabel 4, sedangkan
Tabel 5 menjelaskan pengertian simbol yang disertai perintah pengerjaan.
Tabel 4. Simbol dengan Tambahan Kekasaran
Simbol Pengertian
Nilai kekasaran a yang harus dicapai dengan proses apa saja
Nilai kekasaran a yang harus dicapai dengan proses mesin
Nilai kekasaran a yang harus sudah tercapai tanpa membuang bahan atau
pengerjaan lanjutan
Nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu, artinya
permukaan tidak boleh lebih kasar dai a1 dan tidak perlu lebih halus dari a2
20
Tabel 5. Simbol dengan Tambahan Perintah Pengerjaan
Simbol Pengertian
Permukaan halus dikerjakan dengan mesin tertentu, misalnya dengan
mesin frais
Kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan, misalnya harus
diberi kelebihan ukuran 0,3 mm
Arah bekas pengerjaan (tekstur) yang diinginkan, misalnya harus tegak
lurus terhadap bidang proyeksi
Panjang sampel (contoh) yang dianjurkan misalnya 2,5 mm
a : Nilai kekasaran (Ra) atau tingkat kekasaran
(N1 sampai N12)
b : Cara pengerjaan, produksi atau pelapisan
c : Panjang sampel (contoh)
Gambar 20. Letak simbol-simbol d : Arah bekas pengerjaan
(sumber: Wisnu Suryaputra, e : Kelebihan ukuran yang dikehendaki
suryaputra2009.wordpress.com) f : Nilai kekasaran lain, jika diperlukan
3) Simbol Arah Bekas Pengerjaan (Tanda Pengerjaan)
Arah bekas pengerjaan dapat dituliskan dengan simbol seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 6. Maksud dari penunjukkan arah bekas pengerjaan ini adalah untuk memastikan segi
fungsional permukaan yang bersangkutan, misalnya mengurangi gesekan, wujud tekstur
yang menarik, dan sebagainya.
Tabel 6. Simbol Arah Bekas Pengerjaan
Simbol Arah serat yang diinginkan Gambar
Sejajar terhadap bidang proyeksi
Tegak lurus terhadap bidang proyeksi 21
Diagonal (menyilang) terhadap bidang
proyeksi
Simbol Arah serat yang diinginkan Gambar
Saling membelit dari segala arah
Melingkar terhadap titik pusat permukaan
Radial terhadap titik pusat permukaan
Contoh penggunaan pada gambar:
Gambar 21. Contoh penunjukkan simbol dan huruf pada gambar
(sumber: J Santoso - 2013 - repositori.kemdikbud.go.id)
Gambar 22. Contoh penunjukkan simbol dan huruf dengan beberapa variasi
(sumber: J Santoso - 2013 - repositori.kemdikbud.go.id)
22
Gambar 23. Bagian dongkrak ulir yang dilengkapi tanda kekasaran
(Sumber: http://staffnew.uny.ac.id – Materi tanda pengerjaan)
3. Rangkuman 2
a. Gambar teknik adalah alat untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik, maka gambar teknik
sering disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa bagi kalangan ahli-ahli teknik.
b. Gambar teknik sebagai suatu bahasa teknik mempunyai tiga fungsi penting, yaitu untuk
menyampaikan informasi, sebagai bahan dokumentasi,dan menuangkan gagasan untuk
pengembangan.
c. Proyeksi dapat dibedakan atas proyeksi piktorial dan proyeksi orthogonal.
d. Pada penggunaan proyeksi orthogonal pada gambar teknik yang paling banyak digunakan yaitu
Proyeksi Amerika.
e. Pada gambar teknik sering ditemui beberapa objek tertentu seringkali terdapat rongga atau
bagian yang tertutup sehingga tidak dapat melihat pada bagian tersebut. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut guna menampilkan gambar pada bagian tertutup atau tersembunyi, maka
pada bagian objek yang menutupi dapat dilakukan potong atau juga dapat disebut dengan irisan
jika diperlukan yang berfungsi untuk mengetahui objek tertutup secara lebih jelas.
f. Kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata-rata profil, yang
selanjutnya disebut nilai kekasaran (Ra).
4. Tugas 2
Siapkan berbagai bentuk hasil kerja pembubutan yang sudah jadi, amati, dimensi, dan
gambarlah benda itu sesuai dengan gambar kerja.
5. Tes Formatif
a. Apa saja fungsi dari gambar teknik?
b. Sebutkan macam-macam proyeksi dan jelaskan?
c. Pandangan bagian mana yang memberikan informasi paling lengkap?
23
Lembar Jawaban 2
24
Petunjuk
Cocokan kunci jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif, hitunglah hasil jawaban anda
yang benar dan pergunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui kompetensi dasar “Memahami
Gambar Kerja dan Tanda-tanda Pengerjaan”.
ℎ 100%
ℎ
Kriteria ketercapaian:
90% - 100% = A (Kompeten Istimewa)
80% - 89% = B (Kompeten Amat Baik)
75% - 79% = C (Kompeten Baik)
0% - 74% = D (Belum Kompeten)
Jika tingkat ketercapaian minimal 75%, maka berhak mengikuti kompetensi dasar selanjutnya.
Namun, apabila ketercapaian masih di bawah minimal maka harus mengulangi kembali kompetensi
dasar ini.
25
Kegiatan Belajar 3: Mempersiapkan Pekerjaan.
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
Setelah melaksanakan kegiatan belajar 3 diharapkan peserta didik mampu:
a. Menyiapkan peralatan
b. Menyetel peralatan
c. Menggunakan alat sesuai prosedur
2. Uraian Materi
a. Persyaratan Kerja
Kondisi yang disesuaikan dengan mesin, benda kerja, dan operatornya. Beberapa
persyaratan kerja antara lain:
1) Kondisi Mesin
Menurut Tim Fakultas (2004: 7) Teknik Mesin bubut harus siap digunakan artinya
spindel dapat berputar. Putaran spindel atau sumbu utama mesin bubut akan memutarkan
kepala tetap sehingga benda kerja pada kepala tetap memungkinkan untuk dipotong atau
disayat, eretan atas sebagai tempat pahat harus mudah digerakan agar kedalaman
pemotongan dapat diatur. Eretan bawah dengan gerakan translasi sejajar sumbu utama
harus mudah digerakkan agar pemakanan benda kerja dapat dilaksanakan dengan baik.
Pompa pendingin saluran pendingin harus dapat bekerja dengan baik.
2) Benda Kerja
Benda kerja adalah hasil bubutan berbentuk silinder baik silinder luar maupun
silinder dalam. Ukuran panjang benda kerja harus sesuai dengan Panjang meja mesin bubut,
sedangkan diameter benda kerja harus sesuai dengan ketinggian sumbu utama terhadap
permukaan meja mesin bubut.
b. Persiapan Praktik di Mesin Bubut
Kegiatan menyiapkan, penyetelan, pemasangan, dan pemeriksaan.
1) Kegiatan menyiapkan adalah meyiapkan alat bantu bubut seperti (kunci pas, kunci L, palu
plastik, dan kikir).
2) Kegiatan penyetelan adalah penyetelan putaran spindel yang disesuaikan dengan jenis
bahan benda kerja.
3) Kegiatan pemasangan adalah pemasangan kepala tetap maupun collet termasuk face plat
disesuaikan dengan tujuan pembubutan dan bentuk benda kerjanya. Pemasangan pahat
bubut termasuk penyetelan ketinggian mata pahat disesuaikan dengan tujuan
pembubutannya. Pemasangan benda kerja pada kepala tetap dipastikan tidak oleng dan
kencang untuk menghindari resiko kecelakaan kerja.
4) Kegiatan pemeriksaan adalah pemeriksaan ke satu sumbu antara kepala tetap dan kepala
lepas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan diameter yang sama dengan diameter ujung
sampai pangkal.
26
c. Peralatan Proses Membubut
Peralatan proses bubut adalah pemilihan alat kerja bubut yang sesuai dengan kondisi
benda kerja yang akan dibubut. Beberapa peralatan yang harus disediakan untuk bubut komplek
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
1) Kelompok Alat Potong
Kelompok alat potong yaitu pahat bubut, pahat ulir, senter bor, pisau kartel, mata
bor, dan pahat dalam.
a) Geometri Pahat Bubut
Geometri pahat bubut terutama tergantung pada material benda kerja dan pahat.
Terminologi standar ditunjukkan pada Gambar 24. Untuk pahat bubut bermata potong
tunggal, sudut pahat yang paling pokok adalah sudut beram (rake angle), sudut bebas
(clearance angle), dan sudut sisi potong (cutting adge angle). Sudut-sudut pahat HSS
yang diasah dengan menggunakan mesin gerinda pahat (tool grinder machine).
Gambar 24. Geometri pahat bubut
(sumber: Rodian Situmorang, BSc., M.Eng. (2015) Alat Potong Mesin Perkakas)
Gambar 25. Geometri sudut pahat bubut
(sumber: Rodian Situmorang, BSc., M.Eng. (2015) Alat Potong Mesin Perkakas)
Gambar 26. Pahat kanan dan pahat kiri
(sumber: Rodian Situmorang, BSc., M.Eng. (2015) Alat Potong Mesin Perkakas)
27
Pada bubut di atas apabila digunakan untuk proses membubut biasanya dipasang
pada pemegang pahat (tool holder). Pemegang pahat tersebut digunakan untuk
memegang pahat dari HSS dengan ujung pahat diusahakan sependek mungkin agar
tidak terjadi getaran pada waktu digunakan membubut. Berikut link video untuk
membuat pahat potong dan mengasah pahat potong
https://www.youtube.com/watch?v=Yi4VcDMmZvQ.
2) Kelompok Alat Ukur
Kelompok alat ukur yaitu jangka sorong, pahat ulir, dial indikator, micrometer, snap
gauge, dan mal kisar ulir.
a) Jangka Sorong
Jangka sorong adalah alat ukur yang sering digunakan di laboratorium dan
bengkel mesin. Jangka sorong ini berfungsi sebagai alat ukur operator mesin yang bisa
digunakan untuk mengukur Panjang sampai dengan 200 mm, kecermatan 0,05 mm.
Gambar 27 berikut adalah gambar jangka sorong yang dapat mengukur Panjang dengan
rahangnya, kedalamannya dengan ekornya, lebar celah dengan sensor bagian atas.
Jangka sorong tersebut memiliki skala ukur (vernier scale) pembacaan tertentu. Ada
juga jangka sorong yang dilengkapi jam ukur, atau dilengkapi petunjuk ukuran digital.
Pengukuran dengan jangka sorong dilakukan dengan cara menyentuhkan sensor ukur
pada benda kerja yang akan diukur. Berikut jenis jangka sorong dengan skala
penunjukkan pembacaan. Berikut untuk link video cara menggunakan jangka sorong
https://www.youtube.com/watch?v=v2UbClvRKEw dan link video cara menggunakan
jangka sorong digital https://www.youtube.com/watch?v=8Qa-FEnBFvU.
Gambar 27. Penggunaan sensor jangka sorong
(sumber: iptekindonesiaef.blogspot.com)
Gambar 28. Bentuk penunjukkan nonius, jam ukur, dan digital
(sumber: sihatjok.blogspot.com)
28
b) Micrometer
Micrometer digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih presisi, namun
jangkauan ukuran micrometer kecil, yaitu sekitar 25 mm. Berikut untuk link video cara
menggunakan mikrometer https://www.youtube.com/watch?v=sW0uyBEXe6I.
Gambar 29. Bentuk micrometer luar dan micrometer dalam
(sumber: belajardenganbaik.com)
d. Perencanaan dan Perhitungan Mesin Bubut
Elemen dasar proses bubut dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus dan
gambar sebagai berikut.
Gambar 30. Perencanaan proses bubut
Keterangan:
Benda kerja: Mesin Bubut:
do = diameter mula; mm a = kedalaman potong; mm
dm = diameter akhir; mm f = gerak makan; mm/putaran
lt = panjang pemotongan n = putaran poros utama; putaran/menit
Pahat:
X = sudut potong utama
1) Kecepatan potong
d n
1000
v = kecepatan potong
d = diameter rata-rata benda kerja ((do+dm)/2; mm)
n = putaran poros utama; put/menit
= 3,14
29
2) Kecepatan makan
vf = f.n; mm/menit
3) Waktu pemotongan
4) Kecepatan penghasilan beram
Z = A.v; cm3/menit
5) Menghitung waktu proses pembubutan
T = L/f.n
6) Menghitung waktu total pembubutan = Waktu persiapan + setting mesin + proses
pengerjaan
3. Rangkuman 3
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirangkum sebagai berikut:
a. Kegiatan menyiapkan adalah menyiapkan alat bantu bubut seperti (kunci pas, kunci L, palu
plastik, dan kikir).
b. Beberapa peralatan yang harus disediakan untuk bubut komplek dibedakan menjadi dua
kelompok yaitu alat potong dan alat ukur.
c. Elemen dasar proses bubut dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus dan gambar
sebagai berikut:
1) Kecepatan potong
d n
1000
v = kecepatan potong
d = diameter rata-rata benda kerja ((do+dm)/2; mm)
n = putaran poros utama; put/menit
= 3,14
2) Kecepatan makan
vf = f.n; mm/menit
3) Waktu pemotongan
4) Kecepatan penghasilan beram
Z = A.v; cm3/menit
Dimana: A a.f mm2
4. Tugas 3
Catat kebutuhan alat bantu praktik mesin bubut termasuk alat potong yang digunakan.
30
5. Tes Formatif
a. Kondisi apa saja yang termasuk persyaratan kerja bubut?
b. Apa yang dilakukan untuk menghindari dari benda kerja yang tirus?
c. Apa yang harus diperhitungkan dalam perencanaan praktik mesin bubut?
31
Lembar Jawaban 3
32
Petunjuk
Cocokan kunci jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif, hitunglah hasil jawaban anda
yang benar dan pergunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui kompetensi dasar “Mempersiapkan
Pekerjaan”.
ℎ 100%
ℎ
Kriteria ketercapaian:
90% - 100% = A (Kompeten Istimewa)
80% - 89% = B (Kompeten Amat Baik)
75% - 79% = C (Kompeten Baik)
0% - 74% = D (Belum Kompeten)
Jika tingkat ketercapaian minimal 75%, maka berhak mengikuti kompetensi dasar selanjutnya.
Namun, apabila ketercapaian masih di bawah minimal maka harus mengulangi kembali kompetensi
dasar ini.
33
Kegiatan Belajar 4: Mengoperasikan Mesin Bubut.
1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
Setelah melaksanakan kegiatan belajar 4 diharapkan peserta didik mampu:
a. Memahami pengertian mesin bubut dan bagian-bagian utama beserta fungsinya.
b. Menghitung parameter proses pembubutan.
c. Pembubutan benda lurus rata direncanakan dengan tepat.
d. Pembututan tirus direncanakan dengan tepat.
e. Pembubutan benda berlubang (membubut dalam) direncanakan dengan tepat.
f. Pembubutan benda berulir segitiga (luar dan dalam) direncanakan dengan tepat.
2. Uraian Materi
a. Pengertian Mesin Bubut
Mesin bubut (turning machine) adalah suatu jenis mesin perkakas yang proses kerjanya
bergerak memutar benda kerja dan menggunakan potong pahat (tools) sebagai alat untuk
memotong benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang
dipakai untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris, namun dapat juga dipakai
untuk beberapa kepentingan lain. Pada prosesnya benda kerja terlebih dahulu dipasang pada
chuck (pencekam) yang terpasang pada spindel mesin, kemudian spindel dan benda kerja
diputar dengan kecepatan tertentu.
Alat potong (pahat) yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan ditempelkan pada
benda kerja yang berputar sehingga benda kerja berbentuk sesuai dengan ukuran yang
dikehendaki. Umumnya pahat bubut dalam keadaan diam, pada perkembangannya ada jenis
mesin bubut yang berputar alat potongnya, sedangkan benda kerjanya diam.
Pada kelompok mesin bubut juga terdapat bagian-bagian otomatis dalam pergerakannya
bahkan juga ada yang dilengkapi dengan layanan sistem otomatis, baik yang dilayani dengan
sistem hidraulik ataupun elektrik. Ukuran mesinnya pun tidak semata-mata kecil karena tidak
sedikit mesin bubut konvensional yang dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan besar
seperti yang dipergunakan pada industry perkapalan dan membuat atau merawat poros baling-
baling kapal yang diameternya mencapai 1.000 mm atau lebih. Pada Gambar 31 terlihat contoh
dari mesin bubut.
Gambar 31. Mesin Bubut
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 3)
34
b. Bagian-bagian Utama Mesin Bubut
Bagian-bagian utama pada mesin bubut yang pada umumnya sama walaupun merk atau
buatan pabrik yang berbeda, hanya saja terkadang posisi handel/tuas tombol, tabel penunjukkan
pembubutan, dan rangkaian penyusunan roda gigi untuk berbagai jenis pembubutan
letak/posisinya berbeda. Demikian juga cara pengoperasiannya tidak jauh berbeda. Berikut ini
akan diuraikan bagian-bagoan utama mesin bubut konvensional (biasa) yang pada umumnya
dimiliki oleh mesin tersebut.
1) Sumbu utama (main spindle)
Pada Gambar 32. terlihat gambar sumbu utama atau dikenal dengan main spindle.
Sumbu utama merupakan bagian mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan cekam
(chuck) yang didalamnya terdapat susunan roda gigi yang dapat digeser-geser melalui
handel/tuas untuk mengatur putaran mesin sesuai kebutuhan pembubutan.
Gambar 32. Sumbu utama (main spindle)
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 4)
2) Meja mesin (bed)
Meja mesin merupakan tumpuan gaya pemakanan waktu pembubutan, meja mesin
berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas dan eretan. Bentuk alas ini bermacam-
macam, ada yang datar dan ada yang salah satu atau kedua sisinya mempunyai ketinggian
tertentu. Permukaannya halus dan rata, sehingga gerakan kepala lepas dan eretan menjadi
lancar.
Gambar 33. Meja mesin
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 5)
35
3) Eretan (carriage)
Eretan seperti yang terlihat pada Gambar 34. merupakan bagian dari mesin bubut
yang berfungsi sebagai pembawa dudukan pahat potong. Eretan terdiri dari beberapa bagian
seperti engkol dan transporter.
Gambar 34. Eretan (carriage)
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 5)
4) Kepala lepas (tail stock)
Pada Gambar 35. terlihat gambar dari kepala lepas, kepala lepas digunakan sebagai
dudukan senter putaran sebagai pendukung benda kerja pada saat pembubutan, dudukan
bor tangkai tirus, dan cekam bor sebagai menjepit bor.
Gambar 35. Kepala lepas
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 6)
5) Penjepit pahat
Penjepit pahat digunakan untuk menjepit atau memegang pahat potong yang
bentuknya ada beberapa macam diantaranya seperti ditunjukkan pada Gambar 36. Jenis ini
sangat praktis dan dapat menjepit pahat 4 buah sekaligus sehingga dalam suatu pengerjaan
bila memerlukan 4 macam pahat dapat dipasang dan disetel sekaligus.
Gambar 36. Penjepit pahat
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 6)
36
6) Tuas pengatur kecepatan sumbu utama dan plat penunjuk kecepatan
Tuas pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran mesin sesuai
hasil perhitungan atau pembacaan dari tabel putaran. Plat tabel kecepatan sumbu utama
pada Gambar 37. menunjukkan angka-angka besaran kecepatan sumbu utama yang dapat
dipilih sesuai dengan pekerjaan pembubutan.
Gambar 37. Tuas pengatur kecepatan sumbu utama dan plat penunjuk kecepatan
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 7)
7) Transporter dan sumbu pembawa
Transporter atau poros transporter seperti yang terlihat pada Gambar 38 adalah poros
berulir segi empat atau trapesium yang biasanya memiliki kisar 6 mm, digunakan untuk
membawa eretan pada waktu kerja otomatis, misalnya waktu membubut ulir, alur, atau
pekerjaan pembubutan lainnya. Sedangkan sumbu pembawa atau poros pembawa adalah
poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan.
Gambar 38. Transporter dan sumbu pembawa
(sumber: M. Nala Pratama 2019, hal 7)
8) Chuck (cekam)
Cekam adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk
menjepit/mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Jenis alat ini apabila dilihat dari
Gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cekam sepusat (self centering
chuck) dan cekam tidak sepusat (independent chuck). Pengertian cekam sepusat adalah
apabila salah satu rahang digerakkan maka keseluruhan rahang yang terdapat pada cekam
akan bergerak bersama-sama menuju atau menjauhi pusat sumbu. Maka dari itu, cekam
jenis ini sebaiknya hanya digunakan untuk mencekam benda kerja yang benar-benar sudah
37
silindris. Cekam jenis ini rahangnya ada yang berjumlah tiga (3 jaw chuck), empat (4 jaw
chuck) dan enam (6 jaw chuck) seperti yang terlihat pada Gambar 39.
Gambar 39. Cekam rahang tiga, empat, dan enam sepusat
(sumber: M Komaro, J Situmorang, I Rosmawati - 2016 - repositori.kemdikbud.go.id)
Sedangkan pengertian cekam tidak sepusat adalah masing-masing rahang dapat
digerakkan menuju/menjauhi pusat dan rahang lainnya tidak mengikuti, maka jenis cekam
ini hanya digunakan untuk mencekam benda-benda yang tidak silindirs atau tidak beraturan
karena lebih meudah disetel kesentrisnya dan juga dapat digunakan untuk mencekam benda
kerja yang akan dibubut eksentrik atau sumbu senternya tidak sepusat. Jenis cekam ini pada
umumnya memiliki rahang empat dan beberapa contoh cekam rahang empat tidak sepusat
(independent chuck) dapat dilihat pada Gambar 40.
Gambar 40. Beberapa contoh cekam rahang empat tidak sepusat (independent chuck)
(sumber: M Komaro, J Situmorang, I Rosmawati - 2016 - repositori.kemdikbud.go.id)
Untuk jenis cekam yang lain, rahangnya ada yang berjumlah dua buah yang diikatkan
pada rahang satu dengan yang lainnya, tujuannya agar rahang pada bagian luar dapat diubah
posisinya/dibalik sehingga dapat mencekam benda kerja yang memiliki diameter relatif
besar Gambar 41. Caranya yaitu dengan melepas baut pengikatnya, baru kemudian dibalik
posisinya dan dikencangkan kembali. Hati-hati dalam memasang kembali rahang ini,
karena apabila pengarahnya tidak bersih, akan mengakibatkan rahang tidak sepusat dan
kedudukannya kurang kokoh/kuat.
Gambar 41. Cekam dengan rahang dapat dibalik posisi rahangnya
(sumber: M Komaro, J Situmorang, I Rosmawati - 2016 - repositori.kemdikbud.go.id)
38
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
E-MODULE TEKNIK PEMESINAN BUBUT KELAS X
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search