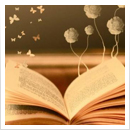PEMBELAJARAN
LINGUISTIK
(MIKROLINGUISTIK
NAMA – NAMA KELOMPOK 9
1. Alfridus Jeharun (18316007)
2. Asri Ainun (18316087)
3. Ignasius Tekeng (18316136)
4. Marcelus P. Habit (18316065)
5. Sirena Asrini Suriani (18316119)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KATOLIK
INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
KATA PENGATAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkatnya,
kami dapat menyelesaikan modul dengan judul “PEMBELAJARAN LINGUSTIK (Mikrolinguistik)”
dengan tepat waktu.
Tujuan penyusunan modul ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester VII Mata kuliah
“Penerbitan Digital”. Selain itu, penyusunan modul ini juga bertujuan untuk menambah wawasan
pembaca tentang Linguistik, terutama Mikrolinguitik.
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Hadrianus Dwianot Momang,
M.PD selaku dosen pengampu mata kuliah Penerbitan Digital, berkat tugas yang diberikan ini, dapat
menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik yang diberikan. Penulis juga mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan proses penyusunan modul
ini.
Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan dan penulisan masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan
dalam modul ini. Penulis juga mengharapkan adanya kritik maupun saran dari pembaca apabila
menemukan kesalahan dalam modul ini.
Ruteng, 7 November 2021
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengatar
Daftar Isi
BAB 1
A. PENDAHULUAN
BAB 2
B. PEMBAHASAN
MIKROLINGUISTIK
A. FONOLOGI
a. Pengertian Fonologi
b. Pengertian Fonetik
c. Alat Ucap Manusia
d. Pengetian Fonemik
e. Analisis dasar Fonem
f. Perubahan bunyi
B. MORFOLOGI
a. Pengertiian Morfologi
b. Istilah morfem
c. Istilah kata
d. Istilah leksem
C. SINTAKSIS
a. Pengertian sintaksis
b. Fungsi kategori dan peran
c. Subyek, predikat, obyek, pelengkap dan keterangan
d. Modus
e. Kala
f. Modalitas
g. Diathesis
D. SEMANTIK
a. Pengertian semantik
b. Aspek – aspek senantik
c. Jenis – jenis makna
d. Jenis – jenis perubahan makna
e. Komponen makna
E. LEKSIKOLOGI
BAB 3
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
BAB 1
PENDAHULUAN
Linguistik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bahasa secara umum maupun khusus.
Penyelidikan dan penyidikan dalam linguistik memiliki tujuan unntuk menguak dan menelanjangi
aspek – aspek kebahasaan yang menjadi objek kajiannya. Sebagai sebuah subdisiplin ilmu yang
mempelajari bahasa yakni mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik merupakan bidang
lingustik yang mempelajari struktur internal bahasa dan tanpa menghubungkannya dengan aspek –
aspek yang terdapat di luar bahasa. Sedangkan makrolinguistik mempelajari penerapan kajian
bahasa terhadap hal – hal yang ada diluar bahasa.
Dalam modul ini menjelaskan tentang mikrolinguistik yang didalamnya terdapat subsistem
yang terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Jenjang dari beberapa subsistem ini
dalam linguistik dikenal dengan nama tataran linguistik atau tataran bahasa. Jika diurutkan dari
tataran yang tertinggi, dalam hal ini yang menyangkut subsistem bahas diatas adalah tataran fonem,
morfem, frase, klausa, dalam bidang kajian fonologi, tataran morfem dan kata masuk dalam tataran
kajian morfologi; tataran frasa, klausa, kalimat, dan wacana merupakan tataran tetinggi, dikaji oleh
bidang sintaksis ( Abdul Chaer.1994:97). Dalam morfologi, kata itu dikaji struktur dan proses
pembentukkannya, sedangkan dalam sintaksis dikaji sebagai unsur pembentuk satuan sintasis yang
lebih besar.
Bahasa dapat dilihat secara deskriptif, historis komparatif, kontrastif, sinkronis, dan
diakronis. Linguistik komparatif membandingkan dua bahasa atau lebih paa periode berbeda.
Linguistik kontrastif membandingkan bahasa – bahasa pada periode tertentu atau sezaman. Dalam
kajian ini dicari persamaan dan perbedaan dalam bidang struktur : fonologi, morfologi, sintaksis
daan semantic.
BAB 2
PEMBAHASAN
MIKROLINGUISTIK
1.1 Pengertian Linguistik
Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja
(Muliastuti, 2014, hlm. 1). Oleh karena itu, terkadang ilmu ini disebut juga dengan linguistik
umum (general linguistics). Meskipun demikian, menurut Chaer (dalam Muliastuti, 2014)
berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan
linguistik khusus. Dapat ditebak bahwa linguistik khusus berarti memfokuskan kajiannya pada
salah satu bahasa saja.
2. Etimologi
Jika ditelusuri, apa itu linguistik sesungguhnya berasal dari kata lingua yang bermakna
“bahasa” dalam bahasa Latin. Selain dari bahasa Latin, beberapa bahasa lain juga merujuk pada
makna yang sama. Misalnya, dalam bahasa Prancis adalah langue atau langage, bahasa
Italia lingua, bahasa Spanyol lengua, dan bahasa Inggris language. Selanjutnya, untuk
memastikan kesahihan pengertian linguistik sebagai ilmu, berikut adalah beberapa pendapat ahli
mengenai pengertian ilmu linguistik.
3. Pendapat Ahli
A.S. Hornby, E.V. Gatenby, H. Wakefield (dalam Dhanawaty, dkk, 2017, hlm. 1)
mengungkapkan bahwa definisi linguistik sebagai kata sifat adalah studi bahasa, sedangkan
sebagai kata benda berarti ilmu dari metode dalam mempelajari dan meneliti bahasa.
Masih berpendapat sama, Kridalaksana (dalam Dhanawaty, dkk, 2017, hlm.1) menyebutkan
bahwa arti linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa.Sehingga dapat
disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari metode mengkaji atau meneliti
bahasa.
Sebagaimana di kutip pada penjelasan sebelumnya mengenai bagian dasar kajian linguistik
berdasarkan hubungan dengan faktor baik internal dan ekternal, yaitu disiplin, Lingustik Mikro
dan Linguistik Makro. Pada materi ini akan dibahas lebih detail dan khusus mengenai linguistik
mikro.
4. Linguistik Mikro
Linguistik Mikro atau disebut juga Mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsen
kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Kajian study ini mengarah pada struktur internal
suatu bahasa tertentu dan atau semua bahasa pada umumnya.
Bagian interdisiplin kajian Linguistik Mikro yang adalah: Fonologi, morfologi, semantik,
sintaksis.
5. Pengertian bidang- bidang linguistik
Pada modul kali ini kali ini kita akan membahas tentang pembidangan-pembidangan yang
ada dalam linguistik. Pimbidangan ini perlu dilakukan mengingat tujuan menggunakan linguistik
berbeda-beda.
Menururut Harimurti Kridalaksana dalam kentjono(1990: 11), pada dasarnya linguistik
mempunyai 2 bidang besar yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah
bidang yang memepelajari bahasa dari dalam(struktur internal). Sedangkan makrolinguistik
adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di
luar bahasa, termasuk di dalamnya bidang interdisipliner dan bidang terapan(Lyons 1975).
Bidang interdisipliner yang dimaksud di sini adalah menggunakan linguistik sebagai pendukung
dari ilmu lain misalnya semiotik, filologi, stilistika dsb. Sedangkan yang dimaksud bidang terapan
ialah bidang-bidang yang menerapkan ilmu linguitik dalam dunia nyata misalnya pengajaran
bahasa, penerjemah, pembinaan bahasa, dll.
Kemudian jika disangkutpautkan dengan tujuannya, linguistik juga dibagi menjadi dua bidang
yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis meneliti linguistik dengan
tujuan untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Linguistik teoritis ini dibagi
lagi menjadi linguistik teoritis umum dan khusus. Umum berarti memahami ciri-ciri berbagai
bahasa yang sifatnya umum atau mayoritas sama. Sedangkan khusus berarti memahami ciri-ciri
berbagai bahasa secara khusus. Di lain sisi, linguistik terapan meneliti bahasa untuk
memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis misalnya pada pengajaran bahasa,
penerjemah, linguitik medis, dsb.
2.1 Fonologi
A. Pengertian Fonologi
Istilah fonologi berasal dari kata phonology, yaitu gabungan kata phone dan logy. Kata phone
berarti „bunyi bahasa‟ , baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan‟. Sedangkan kata logy berarti
„ilmu pengetahuan, metode dan pikiran (Hornby, 1974:627). Dalam ilmu bahasa yang
dimaksudkan fonologi adalah salah satu kajian ilmu bahasa (linguistik) yang mempelajari
bunyibunyi bahasa, baik pada bahasa masyarakat yang sudah maju maupun bahasa pada
masyarakat yang masih bersahaja (primitif) dalam segala aspeknya (Arifin, 1979). Berdasarkan
ruang lingkupnya fonologi dibedakan atas fonologi umum dan fonologi khusus.
1. Ruang Lingkup Fonologi Umum dan Khusus
Fonologi umum ialah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari berbagai bahasa.
Fonologi umum merupakan ilmu yang membicarakan masalah bunyi-bunyi bahasa secara
umum, tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa yang dibicarakan itu terdapat dalam satu
bahasa tertentu atau tidak. Misalnya, fonologi umum membicarakan bunyi-bunyi bahasa di
kawasan Asia Tenggara (rumpun bahasa Austronesia), bahasabahasa di daratan Eropa
(rumpun bahasa Indo-German) atau bunyi-bunyi bahasa lain yang tidak serumpun untuk
diperbandingkan.
Fonologi khusus ialah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi yang terdapat dalam satu bahasa
tertentu. Misalnya, hanya bahasa Batak, Kerinci, Melayu Jambi, Jawa, Tagalok (Filipina) dan
sebagainya.
A. Pengertian fonetik
Bidang kajian fonetik memfokuskan pada analisis bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat
hubungan dengan makna katanya (Verhar, 1978; Kridalaksana, 1982). Fonetik sebagai
bagian dari fonologi memfokuska pada analisis bunyi-bunyi bahasa sebagai berikut.
a. Mempelajari setiap bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia,
b. Mempelajari bagaimana proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa itu,
c. Mengklasifikasi bunyi-bunyi tersebut atas bunyi vokal (vokoid), konsonan (kontoid) dan
bunyi prosidi (jeda, irama, intonasi bunyi),
d. Mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa itu dalam bentuk fonetis sebagai rekaman si
pembicara dalam bentuk tulisan.
B. Alat ucap manusia
1. Fungsi alat ucap
Hans Lapoliwa (1984) menagatakan alat ucap adalah paruparu, pita suara, lidah, bibir
dan sebagainya selain sebagai alat bicara dia berfungsi juga dalam meneruskan kelangsungan
hidup manusia. Misalnya: (1) Paru-paru berfungsi untuk menghisap zat pembakar (O2)
untuk disalurkan ke seluruh tubuh, menyalurkan asam arang (CO2) ke luar tubuh, dan
sumber udara bunyi bahasa; (2) Lidah berfungsi untuk memindah-mindahkan makanan yang
sedang dikunyah, alat perasa untuk mencegah masuknya makanan yang tidak baik, seperti
batu, pasir dan tulang, dan pembentuk bunyi-bunyi bahasa yang dominan dalam berbicara;
(3) Bibir berfungsi sebagai pintu gerbang yang dapat mencegah atau membolehkan segala
sesuatu masuk ke dalam mulut dan membentuk bunyi bibir (bilabial) seperti bunyi [m, b, p,].
Alat tubuh tersebut dipunyai pula oleh binatang akan tetapi pada manusia berfungsi
ganda yaitu fungsi makan, bernafas, di samping itu berfungsi sebagai alat bicara. Demikianlah
Tuhan telah memberi perlengakapan hidup yang lebih sempurna kepada manusia sebagai
makhluk luhur dan berakal.
2. Menganalisis dan Merekonstruksi Letak Alat Ucap
a. Bagian Badan
Alat ucap bagian badan adalah paru-paru, sekat rongga perut dan sekat rongga dada.
Berkaitan dengan itu, kita mengenal pernafasan perut dan pernafasan dada. Pernafasan
perut terjadi karena otot sekat rongga perut (diafragma) berkontraksi sehingga
menyebabkan kedudukan diafragma mendatar, rongga dada membesar, paru-paru
mengembang, tekanan di paru-paru menjadi kecil, mengakibatkan udara dari luar tubuh
masuk ke paru-paru. Selanjutnya, sekat rongga perut melemas menyebabkan kedudukan
diafragma melengkung, rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru membesar,
mengakibatkan udara yang ada di paru-paru terdesak keluar.
Pernafasan dada terjadi karena otot sekat rongga dada (intercostalis) berkontraksi,
hingga tulang rusuk menjadi rapat, tulang dada membusung ke depan, rongga dada
membesar, paru-paru mengembang, tekanan di paru-paru mengecil, mengakibatkan
udara dari luar tubuh masuk ke paru-paru. Selanjutnya sekat rongga dada melemas
menyebabkan tulang dada kembali ke tempat semula, rongga dada menyempit, dada
mengecil, paru-paru menyempit, tekanan dada terhadap paruparu membesar,
mengakibatkan udara yang ada di dalam paruparu terdesak ke luar tubuh.
b. Bagian Tenggorokan
Alat tubuh yang dijumpai bagian tenggorokan ialah batang tenggorokan (trachea),
pangkal tenggorokan (laring, larynx), dan rongga kerongkongan (faring, pharynx). Laring
terletak di pangkal lidah. Di sebelah bawah terdapat dua saluran yaitu saluran makanan
ke lambung (esofagus) dan satu lagisaluran pernafasan. Pada laring terdapat kotak suara
yang terdiri dari: (1) Tiroid (tulang rawan) yang dinamakan juga jakun, Adam’s apple,
terdapat disebelah leher. Pada lelaki tiroid ini lebih tampak atau menonjol. (2) Artenoid
(tulang rawan berbentuk piramid) letaknya di atas krikoid yang terletak di sebelah
belakang leher. (3) Vokal cord (Pita suara) yang membentang dari tiroid ke artenoid. Pita
suara dapat membuka dan menutup dengan kondisi; terbuka lebar, terbuka, tertutup,
tertutup rapat, serta dapat pula bergetar dan tak bergetar. (4) Glottis, yaitu celah yang
ditimbulkan oleh membuka dan menutupnya pita suara
c. Bagian Kepala
Bagian kepala terdapat tiga buah rongga, yaitu rongga mulut, rongga hidung dan
rongga faring. Di sebelah atas rongga mulut terdapat sederetan gigi atas, pangakal gigi,
langit-langit keras, langit-langit lembut dan anak tekak. Bagian bawah terdapat sederetan
gigi bawah dan lidah. Di sebelah belakang dibatasi dinding faring. Di sebelah depan
terdapat bibir atas dan bibir bawah.
Sebagian para fonetis (orang ahli dalam bidang fonetik) beranggapan bahwa mata dan
telinga juga merupakan alat bicara sebab keduanya dapat memberi umpan balik atau
reaksi dalam pembicaraan. Sebagai contoh jika ada pembicaraan berlangsung secara
berbisik kendati pun bisikan itu tidak dapat didengar tetapi mata dapat menangkap
maksud si pembicara melalui gerak bibirnya, maka komunikasi berbisik dapat
berlangsung. Sedangkan telinga jelas merupakan alat dengar yang diperlukan untuk dapat
menangkap berbagai bunyi bahasa dan mengirim rentetan bunyi itu ke syaraf otak untuk
diterjemahkan.
C. Pengertian fonemik
Bidang fonemik sebagai bagian dari fonologi menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang
berperan sebagai pembeda makna kata. Tujuannya untuk mencari sistem ejaan berdasarkan
fonem-fonem yang ada dalam bahasa tersebut.
Cara kerja analisis fonemik sebagai berikut:
a. Menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang dijumpai oleh kajian fonetik,
b. Mencari bunyi-bunyi yang berperan sebagai pembeda makna kata,
c. Bunyi–bunyi yang berperan sebagai pembeda makna kata disebut fonem,
d. Fonem primer dikatakan dengan huruf dan fonem sekunder dikatakan dengan tanda baca.
Menurut Hartman dan Stork (1972) bunyi yang membedakan makna kata dalam ilmu
linguistik (ilmu bahasa) disebut distingtif sedangkan bunyi yang tidak membedakan makna
kata disebut non distingtif.
D. Analisis dasar fonem
Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi, tetapi merupakan aspek tambahan terhadap
bunyi. Jika orang berbicara, akan terdengar bahwa suku kata tertentu pada suatu kata
mendapat tekanan yang relatif lebih nyaring daripada suku kata lain; bunyi tertentu
terdengar lebih panjang daripada bunyi yang lain; dan vokal (pada suku kata) tertentu
terdengar lebih tinggi daripada vokal pada suku kata lain. Tekanan, panjang bunyi, dan nada
dapat merupakan fonem jika membedakan kata dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Batak
Toba, tekanan bersifat fonemis karena membedakan kata, seperi pada /bontar/ 'putih' dan
/bontar/ „darah‟/. Dalam babasa Bahaan (salah satu bahasa di Irian Jaya), panjang bunyi
bersifat fonemis, seperti pada /syo/ 'ketapang‟ dan /syo:/ (atau /syo; syoo/) 'menjemur‟.
Pada semua bahasa, nada memberikan informasi sintaksis. Kalimat Anda dapat pergi
besok dapat diucapkan sebagai kalimat berita atau sebagai kalimat tanya, bergantung pada
naik -turunnya nada atau intonasi yang kita pakai. Jika nada itu membedakan kata dalam
suatu bahasa, bahasa itu disebut bahasa tona.
a. Menganalisis Tekanan
Dalam suatu kata atau suatu kelompok kata selalu ada satu suku kata yang menonjol.
Penonjolan suku kata tersebut dapat dilakukan dengan cara memperpanjang
pengucapannya, meninggikan nada, atau dengan memperbesar tenaga pengucapan atau
intensitas. Gejala ini dinamakan tekanan. Pada umumnya tekanan munciul pada tataran
kata atau kelompok kata. Dalam bahasa Indonesia tertencu ciri suprasegmental ini dapat
mempengaruhi arti kata dengan cara memindahkan letaknya.
Contoh: [béla] bela, [pembelàɁan] pembelaan ,[tàman] taman ,[taman-tàman] taman-
taman
Apabila suku kedua dari akhir mengandung bunyi /ə/, tekanan akan ditempatkan pada
suku akhir. Contoh: [bəlàh] belah , [bəkərjà] bekerja, [təràŋ] terang ,[əmpàt] empat
Dalam kalimat idaak semua kata mendapat tekanan yang sama. Biasanya hanya kata
yang dianggap penting saja yang diberi tekanan. Tekanan yang demikian lazim disebut
aksen.
b. Menganalisis Aksen
Persepsi mengenai aksen itu tidak hanya ditentukan oleh faktor tekanan (keras
lembutya suara), tetapi juga oleh faktor jangka (panjang pendeknya suara) dan nada
(tinggi rendahnya suara). Sebuah suku kata akan terdengar menonjol atau mendapat
aksen jika suku kata itu dilafalkan dengan waktu yang relatif lebih panjang daripada
waktu untuk suku kata yanglain. Suku kata itu juga cenderung dilafalkan dengan nada
yang meninggi.
c. Menganalisis Jeda
Dalam untaian tuturan terdengar juga adanya kesenyapan atau jeda di antara bagian
tuturan yang mengisyaratkan batas satuan tuturan itu. Jeda yang menandai batas kalimat
biasanya ditandai dengan palang ganda (#) yang diletakkan pada awal dan pada akhir
kalimat. Jeda yang menyatakan batas kata, frasa atau klausa dapat ditandai dengan garis
miring (/). Bagian tuturan yang terdapaat di antara dua garis miring biasanya terdapat
dalam satu pola intonasi yang sama.
d. Menganalisis Intonasi dan Ritme
Ciri suprasegmental lain yang penting dalam tuturan ialah intonasi dan ritme.
Intonasi mengacu ke naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat, sedangkan ritme
mengacu ke pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Oleh karena intonasi
merupakan perubahan titinada dalam berbicara, intonasi lazim dinyatakan dengan angka
(1,2,3,4) yang melambangkan tinggi. Angka (1) melambangkan titinada yang paling
rendah dan agka (4) melambangkan titinada yang paling tinggi menurut kesan
pendengaran. Perhatikan contoh berikut.
(1) Dua.
231#
(2) Di mana
233#
Tekanan kata tidak akan hilang sepenuhnya pada tataran kalimat. Dengan adanya
intonasi kalimat, tekanan kata-kata yang menyusun kalimat itu melemah. Walaupun
secara akustik faktor tinggi rendah suara (frekuensi) dan intensitas suku kata sebelum
yang terakhir tidak lagi menunjukkan adanya tekanan, suku kata tersebut masih
terdengar lebih menonjol daripada suku-suku kata lainnya. Ha ini disebabkan oleh faktor
panjang waktu. Gejala tersebut sering terjadi padakata-kata yang ada di awal kalimat.
Kita harus membedakan pengerttian intonasi dari pengertian ritme. Kita berbicara
tentang ritme jika kita membahas pola pemberian aksen pada kata dalam untaian tuturan
(kalimat). Pemberian aksen itu dilakukan dengan selang waktu yang sama untuk
beberapa bahasa dan dengan selang waktu yang berbeda untuk beberapa bahasa yang
lain. Bahasa Inggns, misalnya, mengikuti ritme yang berdasarkan jangka waktu sehingga
kedua kalimat berikut: John’s /here /now , The professor’s /in Bandung /this
evening. diucapkan dengan jangka waktu yang agak sama. The profesor's mempurya
waktu pengucapan yang sama dengan John’s, in Bandung sama lamanya dengan here, dan
this evening sama dengan now.
Sebaliknya, bahasa Indonesa mengikuti ritme yang berdasarkan jumlah suku kata:
makin banyak suku kata, makin lama pula waktu untuk pelafalannya. Perhatkan contoh
yang berikut.
Jono /disini /sekarang
Guru besar itu /in Bandung /malam ini
Kalimat kedua pada contoh di atas dilafalkan dengan waktu yang lebih lama
daripada kalimat pertama karena jumlah suku kata yang ada pada kalimat kedua itu lebih
banyak daripada jumlah suku yang ada pada kalimat pertama. Seperti telah dikemukakan
sebelumnya, intonasi merupakan urutan pengubahan nada dalam untaan tuturan yang
ada dalam suatu bahasa. Pola pengubahan bahan nada dalam untaian tuturan yang ada
dalam suatu bahasa. Pola pengubahan nada itu membagi suatu tuturan (kalimat) dalam
satuan yang secara gramatikal bermakna. Tiap-tiap pola pengubahan nada itu
menyatakan informasi sintaksis tersendiri.
Bagian kalimat tempat berlakunya suatu pola perubahan nada tertentu disebut
kelompok tona. Pada seiap kelompok tona terdapat satu suku kata yang terdengar
menonjol yang meyebabkan terjadinya perubahan nada. Suku kata itulah yang
mendapat aksen. Pada contoh berikut diperlihatkan pengubahan nada dengan angka
yang ditempatkan di bawah kalimat.
E. Perubahan Bunyi
Perubahan bunyi bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu
tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi
tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain,
perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi, apabila perubahan bunyi itu
sudah sampai berdampak pada pembedaan makna atau mengubah identitas fonem, maka
bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Demgan kata lain,
perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis.
1. Menganalisis Gejala Asimilasi
Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang
sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan
secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi.
Perhatikan contoh berikut.
a. Kata bahasa Inggris top diucapkan [tOp‟] dengan [t] apikodental. Tetapi, setelah
mendapatkan [s] lamino-palatal pada stop, kata tersebut diucapkan [s t o p‟] dengan [t]
juga lamino-palatal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa [t] pada [stOp‟]
disesuaikan atau diasimilasikan arikulasinya dengan [s] yang mendahuluinya sehingga
sama-sama lamino-palatal. Jika bunyi yang sudah diasimilasikan terletak sesudah bunyi
yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif.
b. Kata bahasa Belanda zak „kantong‟ diucapkan [zak] dengan [k] velar tidak bersuara,
dan doek „kain‟ diucapkan [duk‟] dengan [d] apiko-dental bersuara. Ketika kedua kata
tersebut digabung, sehingga menjadi zakdoek „sapu tangan‟, diucapkan [zagduk‟].
Bunyi [k] pada zak berubah menjadi [g] velar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyu
[d] yang mengikutinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bunyu [k] pada
[zak‟] disesuaikan atau diasimilasikan artikulasi dengan bunyi [d] yang mengikutinya
sehingga sama-sama bersuara. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi
yang mengasimilasikan disebut asimilasi regresif.
c. Kata bahasa Batak Toba holan ho „hanya kau‟ diucapkan [holakko], suan hon diucapkan
[suatton]. Bunyi [n] pada holan dan bunyi [h] pada ho saling disesuaikan atau
diasimilasikan menjadi [k], sedangkan [n] pada suan dan [h] pada hon saling
disesuaikan atau diasimilasikan menjadi [t]. dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa kedua bunyi tersebut, yaitu [n] dan [h], [n] dan [h] saling disesuaikan. Jika kedua
bunyi saling mengasimilasikan sehingga menimbulkan bunyi baru disebut asimilasi
resiprokal.
Dilihat dari lingkup perubahannya, asimilasi pada contoh 1 tergolong asimilasi
fonetis karena perubahannya masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu /t/.
asimilasi pada contoh 2 juga tergolong asimilasi fonetis karena perubahan [k‟] ke [g‟]
dalam posisi koda masih tergolong alofon dari fonem yang sama. Sedangkan asimilasi
pada contoh 3 tergolong asimilasi fonemis karena perubahan dari [n] ke [k] dan [h] ke
[k] (pada holan ho > [holakko]), serta perubahan dari [n] ke [t] dan [h] ke [t] (pada suan
hon > [suatton]) sudah dalam lingkup antarfonem. Bunyi [n] merupakan alofon dari
fonem /n/, bunyi [k] merupakan alofon dari fonem /k/. begitu juga, bunyi [h]
merupakan alofon dari fonem /h/, dan bunyi [t] merupakan alofon dari fonem /t/.
Dalam bahasa Indonesia, asimilasi fonetis terjadi pada bunyi nasal pada kata
tentang dan tendang. Bunyi nasal pada tentang diucapkan pada apiko-dental karena
bunyi yang mengikutinya, yaitu [t], juga apiko-dental. Bunyi nasal pada tendang
diucapkan apoko-alveolar karena bunyi yang mengikutinya, yaitu [ d ], juga apoko-
alveolar. Perubahan bunyi nasal tersebut masih dalam lingkup alofon dari fonem yang
sama.
2. Menganalisis Gejala Disimilasi
Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau
mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda.
Perhatikan contoh berikut!
a. Kata bahasa Indonesia belajar [belajar] berasal dari penggabungan prefik ber [bǝr] dan
bentuk dasar ajar [ajar]. Mestinya, kalau tidak ada perubahan menjadi berajar [bǝrajar].
Tetapi, karena ada dua bunyi [r], maka [r] yang pertama dibedakan atau didisimilasikan
menjadi [l] sehingga menjadi [bǝlajar]. Karena perubahan tersebut sudah menembus
batas fonem, yaitu [r] merupakan alofon dari fonem /r/ dan [l] merupakan alofon dari
fonem /l/, maka disebut disimilasi fonemis.
b. Secara diakronis, kata sarjana [sarjana] berasal dari bahasa Sanskerta sajjana [sajjana].
Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi [j] ganda. Bunyi [j] yang pertama berubah
menjadi bunyi [r]; [sajjana] > [sarjana].karena perubahan itu sudah menembus batas
fonem, yaitu [j] merupakan alofon dari fonem /j/ dan [r] merupakan alofon dari fonem
/r/, maka perubahan itu disenut disimilasi fonemis.
c. Kata sayur-mayur [sayUr mayUr] adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk
dasar sayur [sayUr]. Setelah diulang, [s] pada bentuk [sayUr] mengalami perubahan
menjadi [m] sehingga menjadi [sayUr mayUr]. Karena perubahan itu sudah menembus
batas fonem, yaitu [s] merupakan alofon dari fonem /s/ dan [m] merupakan alofon dari
fonem /m/, maka perubahan itu juga disebut disimilasi fonemis.
3. Menganalisis Gejala Modifikasi vocal
Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain
yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa
asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, makas perlu disendirikan.
a. Kata balik diucapkan [balȋ?], vokal I diucapkan [ȋ] rendah.tetapi ketika mendapatkan
surfiks –an, sehingga menjadi baikan, bunyi [i] berubah menjadi [i] tinggi: [balikan].
Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya
adalah glotal stop atau hamzah [?], sedangkan kata balikan, bunyi yang mengikutinya
adalah dorso-velar [k]. karena perubahan dari [ȋ] ke [I] masih dalam alofon dari satu
fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Sebagai catatan, perubahan
itu bisa juga karena perbedaan struktur silaba. Pada bunyi [ȋ], ia sebagai nuklus silaba
yang diikuti koda (lik pada ba-lik), sedangkan pada bunyi [i], ia sebagai nuklus silaba yang
tidak diikuti koda (li pada ba-li-kan).
b. Kata toko, koko, oto masing-masing diucapkan [toko], [koko], [oto]. Sementara itu, kata
tokoh, kokoh, otot diucapkan [tOkOh], [kOkOh], [OtOt‟]. Bunyi vokal [O] pada silaba
pertama pada kata kelompok dua dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang
mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua [O], maka pada silaba pertama
disesuaikan menjadi [O] juga. Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu
fonem, yaitu fonem /o/, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Pola pikir
ini juga bisa diterapkan pada bunyi [o] pada kelompok satu (Coba jelaskan!).
4. Menganalisis Gejala Netralisasi
Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan.
Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan
minimal [baraȵ] „barang‟ – [parang] „paraȵ‟ bisa disimpulkan bahwa pada bahasa
Indonesia ada fonrm /b/ dan /p/. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara
/b/ dan /p/ bisa batal – setidak-tidaknya bermasalah- karena dijumpai bunyi yang sama.
Misalnya, fonem /b/ pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan [p‟]: [adap] dan
[sǝbap‟], yang persis sama dengan pengucapan fonem /p/ pada atap dan usap: [atap‟] dan
[usap‟]. Mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambatletup-bersuara [b] tidak
mungkin terjadi pada posisi koda. Ketika dinetralisasikan menjadi hambat-tidak bersuara,
yaitu [p‟], sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem /p/.
Kalau begitu, apakah kedua bunyi itu tidak merupakan alofon dari fonem yang sama?
Tidak! Sebab, dalam pasangan minimal telah terbukti bahwa fonem /b/ dan /p/. Prinsip
sekali fonem tetap fonem perlu diberlakukan. Kalau pun ingin menyatukan, beberapa ahli
fonologi mengusulkan konsep arkifonem, yang anggotanya adalah /b/ dan fonem /p/.
Untuk mewakili kedua fonem tersebut, maka arkifonemnya adalah /B/ (huruf b kapital
karena bunyi b yang paling sedikit dibatasi distribusinya).
5. Menganalisis Gejala Zeroisasi
Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan
atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini bisa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di
dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan
komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan
disepakati oleh komunitas penuturnya.
Dalam bahas Indonesia sering dijumpai pemaikan kata tak atau ndak untuk tidak,
tiada, untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal, pemghilangan
beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tatabahasa baku bahasa Indonesia.
Tetapi, karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung.
6. Menganalisis Gejala Metatesis
Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi
dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami
metatesis ini tidak banyak. Hanya beberapa kata saja. Misalnya:
kerikil menjadi kelikir
jalur menjadi lajur
brantas menjadi bantras
Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya: lemari berasal dari bahasa
Portugis almari
rabu berasal dari bahasa Arab Arba
rebab berasal dari bahasa Arab arbab
7. Menganalisis Gejala Diftongisasi
Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal (monoftong) menjadi dua bunyi vokal
atau vokal rangkap (diftong) secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal
rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu
silaba.
Kata anggota [anggota] diucapkan [aɳgauta], sentosa [sǝntosa] diucapkan [sǝntausa].
Perubahan ii terjadi pada bunyi vokal tunggal [o] ke vokal rangkap [au], tetapi tetap dalam
pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam
rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan, dalam penulisannya pun disesuaikan
dengan ucapannya, yaitu anggauta dan sentausa. Contoh lain:
teladan [teladan] menjadi tauladan[tauladan]
vokal [e] menjadi [au]
topan [tOpan] menjadi taufan[taufan]
vokal [O] menjadi [au]
8. Menganalisis Gejala Monoftongisasi
Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau
vokal rangkap (diftong) menjadi vokal tunggal (monoftong). Peristiwa penunggalan
vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan
terhadap bunyi-bunyi diftong.
Kata ramai [ramai] diucapkan [rame], petai [pǝtai] diucapkan [pǝte]. Perubahan ini
terjadi pada bunyi vokal rangkap [ai] ke vokal tunggal [e]. Penulisannya pun disesuaikan
menjadi rame dan pete. Contoh lain:
kalau [kalau] menjadi [kalo]
danau [danau] menjadi [dano]
satai [satai] menjadi [sate]
damai [damai] menjadi [dame]
9. Menganalisis Gejala Anaptiksis
Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi
vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa
ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi
vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster. Misalnya:
putra menjadi putera [putǝra]
putri menjadi puteri [putǝri]
bahtra menjadi bahtera [bahtǝra]
srigala menjadi serigala [sǝrigala]
sloka menjadi seloka [sǝloka]
Akibat penambahan [ǝ] tersebut, berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan
pertama dari kluster yang disisipi bunyi [ǝ] menjadi silaba baru dengan puncak silaba
pada [ǝ]. Jadi, [tra] menjadi [tǝ+ra], [tri] menjadi [tǝ+ri], [sri] menjadi [sǝ+ri], dan [slo]
menjadi [sǝ+lo].
3.1 Morfologi
1. Pengertian Morfologi
Adalah salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur
internal kata dan pengaruh perubahan struktur tersebut terhadap arti dan golongan kata.
2. Morfem
Adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi
bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Contohnya: Mesjid mesjid), Kedua (ke)+(dua), Berlari
(ber)+(lari) Menggurui (meng)+(guru)
3. Leksem
Adalah satuan kata terkecil dalam sebuah bahasa dan biasa dimasukkan sebagai entri atau lemma
dalam sebuah kamus. Menurut KBBI, arti kata leksem adalah satuan leksikal dasar yang abstrak
yang mendasari pelbagai bentuk kata satuan terkecil dalam leksikon. Contohnya: bentuk kata,
misalnya membunuh, dibunuh, dan terbunuh adalah kata-kata yang berasal dari leksem bunuh.
dalam bahasa Inggris, kita akan menemukan kata playing, played, dan plays yang berasal dari
leksem plai.
4.1 Sintaksis
5.1 Semantik
A. Pengertian Semantik
Semantik (Bahasa Yunani: semantikos, memberikan tanda, penting, dari kata sema, tanda)
adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode,
atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari
ekspresi makna: sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana,
serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau
konteks tertentu. Ada dua cabang utama linguistik yang khusus menyangkut kata, yaitu
etimologi (studi tentang asal usul kata) dan semantik (ilmu makna, studi tentang makna kata).
Di antara kedua ilmu itu, etimologi sudah merupakan disiplin ilmu yang lama mapan
(established), sedangkan semantik relatif merupakan hal yang baru.
a. Menurut Ferdinand de saussure (1966)
Mengemukakan semantik yaitu yang terdiri dari (1) komponen yang mengartikan,
yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan atau makna
dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan tanda atau
lambang, sedangkan yang ditandai atau atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang
berbeda diluar bahsa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk.
b. Menurut Tarigan (1985: 2)
Mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam
pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan
tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut.
Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang
(sign). “Semantik” pertama kali digunakan oleh seorang filolog Perancis bernama Michel
Breal pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang
digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik
dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai
ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis bahasa:
Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami
ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa
pemrograman, logika formal, dan semiotika.
• Kajian formal semantik bersinggungan dengan banyak bidang penyelidikan lain,
termasuk leksikologi, sintaksis, pragmatik, etimologi dan lain-lain, semantik adalah
bidang yang didefinisikan dengan baik dalam dirinya sendiri, sering dengan sifat sintetis
Dalam filsafat bahasa, semantik dan referensi berhubungan erat. Bidang-bidang terkait
termasuk filologi, komunikasi, dan semiotika. Kajian formal semantik karena itu menjadi
kompleks.Semantik berbeda dengan sintaksis, kajian tentang kombinatorik unit bahasa
(tanpa mengacu pada maknanya), dan pragmatik, kajian tentang hubungan antara
simbol-simbol bahasa, makna, dan pengguna bahasa
B. Aspek-Aspek Semantik
aspek-aspek yang ada pada semantik berupa penamaan yaitu proses perlambangan suatu
konsep untuk mengacu kepada suatu referen yang berada diluar bahasa, aspek-aspek semantik
juga mengacu pada tindak tutur, jenis dan satuan semantik.
Aspek semantik terdiri dari:
a. Tanda,dalam aspek semantik tanda merupakan sesuatu yang menunjukan makna lain.
Berdasarkan hal itu tanda dibedakan menjadi tiga yaitu:
Audio: bedug sebagai tiba waktu shalat.
Visual: rambu lalu lintas, warna merah merupakan tanda untuk berhenti, warna hijau
sebagai tanda untuk berjalan.
Audio- visual: ambulan yang membunyikan sirine dan lampu merah yang berputar putar di
atasnya merupakan tanda meminta jalan agar cepat sampai tujuan.
b. Lambang,Lambang sebenarnya juga sama dengan tanda. Hanya saja lambang ini tidak
memberi tanda secara langsung. Melainkan melalui sesuatu yang lain
Contoh: warna merah pada bendera merah putih merupakan lambang keberanian
sedangkan warna putih merupakan lambang kesucian.
c. Simbol,Simbol adalah sebuah obyek yang berfungsi sebagai sarana untuk
mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak. Simbol biasanya berupa tulisan dan
lisan.
Contoh:Simbol-simbol yang terdapat dalam peta.
“Ssssttttttt...” menunjukkan sebuah simbol atau isyarat agar lawan
bicaranya diam.
d. Penanda,Penanda adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi tanda
C. Jenis-Jenis Makna
a. Makna Sempit
Makna sempit (narrowed meaning) adalah makna yang lebih sempit dari
keseluruhan ujaran. Makna yang asalnya lebih luas dapat menyempit, karena dibatasi
(Djajasudarma, 1993). Bloomfield mengemukakan adanya makna sempit dan makna luas di
dalam perubahan makna ujaran.
b. Makna luas dapat menyempit, atau suatu kata yang asalnya memiliki
makna luas (generik) dapat menjadi memiliki makna sempit (spesifik) karena
dibatasi. Perubahan makna suatu bentuk ujaran secara semantik berhubungan,
tetapi ada juga yang menduga bahwa perubahan terjadi dan seolah-olah bentuk ujaran
hanya menjadi objek yang relatif permanent, dan makna hanya menempel
seperti satelit yang berubah-ubah. Sesuatu yang menjadi harapan adalah
menemukan alasan mengapa terjadi perubahan, melalui studi makna dengan segala
perubahannya yang terjadi terus-menerus.
c. Makna Luas
Makna luas (widened meaning atau extended meaning) adalah makna yang
terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang diperkirakan (Djajasudarma,
1993: 8). Dengan pengertian yang hampir sama, Kridalaksana (1993: 133)
memberikan penjelasan bahwa makna luas (extended meaning, situational
meaning) adalah makna ujaran yang lebih luas daripada makna pusatnya; misalnya
makna sekolah pada kalimat Ia bersekolah lagi di SESKOAL yang lebih luas dari makna
‘gedung tempat belajar’.
d. Makna Konotatif dan Emotif
Makna kognitif dapat dibedakan dari makna konotatif dan emotif berdasarkan
hubungannya, yaitu hubungan antara kata dengan acuannya (referent) atau
hubungan kata dengan denotasinya (hubungan antara kata (ungkapan) dengan
orang, tempat, sifat, proses, dan kegiatan luar bahasa; dan hubungan antara kata
(ungkapan) dengan ciri-ciri tertentu yang bersifat konotatif atau emotif.
e. Makna Referensial
Makna referensial (referential meaning) adalah makna unsure bahasa yang sangat
dekat hubungannya dengan dunia di luar bahasa (objek atau gagasan), dan yang
dapat dijelaskan oleh analisi komponen; juga disebut denotasi; lawan dari konotasi
(Kridalaksana, 1993: 133).
f. Makna Konstruksi
Makna konstruksi (bahasa Inggris construction meaning) adalah makna yang
erdapat di dalam konstruksi. Misalnya, makna milik yang diungkapkan dengan
urutan kata di dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, makna milik dapat
diungkapkan melalui enklitik sebagai akhiran yang menunjukkan kepunyaan.
g. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal
Makna leksikal (bahasa Inggris lexical meaning, semantic meaning, exsternal
meaning) adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa,
dan lain-lain. Makna leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa secara tersendiri,
lepas dari konteks.
h. Makna Ideasional
Makna idesional dijelaskan Djajasudarma (1993), makna idesional (bahasa
Inggris ideational meaning) adalah makna yang muncul sebagai akibat penggunaan
kata yang berkonsep atau ide yang terkandung di dalam satuan kata-
kata, baik bentuk dasar maupun turunan.
i. Makna Proposisi
Makna proposisi (bahasa Inggris propositional meaning) adalah makna yang muncul
bila kita membatasi pengertian tentang sesuatu. Kata-kata dengan makna
proposisi dapat kita lihat di bidang matematika, atau di bidang eksaktra. Makna
proposisi mengandung pula saran, hal, rencana, yang dapat dipahami melalui konteks
(Djajasudarma, 1993).
j. Makna Pusat
Kridalaksana (1993: 133) memberikan arti makna pusat (central meaning) adalah makna
kata yang umumnya dimengerti bilamana kata itu diberikan tanpa konteks. Makna pusat
disebut juga makna tak berciri.
Makna pusat (bahasa Inggris central meaning) adalah makna yang dimiliki setiap
kata yang menjadi inti ujaran. Setiap ujaran, baik klausa, kalimat, maupun
wacana, memiliki makna yang menjadi pusat (inti) pembicaraan. Makna pusat dapat
hadir pada konteksnya atau tidak hadir pada konteks.
D. RELAKSI MAKNA
Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. Pada
dasarnya prinsip relasi makna ada empat jenis, yaitu :
1. Prinsip kontiguitas yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki
makna sama atau mirip. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang
disebut sinonim.
Sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim yaitu
suatu istilah yang mengandung pengertian telaah, keadaan, nama lain. Contoh: pintar,
pandai, cerdik, cerdas, cakap, mati, meninggal, berpulang, mangkat wafat .Sinonim tidak
mutlak memiliki arti yang sama tetapi mendekati sama atau mirip. Hal-hal yang dapat
menyebabkan terjadinya sinonim adalah penyerapan kata-kata asing, penyerapan kata-
kata daerah, makna emotif dan evaluatif. Kata bersinonim tidak dapat dipertukarkan
tempatnya karena dipengaruhi oleh ( a ) faktor waktu, ( b ) faktor tempat atau daerah, (
c ) faktor sosial, ( d ) faktor kegiatan dan ( e ) faktor nuansa makna.
2. Prinsip komplementasi yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu
berlawanan dengan makna kata yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi
makna yang disebut antonim.
Antonim adalah nama lain untuk benda lain pula atau kebalikannya.
• Oposisi kembar yaitu perlawanan kata yang merupakan pasangan atau kembaran
yang mencakup dua anggota.
Contoh:
laki-laki perempuan
kaya miskin
ayah ibu
3. Oposisi gradual yaitu penyimpangan dari oposisi kembar antara dua istilah yang
berlawanan masih terdapat sejumlah tingkatan antara. Contoh: kaya dan miskin, besar
dan kecil Pada kata tersebut
terdapat tingkatan (gradual) sangat kaya – cukup kaya – kaya – miskin – cukup miskin
– sangat miskin, sangat besar – lebih besar – besar – kecil – lebih kecil – sangat kecil.
4. Oposisi majemuk yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua
kata. Satu kata berlawanan dengan dua kata atau lebih. Contoh lawan dari kata diam
yakni bergerak, berbicara, bekerja, berdiri, berbaring.
5. Oposisi relasional yaitu oposisi antara dua kata yang mengandung relasi kebalikan,
relasi pertentangan yang bersifat saling melengkapi.
Contoh: menjual beroposisi membeli suami beroposisi istri utara beroposisi selatan
6. Oposisi hirarkis, oposisi ini terjadi karena setiap istilah menduduki derajat yang
berlainan. Oposisi ini pada hakikatnya sama dengan oposisi majemuk. Kata-kata yang
beroposisi hirarkis adalah katakata yang berupa nama satuan ukuran (berat, panjang,
dan isi), satuan hitungan, nama jenjang kepangkatan dan sebagainya.
Contoh: meter beroposisi dengan kilometer kuintal beroposisi dengan ton.
7. Oposisi inversi, oposisi ini terdapat pada pasangan kata seperti beberapa – semua,
mungkin – wajib. Pengujian utama dalam menetapkan oposisi ini adalah apakah kata
itu mengikuti kaidah sinonim yang mencakup (a) penggantian suatu istilah dengan
yang lain dan (b) mengubah posisi suatu penyangkalan dalam kaitan dengan istilah
berlawanan.
Contoh: beberapa negara tidak mempunyai pantai = tidak semua negara mempunyai
pantai
8. Prinsip overlaping yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki makna
yang berbeda atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna berbeda.
Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonym dan
polisemi.
Homonim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya tetapi mengandung makna dan
pengertian yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homonim adalah ( a )
kata-kata yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan, ( b ) kata-kata
yang berhomonim itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis.Homonim yang homograf
dan homofon adalah sama bunyi sama bentuknya.
Homonim yang tidak homograf tetapi homofon adalah bentuknya tidak sama tetapi
bunyinya sama.
Homonim yang homograf tidak homofon sama bentuk tetapi tidak bunyinya.
Contoh:
teras hati kayu atau bagian dalam kayu
teras pegawai utama
teras bidang tanah datar yang miring atau lebih tinggi dari yang lain
Kata berhomonim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya.
Contoh:
bisa dapat
bisa racun
Sedangkan polisemi adalah relasi makna suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu atau
kata yang memiliki makna berbeda-beda tetapi masih dalam satu arti.
Contoh: kepala
1. bagian tubuh dari leher ke atas
2. bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan yang merupakan hal yang
penting
3. pemimpin atau ketua
Dua cara untuk menentukan bahwa suatu kata tergolong polisemi atau homonimi, Pertama
melihat etimologi atau pertalian historisnya. Kata buku misalnya, adalah homonimi yakni ( a
) buku yang merupakan kata asli bahasa Indonesia yang berarti „tulang sendi‟ dan ( b ) buku
yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti „kitab, pustaka‟.Kedua, dengan mengetahui
prinsip perluasan makna dari suatu makna dasar.
Prinsip inklusi yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna satu kata mencakup
beberapa makna kata lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut
hiponim. Hiponim ialah semacam relasi antarkata yang berwujud atas bawah, atau dalam
suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain.Hiponim adalah semacam relasi
antarkata yang berwujud atas bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah
komponen yang lain. Kelas atas mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, sedangkan
kelas bawah merupakan komponen yang mencakup dalam kelas atas
Contoh:
Januari, Februari, Maret, April hiponim dari kata bulan. Kelas atas disebut hipernim,
contohnya, ikan hipernimnya tongkol, gabus, lele, teri.
E. JENIS-JENIS PERUBAHAN MAKNA
a) Generalisasi (Perluasan)
Generalisasi adalah kata-kata yangmaknanya mengalami pergeseranmenjadi lebih luas
dibandingdenganmakna sebelumnya.
Berlayar,Makna kata berlayar yang dahulu adalah melaut dengan perahu yang memiliki
layar saat ini meluas menjadi semuakegiatan melaut meskipun tidakmenggunakan
perahu layar
b) Peyorasi
Peyorasi adalah perubahan yang membuat makna memiliki
pengertian negatif.
Contohnya adalah kata babi. Selain mendefinisikan binatang, babi juga diartikan
sebagai ‘umpatan yang sangat kasar’. Tentu hal ini kita temui juga pada
kata anjing dan monyet. Lebih dari itu, bangsat pun tidak hanya diartikan sebagai
‘kepinding’ atau ‘kutu busuk’. Sekarang, bangsat pun memiliki arti ‘orang yang
bertabiat jahat’.
c) Ameliorasi
Berbeda dengan peyorasi, ameliorasi adalah perubahan yang membuat makna
memiliki pengertian positif.
Contohnya adalah kata sahaya yang berasal dari bahasa Melayu.
Kata ini mengartikan ‘hamba’, ‘abdi’, atau ‘budak’. Namun, saat ini, sahaya berubah
bentuk menjadi saya dan berdiri sebagai pronomina persona tunggal yang bebas
kasta.
Contoh ameliorasi lainnya adalah kata pembantu yang disebut sebagai asisten rumah
tangga.
ameliorasi mempunyai dua golongan lagi, yaitu eufemisme dan disfemisme.
Kridalaksana (2009: 59) menuliskan bahwa eufemisme adalah pemakaian kata atau
bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau tabu,
seperti mati menjadi meninggal dan berak menjadi buang air besar. Bahkan, ada pula
anggapan bahwa mengamankan adalah eufemisme dari menangkap.
Golongan yang kedua, disfemisme, adalah perluasan makna dengan makna
yang lebih kasar, lebih ofensif (Muhadjir 2017: 99). Contohnya adalah pencuri yang
diungkapkan dengan maling.
d) Perubahan Makna Lain,Di luar dua jenis umum tersebut, Muis dkk. pun menambahkan
klasifikasi lain berdasarkan penelitian yang sudah mereka lakukan. Sebuah makna
dapat juga mengalami perubahan akibat perluasan murni, seperti saudara yang
tadinya dilekatkan dengan sifat biologis atau kekeluargaan. Saat ini, saudara dapat
menjadi sapaan umum pada situasi formal.Selain itu, makna kata dapat berubah
karena penyempitan.
Contohnya adalah sarjana yang mulanya mengartikan ‘orang pandai’ atau
‘cendekiawan’. Sekarang, tanpa membuka kamus, besar kemungkinannya bahwa kita
hanya memahami sarjana sebagai seseorang dengan gelar strata satu.
F. KOMPONEN MAKNA
Makna yang dimiliki oleh setiap kata itu terdiri dari sejumlah komponen (yang disebut
komponen makna), yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna ini dapat
dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu per satu, berdasarkan “pengertian-pengertian” yang
dimilikinya. Umpamanya, kata ayah memiliki komponen makna/ + manusia/, /+ dewasa/, /+
jantan/, /+ kawin/, dan /+ punya anak.
Perbedaan makna antara kata ayah dan ibu hanyalah pada ciri makna atau komponen makna;
ayah memiliki makna jantan, sedangkan ibu tidak memiliki kata jantan.
komponen makna ayah Ibu
1 Insane + +
2 Dewasa + +
3 Jantan + _
4 kawin + +
Keterangan : tanda + mempunyai komponen makna tersebut, dan tanda – tidak mempunyai
komponen makna tersebut.
Konsep analisis dua-dua ini (lazim disebut anlisis biner) oleh para ahli kemudian diterapkan
juga untuk membedakan makna suatu kata dengan kata lain. Dengan analisis biner ini kita
juga dapat menggolong-golongkan kata atau unsur leksikal sesuai dengan medan makna.
BAB III
PENUTUP
Ranah mikrolinguistik kajiannya secara struktural sehingga bisa dilihat benar selahnya sebuah
kalimat ; ketepatannya, keseksamaanya serta kelazimannya. Hal ini dikarenakan kehadiran beberapa
sub disiplin dinataranya ; Fonologi yang menyedelidiki ciri - ciri bunyi bahasa, kegiatan yang
dipekerjakan terjadinya, fungsinya dalam sistem kebahsaan secara semuanya. Morfologi yang
menyelidiki struktur kata, bagian – bagiannya serta kegiatan yang dipekerjakan pembentukannya.
Semantik yang menyelidiki makna bahasa patut bersifat leksikal, grmatikal, maupun kontekstual.
Sintaksis yang menyelidiki satuan –satuan kata dan satuan – satuan lain di atas kata, hubungan satu
dengan lainnya, serta kegiatan yang dipekerjakan penyusunannya sehingga menjadi suatu ujaran.
Daftar Pustaka
Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
Chaer, Abdul. 2002. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Adiwimarta, Sri Sukesi, dkk., kamus etimologi bahasa indonesia. Jakarta : pusat pembinaan dan
pengembangan bahasa, 1987.
Alwi Hasan, dkk., tata bahasa buku bahasa indonesia edisi kedua. Jakarta: depdikbud, 1993.
Muis, dkk. 2010. Perluasan Makna Kata dan Istilah dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa
Resmini dkk.2006.Kebahasaan(Fonologi,Morfologi,dan Semantik).Bandung : UPI PRESS
Aminuddin. 2011. Semantik Pengantar Studi Tentang Makna. Bandung: Sinar Baru Alensido
Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. Semantik 1. Pengantar ke Arah Ilmu Makna. Bandung: ERESCO.
Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Mulich, Masnur. 2008. Fonologi Bahasa Indonesia. Tinjau deskriptif system bunyi bahasa Indonesia.
Jakarta: Bumi Aksara.
Noortyani, Rusma. 2017. Buku Ajar Sintaksis. Yogyakarta: Penebar Pustaka Media
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
modul bahan ajar mata kuliah linguistik tentang mikrolinguistik untuk mahasiswa program bahasa dan sastra indonesia
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
modul bahan ajar
- 1 - 24
Pages: