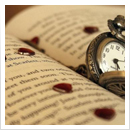TARI TRADISIONAL INDONESIA
SUMATERA UTARA TARI TOR TOR
Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik
gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna
yang lebih dari hanya sekadar gerakan-gerakannya
menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi, di mana
melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara
partisipan upacara.
Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa
dipisahkan. Sebelum acara dilakukan, secara terbuka, terlebih
dahulu tuan rumah (Hasuhutan) melakukan acara khusus
yang dinamakan Tua ni Gondang, sehingga berkat
dari gondang sabangunan.
Dalam pelaksanaan tarian tersebut salah seorang dari
hasuhutan (yang mempunyai hajat akan meminta permintaan
kepada penabuh gondang dengan kata-kata yang sopan dan
santun.
Setiap penari tortor harus memakai ulos dan
mempergunakan alat musik/gondang (Uninguningan). Ada
banyak pantangan yang tidak diperbolehkan saat manortor,
seperti tangan si penari tidak boleh melewati batas setinggi
bahu ke atas, bila itu dilakukan berarti si penari sudah siap
menantang siapa pun dalam bidang ilmu perdukunan, atau
adu pencak silat (moncak), atau adu tenaga batin dan lain-lain.
Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik
kepada roh-roh leluhur dan maupun kepada orang yang
dihormati (tamu-tamu) dan disampaikan dalam bentuk tarian
menunjukkan rasa hormat.
Tarian ini adalah salah satu tarian dari suku batak TARI PISO SURIT
karo, Sumatera Utara. Tarian ini digunakan untuk
menyambut para tamu kehormatan. Arti Piso Surit
adalah burung yang bernyanyi. Tarian ini
menggambarkan seorang gadis yang sedang
menantikan kedatangan sang kekasih. hal ini
digambarkan menyedihkan serta digambarkan
sebagai seekor burung yang suka bernyanyi. Tarian ini
menggambarkan seorang gadis yang sedang
menantikan kedatangan sang kekasih. Hal ini
digambarkan menyedihkan.
Tarian Piso Surit ini biasanya ditampilkan secara
berkelompok yaitu wanita dan pria. jumlah penari
terdiri dari lima pasang atau lebih. Penari
menggunakan busana adat dan menari dengan
diiringin oleh musik tradisional. Gerakan tarian piso
surit memiliki ciri khas yang lemah gemulai dan
berulang- ulang. gerakan tersebut diantaranya
meliputi gerakan kaki, menjinjit, gerakan berputar,
melentikan jari, gerakan naik turun dan gerakan
lainnya.
SUMATERA BARAT TARI PIRING
TARI RENTAK KUDO
Tari piring (bahasa Minangkabau: tari piriang) adalah tarian
tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan
piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti
gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satu pun piring terlepas
dari tangan.[1] Gerakannya diambil dari langkah dalam silat
Minangkabau atau silek.[2]
Tari ini dipopulerkan oleh Huriah Adam. Saat ini, tari piring
dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau
pembukaan upacara adat. Bersama dengan tari saman, pendet,
dan jaipong, tari ini menjadi tarian populer Indonesia yang kerap
ditampilkan di ajang promosi pariwisata dan kebudayaan
Indonesia.[3]
Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatra
Barat.[4] Menurut legenda, tari ini awalnya merupakan ritual ucapan
rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah
mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan
dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di
dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis.[butuh
rujukan]
Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tari piring tidak
lagi digunakan sebagai ritual ucapan rasa syukur kepada dewa-
dewa.[5] Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan
bagi masyarakat banyak yang ditampilkan pada acara-acara
keramaian.
Tari Rentak Kudo adalah tarian kesenian khas budaya asli
masyarakat Kerinci yang berasal dari daerah Hamparan
Rawang Kabupaten Kerinci, Jambi yang banyak diminati kalangan
masayakat di Kabupaten Kerinci.
Tari Rantak Kudo dimainkan dengan diiringi alat musik gendang dan
di iringi oleh nyayian yang berisi pantun-pantun, hal ini berbeda
dengan Tari Rantak dari Minangkabau yang hanya diiringi
instrumen musik. Para penari terdiri dari pria dan wanita yang
menari dengan gerakan yang khas, yaitu kombinasi dari
gerakan silat "langkah tigo" ("Langkah Tiga") dan tari. Biasanya
tarian ini juga dipentaskan dengan pembakaran
kemenyan tradisional upacara ritual yang membuat penari semakin
khidmat dalam geraknya, bahkan kadang-kadang ada di antara
penari yang mengalami kesurupan.
Di Indonesia saat ini, tarian ini biasanya dipentaskan dalam acara-
acara adat dan acara resepsi pernikahan adat Kerinci. Salah satu
lirik lagu di dalam pantun yang bersahut-sahutan adalah: "Tigeo dili,
empoak tanoh rawoa. Tigeo mudik, empoak tanoh rawoa" (Bahasa
Indonesia: "Tiga di Hilir, Empat dengan Tanah Rawang. Tiga di
Mudik, Empat dengan Tanah Rawang"). Lirik tersebut menceritakan
sebuah kisah pada zaman nenek moyang suku Kerinci dahulu kala,
di kala pemerintahan para Depati (Adipati), Tanah Hamparan
Rawang merupakan pusat pemerintahan, pusat kota dan
kebudayaan di kala itu, yaitu dalam lingkup Depati 8 helai kain yang
berpusat di Hiang (Depati Atur Bumi) dimana Tanah Hamparan
Rawang merupakan tempat duduk bersama (pertemuan penting
dalam adat Kerinci).
SUMATERA SELATAN TARI NGANTAT DENDAN
Tari ngantat dendan menceritakan
tentang salah satu rangkaian adat
perkawinan kota lubuk linggau
sumatera selatan, dimana pihak pihak
dari rombongan calon pengantin laki
laki akan datang ketempat pihak calon
mempelai perempuan dengan
membawa jeras. Seni tari ini
terinspirasi dari properti yang
digunakan bernama jeras tersebut.
Jeras berbahan zinc dalam bahasa
Indonesia disebut seng atau
alumunium.
JAWA TIMUR TARI REMO
Berdasarkan perkembangan sejarah Tari Remo, dulunya Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan
Tari Remo merupakan seni tari yang digunakan sebagai tamu yang ditampilkan baik oleh satu atau lebih.
pembuka dalam pertunjukan ludruk. Namun seiring Menurut sejarahnya, Tari Remo merupakan tari yang
berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih khusus dibawakan oleh penari laki – laki. Ini berkaitan
dari pembuka pertunjukan ludruk, menjadi tarian dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan
penyambutan tamu, khususnya tamu – tamu kenegaraan. Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang
Selain itu Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi
kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam
Jawa Timur. Oleh karena itulah kini tari remo tidak hanya menampilkan tarian ini.
dibawakan oleh penari pria, tetapi juga oleh penari wanita.
Sehingga kini muncul jenis tari remo putri. Dalam
pertunjukan Tari Remo putri, umumnya para penari akan
memakai kostum tari yang berbeda dengan kostum tari
remo asli yang dibawakan oleh penari pria.
Karakteristika yang paling utama dari Tari Remo adalah
gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Gerakan ini
didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di
pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari
melangkah atau menghentak di panggung. Selain itu,
karakteristika yang lain yakni gerakan selendang atau
sampur, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi
wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin
atraktif.
Jaran kepang atau jathilan adalah salah satu dari berbagai jenis KUDA LUMPING
tarian kuda lumping di Indonesia. Tari jaran kepang jathilan berasal
dari Ponorogo. Tarian ini merupakan bagian dari satu kesatuan
kelompok utuh Reog.
Jaran kepang atau jathilan digambarkan sebagai pasukan gagah
berani yang menunggangi kuda.[1]
Kata jathil berasal dari bahasa Jawa yaitu jarane jan thil-thilan yang
berarti kuda yang menari tidak beraturan. Di beberapa kesempatan
memang penari jathilan ini kerasukan, namun untuk penari di masa
sekarang para penari jaran kepang atau jathilan pada pertunjukan
Reog tidak kerasukan sehingga tidak melakukan berbagai atraksi
berbahaya seperti halnya dengan tarian kuda lumping dari daerah
lain.
Di masa lalu, jaran kepang atau jathilan ditarikan oleh laki-laki.
Namun pada perkembangannya di masa sekarang, tari jaran kepang
atau jathilan justru ditarikan oleh wanita. Tarian ini
menggambarkan kekuatan prajurit berkuda namun ditarikan indah
dalam gemulai gerakan penarinya. Di masa lalu, tarian ini sering kali
terpisah dengan pertunjukan Reog. Tarian ini banyak dilakukan di
pedesaan sebagai kesenian hiburan bagi rakyat. Namun di Ponorogo
khususnya, tarian jaran kepang atau jathilan menjadi kesatuan yang
tidak terpisahkan dari pertunjukan Reog.
JAWA TENGAH TARI SERIMPI
TARI BEDAYA KETAWANG
Srimpi atau Serimpi adalah bentuk repertoar (penyajian) tari
Jawa klasik dari tradisi kraton Kesultanan Mataram dan
dilanjutkan pelestarian serta pengembangan sampai sekarang
oleh empat istana pewarisnya di Jawa Tengah (Surakarta)
dan Yogyakarta.
Sejak dari zaman kuno, tari Srimpi sudah memiliki kedudukan
yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat
disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang
sakral. Dahulu tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-
orang yang dipilih keraton. Srimpi memiliki tingkat kesakralan
yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang
melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman
Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedhaya.
Srimpi sendiri telah banyak mengalami perkembangan dari
masa ke masa, di antaranya durasi waktu pementasan.[9] Kini
salah satu kebudayaan yang berasal dari Jawa Tengah ini
dikembangkan menjadi beberapa varian baru dengan durasi
pertunjukan yang semakin singkat.[9] Sebagai contoh Srimpi
Anglirmendhung menjadi 11 menit dan juga Srimpi
Gondokusumo menjadi 15 menit yang awal penyajiannya
berdurasi kurang lebih 60 menit.[10]
Tari Bedaya Ketawang (Bahasa Jawa: Bedhaya
Ketawang, ꦨꦝꦼ ꦪꦑꦼꦠꦮ)ꦁ adalah sebuah tarian
kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika
penobatan serta Tingalandalem Jumenengan Sunan
Surakarta (upacara peringatan kenaikan tahta raja).
Nama Bedhaya Ketawang sendiri berasal dari
kata bedhaya yang berarti penari wanita di istana.
Sedangkan ketawang berarti langit, identik dengan
sesuatu yang tinggi, keluhuran, dan kemuliaan. Tari
Bedhaya Ketawang menjadi tarian sakral yang suci
karena menyangkut Ketuhanan, di mana segala
sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang
Maha Esa.
Busana penari Bedhaya Ketawang sangat mirip dengan
busana pengantin Jawa dan didominasi dengan warna
hijau, menunjukkan bahwa Bedhaya Ketawang
merupakan tarian yang menggambarkan kisah
asmara Kangjeng Ratu Kidul dengan raja-
raja Mataram.
JAWA BARAT TARI JAIPONG
TARI WAYANG
Jaipongan adalah sebuah jenis tari pergaulan
tradisional masyarakat Sunda, Karawang, Jawa Barat,
yang sangat populer di Indonesia.
tari Jaipongan boleh disebut sebagai salah satu
identitas kesenian Jawa Barat, hal ini tampak pada
beberapa acara-acara penting yang berkenaan dengan
tamu dari negara asing yang datang ke Jawa Barat,
maka disambut dengan pertunjukan tari Jaipongan.
Demikian pula dengan misi-misi kesenian ke
mancanegara senantiasa dilengkapi dengan tari
Jaipongan. Tari Jaipongan banyak memengaruhi
kesenian-kesenian lain yang ada di masyarakat Jawa
Barat, baik pada seni pertunjukan wayang, degung,
genjring/terbangan, kacapi Jaipongan, dan hampir
semua pertunjukan rakyat maupun pada musik
dangdut modern yang dikolaborasikan dengan Jaipong
menjadi kesenian Pong-Dut.
Tari Wayang yaitu salah satu kelompok atau
genre tari yang latar belakangnya dari cerita wayang.
Tari ini tumbuh mekar di wilayah Jawa Barat, dan
menjadi salah satu tarian tradisional Jawa Barat.
Tari wayang yaitu tari yang mengambil gerak
dasarnya dan gerak intinya dari penokohan wayang.
Tari wayang biasanya menggambarkan penokohan
dan jabatan dalam cerita wayang. Ada beberapa ciri
utama dalam tari wayang yaitu:
1. Tari wayang yang menggambarkan
penokohannya seperti tari Adipati Karna, Tari
Jayengrana, Tari Gatotkaca, dan Tari Srikandi x
Mustakaweni, serta tarian yang menggambarkan
jabatan seperti Tari Badaya.
2. Kekayaan tarian Wayang mempunyai ciri
tingkatan karakter atau watak tertentu.
DKI JAKARTA TARI YAPONG
Tari Yapong merupakan suatu bentuk
tarian dari Jakarta yang diciptakan
untuk sebuah pertunjukan. Tarian ini
bukan jenis tarian pergaulan seperti
tari daerah kebanyakan, misalnya
tari Jaipong dari Jawa Barat. Namun
dalam perkembangannya, tarian ini
sering dijadikan sebagai tari pergaulan
untuk mengisi sebuah acara sesuai
dengan permintaan karena tarian ini
penuh dengan variasi di dalamnya.
KALIMANTAN TIMUR
Hudoq artinya menjelma, oleh karena itu memakai topeng burung TARI HUDOQ
melambangkan menjelma menjadi burung.
TARI BURUNG ENGGANG
Menurut kepercayaan tradisional
orang Bahau, Busang, Modang, Ao'heng dan Penihing, Hudoq
adalah 13 hama yang merusak tanaman seperti tikus, singa, gagak,
dan lain-lain. Dalam festival tersebut Hudoq dilambangkan oleh
penari yang mengenakan topeng yang mewakili hama dan rompi
yang terbuat dari pinang atau kulit kayu pohon pisang.
Gerakan tangan dan kaki mendominasi tari hudoq. Badan penari
tegak yang kemudian terus berputar pelan di setiap
langkah. Tangan terayun ke atas setinggi bahu, diangkat setinggi-
tingginya, lalu dijatuhkan menepuk paha. Gerakan kaki berupa
hentakan: dengan lutut perlahan ditekuk, kaki terangkat hingga 30
sampai 40 cm, kemudian dihentak kuat ke bawah untuk
menghasilkan suara keras. Saat mengambil langkah, kaki yang
terangkat menyilang di atas kaki tumpuan sehingga badan terayun
ke kiri dan ke kanan. Suara hentakan kaki disusul oleh tepukan
tangan ke paha membuat busana yang berjumpai itu berbunyi
‘whuss…’. Gerakan kepala tidak teratur, hanya berupa gerakan
mengangguk. Jika topeng memiliki mulut yang bisa bergerak, setiap
kepala tertunduk mulut topeng akan tertutup dengan berbunyi
meletik. Para penari bergerak dalam lingkaran, yakni bergerak dari
satu sudut arena ke sudut arena yang lain sampai empat sudut
tersentuh.
Tari Burung Enggang atau biasa disebut Tari Enggang adalah sebuah
tarian Suku Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Tari Burung Enggang
menjadi tarian wajib dalam setiap upacara adat Suku Dayak Kenyah.
Tari Burung Enggang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung
enggang yang biasanya dibawakan oleh wanita-wanita muda Suku
Dayak Kenyah.
Menurut kepercayaan orang Dayak Kenyah nenek moyang mereka
berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung
enggang.[2] Oleh karena itu, masyarakat dayak Kenyah sangat
menghormati dan memuliakan burung enggang.[2] Sehingga Tari
Enggang dapat dimaknakan sebagai penghormatan Suku Dayak
Kenyah terhadap asal usul leluhur mereka.
Tarian Burung Enggang menggunakan gerakan dasar
perumpamaan dari Burung Enggang yang mana dalam konsep
gerakan dikelompokkan sebagai berikut:
Nganjat adalah sebuah gerakan utama atau gerakan
khas dari tarian dayak yang menyerupai burung
enggang, gading yang membuka menutup sayap nya
dalam gerakan ini melambangkan gerakan molek dari
seorang penari dayak tersebut.
Ngasai adalah gerakan yang menyerupai burung
enggang yang sedang terbang.
Purak Barik adalah sebuah gerakan dasar yang
merupakan gerakan perpindahan tempat.
Tari Jepen merupakan kesenian khas Kalimantan Timur yang TARI JEPEN
dikembangkan oleh suku Kutai dan suku Banjar yang mendiami
kawasan pesisir Sungai Mahakam, dengan ragam gerak dipengaruhi
oleh kebudayaan Melayu dan Islam.
Dari segi musik, pengaruh alat Musik kontemporer tidak bisa
dihindari. Meski demikian, bukan berarti menghilangkan secara
penuh musik tradisional Kutai. Kelompok tari kreasi jepen yang
banyak bermunculan diberbagai daerah di Kabupaten Kutai
Kertanegara masih menggunakan musik tradisional yang disebut
dengan musik tingkilan sebagai musik yang mengiringi pementasan.
Tingkilan adalah seni musik khas suku Kutai. Alat musik yang
digunakan adalah Gambus, ketipung, kendang, dan biola. Musik
Tingkilan disertai pula dengan nyanyian yang disebut betingkilan.
Betingkilan sendiri berarti bertingkah-tingkahan atau bersahut-
sahutan. Dahulu sering dibawakan oleh dua orang penyanyi pria dan
wanita sambil bersahut-sahutan dengan isi lagu berupa syair-syair
berupa pantun saling berbalas yang berisi petuah-petuah moral
menurut adat ketimuran.
Tari Jepen tempo dulu berfungsi sebagai hiburan dalam rangka
penobatan raja-raja dari Kesultanan Kutai
Kartanegara di Tenggarong dan sebagai tari pergaulan muda dan
mudi, misalnya untuk memadu janji, berkasih-kasihan, dan
sebagainya. Kemudian, sejak era 1970-an tarian seni rakyat ini
umumnya dipergunakan dalam acara penyambutan tamu-tamu
daerah, upacara perkawinan, dan untuk mengisi acara dalam hari
besar lainnya, semisal HUT Provinsi Kalimantan Timur, HUT
Kota Tenggarong, dan HUT Kota Samarinda.
KALIMANTAN BARAT TARI AJAT TEMUAI DATAI
Ragam gerak tari: Tari Ajat Temuai Datai adalah tari penyambutan khas Suku Dayak
- Ngiring Temuai adalah proses pengiringan atau pemaduan tamu Iban di Provinsi Kalimantan Barat. Kata "Ajat Temuai Datai" diadopsi
dari bahasa Dayak Mualang, salah satu sub etnis kelompok Dayak
sampai ke depan Rumah Panjai (rumah panggung yang panjang) Iban.
yang dilakukan dengan cara ngajat (menari). Masyarakat suku Dayak Mualang, menjadikann tarian ini sebagai
- Mancung Buloh bermakna menebaskan mandau atau parang tari menyambut tamu adat, tamu kenegaraan, juga ketika ada
guna memutuskan bambu. Bambu sengaja dibentangkan wisatawan berkunjung ke kampung Dayak Mualang.
menutupi jalan masuk ke rumah panjang dan para tamu harus Arti dari kata Ajat Temuai Datai sebenarnya tidak dapat diartikan
menebaskan mandau-nya untuk memutuskan bambu tersebut secara kata perkata. Namun, secara umum Ajat Temuai Datai jika
sebagai simbol bebas dari rintangan yang menghalangi perjalanan diartikan memiliki maksud proses pengucapan rasa syukur kepada
tamu itu. sang pencipta atas kedatangan tamu atau temuai di tanah
- Nijak Batu adalah proses menginjakkan tumit ketika menyentuh Kalimantan dengan tari penyambutan.
sebuah batu yang direndam di dalam air yang telah
dipersiapkan. Nijak Batu merupakan simbol kuatnya tekad dan
tinginya martabat tamu itu sebagai seorang pahlawan yang
disegani. Air pada rendaman batu tersebut diteteskan pada
kepala tamu tersebut sebagai simbol keras dan kuatnya semangat
dari batu itu untuk diteladani oleh pahlawan atau tamu yang
disambut.
- Tama’ Bilik bermakna memasuki rumah panjang. Ini merupakan
pelajaran akhir dari proses penyambutan. Setelah melalui prosesi
babak-babak tersebut, tamu diizinkan naik ke rumah
panjang dengan maksud menyucikan diri dalam upacara yang
disebut Mulai Burung (mengembalikan semangat perang atau
mengusir roh jahat).
Tari Pedang Mualang suku Dayak Mualang Kalimantan TARI MANANG atau TARI MONONG
Barat adalah sebuah tarian tunggal tradisional yang di sajikan
pada masa kini untuk menghibur masyarakat dalam setiap acara
tradisional. misalnya: Gawai Dayak ( pesta panen padi ), Gawai
Belaki Bini ( pesta pernikahan ) dll.
Tari ini lebih menekankan pada Gerakan aktraktif
menggunakan pedang dalam menyerang maupun menangkis
serangan lawan demikian juga menjadikan pedang sebagai
objek yang di mainkan baik di kepala maupun di bahu serta
keahlian melakukan putaran pedang. Pada masa lalunya, tari
Pedang Mualang di lakukan oleh para kesatria sebagai motivasi
mendatangkan semangat perang sebelum turun
melakukan ekspedisi Mengayau. Hal ini di maksudkan untuk
memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka harus menang
dalam melawan serangan maupun dalam menyerang lawannya.
Tari ini diiringi oleh tebah tradional yang disebut "tebah Undup
Banyur " tetapi adakalanya dilakukan dengan Tebah
Undup Biasa. kini Tarian Pedang Mualang, mulai terancam
punah karena tidak banyak lagi tua – tua yang menurunkan
tarian ini kepada generasi mudanya. Salah seorang generasi tua
yang masih dapat memperagakan tari ini yaitu: bapak Mundus /
Apai Mundus dari Kampung Merbang, Kecamatan Belitang Hilir,
Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat.
Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayatn TARI JONGGAN
di provinsi Kalimantan Barat.
Nama jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau
menari. Menurut beberapa sumber, tarian ini mulai muncul pada
tahun 1950an di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tarian ini
awal mulanya digelar sebagai hiburan bagi masyarakat pada
berbagai upacara adat seperti bayar niat, naik dango, hajatan
sunatan atau babalak, acara perkawinan, festival, dan acara
penyambutan tamu penting. Sebelum Tari Jonggan dipentaskan,
dilakukan ritual khusus terlebih dahulu. Ritual tersebut biasa
disebut dengan nyangahant yang berarti berdoa. Ritual ini
dilakukan untuk meminta izin atau meminta perlindungan kepada
Tuhan agar pertunjukan berjalan lancar. Acara tersebut diawali
dengan bapamang yaitu penyampaian doa hajat oleh pemimpin
upacara di depan sesaji yang sudah disiapkan.
Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa
syukur kepada Jubata (Tuhan) dan suka cita masyarakat yang
dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang dalam tarian ini para penari
mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara
leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari. Sentuhan
emosional juga kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal
maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan
serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antarpersonal. Sebagai tari
pergaulan masyarakat Suku Dayak Kanayatn tarian ini benar-benar
menceritakan suka cita dan kebahagiaan dalam pergaulan muda-
mudi Dayak Kanayatn.
KALIMANTAN TENGAH TARI KAYAU
TARI GIRING-GIRING
Tari Kayau adalah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk
keberanian, kejantanan dan kekuasaan dalam melindungi
keberadaan suku dari musuh, pada masyarakat Kalimantan Tengah
khususnya Suku Dayak. Tidak semua orang bisa mengayau karena
ada aturan dan syarat-syaratnya. Alat yang digunakan mandau;
senjata tradisional Suku Dayak. Kayau atau mengayau memiliki arti
arti memotong kepala musuh. Upacara mengayau merupakan
simbol tanggung jawab sosial, nilai pendidikan dan bersifat untuk
melindungi diri bukan kegiatan negatif.
Tarian Kayau diturunkan kali pertama oleh Urang Lindau Lendau
Dibiau Takang Isang, seorang yang gagah berani pada zamannya.
Ada tiga tahap dalam upacara mengayau.
Pertama, mengantar sesaji pada Bentang [rumah Suku Adat Dayak].
Kedua, turun Bentang, yaitu melakukan pengayauan pada kepala
babi, dan yang terakhir adalah adalah memasuki Rumah Betang
dengan bunyi-bunyian musik.Orang yang akan melakukan upacara
mengayau harus mengikuti aturan diantaranya , bersih hati, berada
dalam kelompok dan tidak terpencar, sesaji tidak boleh diambil atau
dicuri. Kini, setiap upacara mengayau dimana awalnya kepala
manusia menjadi persembahannya diganti dengan kepala babi.
Dalam upacara ini peralatan yang digunakan adalah tombak, perisai
dan mandau, sedangkan peralatan lainnya adalah gong besar, kecil,
dan sesaji.
Tari giring-giring adalah tarian tradisional Dayak Kalimantan Tengah
yang menggunakan tongkat sebagai atribut tari. Di Kalimantan
Selatan, tari ini dinamakan Tari Gintur. Tarian ini mengekspresikan
kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari
dengan menggunakan tongkat sebagai media menarinya.[1] Tari ini
awalnya berasal dari suku Dayak Ma'anyan yang mendiami
daerah Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito
Selatan provinsi Kalimantan Tengah, biasanya ditampilkan untuk
menyambut tamu.
Nama giring-giring diambil dari nama tongkat yang dimainkan oleh
para penarinya, yaitu tongkat giring-giring atau juga
disebut Gangereng oleh masyarakat Kalimantan Tengah.[2] Giring-
giring terbuat dari bambu tipis (telang) yg diisi dengan biji "piding"
sehingga menghasilkan suara yg ritmis dengan
alunan kangkanong (gamelan) oleh penarinya. Dalam tarian ini
terdapat dua macam tongkat, yaitu tongkat panjang dan tongkat
pendek.
Tongkat panjang dipegang tangan kiri dan digunakan untuk
menghentakkan ke lantai. Sedangkan tongkat pendek dipegang
tangan kanan dan dimainkan dengan cara diayunkan, sehingga
menghasilkan suara yang unik apabila dipadukan dengan suara
hentakan tongkat panjang.[1]
Begitu seterusnya sambil berputar terus berlawanan arah jarum jam TARI MANASAI
dengan mengikuti irama lagu pergaulan yang berjudul sama, lagu
Manasai. Setiap gerakan kaki dalam tarian ini, mirip dengan gerakan Manasai adalah salah satu jenis tari pergaulan yang ada pada
dalam irama cha-cha. masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.[1] Tari ini merupakan tari
yang melambangkan kegembiraan. Tari ini biasanya diadakan untuk
Tari Manasai juga biasanya dipentaskan pada acara festival budaya menyambut tamu-tamu pemerintahan yang tiba di Kalteng. Intinya
Isen Mulang yaitu acara tahunan yang diselenggarakan oleh tarian “selamat datang” untuk tamu-tamu yang berkunjung ke
pemerintah daerah dan dibantu oleh Dinas Pariwisata dan dinas- Kalimantan.Tarian ini dilakukan oleh beberapa orang peserta, pria
dinas yang terkait. Tujuannya adalah menarik minat wisatawan dan wanita yang berdiri berselang-seling dalam satu lingkaran,
untuk berkunjung serta memperkenalkan dan melestarikan budaya semua dimulai dengan menghadap kedalam lingkaran, kemudian
daerah sehingga masyarakat luar juga mengetahui budaya dari berputar ke arah kanan sambil melakukan gerak maju bergerak
daerah lain. Hal tersebut akan memperkaya Budaya Nasional Bangsa berlawanan arah jarum jam kemudian menghadap ke arah luar
Indonesia.[1] lingkaran, berputar lagi ke arah kiri sambil melakukan gerak maju.
Terdapat nilai niai tersirat (Belom Bahadat)[a] yang dipresentasikan TARI BAKSA KEMBANG
pada tarian ini diantaranya nilai pendidikan karakter seperti :
religius, jujur, toleransi, kreatif, mandiri, bersahabat/komunikatif,
cinta damai, cinta tanah air, gotong royong, dan tanggung jawab
konsepsi ini juga diuraikan dalam falsafah "Budaya Betang" yang
terdiri dari 4 pilar yaitu yang pertama orang Dayak hidup jujur dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang Dayak hidup
dalam kesetaraan, ketiga orang Dayak hidup dalam kebersamaan,
yang terakhir orang Dayak itu Abdi Hukum.[3]
KALIMANTAN SELATAN
Tari Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar
dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan
penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri keraton Banjar.
Sekarang Tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan
Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan uparara pernikahan.
Tari Baksa Kembang menceritakan tentang putri remaja yang cantik
jelita sedang bermain-main riang gembira di taman
bunga. Penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita berjumlah ganjil
, baik tunggal maupun jamak asal berjumlah ganjil. Gambaran dari
tarian ini merupakan kelembutan tuan rumah dalam menyambut
dan menghormati tamu. Sehingga suasana tariannya akan tampak
riang gembira.
Nilai yang dapat diambil dari Tarian Baksa Kembang sangat luhur.
Karena kegiatan menghormati dan menghargai tamu merupakan
kegiatan yang mulia. Hal ini merupakan budaya bangsa kita yang
harus kita junjung tinggi.
Pada mulanya di Banjar, Tari Baksa Kembang mempunyai banyak
versi. Namun saat ini telah ada kesepakatan dari pelatih tari se-
Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana penari Baksa Kembang
memakai mahkota Gajah Gemuling yang ditatah kembang goyang ,
sepasang bogam ukuran kesil diletakkan pada mahkota, dan untaian
kelapa muda bernama Halilipan. Menggunakan sepasang kembang
kantil, melati dan kenanga.
Tari Baksa Kembang diiringi oleh gamelan dengan irama lagu yang
sudah baku yaitu lagu Ayakan dan Janklong atau Kambang Muni.
TARI RADAP RAHAYU
Tari Radap Rahayu adalah sebuah tarian istana
daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang
didirikan oleh sejumlah penari wanita dewasa
dengan jumlah ganjil. Tari Radap Rahayu
merupakan kesenian yang digunakan untuk
menyambut tambu sebagai bentuk
penghormatan.
Tari Radap Rahayu berawal dari Hikayat Lambung
Mangkurat dalam upacara Puja-Bantan ketika
kapal Prabayaksa kandas di Pambatanan (Lok
Baintan), sungai Martapura. Semua penumpang
kapal kemudian mengadakan upacara pemujaan
kepada Yang Maha Kuasa dengan tari-tarian
Radap Adat. Tari Radap Adat inilah yang
kemudian didusun kembali oleh Pangeran
Tumenggung dari Negara Daha dan diberi nama
tari Radap Rahayu.
KALIMANTAN UTARA TARI KANCET LEDO
Tari Gong menceritakan kemolekan seorang gadis yang menari Tari Gong atau dapat disebut juga Tari Kancet Ledo adalah salah
di atas sebuah gong, dimana gadis itu akan diperebutkan oleh 2 satu tarian Dayak Kalimantan Timur, tepatnya dari suku Dayak
orang Pemuda Dayak. Kesederhanaan tari Gong terlihat pada Kenyah. Tarian ini ditarikan seorang gadis dengan gong digunakan
gerak dan musik. Gerak pada tari Gong hanya beberapa segmen sebagai alat musik pengiringnya. Tari ini biasanya dipertunjukkan
tubuh saja yang bergerak, serta bentuk gerakannya diulang- pada saat upacara penyambutan tamu agung atau upacara
ulang pada saat penari menuju Gong, saat berada di atas Gong menyambut kelahiran seorang bayi kepala suku.
dan turun dari Gong. Tari Gong memiliki gerak kaki yang Gerakan dalam Tari Gong mengekspresikan tentang kelembutan
sederhana dalam melangkah dan ayunan tubuh dan tangan seorang wanita. Tari ini mengungkapkan kecantikan, kepandaian
yang lemah lembut. Kostum yang digunakan sangat mewah dan lemah lembut gerakan tari. Sesuai dengan nama tarinya, tari
karena terbuat dari manik-manik yang dirangkai menjadi motif Gong ditarikan di atas sebuah Gong, diiringi dengan alat
– motif binatang seperti motif Kalung Aso (Naga Anjing), pola musik Sampe.
permainan musik yang mendukung tarian ini datar tidak terjadi
pergantian iringan dari awal hingga akhir tari.
Dilihat dari gerak dan tatapan mata yang dimiliki lembut dan
lincah karena disamakan dengan sifat seekor burung, di mana
burung mempunyai sifat yang cepat, lembut dan lincah. Bentuk
gerak dalam tari Gong ini tergolong sederhana, gerak yang
merupakan ekspresi yang menirukan gerak hewan tiruannya
seperti burung Enggang. Penari melakukan gerakan-gerakan
yang sederhana dan mudah. Dalam gerak yang melambangkan
hubungan manusia dengan burung Enggang terlihat dalam
gemulai gerak tangan, tubuh dan kaki. Gerak pelan pada tangan
mengibaratkan kepak sayap burung Enggang.
Tari Magunatip atau yang lebih dikenal dengan nama Tari TARI MAGUNATIP
Lalatip atau Lalatip adalah seni pertunjukan dari daerah
Tarakan dan kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Indonesia.
Tarian tradisional ini hidup dan berkembang di Suku Dayak
Tahol.
Awalnya, tarian ini berbentuk uji atau latihan ketangkasan kaki.
Karena itu, para pemainnya harus lincah dalam melompat untuk
menghindari rintangan. Pada zaman dahulu, perang antarsuku
sering terjadi. Para pemuda dan pemudi masyarakat Suku
Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam
berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan
ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas
dari Kalimantan Utara.
Dalam tarian magunatip atau lalatip ini terdapat tiga kelompok
pemain, yaitu kelompok penjepit kaki dengan menggunakan
batang kayu atau bambu, kelompok penari sambil menari juga
menghindari jepitan kayu, dan kelompok pemain musik dengan
alat musik tradisional Kalimantan Utara berupa gong dan
kendang.
Tarian ini terbilang cukup mendebarkan karena penari dapat
terjepit atau terapit kakinya oleh batang kayu apabila terlambat
menghindar. Semakin mendebarkan tatkala sang penari harus
ditutup kedua matanya. Tarian Lalatip dinyatakan sebagai
Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tahun 2017.
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
TARI TRADISIONAL INDONESIA
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
TARI TRADISIONAL INDONESIA
- 1 - 14
Pages: